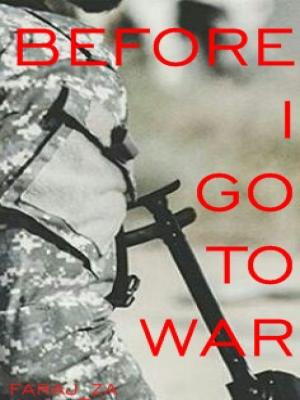"Bukan santri teladan, tapi gue masih usaha agar jadi sebaik-baik pemuda akhir zaman."
-Geandra-
...
Nabastala kala itu masih menampakkan sinar jingganya. Arakan awan putih bersih pun ikut memberikan warna hingga terlihat lebih indah. Sapuan angin sore juga terasa sedikit lebih dingin daripada puluhan menit yang lalu. Mungkin karena sebentar lagi akan memasuki waktu Magrib.
Berhubungan dengan itu, dua pemuda beda usia itu tengah melambatkan jalannya ketika sampai gerbang asrama putra.
Hampir satu jam mereka mengitari area pesantren dan kini saatnya untuk kembali melakukan rutinitas santri sebelum adzan berkumandang. Selain menjelaskan tempat-tempat yang ada di pesantren, Hisyam juga menjelaskan kegiatan apa saja yang wajib dilakukan para santri selama tinggal di pesantren. Mulai dari sholat fardlu berjamaah, mengaji kitab setiap habis subuh dan malam setelah sholat Isya, dan beragam kegiatan lainnya.
Tidak lupa, pemuda itu juga menjelaskan aturan-aturan apa saja yang harus ditaati serta hukuman yang akan diberikan jika melanggar.
Mendengar rentetan aturan, hukuman, serta kewajiban yang harus ia jalani di pesantren, membuat Gean menelan saliva sekuat tenaga.
Dalam hati, ia meragukan keyakinan dan kemampuannya untuk bisa bertahan di tempat ini. Mengingat dirinya yang terbiasa keluar malam bertemu dengan teman-temannya, bermain game sampai kadang lupa waktu, dan bisa dibilang ia hampir lupa caranya membaca Al-Qur’an sangking jarangnya ia membaca kitab suci itu di rumah. Ya, meskipun tidak sepenuhnya lupa, Gean hanya kurang bisa membedakan panjang pendeknya.
Ketika semangatnya mulai kendor, ia kembali teringat tujuan awalnya datang ke sini. Rela berpisah dengan mamanya ditengah kondisi sang mama yang membutuhkan pelukannya. Gean harus bertahan, bagaimanapun konsekuensinya. Ia harus menggunakan kecerdasannya semaksimal mungkin untuk bisa membagi waktu antara pesantren dan teman-temannya. Semua pikirannya seketika hilang karena Hisyam yang menepuk bahunya.
“Eh, iya, Tadz. Gimana?”
Hisyam yang melihat Gean tersadar dari lamunannya langsung tersenyum. “Kamu sedang memikirkan apa? Saya lihat dari tadi kamu hanya diam.”
“Gue. Eh. Maksudnya, saya sedang membayangkan bagaimana caranya agar saya bisa beradaptasi dengan semua peraturan itu,” jelas Gean.
“Kamu tidak usah khawatir. Saya yakin, pelan-pelan kamu pasti bisa.” Hisyam memberi semangat. Ia pun meliarkan pandangannya sampai akhirnya terfokus pada tiga orang yang masih menggantung sarungnya di leher. “Mirza! Basuki! Hanan! Sini!”
Pemilik nama-nama itu menghentikan langkah bersamaan, lalu menoleh ke sumber suara. Begitu mengetahui siapa yang memanggil, mereka lantas memakai sarungnya. Dengan perasaan was-was, mereka berjalan ke arah Gean dan Hisyam. Kepala mereka tertunduk, mungkin takut dimarahi.
“Assalamu’alaikum, Taz,” sapa santri yang memakai koko putih.
Hisyam menyahut dengan tersenyum, “Wa’alaikumussalam. Kalian mau kemana?”
“Kami mau ke masjid, Taz,” imbuh santri yang memakai surban.
“Kalian ke masjidnya habis adzan, ya.”
Ketiganya tersentak dengan kalimat Hisyam tadi. Kompak, mereka mengerutkan keningnya berjamaah.
“Saya mau kalian ke masjidnya bareng Gean, dia santri baru di sini.” Mereka mengangguk paham.
“Oh iya, saya lupa. Gean, ini Hanan, Mirza, dan Basuki. Mereka itu satu kamar dengan kamu. Nanti kamu bisa minta tolong ke mereka. Kalau ada yang perlu ditanyakan, jangan sungkan untuk menanyakannya, ya.”
Cowok itu mengangguk. “Terima kasih, Taz,” balas Gean.
“Kalau begitu, saya permisi dulu ya. Mirza, jangan lupa malam ini kamu ngisi kajian di asrama, ya.”
“Insya Allah siap, Taz.”
“Assalamu’alaikum.”
Keempat orang itu menjawab bersama-sama. “Wa’alaikumussalam.”
Begitu bayangan Hisyam menghilang di balik gedung, ketiga laki-laki itu langsung menyerbu Gean dengan berbagai pertanyaan. Sebelum itu, mereka menjabat tangan Gean dan memperkenalkan diri satu persatu.
Mendapat perlakuan seperti itu membuat Gean tersenyum. Sikap mereka sama dengan keempat sahabatnya di sekolah. Mudah bergaul dan bar-bar meski dengan orang yang baru dikenal.
“Nami kulo Hanan. Salam kenal.” Pemuda bersurban itu mengulurkan tangannya dan langsung dibalas oleh Gean.
Mirza dan Basuki pun melakukan hal yang sama. Mereka berkenalan menggunakan bahasa daerahnya masing-masing, membuat Gean yang asli Jakarta sedikit kebingunan men-translate maknanya.
“Jadi kamu, to, yang jadi bahan pembicaraan santriwati tadi. Nggak heran sih, orangnya memang seganteng ini.”
“Maksudnya?” tanya Gean tidak paham dengan ucapan Mirza.
“Tadi itu, kami denger kalau mereka bilang ada pangeran masuk pesantren. Eh, ternyata bener,” sahut Hanan terkekeh.
Gean yang mendengar itu hanya menimpalinya dengan senyuman. Bukannya sombong, dia sudah kebal dengan sebutan-sebutan itu karena hampir setiap hari ia mendengar cewek-cewek memanggilnya seperti itu.
“Gue udah kebal dibilang begituan, jadi jangan ngomongin hal itu lagi, ya. Mendingan kalian anterin gue ke tempat wudhu. Katanya nggak boleh terlambat sholat jamaah. Gue nggak mau kena hukum di hari pertama gue di sini.”
Bak seorang pemimpin sejati, ucapan Gean seperti perintah untuk ketiga santri yang bersamanya. Mereka pun segera mempersilahkan Gean untuk mengikuti mereka ke tempat yang dimaksud.
***
Satu persatu lampu di setiap bangunan yang ada di pesantren itu dinyalakan. Beriringan dengan gema sholawatan dan puji-pujian kepada Tuhan Seru sekalian alam. Lantunan merdunya mampu membuat setiap hati tersentuh untuk segera menunaikan kewajiban sebagai seorang hamba. Tak terkecuali Gean yang sudah siap dengan peci dan surbannya.
Setelah mengambil wudhu, ia dan teman sekamarnya langsung bergegas untuk pergi ke masjid. Namun, sebelum tiba di sana, sepertinya dia merasa kesulitan karena ini kali pertamanya memakai sarung. Untung Mirza melihat kesulitan yang dihadapinya, sehingga mereka memilih untuk kembali ke kamar dan membantu Gean memakai sarung.
Dengan kecerdasan yang dimiliki, Gean berhasil memakai kain itu setelah diajari oleh teman barunya. Tanpa menunggu lagi, kedua pemuda itu lantas pergi ke masjid. Di sana, sudah ada ratusan santri putra yang sudah siap dengan shafnya. Mereka tak ubahnya seperti para pejuang di medan perang. Berbaris rapi dengan menggunakan koko putih.
Gean yang melihat pemandangan itu menjadi takjub. Untuk pertama kali dalam hidupnya ia melihat barisan orang yang hendak sholat serapi dan sebanyak ini. Mungkin juga karena ia jarang sholat berjamaah di masjid.
Karena terlalu lama mematung di tempat, Mirza memanggilnya untuk memenuhi shaf yang masih kosong. Ia pun manut dan langsung menggelar sajadahnya di barisan ketiga. Bunyi iqamah dilantunkan setelah kyai Zaen hadir sebagai imam sholat.
Allahu Akbar
Takbir pertama usai didengungkan. Gean menyimak setiap bacaan imam dengan seksama seraya mengingat bacaannya. Ia terdiam saat imam membaca surah yang belum ia hapal, dan juga di beberapa rukun sholat yang sudah terlupa bacaannya.
Lima menit berlalu, salam pertanda akhir sholat pun sudah terucap. Selepas berdzikir dan berdoa, kyai Zaen memberikan tausiah singkat mengenai pentingnya menuntut ilmu agama, dilanjutkan dengan kegiatan mengaji bersama sampai memasuki waktu Isya.
Waktu itu Gean belum mempunyai mushaf, alhasil ia hanya mendengar bacaan dari santri yang lain. Hanan yang waktu itu sedang mengulang hafalan, meminta tolong kepada Gean untuk menyimak hafalan Qur’annya.
“Gean, tolong simak hafalan saya, ya,” pinta Hanan menyodorkan mushafnya.
Awalnya Gean hendak menolak karena dia saja belum lancar membaca Al-Qur’an, namun ia memiliki sebuah pemikiran. Mungkin dengan menyimak maka dirinya juga bisa mengetahui cara membacanya dengan baik dan benar.
“Boleh, sini.” Akhirnya Gean mengiyakan.
Hanan tersenyum girang. Ia pun mulai membaca surah Al-Baqarah ayat 280 bersama dengan maknanya. Gean tertegun dengan kehebatan Hanan dalam menghafal kitab suci itu bersama artinya. Ia pun menyimak bacaan Hanan dengan sangat teliti, bahkan fokusnya tidak teralihkan dari makna yang ada di dalam mushaf berwarna hijau itu. Sampai pada ayat terakhir dari surah itu, ia terdiam melihat artinya.
“Allah tidak membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dia kerjakan, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya,” gumam Gean membaca kalimat yang ada di sana.
Entah mengapa, ada sesuatu yang berdesir di hatinya setelah membaca potongan ayat itu. Ia langsung teringat dengan keadaan keluarganya. Hubungan orang tuanya yang hancur karena wanita ketiga itu.
“Ayat yang itu, ya?” terka Hanan.
“Menurut penjelasan Ustaz Alif, maksud ayat itu adalah bahwa setiap ujian yang diberikan Allah kepada manusia itu, sudah sesuai dengan kapasitas hamba-Nya. Jadi, Allah sama sekali tidak pernah memberikan ujian atau cobaan kepada seorang hamba jika hamba itu tidak mampu.” Hanan mencoba menjawab kediaman pemuda di depannya.
“Lalu, setiap perbuatan yang akan kita lakukan, entah itu perbuatan yang baik atau buruk, itu akan berdampak pada diri kita sendiri. Jika kita berbuat baik, maka kebaikanlah yang akan kita peroleh, begitu juga sebaliknya.”
Kini Gean mengerti, mengapa mamanya selalu mengingatkan agar dirinya tidak pernah membalas keburukan orang lain dengan keburukan juga. Tapi bukan Gean namanya jika tidak membalas semua perbuatan orang-orang yang dengan tega menyakiti keluarganya.
Maaf ya Allah, mungkin kali ini aku tidak mengikuti aturanmu. Aku rela menanggung konsekuensi, asal keluargaku bisa utuh lagi. Bagaimanapun caranya. Batin Gean.
***
Bersambung ~


 almayna
almayna