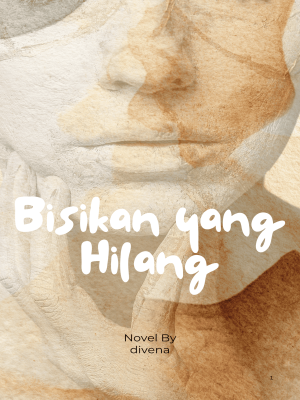Hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Kadang, kita berpikir sudah berada di jalur yang tepat, hanya untuk dihadapkan pada persimpangan yang tak pernah kita duga.
Naisha Zareen Ishraq, seorang wanita berusia tiga puluh tahun, duduk di balik jendela kaca apartemennya yang menghadap langit senja. Warna jingga keemasan merayap di cakrawala, menciptakan gradasi indah yang sering kali ia jadikan refleksi hidupnya. Cangkir teh di tangannya sudah mulai dingin, tapi pikirannya masih bergelut dengan pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung menemukan jawaban.
Mengapa pernikahan selalu dijadikan tolok ukur kebahagiaan seorang wanita? Sebagai seorang pebisnis sukses di bidang fashion muslimah, ia telah mencapai banyak hal. Brand miliknya menjadi salah satu lini fashion yang diperhitungkan di industri. Ia memiliki kehidupan yang mandiri, penuh prestasi, dan dikelilingi oleh orang-orang yang mencintainya. Tapi tetap saja, di mata keluarga dan lingkungan sosialnya, semua itu belum cukup. Yang mereka lihat hanyalah statusnya sebagai wanita lajang yang masih belum juga menikah di usianya yang matang.
Ia menarik napas dalam-dalam, membiarkan aroma kopi hitam yang kuat memenuhi rongga hidungnya. Rasa lelah menguasai tubuhnya, bukan karena pekerjaan yang menumpuk, tetapi karena sesuatu yang lebih dalam. Pertanyaan yang terus menghantuinya sejak beberapa tahun terakhir. "Kenapa aku harus menikah?" Sebuah pertanyaan sederhana, tetapi tidak ada jawaban yang benar-benar memuaskannya.
Sejak kecil, Naisha telah dididik untuk menjadi wanita mandiri. Ayahnya, seorang profesor di bidang ekonomi, selalu mengajarkannya bahwa perempuan harus memiliki pijakan sendiri dalam hidup. Sementara ibunya, seorang ibu rumah tangga yang penuh kasih, selalu mengingatkannya bahwa seorang wanita tetap membutuhkan seorang suami untuk menemani hidupnya.
"Kamu sudah 30 tahun, Naisha, Kapan kamu akan menikah? Jangan terlalu sibuk dengan pekerjaan sampai lupa bahwa hidup bukan hanya tentang karier " kata ibunya berulang kali.
Kalimat itu terngiang lagi di benaknya. Benarkah hidup bukan hanya tentang karier? Naisha sudah memiliki segalanya—perusahaan fashion muslimah yang sukses, rumah nyaman yang ia beli dengan jerih payahnya sendiri, dan kehidupan yang penuh dengan perjalanan bisnis dan pengalaman luar biasa. Ia bisa melakukan apa pun yang ia inginkan tanpa perlu meminta izin dari siapa pun.
Namun, mengapa selalu ada perasaan kosong setiap kali ia pulang ke rumah yang sunyi? Apakah benar yang dikatakan orang-orang, bahwa kebahagiaan seorang wanita hanya akan benar-benar lengkap setelah menikah? Naisha menghela napas panjang. Ia tahu bahwa pertanyaan ini bukan hanya datang dari keluarganya, tetapi juga dari lingkungan sosialnya. Teman-temannya satu per satu sudah menikah dan memiliki anak. Undangan pernikahan terus berdatangan, dan setiap kali ia menghadiri pesta pernikahan seseorang, selalu ada pertanyaan klise yang sama:
"Kapan giliranmu, Naisha?" Ia tersenyum pahit. Seakan menikah adalah tujuan utama hidup yang tak boleh dilewatkan.
Dulu, ia berpikir bahwa waktu akan menjawab semuanya. Bahwa jika memang pernikahan adalah bagian dari hidupnya, maka jodoh akan datang dengan sendirinya. Tapi semakin lama, ia mulai mempertanyakan, apakah ia benar-benar belum siap menikah, atau hanya takut untuk memilih?
Dan jika benar ia takut lalu, takut pada apa? Takut kehilangan kebebasannya? Takut tidak menemukan pasangan yang benar-benar bisa menerimanya? Atau takut bahwa pernikahan tidak seindah yang diceritakan dalam dongeng-dongeng masa kecilnya?
Ia memandangi langit yang mulai gelap. Cahaya senja memudar, berganti dengan pekatnya malam. Seperti hidupnya yang kini berada dalam persimpangan. Seperti hatinya yang masih mencari jawaban.
Dan kali ini, ia ingin menemukan jawabannya sendiri, tanpa tekanan siapa pun. Tanpa ekspektasi orang lain. Hanya dirinya dan takdir yang akan membimbingnya menuju jalan yang seharusnya ia tempuh.
~~ooOOoo~~


 syaraardhiani09
syaraardhiani09