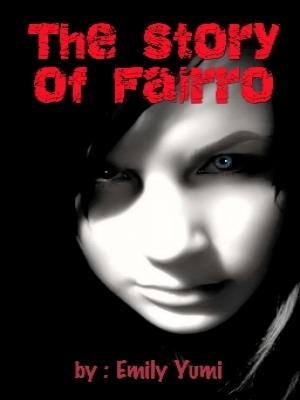Hari Minggu yang cerah. Anita duduk di depan meja belajarnya, ditemani secangkir teh hangat dan mawar putih, bunga yang paling disukainya. Di depannya, sebuah kotak kado berukuran tiga puluh kali sepuluh cm sudah terbungkus rapi, dihiasi pita putih dan gambar balon warna-warni. Ia menyentuh permukaannya pelan, senyumnya mengembang penuh harapan.
“Ra, semoga kamu ngerti isi hatiku lewat hadiah ini.” bisiknya lirih.
Ia menatap mawar putih itu sejenak, lalu beranjak ke kasur dan mengambil ponsel. Dengan senyum lebar, Anita membuka galeri foto dan mulai menelusuri kenangan bersama Askara. Tawa mereka, debat kecil, hingga foto diam-diam yang diambil saat Askara tak sadar, semuanya membuat hatinya hangat. Tapi di balik senyum itu, hatinya mencicitkan rasa ragu.
“Kenapa aku terus berharap? Padahal dia sering dingin. Sering pergi tanpa pamit, seolah aku cuma pengganggu yang nggak harus dilihat.” gumamnya pada dirinya sendiri.
Ia memeluk ponsel ke dada, menutup matanya sejenak. “Tapi, kalau aku nyerah, siapa lagi yang bakal cinta sama dia kayak gini?” bisiknya, seperti memohon agar hatinya tetap kuat.
“Ra, kadang kamu tuh nyebelin, tapi, kok bisa bikin aku suka sama kamu, ya?” bisik Anita sambil masih memeluk ponselnya ke dada.
Ia menatap langit-langit kamar sambil membayangkan reaksi Askara saat menerima hadiah itu. Akan senang? Terkejut? Atau mungkin berkata sesuatu yang membuatnya tersenyum sepanjang hari?
Namun, di balik harapannya, terselip rasa takut. Askara sering bersikap dingin, seolah tak pernah benar-benar memperhatikan perasaannya. Kadang kesal, kadang marah, kadang juga menjauh. Itu menyakitkan.
Tapi Anita belum mau menyerah. Ia yakin suatu saat Askara akan menyadari ada gadis yang tulus mencintainya.
Tiba-tiba suara ibunya memecah lamunannya, memanggil dari dapur.
“Anita, tolong beliin bumbu ke warung dulu, ya, Nak!”
“Iya, Bu!” jawabnya cepat.
Setelah menerima daftar belanja, Anita pun keluar rumah. Jarak ke warung lumayan dekat, hanya butuh beberapa menit jalan kaki. Angin sore saat itu terasa sejuk, langit jingga, keemasan, membuat langkahnya ringan, semangat mengalir.
Dalam perjalanan ke warung, Anita melewati rumah-rumah tetangganya. Pandangannya tertuju pada rumah bercat hijau dengan pot-pot tanaman tertata rapi di halaman. Itu rumah Ifal, sahabatnya. Sunyi, tenang. Anita tersenyum kecil, membayangkan Ifal yang mungkin sedang latihan Taekwondo di sekolah seperti biasa tiap hari Minggu.
“Enak ya jadi cowok. Bisa sering ke luar rumah. Pulang-pulang tinggal makan. Aku? Harus bantu Ibu masak.” keluhnya dalam hati.
Ia terus berjalan menyusuri jalanan komplek. Tapi saat melewati kebun kosong yang tak terawat, Anita mulai merasa tidak nyaman. Kebun itu penuh rumput liar, pohon pisang rimbun dan bayangan gelap dari sinar matahari sore. Di pinggir jalan, ada kali kecil yang memisahkan pemukiman dari kebun itu.
Ia menelan ludah. Setiap kali melewati jalan ini, rasa takutnya muncul. “Gimana kalau ada yang ngumpet di balik pohon pisang?” pikirnya. “Ih, ngeri.” Tubuhnya merinding.
“Jangan lebay, Nit. Cuma kebun doang.” gumamnya bicara sendiri untuk menenangkan diri. Tapi tetap saja, langkahnya jadi lebih cepat. Angin sore tiba-tiba berhembus kencang, membuat dedaunan berdesis seperti suara bisikan. Suasananya terasa aneh, agak menyeramkan.
Meskipun sudah kelas dua belas, Anita masih penakut. Bahkan dibanding Adit, sahabatnya yang juga penakut, Anita lebih gampang panik. Dia sudah berusaha berani, hanya saja rasa takut selalu muncul tiba-tiba.
Setelah selesai belanja di warung, Anita berjalan pulang. Tapi di tengah jalan, matanya menangkap sesuatu yang tak biasa. Sebuah rumah tua bergaya Belanda, Indische Empire, di seberang jalan terlihat sibuk. Pagar besi hitamnya terbuka, truk besar terparkir di depannya dan beberapa orang tampak menurunkan barang-barang.
Namun, perhatian Anita tertuju pada tanaman bunga yang ikut diturunkan. Matanya langsung berbinar saat melihat mawar warna-warni, termasuk mawar putih, favoritnya.
“Eh, ada yang pindah ya ke sini?” gumamnya.
Anita mendekat dan mengintip ke dalam pagar. Rumah tua itu masih kokoh, meski berumur. Pekarangannya dipenuhi bunga-bunga indah, meski belum tertata rapi. Mawar-mawar berwarna menghiasi halaman, membuat suasana rumah itu terasa beda dari yang lain. Ia ingin lebih dekat, ingin tahu siapa pemiliknya. Tapi dia ragu untuk melangkah masuk.
Tiba-tiba, seorang pria paruh baya keluar dari rumah. Pakaiannya rapi, mengenakan jas hitam dan kacamata bulat, seperti pria dari zaman dulu.
Ia berhenti di pintu dan tersenyum ramah.
“Hai, nona. Kamu suka bunganya, ya?” tanyanya dengan suara berat tapi lembut.
Anita terkejut, refleks mundur sedikit. Ia merasa malu karena ketahuan memperhatikan rumah orang lain. “Ah, iya, Pak. Saya cuma lewat dan nggak sengaja lihat bunganya. Cantik-cantik banget ya.” ucapnya sambil tersenyum kikuk.
Pria itu terkekeh. “Masuk saja kalau mau lihat lebih dekat.”
Anita ragu. Masuk ke rumah orang asing? Tapi rasa penasarannya lebih besar. “Beneran nggak apa-apa, Pak?”
“Tidak apa-apa. Aku senang ada yang suka bunga-bungaku.” jawab pria itu ramah.
Akhirnya, Anita masuk pelan-pelan. Wangi mawar langsung tercium, bercampur udara sore yang mulai sejuk. Ia berjalan perlahan, menyentuh kelopak mawar putih yang mekar sempurna. Senyumnya mengembang. Saat matanya bertemu dengan pria itu, ia buru-buru menunduk malu.
“Maaf ya, Pak. Tadi saya asal lihat-lihat.” ucapnya pelan.
“Tak masalah.” jawab pria itu lembut. “Aku senang ada yang bisa menghargai bunga-bunga ini. Siapa namamu?”
“Anita, Pak.”
“Nama yang cantik. Aku Alfred. Baru pindah ke sini beberapa hari lalu. Senang bisa kenal.”
Anita tersenyum. “Saya juga senang, Pak. Apalagi lihat mawar sebanyak ini.”
Alfred mengajak Anita keliling pekarangan, memperlihatkan koleksi mawarnya, beberapa langka. Anita terkagum-kagum. Tapi di balik kekagumannya, ia merasa ada yang aneh. Rumah ini memberi kesan berbeda. Dan tatapan Alfred, entah kenapa terasa agak ganjil, membuatnya sedikit gelisah.
Tanpa sadar, waktu sudah menunjukkan pukul enam sore. Langit mulai gelap. Anita tersentak, sadar ia lupa waktu. Ia buru-buru pamit, dengan alasan harus segera makan malam.
Namun sebelum sempat pergi, terdengar suara remaja dari dalam rumah.
“Alfred, siapa itu?” tanyanya pelan, tapi penuh rasa ingin tahu. Dia melihat sosok Anita yang sedang berdiri. Ketika mata mereka bertemu, William seketika tersenyum ramah.
Anita menoleh dan melihat sosok remaja yang baru muncul. Kulitnya pucat, mata tajam dan rambutnya hitam legam. Ada sesuatu yang aneh, tapi juga memikat, dari senyum dan parasnya. Anita terpaku, tak bisa mengalihkan pandangannya.
“Anda sudah bangun, Tuan?” sapa Alfred dengan hormat.
Anita yang mendengarnya terlihat bingung. “Tuan?” ulangnya dengan dahi berkerut.
Alfred menoleh dan tersenyum sopan. “Oh, maaf, saya belum selesai memperkenalkan diri. Saya asisten rumah tangga di sini. William adalah majikan saya.”
Anita mengangguk pelan, mulai memahami.
Alfred lalu melanjutkan, sambil menoleh ke arah pemuda di dekatnya. “William, ini tetangga baru kita. Namanya Anita.”
William mengangguk kecil dan tersenyum tipis. “Hai, Anita. Aku William Smith, salah satu penghuni rumah ini selain Alfred.”
Mereka kembali saling bertatap, saling mengangguk sebagai salam sambil tersenyum tipis. Alfred lalu menawarkan makan malam.
“Bagaimana kalau makan malam bersama kami?” tawarnya.
Anita terkejut. “Hmm, aku nggak yakin, aku harus izin dulu sama ibu.”
“Oh, begitu. Tak apa jika tak bisa.” jawab Alfred, sedikit kecewa.
Tapi Anita berpikir sejenak, lalu tersenyum. “Tunggu sebentar, aku minta izin lewat telepon.”
Ia menelepon ibunya, bercakap-cakap dan setelah percakapan yang cukup intens, Anita kembali dengan wajah cerah. “Ibuku mengizinkan.”
Alfred tersenyum puas dan William yang memandangi dirinya, tersenyum kembali. Anita merasa senyum William agak familiar, mengingatkannya pada seseorang, Askara. Ya, bagi Anita senyum itu mirip dengan dirinya. Senyum yang jarang sekali dia dapatkan. Sehingga saat William banyak tersenyum padanya, itu membuatnya merasa nyaman untuk tinggal dan menerima ajakan makan malam.
“Silakan masuk.” ujar Alfred.
Anita melangkah masuk ke rumah itu, merasa seperti memasuki dunia lain. Pintu tertutup di belakangnya, memisahkan dunia luar dan dalam. Udara di dalam terasa dingin, dengan aroma mawar dan marmer yang samar. Rumah ini terasa penuh rahasia.
“Maaf kalau berantakan.” kata Alfred.
Anita menggeleng. “Nggak, rumah ini indah kok.”
Cahaya dari lampu taman menembus jendela besar, menciptakan suasana hangat meski rumah ini tetap terasa misterius. Ketika pandangannya bertemu William, lagi-lagi ada perasaan aneh yang muncul.
Ruangan tengah itu luas dan masih agak kosong, hanya ada beberapa perabotan di sudut-sudutnya. Gaya klasiknya memberi kesan tenang dan elegan, seperti menyimpan kenangan lama.
“Ini ruang tengah yang sedang aku dekor. Beberapa barang baru akan datang besok.” jelas William santai.
Anita mengangguk. Pandangannya tertuju pada sebuah piano tua di sisi kanan. Piano itu berdiri anggun, dengan kayu coklat mengkilap dan ukiran yang indah. Merek ternama tertulis di bagian depan, menambah kesan mewah.
“Kamu bisa main piano?” tanya William.
Anita menggeleng. “Nggak. Cuma kagum aja, ukirannya bagus banget.”
William tersenyum. “Itu hadiah dari teman ayahku di Eropa. Umurnya sekitar seratus tahun.”
“Seratus tahun?” Anita terkesiap. Jika umurnya sudah selama itu, Ia membayangkan pasti sudah banyak orang yang pernah memainkan tuts-tuts di pianonya. Memikirkannya membuat Anita merinding.
William mulai bercerita soal sejarah piano milik ayahnya. Suaranya tenang, membuat suasana menjadi lebih hangat. Sesekali ia melontarkan candaan.
“Kamu tahu kenapa pianis bisa diandalkan?” tanyanya.
“Kenapa?”
“Soalnya mereka selalu menekan tuts yang benar.”
Anita tertawa kecil. Bukan karena leluconnya, tapi karena cara William mengatakannya, tenang, dengan senyum tipis yang membuat ruangan terasa lebih hidup. Tapi jauh di dalam hatinya, ada rasa suka yang belum bisa ia jelaskan.
Tiba-tiba, Alfred muncul di pintu. “Makan malam sudah siap.”
Anita mengikuti William ke ruang makan. Begitu masuk, matanya langsung membelalak kagum. Ruangan itu seperti diambil dari masa lalu, meja panjang dengan taplak putih, lilin menyala lembut dan lampu gantung kristal yang mewah. Piring porselen dan peralatan makan perak tertata sempurna.
Mereka duduk, Anita di ujung kiri, William di seberangnya. Suasana hening, tapi terasa hangat dan intim. Tatapan William yang teduh dan senyumnya yang terus tersungging di wajahnya membuat Anita selalu teringat pada Askara.
William lalu melontarkan pertanyaan. “Mau minum apa?”
“Air putih saja.” jawab Anita cepat.
William memberi isyarat ke Alfred. Tak lama kemudian, minuman dan makanan datang. Aroma steak yang masih mengepul memenuhi ruangan. Potongan sayuran berwarna cerah menghiasi piringnya.
Namun perhatian Anita teralih ke gelas William. Dia hanya dihidangkan sebuah cairan merah tua yang tampak kental dan berkilau dituangkan ke gelasnya. Warnanya seperti ruby cair.
“Kamu nggak makan steak juga?” tanya Anita heran.
William mengangkat gelasnya dan tersenyum. “Aku lagi diet daging. Wine ini sudah cukup bikin aku kenyang.”
Anita mengernyit. Rasanya aneh, kenyang cuma dari wine, tapi ia memilih diam. William adalah tuan rumah di sini.
Ia hanya mengangguk dan mulai makan. Dagingnya lembut, sausnya kaya rasa. Setiap suapan membuatnya lupa sejenak pada semua hal aneh yang ia rasakan malam ini.
Setelah beberapa saat, obrolan mereka kembali mengalir. Mereka membahas banyak hal, dari kehidupan sekolah Anita hingga seseorang yang diam-diam mengisi hatinya, Askara. Ketika nama itu terucap, nada suara Anita berubah. William langsung menangkap getaran kecil itu.
“Jadi, cintamu bertepuk sebelah tangan?” tanya William lembut, tapi matanya tajam.
Anita menghela napas. “Aku nggak tahu. Aku berharap, kalau aku cukup sabar dan terus berbuat baik, suatu saat Askara akan membalas perasaanku.”
William menatapnya dalam, seolah mencoba membaca hatinya. “Apa sekarang dia sudah mulai suka sama kamu?”
Anita tak menjawab. Ia hanya menunduk, menatap meja dengan tatapan kosong. Suasana hening dan tegang.
Tanpa peringatan, William berdiri. Langkahnya nyaris tak terdengar. Jari-jarinya yang dingin menyentuh dagu Anita, mengangkatnya perlahan. Ia tersentak.
Jantung Anita berdetak cepat. Ia ingin bertanya, tapi tak mampu bicara. Hanya bisa menatap mata William yang terasa dalam dan menghipnotis. Tatapan itu bukan hanya lembut, tapi juga, lapar.
“Kamu tak perlu bersedih.” bisik William. “Kamu bisa cerita semuanya padaku.”
Ia semakin mendekat, napas dinginnya menyentuh kulit Anita. Anita merasa campur aduk, antara takut dan bingung. Tiba-tiba William menunduk ke arah lehernya. Padahal saat itu dia mengira William akan menciumnya.
Anita membelalak. Tubuhnya kaku. Dan yang terjadi selanjutnya membuat bulu kuduknya berdiri, William mengendus lehernya, seperti menghirup aroma makanan lezat.
Napas Anita tercekat. Ada yang aneh. Ia ingin menjauh, tapi tubuhnya tak bergerak. Saat William menghembuskan napas di kulitnya, ketegangan berubah menjadi rasa takut yang nyata.
Lalu tiba-tiba,
“Hentikan, Tuan!” seru Alfred dari dapur.
William tersentak, seperti bangun dari mimpi. Dia cepat menarik diri, gerakannya nyaris seperti bayangan.
Anita mundur, menarik napas dalam. Matanya langsung mencari Alfred yang berdiri cemas di ambang pintu.
William menunduk, suaranya pelan. “Maaf, Aku nggak sengaja.”
Anita menyentuh lehernya, merasakan dingin di tempat yang hampir disentuh William. Ia menatap pemuda itu penuh tanya, tapi tak mengucapkan sepatah kata pun.
Alfred mendekati William, meletakkan tangannya di bahu tuannya dengan khawatir. “Tuan, Anda baik-baik saja?”
William mengusap pelipisnya. “Aku, baik-baik saja. Terima kasih Alfred.”
Tapi Alfred masih terlihat khawatir. Ia meraba dahi William. “Tubuhmu panas. Kamu pusing?”
William hanya mengangguk lemah.
Lalu Alfred menoleh ke Anita. Gadis itu masih terpaku, bingung dengan apa yang baru saja terjadi.
Dengan nada tenang, Alfred berkata.”Anita, aku minta maaf atas kejadian tadi. William sepertinya tidak enak badan. Aku akan mengantarmu ke pintu gerbang.”
Anita langsung mengangguk, lega punya alasan untuk pergi. “Oh, iya. Aku juga harus cepat pulang. Ibuku pasti sudah menunggu.”
Ia berdiri dan menuju pintu. Alfred membukakan jalan dengan sopan. Sebelum keluar, Anita menoleh. William duduk termenung, seperti tengah berjuang melawan sesuatu dalam dirinya.
Alfred tersenyum canggung. “Semoga lain kali kita bisa bertemu dalam suasana yang lebih baik.”
Anita membalas dengan senyum tipis. Tapi dalam hati, ia bergumam, Aku nggak mau datang lagi. William terlalu aneh. Aku takut aku nggak lagi suka sama Askara.
Setelah berpamitan, ia berjalan melewati taman mawar. Di bawah cahaya lampu, mawar-mawar merah tampak memukau dan misterius. Ia berhenti sejenak, mencoba menyimpan keindahannya dalam ingatan, meskipun malam ini akan menjadi malam terakhirnya di rumah itu.
Gerbang tinggi terbuka sedikit. Cukup untuk Anita melangkah keluar. Di belakangnya, Alfred menutupnya perlahan, menciptakan suara gesekan besi yang nyaring di malam yang sunyi.
Baru beberapa langkah ia berjalan, sebuah suara menghentikannya.
“Hei, ngapain kamu keluar dari rumahku?”
Jantung Anita berdegup kencang. Ia menoleh. Napasnya tercekat.
“William?” ucapnya terkejut.
Tapi, tidak. Wajahnya memang sama, tapi tubuhnya terlihat jauh lebih kuat, walau tetap pucat. Tatapannya tajam dan dingin.
Pemuda itu berkata pelan.”Itu nama saudara kembarku.”
Anita membeku. Wajah pemuda itu lebih tirus, rambutnya acak-acakan dan matanya tampak gelap. Bajunya aneh, seperti dari zaman dulu, kemeja putih kusut, rompi krem pudar, dasi kupu-kupu hitam dan celana pendek dengan kaus kaki panjang serta sepatu tua.
“Kembaran William?” Anita bertanya, bingung, mencoba memastikan.
Pemuda itu menatap tajam. “Ya. Aku kakaknya. Namaku Willie.”
Ia melangkah mendekat. Suaranya dingin. “Aku tanya lagi, apa yang kamu lakukan di rumahku?”
Suasana langsung berubah mencekam. Tak ada kehangatan seperti William. Hanya hawa dingin yang menyeramkan.
“Aku, aku cuma diundang makan malam sama Alfred dan William.” jawab Anita pelan. Ia mundur perlahan, rasa takut mulai menguasainya.
Willie menyeringai. “Kalau dia mengundangmu, berarti kamu istimewa.” Matanya menyipit. “Apa William melakukan sesuatu sama kamu?”
Anita tampak ragu, sorot matanya gelisah, seolah sedang menimbang apakah ia bisa mempercayai orang di depannya. Suaranya lirih, nyaris bergetar saat akhirnya menjawab.”Iya, Dia mengendus leher aku.” Ia menelan ludah, lalu menambahkan dengan nada cemas. “Terus dia mendadak nggak enak badan. Aneh banget sih.”
Ada ketakutan yang jelas di balik ucapannya dan kecurigaan yang belum ia ucapkan sepenuhnya.
“Oh, jadi dia sudah menjalankan tugasnya dengan baik.” ucapnya sambil menyunggingkan senyum puas. “Memilihkan mangsa yang, empuk.” Wajahnya menegang sesaat, lalu perlahan tersenyum, senyum yang tidak membawa kehangatan, melainkan kepuasan dingin yang menjalar dari sorot matanya. Ada sesuatu yang mengerikan dalam cara ia mengucapkannya.
Anita ingin kabur. Tapi sebelum sempat bergerak, Willie sudah menangkapnya.
Terlalu cepat.
Tangan Willie yang dingin dan kuat mencengkram tangannya. Kemudian segera tangannya yang lain di lingkarkan di leher Anita. Kuku-kukunya yang panjang dan tajam seketika ditancapkan ke lehernya. Membuat Anita berteriak. Namun, tangan Willie yang tadi mencengkram tangannya, kini menutup mulutnya rapat-rapat.
Sentuhannya begitu dingin, seperti es. Napas Anita tersengal, tubuhnya menegang.
“Jangan berteriak. Jangan bergerak.” bisik Willie di telinganya. Suaranya pelan, tapi mengancam. “Atau kuku ini bakal ngelukain leher kamu.”
Napas Anita memburu. Ia mencoba menggigit tangan Willie, tapi dia tidak bereaksi. Seolah gigitannya tidak terasa sakit sama sekali. Lalu Anita menginjak kakinya dengan hentakan yang kuat, tapi tetap tak berhasil membuatnya bergeming. Cengkeraman di leher dirasakan Anita semakin kuat.
“Berhenti melawan. Ikut saja kalau kamu ingin selamat.”
Leher Anita terasa perih, tapi tubuhnya seakan membeku dalam dekapan Willie.
“Ikut denganku.” kata Willie datar.
Ia menyeret Anita ke semak-semak dekat rumah. Kakinya sempat tersandung akar karena ia masih mencoba memberontak, tapi cengkeraman Willie makin kuat. Kuku-kukunya semakin menekan.
Mereka tiba di tempat tersembunyi. Willie menyapu daun-daun kering di tanah. Sebuah papan kayu terlihat. Ia menghantamnya beberapa kali dengan kakinya. Kemudian ada celah yang terbuka. Celah gelap muncul di bawahnya, menghembuskan udara lembab dan bau tanah.
Tiba-tiba, tangan muncul dari dalam celah itu. Menyingkapnya lebih lebar.
Itu Alfred.
Pelayan itu berdiri di balik pintu bawah tanah, tampak cemas.
“Cepat!” serunya panik.
Anita bingung. Kenapa Alfred ada disana? Apa yang dia lakukan?
Namun Willie menariknya masuk. Kuku-kukunya melukai leher Anita. Darah mulai menetes. Ia ingin berteriak, tapi suaranya lenyap, tenggelam oleh rasa sakit dan takut.
Mereka turun ke ruang bawah tanah.
“Maaf, nona.” bisik Alfred pelan saat Anita melewatinya. “Saya hanya pelayan yang menjalankan tugas majikan. Saya tak punya pilihan.”
Tangga itu curam, gelap dan hanya diterangi lampu redup yang berkedip. Setiap langkah mereka bergema.
Semakin jauh dari permukaan.
Semakin jauh dari kebebasan.
Alfred menutup pintu di atas. Terowongan sempit membentang di depan mereka. Pipa-pipa menggantung di langit-langit, menciptakan bayangan aneh. Anita menggigil. Napasnya berat. Langkahnya goyah.
Dan ia tahu, apa pun yang menantinya di bawah sana, pasti tidak akan baik.
Udara di terowongan makin dingin dan lembab saat mereka tiba di ruang yang lebih luas. Anita menggigil. Setiap langkah seperti beban.
Willie baru melepaskan tangan dari mulut Anita. Ia terengah-engah, tapi langsung bicara. “Aduh, sakit. Lepasin! Kalian mau apa sih?” tanyanya pelan, suara bergetar.
Tak ada jawaban. Kuku Willie justru mencengkeram lehernya makin kuat. Darah mengalir, menetes ke lantai, meninggalkan jejak merah yang mengerikan.
“Sakit, please, lepasin.” Anita merengek.
Willie menatapnya tanpa ekspresi. “Ikut saja. Jangan banyak tanya.”
Tiba-tiba Willie menunduk dan menjilat darah dari leher Anita.
“Iih apaan sih, jorok.” Anita mencoba menjauh, tapi cengkeraman di lehernya masih terlalu kuat.
Willie justru terlihat senang. “William ternyata benar.” gumamnya. “Katanya darahmu berbeda. Terbukti, lebih enak.”
Anita nyaris tak percaya. “Kamu ini, apa?”
Willie tersenyum menyeramkan. “Malaikat maut. Aku bakal minum darah kamu.”
Tawanya menggema, dingin dan mengerikan.
Anita mencoba kabur. “Lepasin aku!” Tapi Willie menahannya dengan kuku yang semakin dalam menancap ke kulitnya dan juga tangan yang di cengkram nya erat-erat.
Lalu suara Alfred memotong.
“Tuan, tolong ingat rencananya.”
Willie mengangguk, tersadar. “Benar. Oke, ini aku lakukan buat adikku yang terlalu baik hati.”
Alfred menyalakan senter dan berjalan lebih dalam.
Anita diseret masuk ke ruang lain. Kali ini lebih besar, seperti ruang eksperimen. Di tengah ruangan ada ranjang menyerupai ranjang pasien. Dinding ruangan penuh tabung berisi cairan merah pekat.
Matanya tertuju pada botol-botol yang bertuliskan wine di sudut ruangan, botol yang sama dengan yang digunakan saat makan malam William. Ia mulai mengerti sesuatu.
“Jadi itu, darah?” ucapnya.
Willie tertawa pelan. “Memangnya menurut kamu, kami minum anggur?”
“Kalian ini apa? Vampire?” Tanya Anita.
“Kami disebut Vrykolakas, bangsa penghisap darah manusia. Ingat itu baik-baik.”
Anita menelan ludah, ketakutan menjalar di sekujur tubuhnya.
“Naik!” bentak Willie sambil mendorong Anita.
Anita berusaha melawan. Ia mencakar dan menendang, tapi Willie menangkapnya dan mendorongnya ke ranjang.
“Ya ya! Aku naik! Sakit tahu!” isaknya.
“Kalau gitu, nurut!” gertaknya.
Dengan berat hati, Anita naik ke ranjang. Ia berharap Askara datang menyelamatkannya. Tapi tak ada siapa-siapa. Hanya dia, Willie dan Alfred.
Alfred mengikat tangan Anita ke ranjang. Ia meronta, tapi sia-sia.
“Kalian mau ngapain? Kenapa aku diikat?” Tanyanya parau. Keringat mengucur di pelipisnya. Raut wajahnya penuh ketakutan, suaranya tenggelam dalam ruang yang kedap suara.
“Haha, kami bakal ambil darah kamu.” kata Willie dingin.
Anita menangis. “Please, jangan. Ayah, ibu, Askara, tolong.”
Willie mendekat. Ia mencengkeram kepala Anita dan menekan kuat. “Diam!” bentaknya.
Taring tajam keluar dari mulut Willie. Anita menggeliat ketakutan.
“Please, jangan.” isaknya.
Tapi terlambat. Taring itu menancap. Rasa sakit luar biasa merobek lehernya, lalu perlahan berubah jadi mati rasa. Dunianya mulai kabur.
Willie menghisap darahnya dalam-dalam. Tubuh Anita melemah, kesadarannya perlahan menghilang.
Setelah beberapa saat, Willie melepaskan gigitannya. Taringnya menyisakan luka dalam di leher Anita, mengucurkan darah hangat.
Namun itu bukan sekadar gigitan, racun dari taringnya merayap ke otak Anita, menanam mekanisme ketaatan mutlak. Seperti mantra, perlahan-lahan kesadarannya dikunci, tubuhnya siap tunduk pada setiap perintah Willie. Kini Ia membisikkan sesuatu di telinga Anita, sebuah mantra.
“Saat kamu pulang, bersikaplah seolah tidak ada yang terjadi. Tunggu sampai aku balik lagi.”
Anita mengangguk pelan, seolah tak sadar, pikirannya telah dikendalikan.
Alfred mendekat dengan suntikan. Ia menyedot darah Anita dan menyalurkannya ke dalam botol wine.
Semua dilakukan dengan tenang, dingin dan cepat.


 risyadfarizi
risyadfarizi