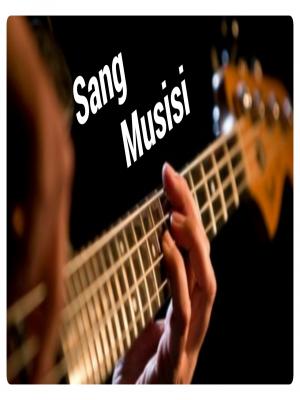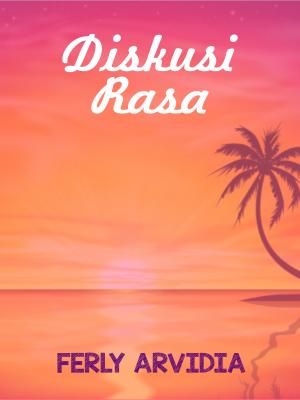Aroma lavender yang menenangkan memenuhi ruangan, bercampur dengan kehangatan cahaya lampu kuning. Lani, dengan mata terpejam rapat, duduk bersandar di sofa empuk.
Suara lembut psikolognya membimbing, "Ikuti saja suara saya, Lani. Biarkan pikiranmu membawa kembali ke masa lalu. Kembali ke saat kamu berusia dua belas tahun... Apa yang kamu lihat lani" Napas Lani terasa sedikit tercekat, namun ia berusaha mengikuti arahan.
Perlahan, gambaran mulai muncul di benaknya, tidak jelas awalnya, lalu semakin fokus. Gelap. Kemudian, cahaya matahari menyilaukan saat mobil yang ditumpanginya memasuki kota baru. Di sampingnya, ibunya tersenyum lebar.
"Kita mulai hidup baru di sini, Sayang." Lani kecil hanya mengangguk, mencoba menyembunyikan kegugupan di dadanya. Rumah baru, sekolah baru, dan… ayah baru.
Suami baru ibunya menyambut mereka di depan pintu dengan senyum hangat dan pelukan canggung untuknya. Usianya baru menginjak dua belas tahun, dan perpindahan ini terasa seperti petualangan yang sedikit menakutkan. Namun, senyum hangat dan sapaan ramah dari suami baru ibunya, yang kini menjadi ayah tirinya, sedikit meredakan kecemasannya. Di mata Lani, pria itu tampak baik dan mudah didekati. Ia bahkan membantunya membawa kotak-kotak ke kamar barunya.
"Apa yang kamu rasakan, Lani?" suara psikolog membuyarkan lamunannya sejenak.
"Awalnya… biasa saja. Dia terlihat baik," jawab Lani dengan suara tercekat.
Beberapa bulan berlalu. Kehidupan di rumah baru terasa normal. Ibunya tampak bahagia. Suatu siang yang terik ibunya lagi pergi keluar sebentar, Lani tertidur pulas di kamarnya. Tiba-tiba, ia merasa berat, seperti ada sesuatu yang menindih tubuhnya. Matanya terbuka dengan kaget. Ayah tirinya berdiri di atasnya, tangannya menekan dadanya. Jantung Lani berdegup kencang. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan.
Ayah tirinya hanya tersenyum tipis, berkata pelan, "Tidak apa-apa, Lani. Ayah hanya ingin memastikan kamu tidur nyenyak." Kemudian, ia pergi begitu saja.
Lani menggigit bibirnya kuat-kuat. Air mata mulai mengalir tanpa bisa dicegah.
"Lalu?" bisik psikolog.
Kejadian itu membuat Lani merasa tidak nyaman, namun ia berusaha menepisnya. Mungkin ia hanya bermimpi buruk. Tapi, kejadian serupa terulang lagi, dan lagi. Ayah tirinya sering masuk ke kamarnya saat ibunya tidak ada dirumah, selalu dengan alasan yang tidak jelas. Ketakutan mulai menggerogoti hatinya.
Puncaknya adalah ketika suatu sore, saat Lani sedang mandi, pintu kamar mandi tiba-tiba terbuka. Ayah tirinya berdiri di ambang pintu, menatapnya tanpa ekspresi. Lani menjerit tertahan, tubuhnya gemetar ketakutan.
"Tidak apa-apa, Sayang," kata ayah tirinya lagi, dengan nada yang sama tenangnya. "Ini tidak apa-apa kalau hanya dengan ayah. Tapi jangan dengan laki-laki lain." Kata-kata itu justru membuat bulu kuduk Lani merinding. Ia merasa ada yang sangat salah.
Tubuh Lani bergetar hebat. Ia mencengkeram erat lengan kursi. "Di… di situ saya mulai merasa ada yang salah," ucapnya dengan suara bergetar.
Ketakutan mulai menggerogotinya. Setiap kali ibunya pergi keluar rumah, panik langsung menyerbunya. Ia mencari cara untuk menghindar. Berpura-pura bermain di rumah teman, atau mengajak teman-temannya menginap, menjadi alasan yang sering ia gunakan. Rasa takut itu akhirnya mereda ketika ibunya bercerai lagi dan mereka kembali ke kota asal mereka.
"Bagaimana perasaanmu saat itu, Lani?"
"Lega. Sangat lega," jawab Lani, air matanya semakin deras.
Dua tahun berlalu. Lani yang kini berusia empat belas tahun, secara perlahan mulai memahami apa yang sebenarnya ia alami. Ia merasa kotor, malu, dan marah. Kenyataan bahwa ia telah menjadi korban pelecehan oleh ayah tirinya sendiri menghantuinya. Sejak saat itu, rasa takut terhadap laki-laki mulai tumbuh dan berakar dalam dirinya. Ia menjadi sangat waspada, bahkan cenderung menghindar dari interaksi dengan laki-laki, kecuali ayah kandungnya. Lani tumbuh menjadi remaja yang pendiam dan tertutup.
"Kamu menyadarinya dua tahun kemudian?" tanya psikolog dengan lembut.
"Iya. Saya… saya baru mengerti," jawab Lani dengan suara parau.
"Dan kamu menyimpan ini sendiri?"
"Saya cerita ke sahabat saya. Mereka yang… mereka yang memaksa saya datang ke sini," Lani terisak.
Psikolog itu mengangguk mengerti. "Kamu sudah sangat berani, Lani. Berani menghadapi ingatan ini, berani mencari bantuan."
Lani terdiam, mencoba mengatur napasnya. Rasa sakit dan ketakutan itu masih terasa nyata, namun ada secercah harapan yang mulai tumbuh di hatinya. Mungkin, dengan bantuan ini, ia bisa melepaskan belenggu trauma yang selama ini menghantuinya.
Perlahan tapi pasti, Lani mulai memberanikan diri. Didorong oleh dukungan tanpa henti dari sahabat-sahabatnya, ia mencoba membuka diri terhadap interaksi dengan laki-laki. Awalnya canggung dan penuh kewaspadaan, namun kehadiran teman-temannya sebagai perantara memberikan rasa aman. Mereka mengenalkannya pada teman-teman laki-laki mereka, menciptakan lingkungan yang terasa lebih bersahabat dan tidak mengancam.
Setiap obrolan ringan, setiap tawa bersama teman-temannya dan teman laki-laki mereka, menjadi langkah kecil namun signifikan bagi Lani. Ia belajar bahwa tidak semua laki-laki sama. Ada yang sopan, ada yang lucu, ada yang benar-benar mendengarkannya tanpa menghakimi. Proses ini tidaklah mudah, seringkali rasa takut itu muncul tiba-tiba, membuat jantungnya berdebar dan keringat dingin membasahi telapak tangannya. Namun, ia selalu mengingat kata-kata psikolognya dan dukungan tulus dari sahabat-sahabatnya.
Lani merasa sangat berterima kasih kepada sahabat-sahabatnya. Merekalah yang pertama kali menyadari betapa dalamnya luka yang ia pendam, merekalah yang dengan sabar mendengarkan ceritanya, dan merekalah yang tanpa henti menyemangatinya untuk mencari bantuan profesional. Tanpa dorongan mereka, mungkin ia masih akan terperangkap dalam ketakutan yang mencekik.
Seiring berjalannya waktu, di antara lingkaran pertemanan itu, Lani bertemu dengan seorang pria bernama Rian. Awalnya, interaksi mereka biasa saja, seperti dengan teman-teman lainnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari Rian. Ia tidak pernah terburu-buru, selalu sabar dalam berbicara, dan memiliki mata yang teduh. Rian tidak pernah memaksa atau membuatnya merasa tidak nyaman. Ia justru menunjukkan ketertarikan pada Lani apa adanya, dengan segala kekurangannya.
Perlahan, rasa takut Lani terhadap Rian mulai berkurang, digantikan oleh rasa nyaman dan aman. Rian selalu menghargai batasan yang Lani buat, dan itu membuat Lani merasa dihargai dan dipahami. Mereka menghabiskan waktu bersama, bukan hanya dalam kelompok, tetapi juga berdua. Obrolan mereka semakin dalam, dan Lani mulai berani menceritakan sedikit demi sedikit tentang masa lalunya, tentu dengan didampingi rasa gugup yang luar biasa. Rian mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menghakimi atau merasa jijik. Ia justru menunjukkan empati dan pengertian yang membuat hati Lani menghangat.
Waktu terus berjalan, dan benih-benih cinta mulai tumbuh di hati Lani. Ia tidak menyangka, di tengah trauma yang pernah menghantuinya, ia akan menemukan seseorang yang bisa menerima dan mencintainya dengan tulus. Rian bukan hanya menjadi teman, tetapi juga seseorang yang memberinya harapan baru tentang hubungan yang sehat dan penuh kasih. Lani akhirnya menemukan cinta sejatinya, bukan sebagai penghapus luka masa lalu, tetapi sebagai teman seperjalanan yang akan menemaninya menyembuhkan diri dan membangun masa depan yang lebih bahagia. Ia beruntung memiliki sahabat-sahabat yang selalu mendukungnya, dan kini, ada Rian yang menggenggam tangannya dengan penuh cinta.
JANGAN LUPA LIKE


 laven
laven