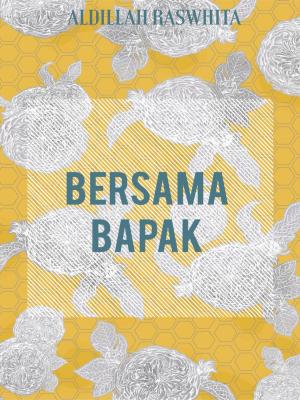Waktu kami semakin sempit. Para pengejar sudah hampir menemukan kami. Jika kami tetap berkeliaran di pusat kota, aku yakin sebentar lagi kami akan tertangkap. Gerimis mulai turun sore ini. Aku meminta Fahmi untuk berteduh sejenak, namun dia menolak. Alhasil, kami basah kuyup.
"Di mana semak yang ditunjuk Pak Fajar? Aku yakin kita sudah menyusuri sungai cukup jauh," tanyaku, menghapus air hujan dari wajahku.
"Betul, aku juga merasa begitu," jawab Fahmi, suaranya nyaris tak terdengar di bawah derai hujan.
"Tunggu, berhenti! Aku melihat sesuatu," seruku sambil menunjuk ke arah semak-semak di tepi sungai yang tersembunyi. disana ada tumpukan kayu berbentuk papan. Sebagian sudah lapuk dan hancur. Kami mendekati tumpukan kayu itu dengan hati-hati, pakaian kami berat karena air hujan.
"Apa ini kayu yang orang tuamu gunakan untuk membuat kotak?" tanyaku pada Fahmi.
"Mungkin," jawabnya singkat, seperti biasa.
Aku meraih salah satu papan dan mengamati bekas-bekas pecahannya. "Jumlahnya cukup banyak. Apa ini hancur oleh arus atau ada yang sengaja merusaknya?" gumamku, lebih kepada diriku sendiri.
Fahmi mengambil beberapa papan lalu menutupkannya di atas kepala kami. Ya, dia menutupi kepalaku juga. Aku sesaat tersipu.
"Cepat pegang. Aku mulai pegal, atau kau akan kehujanan lagi," ucapnya dengan nada datar.
Aku tersenyum tipis. Ternyata, anak ini tidak sepenuhnya dingin. Ada perhatian kecil di balik sikapnya.
Aku mengambil papan itu dan membantunya memindahkan beberapa potongan papan untuk kami selidiki lebih lanjut. Kami mencari tempat yang agak teduh di pinggiran sungai. Di sana, Fahmi memeriksa potongan papan itu.
"Cocok," katanya setelah membandingkan pecahan papan tersebut. "Ternyata benar kalau kotak ini hancur. Namun, pertanyaannya sekarang, hancur karena arus atau sengaja dihancurkan?"
"Ayo coba periksa sekitar sungai. Siapa tahu ada petunjuk," pintaku, berusaha menenangkan pikiranku yang kalut.
Kami terus mencari hingga Fahmi menemukan sesuatu yang mencurigakan. Ada semak-semak yang sebagian hancur seperti terinjak. Ketika dia menyingkapnya, di balik semak itu tampak sebuah gua. Gua itu cukup besar untuk dimasuki orang dewasa dengan merunduk. Mulut gua tampak gelap dan dalam, membuat bulu kudukku meremang.
"Aku akan masuk," ujar Fahmi tanpa ragu.
"Apa kau yakin ini aman? Bagaimana jika ada ular atau buaya?" tanyaku khawatir.
"Setidaknya kita tahu ketika mencobanya," jawabnya tegas.
Aku menghela napas. Anak ini seperti tidak mengenal rasa takut. Sudah beberapa kali dia menghadapi bahaya tanpa gentar. Kali ini, aku tak boleh takut seperti sebelumnya. Dengan gugup, aku mengekor di belakang, menyusuri kegelapan gua.
Sesaat tanpa kata, tiba-tiba aku meminta sesuatu. "Bolehkah aku memegang tanganmu?" tanyaku pelan. Suaraku hampir bergetar karena ketakutan.
"Kenapa?," jawabnya, tanpa menoleh.
"Aku takut".
"Oke".
Aku menyentuh tangannya, dan sentuhan itu membuat jantungku berdetak lebih cepat. Ini kali pertama aku bersentuhan kulit dengan seseorang—terlebih lagi seorang cowok. Perasaan ini begitu aneh.
"Tanganmu dingin. Pegang pundak atau pinggangku saja," ucap Fahmi tiba-tiba.
Astaga. Apa aku tidak sedang bermimpi? Aku boleh memegang bagian tubuhnya? Jantungku semakin berdegup kencang. Aku tak sanggup berkata apa-apa. Dengan tangan gemetar, aku meraih pinggangnya. Meskipun tertutup pakaian basah, aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya.
Kami terus berjalan dalam diam, membisu dalam pikiran masing-masing. Gua itu semakin gelap, dan hanya suara langkah kaki kami yang terdengar. Hingga akhirnya kami menemukan beberapa kotak papan yang belum hancur. Fahmi bergegas meraihnya. Dia tampak begitu bersemangat, mencoba membuka salah satu kotak dengan tergesa-gesa.
Ketika tutup kotak itu terbuka, aku dan Fahmi tertegun. Mata kami membelalak melihat isinya. Kotak itu penuh dengan bom rakitan.
"Astaga. Apa maksudnya semua ini?" tanyaku dengan suara bergetar.
"Kita harus berhati-hati. Kita belum tahu apakah bom ini aktif atau tidak," ujar Fahmi sambil mengeluarkan salah satu bom dengan sangat hati-hati. Dia memeriksanya.
"Sepertinya bom ini mati. Tidak ada lampu indikator yang menyala atau suara mendesing," katanya, mencoba menenangkan.
Aku menghela napas lega, meskipun perasaan was-was belum hilang sepenuhnya. "Apa mungkin bom ini digunakan untuk meledakkan gedung kantorku?" tanyaku pelan.
"Bisa jadi. Ayo kita bawa salah satu sebagai bukti ke kantor polisi. Aku sudah berhasil merusak salah satunya," kata Fahmi.
Dia mengangkat bom itu, menunjukkan kepadaku. Tangannya gemetar saat memegang benda berbahaya itu. Tiba-tiba, bom itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah.
"Awas!" seruku refleks.
Kami berdua serempak memungut bom yang terjatuh. Tangan kami bersentuhan, saling menumpuk beberapa saat. Lalu mata kami bertemu, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Ada perasaan hangat yang menjalar cepat ke jantungku. Degupannya semakin keras, hingga rasanya seluruh dunia terdiam.
Fahmi perlahan mendekatkan wajahnya ke wajahku. Apa yang sedang dia lakukan? Aku tak bisa berpikir jernih. Matanya tiba-tiba saja terpejam perlahan, dan tanpa sadar, aku mengikutinya. Apakah kami akan berciuman? Ini akan menjadi ciuman pertamaku...Namun.
"KETEMU! MEREKA DI SINI!"
Suara keras memecah keheningan. Kami segera membuka mata, terkejut dan terkesiap. Menoleh ke arah sumber suara, kami melihat beberapa pria mendekat. Mereka adalah pengejar kami, para penculik yang sebelumnya menculik Fahmi. Orang-orang ini pasti yang dimaksud David.
"Lari, Maya!" teriak Fahmi sambil menarik tanganku. Kami berlari sekuat tenaga menyusuri gua lebih dalam lagi, meninggalkan bom di belakang.
Ketegangan memuncak. Aku bisa mendengar suara langkah kaki para pengejar semakin mendekat. Napasku tersengal, tubuhku lelah, namun aku tak boleh menyerah. Kami harus melarikan diri dan keluar dari tempat ini hidup-hidup.


 risyadfarizi
risyadfarizi