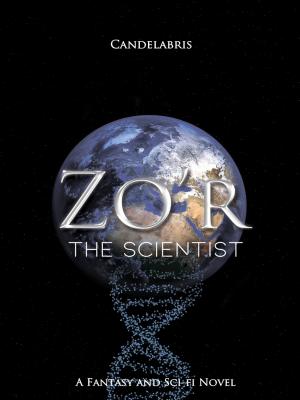"Bu, aku tidak tahu harus berbuat apa sekarang," kata Jaya dengan suara lirih. "Apa yang harus aku lakukan terkait ayahku ini?"
Ekspresi Puspa begitu datar, membuat Jaya semakin frustrasi. Dia benar-benar berharap ibunya berbicara, memberikan petunjuk atau saran untuknya. Jaya sudah tak sanggup menjalani hidup tanpa arah dan meraba-raba.
Jaya terus membuat figur pasir, mencoba menggambarkan perasaannya yang beragam, dari rasa marah hingga rindu. Dia juga membuat figur lain yang mewakili ibunya. Figur pasir itu diletakkan di antara figur Jaya dan figur ayah, menandakan peran ibunya dalam hubungan mereka.
Tanpa sadar, sesi terapi lebih tampak seperti terapi bagi Jaya sendiri untuk dapat mengungkapkan perasaan melalui media mainan pasir. Puspa melihat dengan cermat setiap figur yang Jaya buat dan hanya meresponnya dengan tatapan sendu.
Jaya terdengar jengkel saat berkata, “Kasih tahu aku, Bu, apa yang Ibu inginkan? Apakah kita tetap hidup berdua seperti sekarang, atau bertiga bersama ayah?”
Puspa tetap diam. Beliau hanya memandang Jaya dengan ekspresi bingung. Jaya jadi semakin kalut. Dia berusaha tetap menekan volume suara sambil bertanya, “Kenapa Ibu selalu diam? Aku butuh jawaban Ibu. Sekali ini saja, Bu. Beri tahu aku bagaimana harus bersikap. Ibu mau aku menerima ayah?”
Puspa terus membisu. Ekspresinya mencerminkan ketidakpastian. Beliau kemudian menunduk dan tergugu-gugu. Kedua bahunya tampak mengguncang-guncang. Sejurus kemudian, terdengar isak beliau diiringi gelengan.
Jaya menghela napas panjang. Dia menatap nanar figur pasir yang pertama dibuatnya. “Baiklah, kalau Ibu tidak mau bersamanya, aku pun akan menyingkirkannya,” ujar Jaya penuh tekad. Telapak tangan kanannya mengentak figur yang sedari tadi dipandangnya itu hingga lebur.
Di tengah situasi yang sangat emosional itu, Profesor Wijaya datang menghampiri. Hari itu memang jadwal beliau melakukan kunjungan rutin untuk memeriksa para penyintas ODGJ di panti rehabilitasi Sumber Harapan.
Profesor Wijaya mencermati ekspresi amarah Jaya dan ibunya yang menangis kebingungan. Beliau merasa ada sesuatu yang perlu ditangani. "Apakah semuanya baik-baik saja?" tanya beliau penuh perhatian.
Jaya mengangkat kepala dan memandang Profesor Wijaya. Dia kemudian mencoba menjelaskan situasinya dengan sisa emosi yang mendalam. Profesor Wijaya, menyimak dengan penuh perhatian dan mengangguk-angguk.
“Saya tahu bahwa terkadang ekspresi dan simbolisme dapat menjadi cara yang efektif untuk berkomunikasi, terutama dalam situasi seperti ini, di mana kata-kata mungkin tidak mencukupi,” komentar beliau. “Namun, saya cukup prihatin dengan kondisimu, Jaya. Sepertinya, kita harus bicara. Di ruangan saya?”
“Oh, eh, ruangan saya saja, Prof,” sahut Jaya cepat. “Lebih dekat dari sini dan … saya tidak perlu merasa seperti terdakwa.”
Profesor Wijaya mengernyit dan melirik sekilas ke Jaya sambil tersenyum tipis. Beliau mengikuti langkah Jaya yang memimpin menuju ruang istirahat yang dulunya ditempati Bu Nia. Menggantikan tugas beliau menjadi psikolog klinis yang berkunjung seminggu sekali ke panti rehabilitasi itu membuat Jaya mendapatkan fasilitas tersebut.
Tampak suasana di dalamnya yang tidak cukup nyaman untuk melepas penat. Ruang yang memang sedianya berukuran kecil itu jadi terasa lebih sesak. Di sudut-sudut ruangan, tumpukan alat peraga, media terapi, dan mainan rusak yang berserakan membuatnya terlihat berantakan. Dinding-dindingnya tergores dan kotor. Salah satu sisinya bahkan tampak retak dengan pola seperti bekas sebuah tumbukan.
Di tengah ruangan, terdapat meja kecil dengan kertas dan pena tersebar di atasnya. Matras tipis yang diletakkan di lantai tertekuk di salah satu sudut, terlihat tidak ada usaha untuk sekadar merapikan sejenak.
Udara di dalam ruangan terasa pengap dan berbau apek. Profesor menarik kerai yang berdebu agar terbuka dan mengizinkan kaca jendela meneruskan cahaya matahari masuk mengisi ruangan. Menyadari itu, Jaya buru-buru merapikan ruang tersebut agar ada tempat untuk mereka duduk berdua.
Profesor Wijaya duduk perlahan di kursi yang tersedia, memberikan Jaya waktu untuk juga duduk dan merasa nyaman dengan kehadirannya. Beliau melihat Jaya dengan penuh perhatian, mencoba membaca ekspresi dan tanda-tanda keadaannya. Jaya memandang Profesor Wijaya dengan tatapan yang terlihat kosong dan penuh tekanan.
Dengan penuh kehati-hatian, Profesor Wijaya mulai berbicara, "Jaya, apa yang terjadi? Sudah berapa lama kamu membiarkan ruanganmu tak terurus begini? Jaya yang saya kenal selalu rapi dan terorganisir, apakah ada yang ingin kamu bagikan pada saya?"
Jaya termenung sejenak. Dia menyadari tidak bisa terus-menerus berjuang sendiri. Setidaknya, profesor Wijaya telah memberikan tawaran tangan pertolongan. Bayu pun telah menyarankan hal yang sama. Mungkin, dengan berbicara tentang perasaan, Jaya bisa menemukan jalan keluar dari kebingungan.
Jaya menghela napas dalam-dalam, Dengan berat hati, Jaya setuju untuk berbicara dengan profesor Wijaya. Dia tahu bahwa ini adalah langkah pertama untuk menyelamatkan diri dari kekacauan mental yang sedang terjadi.
Jaya mulai berbicara dengan canggung, menceritakan betapa kehadiran Pak Atma mengingatkannya pada masa lalunya yang terluka. Dia juga menyebutkan bahwa ada perasaan yang rumit di dalam dirinya terkait dengan Pak Atma, terutama setelah mengetahui bahwa ada kemungkinan Pak Atma adalah ayahnya.
Profesor Wijaya mendengarkan dengan saksama. Beliau bisa merasakan betapa beratnya beban yang dipikul Jaya. Beliau berusaha tidak salah langkah dalam momen penting ini untuk membantu Jaya menemukan kembali kualitas hidupnya.
Profesor Wijaya berkata, "Saya akan mendukung kamu sepenuhnya dalam proses ini, Jaya. Mari kita bekerja sama untuk membawa perubahan yang positif dalam hidupmu, agar bisa menolong ibumu. Penanganan yang terlalu melibatkan perasaan pribadi seperti tadi bukan hal yang ideal kan, Jaya? Jangan khawatir! Kita akan melewati ini bersama-sama."
***
Esok siangnya, Bayu memanggil Pak Atma melalui telepon di ruang praktik. Bayu meminta beliau agar ke ruangannya. Pak Atma datang dengan heran. “Ada apa ya, Dok? Hari ini bukannya tidak ada pasien yang membutuhkan tes genetik, ya?” tanya beliau memastikan.
Bayu mengangguk, kemudian mengajak Pak Atma duduk di hadapannya. Bayu menyampaikan alasannya mengajak Pak Atma berbicara empat mata. "Pak Atma, saya benar-benar khawatir soal Jaya. Perubahan perilakunya drastis sekali. Jaya merasa terganggu dan bingung akibat perselisihan antara Jaya dan Anda tempo hari," ungkap Bayu.
Pak Atma kaget dan jadi serba salah. “Jadi, Dokter Bayu tahu kalau …?” tanya beliau ragu.
“Ya, saya tahu bahwa Anda adalah ayah yang selama ini dicari Jaya. Sayang, dia mengetahui ini setelah sesi terapi ibunya yang menunjukkan ada kekerasan di dalam hubungan kalian,” ucap Bayu yang segera disusul dengan deham. “Eh, maaf, Pak Atma. Saya tidak berwenang menghakimi Anda di sini. Saya hanya bermaksud menolong sahabat saya, dan sepertinya saya butuh bantuan Anda.”
Pak Atma mengangguk membenarkan. "Ya, ya, saya paham, Dok. Tidak apa-apa. Saya juga prihatin sama dia. Andai ada cara, saya sangat ingin membantunya. Tapi, saya bisa apa ya, Dok?" tanya Pak Atma ragu-ragu.


 faridapane
faridapane