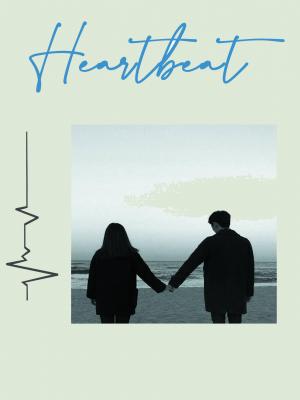Pak Atma mengangguk pasrah. “Saya paham perasaanmu, Jaya. Saya memang tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi saya bersedia mendengarkan dan memahami lebih lanjut tentang keadaan ibumu,” ujar Pak Atma mencoba berdamai.
Mata Jaya sontak memicing tajam ke arah Pak Atma. “Jangan coba-coba mengganggu ibuku lagi. Cukup sekali saya mendengar teriakan histerisnya saat mengingat kenangan bersama Anda. Jangan pernah membangkitkannya lagi,” desis Jaya penuh dendam.
Pak Atma menaruh tangan di dada dengan rasa penuh sesal. “Sebenarnya, saya ingin mencoba berbicara dengannya. Tapi, saya juga tidak bisa memaksa jika kamu masih keberatan,” ucap beliau lirih.
"Ya, saya sangat keberatan," tegas Jaya.
Pak Atma mengangguk maklum. "Saya mengerti, Jaya. Marah adalah perasaan yang sah, dan luka-luka ini memang tidak mudah disembuhkan. Saya cuma ingin kamu tahu, saya ada di sini sekarang, siap menemanimu," ujar beliau bijak tetapi dengan nada getir.
Jaya menghela napas lagi. “Entahlah, saya bingung. Saya butuh waktu untuk mencerna semua ini,” sahut Jaya yang kemudian segera meninggalkan lab.
***
Malam itu, dalam kamar kecil apartemen Jaya yang sederhana, suasana begitu tegang. Jaya duduk di pinggir tempat tidur, wajahnya penuh kemarahan dan kebingungan. Bukannya bersemangat seperti biasanya, dia tampak kacau secara mental.
Berdamai dengan masa lalu masih menjadi PR besar bagi Jaya. Jaya mengutuk keras dirinya sendiri. Kenapa ini terjadi? Kenapa aku harus mencari tahu? Kenapa akhirnya berhasil dan membuatku berantakan begini?
Pikiran-pikiran liar terus memenuhi kepala. Jaya marah pada dirinya sendiri karena telah menilai Pak Atma tanpa cukup bukti. Dia merasa seperti segalanya tiba-tiba berubah menjadi beban yang terlalu berat untuk dipikul.
Jaya memilih bertandang ke RSJ Purnama. Profesor Wijaya heran dan khawatir melihat keadaannya yang sangat berbeda. “Jaya, apa yang terjadi? Kamu terlihat sangat bingung dan marah. Apakah ada yang bisa saya bantu?” tanya beliau berusaha agar tetap tenang.
Jaya dengan nada tumpul menjawab, “Eh, tidak, Prof. Ini hanya masalah pribadi yang harus saya selesaikan sendiri.”
Profesor Wijaya semakin penasaran. “Kamu yakin? Saya bisa memberikan nasihat atau mendengarkan jika kamu mau berbicara,” desak beliau.
Jaya menyahut dingin. “Saya tidak butuh nasihat atau pendengar saat ini. Mari kita bicarakan soal Ibu saja, Prof,” ucapnya mengalihkan pembicaraan.
***
Namun, selama berhari-hari berikutnya, Jaya merasa semakin terisolasi. Hari itu, Jaya sibuk dengan jadwal konselingnya di klinik. Dia merasa agak tertekan karena sejumlah jadwal yang bertumpuk. Sebagai seorang psikolog klinik, tuntutan pekerjaan sering kali mengharuskannya memberikan perhatian penuh kepada para pasien.
Sayang, ada satu hal yang berlangsung tidak seperti yang diharapkan. Dimulai dengan hadirnya pria berusia sekitar 50 tahun dengan rambut yang mulai memutih dan memakai kacamata sebagai klien. Pria tersebut terlihat agak gugup dan gelisah ketika masuk ke ruang praktik Jaya. Beliau duduk dengan tegang di kursi yang telah disediakan. Sayang, Jaya pun hanya memberikan salam singkat dan tampak agak dingin.
Setelan jas berdasi sang klien tampak kusut, seakan-akan memberitakan kondisi perasaan pemakainya yang sedang tidak nyaman. Ekspresi wajahnya terlihat khawatir dan cemas. Matanya tampak gelap dan berkerut, menunjukkan tingkat stres yang cukup tinggi. Beliau sesekali menggigit bibir bawah, antara merasa gugup atau ragu untuk berbicara.
"Jadi, apa yang membawa Anda ke sini, Pak …." Jaya melirik rekam medik di meja, lalu melanjutkan. "... Andi? Padahal, ini rumah sakit untuk ibu dan anak."
Nada bicara Jaya lebih mirip sindiran, seperti ingin meluapkan kemarahan pada pemilik kalimat yang diulangnya, yaitu Pak Atma. Pak Andi berusaha menjawab sopan. "Oh, eh, iya. Itu karena banyak yang merekomendasikan."
Jaya menatap Pak Andi, kemudian memalingkan muka sejenak, seakan-akan ingin menepis sebuah bayangan. Pak Andi bertanya ragu-ragu. “Dok, eh, Pak Jaya, apakah ada yang salah? Anda tampak sedikit ... aneh hari ini,” ucapnya hati-hati.
Jaya jadi sedikit ketus saat menjawab, "Maaf, ini cuma karena ada tugas menumpuk hari ini. Mari kita lanjutkan. Apa yang ingin Anda bicarakan?"
Pertemuan berlanjut dengan suasana yang tegang. Pak Andi benar-benar merasa rikuh. Jaya mencoba berfokus pada perbincangan di antara mereka, tetapi terus merasa terganggu oleh sesuatu yang berputar-putar di dalam benak. Bayu yang hendak menemui Jaya mengintip dari balik kaca pintu dan merasa janggal.
Setelah Pak Andi keluar ruangan, Bayu meminta izin masuk. Terpaksa, Jaya mengiyakan. Bayu pun mengunci pintu ruang praktik Jaya agar mereka bisa berbicara sebentar. "Jay, ada apa, sih? Kok, kamu jutek ke klien?" tanyanya setengah berbisik.
Jaya menghela napas dan menjawab, "Maaf, Bay. Aku lagi ... agak kacau hari ini. Banyak pikiran."
“Bukan cuma hari ini, Jay. Terus terang, aku khawatir banget sama perubahan perilakumu belakangan ini. Beberapa pasien yang aku rekomendasikan ke kamu untuk mendapatkan pendampingan, kasih umpan balik negatif soal sikapmu yang ketus dan tergesa-gesa selama sesi konseling. Makanya aku ke sini. Kamu sebenarnya ada masalah apa, sih? Kamu tahu dong, kalau bisa bicara ke aku?” ungkap Bayu prihatin.
Jaya, yang sudah sangat tertekan, merasa sangat kesal. “Kamu nih, orang lagi kerja malah diganggu dengan bahasan masalah pribadi begini. Seenggaknya, kamu dukung aku tetap profesional dong. Kaya enggak ada waktu lain aja,” semprot Jaya yang kemudian memberi isyarat Bayu untuk keluar.
Setelah semua sesi bersama klien yang penuh ketegangan dan kesalahpahaman berakhir, Jaya keluar dari ruang praktik dengan perasaan bercampur aduk. Jaya terkejut karena bertepatan dengan Bayu yang sedang melintas akan pulang.
Roman wajah Bayu mencerminkan perasaan terluka. Seumur-umur, belum pernah Jaya melihat Bayu yang biasa ceria jadi semuram itu. Mata Bayu memandang tajam ke arah Jaya. Keduanya diam sejenak. Atmosfer di antara mereka begitu tegang.
Jaya merenung sejenak, kemudian mengajak Bayu masuk kembali ke ruang praktik. Di sana, Jaya duduk mencoba mengumpulkan kata-kata yang tepat. "Bay, ada beberapa hal yang sedang aku hadapi," ujarnya lirih. "Aku harus menghadapinya sendirian."
Bayu memandang Jaya dengan kepala sedikit dimiringkan. "Kenapa kamu enggak mau bicara ke aku?” tanyanya.
Air muka Jaya kembali menegang. “Kalau aku cerita, apa yang bisa kamu mengerti, Bay? Hidup ini enggak adil! Semua orang berbohong, dan aku hanya ingin tahu kebenaran,” tandas Jaya geram.
Bayu jadi terpancing untuk ikut gusar. Namun, dia berusaha kembali tenang. "Aku enggak tahu sih, apa yang sedang kamu hadapi. Tapi, kayanya sulit banget, ya? Cuma nih, Jay, marah dan mengabaikan pekerjaan itu enggak akan mengubah apa pun. Kamu harus bicara sama orang-orang yang peduli sama kamu. Ada aku, Profesor Wijaya, Pak Atma …."
Reflek Jaya melengos mendengar nama yang terakhir disebut Bayu. Bayu mendadak heran. Sebelum Bayu bertanya lebih jauh, Buru-buru Jaya berusaha membelokkan topik.


 faridapane
faridapane