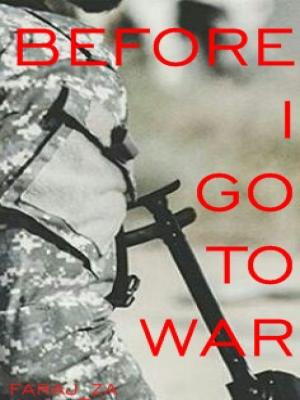* Kinar, gue dah di depan rumah lo.
* Waittt… ya Nel.
* Oks.
* Nel, gue otw ke depan.
Itu isi percakapan WhatsApp gue dengan Kinar. Gak lama Kinar keluar dari balik pagar rumahnya. Penampilannya kasual banget: memakai kaos putih polos, jeans biru tua, sneakers dan tas tenteng modis. Satu lagi, wanginya Kinar seperti habis diguyur bunga seribu rupa. Ibu-ibu millenials banget gayanya. Di belakang Kinar mengekor seorang pria yang sepertinya lebih tua dari gue dan Kinar. Itu pasti suaminya. Batin gue. Gue pun turun dari mobil.
“Janel, ini kenalin, Mas Adi, suami gue.”
Gue tersenyum hangat sambil mengulurkan tangan pada pria dengan badan agak gemuk tersebut.
“Hai, Mas. Janel.” Gue memperkenalkan diri.
“Halo. Adi,” balas Adi ramah. “Rumah di mana?” tanya Adi basa-basi.
“Cibubur, Mas.”
Lalu mata Adi melirik ke mobil gue. “Wah.... mobilnya keren loh. Mas Boy banget nih ceritanya,” ujar Adi mengomentari mobil BMW E30 M40 hitam gue.
Mobil itu memang identik sekali dengan film remaja paling iconic era 1980an: Catatan Si Boy dan sampai hari ini masih diburu orang.
“Makasih, Mas.”
“Perawatannya gimana, ribet gak?” selidik Adi.
“Umm... lumayan sih....”
“Udah akh! Nanti aja ngobrolin mobilnya. Entar kita kesiangan.” Kinar langsung memotong percakapan gue dengan Adi. “Mas... aku jalan dulu ya. Udah tenang, pokoknya aman kalo sama di Janel.” Kemudian Kinar mencium Adi di kedua pipinya.
“Apaan sih kamu?” ujar Adi malu-malu.
Melihat adegan ini gue hanya tertawa tipis. “Jalan dulu ya, Mas.”
“Ya wis, hati-hati ya, Nel,” sahut Adi.
“Baik, Mas.”
Lalu mobil melaju menuju daerah Bogor, tempat Raska katanya sedang direhabilitasi.
***
“Suami lo kayaknya asyik ya, Kin. Gak cemburuan.”
“Terlalu lempeng orangnya, Nel. Malah gue gak suka. Sering gue pancing-pancing dia buat cemburu ke gue, tapi jawabannya cuman, ‘Aku tuh udah percaya sama kamu, jadi buat apa cemburu? Cemburu hanya untuk anak ABG.’ Sebel, gue!”
“Hahaha. Kenal di mana sih lo?”
“Teman kantor.”
Gue manggut-manggut.
“By the way, Nel, lo sering ya nongkrong di Jazztro itu?”
“Yah... sebulan, bisa tiga sampai empat kali lah. Lumayan buat ngilangin stres. Kantor gue gak jauh dari Jazztro soalnya. Jalan kaki cuman lima menit.”
“Lo kok jadi suka Jazz gitu sih? Dulu, perasaan lo suka Nirvana, Oasis, Pearl Jam, pokoknya yang nge-rock gitu deh. Gue inget banget lo waktu SMA, style lo rebel kayak Kurt Cobain.”
Gue ketawa. “Umur, Kin. Makin tua kan kita makin suka ketenangan. Tapi kalo dengerin rock mah masih suka aja.”
“Oh ya, kemarin gue sampe lupa nanya. Lo kerja di mana, deh?”
“Di T3XT, T.3.X.T.” Gue mengeja, “Agency iklan. Sebagai creative director.”
“Elo tuh dulu kuliah apa emangnya? Jadi masuk film?”
“Enggak. Gue ambil desain grafis alias DKV.”
“Oh. Gue pikir lo bakal kuliah film. Soalnya dari SMA kan, lo udah cerita, kalo lulus lo mau lanjut kuliah film, karena cita-cita lo itu bikin film.”
Gue tersenyum getir. “Gak jadi. Tapi dunia gue kadang gak jauh juga sih dari bikin film, iklan, video klip. Ya… gitu deh.”
“Good dong. Artinya cita-cita lo tetap kesampaian.”
“Tapi sebenarnya, gue gak lulus, Kin. Udah keasyikan kerja. Hahaha.”
“Akh, santai aja. Lo boleh gak S-1. Yang penting duit lo harus S-3!”
“Amin, amin!” kata gue dengan senyuman lebar.
“Tapi jangan lupa... kalo udah banyak duit, ikut asuransi. Jadi klien gue!”
Tawa gue dan Kinar pun pecah di dalam mobil. Lalu pembicaraan berganti pada yang lebih serius, soal Raska.
“Kayak gimana ya si Raska sekarang, Kin?”
“Gak tau, deh,” ujar Kinar tanpa memandang gue. Ada jeda beberapa saat sebelum Kinar kembali bicara. “Kenapa sih dia, masih aja kayak gitu? Make, sembuh, terus make lagi, tobat lagi, make lagi, begituuuu.... terus.”
Gue menerawang. “Mungkin ada luka yang dia terus bawa selama bertahun-tahun. Sampai Raska pikir, hanya drugs yang jadi pelarian terbaik dia. Tapi itu ironis sih, dia mengobati luka batinnya dengan racun mematikan.”
“Lo lagi bahas apaan sih? Bukan soal gue sama dia dulu kan?”
“Enggaklah! Ini soal hubungannya sama Bokapnya. Kan selalu itu curhatan dia. Bagaimana dia sama Richie selalu diperlakukan beda. Lo tau, kan?”
“Kalo itu sih, tau.” Kinar lalu terdiam, hanya memandangi jalanan.
“Ngomong-ngomong, suami lo tau lo bakal ketemu sama mantan pacar?”
“Gue cerita semuanya kok. Siapa itu Raska, Mas Adi tau banget. Malah dia yang nge-push gue supaya ketemu Raska. Berbuat baik itu gak ada salahnya, kata dia.”
Gue tersenyum. “Suami yang langka.”
Sekitar satu setengah jam kemudian, gue dan Kinar akhirnya sampai di depan sebuah bangunan tua bergaya kolonial, setelah sebelumnya mampir beli buah dan roti untuk Raska. Kami berdua celingukan, mencoba memastikan.
“Benar ini kan alamatnya?” selidik gue.
“Kalo berdasarkan alamat yang dikasih Richie dan gue lihat di Google Maps, udah benar,” tukas Kinar memastikan.
“Ya udah, kita masuk aja.”
Mobil pun masuk dan terparkir di halaman bangunan bernama, Yayasan Citra Sesama tersebut. Tampak depan, bangunan terlihat putih cerah. Sepertinya bangunan ini baru direnovasi. Gue turun sambil menenteng tidak hanya plastik berisi buah dan roti tapi juga sebuah tas kecil yang isinya mengundang rasa penasaran Kinar.
“Itu apaan yang lo bawa?” selidik Kinar menunjuk pada tas kecil bawaan gue.
“Oh ini? Nanti juga lo tau.”
Kinar hanya merespons datar, “Oh, oke.” Kami kemudian melangkah menghampiri resepsionis di lobi.
“Selamat pagi....” sapa Kinar ramah pada petugas berseragam biru-biru.
“Iya, pagi Ibu.”
“Saya mau menjenguk teman. Namanya, Raska. Bisa?”
“Tunggu sebentar ya, Bu.” Petugas pria yang terlihat seperti baru lulus SMA itu mengecek sesuatu di komputer.
“Oh, Raska Nesardo, ya?”
“Betul,” sahut Kinar.
“Ibu sama Bapak, boleh tunggu sebentar. Kebetulan jam berkunjung baru saja dibuka.”
“Oke.”
Tak lama menunggu, gue dan Kinar diantar ke dalam bangunan, masuk jauh ke belakang, ke sebuah taman luas yang tampak asri.
“Itu kamarnya Mas Raska. Yang nomor tujuh belas. Kebetulan, itu ada Mas Raska-nya sedang duduk.” Petugas mengarahkan pandangan gue dan Kinar pada sesosok pria kurus yang sedang duduk berjemur dan merokok seorang diri di teras kamarnya yang menghadap ke taman.
Gue dan Kinar tertegun selama beberapa saat.
“Terima kasih ya, Mas,” kata gue pada petugas yang langsung pamit.
Kami pun berjalan perlahan mendekati Raska. Raska di masa SMA, adalah seorang idola para gadis remaja. Dia tampan (sebagian teman bilang dia mirip alm. Ryan Hidayat, si aktor legenda pemeran karakter Lupus yang terkenal banget di tahun 80an), dari kalangan berada, anak gaul Jakarta, dan jago main roller blade - itu semacam sepatu roda yang sempat populer di era 90an - dan sampai sekarang sepertinya masih ada yang mainin. Bukan cuma itu, Raska bahkan sempat ikut dalam ajang kontes cover boy majalah. Tapi dia telah salah melangkah, salah arah dan salah tujuan. Ironisnya, dia gak pernah lagi kembali ke titik sebelum dia jatuh.
“Boncuuuuu.......” teriak gue antusias saat udah berjarak hanya beberapa meter dari Raska. Boncu adalah panggilan lain Raska di kalangan teman-teman akrabnya. Jadi kadang dia dipanggil Raska, kadang dipanggil Boncu. Random sih.
Raska menoleh. Sorot matanya langsung menyipit tajam. Sisa ketampanan masa remaja masih terlihat darinya. Tapi garis-garis di wajahnya gak bisa berdusta. Raska terlihat menua. Bukan tua yang alami tapi tua akibat konsumsi narkotika yang menahun. Dia kini adalah mantan idola.
“Nelll!“ Raska membalas tak kalah antusias. Dia segera membuang rokok, bangkit dari duduknya, menghampiri dan memeluk gue dengan erat.
“Gilak! Apa kabar, lo?”
“Baik, Bro!” jawab gue dengan senyum lebar.
Kemudian mata Raska melirik pada Kinar. Mereka saling tatap lalu terdiam.
“Hai, Raska, apa kabar?” tanya Kinar segan, membuka pembicaraannya dengan Raska.
“Hai... Kin.” Raska tersenyum tipis. Ada sedikit canggung dari gayanya. “Yah, seperti yang elo lihat sekarang,” ujar Raska lirih. Dia lalu diam sejenak sembari tak henti memandangi Kinar. “Kita duduk aja kali ya, di sana,” ujarnya.
“Ide yang bagus,” timpal gue.
Gue, Kinar dan Raska lalu duduk saling berhadapan di teras kamar Raska. Sempat dia nanya perihal suguhan tapi gue dan Kinar menolak, karena gak mau ngerepotin.
“Ini buat elo.” Gue menyerahkan kantong plastik berisi buah dan roti.
“Akh, pake repot segala,” kata Raska sambil menyambar sebatang rokok baru dan membakarnya.
“Nggaklah. Soalnya pake uang Kinar. Kalo pake uang gue baru repot.”
Mendengar celoteh gue, Kinar tertawa. Sedangkan Raska, hanya tersenyum tipis.
“Taruh mana, nih, Nyet?” tanya gue.
“Di dalam aja, Nel,” pinta Raska.
Gue menaruh tas plastik di sebuah meja di dalam kamar. Lalu gue kembali ke teras.
“Kalian kok bisa berduaan datang ke sini?” tanya Raska penuh selidik.
“Panjang ceritanya. Yang pasti gue sempat ketemu abang lo, si Richie,” jawab Kinar.
“Oh gitu. T’rus Richie bilang apa?”
“Yah, Richie cerita kalo elo di sini. Gue lalu nyari Janel, ketemu dan ngajak dia untuk nemuin elo.”
Raska menghisap rokoknya. Kepalanya tertunduk untuk segera tegak lagi melihat pada gue dan Kinar. “Gue benar-benar gak nyangka ada yang mau kunjungin gue. Makin gak nyangka lagi, itu kalian, Nel, Kin. Terima kasih, ya. Gue senang banget ketemu kalian,” kata Raska lirih.
Gue berdiri dan menghampiri Raska. “Santai brotherrr... Kita ini kan, sahabat lama.”
Boleh percaya atau enggak, gue sama Raska udah saling manggil brother sejak SMA, jauh sebelum istilah itu populer seperti sekarang.
“Kenapa elo bisa kembali ke sini?!” Tiba-tiba Kinar melontarkan pertanyaan yang menurut gue agak tajam dan sensitif.
Pandangan Raska mendadak gak lagi fokus. Dia menghisap rokoknya dengan liar. “Please, jangan tanyain itu ke gue, Kin.”
“Dua puluh tiga tahun berlalu dan elo masih betah di titik ini, Ras?!”
Pandangan mata Raska semakin bergerak liar. “Gak tau, mungkin ini emang udah takdir gue.”
“Elo salah! Gak ada yang namanya takdir tapi buat hidup lo hancur kayak gini. Ini bukan takdir, ini adalah keputusan yang elo buat sendiri dengan sadar dan seharusnya ini bisa diubah!”
Raska menghisap dalam-dalam rokoknya. “Tolong kasih tau pendapat lo itu ke Bokap gue, jangan ke gue!” ucap Raska dengan nada sinis tanpa memandang Kinar.
“Masih aja lo nyalahin masa lalu dan orang lain!” ketus Kinar, pelan tapi tajam.
Raska langsung menatap tak suka pada Kinar. Dia sontak berdiri. “Gue pikir, lo datang buat bikin gue senang. Tau gitu, mendingan lo pulang aja, deh!” Raska kemudian menatap gue. “Bilangin temen lo, Nel, gak usah datang jauh-jauh kalo hanya untuk khotbah!”
Gue yang ada di tengah-tengah jadi salah tingkah sendiri. Raska bergegas masuk ke kamar. Lalu gue lihat Kinar menarik napas panjang, menggamit tas sambil berdiri, bersiap untuk pergi.
“Kin, lo mau ke mana?” tanya gue.
“Pulanglah. Gak ada artinya juga setelah gue pikir-pikir datang ke sini. Orangnya belum berubah.”
Kinar serta-merta pamit. Gue jadi panik sendiri.
Gue mengejar Kinar. “Kin... tunggu sih!”
Kinar berhenti dan menoleh. “Mau apa lagi yang lo harapin dari orang kayak gitu, Nel? Lo lihat aja sendiri, dia tuh gak bisa berubah!”
Gue melihat Kinar dengan heran. “Kok lo ngomong gitu?”
“Lo kalo masih mau nostalgia sama dia, gak apa-apa, Nel. Gue bisa pulang sendiri. Tapi gue ke sini bukan mau nostalgia. Gue hanya ngikutin apa yang nurani gue bilang, nolong dia supaya sembuh.”
“Kin... please lah. Jangan kayak gini. Cara lo bicara aja tadi udah salah sama dia. T’rus lo berharap bisa nolong gimana? Jelas itu gak bisa nolong dia. Coba lo pikir kalo jadi dia, lagi terpuruk terus di-judge kayak tadi.”
Kinar menatap gue lama. Dia lalu menarik napas dan mengangguk. Seperti menyadari sesuatu. “Maafin gue, Nel, gue bikin kacau suasana. Gak tau nih, kenapa gue jadi emosi gini.”
Bibir gue tersungging tipis. “Gue tau. Ini pasti ada sangkut pautnya sama masa lalu.”
Kinar menatap gue tegas. “Maksud lo?”
“Maksud gue, lo tadi sampai ngomong kayak gitu sebenarnya bukan Kinar dari 2019 tuh yang ngomong. Tapi Kinar dari 90an. Kinar yang masih marah sama apa yang dulu dia alamin, dan pas banget, Raska sebagai pelakunya hari ini tepat ada di hadapan elo.”
Kinar membisu. Ia kembali menghela napas. Pandangannya mengarah tak tentu arah. Raut tegang di wajahnya perlahan mengendur.
“Lo benar, Nel. Gue memang masih marah sama dia. Masih dendam karena semua perbuatan dia di masa lalu.” Mata Kinar mulai memerah.
“Gue ingat, di Jazztro kemarin lo bilang gini, kalo elo sama gue sengaja dipertemukan untuk suatu tugas. Jadi sekarang, kenapa gak lo fokus ke tugas yang lo bilang itu? Ketimbang lo fokus sama perasaan lo.”
“Sekali lagi maafin gue, Nel. Soalnya gue tuh kayak dejavu pas tadi ketemu dia. Kemarahan gue di masa lalu bangkit lagi.”
“It’s OK. Manusiawi kok. Jadi... gak jadi pulang dong?”
Kinar tersenyum dan menggeleng. Ia langsung melangkah cepat kembali ke kamarnya Raska dan gue mengekor di belakang dia. Kinar lalu masuk ke dalam kamar, mendapati Raska yang lagi ngerokok dan asyik main game di HP.
“Raska...” sapa Kinar pelan.
Raska menoleh santai. “Belum pulang?” Ia membalas Kinar dengan dingin. “Apa mau ngambil buah sama rotinya? Tuh, bawa aja.”
“Raska, gue mau minta maaf sama perkataan gue tadi. Gue sama sekali gak ada niat nyakitin perasaan lo.”
Raska mengangguk pelan sambil terus main game. “Gak masalah.”
“Gue yang tadi bicara, itu adalah gue yang masih marah sama elo dari zaman kita masih pacaran dulu. Gue tau, harusnya gue gak boleh kayak itu.”
Raska langsung berhenti main game dan mematikan rokok. Kali ini tatapan Raska agak berbeda. Bibirnya terkunci rapat. Ia menatap Kinar tanpa sedikit pun mengerlipkan mata.
“Duduk sih, santai dikit,” timpal gue berusaha mencairkan kekakuan.
Kinar langsung mengambil tempat duduk berdekatan dengan Raska. Gue juga duduk gak jauh dari mereka.
“Gue gak paham ya, maksud dan tujuan lo datang ke sini tuh buat apaan sebenarnya?” ketus Raska.
“Gue udah bilang tadi kan, kalo gue ketemu sama Richie. Jujur Ras, awalnya gue memang gak peduli waktu abang lo cerita soal keberadaan lo. Sekian tahun gue gak pernah tau apa-apa lagi tentang elo, jelas buat gue jejak lo udah bersih di hidup gue.”
“T’rus kenapa lo mau ke sini?”
“Malamnya, saat tidur, hati gue gelisah banget. Gue sadar, permintaan Richie supaya gue kunjungin elo, itu gak bisa gue tolak begitu aja. Hati kecil gue minta supaya gue datang. Lalu gue berucap di hati, kalo memang gue harus datang, gue harus ketemu Janel, karena gue gak mau datang sendirian. Dan… doa gue dijawab! Gue ketemu Janel tanpa sengaja dan dia mau nemenin gue. Makanya gue yakin, gue memang harus nemuin lo.”
Raska membisu. Dia menatap Kinar erat-erat.
“Jadi, kalo hari ini gue masih marah sama elo, itu harusnya gak boleh. Karena kedatangan gue ke sini, itu gak ada hubungan apa pun dengan apa yang terjadi antara kita dulu,” sambung Kinar.
Raska hening, lalu bicara, “Dua minggu lalu, gak tau kenapa gue galau banget. Lalu gue doa. Seadanya sih. Tapi gue bilang, kalo gue pengin banget dikunjungin teman-teman lama gue, siapa pun itu.”
“Serius lo doa kayak gitu?” tanya gue.
Raska mengangguk halus. Gue lalu melirik Kinar.
“Gak ada yang pernah kunjungin lo apa?” selidik Kinar.
“Palingan Nyokap doang. Richie sesekali. Kalo Bokap atau saudara gue yang lain malah gak pernah,” ujar Raska sambil menerawang kosong. “Gue ngerasa gak berguna banget hidup sebagai manusia!”
Gue lihat pancaran wajah Kinar mendadak muram. Bagaimanapun, gue paham, lelaki yang berhadapan dengannya adalah seseorang yang dulu sangat dia cintai. Jadi pastinya dia ikut sedih mendengar curhatan Raska.
“Tapi gue senang banget lihat kalian datang ke sini,” lanjut Raska lirih.
Gue gak tau, apa yang sebenarnya Raska rasakan. Sedangkan Kinar hanya membisu, tenggelam dalam emosi. Dan ketika suasana semakin mengharu-biru, buru-buru gue ambil alih situasi, supaya gak semakin melankolis.
“Cu.... lo lihat nih, apa yang gue bawa?” Gue mengeluarkan album foto bersampul Fuji Image Plaza dari dalam tas kecil yang gue bawa.
“Apaan ini?” Kepala Raska tegak kembali. Ia menyelidik penasaran.
“Lo lihat dong!”
“Anjirrrrr!” Raska teriak, saat dia melihat foto pertama di halaman pertama album. Itu foto gue sama dia berpose di dekat mobil Evo 3 merahnya, saat nongkrong di Mahakam. “Masih ada aja ini?”
“Yoi! Dulu kan ini yang motoin si Phillip. Nah sempat gue minta tuh klisenya dari dia. Gue cetak ulang.”
Raska tertegun melihat foto.
“Masih ada gak sih ini, boil?” tanya gue.
“Udah lama almarhum, Nel! Gue jual tahun 2004.”
“Yah, mobil legend tuh. Sayang banget.”
Kinar lalu merapat, ikut melihat album foto.
“Jadi ini yang lo bawa? Ya ampunnn, Janel, lo masih nyimpan aja. Gue lihat dong!”
“Bareng-bareng aja lihatnya,” ujar gue.
Kami bertiga mulai membuka lembar demi lembar album foto yang tengah dipegang Raska. Sesekali tawa lepas meluncur dari mulut kami. Tapi sesekali kami juga terdiam. Terdiam karena terenyuh melihat foto yang menurut kami sangat bermakna, apalagi jika yang di dalam foto udah gak ada lagi kabar. Lalu tibalah pada foto yang diambil di Taman Situ Lembang. Foto beramai-ramai (gue, Raska, Kinar, Lovi, Boim, Naya, David, Lila, Prisa, Anit dan Amanda) dengan ekspresi bahagia yang sangat tulus. Gue lihat Raska tercenung lama.
“Gila, lo masih simpan foto ini ternyata. Krazy Squad apa kabar, Nel?”
Gue mengangkat bahu. “Ya... satu-dua orang sih masih ada kabar. Tapi kebanyakan gue udah gak tau kabarnya lagi.”
Kinar ikut tercenung. Gue sadar, foto yang barusan mereka lihat, telah mengusik bagian otak besar mereka, di mana memori tersimpan. Karena itu juga yang terjadi pada gue saat koper penyimpan kenangan gue bongkar. Otak besar gue bereaksi.
“I miss them...” ucap Kinar.
Suasana pun menjadi galau sesaat.
“Eh, by the way, temen-temen lo yang lain, geng Nu Girls pada gimana tuh kabarnya? Dari kemarin kita cuman bahas Lovi doang perasaan,” tanya gue ke Kinar.
“Kalo sama Prisa gue masih kontak sih. Tapi itu pun jarang. Kalo yang lain gue udah gak tau lagi.” Lalu Kinar diam sejenak. “Kalian tau, Lila udah meninggal?”
“Oh ya?” sahut gue, terperanjat. “Meninggal kenapa dia?”
“Sakit, Nel, dan itu udah lama banget, di zaman gue baru kerja.”
Lila adalah sosok paling low profile di geng Nu Girls. Suaranya agak cempreng, tapi dia baik banget dan dia cewek yang lumayan pemberani seperti Prisa. Lila dulu adalah wakilnya Prisa, yang jadi kepala geng. Agak sedih gue dengar kabar meninggalnya Lila ini.
Kemudian Raska membalik halaman album foto. Ada foto saat kami (geng KS dan Nu Girls) nganterin Raska ikut lomba roller blade di Senayan, sekitar Januari 1997. Kami bertiga langsung ketawa ngeliat foto ini.
“Ya ampun… ini foto,” sahut Raska penuh arti.
“Anak roller blade banget gak tuh!” timpal gue.
Raska langsung menutup wajahnya.
“Keren tau, Ras!” sambung Kinar.
“Ehemm…”
Gue mencoba menggoda Kinar, tapi Kinar langsung buru-buru mengalihkan pembicaraan. Dia membuka halaman foto berikutnya.
“Lihat yang lain dong!” seru Kinar.
Kemudian ada foto waktu gue dan Raska masih kelas satu, masih pada cupu, foto beramai-ramai (lintas kelas) di lapangan basket. Momennya waktu itu, kami lagi class meeting.
“Angkatan kita tuh ada grup WA gak sih, Nel?” tanya Raska.
“Ada. Lo mau gue masukin?” kata gue sambil tertawa kecil.
“Kadit hasu (tidak usah), selam eug (males gue).” Raska emang dari dulu suka bicara bahasa kebalik, dan gue paham, meski agak susah kalo ngebalasnya.
Gue kembali tertawa. Lalu tangan Raska membalik halaman berikutnya. Ada foto gue, Raska, Kinar dan Lovi berpose bersama di momen double date di Mall Kelapa Gading. Di bawahnya ada foto gue berdua doang sama Lovi.
“Ehemm...” Kali ini Kinar yang berdehem, menggoda gue. “Kalo yang ini sih gue yakin banget, akan disimpan sampai mati.”
“Yaelah... ini kan juga ada kalian berdua.”
Raska hanya tersenyum tanpa bicara kemudian melirik penuh arti pada Kinar. Merasa dipandangi seperti itu, Kinar malah salah tingkah di hadapan gue dan Raska.
“Cieee....” Gue kembali menggoda Kinar dan Raska.
“Apaan sih, lo?! Masa lalu juga!” ucap Kinar mencoba menepis godaan gue.
“Yang bilang masa kini siapa? Gue kan cuman bilang ciee... doang.”
Terlihat banget ada canggung antara Kinar dan Raska. Sepasang insan yang dulu saling mencintai ini, nampak malu-malu ketika foto double date itu diperlihatkan. Lalu dengan cepat, Kinar langsung mengalihkan situasi.
“Ini kalo gak salah pake kameranya Lovi deh fotonya, waktu kita double date itu kan? Sebelum nonton Romeo and Juliet di Kelapa Gading. Seingat gue, kita juga sempat photo box-an nih di sini.” Lalu Kinar seperti mengingat sesuatu. “Tapi foto-fotonya kayaknya udah hilang deh,” sesal Kinar.
“Yah... begitulah.” Gue tertawa tanpa arti. “Tapi yang nge-date sebenarnya kan kalian berdua. Gue sama Lovi cuman jadi nyamuknya.”
“Akh, itu mah karena elonya aja gak bisa manfaatin momen!” tegas Kinar.
Gue tersenyum kecut.
“Kalo si Lovi apa kabar, Nel?” Kali ini Raska yang bersuara.
Gue mengangkat bahu. “Gak tau. Hilang ditelan samudera.”
Kinar dan Raska tertawa kecil.
“Gampang itu. Bisa kita cari,” ucap Kinar, balas menggoda gue.
“Iya, carilah. Kangen gak sih lo sama Ivol?” Raska menimpali. Dia dari dulu memang acap kali menyebut nama Lovi dengan, Ivol.
“Kayaknya sih kangen nih kalo gue lihat-lihat,” tambah Kinar seperti memprovokasi ucapan mantan pacarnya.
“Biasa aja. Udah masa lalu,” ucap gue ngasal.
”Gue gak percaya sama lo, Nel!” sahut Kinar. “Secara lo dulu, tergila-gila banget sama dia. Jadi, gak usah kebanyakan gimmick deh lo!”
“Hahaha.” Kali ini Raska tertawa. Sedangkan gue hanya tersenyum kaku.
Pembicaraan kemudian mengalir terus: Ringan, santai dan gak lagi tegang seperti di awal. Di situ gue bisa melihat kedewasaan Kinar yang luar biasa. Kami bertiga hanya bincang nostalgia, tentang ini, itu, dan semua cerita kenangan di antara kami. Sampai kemudian datang petugas, mengusir gue dan Kinar dengan halus karena katanya udah waktunya Raska istirahat.
“Gak apa-apa ya guys, kalian pulang? Gue harus istirahat soalnya.”
Kinar dan gue sepakat mengangguk.
“It’s okay, Bro!” kata gue.
“Makasih banyak udah datang.”
Kinar menghampiri Raska, lalu memegang tangan Raska. “Jaga diri lo baik-baik, ya. Gue pengin lihat lo sembuh!”
Raska tersenyum samar.
“Raska, gue serius! Gue pengin lihat lo sembuh, dan kali ini, benar-benar sembuh.”
“Iya, Kin,” jawab Raska singkat.
“Kita pulang dulu, Ras!” timpal gue.
Gue sempat bertukar nomor WhatsApp dengan Raska. Lalu gue dan Kinar pamit. Tapi sebelum menjauh, Raska berseru: “Guys!” Gue dan Kinar menoleh. “Balik lagi, ya. Gue mohon.”
Gue memberikan tanda hormat kepada Raska. “Pasti!”
Setelah itu, gue dan Kinar meninggalkan Raska. Di dalam mobil, suasana sejujurnya mellow banget.
“Gue sedih banget, Nel, lihat keadaan dia tadi.”
“Sama. Tapi kita harus tuntasin tugas kita, Kin. Kita harus terus dampingin dia. Lo gak trauma kan?”
Gue tanyakan hal tersebut ke Kinar, karena gue tau betul bagaimana pahit dan pedihnya Kinar saat harus dampingin Raska di masa-masa kelamnya dia, di awal dia kecanduan drugs. Berkali-kali Kinar dibohongin dan ditipu oleh Raska. Banyak barang Kinar yang dijual oleh Raska. Belum lagi janji Raska untuk berhenti. Semua ternyata hanya lip service.
“Maunya gue sih trauma ya, Nel. Perih banget kalo ingat bagaimana jahatnya dia ke gue dulu. Tapi... gue tau, takdir gue udah ditentukan untuk bantu dia, dan gue gak mau ngelawan takdir,” terang Kinar.
“Jadi, kapan kita balik lagi?”
“Terserah. Waktu kerja gue fleksibel kok, kalo lo gak mau kita ke sana nunggu weekend.”
“Gue sih lagi libur nih sampai Rabu,” ujar gue.
“Nah, pas tuh. Selasa aja kalo gitu, kita ke sana.”
“Boleh.”
“Sip.”
Tapi mendadak pikiran gue tergoda satu hal. Dengan terbata gue ngomong ke Kinar.
“Kin...”
“Ya?”
“Gu-ee bo-leh min-ta tolong gak?”
“Apaan?”
“Kan, guu-e udah nolongin lo, nih. Sekarang gantian dong elo yang nolongin gue.”
“Nel! To the point aja deh! Lo mau apa?”
“Bantu gue, kita cari Lovi,” jawab gue malu-malu.
Kinar langsung tertawa. “Apa kata gue! Lo ternyata emang gak bisa move-on, kan?!”
“Jangan gitu dong. Gue cuman pengin ketemu dia doang kok. Serius!”
Kinar senyam-senyum. “Tenang, Nel. Kita akan cari Lovi sampe ketemu. Tapi kenapa sih, lo pengin banget ketemu dia?” tanya Kinar.
Gue diam. Hanya memandang lurus ke depan. “Terus terang, Kin, setelah pertemuan kita semalam, gue baru sadar, Lovi ternyata gak pernah benar-benar pergi dalam hati dan pikiran gue. Karena selalu ada ruang buat cerita tentang dia. Gue jadi ngerasa bahwa memang ada sesuatu yang harus gue selesaikan dari masa lalu.”
Kinar manggut-manggut. “Boleh gue tanya satu pertanyaan lagi?”
“Apa?”
“Perasaan lo itu, yang dulu ada waktu SMA, apa sekarang masih ada?”
Gue gak segera menjawab. Lama gue mikir sampai akhirnya keluar juga kata-kata dari mulut gue, “Masih, Kin! Gue gak bisa bohong, perasaan itu masih ada, dan gue.... kangennn... banget sama dia!”
Dengan setulus-tulusnya, perkataan itu akhirnya meluncur dari mulut gue.


 stanxmeulen
stanxmeulen