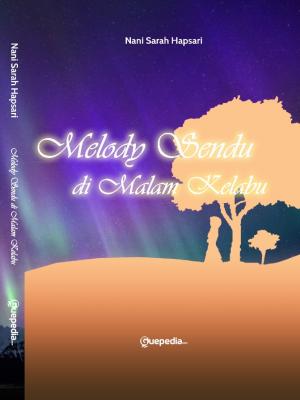Seperti biasa, rumah Ara selalu kosong pada jam sibuk seperti ini. Orangtuanya bekerja, sedangkan kedua kakaknya kuliah, praktis Ara akan sendirian lagi.
“Thanks ya, udah nganterin gue pulang,” ucap Ara pada Iago sebelum dia membuka pintu mobil.
“Anytime.” Namun bukannya pergi, Iago malah mengekori Ara masuk ke dalam rumah.
“Go, lo ... ngapain?” tanya Ara ragu.
“Lo sendirian, kan?”
“Hah?” Ara melongo. “M-maksud lo....”
“Gue temenin lo sampe orang rumah lo ada yang pulang,” jelas Iago, tak ingin Ara salah paham terhadap niat baiknya.
“Nggak usah! Gue udah biasa sendirian.”
“Masalahnya lo itu sedang sakit, Ra! Kenapa dari tadi gue dibantah terus sih?!”
Ara membuka mulut, kemudian kembali menutupnya sebelum ada sepatah kata pun yang terlontar. Tenggorokannya tiba-tiba saja tercekat.
“Gue nggak ada maksud apa-apa kok. Gue cuma,” Iago mengambil jeda, menarik napas dalam-dalam, “nggak mau lo kenapa-kenapa.” Dalam hati, sebenarnya bukan itu yang ingin Iago ucapkan. Namun jika Iago mengucapkan yang sebenarnya, dia takut akan merusak suasana hati Ara.
“Oke.”
Iago mengekori Ara masuk ke dalam rumah. Seperti yang sudah dibayangkannya, sepi. Walau begitu ada jejak-jejak kehangatan yang tersebar di seluruh penjuru rumah. Pasti jika semua penghuni rumah sudah pulang, suasana rumah akan terasa hangat kembali.
“Kamar gue ada di lantai dua,” beri tahu Ara.
“Dapur lo di mana?” tanya Iago.
“Hah?” Lagi-lagi Ara gagal memahami maksud Iago.
“Gue mau bikinin lo air hangat buat kompres perut,” terang Iago. “Lo naik duluan aja.”
“Oh, di sana,” sahut Ara, seraya mengarahkan telunjuknya ke arah dapur. “Kantong air panasnya ada di kotak P3K deket dapur. Punya gue yang warna biru ada gambar Eyore-nya,” lanjutnya.
Iago mengangguk, kemudian menuju ke arah yang ditunjukkan oleh Ara.
Ara tercenung, mematung memperhatikan punggung Iago hingga cowok itu menghilang di balik tembok yang memisahkan ruang keluarga dan dapur. Terus terang apa yang dilakukan Iago membuat hati Ara tergerak. Padahal tadi pagi dia sudah memperlakukan Iago seperti itu.
“Duh, kenapa gue jadi mellow gini, ya?” gumam Ara. Tak ingin pikirannya makin melantur ke mana-mana, Ara memutuskan untuk naik ke kamarnya.
Lagi-lagi ketika sudah di kamar, pikiran Ara melayang, memikirkan Iago. Dari awal mereka bertemu, kemudian berkenalan dengan dengan cara yang tidak biasa, selalu bertengkar setiap kali bertemu, juga ada kalanya mereka berdamai seperti layaknya teman. Baru saja Ara sadari, jika hubungannya dengan Iago terbilang cukup unik.
Ketukan pada daun pintu membuyarkan lamunan Ara. Iago berdiri di ambang pintu. “Gue boleh masuk?” tanyanya kikuk.
“Masuk aja,” balas Ara. “Tapi pintunya jangan ditutup ya.”
Iago mengangguk. Cowok itu duduk di tepian tempat tidur, lalu menyerahkan kompres air panas kepada Ara.
“Thanks.”
“Masih sakit?” Tanpa permisi Iago menyentuh perut Ara, membuat tubuh cewek itu menegang karena terkejut.
“Masihlah,” jawab Ara, lantas menyingkirkan tangan Iago dari perutnya. “Kenapa lancang banget sih? Pakai pegang-pegang perut cewek?” omel Ara sok jutek, padahal tanpa dia sadari, semburat merah muda mulai menjalari wajahnya.
“Sori,” ucap Iago. “Gue nggak ada maksud apa-apa kok.”
Ara meletakkan kompres air panas di perutnya. Rasa nyaman seketika menjalari, mengurangi nyeri serta rasa mulas yang sedari tadi terasa begitu mengganggu. “Lo kayaknya nggak asing banget sama hal beginian?” tanya Ara.
“Kakak gue ada empat. Cewek semua,” jawab Iago. “Dulu waktu masih tinggal serumah, mereka pasti bawel banget kalau lagi datang bulan.”
Ara terkekeh. “Derita lo.”
Iago hanya menanggapinya dengan senyum tipis. Dilihat dari sorot matanya, cowok itu sepertinya sedang bingung. Ada banyak hal yang ingin dia ucapkan, tapi ada sesuatu seolah menahannya.
“Go, makasih ya....” Jujur saja Ara agak malu mengucapkannya.
“Hari ini udah berapa kali lo bilang makasih sama gue?” respons Iago tanpa bermaksud menyindir.
“Terus ... gue juga mau minta maaf soal kejadian tadi pagi,” lanjut Ara tanpa memedulikan respons Iago. “Nggak seharusnya gue nyiram kepala lo.”
“Tapi mungkin gue emang pantas menerima itu.” Iago menarik masing-masing sudut bibirnya, tersenyum datar. Detik berikutnya dia menunduk, entah memikirkan apa. “Setelah dipikir-pikir, sebaiknya gue emang lebih baik angkat kaki dari hidup lo.” Iago mengangkat kepalanya, menatap Ara lurus-lurus. “Gue udah bikin banyak masalah di hidup lo.”
Ara memekik lirih. Harusnya Ara senang mendengar ini, bukankah memang ini yang dia harapkan? Lantas kenapa hatinya malah tidak rela?
“Kata-kata gue malam itu...” Iago berhenti beberapa saat, “...gue nggak bohong. Gue sayang sama lo. Tapi setelah dipikir ulang, gue juga nggak mau egois. Gue pengin bantu lo, pengin banget. Cuma kalau lo nggak mau, lebih baik gue mundur.”
Rasa kecewa menyusup begitu saja di hati Ara. Iago yang berbicara dengannya saat ini seperti bukan Iago yang Ara kenal. Iago yang Ara kenal adalah cowok keras kepala yang tidak akan mundur sebelum mendapatkan apa yang diinginkannya.
“Semoga dengan gue angkat kaki dari hidup lo, Lisa juga nggak akan gangguin lo lagi,” tutup Iago.
Ara tersenyum miring ketika mendengar nama itu disebut. “Lo tahu kenapa gue benci banget sama Kak Lisa?” tanya Ara sekadar berbasa-basi, sebab dia sendiri tahu jika Iago pasti tidak tahu apa penyebabnya.
Iago menggeleng.
“Nih,” Ara menunjuk pergelangan kaki kirinya, “gue cacat gara-gara dia. Dan ... karena itu juga gue mutusin keluar dari tim cheer.”
Tak ada respons apa pun dari Iago. Cowok itu hanya memperhatikan pergelangan kaki yang ditunjuk oleh Ara.
“Kak Lisa sengaja bikin gue cacat karena saat itu gue digadang-gadang bakal gantiin dia sebagai ketua tim,” imbuh Ara menjelaskan. Detik berikutnya Ara tertawa sumbang. “Tenang. Ini nggak ada kaitannya sama lo kok. Sama sekali nggak ada.”
Kedua tangan Iago mengepal. Diam-diam, dada cowok itu mulai dipenuhi dengan amarah. “Gimana kejadiannya?” geram Iago.
Ara membetulkan posisi kantong air panasnya, lalu memulai, “Waktu itu kami sedang latihan formasi piramida. Gue paling atas, Kak Lisa ada di bawah gue. Dia sengaja jatuh, biar gue juga ikutan jatuh. Setelah gue jatuh, Kak Lisa nginjek kaki gue.” Ara menarik napas kuat-kuat, menyusupkan banyak-banyak oksigen ke paru-parunya. Mengingat kejadian itu, tak ubahnya seperti mengorek kembali luka lama yang sudah sekian waktu terabaikan. “Waktu itu gue nggak mikir macem-macem,” Ara mulai sesenggukan, “gue bener-bener mikir kalau Kak Lisa nggak sengaja. Tapi setelah gue denger Kak Lisa ngomong sama Kak Ratih soal dia nggak mau digeser dari posisi ketua, gue langsung tahu kalau semua itu emang disengaja.”
Ragu-ragu, Iago memegang pundak Ara. Menepuknya lembut untuk menenangkan cewek itu.
“Sampai sekarang pergelangan kaki gue kadang-kadang masih terasa sakit, apalagi kalau kelamaan berdiri,” Ara melanjutkan, tangannya buru-buru menyeka air mata agar tak sampai terlihat oleh Iago.
“Gue pernah lihat IG lo, di situ ada foto lo berdua sama Lisa—”
“Gue berusaha berdamai dengan kejadian itu, Go,” potong Ara. “Gue marah. Benci banget sama Kak Lisa. Tapi gue berusaha maafin dia. Gue nggak mau menyimpan sampah di hati gue....”
Tangan Iago yang semula berada di bahu Ara, kini berpindah ke kepala cewek itu. Iago mengelus kepala Ara dengan sayang. “Kenapa hati lo bisa baik banget sih?” komentar Iago.
“Sampah kalau dibiarin lama-lama akan membusuk. Sesuatu yang busuk malah bikin luka di hati gue tambah parah. Jadi gue mikir, mendingan gue buang semua rasa marah dan benci gue. Dengan begitu meski gue udah nggak bergabung di tim cheer lagi, gue masih bisa menjalani hari-hari gue seperti nggak ada yang terjadi.”
“Pasti berat banget buat lo,” anggap Iago.
Ara mengedikkan bahu. “Sebenernya nggak juga. Hidup gue baik-baik aja kok meski gue udah keluar dari tim cheer. Tapi kejadian malam minggu itu bikin rasa benci yang selama ini gue abaikan mencuat kembali. Gue benci banget sama Kak Lisa, Go!” geramnya, kedua tangan Ara mengepal.
“Ra,” Iago meraih masing-masing tangan Ara dan membuka kepalan tangan cewek itu, “soal kejadian malam itu, gue yang salah.” Iago berusaha meredam emosi Ara. “Kalau aja gue nggak minta bantuan lo, lo pasti nggak akan terlibat....”
Ara menghela napas panjang, lalu mengembuskannya dengan cepat. “Karena udah terlanjur kejadian kayak gini, menurut lo kita harus gimana?”
“Hah? Maksud lo?” Iago menelengkan kepala, melemparkan pandangan penuh tanya.
“Setelah malam itu, bahkan sampai tadi pagi gue masih menyalahkan lo. Padahal kita berdua tahu kalau itu bukan salah lo. Setelah Kak Lisa nyamperin gue tadi, gue rasa nggak ada salahnya juga bikin dia putus asa.”
Tatapan Iago melunak, mulai mengerti arah pembicaraan Ara.
“Gue mau bantuin lo. Jadi pacar lo selama sehari,” imbuh Ara. “Tapi setelah itu, kita bener-bener putus hubungan. Jalan sendiri-sendiri, kembali kayak dulu ... waktu kita berdua belum saling kenal.”
“Oke,” lirih Iago. Pikiran dan perasaannya masih berkecamuk. Setengahnya Iago merasa tidak rela, tapi setengahnya lagi dia harus rela. Sebab itu semua demi keselamatan Ara. Ara harus bertemu dengan cowok yang tulus mencintainya—juga, bisa membuat Ara jatuh cinta. “Sebagai gantinya, gue akan bantu lo cari cowok itu. Percaya sama gue, pasti ketemu,” kata Iago yang nada bicaranya dibuat seceria mungkin, berharap Ara akan kembali bersemangat.
“Prince can do anything.” Ara menirukan kalimat yang pernah diucapkan oleh Iago. “Ngomong-ngomong gue juga nggak tahu, kenapa sama lo gue bisa cerita segalanya.” Ara tersenyum miring. “Soal gue dan Kak Lisa hampir-hampir nggak ada yang tahu. Cuma Vika dan Monic. Mereka berdua juga nggak pernah mengungkit karena tahu kejadian itu adalah luka bagi gue. Dan hari ini, gue malah mengungkit luka itu di hadapan lo.”
“Gue bukan Tuhan yang bisa sembuhin luka di hati lo atau menghapus kebencian lo. Tapi gue akan tetep sama-sama lo biar lo nggak sampai terluka lagi,” balas Iago.
Hening. Tak ada kata.
Ara dan Iago saling menatap, bertukar kalimat tanpa perlu berucap. Di saat inilah Ara merasa bila perutnya menggelenyar, rasanya asing dan aneh. Lucunya rasa itu cukup menyenangkan.
“Perut lo udah baikan?” tanya Iago, sengaja mengalihkan topik agar suasana mencair.
“Udah mendingan,” jawab Ara.
“Gue temenin lo sampai ada orang rumah lo yang pulang.”
“Nggak usah!” tolak Ara otomatis. “Lo balik aja ke sekolah.”
“Udah nggak minat balik ke sekolah.”
“Ck—”
“Lo istirahat aja. Kalau perlu apa-apa, bilang sama gue.”
Desahan pasrah lolos dari bibir Ara. Walau kelihatannya sudah lebih jinak, Iago tetaplah Iago, yang tak akan berhenti sebelum tujuannya terlaksana.
“Go,” Ara memberanikan diri untuk menatap wajah Iago, “lo sendiri gimana?” Telunjuk Ara menyentuh lebam di wajah Iago dengan hati-hati.
Iago meringis. “Masih sakit sedikit,” lirih Iago. “Tapi yang terpenting buat gue, lo nggak kenapa-kenapa,” lanjutnya.
Wajah Ara memanas dan untuk mengatasinya, dia buru-buru bersikap tak acuh. “Gue tetep aja kenapa-kenapa, Go,” ujar Ara.
Iago melotot. “Mana? Bagian mana lo yang sakit? Lo sempat dipukul mereka sebelum gue dateng?” cecar Iago. Khawatir.
“Nggak! Nggak!” Ara mengibaskan tangannya. “Gue nggak dipukul kok. Gue nggak apa-apa. Gue baik-baik aja,” konfirmasi Ara.
“Ya udah. Lo istirahat aja,” balas Iago. “Biar lo cepet baikan. Gue nggak terbiasa sama lo yang lembek gini.”
“Lembek gimana maksud lo?”
“Lo biasanya galak.”
“Ck....”
“Udah. Lo istirahat sana.”
“Lo ternyata lebih bawel daripada nyokap gue,” ujar Ara, lantas membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur dan bersembunyi di balik selimut. Diam-diam meski berusaha terlihat tak acuh, Ara sebenarnya tengah berusaha keras menahan senyumnya.
*


 sandrabianca
sandrabianca