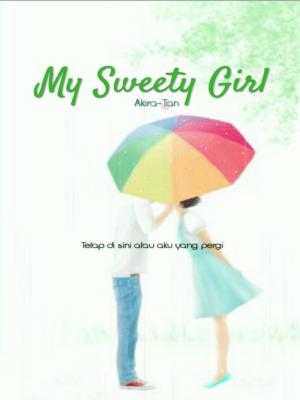Iago tersentak sendiri setelah melontarkan kalimat itu. Di depannya, Ara hanya bisa bengong. Cewek itu terbelalak dengan mulut setengah terbuka.
“Apa ekspresi lo selalu kayak gini setiap kali ada cowok yang nembak lo?” tegur Iago memasang ekspresi datar, padahal dadanya berdegup kencang. Ini memang bukan kali pertama Iago meminta seorang cewek untuk menjadi pacarnya, tapi ini akan jadi kali pertama dia ditolak oleh cewek. Iago tahu benar mengenai hal itu. Ara, bukanlah cewek gampangan yang mudah terlena.
Ara menggeleng cepat. Dia mengangkat tangan dan mengayunkannya ke wajah Iago. Pikir Iago, Ara akan menamparnya. Iago memejamkan mata, mempersiapkan pipinya untuk menjadi tempat mendarat telapak tangan Ara. Dugaan Iago meleset. Telapak tangan Ara mendarat di keningnya dengan cukup keras yang otomatis membuat matanya kembali terbuka.
“Lo sakit?” tanya Ara tanpa dosa.
Iago tak bereaksi. Matanya fokus memperhatikan setiap gerakan kecil yang dibuat oleh Ara. Entah itu senyum sinis, maupun kening yang berkerut dalam.
“Kayaknya emang gitu,” lanjut Ara kemudian menarik tangannya kembali. Iago merasakan mata Ara bergerak menelusurinya, dari atas ke bawah. “Jam segini masih pakai seragam,” Ara nyengir, “kayaknya hidup lo sibuk banget, ya?!”
Rahang Iago mengeras. Setengahnya dia kesal, setengahnya lagi dia heran. Cewek mana pun selalu berlomba-lomba mengejarnya, berusaha mencuri perhatiannya. Namun Ara malah sebaliknya. Tatapan cewek itu padanya begitu menusuk penuh kebencian.
“Lo belum jawab pertanyaan gue,” ujar Iago berusaha sabar.
Ara menepuk dahinya sendiri, lalu terbahak. “Lo itu bego atau gimana sih? Gue nggak punya alasan buat nerima lo.”
“Lo punya.”
Bibir Ara bergeming, matanya menyiratkan sebuah tanda tanya besar.
“Karena lo harus bantu gue.”
“Atas dasar apa gue harus bantu lo?”
“Karena lo benci sama gue.”
Ara menggeleng cepat berulang kali. “Gue bener-bener nggak ngerti sama lo. Tempo hari lo seenaknya nuduh gue nguping, terus sekarang lo nembak gue. Bukan berarti karena lo punya segalanya, lo bisa berbuat semau lo!” Setelah menuntaskan serentetan kalimatnya, Ara mengambil langkah mundur, perlahan menjauhi Iago yang masih terpaku karena berusaha mencerna kalimat yang baru saja didengarnya.
“Tunggu!” Iago berlarian kecil mengejar Ara. Disambarnya tangan cewek itu agar berhenti. “Tunggu dulu, gue mau ngomong.”
Ara berusaha melepaskan tangannya dari cengkeraman Iago. “Gue nggak mau denger!”
“Lo harus denger!” bentak Iago keras.
Ara tersentak, akan tetapi dia tidak bereaksi apa-apa.
Rasa bersalah dengan cepat merambati Iago. Sungguh, dia tidak berniat membentak Ara. Hanya saja berhubung Ara tidak mau mendengar, Iago terpaksa membentak.
“Lepasin gue,” desis Ara, sama sekali tak menggubris Iago.
“Nggak. Kecuali lo mau dengerin gue.”
Ara mendecih. Iago dapat melihat dengan jelas kebencian yang kian membara dalam sorot mata Ara. “Ra, gue mohon, dengerin gue,” kata Iago, melunakkan nada bicaranya.
Ajaibnya kali ini berhasil. Entah karena capek atau karena alasan lain, Ara akhirnya mengangguk. “Tapi lepasin gue dulu,” pintanya.
Iago menggeleng. “Nanti lo kabur,” balasnya. Iago menggandeng Ara, menautkan jemari mereka dan membimbingnya menuju ke tempat di mana mobilnya diparkirkan. “Kita cari tempat buat ngobrol.”
Ara terdiam cukup lama dengan wajah kesal, sebelum akhirnya mengangguk sekali dengan terpaksa.
Dalam genggamannya, Iago merasakan telapak tangan Ara berkeringat. Tiba-tiba saja dia ingat, entah betapa banyak cowok yang ingin menggandeng tangan ini. Harusnya Iago merasa bangga karena bisa berada di posisi yang teman-temannya inginkan. Namun bukan itu tujuannya. Iago hanya butuh bantuan Ara.
*
Ara tidak mengerti kenapa dadanya bergemuruh seperti ini. Ada kemarahan yang menggebu-gebu dalam dirinya, juga ada rasa benci yang kian membengkak di hatinya. Bahkan dia sendiri tak mengerti kenapa saat ini dia duduk berhadap-hadapan di sebuah kafe dengan cowok sinting ini. Cowok yang selalu tampil serba putih, akan tetapi Ara berani bertaruh jika hati Iago sehitam arang.
“Lo mau jadi pacar gue?” Iago mengulangi pertanyaannya.
Ara menyeringai, berharap terlihat sejahat mungkin di hadapan Iago. Sekalipun Iago tahu kalau dia membencinya, Ara tetap ingin cowok itu melihat sebesar apa rasa benci yang dimilikinya.
“Gue nggak mau,” ketus Ara.
Iago melempar pandangan lurus-lurus padanya, memaksa Ara untuk balas menatapya. “Gue cuma minta waktu lo sehari aja.”
Mau tak mau Ara bertanya-tanya, sebenarnya ke mana arah pembicaraan ini?
“Bulan depan gue ulang tahun ke-17. Bokap gue udah ngejodohin gue sama seseorang,” lanjut Iago.
Dijodohkan?
Nyaris saja Ara tertawa mendengar itu. Namun bila mengingat Iago adalah satu-satunya anak laki-laki yang kelak akan mewarisi ‘tahta’ ayahnya, wajar jika sosok yang akan mendampinginya kelak sudah ditentukan sejak sekarang. Pastinya cewek itu setara dengan Iago, sama-sama anak dari keluarga kaya dan terpandang. Ara masih mengira-ngira seperti apa sosok cewek yang dijodohkan dengan Iago, saat mendengar cowok itu berdeham. Sebuah dehaman yang jelas-jelas disengaja untuk mengembalikan perhatiannya.
Ara menyedot buble milk tea-nya, kemudian meresponsnya malas-malasan, “Terus, apa urusannya sama gue?”
“Gue nggak mau dijodohin, makanya gue berencana ngenalin lo ke bokap sebagai pacar gue.”
Ara langsung tersedak. “Lo sinting?!” umpatnya lalu terbatuk-batuk.
“Gue nggak sinting, Ra. Gue minta tolong sama lo.”
“Tapi gue nggak bisa nolongin lo,” balas Ara cepat.
“Lo bisa, cuma lo-nya aja yang nggak mau.”
“Kenapa harus gue?!”
“Karena cuma lo yang bisa.”
Tangan Ara mengepal di pangkuannya. Iago begitu ulet, sampai-sampai membuat Ara luar biasa frustrasi.
Ara bertanya, Iago menjawab.
Ara mengelak, Iago mengejar.
“Go, kalau lo butuh pacar sewaan, lo cari orang lain aja. Jangan gue.” Ara meringis mengingat soal ramalan hidupnya. “Karena gue juga punya urusan yang harus gue selesaikan sebelum ulang tahun gue yang ke-17. Waktu gue bakal terbuang percuma kalau gue nolongin lo.”
“Gue bakal ganti waktu lo.”
Ara mengerang, makin frustrasi. “Lo pikir waktu bisa dibeli pakai uang?”
Setelahnya tak ada kata di antara mereka. Ara sibuk memainkan sedotan dengan jemarinya, sementara Iago mengamati setiap gerakan kecil yang dibuat Ara—sesekali cewek itu meringis, detik berikutnya cewek itu menggigit bibirnya.
“Gue mau ambil sesuatu dari mobil, lo tunggu di sini bentar,” izin Iago sembari bangkit dari duduknya. “Jangan ke mana-mana,” pintanya sekali lagi sebelum melangkah pergi.
Ara hanya bisa bengong dan menatap punggung Iago yang menjauh. Pikirannya berkabut, perasaannya kacau. Misi utamanya adalah menemukan ‘cowok kekurangan cinta’, cowok yang mencintainya dan bisa membuatnya jatuh cinta—cowok yang bisa menyelamatkan hidupnya dari permainan takdir yang semaunya sendiri. Lucunya, kenapa semua tidak berjalan lancar seperti yang dia harapkan?
Kehadiran Iago bak serangan hama. Sangat mengganggu dan membuatnya kesal setengah mati. Ara nyengir sendiri, mungkin Iago adalah wujud kesialan yang dikirim oleh semesta untuk mengganggunya, sehingga usahanya untuk menemukan ‘cowok kekurangan cinta’ itu akan terhambat.
“Ke siniin kaki lo,” perintah sebuah suara yang seenaknya membuyarkan pikiran Ara.
Ara menoleh, kaget mendapati bila Iago sudah duduk di sebelahnya. Cowok itu merobek kemasan plester dan sedikit membungkuk untuk menempelkan plester pada lutut Ara.
“Nanti sampai di rumah, cepet diobatin. Jangan sampai lukanya berbekas,” ujar Iago.
Untuk sejenak, Ara tertegun. Dia tak mengira bila Iago akan melakukan hal ini untuknya. Benci di hati Ara sedikit luntur, meski begitu dia tidak mau membiarkan rasa benci itu luntur sepenuhnya. Karena jika kebenciannya pada Iago lenyap, dia tidak akan lagi memiliki alasan untuk mendorong cowok itu pergi.
“Makasih. Tapi gue nggak bisa nolongin lo.”
Iago melempar seringai samar. “Karena lo benci sama gue?”
“Salah satunya.”
“Gue—”
“Gue tahu siapa lo dan selama ini kita nggak pernah berurusan,” potong Ara. “Gue mau kita kayak gitu terus.”
“Kenapa?” tuntut Iago. “Lo takut jatuh cinta beneran sama gue setelah kita deket?”
Ara melotot. “Sinting lo!”
“Gue cuma minta waktu lo sehari aja, Ra. Sehari,” tegas Iago.
“Sehari gue terlalu berharga buat dihabiskan sama lo.”
Kini giliran Iago yang tampak frustrasi, siapa sangka meminta tolong saja akan sesulit ini. Masalahnya, hanya Ara yang bisa membantu Iago, tidak ada yang lain. “Oke, hari ini cukup sampai di sini. Kayaknya otak lo agak geser setelah keserempet motor tadi. Besok-besok kita ngobrol lagi.”
“Nggak ada besok-besok!” sambar Ara cepat.
Iago berdiri dari duduknya. “Ada. Karena gue cuma mau lo. Dan lo harus mau.” Sesudahnya, tanpa menunggu respons Ara, Iago pergi begitu saja.
Sementara itu, Ara yang bingung hanya bisa diam sembari hatinya bertanya-tanya, Kenapa harus gue?
Capek berpikir, Ara mengambil ponselnya dan menelepon Vika. “Gue ke rumah lo sekarang.”
*


 sandrabianca
sandrabianca