Suara dentuman keras menghentakkan hati. Aku tahu itu pasti Cedric. Suaranya seperti amukan badai yang merobek kesunyian, membuat setiap getaran terasa sampai ke dalam tulang. Kekecewaannya bisa kurasakan, begitu tebal dan menyengat, seperti racun yang perlahan menggerogoti jiwa. Aku mengerti perasaannya, rasa bersalah yang menyelimuti hati, menyayat setiap inci dari kesadarannya. Ini bukan hanya tentang kegagalan misi, tapi lebih dari itu, ini adalah tentang pilihan yang dia buat—pilihan yang sekarang menghantuinya, menyisakan kehancuran.
Aku juga bertanggung jawab. Jika saja aku menentang lebih keras keputusannya, mungkin semuanya akan berbeda. Mungkin sekarang kami masih tertawa bersama, menjelajah dunia ini dengan hati yang ringan, ditemani canda tawa, teriakan penuh semangat dari Luna yang selalu penuh energi, dan celotehan Freya yang tak pernah habis siang dan malam. Kenangan itu melintas di benakku, membuatku tertawa sejenak meski rasanya pahit. Itu adalah masa-masa yang indah, masa-masa yang kini terasa begitu jauh, tak mungkin terulang lagi. Semua telah tamat, takdir telah berbicara.
Cedric pasti berpikir untuk meninggalkan masa lalunya, memutuskan semua ikatan yang pernah ada. Aku juga punya rencana. Pertarungan ini, balas dendam yang begitu dalam, akan menjadi kenangan terakhirku bersama party Alaya. Setelah itu, aku akan menghilang, seperti bayangan di malam hari.
Aku memutuskan untuk pergi menemuinya. Cedric masih di sana, memukul apapun yang ada di hadapannya dengan amarah yang tak terbendung. Setiap pukulan adalah pelampiasan dari rasa sakit yang dia rasakan di dalam hatinya. Dia tidak peduli jika itu akan melukai dirinya sendiri. Ketika aku mendekatinya, hanya berjarak dua meter di belakang, punggungnya yang lebar tampak begitu rapuh.
“Cedric,” panggilku, suaraku sayup di tengah keributan yang dia ciptakan. Beberapa prajurit melihat dari kejauhan, tak ada yang berani mendekat. Mereka tahu, amarah Cedric adalah sesuatu yang tidak bisa dianggap remeh. Sesekali, prajurit lain mencoba menyuruhku untuk mundur, tapi aku menolak. Ini tanggung jawabku, aku harus membawanya pergi, ke tempat yang lebih aman. Aku tidak akan membiarkannya jatuh lebih dalam ke jurang keputusasaan.
“Cedric, berhenti,” kataku lagi, suaraku sedikit lebih keras namun tetap lembut. Dia masih memukuli pohon di hadapannya, sebuah pohon besar yang kini berlubang di tengah, mulai tumbang terkikis oleh kekuatan pukulannya yang tanpa henti. Aku bisa melihat darah yang menetes dari tangannya, bercampur dengan keringat dan tanah yang kotor.
Aku mencoba sekali lagi, kali ini lebih tegas. “Cedric, dengarkan aku!”
Akhirnya, pukulannya berhenti. Tangannya yang besar dan kuat tergantung lemas di sisinya, darahnya menetes perlahan ke tanah. Aku segera merobek kain dari lenganku, bersiap untuk mendekatinya dan membalut lukanya. Namun, dia menghentikanku dengan suara yang penuh amarah dan ketegasan.
“Berhenti di situ, Rika!” serunya, suaranya dalam dan bergetar dengan emosi yang mendalam. Aku terhenti sejenak, mendengarkan, merasakan setiap kata yang keluar dari mulutnya.
“Kamu akan terluka jika mendekat,” lanjutnya dengan nada yang lebih rendah, namun tetap tegas.
Aku menggeleng pelan, menunjukkan bahwa aku tidak peduli. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak bisa meninggalkannya dalam keadaan seperti ini. Dengan langkah perlahan, aku kembali mendekatinya, menembus batas yang dia ciptakan dengan amarahnya.
Cedric tiba-tiba berseru, kali ini dengan kemarahan yang meledak-ledak, “RIKA, CUKUP SAMPAI DI SITU ATAU—“
“Atau apa? Membunuhku? Melukaiku?” potongku, suaraku penuh keberanian yang tiba-tiba muncul entah dari mana. “Aku tidak peduli, Cedric.” Kini aku sudah cukup dekat untuk bisa menyentuh tangannya yang terluka, meski dia berusaha menjauh. Aku mulai membalut lukanya dengan kain yang tadi kucopot, merasakan detak jantungnya yang cepat di balik kulitnya yang dingin.
“Aku sudah tidak peduli dengan dunia ini sejak lama,” bisikku pelan, namun cukup kuat untuk didengarnya. “Aku hanya menginginkan keluarga. Sekarang, keluarga ku tinggal dirimu.”
Cedric terdiam, tangannya tidak lagi berusaha menolak saat aku merawat lukanya. Kata-kataku sepertinya meresap ke dalam pikirannya, membuatnya terhenti sejenak dalam kesedihannya.
“Kamu naif, Rika,” katanya, suaranya rendah dan berat. “Aku pembunuh yang kau anggap keluarga.”
“Iya, kau adalah pembunuhnya, dan aku adalah rekan pembunuh. Kita berdua yang telah membunuh mereka,” jawabku tanpa ragu. Aku menatap matanya dalam-dalam, mencoba menghapus rasa bersalah yang menguasainya. Cedric menunduk, tidak menjawab. Aku tahu, dia merasa seluruh beban dunia ada di pundaknya.
“Ini juga salahku, Cedric, bukan hanya dirimu. Bukan berarti seorang kapten harus menanggung bebannya sendirian, kan?” lanjutku, suaraku lembut namun tegas. “Aku selalu mendukungmu, dan sebaliknya, saat aku butuh, kamu selalu memberikan aku harapan. Sekarang, aku juga akan memberikan harapan—harapan untuk terakhir kalinya di dunia ini.”
Cedric mengangkat kepalanya sedikit, menatapku dengan tatapan yang penuh kebingungan dan rasa penasaran. “Apa maksudmu?” tanyanya, suaranya sayup namun penuh dengan keingintahuan.
Aku menelan ludah, berusaha mengumpulkan keberanian untuk mengatakan apa yang ada di hatiku. “Aku tidak akan bertahan di dunia ini setelah pertempuran ini. Kamu, pergilah sejauh mungkin setelah semua ini berakhir. Aku hanya akan menjadi beban hidupmu, lebih baik aku berakhir di tempat ini kapanpun aku mau.”
Cedric tampak terkejut, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. “Pergi? Kau ingin mengusirku?” tanyanya, suaranya terdengar sedikit putus asa.
Aku menggeleng tegas, mencoba menjelaskan maksudku. “Bukan itu. Aku tidak ingin kita berpisah, bahkan satu meter pun tidak akan.” Aku menarik napas panjang, melanjutkan dengan suara yang lebih pelan namun penuh emosi. “Aku sebenarnya takut dengan kesepian, setiap malam hanya ditemani suara jangkrik dan lolongan serigala. Walau menenangkan buatku untuk menghukum diri, tapi aku tidak bisa berbohong, itu menakutkan.”
Aku berhenti sejenak, merasakan hatiku yang bergetar. “Namun, itu lebih baik daripada harus melihat sosok keluarga terakhirku, mati di hadapanku lagi. Aku tidak ingin kehilanganmu, keluargaku satu-satunya di dunia ini.” Aku kembali merawat tangannya yang luka, berharap tindakan kecil ini bisa menyembuhkan sebagian dari rasa sakit yang dia rasakan.
“Aku hanya akan jadi biang masalah bagi dunia ini,” gumam Cedric, suaranya hampir tak terdengar.
Cedric menatapku dalam-dalam, lalu tiba-tiba kedua tangannya yang besar menggenggam bahuku dengan erat. Aku bisa melihat bahwa tangan-tangannya telah diperban, luka-luka dari kemarahannya sendiri masih baru dan pasti terasa nyeri. Tetapi dia tetap memegangku dengan kuat, seolah-olah aku adalah satu-satunya hal yang bisa menahannya dari kehancuran total.
“Hey, jangan banyak gerak. Cedera itu—“ Aku mencoba memperingatkannya, suaraku penuh kekhawatiran, namun ia memotongku dengan nada yang dalam dan serius.
“Cedera ini hanya luka kecil,” ujarnya sambil menggeleng pelan. Matanya menatapku begitu intens, dekat sekali dengan wajahku sehingga aku bisa merasakan setiap napasnya. “Bukankah cederamu lebih parah?”
Aku tersentak mendengar kata-katanya. Rasanya seperti dia bisa melihat langsung ke dalam hatiku, melihat luka-luka yang tidak terlihat dari luar. “Tidak juga,” jawabku dengan cepat, mengalihkan pandangan. Aku tidak ingin dia melihat betapa hancurnya aku sebenarnya. Tapi dia terlalu dekat, terlalu tajam dalam menilai.
“Rika,” panggilnya lembut, namun penuh penyesalan. “Maaf atas perbuatanku. Sungguh-sungguh maaf. Aku tidak tahu hukuman apa yang pantas untukku. Aku menyesalinya, sangat menyesal. Aku mungkin tidak menangis, tapi aku bohong jika aku bilang tidak ingin menangis.”
Kata-katanya menyentuh hati kecilku yang paling dalam. Dia menundukkan kepalanya, menahan emosi yang bergolak di dalam dirinya, tapi aku bisa melihatnya berjuang untuk tetap kuat. “Terima kasih, Rika,” lanjutnya dengan suara bergetar. “Kamu yang terbaik di dunia ini. Kamu bukan biang masalah semua ini. Takdir telah membawa kita ke titik ini, pasti ada tujuannya.”
Aku merasakan sesuatu berubah dalam dirinya. Amarah yang tadinya meluap-luap kini mulai mereda. Auranya yang sebelumnya penuh dengan api kini perlahan-lahan mendingin, seperti ombak yang surut setelah badai.
“Jadi, apa yang ingin kamu lakukan sekarang, Rika?” tanyanya sambil menatap mataku dengan penuh harap.
Aku balas menatapnya, mencoba mengumpulkan keberanian untuk mengucapkan apa yang telah lama ada di pikiranku. Ini harus disampaikan dengan serius, dengan penuh keyakinan. “Balas dendam,” kataku pelan namun tegas. “Seluruh faksi Teror Malam, mereka harus bertanggung jawab.”
Cedric tersenyum kecil, lalu tertawa—tawanya terdengar pahit, hampir seperti tertawa orang yang putus asa. Kami berdua kini seperti orang-orang gila, tertawa dalam keputusasaan, membicarakan balas dendam seolah-olah itu adalah satu-satunya hal yang tersisa dalam hidup kami. Ironisnya, bagi kami, itu mungkin benar.
“Baiklah,” jawabnya sambil menghela napas panjang. “Mari kita habisi mereka semua. Jika aku mati, biarlah mati, begitu bukan?”
Aku menggeleng dengan cepat, menolak gagasan itu dengan segenap hatiku. “Tidak,” jawabku keras. “Aku tidak akan membiarkan kapten mati lebih dulu dariku.”
Cedric kembali tertawa, tapi kali ini ada sesuatu yang lebih dalam, lebih sedih di balik tawanya. “Ha-ha-ha. Jika begitu, aku juga akan mati lebih dulu untukmu, Rika.” Wajahnya mendadak murung, tatapannya sayu, seolah beban dunia jatuh di atas bahunya. Tidak ada yang bahagia hari ini, tidak ada yang merasa baik-baik saja. Tapi kami semua tahu, apapun yang terjadi, kami harus tetap terlihat baik-baik saja.
“Terima kasih telah menerima aku hari ini,” ujarnya akhirnya, suaranya hampir seperti bisikan. “Aku seharusnya tidak pantas berdiri di hadapan siapapun.”
Aku balas menatapnya dengan senyum yang aku paksa, meski berat rasanya untuk tersenyum setelah kehilangan seseorang yang sangat berharga. “Tidak, Cedric, ini tidak sepenuhnya salahmu. Terima kasih untuk dirimu yang selalu melindungi kami setiap saat.” Senyumku mungkin tidak tulus, tapi aku tahu dunia ini lebih baik jika ada senyum, meskipun itu senyum palsu.
***
Waktu terasa berjalan begitu lambat setelah percakapan yang menyedihkan dan menguras emosi itu. Dua puluh menit berlalu, dan seorang prajurit datang menghampiri kami. Aku tahu apa artinya ini. Ini pertanda bahwa tugas kami akan segera dimulai. Balas dendam! Kata itu berputar di kepalaku, menjadi satu-satunya hal yang bisa kupikirkan.
“Terima kasih telah hadir menerima panggilan darurat kali ini,” suara tegas seorang jenderal memecah kesunyian. Aku mengenalinya—itu Jenderal 1, dengan wajahnya yang tirus, kantung mata yang hitam menghiasi wajahnya, dan tubuhnya yang tegap berdiri penuh otot. Dia berdiri dengan auranya yang tenang, seolah-olah tidak ada sedikit pun kepanikan di hatinya. Seolah semuanya telah terkendali, padahal aku tahu, kami semua berdiri di atas tepi jurang.
“Ada beberapa hal yang harus disampaikan,” lanjutnya dengan nada yang tenang namun tegas. “Baiklah, mari kita mulai dengan yang paling menyedihkan terlebih dahulu.” Matanya berpindah-pindah antara aku dan Cedric, seolah menilai seberapa kuat kami dalam menghadapi kabar buruk yang akan datang.
“Tim Alaya berhasil menyelesaikan tugas dengan baik, tetapi dua prajurit gugur di medan tugas. Kami, segenap jenderal dan panglima, turut berduka cita.” Hatiku mencelos mendengar kata-kata itu. Aku menundukkan kepala, mencoba menahan rasa sakit yang masih begitu segar di hatiku. Kehilangan dua prajurit itu bukan hanya kehilangan rekan, tapi kehilangan bagian dari keluarga yang kami bangun bersama.
“Tidak ada waktu untuk bersedih, prajurit,” lanjut Jenderal 1 dengan suara yang lebih keras dan penuh wibawa. “Kalian adalah pasukan elite. Bunuh emosi kalian. Dunia ini sejak lama sudah tentang hidup dan mati, tentang kehilangan dan keberadaan.” Kata-katanya seperti cambuk yang menghantam kesadaranku, memaksa aku untuk tetap kuat meskipun hatiku hancur berkeping-keping.
Dia diam sejenak, membiarkan kata-katanya meresap sebelum melanjutkan. “Baiklah, kabar buruk berikutnya. Seluruh pasukan telah dipukul mundur jauh dari garis netral.”
Bisikan ketakutan dan keputusasaan mulai terdengar di sekitar ruangan. “Apa kita kalah?” suara bisikan Stark terdengar samar, penuh dengan ketidakpastian. Aku baru menyadari bahwa dalam pertemuan darurat ini, tim Constellation juga bergabung. Tatapan mereka yang sinis menusukku dan terutama Cedric. Rasanya seperti setiap mata di ruangan ini menilai, menghakimi, dan mempertanyakan setiap keputusan yang kami buat.
Namun, tidak ada yang lebih penting sekarang selain balas dendam. Kami mungkin kalah, kami mungkin jatuh, tapi selama masih ada napas di dalam tubuhku, aku akan memastikan mereka yang telah merampas segalanya dariku membayar dengan darah.
Aku berdiri di sana, mendengarkan dengan saksama saat Jenderal berbicara, suaranya keras dan penuh wibawa, memenuhi udara yang tegang di antara kami. Kata-katanya memotong keraguan yang menyelimuti hati kami, memberikan perintah yang tak bisa dibantah. “Saya mendengarnya, prajurit Stark. Itu tidak bisa dipungkiri, kita hampir kalah. Kita kekurangan kekuatan, tetapi perang jauh dari kata selesai. Masih ada kalian sebagai harapan kami, para Jenderal juga akan turun tangan menghabisi petinggi Teror Malam.”
Saat dia mengatakan itu, aku merasakan getaran di dadaku. Nyaris kalah? Aku tahu situasi ini gawat, tapi mendengar langsung dari mulut seorang Jenderal membuat segalanya terasa lebih nyata, lebih mengancam. Tapi aku tak punya pilihan. Aku harus tetap berdiri tegak, mengikuti perintah.
“Singkatnya, misi kalian adalah untuk menghabisi Jenderal musuh bersama kami. Setelah itu, mari bunuh pemimpin mereka. Apa kalian siap, prajurit?” serunya dengan semangat membara.
“Siap, Jenderal!” kami semua menjawab serentak. Suara kami bergema di udara, mencoba menutupi rasa takut dan kecemasan yang bersembunyi di balik dada kami masing-masing.
“Baiklah, kami berikan waktu lima menit untuk bersiap. Kemudian berkumpul, kita akan pergi ke medan perang. Bubar jalan!” perintahnya lagi, dan kami pun membalikkan badan, bergegas menuju tugas kami yang berikutnya.
Aku dan Cedric kembali berjalan menuju tenda medis, di mana tubuh Freya dan Luna terbaring, dingin dan tak bernyawa. Begitu aku memasuki tenda, hatiku terasa seperti dihancurkan sekali lagi. Mereka berdua—sahabatku, keluargaku, rekan seperjuanganku—kini hanya menjadi bayangan dari apa yang pernah mereka miliki. Wajah mereka yang dulu penuh kehidupan kini pucat, membisu. Aku berdiri di sana, memandang mereka tanpa mampu mengucapkan sepatah kata pun. Kata-kata seakan tersangkut di tenggorokanku, tak bisa keluar.
Sementara itu, Cedric tetap tenang, mungkin terlalu tenang. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan emosi, sama seperti saat pertama kali dia mengetahui mereka tiada. Dia tidak menangis, tidak juga tampak sedih. Namun aku tahu, jauh di dalam hatinya, ada badai yang sedang berkecamuk—kekesalan, kesedihan, dan keputusasaan yang bercampur menjadi satu, membuatnya bingung bagaimana harus bereaksi. Bahkan senyum pun tidak akan mampu mengubah apa pun saat ini.
“Rika, mari pergi,” Cedric menyikut lenganku, membawaku kembali ke kenyataan. Aku masih menatap wajah pucat Freya dan Luna, seolah berharap mereka akan membuka mata dan tertawa seperti dulu. Tapi aku tahu itu tidak mungkin.
Aku mengangguk pelan, meski rasanya berat untuk melangkah pergi. “Ayo,” jawabku akhirnya, mencoba menguatkan diri.
Namun sebelum aku benar-benar pergi, aku berhenti sejenak, berbalik untuk melihat mereka sekali lagi. Hatiku berat, dan aku tahu aku harus mengatakan sesuatu, meskipun mereka mungkin tidak bisa mendengarnya. “Freya, Luna... Aku akan menyusul kalian kok. Jangan khawatir, aku akan sampai ke tempat kalian berada. Karena di mana pun itu, tim Alaya akan tetap bersama di alam mana pun. Aku merindukan kalian.”
Air mataku mulai tumpah, dan aku cepat-cepat menyeka pipiku yang basah. Ini adalah perpisahan terakhir, dan rasa kehilangan ini begitu mendalam, begitu menyakitkan.
***
Waktu berlalu dengan lambat, begitu menyiksa. Semua Jenderal telah berkumpul sekarang, dengan Yeriko dan Panglima sebagai pusat informasi. Sisanya, mereka yang biasanya berada di belakang layar, kini turun langsung ke medan perang. Ini adalah pertaruhan terakhir, misi yang tak boleh gagal.
Sesampainya di medan perang, kami tiba di perbatasan netral. Di depan kami, puluhan mayat bergelimpangan, dan bau kematian memenuhi udara. Pasukan di depan kami tampak begitu lelah, seolah-olah mereka tidak tahu kapan atau apakah mereka akan bertahan lebih lama lagi. Inilah akhirnya, perang ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Kami harus mengakhiri semuanya sekarang, atau tidak pernah.
“Ini lebih mengerikan dari pada perang militer yang pernah kusaksikan,” gumam Jenderal 3, suaranya terdengar rendah namun penuh ketegangan.
Aku menelan ludah, melihat sekeliling. Dia benar. Apa yang dia katakan benar adanya. Perang militer biasanya memakan waktu berhari-hari untuk menyebabkan kerusakan sebesar ini—tetapi di sini, hanya dalam beberapa jam, segalanya telah hancur. Bangunan-bangunan runtuh, jalanan porak-poranda, dan mayat-mayat tergeletak di mana-mana. Debu dan asap memenuhi udara, menyembunyikan kehancuran yang telah terjadi. Beberapa bangunan penting bahkan sudah rata dengan tanah.
“Di mana musuh kita?” tanya Jenderal 2, suaranya penuh kehati-hatian.
Jenderal 3 menyapu pandangannya ke sekeliling, akhirnya matanya menangkap sesuatu. “Di sana, arah jam 3,” sahutnya cepat, menunjuk ke arah musuh yang kini terlihat di kejauhan.
“Kita berbagi tugas. Lawan Jenderal yang bisa kalian kalahkan. Hanya seperti itu, ini tugas yang mudah,” seru Jenderal 2, mencoba memberikan semangat.
Namun sebelum kami bisa bergerak, Jenderal 1 menahan langkah kami. “Tahan,” katanya dengan tegas, menghalangi jalan Jenderal 2. “Tim Alaya akan bergabung dengan tim Constellation.”
Kapten Lilyfa, yang berdiri di dekatku, segera mengangkat tangannya, meminta izin untuk berbicara. “Izin membantah, Jenderal.”
Jenderal 1 mengangguk, memberinya kesempatan. “Silakan.”
“Kami sepakat tidak ingin mereka berdua ada dalam formasi penyerangan kami. Mereka hanya sekumpulan orang egois yang mementingkan diri sendiri,” kata Lilyfa tegas, nadanya tajam dan penuh emosi.
Aku merasakan darahku mendidih, tapi aku tahu ini bukan saatnya untuk tersinggung atau marah. Ini saatnya untuk fokus pada misi.
Namun, Jenderal 1 tetap tenang, mengabaikan bantahan itu dengan tegas. “Bantahan ditolak. Kalian harus bersama atau semuanya akan bernasib sama seperti mereka yang gugur. Jika ada masalah personal, harap jangan diungkit dalam misi ini dan tetaplah bersikap profesional. Barisan dibubarkan.”
Semuanya memberi hormat dan bersiap.
Dalam sekejap, para Jenderal melesat ke arah jam 3, tempat musuh berada. Hanya dalam hitungan detik, suara dentuman pertama terdengar, menandakan bahwa pertempuran sudah dimulai. Aku menarik napas dalam-dalam, mengetahui bahwa ini adalah awal dari akhir—akhir yang mungkin akan membawa kami semua menuju nasib yang sama dengan mereka yang telah pergi. Tapi aku tidak akan mundur. Tidak sekarang. Perang ini harus diakhiri, dan aku akan memastikan bahwa mereka yang telah merenggut segalanya dari kami, akan membayar dengan harga yang setimpal.
“Ayo tim, kita pergi,” seru kapten Lilyfa dengan nada tegas yang langsung menarik perhatianku.
“Ke mana?” tanyaku, tanpa sadar terdengar begitu polos. Di tengah kekacauan dan ketegangan ini, sepertinya aku masih bisa bertanya dengan nada tak tahu apa-apa.
Kapten Lilyfa memandangku sekilas, matanya penuh ketegasan dan sedikit kekesalan. “Kami akan ke timur, dan kalian,” dia menekankan, “ku peringatkan, jangan sesekali mengganggu formasi tempur. Kalian berdua cukup melindungi kami. Hanya itu yang bisa dilakukan. Ayo pergi.”
Seketika itu, mereka semua bergerak cepat. Flash! Flash! Flash! Mereka melesat dengan cepat meninggalkan kami berdua.


 silvius
silvius 


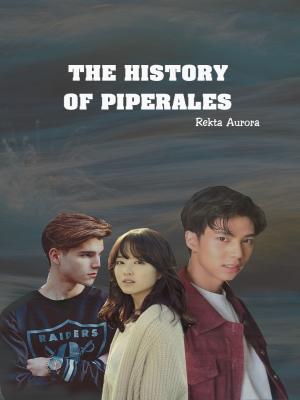






Halo readersvol. ada perubahan jadwal upload mulai bab berikutnya. Evolvera Life akan upload bab baru setiap 3 hari sekali. Terimakasih sudah menikmati cerita.
Comment on chapter Episode 22