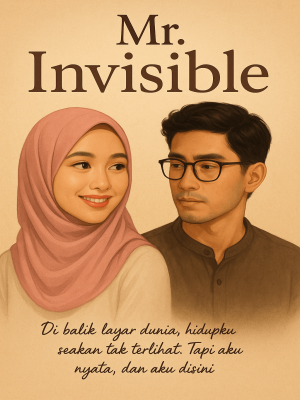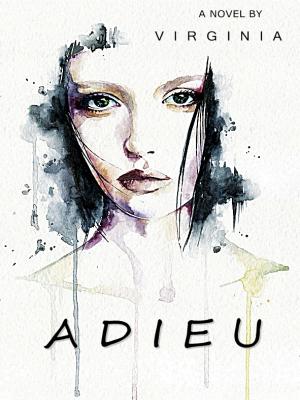Aku berguling ke kanan dan ke kiri di atas tempat tidurku, tidak bisa memejamkan mata meski jam dinding sudah menunjukkan pukul 2 lewat. Suara petir dan gemuruh angin yang membersamai jatuhnya hujan ke bumi membawa ingatan-ingatan tidak menyenangkan. Satu kenangan menyakitkan diikuti kenangan menyakitkan lainnya. Peristiwa-peristiwa yang sampai saat ini masih membuatku bertanya, “Kok begitu sih? Kenapa harus aku?”
Semua itu membuatku kesal. Namun, aku tidak bisa mengenyahkan perasaan kesal itu. Itu di masa lalu, itu sudah terjadi dan tidak bisa diubah lagi. Meski aku mengucapkan kalimat itu berulang kali, bagaikan mantra, tapi aku tetap gelisah. Saat aku berhasil mengosongkan pikiranku, supaya bisa tidur, perasaan tidak nyaman itu tetap bercokol di balik dadaku. Rasanya dadaku makin sempit. Bukan hanya benakku yang tidak nyaman, fisikku juga. Malam itu aku tertidur dengan kepala yang terasa tegang. Hanya suara hujan yang kudengar, menghipnotisku hingga tertidur.
Subuh pun datang, tapi perasaan gelisah itu tidak jua hilang. Kata orang, kalau kamu merasa gelisah tanpa sebab, itu karena akibat dari dosa-dosa. Dosa-dosa itu menjelma menjadi titik-titik hitam di hati. Makin banyak, titik-titik hitam itu akhirnya menyelubungi hati sehingga hati menjadi sakit. Kegelisahan itu adalah gejala bahwa ada yang tidak beres. Aku beristighfar seratus kali. Meski begitu, bukannya ketenangan yang kurasakan, tapi justru imaji-imaji kejadian tidak menyenangkan kembali muncul di benakku.
Bagaimana kabar mereka yang dulu pernah menyakitiku? Tidak tahukah mereka kesemboronoan mereka itu membuatku terkadang mempertanyakan diriku sendiri: apakah aku tidak berarti? Apakah mereka pikir aku tidak punya perasaan? Benakku digerogoti rasa sakit dan kemarahan.
Hari-hari berlalu. Seminggu. Dua minggu.
Kenapa aku membiarkan perasaan gelisah ini berlarut-larut? Aku perlu bicara dengan seseorang. Aku perlu menceritakan perasaanku dan meminta nasihat bijaksana. Aku menghubungi satu nama di kontakku.
Kak Maira. Dia sudah seperti kakak perempuan bagiku. Usianya beberapa tahun lebih tua dan dia memiliki pemahaman agama yang cukup luas. Kalau bertanya kepadanya, aku tak perlu ragu dia pasti akan memberikan nasihat yang sesuai ajaran agama.
Aku mengiriminya pesan di WhatsApp, mengajak untuk bertemu. Akhirnya, di hari yang ditentukan, aku pun berangkat naik bus TransJakarta. Aku memakai jaket cokelat di luar gamis kremku karena sekarang sudah mulai sering hujan, supaya aku tidak kedinginan.
Kami bertemu di sebuah kafe yang merangkap perpustakaan. Kak Maira yang mengajak bertemu di sini. Kebetulan aku belum pernah ke tempat ini, jadi ini kesempatan menarik bagiku. Saat aku tiba, tempat itu tidak sepi tetapi juga tidak terlalu ramai. Aku masuk ke area kafe dan mencari-cari sosok Kak Maira.
Itu dia. Kak Maira mengenakan kerudung krem dan gamis biru muda kotak-kotak. Dia melambaikan tangan ke arahku ketika aku memasuki area kafe. Aku pun menghampirinya.
“Assalamu ‘alaikum, Kak!” Sapaku. Aku langsung bersalaman dengannya dan melakukan cipika-cipiki.
“Aium halam, Hehisa, hapa habar?” Tanyanya sambil tersenyum manis. Bagi orang yang pertama kali mengobrol dengan Kak Maira, pasti akan kesulitan memahami ucapannya. Namun, aku sudah langsung mengerti. Wa’alaikumussalam, Elysa, apa kabar? Tanyanya.
Alih-alih menjawab, aku mengembuskan nafas berat. Kak Maira langsung tahu aku pasti sedang ada masalah.
“Hesan ulu, hinum, mahan.” Pesan dulu, minum, makan.
Aku membaca kertas menu dan memutuskan memesan milkshake cokelat dan spagheti bolognaise. Kak Maira juga memesan menu yang sama.
“Hanapa?” Ada apa?
“Akhir-akhir ini, aku sering merasa kewalahan dengan perasaanku sendiri, Kak. Rasanya gelisah. Aku merasa… hatiku mudah sekali iri dengan orang lain, dan berpikiran buruk tentang mereka. Aku juga merasa marah kepada diriku sendiri karena hal itu. Aku merasa buruk. Aku merasa…”
Kak Maira mengusap-usap punggung atasku sambil tersenyum.
“Terutama ketika aku mengingat-ingat kejadian di masa lalu. Aku merasa marah, kesal, ingin mengamuk.”
“Hadian napa?” Kejadian apa?
“Yah, ada beberapa kejadian yang terus-menerus muncul di pikiranku. Saat malam-malam aku tidak bisa tidur, pikiranku pasti teringat kejadian itu. Misalnya, saat aku SD, orang tua dan keluarga besar kerap membanding-bandingkan aku dengan kembaranku.”
Itu terjadi belasan tahun lalu. Aku selalu sekelas dengan saudari kembarku, Erica. Kelas satu, dua, tiga… tidak ada masalah. Saat kelas empat, Erica dipilih untuk mewakili sekolah kami mengikuti lomba pidato sekecamatan, lalu lolos ke tingkat kotamadya. Orang tuaku sangat membanggakan Erica karena lomba itu. Mereka jadi mendorongku untuk ikut lomba juga. Kebetulan mereka tahu aku suka menggambar, jadi mereka selalu menanyakan apakah aku tidak ikut lomba menggambar saja?
“Memangnya kamu tidak mau seperti Erica?” Tanya Mama. Memangnya kenapa kalau aku tidak ikut lomba? Memangnya kenapa kalau aku tidak sama dengan Erica? Hanya karena kami kembar, bukan berarti segala-galanya harus sama, kan!? Namun, aku tidak bisa menyuarakan pikiranku kepada Mama waktu itu.
Terlebih ketika Erica mengatakan dia ingin menjadi dokter, dia langsung mendapatkan perhatian lebih dari kedua orang tuaku. Aku menjadi minder. Kurasa, sejak saat itulah aku memutuskan lebih baik menyimpan sendiri pikiran, perasaan, dan harapan-harapanku. Karena tidak ada yang menganggapku penting, sepenting Erica.
“Jangan salah, aku menyayangi kedua orang tuaku,” ujarku. “Tapi kadang aku berharap mereka dulu bersikap adil. Bahkan, aku masih berharap mereka mengatakan mereka bangga kepadaku sekarang. Sebagaimana mereka dulu bangga kepada Erica karena menang lomba pidato, atau karena masuk kedokteran, dan lulus kedokteran.”
“Muhanhah o ang tuamu hanang hewisudamu?” Bukankah orang tuamu datang ke wisudamu?
“Iya, tapi… Seakan-akan itu hanya kewajiban saja bagi mereka.”
“Hari mana hamu ahu halau meka tidak bangga padamu?” Dari mana kamu tahu kalau mereka tidak bangga kepadamu?
Aku terdiam. Ya, betul. Mungkin mereka sebenarnya bangga kepadaku. Setelah wisuda itu, kami langsung ke studio foto untuk mengambil foto keluarga. Lalu, Papa mengajak kami makan-makan di restoran pizza. Makan besar. Papa mengucapkan syukur karena telah mengantarkan satu anaknya menyelesaikan pendidikan tinggi. Itu salah satu hari yang membahagiakan untuk dikenang. Lalu, mengapa aku tidak bersyukur atas hal itu? Dan atas kebaikan-kebaikan lain yang mereka lakukan untukku?
“Hanganlah hamu bebuat joim hanya harena hatu dua hal yang hidakkamu suka. Hidak ada oang tua yang semuhna.” Janganlah kamu berbuat zalim hanya karena satu dua hal yang tidak kamu suka. Tidak ada orang tua yang sempurna.
Pikiranku teringat kejadian lain yang sering muncul di dalam ingatanku.
“Ada kejadian lain, Kak. Ketika aku SMA. Sudah kubilang, kan, aku selalu sekelas dengan Erica? Kami selalu sekelas, entah kenapa. Bahkan sampai SMA. Waktu SMA, Erica punya teman-teman karib satu gengnya. Mereka bertiga, berempat dengan Erica. Mereka senang menghabiskan waktu bersama. Erica selalu mengajakku, meski aku tahu teman-temannya tidak terlalu suka kalau aku ikut dengan mereka. Sebisa mungkin aku mencari kesibukan sendiri.
“Suatu hari, aku tak sengaja mendengar dua teman Erica sedang membicarakanku. Mereka berbicara yang jelek tentangku, Kak! Mereka bilang, aku hanya duplikat Erica yang tidak bisa apa-apa. Tentu saja hal itu membuatku teringat kembali dengan kejadian waktu SD, yang kuceritakan sebelumnya.”
Waktu itu, aku menampakkan diri di depan kedua orang itu, dan berkata, ‘Kalian ngomong apa tadi?’. Mereka terkejut dan tampak bersalah, tapi mereka tidak meminta maaf. Sejak saat itu aku selalu memasang tampang jutek di depan mereka. Aku tahu mereka tahu kesalahan mereka, tapi mereka tidak mengakuinya.
Tanpa sadar, aku merobek-robek tisu sembari bercerita kepada Kak Maira. Kekesalan yang kurasakan bertahun-tahun lalu itu muncul kembali di benakku. Aneh, ya? Padahal kejadiannya sudah lama, tapi perasaan yang kurasa masih sama. Bahkan seiring waktu, perasaan itu teramplifikasi, lebih besar dari yang semula. Lebih menyakitkan. Mungkin karena aku berharap bisa mengubah sesuatu dari masa lalu sehingga tidak merasakan sakit itu, yang mana hal itu tidak mungkin.
Saat pesanan kami datang, kami menyantapnya sambil mengobrol. Dengan Kak Maira, aku bisa menumpahkan semuanya.
“Aha patnya hang ngamu hasakan haharang?” Apa tepatnya yang kamu rasakan sekarang?
“Aku mengambil jalanku sendiri. Selepas tamat SMA, aku sengaja memilih kampus di luar kota, supaya aku terlepas dari bayang-bayang saudariku. Bisa dibilang, sekarang aku menjalani hidup yang aku mau. Tapi rasanya aku tidak bisa tenang, Kak. Setiap aku tenang sedikit, ingatan-ingatan buruk itu langsung muncul. Aku tidak bisa lepas dari masa lalu yang tidak menyenangkan itu.”
Kak Maira tersenyum bijaksana. “Hita memang ida bisa lepas sari masa lalu. Hang bisa hita lahukan halah menerima, memaafkan, han nambil hikmahna.” Kita memang tidak bisa lepas dari masa lalu. Yang bisa kita lakukan adalah menerima dan mengambil hikmahnya.
Aku tidak menjawab. Yang Kak Maira katakan itu klise. Menerima, memaafkan, mengambil hikmah. Namun, rasanya aku tidak rela melakukan itu semua. Enak sekali orang-orang itu, kalau aku menerima begitu saja dan memaafkan mereka. Apakah dengan memaafkan mereka hidupku bakal berubah?
Kurasa Kak Maira merasakan perlawanan dari dalam diriku.
“Hamu inhat ceritha aditsul ifhki?”
Aku sempat loading lama untuk memahami maksud Kak Maira. Oh! Dia bertanya, kamu ingat cerita haditsul ifki?
Haditsul ifki atau berita dusta adalah kejadian ketika Ummul Mukminin Aisyah RA, istri Baginda Nabi SAW, difitnah melakukan hal tidak senonoh dengan seorang sahabat. Padahal, waktu itu Aisyah RA sedang mencari kalungnya yang hilang saat beliau sedang buang hajat. Eh, ternyata ditinggal sama rombongan Nabi SAW. Untungnya, ada seorang sahabat yang datang belakangan dan melihat beliau. Sahabat tersebut pun mempersilakan Aisyah naik untanya dan mengantarkan beliau sampai ke Madinah. Hal tersebut menimbulkan desas-desus yang tidak menyenangkan, tapi Aisyah RA sendiri tidak mengetahui hal itu karena setibanya di rumah dia jatuh sakit. Namun, berita miring tersebut sangat memengaruhi hubungan rumah tangganya dengan Nabi SAW.
“Ingat, Kak.” Jawabku. Entah apa hubungannya hal itu dengan situasiku.
Kak Maira lalu berbicara panjang lebar. Inilah yang kutangkap dari ucapannya: Kamu kan tahu, ummul mukminin Aisyah RA difitnah. Hal itu sangat membuat sedih Ummul Mukminin, Rasulullah SAW, dan tentu saja kedua orang tua Aisyah RA, Abu Bakar dan Ummu Ruman. Setelah diusut, ternyata salah satu yang menyebarkan fitnah tersebut adalah kerabat Abu Bakar sendiri. Selama ini, Abu Bakar-lah yang menanggung biaya hidup orang tersebut, tapi dia malah memfitnah putri Abu Bakar. Abu Bakar sangat sedih dan marah. Bahkan dia bersumpah tidak akan lagi bersedekah kepada orang itu. Tapi, tahu nggak, ternyata Allah menurunkan satu ayat tentang hal itu?
Kak Maira membacakan sebuah ayat. Dia memang hafal sebagian dari Al Quran. Meski ketika berbicara ucapannya tidak begitu jelas, tapi ketika membaca ayat Al Quran lain lagi ceritanya. Suaranya merdu dan setiap hurufnya dibaca dengan fasih.
Dia lalu membacakan arti ayatnya: Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkah dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
“Abu Bakar sahabat yang haat. Hetika menhengar ayat itu, beliau kembali behbuat wahyik hepada hehabatnya. Beliau hemaaf han ya, sebab beliau ingin Allah mehampuni dosa-dosan ya. Hitu janji Allah, Hehisa. Khalo hita memaaf han kesalahan ohang lain, Allah huga ahan hampuni hita.”
Abu Bakar sahabat yang taat. Ketika mendengar ayat itu, beliau kembali berbuat baik kepada kerabatnya. Beliau memaafkannya, sebab beliau ingin Allah mengampuni dosa-dosanya. Itu janji Allah, Elysa. Kalau kita memaafkan kesalahan orang lain, Allah juga akan mengampuni kita.
Aku merasa tertohok. Tentu saja aku ingin dosa-dosaku diampuni Allah! Aku menyadari, mungkin aku telah bersikap tinggi hati, enggan memaafkan orang lain. Merasa menjadi si paling tersakiti. Memang, kejadian-kejadian itu menyakitiku, tapi bukan berarti hal itu menjadi pusat hidupku. Pusat hidupku adalah Allah, untuk beribadah kepadanya. Orang-orang yang pernah menyakitiku adalah ujian sekaligus pelajaran, agar aku mengambil hikmahnya.
Kurasa Kak Maira sudah menyampaikan maksudnya dengan baik. Aku mengerti. Aku punya alasan yang lebih besar untuk memaafkan, bukannya tetap berpegang erat pada rasa marahku. Namun, ternyata Kak Maira belum selesai.
Di zaman Nabi juga ada seorang sahabat yang kata Nabi beliau itu adalah ahli surga. Sahabat-sahabat yang lain bertanya-tanya, apa sih amalan orang tersebut sehingga disebut sebagai ahli surga? Salah seorang sahabat pun menginap di rumah orang itu untuk mencari tahu amalan apa yang dikerjakannya…
Ya, kalau yang itu sudah pernah dengar ceritanya. Sahabat itu menginap selama 3 hari di rumah ahli surga itu, tapi tidak menemukan amalan istimewa yang dilakukan. Hingga pada hari terakhir, sahabat ahli surga itu pun memberi tahu bahwa setiap malam sebelum tidur, dia memaafkan orang-orang yang pernah menyakitinya di hari itu. Masyaallah, begitu besarnya ‘amalan’ memaafkan orang lain ini.
Kok bisa-bisanya aku lupa tentang cerita ini? Bukan, bukan lupa. Tepatnya aku tidak benar-benar menghayatinya dan mengambil pelajaran. Aku hanya menganggap itu hanyalah satu dari kisah sahabat-sahabat yang saleh. Padahal, bukankah selayaknya kita meniru perbuatan para sahabat yang dijamin surga itu?
Astaghfirullah.
“Hetlah ini, aku mau mehajak hamu ke huatu hempat.” Setelah ini, aku mau mengajak kamu ke suatu tempat.
Keningku berkerut. Aku tidak membantah.
Setelah kami menyelesaikan makan siang dan aku membayar semua pesanan kami, kami pun meninggalkan kafe. Aku menatap sedih area perpustakaan yang belum sempat kujamah. Mungkin lain kali.
Kami berjalan dalam diam. Tanpa bertanya apa-apa, aku mengikuti Kak Maira. Kami tidak menuju halte bus. Kami melewati sebuah RPTRA, terus masuk ke jalan kecil yang masih cukup lebar dilalui satu mobil. Kak Maira hanya berkata bahwa rumahnya di dekat sini (karena itulah dia mengusulkan kami bertemu di kafe tadi) dan ada satu tempat yang menurutnya bisa membantuku.
Di sebelah kiri jalan, di balik pagar beton, terhampar pekuburan kaum muslimin. Aku mengucap salam dengan lirih. Tak kusangka, ternyata Kak Maira berbelok di pintu masuk pemakaman itu. Mungkinkah ada seseorang yang Kak Maira kenal yang dikuburkan di sini? Apakah orang tuanya? Aku jadi merasa tidak enak karena mengeluhkan tentang perlakuan orang tuaku di masa lalu, sementara bisa jadi Kak Maira sudah kehilangan orang tuanya.
Kak Maira terus berjalan dan aku terus mengikutinya. Dia berhenti di dekat dinding yang membatasi area pekuburan dengan area perumahan di sampingnya. Kak Maira lalu membalikkan badan menghadap hamparan nisan-nisan itu. Aku berdiri di sampingnya.
“Afha yang hamu lihat?” Apa yang kamu lihat?
“Pemakaman?”
“Tul. Satu saat, hamu nyang ahan di uburhan di hini. Kamu ahan neninghalkan dunia ni dan memasuki alam barzakh. Menunggu hari Hiamat hiba. Lalu, hamu ahan hetemu hangan Rabb-mu. Aku pun juha.” Betul. Suatu saat, kamu yang akan dikuburkan di sini. Kamu akan meninggalkan dunia ini dan memasuki alam barzakh. Menunggu hari Kiamat tiba. Lalu, kamu akan bertemu dengan Rabb-mu. Aku pun juga.
Aku merenungi ucapannya.
“Radhitu billahi rabba… Hitulah yang hita bahca sebagai dzikir pahi dan petang. Hita bahca tiap hari. Namun, afha benar hita hudah rida bahwa Allah sebagai Rabb hita? Sudahkah hita rida Allah yang mengatukh takdikh hita?”
Radhitu billahi rabba… (Aku rida Allah sebagai tuhanku…) Itulah yang kita baca sebagai dzikir pagi dan petang. Kita baca setiap hari. Namun, apa benar kita sudah rida bahwa Allah sebagai Rabb kita? Sudahkah kita rida Allah yang mengatur takdir kita?
Pandanganku mengabur karena air mata yang tiba-tiba terbit.
Kurang lebih yang Kak Maira katakan berikutnya begini: Apa yang sudah terjadi, itu terjadi atas ketetapan Allah. Tidak lain dan tidak bukan adalah ujian untuk kita. Terutama ujian keimanan, apakah kita rida dengan takdirNya dan percaya Dia pasti punya maksud di baliknya.
Suatu saat, kita akan berada di bawah tanah dengan kain kafan kita. Apakah sepadan tidak memaafkan kesalahan orang lain, sementara Allah menjanjikan ampunan dan surga bagi orang yang memaafkan? Kamu akan berharap dibangkitkan dalam keadaan qalbun salim, hati yang selamat. Selamat dari mempersekutukan Allah, yang utama. Selain itu, juga selamat dari penyakit-penyakit hati. Selamat dari kebencian. Selamat karena memaafkan kesalahan orang lain.
Aku memandangi nisan-nisan di dekatku. Ada yang sudah meninggal beberapa tahun lalu, ada yang beberapa bulan lalu. Entah sampai kapan mereka akan berada di sana, sebelum dibangkitkan kembali.
Entah bagaimana, aku seakan lupa bahwa hidupku di dunia hanya sebentar saja. Benar, tidaklah sepadan berpegang pada rasa marah, padahal ada hal yang lebih layak kuperjuangkan: ampunan dan rahmat Allah.


 yuniyustikasari
yuniyustikasari