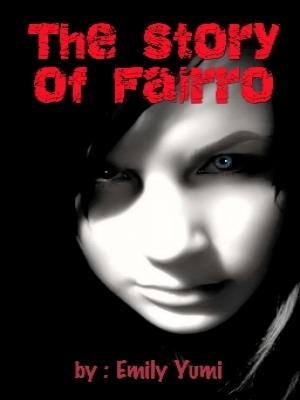Bagaikan zombi di tengah-tengah makhluk hidup, itulah aku. Kakiku melangkah dari satu kelas ke kelas berikutnya, tapi seakan-akan nyawaku tidak berada di dalam tubuhku. Ah, apalah artinya hidup ini! Aku sudah tidak punya tujuan lagi.
Dibandingkan dengan para mahasiswa kedokteran yang lain, yang enerjik, antusias mengikuti kuliah, kerja kelompok, tutorial… meski terkadang terdengar juga keluhan dari mereka, entah karena tugas yang banyak, dosen killer dan aturan-aturannya yang strict, ujian yang susah, atau materi yang tidak dipahami… Namun, dibandingkan dengan mereka, yang penuh warna kehidupan, aku merasa memudar. Pudar.
Siapa sangka kekacauan hidup bisa membuatku merasa melankolis seperti ini. Seperti bukan diriku.
Ah, tapi aku memang tidak menjadi diriku sendiri beberapa waktu terakhir ini. Erica yang ceria, social butterfly, sering tertawa keras karena lelucon remeh, dan yang percaya diri itu rasanya sudah kutinggalkan jauh di belakang. Erica yang itu berada di masa lalu. Erica yang sekarang hanyalah sebuah cangkang kopong yang ditinggalkan pemiliknya. Ah, aku melantur lagi.
Rasanya aku tidak sanggup melangkah ke kelas berikutnya. Kepalaku bisa meledak kalau aku mendengar satu lagi kata anatomi, histologi, patologi. Aaah! Bikin sesak kepalaku saja!
“Erica, mau ke mana?” Tanya Bobby.
“Eh, sebentar…” ujarku tidak jelas. Mahasiswa seangkatanku melangkah ke satu arah, sementara aku melangkah ke arah sebaliknya.
Makin jauh berjalan, aku makin mempercepat langkahku. Seakan-akan kalau aku berjalan lambat, seseorang akan menangkapku dan menyeretku ke belakang. Lalu aku harus duduk di auditorium, menyimak satu lagi kuliah tentang fisiologi jantung.
Tak terasa aku berlari dan tiba di luar gedung kampus. Orang-orang memandangiku tetapi mereka terlalu sibuk untuk memedulikanku. Aku bebas! Aku terus berlari ke luar kampus. Aku tertawa. Aku tertawa! Hahaha. Aku melarikan diri.
Namun, kesenangan itu hanya sesaat. Sekarang aku kebingungan. Di mana aku? Harus ke mana aku? Tidak mungkin aku kembali ke gedung berwarna putih itu lagi. Lagipula, kelas sudah berlangsung. Aku tidak akan diperbolehkan masuk kalau terlambat.
Aku mengelap keringat di keningku dengan punggung tangan.
Sepertinya aku akan gagal blok ini. Aku sepertinya harus mengulang kuliah tahun depan. Hah. Bodoh.
***
Ketika usiaku tujuh tahun, Papa bertanya kepada kami, yaitu aku dan saudari kembarku, apa cita-cita kami.
Elysa menjawab asal, dia ingin jadi polwan.
Aku tak kalah ngasal. “Aku ingin jadi astronot!”
“Tidak ada yang ingin jadi dokter seperti Papa?” Tanya Papa. Beliau menunjukkan wajah cemberut. Tentu saja waktu itu Papa hanya berpura-pura, tapi Erica kecil mengira Papa sungguhan sedih. Jadi aku ingin membuat Papa tersenyum lagi.
“Aku! Aku!” Seruku. “Aku ingin jadi dokter kayak Papa!”
“Nah, begitu dong!” Papa tersenyum dan memelukku. Aku merasa bangga. Aku merasa hebat telah membuat Papa senang.
Aku memeletkan lidah ke arah Elysa. Aku menang, batinku kala itu. Elysa mengangkat bahu dan tidak mempemasalahkannya. Dia sibuk sendiri dengan bonekanya.
Sejak saat itu, kalau ada orang yang bertanya aku ingin jadi apa, aku selalu menjawab dengan mantap bahwa aku ingin jadi dokter. Tak sekali pun aku mempertanyakan ulang pilihanku itu. Begitu pula orang-orang di sekitarku. Tidak ada yang memaksaku harus jadi dokter. Bahkan, kedua orang tuaku juga tidak. Hanya saja, mereka sangat mendukung cita-citaku menjadi dokter. Aku merasa aku memang ditakdirkan untuk menjadi dokter.
Tidak ada keraguan bahwa aku ingin jadi dokter dan akan menjadi dokter. Papa mendorongku untuk belajar sungguh-sungguh, karena menjadi dokter itu tidak mudah. Menjadi dokter itu harus pintar, kata Papa. Kalau tidak pintar, akan membahayakan orang lain yang menjadi pasien kita.
Aku rajin belajar. Membaca buku-buku pengetahuan. Aku bahkan ikut program dokter cilik di sekolahku. Masa-masa yang menyenangkan.
Tak sepertiku, Elysa tidak jelas mau jadi apa. Cita-citanya selalu berubah-ubah. Dia juga sering mencoba hal baru, tapi tak pernah konsisten menekuni satu bidang. Hanya saat SMA Elysa mulai menunjukkan kesukaan pada fotografi dan desain grafis. Ketika menentukan jurusan, Elysa memilih jurusan DKV di Kota Seni, Yogya. Aku heran orang tuaku menyetujui keinginannya untuk merantau.
Menginginkan menjadi sesuatu dan benar-benar menjalaninya adalah dua hal yang berbeda. Aku memang berhasil masuk Prodi Pendidikan Dokter di universitas negeri terbaik lewat jalur prestasi. Aku sudah masuk ke gerbang menuju cita-citaku.
Namun, siapa sangka…
Ternyata menjalaninya tidak semudah mengimpikannya. Kuliah kedokteran jauh berbeda dari menjadi dokter cilik sewaktu aku SD dulu. Bahkan sepuluh persennya pun tidak bisa menyamai. Aku sampai mempertanyakan keputusanku sendiri. Apa, sih, yang membuatku mantap ingin jadi dokter?
Apa yang salah dengan diriku? Di satu waktu aku sangat menginginkan ini, tapi sekarang tiba-tiba yang kuinginkan adalah membuangnya jauh-jauh dan tak ingin berurusan lagi dengannya.
Ini membuat batinku benar-benar tersiksa.
Andai aku bisa hidup di dunia khayalan atau dunia mimpi saja. Di mana tidak ada tuntutan untuk menjadi sukses. Aku ingin bertemu teman dan mengobrol santai di kafe, saling bercanda dan membicarakan apa saja, seperti masa lalu. Faktanya aku malah merasa terjebak di dunia nyata.
***
Layar ponselku menyala terang tiba-tiba. Aku menyipitkan mata dan menjauhkannya dariku untuk melihat siapa yang menelepon. Nama Elysa dalam huruf-huruf besar terpampang di layar. Apakah aku harus mengangkatnya? Sudah lama aku tidak video call dengan saudari kembarku, tapi kurasa ini bukan waktu yang tepat. Aku sedang … yah, tidak sedang melakukan apa-apa, sebenarnya.
Setelah meragu beberapa saat, aku menekan tombol ‘angkat’. Wajah Elysa memenuhi layar ponselku.
“Assalamu ‘alaikum! Kok gelap banget, Er? Kamu di mana?”
Oh iya, benar juga. Aku dari tadi hanya melamun dalam gelap, tidak melakukan apa-apa. Tanpa berdiri dari kursi belajarku, aku menekan tombol lampu belajar dan kamarku pun jadi lebih terang.
“Kamu tadi tidur, ya?”
“Enggak.”
“Oh… Kirain. Gimana kabarmu, Er? Sibuk banget, ya, kuliahnya?”
Aku hanya menatap layar tanpa bisa menjawab. Kotak kecil di sudut kanan bawah layar menampakkan wajahku yang tanpa ekspresi. Di ponsel Elysa, tentunya wajah tanpa ekspresiku memenuhi layarnya.
Sejujurnya, aku sudah dua mingguan ini tidak masuk kelas. Aku memang pergi, tapi tidak ke kampus. Biasanya aku ke mal atau kafe-kafe pinggir jalan, menyendiri di tengah keramaian. Terkadang aku khawatir ada seseorang yang mengenaliku dan menanyaiku macam-macam. Misalnya, kenapa aku berada di sini dan tidak di kampus? Namun, aku menyadari, tentu teman-teman seperkuliahanku sedang di kampus dan tidak mungkin aku berpapasan dengan mereka di tempat-tempat itu.
Dua minggu memang bukan waktu yang terlalu lama bagi sebagian besar orang. Namun, berbeda dengan di dunia perkuliahan pendidikan dokter. Kuliah kedokteran tak seperti kuliah pada umumnya. Dalam satu semester, ada beberapa blok yang harus dijalani. Kamu dapat ketinggalan banyak hal dalam dua minggu. Bahkan, hampir pasti gagal pada blok itu.
“Er?”
Oh, benar. Aku sedang video call sama Elysa.
“Ya?”
“Gimana kabarmu?”
Apa yang akan kukatakan kepadanya? Kurasa mengangkat teleponnya adalah sebuah kesalahan. Namun, kalau aku tidak mengangkatnya atau membalas pesannya, dia akan terus mengejar jawaban. Kalau dia tidak mendapatkannya dariku, maka dia pasti akan bertanya kepada orang tua kami. Jangan sampai orang tuaku tahu, deh!
Kurasa aku harus jujur saja kepada Elysa.
“I wanna quit, Lys.”
“Hah?”
“I can’t take it anymore! Aku udah gak sanggup. Aku merasa udah kehilangan tujuan hidup.”
“Astagfirullah, Er. Ngomong apa, sih, kamu? Pelan-pelan. Ada apa sebenarnya?”
Kata-kata meluncur dari bibirku. Bagaimana aku merasa terkungkung dan terpenjara, dan beban berat yang seakan terus bertambah di pundakku. Aku ingin meninggalkan semua ini! Namun, pada saat yang sama, aku tidak tahu ke mana harus berlari.
Aku juga berterus terang sudah bolos kuliah dan melalaikan tanggung jawab perkuliahanku beberapa lama.
“Have you talked to Mama Papa?”
“Sudah, Lys! Dan tahu nggak apa kata mereka?” Ketika tersadar aku sedang berada di mana, aku memelankan suaraku. Aku tak ingin kedua orang tuaku mendengar percakapan ini. “Kata Papa, aku sudah separuh jalan dan tinggal sedikit lagi lulus. Papa mengira aku cuma burnt out dan gak serius ingin berhenti. But he’s wrong! Aku gak bisa menunggu satu setengah tahun lagi. Aku gak bisa harus menjalani co-as. Aku gak melihat aku bisa menjalani profesi sebagai dokter di masa depan.”
Jangankan bertahan sampai lulus, bertahan sampai akhir semester ini saja aku sudah tidak sanggup lagi. God, help me!
“Dan kata Mama?”
Aku mengembuskan napas kesal. “Mama bilang ini pilihanku. Aku sendiri yang memilih masuk kedokteran dan aku harus menyelesaikannya. Papa sudah mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk kuliahku, tanggung jawabku adalah menyelesaikannya.”
“Yah, Mama ada benarnya.”
Aku menggeleng kuat-kuat. “Tapi aku nggak bisa, Lys. Aku nggak bisa …”
“Er, aku mungkin nggak ngerti apa yang kamu rasakan saat ini. Tapi, coba deh, kita cari jalan keluarnya.”
Ucapan Elysa memberiku harapan. Dia bilang ‘kita’, yang membuatku merasa tidak sendirian dan sebagian bebanku terangkat.
“Gimana, ya, Lys?”
“Gini … Coba kita menempatkan diri kita di posisi orang tua kita. Mereka pasti menginginkan yang terbaik buat kamu. Mereka gak ingin kamu putus kuliah padahal kamu sudah sejauh ini. Menurutku, kamu harus bisa meyakinkan mereka, kalau kamu enggak mau meneruskan kuliah jadi dokter, rencanamu selanjutnya apa?”
Aku menggeleng putus asa. Rasanya hidupku berakhir sudah. “Enggak tahu, Lys. Aku enggak tahu.”
Elysa tersenyum menenangkan, yang membuatku makin ingin menangis dan menjerit, karena begitu lama aku memendam ini sendirian dan akhirnya ada seseorang yang siap mendengarkan dan mendampingiku melalui ini semua. Dia berkata, “Hey, enggak harus kamu jawab sekarang. Coba kamu pikirkan saja apa yang mau kamu lakukan. Kan, tidak mungkin kamu berhenti kuliah lalu tidak melakukan apa-apa? Take your time to figure it out.”
Kami mengakhiri panggilan beberapa menit kemudian. Aku memang butuh waktu untuk mencari tahu apa yang akan kulakukan. Namun, sebelum kami berpamitan, Elysa memberikan petunjuk kepadaku.
“Temukan tujuan hidupmu, Er. Itu akan menjadi kompasmu. Tujuan hidup itu selayaknya lebih besar dari sekadar sebuah profesi. Kamu enggak jadi dokter bukan berarti hidupmu berakhir. Kita diciptakan untuk menjadi abdi Allah dan memakmurkan bumi. Temukan dengan cara apa kamu ingin berkontribusi bagi bumi dan orang-orang di dalamnya, dengan cara apa kamu bisa bermanfaat bagi orang lain.”
Aku menggigit bibir bawahku, mencerna ucapan Elysa barusan, saat sebuah pemikiran muncul di benakku.
“Lys, bagaimana jika aku menemukan panggilan hidupku, tapi Papa dan Mama tetap ingin aku menyelesaikan kuliah kedokteran ini?”
Elysa terdiam sejenak, lalu berkata, “Yah, seorang muslimah itu akan melakukan yang terbaik di tempat dia berada saat ini. Kalau memang keputusannya begitu, ya, berarti kamu harus menjalaninya dengan sungguh-sungguh, sambil mempersiapkan untuk berpindah haluan karier nantinya. Satu per satu, Er. One thing at a time. Yang pasti, mintalah bimbingan dan petunjuk Allah.”
***
Aku mengembuskan napas sekali lagi untuk mempersiapkan diri mengetuk pintu kantor dosen pembimbing akademikku.
“Ya, masuk!” terdengar suara dari dalam ruangan.
Aku mendorong pintu dan separuh masuk ke dalam ruangan. Dosenku duduk di balik meja, sedang meneliti kertas-kertas di hadapannya. Beliau mengenakan kemeja merah hati lengan panjang. Meski usia beliau sudah lima puluh tahun lebih, tapi rambutnya masih berwarna hitam, hanya ada satu dua helai uban menyembul di antaranya.
Aku mengucap salam, “Selamat siang, Dok.”
Pak Lukmana mendongak dan kedua alisnya terangkat ketika melihatku. “Erica… Erica. Ke mana saja kamu?”
Nada suara Pak Lukmana membuatku tersenyum masam. Aku memang sudah mempersiapkan diri akan dimarahi. Jangan salah, Pak Lukmana bukan dosen killer, tapi mengingat apa yang sudah kulakukan hampir tiga minggu terakhir, yakni membolos dan tidak ikut ujian, rasanya masuk akal kalau beliau menegur atau bahkan memarahiku. Meski hal itu tidak menyenangkan, tapi apa boleh buat? Semua ini ulahku sendiri. Aku harus berani bertanggung jawab. Aku berniat memperbaiki nilai-nilaiku dan mengejar ketertinggalan.
Jadi, aku maju dan duduk di kursi di hadapan meja Pak Lukmana. “Sebelumnya, saya minta maaf, Dok …”
***
“Semangat, Er!” ujar Bobby yang berjalan di sisiku. Dia memberiku senyum miringnya.
“Iya, iya, Dokter Bobby.”
Kami berjalan ke auditorium, searah dengan teman-teman seangkatan kami lainnya. Aku tidak bilang langkahku kini makin ringan. Aku hanya bisa mengatakan kehidupanku saat ini tidak seburuk sebelumnya. Memang aku belum tahu akan melakukan apa selepas lulus sarjana nanti. Juga masih ada PR tanggung jawab yang harus kutunaikan, sebagian adalah akibat dari kelalaianku. Namun, sekarang aku punya harapan.
Masa depanku memang gelap, tapi harapan memberi setitik cahaya. Bukannya berlagak bijak, tapi memang itulah yang kurasakan. Terlebih ketika Elysa mengingatkanku bahwa Allah selalu memberikan kemudahan bersama dengan kesulitan.
“Bukan hanya satu, Er, tapi ada dua kemudahan bersama satu kesulitan. You’ll be fine.”
Kupegang kata-kata saudari kembarku itu. Mau tidak mau, suka tidak suka, aku harus menjalani dan melalui fase hidupku yang sekarang. Meninggalkan tanggung jawab tidak akan membuatku bebas. Justru aku akan makin terbebani oleh rasa bersalah, kan?
Jadi, seperti kata Elysa, aku berusaha melakukan apa yang kubisa, satu per satu. Sambil terus berdoa agar yang kulalui ini berakhir indah nantinya.


 yuniyustikasari
yuniyustikasari