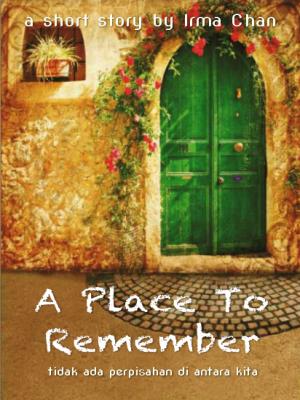Pukul 4 sore sampai 7 malam adalah waktunya warga Batam diuji kesabarannya ketika berkendara menuju rumah masing-masing. Mereka harus menghadapi macet panjang di setiap persimpangan lampu merah. Apa lagi kalau sedang melewati Simpang Kepri Mall. Sebab, ada delapan jalur yang berinterseksi di area ini. Belum lagi durasi satu lampu merah di setiap jalur mencapai 12 menit. Macetnya bisa berkil-kilo meter!
Sedan hitam Arga termasuk satu dari kendaraan yang merayap pelan menuju Simpang Kepri Mall. Sebelum sampai ke kafe tujuan, Cori memanfaatkan macet panjang ini untuk menyusun kata-kata dan mempersiapkan hati, apapun hasil pembicaraannya nanti.
Sepertinya, Arga sudah mulai curi start.
"Kok kamu nggak pernah kasih tahu Mas kalau kamu temenan sama Ben?"
Here we go, batin Cori.
"Kenapa? Mas khawatir Bang Ben bakal 'bicara' yang aneh-aneh soal kamu?" ketus Cori.
"Kok kamu kesannya nuduh aku?! Mas nanya baik-baik, lho."
"Really?" cebik Cori tak percaya.
Ia memilih memalingkan wajahnya ke jendela, menatap para pemotor yang dengan mulusnya menyalip lincah di antara mobil dan truk.
"Sayang, kalau memang kamu lagi rebel, protes dengan cara pergi bersama laki-laki lain karena Mas nggak bisa antar kamu ke reuni, Mas minta maaf. Okay? Maafin Mas, Sayang. Ya?" mohon Arga sambil memajukan mobilnya seinci demi seinci, lalu tuas rem ditarik lagi karena mobil di depan tak lagi bergerak.
Kali ini Cori mengikat amarahnya kuat-kuat sebelum bicara.
"Mas beneran pergi ke Tanjung Pinang waktu itu?" tanyanya lebih lembut. Cori hanya butuh kejujuran Arga.
"Ya."
"Sama siapa?"
"Sama Haryo."
"Aku bisa konfirmasi Mas Haryo?"
"Untuk apa?!" Arga seketika panik. "Kamu nggak percaya aku? Kamu anggap apa hubungan kita tiga tahun ini? Kamu buat aku kecewa, Cori."
Kali ini tuas rem dilepas kasar dan mobil melaju kencang walaupun hanya berjalan dua meter. Badan Cori sampai terhuyung ke depan gara-gara Arga menginjak rem terlalu dalam.
"Mas! Bisa lebih tenang bawa mobilnya?" Cori teriak tertahan.
"Kamu yang bikin aku kayak gini!"
Bulu roma Cori tiba-tiba meremang. Ia merasa terancam untuk alasan yang ia tidak tahu.
"Kenapa Mas malah marah?" katanya melembut. Cori tidak mau mau memancing pria di sebelahnya lebih jauh. "Aku hanya ingin confirm ke Mas Haryo. Nggak boleh?"
"Itu sama aja kamu nggak percaya Mas." Arga mulai gusar.
"Bagaimana mau percaya Mas ke Tanjung Pinang kalau aku lihat seseorang mirip Mas muncul di tempat aku reuni," tutur Cori. Ia menoleh lemah pada kekasihnya. "Dan lebih parahnya lagi, dia mencium bibir kakak kelasku dengan mesra." Cori meremas jemarinya yang mulai tremor.
Percayalah. Selain mengikat amarah, Cori juga menjaga suaranya agar tak bergetar. Ia berusaha membendung gejolak ingin menangis, menangisi nasibnya yang malang. Tapi Cori tidak mau menangis di depan pria ini.
Lagi-lagi mobil dikemudikan dengan ugal-ugalan. Kali ini Cori memilih diam dan berpegangan pada hand grip di atas jendela demi keamanan dirinya sendiri.
"Jadi kamu datang ke reuni itu? Kamu bohong, Cori!"
Cori memutar bola matanya dramatis. "Apa itu penting sekarang?!"
Arga mendengkus tidak senang. "Penting! Pasti Ben yang ngadu ke kamu, kan? Halah. Mas udah curiga sejak bertemu dia di depan kantor kamu. Dia nggak senang sama Mas. Dia pasti ngejelekin Mas."
"Memangnya Mas berbuat apa sampai dia nggak seneng sama Mas?" tantang Cori.
"Ya ... nggak tahu. Dia mau ngerebut kamu dari Mas, mungkin?"
Cori tertawa kering. "Yang benar aja, Mas. Bukannya Mas yang harus beri aku penjelasan mengenai Kak Riri?"
"Ri-Riri?"
"Ya. Hanari Anjani, kakak kelasku waktu di SMA sekaligus teman dekatku. Hm, apa karena aku sering ceritain dia ke Mas, Mas Arga jadi suka sama dia? Atau kalian pernah bertemu di luar tanpa sepengetahuanku?"
"Sayang, Mas nggak ngerti maksud kamu." Lagi, Arga memakai taktik pura-pura naifnya.
Cori terkekeh kecil. Ia tidak mau repot-repot meladeni keluguan pertanyaan Arga. "Dia ... calon istri Mas, kan? Congratulations, Mas Arga. Kenapa Mas nggak kasih tahu aku kabar baik ini? Pasti bahagia jadi Kak Riri. Dia ... sudah merebut mimpiku."
Pijakan rem yang cukup dalam membuat mobil Arga berhenti mendadak di tengah jalan. Baik Arga dan Cori terlempar ke depan kemudian sama-sama terhempas ke sandaran kursi detik berikutnya.
Seketika mereka disembur klakson marah dari pengendara lain. Tapi Arga tidak peduli dan memilih mengemudikan mobilnya di lajur kiri dan berhenti di pinggir jalan begitu saja.
Wajah Cori kehilangan darah. Dia menekan dadanya kuat meredakan jantungnya yang berdegup tak beraturan. Beberapa menit yang lalu Arga bisa saja membuat mereka dibawa ambulans ke rumah sakit.
"Bagaimana..."
"Aku tahu?" sambung Cori bergetar. "Itu nggak penting."
"Cori, dengarkan aku."
Gadis itu menggeleng pelan. "Mas Arga... Aku cuma mau Mas jujur. Apa karena aku gemuk? Nggak menarik? Nggak secantik Kak Riri?"
"Omongan kamu mulai ngaco. Kamu itu cantik, smart, baik, Sayang."
"Stop manggil aku 'sayang'!"
"Oke-oke. Cori, ini nggak seperti yang kamu pikirkan."
“Lalu apa? Aku seharusnya berpikir ciuman dalam dari Mas ke Kak Riri hanya ciuman antar teman? Aku seharusnya berpikir belaian tangan Mas ke punggung Kak Riri hanya belaian seorang teman?”
“Ben yang kasih tahu kamu, kan?”
“I saw everything, Mas. Aku juga mendengar semuanya! Jadi jangan coba-coba menyangkal."
“Jadi, kamu … beneran datang ke acara reuni SMA-mu?” Arga bertanya dengan ketakutan.
“Ya."
Pria itu tak jadi membela diri. Dirinya terpojok oleh fakta.
"Apa artinya hubungan kita selama tiga tahun ini? Sejak kapan aku mulai tidak ada dalam rencana masa depan Mas? Atau ... sejak awal memang nggak ada?"
Pria itu diam, tidak mengelak, ataupun membantah. Tubuh tegapnya membungkuk dan tersandar lelah ke sandaran jok.
"Mas masih ingat kan, cerita tentang mamaku yang nggak pernah mengharapkan eksistensiku di dunia? Dia yang tidak pernah menumbuhkan harapan sedikit pun untuk mempunyai aku sebagai anaknya? Aku trauma dengan perasaan seperti itu. Ditinggalkan, tidak diharapkan. Perasaan tidak diinginkan membuatku nggak percaya pada orang lain. Tapi Mas datang memberi aku harapan baru itu."
Tubuh pria itu kembali menegang. Remasan setir menjadi pelampiasan emosi yang tertahan. Arga kembali mengingat cerita sedih itu dari masa lalu. Dan detik itu juga, ia diserang berbagai macam emosi. Marah, sedih, kesal, dan menyesal … pada dirinya sendiri.
"Lebih baik Mas bilang padaku sekarang juga bahwa kita memang tidak mempunyai harapan untuk bersama, untuk menikah dan membangun keluarga kecil bahagia seperti mimpiku. Jangan menjadi manusia seperti mamaku. Mas menghancurkan kepercayaanku. Dan Mas ... menghancurkan mimpi sederhanaku."
Karena Arga tidak juga mengeluarkan suara, Cori memilih bungkam sambil menenangkan diri dari gejolak ingin menangis. Cori tidak mau menangis untuk hubungan ini. Rasanya ... sia-sia.
Dua manusia itu duduk dalam hening selama beberapa menit. Hanya hembusan napas yang terdengar, menandakan masih ada jiwa yang hidup di dalam mobil.
"Ikhlas nggak ikhlas, aku harus pergi dari hidup Mas. Aku juga nggak mau mempertahankan hubungan penuh dusta seperti ini. Tapi aku mohon, kali ini jangan bohong padaku. Jangan tinggalkan aku diam-diam seperti yang mamaku lakukan padaku dulu. Jadilah pria gentle, Mas!"
Setelah mendesah lelah, Arga berkata, "Maaf."
Cori tersenyum miring. Satu kata itu sudah cukup menyimpulkan apa yang terjadi. Gadis itu mengangguk samar lalu membuka seat belt.
"Jangan pernah hubungi aku lagi. Jangan kirimi aku undangan pernikahan kalian. Jangan pernah muncul di hadapanku. Kalau Mas bertemu aku di jalan, anggap aku orang asing. Bila papaku menelepon Mas, tolong dijawab. Ceritakan apa adanya tentang kita dan tetap hormati beliau. Aku juga akan melakukan hal yang sama bila Ibu meneleponku."
Tanpa menunggu jawaban Arga, Cori keluar dari mobil dan menjauhi sedan hitam itu. Kali ini ia memasrahkan diri pada kakinya yang akan membawanya entah ke mana.
***
Ben mengandalkan Google Map untuk menjemput si Gadis Ketumbar. Tapi kenapa dirinya dibawa ke halte bus? Kenapa Cori duduk di pinggir jalan?
Satu klakson singkat membuat Cori terperanjat. Matanya jelas menyorot jalanan sibuk, tapi pandangannya kosong. Ben yakin telah terjadi sesuatu antara dia dan pria pengecut tadi.
Jendela mobil penumpang dibuka. Kepala Ben menyembul. "Cori, ayo," teriak Ben, lalu dibalas dengan seulas senyum yang tak ada emosi di dalamnya.
"Bang Ben, aku lapar," ucap Cori tepat setelah pintu mobil ditutup.
Bukannya menangis atau curhat, Ben dikejutkan dengan permintaan Cori yang di luar ekspektasinya.
"Baiklah. Makan di mana kita, Coriander?
Ben kesulitan membaca wajah si tetangga di bawah temaram senja. Dan Ben mesti menahan diri untuk tidak menyerbu Cori selama di jalan dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai apa yang telah terjadi.
Sabar, Ben. Beri dia waktu, batinnya pada diri sendiri.
Setelah dua puluh menit mengarungi aspal, Brio putih Ben berhenti di depan sebuah rumah makan yang berada di salah satu bangunan ruko.
"Podomoro Sambel Idjo?" baca Ben pada spanduk yang ditempel di dinding lantai dua.
"Pernah ke sini?"
“Belum pernah."
"Bagus. Bang Ben harus coba makanan di sini. Mereka udah punya banyak cabang di Batam karena saking rame pelanggannya. Eh tapi, Bang Ben suka pedas? Soalnya mood-nya aku lagi mau makan makanan pedas malam ini."
"Hm ... aku akan coba," jawab Ben ragu.
Mereka duduk di bagian dinding yang dihias lukisan dua perempuan Jawa yang berdiri di antara tiga keranjang bambu penuh dengan cabe rawit hijau segar.
"Sambel ijonya pakai cabe rawit?!" tanya Ben horor setelah melihat lukisan itu.
"Iya."
"Aku pikir pakai cabe keriting."
Tepat setelah Ben bergidik, pesanan demi pesanan muncul: ayam goreng sambal ijo kebanggaan rumah makan ini, sosis sambal ijo, tahu tempe sambal ijo, dan telur dadar. Last but not least karena Ben yang minta, Cori terpaksa memesan sayur cah kangkung. Dia tidak yakin akan menyentuh sayur itu.
Setelah pelayannya pergi, Ben akhirnya mengeluarkan uneg-unegnya yang tertahan sejak tadi.
"Jadi, semua sambal di sini pakai cabe rawit?!" tunjuk Ben ngeri pada piring-piring pesanan mereka.
"Iya. Bang Ben ... nggak suka?"
"Beri aku semua coba cabe-cabe itu!"
Cori tertawa menikmati wajah Ben yang sedang mati-matian membulatkan tekad demi si cabe rawit.
"Kenapa ketawa?"
"Nggak ada. Yuk makan."
Diam-diam pria itu melengkungkan garis senyumnya ke atas. Itu adalah tawa pertamanya setelah memamerkan wajah cemberut sepanjang perjalanan tadi. Fakta bahwa Cori mau mengabulkan permintaan konyolnya tadi sore saja sudah melambungkan hatinya. Kini ia juga berhasil membuat wanita itu tertawa.
Tak terperi betapa senangnya Ben malam ini. Ia rela menukar apa pun untuk membuat Cori tidak bersedih lagi. Misalnya, dengan melahap cabe-cabe mengerikan ini! Ya, walaupun Ben tahu apa konsekuensi setelah perutnya bercengkerama dengan cabe tak berperi kemanusiaan itu.
Bersambung


 kepodangkuning
kepodangkuning