Aspal tampak mengilap karena basah. Hujan kini sudah mulai reda, menyisakan gerimis saja. Petir melengking kuat telah digantikan oleh gemuruh-gemuruh dengan suara dalam dan berat. Aku memandangi sebingkai kota yang murung ini, mataku beralih dari tanah ke langit berkali-kali
“Kamu udah makan?” tanya Aruna. Dia sedang menyalakan teko untuk memanaskan air. Seturut deru hujan mulai tenang, tangisan Aruna ikut berkurang. Sekarang dia sedang berusaha bersikap seperti biasa dengan menyibukkan diri di pantry. Seolah pelukan dan tangisan sepuluh menit lalu hanya sebuah sesi melarikan diri dari hidup yang terlampau tengik.
“Udah, aku tadi kerja wedding-an, makan di sana,” jawabku sambil memikirkan bagaimana caraku memulai topik utama.
“Bareng Ares juga?”
“Ya. Ada Ares dan satu orang lagi. Zacky. Kamu tahu, kan?” tanyaku menoleh kepadanya.
“Ya,” sahutnya cepat, “kamu pernah cerita juga tentang …,” Aruna melirikku dari sudut atas matanya dan terlihat ingin tertawa, “namanya.”
Melihatnya mengatupkan kedua bibir kuat-kuat begitu justru aku yang tertawa. Mungkin karena merasa Zacky boleh ditertawakan, dia pun melakukan hal yang sama, tertawa. Untuk sesaat, kami seperti dulu, tawa berderai tanpa beban. Tidak selang berapa lama, tawaku surut karena menyadari situasi ini tidak benar. Dia juga perlahan berhenti tertawa dan dengan kaku mengaduk cangkir, menyelipkan rambutnya ke belakang telinga. Aku meninggalkan jendela, menghampirinya saat aroma kopi menguar dari minuman yang diaduknya. Dia menyerahkan cangkir kopi itu padaku. Aku menerimanya dan mencicipi sedikit karena masih sangat panas.
“Runa, aku pik-”
“Kamu tahu gak?” dia menyambar cepat, “foto aku pose selamat datang udah terpampang loh di lobby rumah sakit … juga di farmasi.” Dia tersenyum kikuk. Aku tahu dia hanya berusaha mengulur kalimat –yang tidak dia suka– dariku, lantas aku tersenyum sambil mengucapkan selamat.
“Aku fotoin buat liatin ke kamu. Bentar, ya, aku ambilin. Handphone aku di kamar,” ucapnya lagi dengan wajah ceria yang dibuat-buat dan hendak pergi. Dengan cepat aku menyergap pergelangan tangannya, dia menatapku sambil bergeleng seolah memohon agar jangan mengatakan apapun yang dia pikirkan. Matanya bergerak-gerak mencari jawaban pada mataku dengan raut tegang.
“Semuanya ada alasan, Runa,” kataku sambil melepaskan tangannya perlahan. Bahu Aruna turun lemas, dia melempar pandangannya ke kanan untuk menyembunyikan air mata yang tidak ingin diperlihatkan padaku. Aku yang sudah tahu hanya bisa mengusap pipinya yang mulai basah
“Setelah aku pikir, kamu memang lebih baik ikutin alur yang sejak awal udah dipersiapkan. Kamu gak rugi apa-apa,” kataku mencoba menjelaskan dengan pelan, “kamu bahkan akan menikah dengan teman baikmu.”
“Jangan bilang aku gak rugi apa-apa. Kamu tahu itu,” Aruna menatapku dengan kepastian, “aku masih berusaha, Gam. Aku masih membujuk Andre untuk bilang alasannya ke Bu Sarah.”
“Aku gak sedang bahas Andre, Runa. Aku bahas kamu. Mau dia Andre atau laki-laki lain, yang jelas aku tahu Bu Sarah gak mungkin menjerumuskan kamu pada orang yang salah.”
Aruna mematung, matanya berkedip-kedip seakan tidak percaya apa yang baru saja dia dengar, “Jadi … begini, ya?” dia mundur perlahan hingga bersandar pada meja pantry, menunduk menatap lantai marmer putih. Tangan kanannya meremas pergelangan tangan kirinya untuk menguatkan diri, “Kamu nyerah, ya?” katanya lagi, dengan suara yang lirih.
Aku terperangah.
Menyerah? Aku tidak suka kata itu. Menyerah itu tidak melakukan apa-apa saat tahu harus melakukan sesuatu. Sedang aku melakukannya, memilih jalan termudah untuk dia lalui. Aku merelakan perasaan berharga untuk kepentingannya, demi kebaikannya, demi masa depannya yang besar pula. Aku berusaha tidak egois, tidak mempertaruhkan dirinya. Rasanya benar-benar tidak adil jika ini disebut sebagai sikap seorang penyerah. Tetapi aku sedang tidak ingin memperdebatkan pengertian menyerah dengan Aruna karena akan mengulur waktu saja.
“Ya, Runa. Anggaplah begitu ….”
Lalu aku terkejut atas apa yang baru saja meluncur dari mulut sendiri. Aruna juga tampak lebih tidak percaya. Dia tersentak, mulutnya sedikit terbuka seperti ingin menyela, tapi dia kembali diam.
“Jadi …,” kataku sambil menegakkan pandangan padanya, “jangan lagi berusaha lebih untuk kita,” nada kepastian yang dibuat-buat itu membuatku ingin meninju mulut sendiri.
“Aku udah bilang, kan? Kamu pembohong yang buruk,” katanya dengan suara yang terdengar begitu tegas meski bahunya bergetar. Dia menatap tajam seolah menungguku membenarkan apa yang baru saja dia katakan. Aku hanya mengulum senyum, mencoba menyembunyikan raut kesedihan dari sebalik cangkir, menyesap kopi yang sudah tidak terlalu panas.
“Gam, aku masih percaya,” suara Aruna terdengar menyangkut.
“Apa?”
“Cinta yang kita punya jauh lebih kuat meski kadang diselingi perdebatan hebat.”
Dia diam menatapku penuh cemas dan harap.
Sedang aku gagal menyeruput kopi karena tersentuh mendengar pernyataan Aruna. Aku tidak dapat menyangkal kata-katanya. Namun, aku tidak boleh mengakuinya begitu saja karena khawatir hal itu akan menggoyahkan seluruh tekad.
“Kalimat terakhir itu terdengar seperti harapan, Runa.”
“Ya. Memang. Lagipula aku benar-benar berharap.”
Aku diam lagi, menghela napas panjang sambil menatap kopi dalam cangkir yang sedikit beriak. Apa tanganku bergetar?
“Kamu ingat? Kamu pernah bilang ke aku untuk gak terlalu berharap karena kita gak tahu apa yang bakalan terjadi di masa depan,” aku diam sejenak, menatapnya, “ingat?”
“Ya. Aku ingat.”
“Aku sempat protes, kan? Ayolah santai aja, jangan begitu. Ingat?”
“Ya. Gam.” Lagi-lagi dia tampak ingin bicara, namun dia ragu, kemudian tertunduk lesu karena mulai paham kemana arah pembicaraan ini, juga (mungkin) merasa sedang disuapi ludah sendiri hingga tampak putus asa dan mengecil.
“Waktu itu kamu bilang, kamu cuma menyoalkan realitas.”
Aku menguatkan diri dan hati saat menegaskan hal-hal semacam ini padanya. Samar-samar sebenarnya dadaku nyeri. Aruna masih diam, menunduk dan membisu. Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi.
“Sekarang harusnya kamu tahu alasan aku apa, kan?” tanyaku dengan suara yang dirambati kegetiran.
Sambil mengatupkan kedua bibirnya rapat-rapat dia membuang muka sehingga aku tidak bisa menafsir ekspresinya, apakah sedih atau marah. Atau bisa saja keduanya.
“Percayalah, Runa. Kamu bakal baik-baik aja. Aku juga bakal … baik-baik aja,” pada kalimat terakhir, aku meragukan diri sendiri, “lagipula aku gak mau kamu dinilai buruk oleh Bu Sarah. Budi tetaplah budi.”
“Dan orang yang menerimanya harus tahu diri,” Aruna menyambungnya buru-buru, seolah dia menghadang kalimat itu keluar dari mulutku. Padahal tidak sama sekali. Aku bahkan tidak terpikir mengatakan itu.
Aku berdeham, “Bukan gitu maksud aku. Orang yang bahkan gak punya kewajiban membesarkan kamu dengan rela memberikan segalanya supaya kamu bahagia, supaya kamu sekolah. Kamu tumbuh menjadi perempuan cerdas. Tandingan aku orang yang seperti itu, Runa. Aku gak bisa bermodalkan cinta menghadap Bu Sarah. Beda cerita kalau pernikahan kamu masih lama dan aku punya waktu mengejar apa yang tertinggal. Dalam sebulan aku bisa apa?”
“Ini realitas yang kamu maksud?” tanyanya dengan memangku tangan di depan dada, seakan menuntutku dengan keputusan sepihak. Walaupun tampak marah, namun pada matanya terpancar kegelisahan dan kesedihan yang mendalam.
“Ya. Kamu bakalan mensyukuri ini suatu hari nanti.”
Aruna mengembuskan napas kasar sambil bergeleng kesal, “Nonsens!”
Kami diam lagi. Dan benar-benardengan canggung.
Tidak lama, dia menghampiriku, mengambil cangkir kopi yang masih tersisa setengah dari genggamanku dan mencucinya.
“Nanti aku aja yang cuci, Runa,” kataku.
“Kamu gak boleh terlalu sering minum kopi, apalagi kopi instan.”
Dia memunggungiku, mengabaikan perkataanku dan menyibukkan diri dengan cangkir yang dia cuci. Seperti melepas segala kecemasannya pada spons hijau-kuning itu, dia remas-remas kuat hingga buih-buih busa mengembang cepat.
“Runa?” aku mendekatinya perlahan.
“Selalu balur minyak angin kalau mau keluar,” katanya lagi setelah membilas cangkir itu dan menyibukkan diri dengan menyusun piring yang bahkan sudah rapi. Aku tahu dia hanya berusaha menghindari tatapanku.
“Hei?”
“Kurangi merokok, jangan telat makan, jangan bergadang, jangan keluyuran di bar dan juga jang-”
“Runa!” Aku menariknya mendekatiku, “Kamu kenapa?”
“Dan juga jangan minum alkohol lagi ….” katanya terbata-bata. Mata dan ujung hidungnya tampak memerah begitu menyelesaikan kalimatnya. Aku tahu, wajah itu sedang berusaha menahan tangisan.
Sambil mengusap-usap pipinya, aku bertanya, “Kamu kenapa?”
“Aku melakukan apa yang orang-orang lakukan saat perpisahan.”
“Apa emang? Nyuci piring?” tanyaku dengan alis hampir menyatu.
“Nasihat.”
Aku diam sesaat, sejujurnya ingin tertawa, “Pasangan mana yang kamu tahu saling memberikan anjuran kesehatan pas perpisahan?”
Aruna tampak berpikir namun desiran hidungnya terdengar jelas, “Jadi benar. Ini perpisahan,” ujarnya dengan nada bicara dan mata yang menyiratkan luka. Dia melepaskan dirinya dari peganganku dengan perlahan. Aruna kembali bersandar di meja pantry, mengusap-usap dahinya sekaligus, sepertinya, caranya menutup wajah untuk menyembunyikan tangis. Aku bersandar di dinding di hadapannya, menunduk melihat ujung-ujung jari kakiku yang memutih kedinginan sambil menahan ulu hati yang perih mendengar kata perpisahan.
Aruna berbalik, dia memutar keran cuci piring, menampung air dengan kedua tangannya dan membasuh wajahnya. Dia juga merapikan rambutnya. Untuk beberapa saat, dia mematung, menatap dinding di atas keran dengan cat yang sudah pudar dan terdapat cipratan noda minyak. Kedua tangannya menopang di meja, jari-jemarinya mengetuk-ngetuk pelan. Dia juga berdeham beberapa kali membersihkan tenggorokannya, lalu berbalik. Kami saling pandang, aku tahu dia sedang memikirkan kata-kata di kepalanya.
“Cinta itu menyembuhkan. Cinta memudahkan,” Aruna akhirnya mengemukakan apa yang sedari tadi telah dia susun di kepalanya, “Nyatanya sekarang aku merasa sakit dengan cara yang rumit” katanya lagi sambil mengusap-usap dada dan sedang mengatur isakan.
Jangan begitu. Jangan mengais-ngais kesedihan dan mencoba meraih kesempatan agar aku merubah pikiran. Jangan gunakan kesakitan sebagai umpan. Aku juga sakit, Runa. Tapi aku tahan demi kebaikanmu di tahun-tahun kemudian. Mungkin bersamaku memang menyenangkan. Saat sedang dalam perjalanan panjang dan membosankan kamu menemukan danau. Kamu gembira dan bersuka cita memercik air kemana-mana. Menghilangkan lelah dan gerah. Tapi itu hanya kesenangan sementara, sebab aku danau musiman, jika hujan akan tergenang, saat kemarau datang akan kerontang. Aku hanya tempat wisata yang didatangi saat senggang dan tidak untuk berdiam dalam jangka waktu panjang. Kamu lebih baik melanjutkan perjalanan sampai tujuan.
“Sakitnya itu sementara aja, Runa. Percayalah … Suatu saat kamu bakalan lupa gimana rasanya. Lagipula siapa yang gak sakit cinta di usia dua puluhan?” hanya itu yang bisa aku ucapkan untuk membentengi perasaan yang sudah menggelepar.
Dia menggeleng dengan lemah, sudah benar-benar tampak putus asa. Kata maaf menggantung di mulutku. Juga sepertinya menggantung di ujung lidah Aruna. Aruna menunduk, sesekali mengusap-usap tengkuknya, sedang aku melempar pandangan pada meja kerja. Kami seakan sama-sama setia tidak ingin melihat dan memperlihatkan bagaimana air muka yang sedang menahan perihnya luka.
“A-aku … balik ke kamar, ya,” ujar Aruna tiba-tiba, hendak pergi. Aku mencekal lengannya saat melewatiku. Lalu aku dan dia sama-sama terkejut akan sikapku. Aku yang memutuskan hubungan ini tapi disaat yang sama juga tidak ingin dia pergi. Tidak masuk akal.
Aruna melirik pergelangan tangannya yang aku pegang kuat.
Lalu menatapku seakan bertanya ada apa lagi.
“Sini, masih ada sesuatu yang harus aku kasih.” Aku membawanya meninggalkan pantry menuju meja kerja. Aruna duduk di kursi saat aku membuka laci dan merogoh bagian terdalam.
“Ini aku beli dulu pas pulang dari nganter ayah kamu ke pelabuhan,” kataku sambil menyerahkan kotak beludru merah menyala.
Aruna membukanya dan seketika menatapku penuh makna saat tahu isinya cincin berpermata.
“Aku merencanakan suasana pantai malam hari pas ngasi ini. Gak tahunya karena nunggu-nunggu momen itu, aku kehilangan banyak hal, studio dan … kamu. Aku sempat menunda dan masih pengen nabung untuk bawa kamu ke pantai,” kataku dengan sungguh-sungguh.
Aruna diam sejenak, dan mengingat-ingat, “Kamu mau ajak aku ke Bali atau ke Padang, kan? Waktu itu kamu pernah bilang.”
“Ya. Itu.”
“Aku pikir kamu bercanda.”
Aku diam, mengusap rambutnya perlahan. Nyeri pada dada semakin terasa saat dia mengira aku bercanda, namun aku abaikan. Kadang memang tidak semuanya harus diutarakan agar tidak mengaburkan suasana, lantas aku tersenyum saja.
“GA dan AG. Udah berapa banyak barang kita yang ada inisial ini?” tanyanya sambil membaca ukiran bagian dalam cincin itu.
Aku mengangkat bahu, “Entah. Kamu yang mulai dari jam weker.”
Aruna menoleh kepada jam yang diberikannya padaku, “Aku yang mulai, ya?” gumamnya pada diri sendiri.
Aku mengangguk.
Aruna kini sibuk melihat-lihat cincin sederhana itu, memutar-mutarnya, mengusap-usap huruf yang terukir di dalamnya. Aku melihat mata Aruna bersinar terkena pantulan bayangan permata putih kecil.
“Bawalah, Runa. Cincin itu punya kamu sejak awal,” kataku.
Dia mendongak, terperangah. Kelopak matanya naik tinggi sambil menggeleng kuat, “Gak. Aku gak berhak, Gam.” Kemudian memasukkan cincin itu cepat-cepat ke kotaknya lagi.
Aku mengusap-usap jarinya dan menatap hanya kesana, “Entah sejak kapan, tapi aku selalu mengira-ngira ukuran jari manis ini kalau sedang memegangnya begini.”
“Gam …,”
“Bawalah. Simpan,” pintaku lagi menangkupkan kotak itu ke dalam telapak tangannya.
Kamu selalu memiliki tempat di hati, selamanya.
Hampir menangis aku mengucapkan itu. Meskipun tidak terdengar olehnya. Meskipun tidak ada pantai malam ini. Tapi kalimat yang akan aku ucapkan saat memberikan cincin ini setidaknya terungkapkan dalam hati. Di antara perasaan yang menyesakkan, aku merasa sedikit lega karena cincin ini sudah berada di tangan pemiliknya.
Dengan perlahan Aruna membuka kotak beludru itu dan memakai cincin pada jari manis kanannya dan tangan itu belum berhenti bergetar saat dia tatap penuh haru.
“Pas. Bagus. Cocok banget,” ucapku lirih. Aku menatap jarinya lama, mengusap-usap jari yang mengenakan cincin itu sambil tersenyum simpul.
“Makasih, Gam. Makasih ….” Lalu dia memelukku yang berdiri di hadapannya, menekan wajahnya kuat-kuat pada perutku. Aku mendekap kepalanya, mengelus rambutnya. Dia tersedu-sedu, benar-benar seperti mencurahkan segala kepedihan hatinya. Suara tangisnya sangat tajam mengiris jantung. Aku sekuat-kuatnya memejamkan mata, menahan air tidak menetes karena menyadari inilah momen-momen perpisahan kami yang sebenarnya. Kenangan-kenangan lama berputar kembali dalam kepala, dari dirinya yang baru saja pindah, membawa tumpukan kardus di lorong yang berantakan hingga pada pertengkaran kami dua minggu lalu. Waktu-waktu sedih hingga waktu-waktu bahagia, waktu-waktu serius hingga waktu-waktu bercanda, yang jelas saat itu kami saling memiliki dan menggenapkan. Itu saja. Cukup itu saja. Cukup sampai disini saja sebab perkara hidup tidak hanya menyoal cinta. Diam-diam aku menangis juga, menghadapi kenyataan Gamma Aditya dan Aruna Gantari tidak ada lagi setelah malam berganti pagi.
“Sshhh … sshhh …” kataku menenangkan tangisannya, masih sambil mengelus rambutnya yang halus. Aku lalu duduk bersimpuh di depannya, memegang kepalanya dengan kedua tanganku yang membuat wajahnya nyaris tertutup semua. Jempolku mengusap-usap pipinya yang basah. Dia memegang tanganku dan memiringkan kepala untuk mencium sebelah telapak tanganku.
“Sejujurnya, aku gak mau menangis. Aku udah nebak kejadian ini. Aku bahkan mempersiapkan diri. Tapi aku malah nangis, Gam,” katanya sambil berusaha tersenyum. Aku membalas senyumannya. Matanya yang penuh genangan itu menyimpan banyak kenangan. Aku mengangguk-angguk, “Kamu memang orang yang gampang nangis, sekalipun gak pengen.”
“Kamu … kamu gak nangis.” Katanya.
Aku memang terlihat tidak menangis karena sekuat tenaga menahannya hingga hatiku berlumuran darah. Dia menatapku lama dengan mata yang penuh pecahan kaca. Aku menahan diri untuk tidak mengecup mata itu dan menelan mentah-mentah butiran kaca yang berserak di pelupuknya.
“Gam? Sekarang ini kita belum selesai, kan?” katanya sambil mengusap-usap pipiku. Pertanyaannya sederhana, namun aku tahu arahnya kemana dan juga … aku takut menjawabnya. Dia meraihku, kepalanya bersandar pada bahuku. Dia sangat dekat hingga permukaan bibirnya yang bergetar dan napasnya yang tersengal terasa hangat menyentuh kulit leherku. Dan itu benar-benar merepotkan gejolak darahku. Aku memegang bahunya dan menjauhkan dirinya. Kami berpandangan. Ada sesuatu dalam sorot matanya, yang membuatku tahu, dia ingin begini lebih lama. Lalu aku lalai, menatap mata yang bagai lautan itu lekat dan lama. Benar saja, aku yang rasanya sedang bermain di pantai sambil mendengar deburan, tiba-tiba terbawa ombak dan air menggulungku hingga ke tengah. Tidak lagi memiliki akal sehat, aku mengangkatnya dan mendudukkannya di meja. Dia membiarkan bibirku menciumi bibirnya, menyusuri pipi, telinga dan lehernya dengan segera dan tergesa, dengan kuat, dengan segala perasaan yang terombang-ambing. Dalam segala keraguan dan keresahan, satu hal yang bisa aku pastikan. Aku rindu. Sangat. Rindu yang menggebu hingga rasanya memberontak ingin keluar dari dada. Lalu segera sadar bahwa sesuatu telah mendesak perutnya. Kami bertatapan. Dia … entah untuk memastikan atau sekedar ingin menggoda, justru membelai sesuatu itu dengan lembut, membuat seluruh tulang yang menopang tubuhku mencair hingga aku ingin jatuh. Aku gemetar, semua bulu roma bangkit, jantungku gelagapan dan jika saja tidak berpegangan kuat pada meja aku benar-benar akan jatuh. Melihatku begitu, Aruna tersenyum, lalu membisikkan kalimat yang membuat rasionalitas yang sudah tinggal seujung kuku berhasil melayang jauh. Aku melirik Aruna, matanya menyoroti sangat dalam dan penuh keyakinan. Sambil mengalungkan kedua tangannya pada leherku, dia mencium telingaku. Lantas aku mengangkatnya, terhuyung-huyung membawanya pada kasur. Kami pun saling melepaskan apa yang masih melekat pada tubuh. Lalu jari-jemari saling menyusuri setiap jengkal kulit hingga sudut paling dalam, tanpa tertinggal satu senti. Tidak ada lagi percakapan sebab mata dan sentuhan telah menguraikan kata-kata lebih dari yang mampu diucapkan bibir dan yang didengar telinga. Kini aku paham kenapa wanita menjadi simbol ketenangan dan kasih sayang, ada Shinta untuk Rama, Frigg untuk Odin, Mumtaz Mahal untuk Shah Jahan, sebab segala keresahan, kegelisahan bahkan ketakutan yang aku alami sejak kejadian kebakaran hingga hari ini tiba-tiba saja sirna hanya karena merasakan hangatnya bagian terdalam Aruna. Lalu kini aku meyakini: Aruna untuk Gamma. Aku sadar apa yang dikatakan Ares tentang satu tubuh satu jiwa. Memang begitulah adanya, dua jiwa terjalin dalam tarian cinta. Berbagi napas, darah dan denyut nadi. Semuanya terjadi dalam hening paling bening. Suara gerimis dan gemuruh di luar pun tergantikan oleh lenguhan napas Aruna yang menggetarkan hasrat.
-oOo-
Aku bangun karena berkeringat. Matahari sudah mulai mengantarkan hawa panas ke dalam kamar. Dengan mengusap-usap wajah aku mencoba duduk.
“Runa?” Aku memanggil Aruna pelan karena dia sudah tidak di kasur lagi, entah dia sedang di pantry atau di kamar mandi. Tidak ada jawaban. Lalu handphone-ku di atas meja kerja berdering kuat. Ares menelepon mengatakan agar aku bergegas ke bandara. Saat dia masih berbicara, aku memungut celana yang tergeletak di lantai dan mengenakannya. Berjalan memeriksa pantry dan membuka pelan pintu kamar mandi. Aruna tidak ada.
“Iya. Iya. Gua siap-siap ntar lagi.” Aku menyambar ucapan Ares yang cerewet dan sempat melihat layar ponsel saat Ares masih menyerocos. Benar saja sudah pukul sebelas dan aku hanya punya waktu sekitar satu setengah jam untuk sampai ke bandara agar tidak ketinggalan pesawat. Ares memutuskan telepon dan saat itu aku melihat satu pesan yang ditinggalkan Aruna.
‘Makasih dan maaf untuk segalanya Gam’
Aku yang terperangah segera meneleponnya, namun tidak aktif. Aku menyibak selimut, membalikkan bantal hingga membungkuk melihat ke bawah dipan untuk mencari kaos, namun tidak kutemukan. Hanya kaos biru Aruna yang terselip di antara bantal. Lalu aku mengambil satu kaos dari dalam lemari, memakainya sambil berjalan cepat keluar dan mengetuk pintu Aruna. Berkali-kali dan tidak kudengar suaranya menyahut dari dalam. Aku mulai panik saat kembali ke kamar dan mengirimkan pesan padanya dengan jari-jari gemetar. Belum selesai menata pikiran, telepon dari Pak Bahar masuk, mengatakan aku harus segera bergegas sebab tim sudah dalam antrian check-in. Aku bergerak cepat, mandi, bersiap, meraih koper dan mengendarai mobil Kak Roni untuk dikembalikan ke studio. Kak Roni yang paham segera mengantar ke bandara dengan kecepatan yang membuatku merasakan pengalaman nyaris mati hingga dua kali. Selama perjalanan dan melewati prosedur keberangkatan hingga sudah duduk di pesawat, aku masih bingung, kosong dan bodoh menghadapi perasaan dan pikiranku sendiri mempertanyakan Aruna. Ares yang duduk disebelah menyadari sesuatu telah mengganggu pikiranku. Aku yang sedari tadi resah dalam diam, menoleh kepadanya, “Gua mesti gimana, Res?”
Mendengar itu, Ares mengangkat kedua alisnya seolah tidak percaya. Dia tidak berkata apa-apa, tapi kami memang selalu luar biasa komunikatif walau dengan cara diam. Lalu dia menghela napas panjang sambil berdecak gusar. Aku mengerti maksudnya lebih dari itu. Pesawat menderu melintasi awan. Aku duduk terdiam, tenggelam dalam pikiran. Kenyataan lain justru terjadi saat detik-detik terakhir hubungan kami. Dan berhasil, dalam sekejap saja membuatku berubah pikiran. Bagaimana ini? Aku ingin bertemu lagi. Berapa lama aku akan berada di pulau itu? Apa aku masih sempat mengatakan padanya untuk jangan menikah?
(Bersambung)
Restart ©2023 HelloHayden


 hellohayden
hellohayden












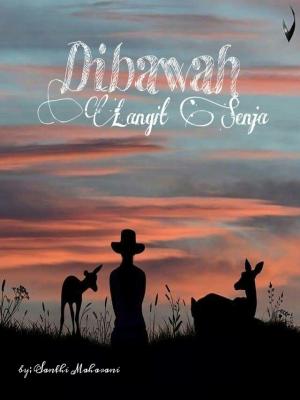
Baca cerita ini udah kayak masuk ke kedai all you can eat. Daging semua. Sbg cowok baca ini gk merasa aneh sama sekali untuk crita roman dan rasa kembali ke masa kuliah. Mantap lah
Comment on chapter Bab 14 (Cukup)