“Life is like a camera. Focus on what’s important. Capture the good times. Develop from the negatives. And if things don’t work out, just take another shot.”
Itu adalah kutipan Ziad K. Abdelnour, seorang pebisnis, aktivis dan penulis. Kutipan itu ada dalam bukunya dengan judul Economic Warfare. Marwa membacakan kutipan itu saat kami tengah santai menonton TV bersama di rumah. Lalu kalimat tersebut sempat digaungkan ulang oleh seorang sineas yang mengisi acara orasi interaktif yang diadakan kampus. Aku dan Ares saat itu bertugas sebagai panitia registrasi. Ares mengatur pendaftaran on-site, sedangkan aku pada pendaftaran online. Sudah beberapa kali, kehadiran Ares sebagai tim registrasi membawa keuntungan besar untuk kampus. Lagi-lagi, dengan perpaduan antara daya tarik fisik dan keahlian retorika-nya (hanya pada wanita), Ares adalah magnet luar biasa yang tidak tertolak.
Kembali pada kutipan tadi. Saat dibacakan Marwa dulu, aku merasa kutipan itu hanya terdengar seperti nasihat lazim. Kau jatuh, kau harus berdiri untuk bangkit lagi. Iya, begitu. Umum, lazim, biasa-biasa saja. Hanya karena memfilosofikannya dengan kamera, kutipan itu jadi terdengar distingtif, terlebih pada bagian developed from negativity yang mengingatkanku pada kamera analog. Tapi mendengar kutipan itu menggema untuk kedua kali, entah kenapa degup dada terasa berbeda, dengan cara aneh tentunya. Aku yang saat itu bersama tim desain, tengah sibuk memasukkan nama untuk sertifikat peserta, segera merogoh ponsel, mencari kutipan itu, menyimpannya untuk dicatat kembali pada buku bersampul coklat. Ah, buku itu dan temanku. Dua hal yang raib pada waktu hampir bersamaan. Buku memang aku buang. Mengenai temanku? Ares? Saat aku tidak terpikirkan untuk mengikuti jalan pilihan bapak –menyingkirkan seorang teman yang berkhianat– justru dia yang memutuskan untuk pergi duluan. Alasan terkuat memang hanya ada dua. Pertama, dia merasa sudah menjalankan tanggung jawab dengan mengirimkan uang, sehingga menganggap dirinya lepas dari beban. Kedua, dia merasa bersalah sehingga tidak punya muka lagi menemuiku. Setelah terlanjur berlalu hingga hitungan minggu, lembaran-lembaran rasa bersalah itu kini ditambah dengan tumpukan lembaran baru: rasa malu. Alasan kedua itulah yang aku percayai. Tidak dimungkiri, memang terbesit kekhawatiran sebab telah berteman lama dan tahu segala kisah keluarganya. Namun kekhawatiran itu hanya hilang timbul. Seperti gelembung pada danau yang hanya akan muncul saat permukaannya tenang dan tidak saat permukaannya beriak karena hembusan angin. Lagipula, aku tidak punya waktu mendramatisir hal-hal yang tidak terlihat di saat perkara nyata mengantre panjang dengan tatapan meminta diselesaikan segera.
Kamu jatuh, kamu harus berdiri untuk bangkit lagi.
Begitulah. Tidak diberi waktu untuk mengobati luka, justru aku menahan sakitnya sepanjang perjalanan walau terseok-seok.
-oOo-
Aku mungkin beruntung hidup ditengah orang-orang baik. Sore itu pada hujan pertama di bulan Desember, saat sedang membuat video animasi pendek untuk salah satu klien Gammares dulu, Ikhsan datang ke kost. Dia jauh-jauh dari Bogor untuk menunjukkan kepedulian. Menyampaikan maaf sebab baru bisa datang dan tidak melanjutkan alasan keterlambatannya yang menurutku juga bukan suatu kesalahan. Dia peka, sebab itulah dia menyimpan alasan keterlambatannya yang jelas-jelas aku tahu, dia sibuk menjalankan klinik psikologi. Kami bercakap-cakap dengan santai dan terasa cukup menyenangkan karena dia tidak mencoba menyampaikan ilmu yang dipelajarinya saat kuliah (meskipun sebenarnya dia bisa saja berpikir bahwa kata-kata bijak psikologi dapat membantuku melewati fase ini), dia lebih memilih bertindak sebagai seorang saudara daripada psikolog.
Tidak ada hari dimana ibu tidak menelepon sejak kejadian kebakaran. Meskipun yang dibahas tetap hal itu-itu saja, tapi aku tidak bisa menyela ibu yang selalu membawa kisah ini ke arah nelangsa. Bagaimana juga, perih hatinya juga tidak terukur mengetahui usaha yang sedang digeluti anaknya hancur. “Ares gimana? Masih belum ada kabar, Nak?” tanya Ibu suatu waktu.
“Belum.”
Ibu menghela nafas, “Kamu masih marah?”
“Yah, kayak kebanyakan masalah lain. Marah pun surut seiring waktu, Bu. Aku sekarang cuma fokus buat ngumpulin uang lagi. Marwa mau wisuda.”
“Jangan terlalu dipaksakan. Adikmu juga punya tabungan, Ibu juga masih ada pegangan,” jawab Ibu segera.
Tidak seperti permulaannya yang cenderung memprihatinkan, telepon dengan Ibu hampir selalu berakhir menyenangkan. Entah itu dengan cerita lucu tentang tetangga, hingga kisah mamang bakso yang lari terbirit-birit dikejar anjing milik pensiunan tentara yang baru saja pindah ke sekitar rumah. Kali ini cerita beralih ke Marwa yang memutuskan memotong rambut sebab kemarin malam ada kecoa hinggap pada ujung rambutnya.
Saat ponsel masih aku genggam, sebuah pesan masuk dari Bu Lin. Klien yang pada awalnya banyak berkeluh kesah terhadap Gammares, namun kini dia yang sudah tahu bagaimana hasil kerjaku, tetap mau bekerja sama. Materi sosial media toko TinyTreats Delight itu aku kerjakan dengan membawa nama sendiri, Gamma. Pesan dari Bu Lin mengatakan dia ingin membuat promo khusus untuk menyambut Natal dan Tahun Baru dengan beberapa foto dan video untuk kue kering.
Selain Bu Lin, Kak Amy juga datang kembali. Dia yang baru aku ketahui sudah setengah tahun keluar dari pabrik garmen dan kini sedang membuka usaha franchise sebuah cemilan ayam goreng. Baru-baru ini menghubungi agar Gammares membuatkan materi iklan. Dia terkejut sampai tidak ada obrolan untuk beberapa detik saat aku mengatakan alasan Gammares sudah tidak ada, lalu segera mengajak bertemu di gerai franchise-nya untuk membahas materi.
-oOo-
Ini sudah memasuki minggu kedua Desember berarti sudah hampir sebulan kejadian kebakaran berlalu. Dalam dua hari, masa sewa ruko berakhir. Untungnya, ruko sudah selesai dibenahi nyaris seperti sedia kala. Hanya beberapa bagian yang berbeda, pintu kamar mandi yang dulunya PVC berwarna biru muda kini berganti kuning, rolling door yang dulu dibuka ke atas, kini menyamping. Ibu pemilik ruko tidak mempermasalahkan hal itu. Justru yang menjadi permasalahan adalah kunci pintu belakang yang salah satu duplikatnya masih Ares pegang.
Saya minta itu. Kamu tolong lengkapi kunci ini jadi tiga lagi. Begitu ujar Ibu pemilik ruko. Sempat terpikirkan untuk membuat duplikatnya dan mengatakan bahwa itu dari Ares agar masalah ini selesai segera, tapi nyatanya selain kunci itu dari merk terkenal yang tidak mudah diduplikasi persis sama, moralku tergerus jika harus menyelesaikan masalah itu dengan cara curang. Lagipula aku menantang seorang teman dan meninggalkan pesan (yang entah dia baca atau tidak) untuk mengingatkannya mengembalikan kunci.
Jam masih menunjukkan pukul delapan malam. Aku minum obat lambung, makan, lalu minum obat lainnya setelah itu, walau masih untuk lambung. Aruna geleng-geleng kepala, “Masih muda, belum juga dua lima, udah banyak minum obat.”
Aku terkekeh, “Yah, terima aja, deh. Lagian kamu masih sayang, kan?”
Aruna merespons dengan menjepitkan ujung lidahnya di antara bibir. Dengan segera aku menangkup lidah mungil itu dengan bibir juga.
Dia tersentak, “Bau rendang!” ujarnya lagi.
“Ya wajar, lah. Makan rendang ya bau rendang. Yang aneh kamu, mau makan apa aja selalu rasa strawberry!”
“Asem, dong!” protes Aruna.
“Permen strawberry yupi, yang pakai gula itu.”
“Ah? Masa, sih?” Dia justru menjilat bibir sendiri dengan naif.
Aku tersenyum, sudah dua tahun sebagai pacarnya dan dia masih saja terlihat menggemaskan.
“Aku yang harusnya nanya, kok bisa?” aku mengecupnya lagi. “Kok bisa?” kecupan kedua. “Kok bisa?” kecupan ketiga ini berakhir dengan aku didorong kuat olehnya.
“Udah, ah! Aku ada kerjaan!” ujarnya dengan nada jengkel yang lucu.
Aku tertawa.
Kami kembali pada pekerjaan masing-masing. Aku mengerjakan animasi dengan adobe after effects, sedang Aruna berbaring tertelungkup di kasurku dengan catatan terbuka dan ponsel menyala. Saat aku perhatikan, dia tampak serius menyalin sesuatu dari sebuah foto yang ada pada ponselnya. Data asesmen pasien, katanya. Aku perhatikan lama dirinya. Sudah seminggu ini sepertinya dia kelelahan. Uluran tangannya kepada bebanku membuatnya disibukkan antara bekerja dan membantu urusan pembenahan studio. Lima hari lalu dia demam. Tapi dia Aruna, tidak mengeluh, tidak merengek justru berusaha selalu terlihat kuat. Seolah mata itu berkata aku di sini dan siap sedia.
Dia melirik sebentar sebelum akhirnya tersenyum tipis dan kembali menulis, “Kamu liatin aku begitu terus, ntar kerjaannya gak selesai, lho!”
Aku menggeleng kepala mendengar sentilannya, “Ya. Kamu bener.”
Aku memutar lagi kursi menghadap komputer. Menjelang akhir tahun, ada sebuah proyek cukup besar. Pak Purwa, orang yang dulu bekerja sebagai copywriter pada brand kecap, menghubungiku sekitar tiga hari bulan Desember baru saja mulai. Dia mengatakan sedang bekerja untuk Pemprov DKI sebagai konseptor naskah projection mapping yang akan menjadi sebuah pertunjukan pada Monas Week untuk mengisi acara Natal dan Tahun Baru. Pak Purwa mengatakan tim animator sedang kekurangan orang. Walau harus melewati beberapa rentetan tes, namun prosesnya berjalan cepat. Hanya sekitar empat hari sejak mendaftar sebagai pelamar, lalu melakukan dua tes rekrutmen dalam satu hari, aku ditelepon dinyatakan lulus untuk bergabung. Aku sungguh bersyukur. Video animasi itu lah yang sedang aku kerjakan sekarang. Aku membuka laci dan merogoh bagian terdalam untuk mengambil mouse cadangan. Namun, aku justru salah sasaran. Yang kuraih adalah kotak beludru merah berisi cincin untuk Aruna. Aku benar-benar lupa mengenai cincin ini sebab sibuk sebulan terakhir. Aku menoleh ke arah Aruna, beruntung dia tidak melihat. Segera aku simpan kembali kotak itu dan mulai mencari mouse.
Aruna masih sibuk dengan data pasien, sesekali dia berdendang ringan mengikuti lagu yang mengalun pelan.
“Runa? Setelah semua ini baik-baik aja, kita ke pantai, yuk?”ajakku, masih ingin mewujudkan impian meromantisasi pantai malam hari. Lagipula, dia pantas mendapatkannya setelah semua bantuan yang aku terima.
“Pantai? Ancol?” Aruna terdengar bingung.
“Bukan. Kita bisa ke Bali atau, hmmm, ke Padang?”
“Lihat patung Malin Kundang?” Aruna masih bingung.
Aku menoleh dan melihatnya, “Ya, boleh aja.”
Dia tertawa, masih dengan raut bingung, “Boleh! Kamu bisa lihat contoh nyata anak durhaka.”
“Andai ada contoh nyata pacar durhaka,” Aku bergumam pelan yang sayangnya terdengar jelas oleh Aruna. Dia menatap sinis, “Awas kamu!” sambil mengarahkan ujung pulpen padaku. Ancaman yang menggemaskan itu aku balas dengan ejekan.
Tidak lama, pintu kamar diketuk, suara Pak Yahya terdengar memanggil. Aku membukanya lalu dia menyerahkan sebuah amplop putih terlipat yang bertuliskan ‘Untuk Gamma 303’.
“Dari siapa, Pak?” tanyaku.
“Gak tau. Orang ojek tadi anter,” jawab Pak Yahya sambil mengangkat bahu.
“Makasih, Pak.”
“Yowes, saya kebawah lagi, Mas.”
Aku menutup pintu, mengulurkan amplop itu pada Aruna dan berangsur ke jendela. Aku bahkan tahu tanpa membuka bahwa isi amplop itu adalah kunci yang sudah pasti dikirim oleh Ares.
“Ini kunci pintu belakang studio, kan?” Aruna melihat lamat-lamat kunci itu saat dia buka dari amplop, “Ares?” tanyanya bingung sambil mentapku.
Aku yang tengah berdiri berhadapan dengan sebingkai pemandangan lalu lintas malam hanya mengangguk. Walau rasanya sia-sia tapi aku tetap berusaha memperhatikan sekitar, berharap melihat Ares di antara lampu jalan yang kekuningan. “Udah hampir sebulan dia gak ada kabar,” aku bergumam, “dia udah tiga kali kirim uang, satu diantaranya melalui rekening Trisna.”
“Gam?” bujuk Aruna. Aku memalingkan wajah dari jendela dan kini menatap Aruna. Di tengah-tengah kasur yang beralas sprei abu-abu dan sedikit berantakan sebab kertas, buku dan alat tulisnya, dia tampak kontras dengan kulit putih dan duduk menyilangkan kaki, menatapku dengan wajah sendu. Membujuk, memelas. Sudahlah, begitu wajah itu berkata.
“Runa …, aku cuma berharap dia gak ngelakuin hal bodoh demi ngumpulin uang sebanyak itu.”
Dia beringsut-ingsut ke tepi untuk turun dan menghampiriku. Satu tangannya dengan lemas bertengger di pundakku, satu lagi dia gunakan dengan tenang untuk merapikan rambut yang nyaris menusuk mataku.
“Sudahlah, sudah…,” bisiknya lembut penuh bujuk rayu.
Matanya memancarkan ketabahan luar biasa yang membuatku merasa jauh lebih tenang. Angin yang masuk melalui jendela membuat rambutnya menutupi sepasang mata yang sedang aku nikmati kedalamannya. Aku rapikan rambut itu, menyelipkan ke belakang telinganya yang kemerah-merahan karena udara terasa dingin. Untuk memberi kehangatan, aku mengusap-usap telinga itu, pula aku ingin mengecupnya dan tiba-tiba itulah yang terjadi. Perlahan aku mengecup telinga kanannya, mencium telinga itu kemudian menggigit kecil cuping telinganya. Ujung telunjukku kini menyusuri leher hingga pundaknya. Bermain-main, melukiskan lingkaran-lingkaran kecil dengan tekanan halus pada cekungan bawah lehernya saat bibirku bergelayut manja di bibirnya. Alunan nafasnya terdengar berat. Sepertinya juga sedang sekuat-kuatnya membuat pola nafas itu terdengar teratur olehku. Aku mengatakannya begitu, walau sebenarnya juga sedang melakukan hal yang sama, berusaha bernafas senormal-normalnya. Kedua tangannya meremas kuat kaosku untuk menahan seluruh gelora yang menjalari tubuhnya.
“Gam …,” panggilnya pelan.
“Hm?”
“Ki-kita masih ada kerjaan, kan?” pertanyaan itu dia utarakan dengan suara tertahan. Aku berhenti menciumnya, berdeham untuk membersihkan hasrat-hasrat yang telah merayap dari perut dan kini tersangkut pada tenggorokan. Kemudian menjatuhkan dahi pada pundaknya, “Ya. Ya,” jawabku dengan nafas tersengal.
-oOo-
Kepalaku berputar, memandangi ruangan yang dulunya terdapat dua hingga tiga tripod dan lighting berdiri tegak dan indah, lemari yang berisi kamera dan lensa-lensa, peralatan audio mixing, peralatan dekorasi set. Tak terelakan bayangan aku dan Ares yang bekerja sama, hilir-mudik bayangan kami berdua melewatiku seolah aku lah yang berdiri sebagai ilusi. Satu setengah tahun, usia Gammares ternyata tidak lebih lama dari rencana pendiriannya yang aku dan Ares gadang-gadang sejak semester tiga. Aku mengelilingi ruko ini sekali lagi sebelum benar-benar pergi. Ibu pemilik ruko juga sedang memeriksa kembali ruangan satu per satu, termasuk kamar mandi. Aku berada di kamar kecil pada lantai dua, memejamkan mata mengingat-ingat dulu aku tidur di kamar ini untuk menyelesaikan pekerjaan sendirian saat Ares tengah fokus pada kelulusan. “Maaf, karena satu dua hal, saya tidak bisa mempercayakan ruko ini pada kalian. Semoga rezeki kamu ada di tempat lain, Gam,” ujar Ibu pemilik ruko yang tiba-tiba datang. Terdengar olehku kalimat itu menyulih menjadi: Gammares VisualCraft usai.
Aku mengangguk dan menyerahkan semua kunci yang disatukan oleh mainan berbentuk kamera, “Terima kasih banyak, Bu.”
Ibu itu mengangguk, lalu kami bersama-sama turun. Aku menyaksikan dia sendiri mengunci pintu kaca dan rolling door setelahnya. Lalu pergi membawa mobil kuningnya membelah deruan suara kendaraan lain di jalan raya.
Aku masih diam, menatap ruko dua lantai ini dari luar, mengambil nafas dalam sambil memejamkan mata. Sinar matahari menyilaukan masuk dalam gelombang kemerahan dari balik kelopak mataku yang gelap. Aku hanya membayangkan dulu signboard Gammares terpampang gagah. Dan benar, walaupun tertutup rapat dan semburat merah berkeliaran, tulisan Gammares VisualCraft itu masih terlihat jelas dalam bayangan, beserta ingatan-ingatan saat pertama kali memasangnya.
“Mas? Mampirlah. Minum dulu. Gratis!”
Aku membuka mata. Entah kapan dia menyebrang, tiba-tiba mbak penjual minuman sudah berdiri persis di sampingku.
“Beneran?”Aku mulai bercanda.
“Anggap aja traktiran perpisahan, Mas.”
Aku tertawa, “Ngusir banget, nih! Emangnya gua gak boleh mampir kapan-kapan?”
Dia merespons candaanku dengan serius, “Oalah! Maaf, Mas! Saya pikir Mas gak bakalan mau datang lagi! Maaf yo, Mas …,” ujarnya dengan wajah penuh rasa bersalah.
“Jadi gimana? Undangannya masih berlaku?” Aku berguyon pada perempuan yang masih tampak rikuh ini.
“Masih, Mas! Masih.” Dia menjawab cepat dan mantap.
Kami menyebrang menuju kedai sederhana miliknya. Sebenarnya kedai itu hanyalah sebuah stan kayu yang pada tanah sisa di belakangnya dipasang tenda dan berjejer kursi di bawahnya sebanyak lima. Aku minum dan bercengkrama dengan beberapa pengemudi ojek yang sehari-hari mangkal di sana. Mendengarkan sepak terjang mereka sebagai pengemudi ojek online, kemudian tertawa bersama jika cerita itu terdengar lucu.
“Saya kira Mas Gamma dan Mas Ares beneran pasangan homo, lho!” Tiba-tiba mbak penjual minuman –yang tengah sibuk membuatkan beberapa bungkus minuman sachetan untuk anak-anak– memangkas lelucon kami. Semua berhenti tertawa dan kini melongo menatapku dengan raut setengah jenaka setengah cemas pula.
“Sebelum saya tahu kalau Mbak Aruna itu pacar Mas Gamma.”
Sepertinya dia sengaja memberi jeda di antara dua kalimatnya, mungkin karena kedua tangannya juga tengah fokus bekerja. Lalu reaksi teman-teman baruku ini tak kalah jenaka dari raut sebelumnya. Ada yang langsung berucap syukur, ada yang mengelus dada, bahkan ada juga yang mengaku nyaris saja memberikan kontak dukun di kampungnya untuk mengobatiku. Aku lupa kapan terakhir kali tertawa lepas begini. Tapi ini begitu menyenangkan.
Memang benar, rasanya memulai kembali semua dari awal. Aku menjadi freelancer lagi seperti dulu pada beberapa tempat sambil terus mencari pekerjaan tetap. Pelajaran hidup yang aku juga dapati dari cerita teman-teman baru ini, bahwa aku masih sangat muda untuk memulai lagi. Masih banyak kesempatan di depan mata. Masih banyak waktu untuk menata semua.
“Kunci semua itu ikhlas, Mas. Kalau masih mendem, ya, langkah kedepannya masih terikat sama kisah lama, Mas! Gak maju-maju ntar! Opo yo bahasa gaulnya? ” Kata pengemudi dengan jaket kuning.
“Move on, Pak!” Celetuk mbak penjual minuman.
“Noh! Itu!”
“Asal Mas-nya sabar, giat, gigih. InsyaAllah semua lancar. Rezeki itu disebar di muka bumi dari langit. Kita tinggal nyari.” Begitu ucap salah satu pengemudi dengan jaket hijau yang kemudian disambut dengan anggukan semuanya.
Lalu mereka yang berada di usia kepala empat akhir ini mengaku sangat peduli terhadap anak-anak muda yang sedang berproses. Tiga bapak-bapak ini berebut mengatakan bahwa seandainya dia punya kegigihan dan keyakinan besar saat muda, “Mas-nya gak akan menyesalinya. Walau gagal seenggaknya Mas udah nyoba. Malah perasaan paling gak nyaman itu justru suatu saat di masa depan Mas berandai-andai tentang kesempatan yang dilewatkan gitu aja. Tapi Mas-nya udah terlalu tua untuk mulai, terlalu banyak resiko untuk coba-coba.” Ujar salah satu bapak yang sepertinya orang Batak. Sedari tadi dia yang paling banyak membuat kami tertawa, tapi juga paling banyak memberikan nasihat.
Benar, aku tidak mau nanti di saat rambutku memutih, tulangku ringkih, duduk berdiam di rumah yang jauh dari kata nyaman sambil mengatakan seandainya … Seandainya dulu.
Selama mereka menasihati, aku cukup mendengarkan. Tidak ingin menambah perkataan, karena kata-kata itu keluar dari mulut orang yang sepertinya sudah mengerti seluk-beluk kehidupan. Observasi dan pengalamannya cukup meyakinkan.
Setelah sekitar setengah jam, aku berpamitan pada mereka sebab, lagi-lagi, harus merampungkan satu materi produk dari klien Gammares dulu. Ini adalah klien terakhir yang aku kerjakan sebagai perwakilan Gammares. Sebelum pergi, aku menyelipkan uang di bawah gelas es kelapa muda. Bukan bermaksud untuk tidak menghargai kebaikan hati pemilik kedai ini. Bagaimana juga, dia sedang mencari rezeki. Lagipula aku tidak terbiasa menerima sesuatu secara cuma-cuma.
Sepanjang jalan, di atas motor, aku merenung kembali.
Jujur, sulit memang beralih dari orang yang sempat memiliki cukup uang menjadi orang yang harus berpikir-pikir untuk sekedar membeli perlengkapan mandi. Aku bahkan berdiri lama di depan rak sabun untuk membanding-bandingkan harga. Mencari produk dengan manfaat yang sama dengan harga serendah-rendahnya. Kalau kata Marwa ini adalah efisiensi alokatif, equilibrium price atau macam-macam istilah ekonomi yang aku tidak tahu. Tapi kalau aku bilang: bang for the buck.
Sebulan ini, aku memang bergulat tanpa tahu batas siang dan malam. Aku lebih sering tertidur pada kursi kerja, dan bangun-bangun masih dengan komputer menyala. Lantas hanya makan dengan benar saat bersama Aruna. Selebihnya tentu saja aku memilih yang praktis. Makanan yang bisa dimakan tanpa harus menghabiskan waktu duduk menghadapi sepiring kudapan. Aku jauh lebih memilih roti dan terkadang hanya sebuah minuman penunda lapar yang aku harap berfungsi lebih sebagai pemusnah rasa lapar. Bagiku, jika perut sudah terisi dan rokok serta kopi sudah terpenuhi, itu sudah cukup. Pengeluaran untuk menyenangkan Aruna yang juga hanya sekali seminggu sudah bisa aku kelola. Uang yang dulu ibu kirimkan untuk jaga-jaga sudah aku kembalikan sisanya dan tetap berusaha mengirimkan uang belanja pada ibu walau tidak sebanyak dulu.
-oOo-
Sore itu seluruh Jakarta terasa menyengat. Panas dan berkeringat. Aku yang masih menumpang pada studio kakaknya Fahmi sedang mengemas set dari meja kecil karena telah selesai syuting materi produk franchise kak Amy. Walau ruangan ini memiliki AC tapi hawa panas yang menghantam dari segala sisi luar benar-benar membuatku seperti ubi kukus dalam dandang. Satu jam lagi aku harus menemui tim animator projection mapping di salah satu restoran di Bekasi. Studio kakak Fahmi tidak berada jauh dari rumah Cak Son, daerah Mampang. Itu berarti aku harus melewati kost dan menempuh perjalanan lebih dari setengah jam untuk sampai pada tempat pertemuan dengan tim.
Fahmi masuk dengan gaduh. Tas ransel yang hanya disandang pada satu bahu itu menabrak tiang lighting dan membuatnya nyaris jatuh. Selain dia masuk dengan bau matahari yang sangat kentara, ekspresi wajah Fahmi tidak dapat kutafsirkan. Dia terlihat ragu dan bimbang tapi saat bersamaan juga tampak antusias.
“Gua liat Ares, Gam! Asli kurus banget!” ujarnya sambil mengibas-ngibas kaos lembab sebab keringat.
Aku menoleh segera, “Ares?”
“Iya! Ares! Gua tadi ngeliput kampanye. Pas gua samperin, dia kaget. Kayak mau ngindar tapi subjek fotonya lagi bagus,” ujar Fahmi lagi dengan mata melotot, tak lupa tiga kerutan di keningnya melintang panjang. Benar-benar meyakinkan.
Dia menghempaskan bokongnya pada sofa, membiarkan udara dari AC menerpa tubuh lembabnya, “Tuh anak nanyain kabar lu,” kini sambil membuka kaosnya dan membuat gerakan seperti berkipas.
Aku diam saja dan terus berkemas.
“Eh! Tapi dia tahu kondisi studio sekarang udah beres. Gila! Berarti dia mondar-mandir sekitaran studio!” Fahmi yang kesal memukul sofa kuat dengan kedua tangannya.
Aku melotot menoleh kepada Fahmi. Bingung dan berang datang bersamaan. Fahmi tampak terkejut melihat reaksiku, seolah apa yang dia katakan telah melewati batas kewajaran. Lalu dia mulai gelagapan dan mencari pengalihan. “Lu sih! Hape pake silent, udah gitu dalam tas segala! Napa gak lu simpen di kulkas aja sekalian! Kalau gak, kan, bisa lu nyusulin pas gua kirim alamat!” Fahmi melirikku dengan wajah kaku. Memang benar, aku memeriksa pesan yang dimaksud Fahmi justru beberapa menit sebelum Fahmi datang. Pesan yang telah dia kirimkan dua jam lalu itu berisi alamat dan satu foto. Foto Ares dalam kerumunan, sedang bekerja sebagai fotografer entah untuk pewarta apa di sebuah panggung kampanye salah satu pasangan calon presiden.
Aku menanggapi semua perkataan Fahmi dengan dingin. Apa yang membuat Fahmi kesal? Baca pun pesan itu, aku tidak bisa langsung terbang menemui Ares. Enggan tepatnya. Masih mempertahankan ego dalam diri bahwa aku merasa dia lah yang seharusnya menemui.
Gam?
Tiba-tiba suara membujuk Aruna terdengar dan kini bayangan wajahnya berada hanya sekitar sepuluh senti dari wajahku. Wajah memelas yang mengatakan sudahlah.
Aku menghela nafas.
Kembali mengemas ransel, memasukkan kamera, tablet dan beberapa alat tulis dan segera ingin berangkat.
“Mau kemana lu?” tanya Fahmi.
“Ada kerjaan lain.”
“Emang ya, duit selalu nyari orang pinter. Gua udah lamar sana-sini aja masih zonk!” Kini Fahmi berkeluh-kesah dan menyadarkan punggungnya dengan kasar.
Aku nyengir, mengabaikannya dan pergi, “Eh! titip barang bentar,” ujarku sambil menunjuk produk yang tersusun di meja. Aku lari beberapa langkah dan tiba-tiba mengingat sesuatu lalu kembali lagi, “Jangan sampai kebakaran! Panas begini susah padam ntar!” tunjukku pada Fahmi yang masih duduk di sofa sambil kembali berkipas dengan kaos lembabnya.
Dia tertawa, “Sialan!”
Untuk sampai ke tempat janji temu dengan tim animator, aku memang harus melewati alamat yang dikatakan Fahmi sebagai tempat dia melihat Ares. Sempat terbesit untuk berhenti, namun urung karena jam pertemuanku sudah sangat dekat. Ada reputasi yang harus aku jaga, ada tim yang tidak boleh aku buat kecewa, lantas aku terus melanjutkan perjalanan.
Perbincangan kami dengan tim berjalan baik. Ketua tim ini, seorang art director, pria berusia nyaris kepala lima dan merupakan salah satu animator yang cukup disegani dalam dunia film, merevisi beberapa pekerjaan, termasuk hasil animasi yang aku buat. Hanya ada lima orang dalam tim ini sudah termasuk seorang storyboard artist dan lightning artist. Ketua tim mengingatkan lagi bahwa selama sepuluh hari terakhir tahun ini, setiap malam selama dua jam pemutaran video mapping di Tugu Monas, tidak satu pun dari kami yang boleh mangkir.
“Jika ada acara atau undangan Tahun Baru dari pihak lain, segera konfirmasi dari sekarang bahwa kalian tidak bisa hadir.” Tegas ketua yang hanya memiliki sorot mata penuh perintah. Dia juga jarang tersenyum. Tapi aku paham itu semua karena beban pekerjaan yang diembannya. Tidak satupun dari kami yang menganggap sorot dan wajah itu sebagai bentuk kekejaman.
Urusan pekerjaan telah selesai, ketua tim pamit undur diri sebab ada pekerjaan lain. Kami berempat menikmati makanan dan minuman yang tanpa disengaja memang tidak tersentuh sama sekali saat membicarakan video mapping. Walau makanan sudah terasa dingin dan minuman sudah mencair, kami lahap tanpa banyak membebek. Pembicaraan bergeser dari pekerjaan kepada perbincangan politik. Seorang pria, yang sepertinya sudah sangat mengenal orang-orang dalam tim ini kecuali aku, menanyakan pilihan presiden masing-masing kami. Walau banyak yang menjawabnya asal-asalan dan melemparkan candaan, tapi aku memilih diam.
“Lu, Gam?” Tanya pria itu menggagalkan rencana untuk tetap bungkam.
“Abstain.” Jawabku singkat.
Lalu yang lain tertawa.
“Sekarang golput udah jadi satu kelompok lain, ya. Capres ada dua, yang pemilih terbagi jadi tiga. Satunya golongan lu, Gam!” Sahut satu orang yang sedang mengunyah mie.
“Lu paling muda di antara kami. Baru milih besok ini, kan?” tanya pria ini lagi.
Aku menggeleng, “Udah dua kali sama ini.”
“Yang pertama? Golput juga?” desaknya.
Aku mengangkat bahu sambil menjawab, tapi satu kata itu tertelan oleh suara hiruk-pikuk tepukan tangan dan jeritan-jeritan riuh dua meja di depan kami. Acara ulang tahun remaja. Lalu kemudian mereka semua lupa telah membincangkan pilihan calon presiden karena meja kami mendapatkan kue tart dari si empu acara. Saat mereka sibuk mencicipi tart berwarna putih-biru itu, jauh dalam pikiranku, aku teringat perkataan Fahmi sore tadi yang menemukan Ares tengah bekerja dalam panggung kampanye.
Saat pulang, nyaris pukul sepuluh malam, entah merupakan satu kebiasaan tapi aku hampir selalu berhenti pada minimarket dalam sebuah perjalanan. Sekedar mampir membeli rokok, atau akan duduk dan minum kopi jika waktu cukup senggang. Begitulah, karena berhenti di minimarket itu, rentetan kejadian berikutnya mengejutkanku dan juga mengejutkan seseorang.
Aku tengah berdiri di depan showcase yang memajang puluhan botol kopi instan, mencoba menemukan merk yang biasa aku minum lantas aku merungkuk untuk melihat sampai ke barisan bawah. Saat itulah aku mendengar suara yang sangat aku kenal, tengah tertawa pada sebalik rak di belakangku yang kalau tidak salah, deretan makanan ringan.
Aku menelan ludah dan menegakkan badan perlahan lalu menoleh kebelakang.
Ya, benar. Orang yang aku kenal bersama dua laki-laki yang sepertinya seumuran dan juga tidak pernah aku lihat sebelumnya. Mereka bertiga tampak sama-sama kusut, terlebih temanku yang lagi-lagi benar seperti Fahmi ungkapkan: kurus.
“Lu bayar, ya, Beng!” ujar salah satu mereka sambil membawa beberapa produk instan seperti mie, kopi dan roti. Tak lupa mereka menunjuk-nunjuk rokok di belakang kasir untuk diambilkan.
Si teman yang aku kenal dan di panggil Beng ini menyanggupi sambil menunjukkan cengar-cengir yang khas.
Aku segera menyusul dan berada di belakang mereka, “Ini sekalian, Beng!” ujarku sambil meletakkan kopi pada meja kasir yang tengah penuh oleh belanjaan.
Tiba-tiba mereka semua menoleh ke belakang, menatapku dengan heran, kecuali si teman. Dia justru menunduk sesaat setelah menatapku.
Dalam jarak sedekat ini, meskipun dia dipanggil dengan nama berbeda dan tampil dengan gaya yang bukan seperti biasanya, aku tahu benar bahwa dia adalah temanku yang telah menghilang lebih dari sebulan. Ares. Syahreza.
(Bersambung)
Restart ©2023 HelloHayden


 hellohayden
hellohayden







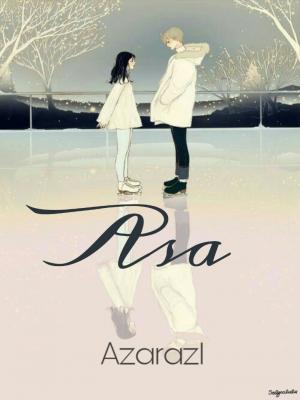





Baca cerita ini udah kayak masuk ke kedai all you can eat. Daging semua. Sbg cowok baca ini gk merasa aneh sama sekali untuk crita roman dan rasa kembali ke masa kuliah. Mantap lah
Comment on chapter Bab 14 (Cukup)