“Bisa. Bisa, Pak. Saya yang berterima kasih banyak karena sudah menerima solusi yang kami berikan.” Ujarku melalui sambungan telepon. Sesekali aku melirik Tyas yang sedang menyeruput es teh manis. Dia menatap datar tanpa emosi tapi senyumnya getir. Risau namun berusaha tidak terlalu kentara.
“Ya. Saya kirimkan alamatnya nanti, Pak.” kataku lagi.
Tyas mengeluarkan notebook kecil dari tas selempangnya, mengetuk-ngetukkan pulpen menunggu aku selesai. Telepon itu aku tutup dengan lega dan nafas terhela melepas tegang.
“Gimana, Kak?” tanya Tyas.
Aku mengangguk.
Tyas tersenyum lalu mencentang salah satu isi tabel yang berisi daftar klien.
“Udah empat, kan yang setuju begitu?” sambung Tyas masih sambil mencatat.
“Iya. Ini yang akan datang semoga mau, ya kalau engga terpaksa balikin uang,” kataku kini sedang menyeruput es kopi yang sudah mulai encer.
Ini sudah sepuluh hari sejak studio terbakar. Aku mencari cara agar tetap bertanggung jawab atas uang yang sudah aku terima dari klien, mencari sana-sini studio beberapa teman agar bisa ditumpangi sementara. Akhirnya aku bisa menggunakan studio foto kakaknya Fahmi untuk menyelesaikan materi klien yang sempat tertunda. Dari total tiga belas klien yang memberikan uang muka bahkan ada yang sudah membayar lunas, lima diantaranya menolak untuk tetap melanjutkan kerjasama. Tentu saja itu disertai dengan pengembalian dana. Tiga lagi aku tidak sanggup mengatakan akan memberikan solusi, malu, karena produk mereka ikut terbakar, dua diantaranya masih bisa diselamatkan sebagian, satu lagi dan justru yang paling membuatku kelimpungan adalah produk jam Lenkco yang terbilang mahal telah hangus menjadi puing hitam. Walaupun mereka mengungkapkan kesedihan setelah mengetahui tragedi kebakaran, tapi rasa kecewa dan kesal tidak mampu mereka tutupi meski tidak dengan emosi berlebihan. Aku harus mengganti selusin arloji model terbaru dengan kebaikan hati yang masih aku terima, diskon karyawan. Lalu lima klien lagi yang hari-hari berikutnya akan aku temui untuk membicarakan solusi.
Tyas yang sudah kembali dari liburan tujuh hari di negara tetangga langsung menghubungi dan menawarkan bantuan. Aku menerima bantuan Tyas dengan berlega hati. Aku peringatkan dia, kemungkinan paling buruknya adalah dia akan terkena caci-maki.
“Never been this ready before!” Jawabannya mengejutkan sekaligus menyenangkan.
Kami duduk pada sebuah cafe tidak jauh dari perusahaan fintech yang sudah hampir enam bulan bekerjasama dengan profesional. Sejujurnya perusahaan ini merupakan salah satu perjanjian besar yang pernah Gammares tanda tangan. Walau sudah menyiapkan beberapa alternatif yang aman bagi kedua belah pihak, aku tetap gugup menantikannya. Entah apa yang akan menjadi keputusan terakhir nanti.
Dari kejauhan, dua wajah yang aku kenal, seorang laki-laki dan seorang perempuan datang menghampiri, menyalami kami, mengucapkan ujaran basa-basi tentang keterkejutan mereka mendengar berita kebakaran, lalu duduk sambil kami tawarkan makanan dan minuman. Mereka adalah perwakilan dari perusahaan fintech. Setelah obrolan trivial sebagai pembukaan, kami berlanjut membahas masalah yang dipentingkan: penawaran alternatif atau justru ganti rugi.
Perbincangan berputar-putar karena mereka sepertinya enggan memutuskan sebelah pihak, walaupun terlihat sangat ingin, mengingat salah satu klausul dalam surat perjanjian dulu, pasal tentang pembayaran denda oleh satu pihak yang memutuskan kerjasama. Maka aku dengan sangat mengerti mulai membuka obrolan persoalan ganti rugi. Benar, saat masuk pembahasan itu, wajah mereka yang kaku berubah menjadi luwes. Pada akhirnya dengan pertimbangan cukup sengit, kerjasama ini berakhir oleh persetujuan kedua belah pihak. Sebagai penghalus kata mereka mengucapkan akan menghubungi lagi jika semuanya telah rapi dibenahi.
Senyumku mungkin terlihat kecut sebab sangat tahu perkataan mereka hanyalah courtesy. Tyas menunduk sambil berpura-pura sibuk menuliskan sesuatu.
Mereka pergi setelah beberapa berkas yang ternyata sudah mereka siapkan aku tanda tangani.
“Kak? Gak sayang tuh klien besar di cut?” tanya Tyas lemas.
Aku berdeham menelan kekecewaan, “Kita udah tawarkan solusi, alternatif yang sama-sama aman. Tapi mereka walau gak langsung bilang enggak, bahasanya udah jelas menolak.”
“Iya. Tapi kalau dibujuk dikit lagi, mungkin bisa, Kak.”
Masih dengan suara lesu, harapan Tyas terdengar tidak membantu.
“Engga, Yas. Mereka menyembunyikan apa yang sebenarnya mereka kehendaki karena takut kalau salah omong malah dapat ganjaran dan bawa bencana bagi perusahaannya. Mau gak mau kita yang harus ngalah demi keinginan mereka juga,” jawabku sambil menatap lurus menembus pintu kaca, “Yah, walau bagaimana juga, ini salah pihak kita,” aku lagi-lagi membersihkan tenggorokan, “gua dan Ares tepatnya.”
Aku menyadari sejak beberapa hari terakhir, sikap paling rumit yang harus aku kendalikan dan sayangnya secara berseberangan mengganggu mental adalah, selain harus menerima guncangan karena kemalangan, aku juga harus mampu berempati terhadap klien yang merasa dirugikan. Belum lagi aku harus kesana-kemari dan lebih sering sendiri mengurusi berbagai hal. Pikiran, tubuh dan perasaan benar-benar bergulat tidak tahu siang dan malam.
Diseberang sana terpampang baliho besar salah satu pasangan calon presiden dengan wajah senyum ramah, sumringah dan seolah menertawai.
Hah~
Aku menyeruput kopi encer lagi. Tyas sudah sibuk saling bertelepon dengan temannya membicarakan pekerjaan lain.
“Yas. Lu kalau ada kerjaan lain, gak perlu nemenin gua juga. Gak apa-apa. Masih bisa handle sendiri,” kataku setelah dia menutup telepon.
“Hmmm …, kak Ares masih belum ada kabar?” tanya Tyas ragu-ragu.
Aku diam, menelan ludah, menumbuhkan sabar sebesar-besarnya lalu menggeleng sekali dengan tegas, “Belum.”
Tyas pergi menemui temannya. Aku masih memilih duduk di sini, merokok, menghabiskan kopi yang sudah tidak ada rasa lagi. Menulis, mencoret-coret, menandai sebuah catatan yang berisi daftar panjang permasalahan. Aku dibiarkan mengelola semuanya sendiri oleh seorang teman yang sama sekali tidak aku sangka tega meninggalkan. Dia boleh saja marah sebab aku lemparkan tinju, tapi suatu perkara tetap harus ada penanggung jawabnya. Kini aku berdiri sendiri, memasang badan untuk semua keluhan, ujaran kekecewaan hingga pandangan kurang menyenangkan dari pihak-pihak yang dirugikan. Seseorang yang seharusnya paling banyak bertanggung jawab kini menghilang.
Ares.
Sudah enam hari sejak pertemuan terakhir kali –yang buruk, Ares tidak pernah menampakkan diri. Pagi besoknya, dia hanya mengirimkan bukti transfer sejumlah uang. Lalu pesan setelahnya hanya permintaan maaf. Saat itu aku tidak membalas apapun. Uang itu aku terima tanpa pikir panjang. Memang itu yang seharusnya dia lakukan. Tabunganku benar-benar terkuras untuk biaya perbaikan studio, penggantian barang klien, kompensasi dan pengembalian dana. Kini justru aku dengan sangat berat hati menggunakan uang yang ibu beri untuk keperluan sehari-hari. Aku malu. Sungguh. Meskipun ibu berkata itu adalah sisihan sisa belanja yang aku kirim rutin tiap bulan, aku tetap membuat janji pada diri sendiri bahwa suatu saat nanti akan aku kembalikan uang itu berkali-kali.
Hari ketiga Ares tidak ada kabar, aku mencoba menelepon. Setiap deringan berakhir tanpa jawaban. Kali berikutnya nomor itu tidak aktif. Pesan terkirim tanpa balasan. Aku mendatangi rumahnya, hanya ada Mbok Rah dan sayangnya Mbok Rah juga menanyakan hal yang sama, Mas Ares kemana?
Aruna juga mengatakan bahwa Ares tidak kembali ke rumah sakit untuk jadwal kontrol.
Aku mencoba menghubungi semua teman, termasuk Trisna yang ternyata masih memendam kemarahan, dia ikut-ikutan tidak mengangkat telepon.
Tidak ada yang tahu keberadaan Ares dan dia juga sengaja tidak mengangkat telepon teman lain.
Aku kembali melemparkan pandangan lurus ke baliho lebar yang memamerkan slogan menjanjikan untuk negara ini selama lima tahun ke depan. Senyum pahit tersungging. Lalu pergi untuk kembali ke studio, menemui tukang yang akan memasang plafon. Ruko itu harus kembali rapi seperti sedia kala sebelum pertengahan Desember, saat masa sewanya berakhir. Di dalam hati, aku sudah tahu bahwa saat itu juga Gammares hanya akan tinggal nama dan kenangan saja.
-oOo-
Pintu kamar terbuka pelan, Aruna yang mengira aku sedang tidur masuk mengendap-endap, “Loh? Aku pikir kamu baringan. Aku chat gak bales,” ujarnya menghampiriku yang sedang duduk di meja kerja.
“Oh? Hape aku di tas kayaknya, masih silent,” jawabku tanpa menoleh ke Aruna yang kini mendekat, “Udah siap? Yok, berangkat!” ajakku yang tadi siang mengatakan pada Aruna akan mengantarnya dinas malam.
“Gam?” nadanya terdengar membujuk dan memelas saat dia melihat aku merobek lembaran-lembaran dimana cita-cita dan impian tertuang dalam buku bersampul cokelat.
Aku menarik bibir, membuat senyuman seolah ini bukan apa-apa. Cita-cita dan impian yang kutulis dalam tiap lembaran kini terlihat sebagai angan-angan pucat, tidak berwarna, tidak juga cerah. Justru kini gelap.
Seolah tahu apa yang aku pikirkan, dia menjawab, “Tiap impian itu ada waktunya. Jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa kamu sudah gagal.”
“Ini gak serius-serius amat. Perkara sepele aja.” Jawabanku memang terdengar santai, legowo, tegar atau apapun yang membuatku sepertinya menerima kepahitan dengan lapang dada. Sebenarnya dalam hati perasaanku berkecamuk, mencak-mencak dan memberontak. Aku segera mengemas kertas-kertas yang sudah lepas itu menjadi satu tumpuk dengan buku. “Yok! Ada perawat yang gak boleh datang telat!” Ujarku mengalihkan obrolan. Aruna berjalan duluan, aku menyusulnya sambil membawa tumpukan itu dan membuangnya saat melewati tong sampah di balik pintu.
Setelah mengantar Aruna, aku berhenti pada swalayan di sekitar rumah sakit. Membuat sendiri kopi cuang. Duduk sambil merokok. Dari arah belakang aku mendengar obrolan dua laki-laki yang sepertinya masih usia SMA sedang menceritakan kejadian lucu di sekolah. Lalu mereka tertawa, begitupun aku. Aku tidak mencuri dengar, mereka lah yang membiarkan obrolan itu terdengar.
“Giliran lu yang bayar, Nyet! Gua mulu dah perasaan!”
Seru salah satu dari mereka, aku menoleh ke belakang. Mereka tampak akrab walau sedang meributkan siapa yang akan membayar.
Nyet?
Tiba-tiba aku teringat Ares. Dulu kami juga menertawai hal lucu bersama. Walau bagaimana juga, dia teman yang selalu ada. Aku berusaha meletakkan dulu masalah studio ke pinggir dan menarik ke tengah permasalahan kami berdua. Dia orang yang sembarangan, ceroboh, impulsif dan memang cenderung tidak sabaran. Tapi setelah aku ingat-ingat, tidak bertanggung jawab bukan lah sikap yang mengisi deretan perangai buruknya. Meskipun terlambat dan setelahnya harus berkejar-kejaran dia akan tetap melakukan apa yang menjadi tugasnya. Kendati dalam keadaan berduka, dia tetap meminta pekerjaan. Dia tidak tega meninggalkan aku sendirian walau saat itu ada Tyas dan seorang pekerja lepas. Rasanya tidak mungkin saat ini, justru dia tahu kami berdua sedang menanggung beban berat, lalu dia memutuskan pergi begitu saja. Tapi, entahlah. Apa mungkin aku yang belum terlalu mengenalnya. Atau memang benar kebanyakan orang kata, bahwa suatu perkara bisa menjadi alasan seseorang berubah.
Aku kembali memeriksa pesan dari Ares, masih sama, belum dibaca, atau mungkin tidak dibaca sepertinya.
Saat itu juga, sebuah pesan masuk. Cak Son, orang yang selalu pasif dalam memanfaatkan modernisasi komunikasi, kini mengirimkan pesan dengan mengatakan:
‘Sini. Gua ada bir selusin’
Belum sempat aku membalasnya, masuk satu pesan lagi:
‘Bagi gua rokok’
Aku membalas:
‘GAS’
Rumah Cak Son berada dalam satu gang kecil padat pemukiman. Rumah-rumah di sana umumnya tidak memiliki pagar. Tetangga-tetangga yang hilir mudik bisa dengan leluasa melongok ke dalam rumah jika pintu terbuka, itulah alasan Cak Son selalu menutup jendela dan pintunya.
Saat aku sampai, tetangga depan rumahnya yang sedang main catur menyapa ramah. Aku turun dari motor, menggiringnya dan tersenyum sambil mengangguk untuk membalas sapaan mereka.
Rumah Cak Son yang dulunya lebih temaram, kini pada teras telah dipasang lampu terang. Sudah ada sepasang kursi plastik lengkap dengan meja kecil tersusun rapi di depan jendela.
Seorang perempuan keluar saat aku hendak mengetuk pintu, diiringi oleh Cak Son dibelakangnya.
“Cewek gua,” katanya setelah mengantar perempuan itu beberapa langkah menjauhi pintu. Kami masuk. Sebagaimana di luar, di dalam rumah pun terang. Sudah lebih rapi, tidak pengap lagi. Salib berlampu kuning itu telah diganti dengan salib lebih besar dan dengan ukiran Yesus lebih bagus, walau wajahnya tetap menunduk menerima dirinya disalib paksa.
Sudah hampir empat bulan tidak bertemu, kini Cak Son jauh lebih bersemangat. Wajahnya cerah dan rautnya ceria. Rambutnya sudah sangat panjang sehingga bisa digulung semua ke atas. Lalu perubahan paling mencolok adalah, tubuhnya gempal dengan perut buncit. Tulang pipi yang dulu menonjol berganti dengan pipi yang penuh bulat Penampilannya kini sudah seperti bapak-bapak.
“Noh! Bir di kulkas.” Ujarnya sambil berlalu ke ruang kerja yang justru terlihat sama saja, berantakan. Aku membawa lima bir, meletakkannya di meja tempat biasa kami membahas pekerjaan. Di meja itu sudah tersedia kentang goreng.
“Sundari tadi yang bawain,” ujarnya lagi. Aku bahkan tidak menanyakan apa-apa, tidak juga dengan raut meminta penjelasan. Juga aku bukan orang yang ingin tahu segala sesuatu tentang orang baru.
“Banyak berubah, nih!” Aku berceletuk sambil mata mengarah ke ruang tamu.
“Iya, nih! Sundari yang beresin semua,” tukas Cak Son segera.
Aku manggut-manggut saja sambil memperhatikan sekitar.
“Lagi sibuk, Cak?” tanyaku lagi yang melihat Cak Son sedang menghaluskan tepi potongan akrilik. Entah kriya apa yang akan dibuatnya tapi meja kerjanya penuh dengan perkakas.
“Pesenan Sundari.” jawabnya lagi dengan senyuman yang aneh.
Aku mulai paham. Bapak-bapak ini dengan menyebut nama Sundari berkali-kali, sedang memamerkan pencapaian baru: dapat pacar.
“Yaudah iya! Cocok! Cakep! Mantep!” ujarku berseru sambil mengacungkan kedua jempol, namun rautku justru sebaliknya, datar. Cak Son terbahak. Dia meninggalkan bubuk akrilik dan menyusul duduk, membuka satu botol bir untukku dan satu untuknya.
Kami menikmati bir dengan kudapan kentang goreng.
“Lu gak usah panjang lebar cerita, gua udah tahu semuanya.” Tiba-tiba saja Cak Son mengatakan itu walau sedang mengunyah cemilannya.
Aku cukup terkejut lalu memandangnya. Aku datang justru karena undangan darinya bukan serta merta untuk berkeluh kesah atas masalah yang aku hadapi. Tidak terlalu peduli bagaimana atau dari siapa berita kebakaran sampai ke telinganya, aku justru khawatir apakah berita itu sampai sesuai kebenarannya.
“Udah lu gebukin tuh si Portugis?” tanya Cak Son kemudian.
Aku mengangkat bahu dengan santai. Lalu pertanyaan itu menjawab kebimbangan mengenai kebenaran cerita.
“Abis dong tuh anak?” tanya Cak Son lagi.
“Enggak. Tangan gua yang sakit, Cak.”
“I-iye, sih. Rangka dia gede.” Cak Son menyetujui, dia mengangguk ragu, “berapa hari udah ini?”
“Ada kali semingguan gak ada kabar.”
“Orang tuanya gak nyariin apa? Dimana-mana orang ilang satu kali dua puluh empat jam udah pada heboh emak bapaknya ke polisi.”
“Itu kalau orang, Cak. Dia kan enggak.”
Cak Son kembali tertawa sambil mengatakan sialan. Tawa Cak Son menggelegar, tawaku justru tertahan.
Lalu Cak Son dengan tulus menawarkan beberapa kameranya untuk aku pakai sementara dan mempersilahkanku menggunakan kamar kecil dibelakang rumahnya yang sekarang hanya tempat kanvas yang tidak terpakai serta barang-barang lain yang usang.
“Gudang lah ceritanya.” Ujar Cak Son setelahnya.
“Aman, Cak. Kalau perlengkapan masih ada di kost satu dua. Ntar kalau studio bisa nebeng sama temen.”
Kami bercerita banyak hal. Sekalipun aku tidak bermaksud mencurahkan segala kecemasan pada Cak Son, pada akhirnya kalimat-kalimat itu keluar juga walau sekedarnya. Cak Son, mendengarkan tanpa menyilang kata. Dia benar-benar tahu yang aku butuhkan saat ini hanya seseorang dengan telinga yang sedia dan setia, tidak butuh mulut yang berucap belasungkawa atau kata-kata mutiara.
Setelahnya, aku membantu Cak Son bekerja, mencairkan bubuk akrilik, membuatnya kental dan menyalin ke wadah untuk dicetak. Sambil bekerja, dia yang biasanya tidak menceritakan hal pribadi, kini mulai berkisah tentang pertemuannya dengan Sundari. Walau aku dapat merasakan keengganan Cak Son, tapi sepertinya dia tidak punya cara lain bagaimana menghiburku walau hanya sesaat. Aku menghargai usahanya, mendengarkan Cak Son dengan atentif dan antusias.
“Namanya Puspita Sundari, dia lagi sibuk menata gerai buah yang baru buka di perempatan depan pas gua mampir di kedai kelontong sebelahnya, beli rokok. Gak taunya satu jeruk jatuh dan gelinding ke gua. Gua ambil gua makan.”
“Hah? Terus?”
“Yaa ditagih, lah!”
“Berapaan emang sebijik?”
“Tiga ribu katanya.”
“Bayar?”
“Waktu itu gua gak ada sisaan beli rokok. Gua bilang ntar balik lagi.”
“Terus balik?”
“Kagak. Lupa gua asli.”
“Terus?”
“Yaaa, gua ingatnya lagi udah beberapa hari, pas tetangga depan berantem suami istri, gara-gara suaminya sering nongkrong di kedai kelontong sejak Sundari buka gerai buah. Sayup-sayup gua denger kalau Sundari itu ex-con.” Jelas Cak Son.
Aku sedikit terkejut, “Oh, ya? Kasus apa, Cak?”
“Dia mukul kepala suaminya pakai teflon berkali-kali sampai lebam. Ya, itu juga setelah dia bertahun-tahun ngalamin kekerasan. Suaminya main tangan. Mantan, sih sekarang.”
“Aduh …,” Ujarku sambil memejamkan mata, ngeri. “Jadi malam itu langsung bayar?”
“Iya. Duit gua gede. Kagak ada kembalian. Gua bilang ambil aja. Eh, besokannya dia dateng bawa sekeranjang buah. Katanya sisaan duit gua,” ujar Cak Son.
“Oh! Pantesan.” Aku menukas segera.
“Apaan?”
“Lebih seger, lebih sehat. Nyemilin buah ternyata,” aku berkomentar.
“Dan buah-buah lainnya juga, dong, pastinya,” Ujar Cak Son sambil tersenyum usil dan tawa yang membuat perut buncitnya bergetar.
Ah! Bisa aja nih orang tua!
Aku mulai paham situasi mereka.
Bir hanya habis sekitar tiga botol, pekerjaan Cak Son juga hampir selesai saat gorden motif gingham yang terpasang alakadar ini berwarna kekuningan sebab cahaya matahari mulai menyebar. Aruna mengirimi pesan mengatakan dia sudah selesai dinas dan akan pulang dengan ojek. Aku membalas mengatakan akan menjemputnya.
“Gam, penghianatan dari seorang teman memang lebih menyakitkan daripada segerombolan musuh menyerang,” ujar Cak Son saat mengantarku ke pintu depan.
Aku tidak menjawab sebab sedang menghisap rokok, tidak ingin sebenarnya.
“Gua gak suruh lu maafin dia. Lu cari lu gebukin lagi. Abis itu selesaikan. Mau gimana juga dia harus pasang badan, ini kesalahannya. Setelahnya mau berakhir kayak apa itu urusan kalian.” Cak Son memandangiku, “tapi gua yakin, si Portugis itu walau bajingan, dia gak bermaksud buat melakukan penghianatan. Lagi pula dia cukup bodoh untuk disebut sebagai musuh.”
Pada kalimat terakhir Cak Son menghembuskan asap putih menerawang jauh melongok ke langit bak cenayang ulung. Aku menatapnya dengan rikuh. Dia tersenyum dan merangkul sambil mengantar ke teras.
“Gam. Que sera, sera …,” kata Cak Son lagi saat aku mulai menyalakan motor.
Aku mengangguk, “Ya, Cak. Gracias!”
Aku dan Aruna sedang sarapan dengan sisa roti bakar tadi malam. Aruna membuat susu hangat untuknya dan teh hangat untukku. Sambil makan aku bercerita bahwa semalaman tidak tidur karena tengah bersama Cak Son di rumahnya.
“Pake minum, kan?” tanya Aruna melirikku dari dapurnya, dia tengah mendidihkan air dengan panci kecil. “Iya …,” aku terkekeh. Aruna menggeleng, namun tidak dengan kesal. Dia hanya menggeleng seolah berhadapan dengan anak kecil yang membuat kesalahan, menerima dengan segala tingkah lucunya. “Pas gak begitu fit gini, jangan terlalu banyak minum alkohol,” ujarnya lagi kini tengah sibuk mengupas sesuatu.
Saat mencuci gelas, ponselku berdering. Aruna yang tengah membersihkan lantai dengan segera membawa ponsel padaku, “Mami,” katanya. Aku segera mematikan keran dan dengan sembarangan menyeka tangan pada kaos. Menjawab telepon itu dengan perasaan gusar.
Aku dan mami berbicara, wajahku yang tegang membuat Aruna terus memperhatikan dengan lamat. Alisnya bertaut kuat menunjukkan kekhawatiran dan tentu, penasaran.
Telepon itu berakhir dengan singkat, hanya sekitar dua menit.
“Apa kata mami? Ares dimana?” tanya Aruna mengikutiku yang berjalan menuju kasur, duduk sambil memijat dahi.
“Mami ajak ketemu. Ada yang mau dia ceritakan dan ada yang mau dikasih juga. Ares belum ada kabar.” Aku bisa mendengar suaraku mulai parau.
“Kapan?” tanya Aruna lagi ikut duduk di sampingku.
Aku melihat jam dinding di atas jendela, “Satu jam lagi, jam sepuluh ini.” “Kamu belum tidur, Gam. Kamu juga butuh istirahat.”
“Iya. Aku tahu. Tapi ini juga gak bisa ditunda, Runa.”
“Jangan mandi. Kamu belum tidur semalaman.” Aruna menegaskan.
“Iya.”
Aku kembali ke kamar, membersihkan diri, menyikat gigi, mencuci wajah. Untuk sesaat aku tertegun melihat pantulan diriku pada cermin. Bulu-bulu halus tumbuh tidak merata membingkai tepi wajah. Lingkaran hitam pada bawah mata sangat kontras dengan wajahku yang tampak pucat. Mata merah dengan kelopak mata yang turun benar-benar menunjukkan aku kurang tidur. Aku menghela nafas mengeluarkan segala kegundahan. Melanjutkan lagi mencukur habis bulu-bulu wajah berharap akan terlihat lebih segar.
Dari luar kamar mandi, terdengar Aruna mengatakan dia menaruh minuman hangat. Lalu terdengar kertas-kertas yang sepertinya dirapikan. Dia berbenah di kamarku yang akhir-akhir ini berantakan. Tak lama terdengar pintu ditutup.
Saat aku keluar kamar mandi, meja yang banyak tumpukan kertas memang sudah rapi, tong sampah sudah kosong. Semua sampah termasuk buku cokelat itu sudah dibuang Aruna. Entah kenapa, walau aku yang memutuskan untuk membuangnya, kini cukup sedih melihat buku itu sudah tidak ada lagi. Aku menghela nafas, duduk berdiam menatap keluar jendela, sambil menyesap rebusan ramuan jahe dan madu dari Aruna yang masih hangat suam.
Ini tadi yang membuat dia sibuk di dapur. Pikirku.
Wanginya menenangkan, begitu juga saat air itu turun menyusuri rongga dada hingga perut, memberikan sensasi hangat. Sangat nyaman sehingga setumpuk kecemasan rasanya luruh sesaat.
-oOo-
Aku dan mami bertemu di sebuah cafe yang materi promosinya Gammares kerjakan, cafe dengan pemilik cenderung gagap teknologi yang tidak mengerti menyimpan data dengan cara online.
Pegawainya masih mengingatku, dia memberikan krim whip ekstra pada avocado coffee yang aku pesan. “Semangat, Kak. Semoga studionya cepat buka lagi.” Ujarnya saat menaruh minuman. Mendengar itu, aku menyimpulkan bahwa Gammares cukup tegak sehingga tampak. Kini nama yang berusaha tegak tinggi itu sedang rebah. Bukan, bukan rebah lagi. Tumbang.
Mami datang, tepat pukul sepuluh. Duduk di depanku dengan tergopoh-gopoh. Ekspresinya datar, tidak ada emosi. “Gam, apa kabar?” Ujarnya ragu, bibirnya yang diberi sentuhan lipstik merah tampak terhenti sejenak. Mami memang tidak pandai bermain kata. Basa-basinya justru terdengar sangat basi. Aku hanya bisa mengangguk sambil tersenyum tipis. “Ya, gitu lah, Mi.”
Mami menyandarkan punggungnya, menghela nafas, lalu bertanya, “Ares dimana, Gam? Kamu pasti tahu, kan?” Gabungan pasti dan kan itu sungguh mengekang kebebasan. Seolah aku tidak punya perkara yang lebih penting selain mengurusi, membela, dan menyembunyikan anak manja dari amukan orang tuanya. Tidak ada kata-kata yang mampu mewakili keterkejutanku menghadapi pertanyaan mami yang mendakwa. Emosi yang telah aku tekan mati-matian beberapa hari terakhir kini terasa menyengat kembali. Tahu-tahu aku berdiri, berteriak pada mami menanyakan hal yang sama sambil menggebrak meja dengan kuat hingga menjatuhkan gelas. Semua orang melihat dengan cemas. Lalu terdengar suara anak kecil menangis. Aku tersadar, melihat kiri-kanan, semua itu –rentetan peristiwa mulai dari aku berdiri hingga semua tatapan cemas orang lain, hanyalah sebuah ilusi. Tindakan yang sangat ingin aku lakukan tapi justru aku tahan. Aku melirik ke arah anak kecil yang menangis di dalam gendongan ibu yang juga tampak gelisah. Ibu itu memandangku dengan raut bersalah sambil bibirnya mengatakan maaf. Aku membalas dengan anggukan dan senyuman. Lalu kembali menatap mami, “Aku pikir mami tahu makanya ajak ketemu,” jawabku dengan suara yang sudah berat.
Kami terpaku dalam bisu. Aku memang menunggu mami mengatakan sesuatu. Sejak awal dia lah yang ingin bertemu.
“Gam? Mami mewakili Ares ingin minta maaf atas segala yang dia tinggalkan gitu aja. Mami paham sepuluh hari belakangan gak gampang. Terlebih sejak kamu tahu Ares penyebab kebakaran,” ujar mami tanpa benar-benar menatapku, entah dia mengucapkan dengan tulus atau tidak, aku tidak tahu. Lagipula aku tidak butuh perwakilan Ares untuk meminta maaf, aku butuh dia yang datang, menunjukkan wajahnya dan siap bertanggung jawab.
“Malam itu, kami semua baru kembali dari Magelang. Ares berantem hebat sama papinya. Karena dua lukisan sudah dikirim ke Malaysia, dijual.” Mami menelan ludah dan segera mengambil tisu yang tersedia di meja, melipatnya dan menempelkan tepat pada bawah mata.
Aku masih bertahan agar tetap diam walau tercengang.
Lukisan itu jadi dijual?
Astaga!
“Ares yang kesal dan marah, menuntut papi atas segalanya. Mereka ribut cukup lama sampai akhirnya papi ngusir Ares.” Mami mulai mendesir.
Cerita bergulir dari satu gumpalan kesedihan kepada gumpalan kesedihan lain. Sisi kemanusiaan pada diriku nyaris saja terpedaya oleh cerita melodrama keluarga mereka jika saja aku tidak mengingat apa yang telah Ares lakukan padaku, pada Gammares. Sejujurnya, aku memang merasa kasihan tapi malas berkomentar.
“Malam itu, sebelum pergi, Ares bilang ke mami kalau dia mungkin akan tidur di studio sampai nemu kost. Besoknya mami di telepon rumah sakit, Ares di rawat. Studio kebakaran,” Mami melemparkan wajahnya melihat jalanan sambil menyeka air mata dengan cepat, “terus pas mau pulang, Ares bilang mami gak perlu jemput. Dia pulang sama teman. Tapi ternyata gak ke rumah. Malamnya mami telepon, dia bilang dia penyebab kebakaran, beberapa hari harus bolak-balik kantor polisi buat keterangan sama proses mediasi. Setelah itu handphone-nya mati, Gam. Mami gak tau mesti cari kemana.” Walaupun menangis, mami tetap menahan dirinya agar tidak terbawa perasaan. Air mata itu tidak pernah melewati pipi karena sudah dinanti tisu. Mami menangis tapi tampak seperti tidak. Mami ingin aku tahu bahwa dia sedang bersedih tapi saat bersamaan juga menunjukkan keangkuhan. Mami benar-benar tidak ingin melihatkan kelemahan padaku
Sepanjang cerita –yang kebanyakan hanyalah cerita sedih tentang Ares, aku hanya bisa diam. Aku mengingat-ingat kembali rekaman CCTV, menyamakannya dengan waktu yang mami katakan. Jika malam itu mereka baru kembali dari Magelang, lalu pertengkaran Ares dan papinya membuat dia mengalihkan masalah itu kepada minuman, maka terjawablah sudah alasan dia pulang dalam keadaan teler dan menyebabkan kebakaran. Cerita ini, yang mungkin mami harapkan membuatku bersedih dan memaafkan kesalahan anaknya, malah menambah deretan kekecewaan. Walau sudah tahu alasan dia mabuk, aku tetap tidak bisa menerima masalah pribadi yang dia campurkan dengan profesionalitas. Masalah di rumah dibawa ke studio. Saat ini aku mengalami apa yang banyak studi psikologi temui bahwa manusia memang makhluk egois. Kita lihai merasionalisasi sudut pandang sendiri hanya untuk terlihat benar, daripada menjadi benar. Bias konfirmasi, itu yang sekarang aku dan mami lakukan. Mami mengangkat cerita kesedihan dan aku menentangnya dengan kemalangan yang aku rasakan.
Kemudian mami mengeluarkan amplop cokelat dari tas tangannya, “Gam, anggap ini dari Ares. Mami tahu pasti banyak dana yang harus kamu keluarkan untuk membenahi semua. Semoga ini membantu.” Ujar mami sambil menangkupkan amplop itu pada kedua telapak tanganku.
“Mami harus balik ke kantor,” ujarnya lagi sambil mengusap-usap bawah matanya, memastikan riasannya tidak rusak, “kamu kalau masih berkenan, cobalah cari Ares, ya? Mami tunggu kabar dari kamu.”
Permintaan itu justru terdengar seperti sebuah perintah. Memperlihatkan padaku garis hierarki bahwa mami tetaplah seseorang yang berada di atas dan sedang memberi perintah ini-itu kepadaku yang dia anggap bawahan. Seperti sebuah kepatuhan tanpa kompromi yang harus segera aku turuti.
Mami tidak menunjukkan empati sama sekali terhadap kemalangan yang aku rasakan akhir-akhir ini, sepertinya tidak juga merasa bersalah melihat aku harus menghadapi semua ini sendirian, atau paling dangkalnya dia bahkan tidak menunjukkan rasa iba. Seolah-olah tanggung jawab anaknya menguap begitu saja setelah amplop itu berpindah tangan. Benar. Ibu dan anak ini walau nyaris selalu berlawanan, kali ini mereka menyelesaikan sesuatu dengan cara yang sama: memberi uang lalu pergi begitu saja. Aku merasa harga diriku terkikis sebab mau tidak mau harus menerima uang itu walau keinginan terkuat justru mendorong kembali ke arah mami sambil mengatakan Ares masih punya urusan denganku.
Hal pertama yang aku lakukan sesampainya di kost adalah mendinginkan dada yang mendidih dengan minum sekaleng soda. Lalu merogoh-rogoh ransel menemukan amplop cokelat itu, meletakkannya dengan kasar pada meja. Aku duduk memandangi amplop yang ternyata tidak tebal untuk berisi uang yang cukup sebagai kompensasi, juga tidak tipis hanya untuk berisi selembar dua lembar cek. Aku membukanya lalu terkejut setelah melihat isinya. Lima puluh lima lembar dolar Singapura dengan pecahan seratus. Berkali-kali aku hitung uang itu, benar lima puluh lima lembar. Segera aku menghitungnya dalam rupiah, jika ditambahkan dengan uang yang Ares transfer dulu, jumlahnya akan cukup untuk mengganti alat auto refraksi optik, yang merupakan penggantian terbesar dari dampak kebakaran.
“Gimana, Gam?” tanya Aruna yang baru saja masuk.
Aku mengangkat amplop itu untuk memperlihatkan pada Aruna, “Uang untuk ganti alat optik.”
Aruna mendekat, “Dari mami, ya?”
Aku mengangguk, “Mau aku tukerin sekarang,” kataku sambil memberikan amplop itu. Aruna dengan ragu menerima lalu dengan takut-takut mengintip isinya. Dia mengeluarkan selembar dengan raut heran.
“Singapura?” tanyanya lagi ingin memastikan setelah meneliti lembaran itu.
Aku mengangguk yakin.
Tiba-tiba Aruna memeluk, “Syukurlah, Gam. Syukurlah. Kamu gak perlu jual motor.” Ucap Aruna dengan lirih. Memang, dua hari lalu, setelah menghitung-hitung, aku memutuskan untuk menjual motor dan dua kamera untuk mengganti alat optik. Itu juga sebenarnya masih belum cukup. Aku yang sempat putus asa kini merasa lega.
“Besok pagi aja nukerinnya. Kamu belum tidur. Badan kamu mulai dingin.” Kata Aruna sambil melepas pelukan dan mengusap-usap kedua pangkal lenganku.
Aku menuruti karena juga menyadari tubuhku lembab dan berkeringat dingin.
Aku mencoba tidur setelah kami makan bersama. Aruna sedang menutup gorden dan menyalakan AC saat aku mengirimkan pesan untuk mengabarkan pemilik optik bahwa uang penggantian sudah bisa aku serahkan besok.
“Tidurlah …,” kata Aruna, “jangan cek handphone terus.”
“Kamu dinas jam berapa?”
“Malam.”
“Bangunkan aku.”
Aruna mengangguk, “Aku bakalan di sini, sambil lanjut ini.” Aruna mengangkat sebuah novel yang kini di pegangnya, A Man Search for Meaning. Aku tersenyum lalu entah bagaimana, aku langsung jatuh dalam tidur.
-oOo-
Kepalaku berisik. Selalu seperti ini setiap mulai memejamkan mata. Api berkobar merah menyala kembali memenuhi penglihatan, lengkap dengan suara decitan barang-barang yang terbakar dan hiruk pikuk serta sirine mobil pemadam lalu semua itu saling tumpang tindih dengan ujaran kekecewaan pelanggan dan juga tatapan tidak menyenangkan dari setiap orang yang merasa dirugikan. Siluet ibu dalam temaram, duduk bersimpuh menengadahkan tangan sambil menangis mengharapkan Tuhan memberi kemudahan untuk anaknya. Rekaman CCTV memperlihatkan Ares masuk terhuyung serta api yang berkobar. Ujaran Trisna yang menyudutkan serta pada wajah Ares yang aku tinju. Lalu semuanya berjalan seperti video yang diputar mundur dengan cepat kepada situasi di Magelang saat aku mendengar paman dan bibi Ares berbincang mengenai lukisan yang dijual. Suara-suara semua kejadian itu menyatu membentuk gaungan berdengung membuat telinga sakit.
Mataku terbuka tiba-tiba. Aku bangun dalam keadaan mengejutkan. Sesak dan berkeringat. Ingatan tidak menyenangkan itu menggerayangi hingga masuk dalam mimpi. Benar-benar mengganggu, meresahkan dan membuat cemas. Aku melihat sekitar, kamarku gelap, Aruna tidak terlihat.
“Runa?” panggilku pelan.
Tidak ada jawaban.
Setelah sedikit tenang, aku mencuci wajah, minum lalu membuka jendela, merokok sambil memeriksa ponsel. Jam sudah menunjukkan pukul lima saat aku membuka kunci layar lalu mendapatkan e-mail bahwa rekening atas nama Santrisna –nama panjang Trisna, mengirimkan uang sebesar tujuh juta rupiah dengan berita bahwa itu uang dari Ares.
Ares? Trisna?
Mereka sedang bersama?
Aku segera menelpon Trisna, berkali-kali, tidak diangkat dan terakhir dering telepon itu dialihkan. Aku mencoba menelepon Ares, sama, panggilan tidak terhubung. Aku kesal sendiri dan geram hingga gigiku terdengar bergemetukan. Aku ingin mengasihani Ares, sungguh. Cerita mami tentang dia cukup membuat perasaanku gentar sebentar. Namun jika mengingat semua rentetan kejadian setelah kebakaran yang benar-benar menyakitkan dan menyesakkan, aku justru lebih mengasihani diri sendiri.
“Eh? Udah bangun?” Suara lembut Aruna yang baru saja masuk membuyarkan lamunan, “gimana tidurnya? Enakan?”
Aku menoleh dan tersenyum, “Yah, gitu-gitu aja. Kamu abis dari mana?”
“Tadi nemenin Bu Dewi ke minimarket depan. Nih, aku bawain buah potong. Ada semangka ada melon juga.” ujarnya sambil berlalu ke pantry, menyusun belanjaannya dalam kulkas mini.
Aku duduk pada meja kerja, menyalakan komputer, mengangsur pekerjaan.
Aruna memijat bahuku, “Gak istirahat dulu?”
“Gak ada waktu.” Jawabku.
“Jaga–”
“Kesehatan.” Aku menukas segera yang membuat kami mengatakan kata itu bersamaan. Dia tertawa seraya memukul pundakku.
“Pijat lagi, dong.” pintaku.
Dia menuruti, justru kali ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh hingga membalurkan minyak kayu putih disekitar tengkuk dan pundak. Selama dia memijat, aku menceritakan apa yang aku dengar tentang lukisan nenek namun aku memilih bungkam dari Ares dengan alasan masalah internal.
“Itu bukan salah kamu. Keluarganya bakalan tetap jual itu walau Ares udah tahu.” Ucap Aruna. Dia menyandarkan dagunya pada puncak kepalaku. “Kamu gak perlu menyesalkan hal itu,” bisik Aruna menghiburku.
Aku mengangguk menyetujui ucapan Aruna.
“Kamu tahu kamu gak punya banyak waktu. Pekerjaan berdua harus kamu selesaikan sendirian. Untuk tidur aja kamu harus curi waktu. Kamu udah berapa hari ini? Semingguan? Bukan. Lebih malah udah habis-habisan bergulat, Gam. Gimana bisa kamu juga harus mengelola hal intangible begitu sedangkan jelas-jelas ada masalah nyata yang harus kamu selesaikan?” ujar Aruna lagi kini melingkarkan kedua lengannya pada leherku, mencium kepalaku, “aku cuma gak mau kamu lebih drop daripada sekarang.”
Aruna tertelan oleh risau yang membuat suaranya parau. Aku mendongak memastikan tidak ada air yang menggenangi pelupuk matanya. Tapi sayangnya air itu sudah merembes melewati pipinya. Aku menatapnya iba, menggeleng penuh penyesalan, mengusap-usap lengannya yang masih melingkari leherku, memelas padanya agar tidak menangis, “Sshh … sshh…,”
Ini semua bebanku. Aku tidak bermaksud membagi beban ini padanya. Dia, air mata itu terlalu berharga untuk meratapi perkara yang bukan sama sekali ulahnya.
Menyadari aku memohon padanya, Aruna segera menyeka kedua pipinya dan menarik kedua ujung bibir membuat senyuman mungil, “Dah.. Sekarang kamu lanjutin itu,” ujarnya sambil menunjuk layar komputer.
“Ya. Siap-siaplah. Sebentar lagi kita berangkat. Ada perawat yang–”
“Gak boleh terlambat!” sahutnya segera sambil berjalan keluar. Dia mengerlingkan sebelah mata saat mengucapkan itu. Aku terkekeh.
Aku kembali memikirkan perkataan Aruna yang memang sudah tepat. Harus bekerja keras dan di saat bersamaan juga harus tetap waras. Kebakaran, kerugian, klien dan pembenahan sudah benar-benar menyita waktu dan menguras tenaga. Aku tidak diberi waktu untuk berlama-lama sentimental. Deretan pekerjaan berbaris panjang di depan mata, mengantre untuk diselesaikan.
Tiba-tiba aku teringat Ares dan bergumam. Kembalilah selayaknya laki-laki, Nyet!
(Bersambung)
Restart ©2023 HelloHayden


 hellohayden
hellohayden






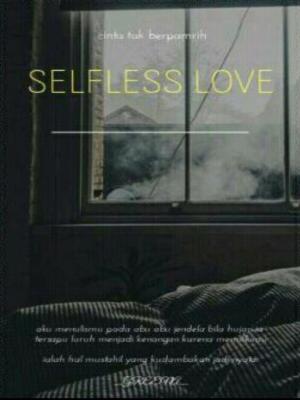






Baca cerita ini udah kayak masuk ke kedai all you can eat. Daging semua. Sbg cowok baca ini gk merasa aneh sama sekali untuk crita roman dan rasa kembali ke masa kuliah. Mantap lah
Comment on chapter Bab 14 (Cukup)