Sudah sekitar sepuluh hari bapak meninggal, dan hingga hari ini ibu tidak pernah sekalipun mengeluhkan masalah keuangan. Setiap kali kami berbicara melalui telepon atau bahkan video call, ibu dan Marwa terlihat semakin tampak baik. Tidak lagi aku melihat mata yang sembab, juga tidak mendengar suara-suara yang parau. Tiap aku bertanya mengenai kebutuhan di rumah misal; apakah listrik, air, dan internet sudah dibayarkan atau apakah kulkas selalu terisi bahan makanan dan cemilan, serta hal-hal serupa lain yang merupakan kebutuhan dasar, ibu selalu memberikan jawaban yang menenangkan dengan mengatakan semuanya baik-baik saja dan aku tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku mulai menyadari bahwa sebenarnya aku tidak memiliki pemahaman apa-apa tentang pengeluaran di rumah, karena selama ini ibu dapat mengaturnya dengan baik,
Aku pernah mengirimkan ibu uang –uang tabunganku, lalu ibu mengirimkan kembali uang itu padaku, kemudian menelepon. Ibu mulai bercerita mengenai asuransi jiwa yang telah didaftarkan perusahaan bapak sejak hari pertama bapak bergabung dengan kantor itu. Uang jaminannya telah diurus dan diserahkan kepada ahli waris, yaitu ibu. Ibu memaparkan alokasi-alokasi dana yang sudah menjadi program dari asuransi tersebut dan dengan jelas menyebutkan angka-angka yang tertulis. Selain itu perusahaan bapak yang memang BUMN telah membayarkan Uang Penghargaan Masa Kerja – pesangon istilah umumnya. Menurut ibu, itu semua sudah cukup untuk menopang kebutuhan harian dan kebutuhan kuliah Marwa, bahkan bisa sebagai tabungan hari tua.
Mendengar itu hatiku lapang. Pikiran-pikiran yang datang menyerbu dan menyesakkan yang akhir-akhir ini menghantam, mulai mundur perlahan. Aku meyakinkan ibu bahwa di sini aku mampu mengurus diriku sendiri; mencukupi kebutuhan harian dan kuliah dari hasil komisi. Kukatakan pada ibu sebisa mungkin akan membantu dengan mengirimkan uang bulanan untuk kebutuhan di rumah.
Di akhir pembicaraan, suara Ibu terdengar menahan tangis. Ibu menyampaikan terima kasih dan juga menegaskan agar aku tidak sungkan untuk segera memberitahu jika di sini mengalami kesulitan.
“Ibu doain aja, ya. Semoga dalam waktu dekat aku dapat kerjaan baru.”
“Nak, urusan mendoakan itu memang udah jadi tugas Ibu. Yang jadi tugas kamu sekarang itu kuliah. Kamu gak perlu khawatir berlebihan. Kami di sini baik-baik, aja.” Sejujurnya, pada nada tiap perkataan ibu itu terdengar lebih mengkahawatirkan aku daripada dirinya sendiri.
“Iya, Bu,” jawabku.
-oOo-
Siang tadi, Ares mengabarkan bahwa malam ini dia akan meliput acara fashion show anak yang diselenggarakan salah satu mal. Aku berencana menyusulnya, sekedar melihat-lihat dan anggap saja bersantai setelah akhir-akhir ini memikul pikiran berat. Saat aku ingin menelepon Ares, memastikan apakah dia sudah di lokasi atau belum, mataku terpaku pada satu nama di bawah Ares: Aruna. Lalu sesuatu yang menggelitik pikiran datang seturut dengan senyuman yang aku sunggingkan tanpa sadar.
Ajak Aruna, pikirku.
Cukup lama aku memikirkan bagaimana sebaiknya. Akhirnya aku menyadari bahwa sebaiknya harus menanyakan dulu apakah dia sedang di kamar atau tidak dan bersedia atau tidak pergi bersama. Aku ingin menelepon Aruna tapi jempolku ragu menekan tombol panggilan, rasanya degup jantung akan mengganggu suara yang keluar. Karena khawatir akan berbicara gagap, lantas kuputuskan untuk menanyakan melalui pesan saja. Beberapa kali aku menghapus dan ketik ulang, sebab kata-kataku sangat kaku, lain percobaan justru sangat formal. Lalu pada kalimat lain malah terkesan cuek dan sangat santai.
Ah! bego banget!
Aku mengumpati diri sendiri.
Akhirnya pesan yang lebih lama proses memikirkan kata-kata itu terkirim dengan kalimat sangat biasa dan singkat:
‘Aruna, lagi ngapain?’
Aku terus memperhatikan tanda di pesan itu, memastikan sudah terkirim dan menunggu dibaca oleh penerima. Setiap detik terasa begitu lama. Sudah lebih dari dua menit, tapi pesan itu belum juga dibaca. Aku menunggu dengan cemas, menggigit ujung kuku ibu jari, sementara mataku terpaku pada layar handphone. Untuk mengalihkan perhatian, aku mencoba mencari lowongan pekerjaan di internet. Sambil menggulir layar, membaca dan memilah setiap iklan yang muncul, sesekali aku kembalu lagi ke halaman chat dengan Aruna. Sudah dua belas menit berlalu, pesanku sudah dibaca, tapi belum ada balasan darinya.
Akhirnya, dengan sedikit malas-malasan, juga dengan –yang entah bagaimana, kecewa, aku memutuskan menyusul Ares saja.
“Nyet! Di mana tadi? AEON, ya?” aku bertanya sesaat setelah Ares mengangkat telepon.
“Ya. Ayok sini!” jawab Ares singkat yang tampak sibuk. Terdengar hiruk pikuk di sekitarnya.
“Ok!” ujarku sambil menutup panggilan.
Lalu dengan cepat mempersiapkan diri karena jarak tempuh yang cukup jauh, memakan waktu sekitar empat puluh lima menit untuk sampai kesana dengan segala kemacetan yang ada. Aku meraih semua yang diperlukan, dompet, handphone, jaket, helm dan kunci motor. Masih sempat aku melihat layar handphone, memastikan dan sejujurnya berharap Aruna membalas pesan. Melihat layar itu kosong dari notifikasi, aku segera keluar. Pintu 301 tertutup rapat dan aku menghibur diri dengan menganggap mungkin penghuninya sedang istirahat atau tidak di tempat. Aku tergesa melewati lorong dan tepat saat aku mulai melangkah menuruni tangga, suara lembut memanggil.
“Gam?”
Suara itu memang lembut namun gaungannya memenuhi lorong, membuatku terhenti. Aku menoleh, Aruna berdiri di depan pintunya yang terbuka. Dia mengenakan baju kaos kebesaran dan celana panjang yang longgar. Sungguh menggemaskan sebab tubuhnya yang kecil ditutupi pakaian besar, seperti balita yang sengaja dibelikan pakaian kebesaran oleh ibunya berharap bisa dipakai lebih lama. Rambutnya yang sehat berkilau itu kali ini tampak lebih mengembang pada wajahnya tidak lebih lebar dari telapak tanganku jika aku renggangkan kelima jarinya.
“Kamu mau pergi, ya?” tanya Aruna lagi.
Aku mendekatinya perlahan. “Iya…," jawabku.
“Ooh….” Aruna diam saja melihatku mendekat kepadanya, juga sepertinya menunggu, “Maaf tadi aku belum sempat balas chat kamu. Handphone aku jatuh terus mati. Itu belum nyala lagi. Sedang aku coba isi batrai,” jelasnya.
"Ya. Gak apa-apa.”
Kini aku tepat berada di depannya, jarak yang aman sebagai lawan bicara. Namun pada jarak ini, aku bisa menghirup aroma parfumnya, wangi strawberry dengan sedikit sentuhan vanilla. Manis yang menenangkan. Juga menggembirakan.
“Makanya tadi mau ketemu kamu langsung aja buat jelasin. Bukan aku gak mau balas, tapi gak bisa balas,” papar Aruna lagi.
“Ya. Aku ngerti,” aku menjawab seadanya sebab semakin terpana melihat isi wajahnya.
“Untung gak terlambat ya, kamu belum pergi.”
Aruna tersenyum! Astaga! Menawan sekali. Sudut bibirnya yang terangkat runcing itu rasanya sampai menusuk jantungku, membuatnya heboh sendiri di dalam sini dengan degup yang kencang sekali.
“Oh, aku cuma mau ke Pak Yahya bentar,” aku meracau. Tadinya aku ingin mengatakan bahwa aku akan mengurungkan niat untuk pergi jika dia bersedia bersamaku kali ini. Tapi justru kata-kata yang keluar seperti sebuah guyonan.
“Pak Yahya masih di bawah, kan?” tanya Aruna dengan dahi berkerut-kerut, keheranan. “Kamu lagi gak enak badan ya sampai harus pakai jaket ke bawah?” Aruna menatapku lamat, “bawa helm lagi.”
Kacau!
Aruna masih menatapku dengan sorot mata penuh kekhawatiran. Dia menunggu jawaban. Tidak sanggup rasanya aku berkata-kata, lidahku mendadak kaku. Tanpa kusadari, aku terkekeh pelan, menertawakan diri sendiri yang mendadak bodoh di hadapannya. Sambil menggigit bibir bawah, aku salah tingkah. Dengan menarik napas dalam-dalam, berusaha mengendalikan perasaan yang meluap ini. Arunatersenyum kecil sambil menggeleng-gelengkan kepala. Sepertinya dia menyadari sesuatu, entah sikap bodohku atau justru kebohonganku yang juga tak kalah bodohnya. Lalu aku, orang yang tidak terlalu pandai bicara memilih diam saja. Tidak berusaha menjelaskan. Malah sejujurnya, semakin kujelaskan, maka akan berakhir semakin kacau saja.
“Kamu udah makan?” tanyaku memutus situasi yang lucu, mengalihkan pembicaraan dan berharap menghentikan kebodohanku.
“Belum. Tadinya juga mau sekalian turun, mau ke minimarket depan. Beli mi instan,” ujarnya sambil maju selangkah, memutar badan dan mengunci pintu kamarnya.
“Oohh yuk, bareng.”
“Kamu juga belum makan?” tanya Aruna
Aku mengangguk ragu. Belum makan, memang, tapi tidak lapar.
Kami mulai berjalan beriringan, tetapi saat menuruni anak tangga, aku membiarkannya berada satu langkah di depan. Sementara itu di belakangnya, alisku nyaris saling bertaut sebab berpikir bagaimana cara agar bisa terus bersama Aruna setelah dari minimarket.
“Nanti mau makan bareng?” tanya Aruna tiba-tiba. Biasanya dia lebih pendiam dan tidak suka mengambil inisiatif, tetapi kali ini dia justru menanyakan hal yang diam-diam aku harapkan. Sementara aku susah payah mencari cara, Aruna dengan santai sudah menemukan solusinya.
“Mau banget!” jawabku semangat. Aruna menoleh ke belakang lalu tertawa kecil. Aku terkekeh sambil menggaruk belakang kepala. Malu sendiri.
Saat melewati pagar depan, Aruna mengatakan bahwa dia akan menunggu jika aku ingin berbicara dengan Pak Yahya. Untungnya saat itu Pak Yahya sedang sibuk, dia sedang berbicara dengan seorang pria berkacamata bingkai hitam, kurus tinggi dan berkulit cerah. Usianya kelihatan jauh lebih tua dari Pak Yahya. Sepertinya dia bertanya apakah masih ada kamar yang bisa ditempati. Pria berkacamata itu melirik kami saat berjalan melewatinya dan menatap Aruna lebih lama. Aku melirik pria tua itu dengan tatapan menekan. Anehnya dia justru tersenyum ringan, dan itu membuatku kurang nyaman.
“Besok aja, Pak Yahya lagi sibuk juga,” ujarku pada Aruna. Aku sempat bingung jika harus bertemu Pak Yahya sembari di tunggu Aruna. Situasi mendukung, aku punya alasan untuk tidak berbicara pada Pak Yahya.
-oOo-
Kami memutuskan untuk masak dan makan malam bersama di dapur Aruna. Pilihan furniture dengan tone warna natural memberikan kesan hangat dan nyaman di kamarnya. Barang-barangnya tidak begitu banyak. Selain kasur ukuran kecil, lemari pakaian dan meja belajar, terdapat satu sofa berwarna coklat muda yang hanya bisa diduduki oleh satu orang saja. Baju seragam akademinya tergantung rapi di salah satu sisi dinding. Beberapa hiasan seperti lukisan abstrak dan sebuah foto dirinya dengan Bu Sarah di depan bangunan yang sepertinya panti asuhan tempat Aruna dibesarkan, tergantung di dinding. Tidak ada televisi, hanya ada dua buah portable bluetooth speaker yang terletak sudut meja, persis di samping laptopnya yang tertutup, kipas angin model persegi yang berdiri hampir sama tinggi dengan Aruna. Meja belajarnya disesaki oleh buku-buku tebal dan beberapa jurnal yang di print out. Sepertinya karena berpindah-pindah, Aruna membatasi barang-barang yang dia bawa. Lalu mataku tertuju pada handphone yang terletak di meja tersebut tidak sedang dalam pengisian baterai, layar nya menyala sebab bunyi notifikasi singkat. Aku sempat heran, bukannya tadi dia mengatakan handphone-nya mati karena terjatuh? Ah, sudahlah, toh dia juga akhirnya keluar menemuiku. Aku tidak ingin memikirkannya terlalu dalam. Lebih baik fokus pada momen sekarang yang susah payah aku dapatkan.
Baru kali ini masak mie instan terasa begitu menyenangkan. Aruna begitu cekatan dan lihai dengan gerak-geriknya terlihat anggun namun tegas. Pendidikannya sebagai tenaga kesehatan telah mempengaruhi level kebersihannya, Aruna bahkan tidak membiarkan tetesan bumbu mengotori meja pantry, dia dengan segera membersihkannya. Dengan memasak bersama ternyata mampu mengikis batas sedikit demi sedikit. Aruna perlahan mulai memberanikan diri untuk sesekali bercanda. Hidangannya memang sederhana, namun waktu-waktu ini sungguh luar biasa.
Benar, dia adalah perempuan yang begitu menyenangkan. Bersamanya, pikiran-pikiran beratku seakan beristirahat sejenak. Kami menemukan banyak kesamaan dalam hal-hal kecil, mulai dari film kartun masa kecil yang kami favoritkan hingga lagu-lagu lama yang mungkin sudah dilupakan banyak orang, tapi masih ada di playlist handphone kami. Film-film yang umumnya populer justru sering kali menjadi pilihan untuk tidak kami tonton. Di sela-sela obrolan, Ares beberapa kali menelepon, tapi sengaja aku abaikan hingga akhirnya dia hanya meninggalkan pesan. Jujur saja, aku lupa mengabarinya karena terlalu menikmati waktu bersama Aruna. Meskipun percakapan kami mulai berkurang dan sering diisi dengan keheningan, aku tetap tenggelam dalam tatapan matanya. Juga suaranya dan senyumnya yang membuat pandanganku tak beranjak kemana-mana. “Gam? Itu mi nya udah ngembang, lho,” kata Aruna ketika melihat mi dalam mangkuk yang sudah gemuk-gemuk karena lupa aku suap.
“Oh? Ya. Gak apa-apa. Aku suka.”
Kamunya.
Tentu saja bagian ‘kamunya’ itu aku ucapkan dalam hati saja.
(Bersambung)
Restart ©2023 HelloHayden


 hellohayden
hellohayden











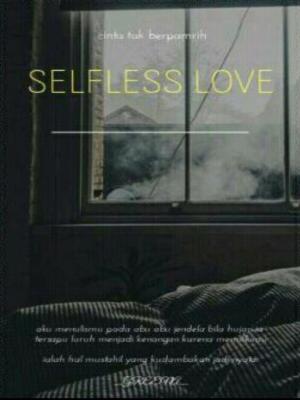

Baca cerita ini udah kayak masuk ke kedai all you can eat. Daging semua. Sbg cowok baca ini gk merasa aneh sama sekali untuk crita roman dan rasa kembali ke masa kuliah. Mantap lah
Comment on chapter Bab 14 (Cukup)