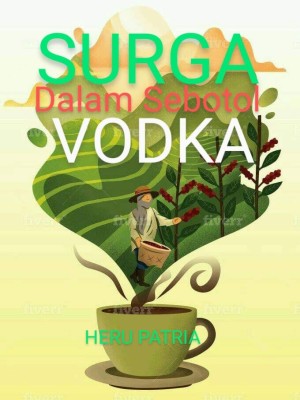Kota kecil di Jawa Timur, Oktober 2023
Aku duduk di teras rumah sembari bercengkerama dengan senja. Angin kemarau yang kering memainkan helaian rambut hitamku.
Tidak ada kopi ataupun teman cemilannya yang mengiringi kegiatanku sore ini. Itu tidak mengapa, karena hatiku gempita sepanjang hari ini.
Karena aku baru saja mendapatkan sebuah harta tak ternilai. Aku seperti menemukan sebuah harta karun. Bahkan nilai harga ini tidak akan sebanding dengan bongkar batu mulia sekalipun.
Benda apakah itu? Mengapa hatiku amat senang saat ini.
Iya, aku memeluk sebuah buku harian usang. Nilai yang tak terukir itu karena buku harian itu merupakan milik wanita yang telah melahirkan aku.
"Ibu, Nayla mohon izin untuk membukanya, ya?" kataku pelan seolah-olah mendiang ibuku bisa mendengar apa yang kukatakan.
Buku seukuran telapak tangan orang dewasa itu telah berumur puluhan tahun. Bahkan, usiaku saja tidak mampu menandingi keantikkannya.
Catatan harian berwarna merah maroon itu seperti lambaikan tangannya padaku. Bak memohon agar diri ini segera menjamahnya.
Tapi, ini milik ibuku. Apakah aku boleh membuka dan membacanya? Tidakkah ibu keberatan?
"Namun, aku telah meminta izin pada ibuku." Kembali aku bergumam membenarkan tindakan tidak sopan ini.
Membuka dan membaca buku harian orang lain merupakan tindakan tercela, bukan?
Tapi, ini milik ibuku sendiri. Ini peninggalannya. Kucoba menguatkan hati ini untuk memberanikan diri membukanya.
Buku dengan gambar hati sebagai sampul depannya itu masih cukup layak jika dikatakan sebagai buku tua. Aku menemukannya di tumpukan pakaian ibu dalam lemari mendiang.
Gambar hati yang begitu mencolok itu, telah kulewati. Kini, aku telah berada pada halaman pertama.
Kesan pertama yang kudapat ketika membuka lembar pertama adalah tulisan ibu yang begitu rapi. Aku teringat perkataan ibu dahulu, "Nduk, dadi bocah wedon iku kudu sing rapi. Nulis yo kudu rapi, supoyo sing moco seneng." Itu nasihat ibu pada suatu malam ketika mengajariku belajar.
"Halah ibu, sing penting iso diwoco beres wes." Aku malu pada diriku sendiri.
Aku yang hidup di zaman modern ini kalah jauh dibandingkan dengan ibu. Padahal, ibuku hanya lulusan sekolah rakyat saja.
Hanya saja, aku selalu mengingat pesan mendiang ibu kala itu, "Dadio wong sukses, Nduk! Senajan ibumu ming buruh cuci."
Tanpa terasa, pipi ini basah oleh linangan air mata. Aku kembali teringat sosok wanita yang sudah membesarkan aku seorang diri.
Atas kasih sayangnya itulah, ibu mengantarkanku hingga seperti ini hidupku.
Kembali lagi pada buku harian ibu, aku tidak menyangka jika wanita pekerja keras seperti ibu rupanya memiliki hati yang cukup lembut. Pada bait pertama tulisnya, disebutkan oleh ibu dia sangat antusias pada hari pertama masuk ke sekolah menengah pada sekolah rakyat dulu.
Kenapa aku menyebutnya sekolah rakyat, karena sekolah itu memang diperuntukkan untuk orang miskin seperti kami. Kaum seperti kami yang tidak mampu menyekolahkan putra putri mereka ke sekolah elit atau yayasan.
Meski begitu, nyatanya ibu sangat girang. Dia menyebutkan memiliki banyak teman baru pada buku hariannya.
Kurasa kehidupan awal tahun ajaran baru memang seperti itu. Para murid akan mendapatkan banyak pengalaman dan teman baru mereka. Begitupun dengan ibu.
Ah ... Aku kembali teringat pada masa kecilku. Ibu, bukumu ini mengingatkan aku pada masa sekolahku dulu.
Belum, usai menyelesaikan kegiatan membaca buku harian ibu, aku dikejutkan oleh kedatangan Abah.
Pria di usia senja itu sudah kuanggap seperti bapakku sendiri.
"Assalamualaikum, Nayla. Abah mari panen mangga. Ki loh, incipono."
Aku menerima bungkusan plastik hitam itu dari tangan rentannya yang sudah keriput.
"Mlebet, Bah. Kulo damelaken kopi rumiyin."
Dia tersenyum dengan menampilkan giginya yang telah gugur satu demi satu. Usai mensetandarkan sepeda tuanya, Abah masuk ke dalam rumah kami.
Mendengar ada suara Abah datang, Mas Anto suamiku yang baru saja menuntaskan salat Ashar sekonyong-konyongnya keluar.
"Ayo, To konconi abah maen catur!"
"Nggih, Abah. Sampun siap kalah nopo?"
"Enak tenan, kowe sing siap-siap kalah, To."
Mereka berdua memang gemar bermain catur ketika bertemu. Mas Anto, suamiku juga sudah menganggap abah seperti bapaknya sendiri. Karena dia tahu, aku tidak memiliki figur seorang bapak.
Aku hanya tersenyum mendengar mereka berdua berkelakar satu sama lain. Sembari menunggu air yang kumasak mendidih, aku akan meracik dua gelas kopi untuk mereka berdua.
"Dek, gorengin pisang sekalian ya kanggo Abah." pinta Mas Anto dari ruang tamu.
#twmxnovelindoS3


 penyukahalu
penyukahalu