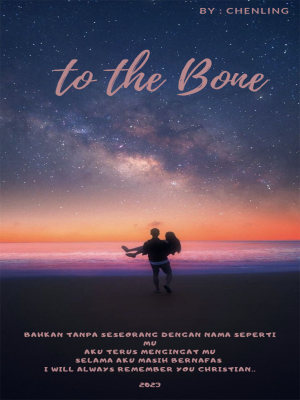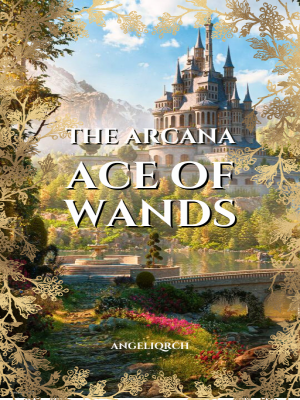Masih tersisa tiga cerita, tapi Danu meminta kami untuk beristirahat dulu selama lima belas menit. Acara ini selain menghabiskan waktu, tanpa diduga juga bisa menghabiskan pikiran dan energi. Beberapa dari kami kembali lapar padahal jam masih menunjukkan pukul delapan lewat. Baru berlangsung kurang lebih satu jam dari waktu makan malam. Alhasil aku menyeduh mi instan cup sebagai pengganjal perut.
“Ana yang baik, sekalian buatin doong,” rayu Tito.
Tidak tanggung-tanggung tiga buah mi instan cup diletakkannya di atas meja.
“Banyak juga ya nitipnya,” cetusku agak menyindir. Tito cengengesan. “Emangnya buat siapa aja?”
“Biasalah. Gue, Aldi sama Randa. Buatin yang enak ya. Tambahin bumbu cinta kalau bisa,” kekeh Tito dimana aku langsung menatap kesal. “Bercanda ih. Thank you, Ana!”
Jadi, dua pemain futsal dan satu pemain basket andalan kelas kami sama-sama menyukai mi instan ya?
Usai membuat, aku berniat membawa mi tersebut keluar. Apa ada cara yang bisa mengefisienkan waktu agar tidak perlu membawa satu per satu? Mungkin aku butuh semacam nampan, tapi tidak ada nampan di vila ini. Tim perlengkapan kami juga tidak memasukkan benda itu dalam daftar yang harus dibawa.
“Sini gue bantu.”
Yogi tiba-tiba saja muncul dengan sebungkus kopi susu di tangannya. Kelihatannya dia ke dapur karena ingin membuat itu.
“Ng, bisa sekalian lo bawain aja ke Dinda, Randa, Aldi, sama Tito? Biar gue yang buatin kopi lo.”
Tidak perlu berpikir lama, Yogi langsung mengangguk setuju.
“Oke. Gue tunggu di depan ya,” katanya tersenyum meninggalkan dapur. “Oya, lo masih kedinginan? Tadinya gue mau pilih jaket yang lebih tebal, tapi jadinya yang itu aja.”
Pikiranku mengambang sejenak. “Oh, ngga kok. Ini udah cukup. Makasih,” jawabku gugup, sedangkan Yogi kembali berjalan.
Akhir-akhir ini ucapan Yogi padaku selalu membuatku kaget dan blank. Saking blank-nya aku sampai lupa jika air termos sudah habis untuk membuat mi tadi. Seharusnya aku tidak perlu memberi tawaran untuk membuatkan, karena itu tandanya aku harus memasak air panas untuk menyeduh kopi. Mau bagaimana lagi? Jika tidak dibuatkan, aku merasa tidak enak dengan Yogi yang sudah mengantar mi instan ke depan.
“Ayo, Ana. Kumpul lagi,” ajak Nina yang baru saja turun dari lantai dua bersama Sisi juga Wine. Syukurlah. Wine sudah kembali bergabung, meski matanya terlihat sembab.
“Gue lagi masak air panas buat bikin minuman. Tolong bilang Danu ya, Nin. Sepuluh menit lagi gue ke sana.”
Nina mengangguk paham, kemudian mereka bertiga pergi. Aku sangat ingin berada di sana sekarang. Melihat bagaimana reaksi yang lain saat tahu Wine sudah kembali bergabung. Terutama reaksi Kevin, Tere, juga Sonya. Tapi apa daya. Aku harus menunggu air mendidih terlebih dahulu. Kalau kutinggalkan dan aku lupa, bisa menimbulkan bahaya.
Aku memilih menunggu di ruang tamu. Menikmati saat-saat duduk berselonjor kaki di sofa. Namun, yang terjadi malah aku teringat pada rumah. Tidak terasa ini adalah malam ketiga kami menginap di vila dan besok siang kami akan pulang. Rasanya sudah nyaman dan belum ingin pulang. Baik dari dekorasi vila, suasana, ataupun fasilitas yang disediakan benar-benar membuat betah. Kuacungkan dua jempol untuk Aldi yang telah mencari dan memilih vila ini.
“Ah, gue pikir bakal gue doang di sini.”
Sonya mendadak muncul entah dari mana. Membawa gitar dan ikut duduk di sofa bersamaku. Agak canggung berduaan dengannya setelah tadi aku begitu tidak membelanya. Kalau ditinjau ulang, sebenarnya akulah penyebab dari membesarnya masalah ini. Sonya sudah sempat menolak untuk tidak membahas cerita kedua karena bertentangan dengan tema, tapi aku memaksa agar terus dilanjutkan dengan alasan untuk menghargai Wine, penulisnya.
Tapi tenang saja, sepuluh menit akan berlalu cepat.
“Gitar Zaki?” tanyaku basa-basi. Sonya menggelengkan kepala. “Oh, Vino,” jawabku. Aku yang bertanya, kemudian aku yang menjawabnya sendiri. Menjadikanku tampak bodoh.
“Kenapa lo ngga balik ke halaman?” balas Sonya dimana jarinya mulai memetik asal senar gitar.
Aku mengambil bantal sofa dan mendekapnya. “Lagi masak air panas buat bikin kopi,” jawabku dan Sonya langsung menatapku seolah aku baru saja mengucapkan sesuatu yang salah.
“Air panas? Lo ngga tau situasi di luar lagi panas-panasnya? Seharusnya yang lo buat itu berbongkah-bongkah es batu!” serunya dengan seringai yang khas.
Aku tahu bersedih tidak ada dalam kamus Sonya. Dikhianati oleh Gerry pun dia tetap tegar, walau aku tahu di dalam hatinya dia kesal dan mungkin dendam. Jadi, apa yang baru saja terjadi padanya kupikir tidak ada apa-apanya. Meski anak-anak tahu kesalahan apa yang pernah dia lakukan pada Wine, Sonya pasti bisa melaluinya.
“Lo sendiri kenapa ngga balik ngumpul? Nanti ceritanya keburu dibacain loh,” ujarku bermaksud mengingatkan bahwa kami sudah menunggu cerita miliknya dibacakan dan dia harus hadir di sana juga.
Sonya fokus pada gitarnya. “Ngga ada lagi cerita yang perlu dibacain dan lo pasti tau alasan kenapa gue di sini,” jelasnya tanpa melihatku.
Jari-jarinya mulai bermain dengan lihai. Kali ini perlahan demi perlahan membentuk irama. Setelah percaya diri dengan kemampuan bermainnya, Sonya pun mulai bernyanyi. Kudengar setiap liriknya hingga aku tahu lagu apa yang menjadi pilihannya. Lagu yang terdengar lebih menyerap ke hati ketika dinyanyikan dengan ketukan pelan. Lagu yang seakan-akan memang ingin dinyanyikan untuk menggambarkan perasaannya saat ini.
Is it too late now to say sorry. Yeah I know that I let you down.
Is it too late to say I’m sorry now.


 elhrln
elhrln