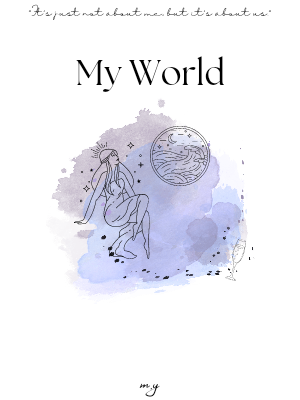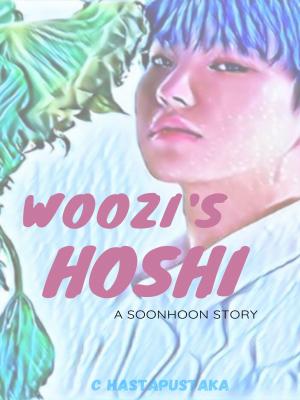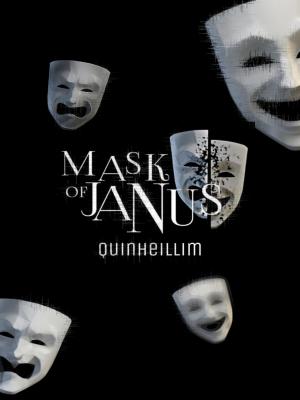Sebuah bunyi yang sangat keras membuatku bangun dengan tergeragap pagi itu. Kusambar ponsel; jam delapan tepat. Apakah alarmku tadi tidak berbunyi? Kenapa akhir-akhir ini terompet Fidelia jadi luar biasa kerasnya?
Tapi tidak. Yang membangunkanku bukan terompet si Pengingat, melainkan bel di asrama. Bel ini jarang dibunyikan, hanya ketika hari-hari libur dan ada agenda bersih-bersih di hari Sabtu ....
Oh, tidak. Hari ini memang hari Sabtu dan sudah dijadwalkan operasi bersih-bersih seasrama jam delapan pagi. Semalam aku pergi nonton dengan Markus dan masih melanjutkan obrolan soal filmnya lewat chat sampai tengah malam—musikal dari Beauty and the Beast yang diperankan Emma Watson. Itu adalah acara nontonku yang kedua setelah Black Butler di awal bulan. Bagiku itu adalah pelampiasan, selepas menunaikan tugas paduan suara di hari Minggu yang lalu dan setumpuk presentasi kelompok sepanjang minggu itu. Aku buru-buru ke wastafel dan melewati ruang ganti.
“Ra, kamu baru bangun?” seru Asti, ketua kamarku yang sedang menyisir rambutnya di ruang ganti. “Dari tadi Elena udah coba bangunin kamu, lho.”
“Iya, nih. Rasanya capek banget,” sahutku. Elena sudah siap di teras kamar, memakai baju olahraga yang ngepas di badannya, nyengir ke arahku.
“Habis nge-date sih ya ...,” godanya. Aku melempar senyum miring sebelum menyalakan keran air untuk cuci muka. Dalam hati kucatat bahwa Elena makin gemuk saja.
“Kami duluan, ya, Ra.” Asti menyusul Elena. Anggota kamarku yang lain tampaknya sedang ada perlu di kampus, karena tak ada lagi yang terlihat di kamar.
“Bawa masker, As,” ujarku.
“Oiya. Trims udah ngingetin.”
*
Tugas paduan suara asrama bukanlah proyek terakhirku di semester keenam ini. Ada satu lagi proyek besar yang menanti, dan aku jadi terlibat gara-gara Elena mengumbar fakta bahwa aku suka menulis di blog,
“Mau bikin pentas drama? Ashira aja tuh, dia pinter nulis!”
Rasanya semester enamku begitu sibuk. Kegiatan asrama bertumpuk-tumpuk tanpa kusadari, saling tumpang tindih dengan pilihan-pilihanku di kampus. Baru kemarin kami bersih-bersih asrama untuk yang kesekian kali dalam semester ini, dan tanpa pengumuman apa pun, hari ini namaku tiba-tiba nongol di daftar panitia Dies Natalis asrama sebagai sie acara.
“What the ... beep?” Aku memang tahu umpatan dalam bahasa Inggris tapi bukan berarti aku akan menggunakannya, jadi kusamarkan saja. Elena ada bersamaku ketika membaca daftar itu di majalah dinding. Kami baru mau keluar untuk belanja bulanan, Elena yang mengendarai motor dan aku membonceng.
“Mereka mau nampilin drama, Ra. Kamu, ‘kan, bisa nulis skenario?”
Tahulah aku dari mana asalnya namaku bisa terpampang di sana. Dapat wangsit apa, sih, Elena ini? Mana pernah aku menulis naskah drama? Mana pernah aku ikut rapat panitia? Aku tak pernah terlibat sebagai panitia di divisi sepenting ini di Dies Natalis. Biasanya hanya jadi tenaga bantu-bantu menjelang persiapan, tak ikut duduk berpikir merancang acara, tak selalu ikut acaranya sendiri, ataupun serta dalam pembubaran panitia.
“Lihat, nih, Kak Vira jadi pendamping sie acara. Dia, ‘kan, anak teater, juga denger-denger jago nulis puisi. Kalian pasti jadi duel maut drama asrama!” tutur Elena berapi-api.
“Duet, kali, bukan duel,” komentarku sambil memperagakan orang memegang tongkat. “Kalau duel, aku dan Kak Vira kayak Harry Potter versus Voldemort, dong.” Tongkat sihir imajiner kuayun, sembari kuserukan, “Avada Kedavra!”
“Expelliarmus!” balas Elena, mengambil pose yang sama, dan kami tergelak.
“Eh, jadi kamu Voldemort-nya, dong, Ra?” gurau Elena sambil terus berjalan. “Aku Harry-nya.”
“Woi!”
“Mbak Beta, pergi dulu ya ...,” ujar Elena mengalihkan pembicaraan begitu melewati pintu dapur.
“Pamit Mbak,” timpalku, lalu mengejar Elena yang tiba-tiba ngibrit.
“Elena, nanti kamu jadi tokoh utama di dramaku, ya! Harus mau! Kalau nggak mau, nanti jajanan Chitato-mu aku embat!”
Elena mengerang. “Kok tahu aja kalau aku lagi pengin beli Chitato!”
“Hey. I’ve been living with you for three years!” balasku sengit, setengah tertawa puas karena tebakanku benar. Elena selalu punya stok makanan ringan bermicin di meja belajarnya; kalau bukan Cheetos yang adalah keripik jagung, pasti Chitato keripik kentang. Karena kulihat ada bungkus Cheetos di tempat sampah beberapa hari ini, kuasumsikan dia sudah agak bosan makan keripik jagung. “Belum ditambah ngorokmu setiap malam, kalikan 365 dengan tiga tahun. Bikin tidurku tambah nyenyak. Makasih banyak, ya.”
“Oi! Belum genap tiga tahun juga kita di asrama, ‘kan?”
Elena dan aku sudah sampai di parkiran motor.
“Lha, ini, ‘kan, Dies Natalis kita yang ketiga?” ujarku sambil memakai helm. Elena menyalakan mesin sepeda motornya.
“Makanya. Jangan dihitung tiga kali tiga-enam-lima dong. Nggak valid.”
“Oh iya, ada tahun kabisatnya juga. Jadi ada yang 366.”
“Ashira ...!”
*
Bukannya aku betulan mau ngembat jajanannya Elena yang isinya micin melulu; dari pengalaman aku tahu bahwa migrainku tambah mudah kumat kalau aku makan monosodium glutamate—bahkan meski hanya sedikit. Untung sekali, aku sangat beruntung dan bersyukur karenanya, masakan di asrama tidak ditambahi micin. Sejak Suster Eva memimpin asrama ini delapan tahun yang lalu, Mbak Beta dan yang lain sudah dihimbau untuk menggunakan garam, kaldu jamur, dan penyedap rasa alami selain MSG.
“Jadi, mau gimana? Kamu ada usul?”
Pertanyaan Kak Vira di ruang belajar terdengar familier. Bulan lalu aku juga ditanyai seperti ini oleh Kak Prita dan aku tidak mengecewakannya. Kali ini pun harus demikian. Saat itu Senin siang dan sebagian besar anak asrama ada jadwal kuliah—kebetulan sekali aku dan seniorku yang ini punya jadwal kosong hari Senin.
Kak Vira melanjutkan, “Sound system di aula asrama memang menggaung. Kayaknya karena arsitektur gedungnya juga, sih. Kalau buat teater kurang bagus, tapi panitia minta ada dramanya. Padahal kalau pakai mikrofon, selalu menggema kayak gitu. Tahu sendiri, ‘kan.”
Aku mengetuk-ngetukkan pensil ke meja. Kami memang rapat berdua saja karena aku ingin bertukar ide dahulu dengan sang pakar teater ini sebelum rapat dengan anggota sie acara lainnya. “Menurutku kita rekam aja, Kak.”
Kurva alis Kak Vira yang tergambar rapi berkerut. “Maksudnya?”
“Suaranya kita rekam. Nanti pas tampil, tinggal arahin gerak dan akting saja, sama mulutnya yang komat-kamit.”
Seniorku yang berambut sebahu itu mengedip-ngedipkan mata sebelum berujar takjub, “Wow, ide brilian.”
Bibirku melengkung naik seiring harga diriku yang dipuji. “Thanks, Kak. Kalau direkam, suaranya akan langsung masuk speaker. Harusnya nggak terlalu menggema.”
“Betul, betul. Nanti biar diatur volumenya sama Pak Rahmat yang biasa mengurus sound.”
“Iya, Kak.”
“Bisa juga nih, backsound lagu-lagu kamu masukin di rekaman juga. Lebih bagus lagi, kamu edit audionya jadi satu dulu, yang rekaman suara sama yang lagu.”
Aku coba mencerna usul Kak Vira. “Oh ... berarti editing mp3, digabungin gitu, Kak?”
“Iya. Aku ada aplikasinya sih, di laptop. Lumayan gampang, kok, bisa belajar sendiri. Nanti aku cariin bentar, aku lupa namanya.”
“Oke, deh, Kak.” Aku menjeda. “Oh, iya, Kak. Aku mau nanya sesuatu.”
“Oh? Nanya apa, ya?”
“Di ruangan ini, Kakak lihat ada sesuatu yang lain? Sesuatu yang biasanya nggak kelihatan,” suaraku menjadi bisikan di akhir kalimat, menatap seniorku sungguh-sungguh.
Kak Vira mengedarkan pandangan, ke kiri, lalu ke kanan. Dia menggeleng. “Nggak ada apa-apa.” Dia menatapku balik. “Jadi, kamu beneran bisa lihat mereka, toh, Ra?”
“Nggak selalu sih, Kak,” ujarku menghindar, karena yang kulihat berbeda dengan apa yang Kak Vira pikir kulihat.
“Mereka baik, ‘kan? Maksudnya, nggak pernah ngapa-ngapain kamu?”
Aku tersenyum, menggeleng. “Nggak. Kalau Kakak pernah lihat? Atau cuma denger aja?”
“Pernah lihat juga, tapi lebih sering denger. Kamu mau aku beri tahu, mana aja di asrama ini yang banyak ada mereka?”
Aku mengernyit tapi tertarik. Mungkin Kak Vira termasuk salah satu dari mereka yang disebut indigo? “Tapi jangan sebutin yang di dekat kamarku, deh, Kak.”
“Wah, sayang banget. Padahal yang di ruang cuci tempatmu itu biasanya ada sinyo-sinyo Belanda. Dia cakep, lho. Sayang mati muda.”
Dan Kak Vira mengucapkan itu sambil nyengir seolah sedang mengomentari aktor sebuah film. Astaga, padahal aku hanya iseng bertanya pada kakak satu ini karena aku melihat si Bocah Fidelia berdiri persis di sampingnya!
*
Aku pernah bertanya-tanya bagaimana kalau bocah laki-laki yang disebut Hakim itu masih mempunyai mata. Seperti apa matanya? Lebar? Sipit? Apa gerangan warna irisnya? Karena dia tak pernah muncul lagi di dekatku sejak kasus Frida, aku belum bisa bertanya langsung. Hari itu, ketika kulihat dia berdiri di dekat Kak Vira selagi aku mengobrol dengan seniorku itu, pertanyaan itu segera muncul dalam pikiran. Kulit si Bocah sawo matang seperti penduduk asli negaraku, tapi belum tentu matanya hitam karena aku juga tak tahu apa warna asli rambutnya. Kalau si Pengingat, kulitnya pucat dan rambutnya kecokelatan, matanya biru khas orang Kaukasia. Sementara si Pemberi, rambutnya hitam keriting dan kulitnya terang seperti wanita Celtic; matanya hijau.
Tapi keberadaan si Bocah Hakim yang mendadak juga menimbulkan tanda tanya; apakah artinya akan ada pencurian lagi di asrama? Tapi si bocah tidak bernyanyi, dia hanya berdiri di situ sambil tersenyum, seolah turut asyik menyimak penuturan Kak Vira soal roh-roh yang menurutnya gentayangan di asrama. Andaikan dia masih punya mata, tentu aku bisa menerka perasaan hatinya lewat sinar matanya, apakah dia memang ingin tahu pada kisah Kak Vira atau dia tersenyum karena geli mendengar percakapan dua manusia fana ini soal roh yang tak kelihatan. Dan aku tidak mendengar bunyi terompet si Pengingat baru-baru ini, serta baru sadar bahwa aku sama sekali tak pernah mendengar mereka lagi sejak peristiwa ponsel hilang di jogging track Gedung Utama kampus—disusul kecelakaan yang merusakkan kacamataku.
“Jadi, yang kamu lihat, kayak apa?”
Kak Vira rupanya sudah selesai bercerita dan aku melewatkan sebagian besarnya. Aku malah bersyukur, karena aku sesungguhnya tak ingin tahu macam-macam yang bisa dilihatnya. Aku sudah membuka mulut untuk menjawabnya, tapi si Bocah Hakim menoleh ke arahku—dan dia memberengut.
Seketika aku bergidik. Dengan rautnya yang tanpa mata itu si Hakim jadi tampak buruk rupa sekaligus menyeramkan. Justru dari rongga kosong itu aku merasa sedang dituduh, sedang dimarahi, oleh sebuah eksistensi mengerikan yang tak ada di sudut mana pun di planet ini.
“Ra? Kalau nggak dijawab, nggak apa-apa, kok.” Suara Kak Vira menyadarkanku dari ilusi mencekam barusan. Aku mengerjap.
“Yang penting, kamu nggak diganggu.” Kak Vira menatapku sungguh-sungguh. “Sudah cukup berat punya kemampuan melihat mereka.”
Aku menggeleng, mendadak merasa air mataku sudah siap terjatuh. Bukan roh-roh gentayangan yang menggangguku, tapi aku tak bisa cerita pada seniorku ini yang begitu terbuka mengakui dirinya berbeda.
“Kak Vira ... sejak kapan, sih, Kakak bisa lihat?” Suaraku terdengar gemetar; aku sendiri seolah mendengarnya dari tempat yang jauh, sambil merasa seluruh tubuhku kebas. “Apa Kakak senang bisa lihat?”
Orang yang kutanyai tak langsung menjawab. Mungkin karena sedang memikirkan jawaban yang akurat, atau mungkin karena aku yang salah karena bertanya dua hal sekaligus. Dalam kuliah tentang komunikasi tenaga kesehatan, aku diajari untuk menggali informasi tanpa terburu-buru—artinya, menanyakan satu topik dan menunggu respon dulu, baru lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Orang cenderung hanya menjawab pertanyaan yang terakhir kalau ditanyai secara berondongan.
Tapi rupanya Kak Vira menjawab kedua pertanyaanku. “Kayaknya sejak aku SD, karena di SD-ku ada gedung olahraga lama yang angker. Aku udah agak lupa sih. Kalau senang atau nggak, aku nggak bisa bilang salah satu. Ada kalanya mereka ngganggu aku. Tapi, yang di sini, nggak ada yang mengganggu. Dan kupikir, pasti ada maksudnya aku diberi Tuhan kemampuan ini.”
Aku menangis sejadi-jadinya; dalam hati bersyukur asrama sedang sepi, tapi kurasa kalau aku terlalu keras maka juru masak bisa mendengarku.
Aku lelah. Aku tak peduli apa maksudnya Tuhan mempertemukanku dengan Fidelia, tapi aku sudah muak dengan keberadaan mereka yang menggangguku—malah mending aku bisa melihat yang lain-lain yang dibilang Kak Vira tadi saja, karena katanya mereka tidak mengganggu, daripada hidupku dihantui ketidaktenangan macam begini. Rasanya seperti diuntit psikopat—dan psikopatnya ada tiga, pula.
Tapi yang keluar dari mulutku adalah keluh-kesah mengapa aku dipilih jadi panitia Dies Natalis bahkan tanpa menanyaiku, minta persetujuanku terlebih dahulu. Main tunjuk saja; siapa yang senang dibeginikan?
Kak Vira tidak terlihat canggung saat coba menenangkanku. Dia menggeser duduknya mendekat lalu menepuk-nepuk punggungku dalam diam, menungguku selesai menumpahkan air mata. Aku tak pernah tahu perihal keluarganya atau kepribadiannya, karena kami tak pernah sekamar dan jam terbangnya di luar asrama bisa dibilang seperti kombinasi aku dan Kristin, bahkan masih lebih dari itu.
“Kak, aku masih ada PSM, ada gathering beasiswa, kegiatan BEM, belum lagi mau persiapan kerja praktik.”
Kak Vira menyahuti, “Terus ditambah panitia Dies Natalis? Rasanya kayak kamu ketiban gunung, iya nggak, sih?”
Sesenggukanku makin parah. Kalimat Kak Vira betulan mengena persis apa yang kurasakan. Aku menggelepar tak siap dengan tambahan beban seberat ini.
“Itulah gunanya keluarga, Ra. Kamu nggak sendirian menghadapi ini. Soal Dies Natalis saja, sayangnya, bukan yang lain-lain.”
“Keluarga?” Kenapa kata itu terasa asing di mulutku?
“Asrama bagiku seperti keluarga kedua,” sahut Kak Vira. Dia menambahkan setelah tersenyum singkat, “Orang tuaku bercerai waktu aku SMA.”
Hatiku serasa diremas. Kutelan ludah sambil menatap seniorku tak percaya. Dia masih meneruskan,
“Ada yang bilang, orang yang sudah pernah ketiban gunung pasti bisa mengangkatnya.”
Kak Vira terdiam cukup lama sembari aku merenungkan kalimatnya yang puitis. Aku tak pernah menganggap warga asrama sebagai keluarga—tempat ini adalah tempat tinggal sementaraku selama di Kota Pelajar dan aku akan pergi dari sini setelah lulus kuliah. Aku taati aturan yang ada tapi segitu saja. Beberapa teman seperti Kristin dan Elena mungkin akan menjadi temanku untuk seterusnya, tapi, menyebut orang-orang lainnya sebagai keluarga? Dan, Suster Eva sebagai ibuku? Beliau seperti guru yang harus disegani bagiku, bukan sosok ibu seperti di rumahku.
Entah dari mana, dalam pikiranku terngiang sebuah lagu dari waktu lampau; puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mungkin bagi Kak Vira, pengalamannya punya makna mendalam yang bisa membuatnya bertahan sampai kini.
“Maaf, ya, tiba-tiba cerita beginian,” seloroh Kak Vira, senyum sendunya masih ada. Air mataku sudah kering sama sekali, aku menggeleng tapi masih belum sanggup berkata-kata. “Aku cuma pengin bilang: Kalau kamu merasa bebanmu terlalu berat, jangan berdoa biar Tuhan memperingan bebanmu, tapi berdoalah minta diberi punggung yang lebih kuat. Dan di sini, banyak punggung-punggung lain yang mau sama-sama menyangga gunung Dies Natalis.”


 roux_marlet
roux_marlet