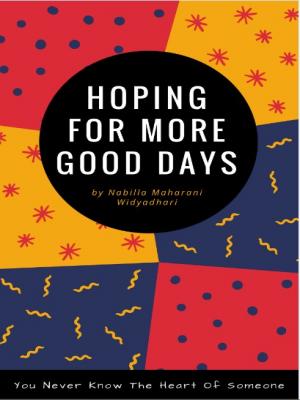“Kita mau latihan lagu ini lagi, Kak?” Kusodorkan kembali seberkas kertas ke arah seniorku yang kecil mungil dan berkacamata bulat.
“Iya, Ra. Atau, kamu ada usulan lagu lain?” Kak Prita menyahut, menatapku seolah berharap aku memang punya usul. Malam itu kami sedang duduk bersila di kapel asrama, yang kadang juga berfungsi sebagai tempat latihan paduan suara, yang mana aku akan menjadi pelatihnya mulai besok malam. “Mungkin di PSM ada lagu-lagu gereja?”
Aku tertawa sambil geleng-geleng kepala. “Ya, ada. Tapi, jangan lah, Kak. Terlalu tingkat tinggi.”
Kak Prita ikut tertawa. “Iya, sih, ya. Pasti lagunya level dewa, nadanya sulit-sulit. Kelas panggung dunia memang beda, sih.”
Tersipu, aku terpaksa mengiyakan. “Tapi memang kalau kita tugas di misa, lagunya itu-itu aja, ya, Kak.”
“Ya, kamu tahu sendiri. Tiap tahun pengurus asrama pasti ganti orang, dan masing-masing punya kesibukan di kampus. Belum pernah ada yang cukup ... rela … mempersembahkan waktunya buat paduan suara asrama, jadinya ya selalu apa adanya kayak gini. Aku pun begitu, aku nggak nyangkal.”
Aku tersenyum datar. “Dan Kak Prita udah mau mulai tugas akhir beberapa bulan lebih cepet, makanya nggak ada yang melatih kita.”
“Yes,” sahutnya yang jurusan Sastra Inggris di kampus sebelah. “Makanya aku berterima kasih banget, kamu mau gantiin aku, Ra.”
“Padahal aku bukan pengurus,” balasku sambil angkat bahu. Kegiatan-kegiatan yang kuikuti di kampus, semuanya terlapor pada Suster Eva, dan beliau cukup bijak untuk tidak memasukkanku ke dalam jajaran pengurus asrama. Bisa remuk badanku mengemban aktivitas sebanyak itu.
“Untuk berbuat baik bagi asrama ini, nggak harus jadi pengurus, kok,” timpal Kak Prita. “Lihat aja si Vira. Dia, ‘kan, suka fotografi dan kebetulan punya kamera SLR tuh. Kapan pun ada acara asrama, dia pasti maju jadi sie dokumentasi. Padahal dia bukan pengurus. Bahkan, dia seorang Muslim, tapi selalu mau terlibat di kegiatan-kegiatan rohani asrama.”
Aku mengiyakan, mengingat bahwa di majalah dinding tentang serba-serbi kegiatan asrama yang dikelola Elena dan Kak Sita mayoritas fotonya berasal dari kamera Kak Vira. Dia pandai membidik momen pada sudut dan waktu yang tepat, mengabadikan emosi dan kenangan dalam gambar. Begitu pun, baru-baru ini aku tahu bahwa dia rupanya ikut klub teater di kampusnya, dan jadwal latihan orang teater jauh lebih intensif daripada orang paduan suara.
“Kak Vira memang hebat,” aku menyuarakan pendapatku. “Angkatan kalian banyak yang hebat-hebat. Kak Ribka tuh, apalagi. Berprestasi tapi juga aktif di asrama.”
Kak Prita diam sejenak. “Yah ... mungkin, angkatanku solid karena banyak dari kami yang bertahan dari awal. Teman-teman angkatanmu banyak yang sudah pindah.”
Kuanggukkan kepala, mengingat satu per satu temanku yang memilih hengkang dari asrama. Yang pertama adalah Frida, dan hanya dia yang alasannya berhubungan dengan Fidelia. Yang lainnya pindah karena tak kuat dengan aturan ketat asrama, ingin bisa pulang lebih malam daripada jam dua puluh satu, ingin bisa jajan tanpa dicibir tak menghargai masakan juru masak asrama, ingin bermalas-malasan ketika di asrama ada kegiatan. Perihal jam malam memang yang paling berat. Ada seorang temanku yang kelas kuliahnya memang sampai malam disambung mengerjakan tugas secara berkelompok, dan pilihannya hanyalah pindah kos daripada setiap malam selalu dihadang satpam di balik pagar asrama yang terkunci.
“Di angkatanmu juga banyak yang hebat, kok, Ra.”
Suara Kak Prita menggugahku. “Oya?” Aku berpikir cepat. “Kristin? Dia memang keren banget, sih. Terpilih jadi mahasiswa berprestasi fakultasnya dan anggota Buddy Club kampus. Padahal tiap hari tugasnya bikin makalah empat ribu kata.”
Senyum yang merekah di wajah Kak Prita terlihat tulus. “Ada yang lain yang keren, kok. Yang ikut seabrek kegiatan di kampus, yang selalu lembur laporan praktikum sampai tengah malam, tapi masih mau ngelatih paduan suara asrama.”
Astaga, caranya memuji halus sekali, aku tak sadar sampai Kak Prita tiba di akhir kalimatnya! Tak akan kusia-siakan pujian yang dalam sedetik sudah bisa memelembungkan kepalaku ini.
Tak akan kubiarkan paduan suara yang akan kulatih ini tampil biasa-biasa saja.
*
“Tin, gimana menurutmu?”
Besok paginya, kudatangi Kristin di kamarnya dan kutunjukkan beberapa teks lagu yang kupilih. Dia sedang membersihkan sepatunya, siap-siap untuk berangkat ke kampus. Aku beruntung masih bisa menemuinya.
“Mau buat apa?” tanyanya kebingungan. “Konser PSM?”
“Ya, nggak, lah. Ini buat tugas paduan suara kita, buat misa akhir bulan ini.”
“Kamu dapet dari mana?”
“Cari di internet semalem.”
Kristin meneliti lagu-lagu dalam not angka itu sebentar sebelum akhirnya mendongak. “Apa nggak terlalu sulit? Latihannya mau berapa kali?”
“Kalau seminggu dua kali, maksimal cuma tujuh kali sampai misa. Itu pun kalau semuanya bisa datang tiap latihan, yang kamu juga tahu, itu mustahil.”
Kristin menangkap sarkasme dalam kalimatku. “Nah, dengan sulitnya ngumpulkan orang untuk latihan yang kamu sendiri juga tahu, kamu mau pakai lagu-lagu ini, Ra?”
Sarkasme Kristin malah lebih keras dariku. Aduh, aku lupa kalau dia punya karakter yang mirip diriku.
“Coba, yang Rejoice in the Lord Alway ini. Eh, judulnya memang alway, tanpa huruf ‘s’ ya?”
“Itu ejaan bahasa Inggris kuno,” sambarku dengan nada bangga, karena aku tahu sesuatu yang Kristin tak tahu. “Lagunya bagus, aku dengar di internet. Judulnya diambil dari Filipi 4 ayat 4.”
“Oh, gitu, baru tahu aku,” sahutnya sambil mengangguk-angguk. Bedanya Kristin dariku adalah, dia lebih bisa menerima fakta bahwa dirinya tidak lebih tahu dari orang lain. “Nah. Lagunya ada empat halaman dan ini komposisi empat suara. Sopran-alto-tenor-bas. Di asrama, ‘kan, cuma ada sopran dan alto. Tambah mezzosopran mungkin masih bisa, tapi itu maksa banget.”
“Bagian tenor dan basnya nggak usah dinyanyikan, atau orangnya dibagi jadi empat suara. Menurutku, tenor dan basnya lebih ke harmoni, bukan melodi.”
“Orangnya dibagi jadi empat suara?” Alis Kristin naik.
“Oke, itu jelas nggak mungkin.” Cepat-cepat kutarik usulku yang satu itu. “Masih bisa dengan hanya dua suara.”
Kristin mendendangkan beberapa not sebelum berkomentar, “Ada bagian di mana tenor dan bas masuk sebagai melodi, dan justru di situ indahnya komposisi ini. Kamu nggak bisa nyanyi lagu ini hanya dengan sopran dan alto, Ra.”
Aku mencebikkan bibir, sedikit merasa iri pada kemampuan Kristin membaca cepat sebuah partitur lagu. “Yah. Ya udah. Lagu yang lain?”
Dibolak-baliknya teks yang kubawa, lalu menggeleng. “Nggak banyak lagu dengan komposisi paduan suara sejenis. Agak susah kalau mau cari lagu baru. Kenapa nggak pakai yang biasanya aja, Ra?”
“Justru itu. Karena yang biasanya terlalu biasa, Tin.”
“Lha. Waktunya tinggal tujuh kali latihan. Aku berani bertaruh, yang datang latihan pasti kebanyakan anak tingkat satu. Dan mungkin mereka sama sekali belum pernah dengar lagu yang biasanya. Bakal mulai dari nol, Ra.”
Aku mengernyit, memasang wajah memelas pada Kristin. “Nanti malam latihan yang pertama, Tin. Kamu bisa ikut, nggak? Aku belum pernah, lho, ngelatih paduan suara. Apalagi jadi dirigen.”
“Waduh, sori. Ada pertemuan Buddy Club nanti malam.” Suara Kristin lirih tapi tegas, tanpa tersirat alasan yang dibuat-buat, tampaknya dia betul-betul menyesal tak bisa membantuku. Tiga tahun aku tinggal bersama Kristin membuatku banyak belajar tentang sisi psikologi hubungan manusia. Seperti kubilang tadi, Kristin dan aku mirip. Kami sama-sama perfeksionis dan suka sarkasme, suka hal mendetail dan teliti, suka menulis dan membaca, terlepas dari kesenangan kami yang sama soal musik. Jadi ketika aku bicara dengan Kristin, aku seolah melihat bayangan cerminku, dan siapa sih, yang berprasangka pada bayangannya sendiri di dalam cermin?
“Oke, deh. Doakan saja, Tin.”
Nada pasrahku rupanya membuat Kristin merasa bersalah. “Nanti aku pulang siang sih, Ra. Mau aku bantu nyiapin dulu?”
“Yaaah. Akunya yang kuliah sampai sore,” balasku. “But, thanks. Mungkin latihan berikutnya, kamu bisa ikut?”
“Coba kulihat dulu jadwalku, ya.” Kristin melihat jam tangannya dan memekik. “OMG, Ra, aku telat!”
Aku melompat mundur, dia meloncat berdiri lalu berlari. “Sori, sori! Hati-hati di jalan, Tin!”
Kristin masih sempat melambaikan tangan tergesa, berlari tanpa menoleh lagi. Aku hanya berdoa, Pak Santoso si petugas kebersihan asrama belum mulai mengepel lantai koridor; nanti Kristin bisa terpeleset!
*
Perkara paduan suara asrama membuatku teringat lagi pada Fidelia. Pasalnya, saat di kelas, aku membuka ponselku untuk mencari dasar-dasar teknik dirigen selagi dosenku berbicara. Terompet si angsa trumpeter—eh, maksudku, si Pengingat—berbunyi sumbang dan pendek, seolah sedang mengejekku.
“Jangan mencuri waktu, Ashira,” bisik si Pengingat.
Aku mendengus dan menutup ponselku. “Pergi kau,” desisku.
Dian menoleh. “Apa, Ra?”
“Nggak. Bukan apa-apa.”
Bahkan saat istirahat, aku minta saran dari Markus untuk latihan nanti malam.
“Gini, lho. Aku pernah baca di buku musik, kalau harusnya gerakan dasarnya tuh kayak begini. Tapi, di video ini, gayanya malah begini. Menurutmu bagus yang mana? Yang ini kusebut ‘yang ideal’ dan ini ‘yang milenial’. Tahu, ‘kan, teori bahwa yang ideal itu nggak real, dan bahwa kita hidup untuk terus menuju ke yang ideal itu meski nggak akan pernah tercapai. Yang ideal dan yang sempurna itu nggak ada di dunia ini. Nah kalau gitu, berarti yang di buku musik nggak benar, dong?”
Alih-alih menjawab pertanyaanku, Markus malah berkomentar sambil mengulum senyum, “Kamu semangat banget, ya?”
“Oh, ya jelas!” sahutku berapi-api. “Akan kubuktikan kalau orang PSM kampus bisa menyulap paduan suara amatir jadi profesional.”
“Padahal semalam kayaknya kamu udah mau nolak?” Markus menahan tawa, geli melihat antusiasmeku.
“Nggak jadi, lah. ‘Kan, udah janji. Nah, karena udah terlanjur nyemplung, menyelam aja sekalian. Totalitas, gitu, loh.”
Kali ini Markus terbahak mendengar analogiku. “Ya, ya. Semoga lancar, ya. Tapi nggak usah kepikiran sampai segitunya, seandainya ada yang nggak sesuai dengan harapanmu. Yang penting kamu udah mencoba.”
Kalimat penyemangat yang klasik, tapi karena yang mengucapkan adalah Markus, kuterima dengan senyuman. Tapi, tak serta-merta senyuman saja.
“Eh. Kamu belum jawab pertanyaanku tadi. Bagusan yang mana?”
Jawaban Markus rupanya bijak juga, “Orang bisa praktik kalau sudah belajar teorinya. Coba latihan di depan kaca. Kamu coba aja dulu sesuai teori, nanti kamu bisa tahu sendiri mana gaya yang cocok buatmu.”
*
Terlalu berlebihan memikirkan sesuatu; salah satu hal yang menenangkan sekaligus tidak menenangkan dari seorang INFJ[1]. Istilah empat huruf itu kudapat dari Kristin yang membagikan kepadaku sebuah tautan menuju laman tes kepribadian, dan hasilnya terbagi dalam enam belas kategori berupa empat huruf. Kristin bilang dia juga INFJ, dan itu menjelaskan betapa banyaknya kemiripan kami—meskipun, dari apa yang kudengar, pembagian enam belas tipe kepribadian oleh Myers-Briggs itu seharusnya hanya dianalisis melalui tes lembaga yang berkompeten, bukannya lewat tes online macam begini. Tapi aku menikmati saja artikel-artikel yang berkaitan dengan INFJ dan merasa sedikit-banyak memang ada hubungannya denganku sehari-hari. Aku tersanjung bahwa tokoh dunia yang berkarakter sama denganku adalah Mahatma Gandhi dan Bunda Teresa dari Kalkuta. Mereka orang-orang besar yang berbelas kasih pada orang lain dan tindakan mereka bisa mengubah lingkungan sekitarnya. Hanya saja, saat sampai pada seorang tokoh besar yang disebut sebagai INFJ antagonis dunia, aku tertegun.
Adolf Hitler, rupanya juga seorang INFJ. Aku bergidik, seketika teringat lagi pada si Bocah Hakim dan rongga matanya yang kosong. Memang benar bahwa INFJ, sepertiku dan Kristin, hebat menggunakan kata-kata dan kharisma untuk memengaruhi orang—aku teringat berapa banyak kakak tingkat yang akhirnya secara sukarela menghibahkan buku teks dan master laporan mereka padaku—INFJ bisa sampai pada tingkat manipulatif kalau bakat itu disalahgunakan. Perlu beberapa hari bagiku untuk tidak lagi kepikiran soal Hitler dan INFJ.
Tapi paduan suara asramaku membuat overthinking-ku kumat. Aku sudah coba untuk latihan dirigen di depan cermin seperti saran Markus. Gerak tanganku kaku dan aku ragu orang akan mengikuti arahanku. Bahkan sampai saat makan malam aku tidak bisa ceria karena pikiranku begitu sibuk sampai Elena bertanya padaku dengan makanan masih di mulutnya,
“Ra, kamu lagi dapet, kah? Kok, diem terus.”
“Hah? Nggak, kok. Ini, lho. Nanti malam latihan, ‘kan, dan aku diminta Kak Prita ngelatih.”
Elena menepuk dahi. “Ya, ampun, latihannya malam ini, ya! Padahal aku mau jajan martabak terang bulan dulu. Tahu, ‘kan, yang jual deket Alun-alun itu, enak banget.”
Memang begitulah Elena. Bukannya mendorongku untuk slow down dan lebih santai menghadapi latihan perdanaku, dia malah membuatku terdistraksi—dan inilah yang aku suka darinya. Dengan sekamar bersama Elena, hidupku jadi tidak terlalu penuh tekanan seperti yang kubayangkan.
“Dasar. Nanti beliin sekalian, deh, buat semua yang latihan!” gerutuku dengan nada bercanda.
Elena melolong. “Bokek, dong! Ini udah tanggal tua!”
“Salah sendiri jajan!”
*
Latihan perdana yang kuantisipasi pun dimulai. Betul kata Kristin, bahwa yang hadir kebanyakan mahasiswi tingkat pertama. Kalau tingkat empat seperti angkatan Kak Prita, sih, maklum karena harus fokus skripsi. Tingkat tiga juga ada yang KKN, kerja praktik, dan menyiapkan tugas akhir. Harusnya tingkat dua masih banyak juga, tapi ini hanya segelintir. Setelah mengawali latihan dengan doa bersama, aku pun bergerilya,
“Kita pemanasan dulu, ya. Biar mulutnya lentur, nyanyi jadi lebih lantang.”
Sambil duduk bersila, aku menyanyikan nada doremiredoremiredo berulang-ulang. Adik-adik asramaku mengikuti; ada yang dengan lantang serta-merta seperti yang diminta, ada yang menggunakan suara seperti sedang bicara bukannya bernyanyi, dan ada yang nadanya meleset.
Aku menahan diri untuk tidak menepuk jidat di depan mereka. Bagaikan langit dan bumi dengan apa yang kulihat di PSM. Kutekan salah satu tuts di keyboard dan berujar, “Pertama pakai iringan dulu, ya. Do-re-mi-re-do-re-mi-re-do.” Pelan-pelan kutekan tuts satu per satu, minta mereka mengikutiku. Ketika nadanya sudah tepat, kunaikkan satu nada dasar, begitu seterusnya. Sambil jalan, kukomentari dengan suara keras, “Lantang tapi bulat, ya. Jangan kayak orang teriak, nanti Suster Eva ngira kita lagi nonton Piala Dunia di kapel.”
Mereka tertawa mendengar kelakarku. Rasanya aku berhasil menciptakan suasana santai. Mulai dari sini akan kubentuk mereka pelan-pelan!
Aku menghabiskan hampir setengah jam untuk pemanasan; agak terlalu lama, tapi biarlah. Ini demi menghasilkan produk yang bagus.
“Kita mulai latihan lagu pembuka, ya.” Aku menyebutkan lagu itu, yang setiap kali memang digunakan sebagai lagu pembuka kalau asrama kebagian tugas paduan suara. “Mungkin yang tahun lalu sudah ikut paduan suara, bisa contohin ke yang lain.”
Perihal ‘mulai dari nol’ seperti yang dibilang Kristin juga ada benarnya. Sebagian besar dari mereka belum pernah menyanyikan lagu yang menurutku sangat mudah itu. Latihan hari itu berakhir dengan hanya satu lagu yang dilatih, mulai dari membaca not sampai menyanyikan liriknya dan menambahkan dinamika keras-lembut seperlunya.
Aku merasa lega ketika menutup latihan. “Hari Jumat malam kita latihan lagi, ya. Teksnya boleh dibawa ke kamar, buat latihan di kamar masing-masing. Ajak juga yang belum ikut, ya.”
“Waduh Kak. Aku Jumat ada presentasi sampai malam,” ujar Imelda, mahasiswi Hukum.
“Aku juga ada tugas kelompok,” timpal Anisa yang kuliah di Institut Pertanian.
Banyak lagi yang tidak bisa latihan hari Jumat dengan alasan serupa.
Cobaanku rupanya belum berakhir. Rasanya percuma mereka berdua puluh empat ini kubentuk sedemikian rupa di awal kalau mereka tidak selalu datang latihan. Tapi inilah kenyataannya, orang punya banyak keperluan lain di luar paduan suara asrama ini, dan akulah yang bodoh karena berharap terlalu tinggi. Kupikir mereka akan sepikiran denganku, yang mau-maunya mengorbankan waktu dan tenagaku untuk paduan suara asrama.
“Aku coba latihan di kamar deh, Kak,” Imelda bicara lagi. Anisa menyusulnya,
“Aku usahakan bisa pulang cepat hari Jumat, Kak.”
Riana yang kuliah Akuntansi menimpali, “Lagunya bagus, Kak. Aku jadi semangat mau latihan lagi.”
“Bagus apanya? Gigiku sampai hampir copot saking susahnya!” sembur Gita, mahasiswi Kedokteran Gigi.
Aku ikut tertawa.
“Lho, yang susah itu malah bagus,” sahut Elena. “Apalagi kalau yang ngelatih Kak Ashira. Mantap! Nanti kita bisa nyanyi sebagus malaikat!”
Aku tersipu tapi senang sampai bingung mau membalas apa. Untungnya Siska, teman seangkatanku juga, menanggapi Elena,
“Cuma, nggak ada malaikat yang gembrot kayak Elena!”
Para mahasiswi itu cekikikan tak terkendali sementara Elena manyun, meratapi nasib sebagai orang yang tertindas. Aku was-was kalau Suster Eva yang kantornya ada di bagian depan asrama sampai mendengar keributan ini padahal ruangan ini harusnya adalah ruang berdoa. Aku bertumpu pada lututku dan bicara agak keras,
“Ya, karena sekarang sudah jam sembilan lewat sepuluh menit, sudah waktunya para malaikat istirahat.” Oke, itu lelucon yang sangat maksa. Buru-buru kusambung ketika mereka mulai diam, teringat omongan Markus soal menyuruh-nyuruh orang, “Imelda, pimpin doa penutup, ya.”
*
Berikut ini adalah postinganku di blog pada akhir bulan, seusai tugas paduan suara itu:
Orang bilang, bernyanyi dengan baik sama dengan berdoa dua kali. Apakah artinya kalau bernyanyi dengan buruk, sama dengan melewatkan berdoa sebanyak dua kali? Atau sama dengan negasi dari berdoa, yaitu berdosa dua kali?
Apa pun itu, sebagai anggota PSM (Paduan Suara Mahasiswa) kampus, aku tentu mau teman-temanku di asrama juga bernyanyi dengan baik untuk tugas di gereja. Dan tanpa latihan, tak mungkin kami bisa mewujudkan hal itu. Jadi, latihan memang sebuah keharusan; tapi ternyata, mengumpulkan orang untuk datang latihan sama sulitnya dengan berburu telur Paskah. Dari tujuh kali latihan, ada yang hanya bisa datang dua kali. Ada yang datang hanya di latihan terakhir. Ada yang datang di latihan pertama tapi tak pernah latihan lagi dan tiba-tiba muncul di gereja pada jadwal tugas. Memang begini risikonya paduan suara yang terdiri atas mahasiswi-mahasiswi dengan agenda sendiri-sendiri.
Tapi aku punya prinsip, dan, menurut pengalaman orang tuaku yang sudah lama menggeluti paduan suara, prinsip itu sudah terbukti akurat.
Mereka yang datang latihan kurang dari tiga kali sampai dengan latihan terakhir, kudatangi di kamar masing-masing. Apa artinya tiga dari tujuh? Tak sampai setengah, bukan? Apakah bisa bernyanyi dengan baik kalau latihan saja tak mencapai setengahnya? Pelan-pelan kuselidiki; apakah di kamar, di luar jam latihan, mereka mencoba latihan sendiri? Atau, mereka sudah pernah bertugas di paduan suara asrama dan cukup mengenal lagu-lagunya? Kalau memang iya, pesan terakhirku pada mereka sebelum bertugas adalah: ‘Do your best, tapi jangan sampai God do the rest karena kamu kurang latihan’. Sebuah sarkasme yang terbungkus gula-gula motivasi.
Pada paduan suara yang ideal, di PSM sendiri misalnya, orang-orang yang tak mencapai setengah jumlah latihan pasti didepak dari daftar tampil. Istilahnya, tak ada komitmen. Tapi, di level asrama, dengan kadar kesibukan dan pengalaman orang yang berbeda-beda, situasi seideal itu bakal membuat paduan suara kami tak berjalan. Jadi yang bisa kulakukan adalah menerima risiko—tapi tak serta-merta menerima.
Alhasil, kami ada bertiga puluh saat bernyanyi dalam misa tadi pagi. Aku sudah mengerahkan semua strategi yang terpikirkan demi tugas itu dan kerja kerasku—kerja keras kami—selama sebulan terbayar oleh ucapan terima kasih Sang Pastor yang di akhir misa menyebut kami ‘PSM’, singkatan dari ‘Paduan Suara Malaikat’.
---
[1] INFJ: Introverted, iNtuitive, Feeling, Judging, salah satu dari enam belas tipe kepribadian menurut Myers-Brigg Type Indicator. INFJ dikenal dengan istilah ‘Advokat’ atau ‘Idealis’.


 roux_marlet
roux_marlet