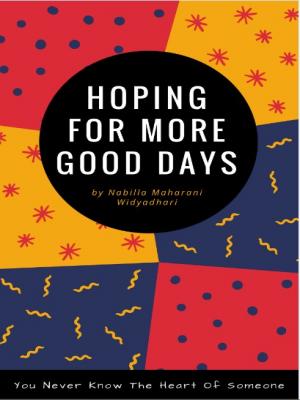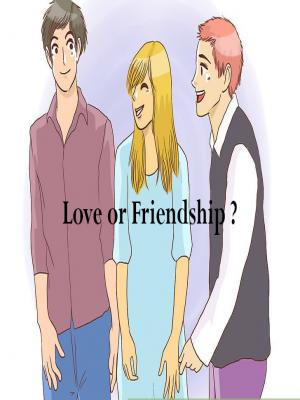“Nggak masalah. Aku, ‘kan, sudah janji.”
Markus masih kelihatan khawatir meskipun aku sudah bilang berkali-kali tentang ini, saat kami latihan PSM.
“Beneran nggak apa-apa? Kamu pasti masih kepikiran soal Dian.”
Ya, aku sudah cerita pada Markus apa yang terjadi terhadap kawanku di hari terakhir ujian tengah semester. Dia juga merasa kasihan pada Dian, tapi, apa yang bisa kami lakukan? Kami dapat libur kuliah satu minggu setelah ujian, dan kabar terakhir yang kudapat dari Dian saat kuhubungi di media sosial adalah, dia mendapat surat peringatan dari pihak kampus dan harus mengulang ujian matakuliah yang satu itu tahun depan. Aku tidak bertanya soal beasiswanya, tapi aku bersyukur dia tidak serta-merta dikeluarkan dari kampus.
“Kamu nggak akan pernah dapat kesempatan kedua untuk mengeluarkanku dari cangkang,” kekehku. “Aku nggak pernah suka olahraga, tapi ini, ‘kan, liburan, dan di sinilah aku sekarang, menemanimu jogging seperti yang kujanjikan minggu lalu. Ayo, jalan. Jangan buat aku berubah pikiran!”
“Oke, oke,” Markus mengangkat tangan pertanda menyerah. “Tapi, bilang-bilang, ya, kalau kamu mulai capek.”
“Iya deh, iya.”
Markus masih memandangiku, seolah menilai ketetapan hatiku. Aku balas memelototinya sambil berkacak pinggang. Akhirnya dia tertawa.
“Ya sudah. Ayo kita ke Gedung Utama. Sabtu pagi begini, pemandangannya ke arah utara bagus banget.”
“Oki-doki.”
Kami berdua berangkat. Markus tadi menjemputku di asrama, diparkirkannya sepeda motor di parkiran tamu, dan mulanya kami harus lari-lari kecil dulu dari asrama sampai ke wilayah kampus (yang menurut perkiraanku tak sampai satu kilometer jaraknya). Sampai di halaman Gedung Utama (yang adalah lapangan tempat kami OSPEK dulu), rupanya sudah ramai. Tak hanya orang, tapi juga ada sekelompok anjing. Beberapa golden retriever, ras anjing berbulu keemasan. Ada juga pudel dan anjing ras lainnya yang aku tak tahu namanya. Tampaknya sedang ada pameran hewan atau semacamnya? Oh, aku harus hati-hati, karena aku punya pengalaman tak enak digigit anjing sewaktu kecil.
Markus mulai mempercepat larinya waktu kami sudah mencapai jogging track di sekeliling lapangan. Saking sibuknya aku mengawasi anjing yang mendekat, aku terlambat menyadari bahwa Markus sudah jauh di depanku. Kutarik napas dalam-dalam, mempersiapkan diri untuk menambah kecepatan juga untuk menyusulnya. Saat itu, kudengar terompet si Fidelia yang sudah kuhapal bunyinya, keras dan jelas. Sambil berlari, aku melihat ke sekitar, mencoba mencari pertanda adanya pencurian—tapi orang-orang terlalu banyak dan semuanya bergerak, jadi aku memilih fokus pada lariku dan punggung Markus beberapa meter di depanku.
Tak butuh lebih dari lima menit berlari untuk membuatku kehabisan napas. Aku mencoba memanggil Markus, tapi suaraku tidak keluar lantaran napas yang tersengal. Paru-paruku seolah mau meledak. Sudah lama tidak berolahraga dan mendadak lari sekencang ini, tentu saja tubuhku tidak kuat. Kepalaku berputar dan pandanganku memburam—rasanya persis seperti bangkit berdiri setelah habis berjongkok dalam waktu lama untuk menyikat lantai kamar mandi asrama—dan kuulurkan tanganku sambil coba berteriak sekali lagi, berharap Markus akan menoleh dan menyadari bahwa aku nyaris pingsan.
Harapanku terkabul. Markus memutar kepalanya seraya menatapku dengan panik, dan aku merasa lega. Terlalu lega sampai tak menyadari sebuah tangan besar sedang terayun ke arahku ....
Sebuah suara yang amat keras bergema di kepalaku dan kegelapan melingkupiku, disertai rasa nyeri yang begitu tajam di balik kelopak mataku, seolah ada yang menaruh pecahan kaca di sana. Aku kehilangan keseimbangan dan masih sempat mendengar Markus berteriak.
Beberapa menit kemudian, aku mendapati diriku sedang terbaring di bangku di pinggir lapangan dengan sekantong es di dahiku, jantungku berdebar-debar kencang sekali. Pandanganku kabur, dan, saat kucoba menyentuh mataku yang sakit, aku baru sadar bahwa kacamataku tidak di tempatnya.
“Ra, kamu nggak apa-apa?”
Wajah Markus ada di atasku. Pertanyaan konyol, membuatku mengernyit.
“Ada apa, ya, tadi?” gumamku sambil mencoba bangun pelan-pelan, dibantu Markus. Kepalaku amat nyeri, rasanya seperti habis dihantam batu, dan es itu tidak terlalu membantu.
“Theo nggak sengaja mukul wajahmu. Dia teman sekelasku.”
Aku menoleh, menemukan seorang pemuda bertubuh tinggi besar sedang berjongkok di sisi bangku. “Maaf, Ra. Aku nggak tahu kamu lagi lari di dekatku. Terlalu semangat senam,” dia berujar, suaranya berat dan dalam, mengayunkan tangannya yang besar dan panjang dengan kikuk. Kalau dia merentangkan tangannya lurus-lurus saat senam tadi, memang benar bahwa dia bisa mengenai orang yang lari di dekatnya.
“Kacamataku ...?” Aku bersuara, bukannya tidak menerima permintaan maaf Theo ataupun sudah memaafkannya, tapi kacamata lebih penting untuk dipertanyakan sekarang.
“Sori, kacamatamu pecah,” sahut Markus dengan nada pahit, menyodorkan kepadaku bingkai kacamataku yang berwarna hitam, bengkok di satu sisi dan patah di sisi lain, satu lensanya hancur sama sekali. Aku tertegun; kuat sekali orang ini, dan tadi kepalaku kena pukul olehnya!
“Aku akan ganti biayanya,” sambung Theo.
“Ng, nggak usah, nggak apa-apa,” aku memaksakan senyum lemah. “Aku masih punya cadangannya, kok.” Meskipun ukuran lensanya sudah kedaluwarsa setahun, karena aku cukup sering ganti lensa—intensitasku membaca berbanding lurus dengan bertambahnya minusku.
“Eh, aku serius, aku ganti aja,” balas Theo.
Aku menggeleng. “Nggak usah. Beneran, aku masih punya satu di kamar.”
Theo tampak setengah lega, tapi pandangannya masih cemas. Markus juga sama cemasnya.
“Kepalamu gimana, Ra?” tanyanya saat melihatku meraba-raba dahiku dengan hati-hati.
“Nggak berdarah, ‘kan?” balasku, masih merabai kepala.
“Nggak ada darah. Tapi, ayo, kita pulang aja sekarang.”
Aku setuju karena aku merasa pusing tak karuan. Tapi, sebelum aku bisa berdiri dengan Markus menarik tanganku, seorang wanita di dekat kami menjerit keras. Aku menoleh, mendapati wanita itu sedang bersimpuh di jogging track sambil menutupi mukanya dengan tangan—dia seperti baru kehilangan sesuatu, dan aku terlambat menyadari bahwa suara terompet si Fidelia sudah tak berbunyi—sejak kapan?
“Kenapa dia?” tanyaku. Markus dan Theo menoleh ke arah yang kutunjuk.
“Kayaknya dia kehilangan ponsel,” Theo yang menjawabku. “Tadi dia udah sempat histeris.”
Kutajamkan telinga dan juga tak menemukan suara nyanyian si Bocah Hakim. Apakah tahap pengadilan juga sudah terlewat olehku selama pingsan tadi? Apakah si pencuri sudah dicatat namanya di buku hitam wanita Fidelia?
Oh, itu semua bukan urusanku. Aku harus melakukan sesuatu untuk meredakan sakit kepalaku.
“Yuk, pulang,” suaraku agak meninggi waktu bicara pada Markus.
“Ra, maaf, ya. Maaf banget,” ulang Theo waktu aku sudah mulai berjalan setengah dipapah oleh Markus.
Aku tak menjawab, dan Theo berpamitan lirih, masih bertanya pada Markus,
“Dia marah sama aku?”
Aku merasakan Markus menggeleng atas pertanyaan terakhir kawannya.
Bukan marah yang kurasakan; aku lebih merasa malu karena kelihatan lemah sekali dan bahkan tak sempat terpikir olehku untuk marah pada Theo. Itu tadi, ‘kan, kecelakaan, bukan salahnya Theo. Aku malu karena Markus harus melihatku dalam keadaan begini—hal yang kekanak-kanakan sekali, tapi aku tak bisa menahannya. Harga diriku seolah jadi menara pasir yang rapuh, runtuh sedikit demi sedikit.
*
Kuakui bahwa aku kadang memang sombong pada beberapa kesempatan, meski berkali-kali juga mengingatkan diri sendiri agar tetap rendah hati; karena menurut ajaran Gereja, kesombongan termasuk salah satu dari tujuh dosa yang mematikan. Sejak kecil, aku bisa terus menerus mencapai prestasi di bidang akademik karena aku memilih untuk rajin belajar daripada bermain. Aku punya caraku sendiri untuk menghibur diri, salah satunya, membaca—dan semakin bertambah umurku, ada tambahannya: menulis.
Orang bilang, anak yang pintar biasanya kutu buku. Dua-duanya benar dalam kasusku, tapi aku tidak suka dikenal sebagai kutu buku yang canggung dan lemah. Aku seorang kutu buku keren yang aktif berorganisasi, seorang penyanyi di grup PSM kampus. Itulah mengapa aku merasa down saat Markus sampai perlu memanggil becak untuk membawaku pulang ke asrama.
Kubilang padanya bahwa aku baik-baik saja, tapi semua orang tahu tidak benar ketika seorang gadis bilang begitu. Aku bersyukur punya kekasih yang begitu perhatian seperti Markus—dia bahkan menawarkan untuk menemaniku melapor pada Suster Eva tentang kecelakaan tadi, yang kutolak mentah-mentah—tapi ini bukan saat yang tepat untuk membicarakan harga diriku. Kuyakinkan dia bahwa aku baik untuk saat ini, kudorong dia untuk pulang, dan aku pun pergi ke kamarku.
Hanya ada Elena di kamar, masih tidur sejak tadi malam. Teman sekamarku yang lain mungkin sedang mencuci baju atau pergi main, toh ini hari Sabtu dan kebanyakan kampus memang libur di hari itu. Tadi, aku berpikir untuk langsung tidur begitu sampai di asrama, tapi memikirkan Markus malah membuatku ingin menulis. Pertama-tama, aku mencuci muka di wastafel lalu mencari kacamata cadanganku. Sebelum memasangnya, aku berdiri di depan cermin di ruang ganti dan memeriksa mataku. Kelihatannya baik-baik saja, tak ada darah, tak ada iritasi. Dari nyeri berdenyut yang masih kurasakan, tampaknya tangan Theo tadi mengenai pelipis kananku—yang dibenarkan dengan fakta bahwa lensa yang masih utuh dari kacamataku yang rusak adalah yang sebelah kiri. Besok, pasti sebelah situ tampak memar. Aku mendengus, kesal dengan tambahan pe-er untuk menyamarkan warna gelap di atas kulitku. Tapi lagi-lagi kusingkirkan rasa kesalku dengan berterima kasih pada Markus.
Kunyalakan laptopku sambil memikirkan Markus sebagai salah satu pencapaian besarku dalam hidup. Di luar ranking sekolah, aku juga punya beberapa prestasi, yaitu di bidang menulis—sesuatu yang aku dapatkan dari hobi membaca. Dengan membaca, aku mengenal berbagai dunia dan gaya tulisan. Penulis favoritku, Joanne Kathleen Rowling si pengarang Harry Potter yang tenar itu, pernah bilang bahwa semua penulis bermula dari pembaca, dan kuakui itu ada benarnya. Aku menulis cerita-cerita fiksi dan mengirimkannya ke berbagai lomba, dan memenangi beberapa. Pernah juga mengirim cerpen ke media cetak, dan diterima beberapa. Kadang aku suka berkhayal dan ke mana-mana selalu membawa buku kecil untuk mencatat ide yang tiba-tiba menempel di kepala—ini terjadi paling sering kalau aku sedang dalam perjalanan naik sepeda, atau menunggu angkot, atau di dalam kereta pulang ke kampung halaman.
Aku juga masih menulis di blog secara rutin dan postinganku yang terbaru adalah sebuah cerita bersambung. Aku menceritakan tentang Fidelia dan melabelinya kisah fiksi—tapi, aku juga mencantumkan bahwa cerita itu berdasarkan kisah nyata. Beberapa kali aku memikirkan ulang soal disklaimer—di dunia fiksi, ada yang namanya fiksi penggemar atau fan-fiction, dan dari sanalah aku mengenal istilah itu—yaitu pernyataan bahwa ada bagian dari karya fiksi penggemar itu yang bukan hak ciptanya, tapi milik pengarang aslinya. Misalnya, bila aku menulis fiksi penggemar di mana Harry Potter itu sesungguhnya anak kandung Lord Voldemort, aku harus menyertakan disklaimer bahwa semua tokoh dan atributnya adalah milik J.K. Rowling.
Tiap kali memposting bab yang baru, aku selalu memutuskan membiarkan label berdasarkan kisah nyata itu tetap di sana sampai ceritanya tamat karena aku berpikir, kalau aku tidak mencantumkan begitu, itu seperti aku mencuri hak cipta cerita hidupku di mana Tuhan adalah penulis asli skenarionya, bukan? Jadi, aku selalu klik ‘post’ tanpa mengubah keputusanku. Fidelia tak pernah muncul untuk menuduhku tak setia pada janji yang, sekali lagi kutegaskan, tak pernah kubuat dengan sukarela.
Kalaupun mereka toh suatu saat muncul dan menghakimiku, aku sudah punya pembelaan. Lagipula, dalam ceritaku tentang Fidelia, kubuat mereka bertiga menjelma jadi unggas sesuai karakteristik yang kulihat. Misalnya saja, si Pengingat, kubuat angsa trumpeter, karena instrument terompet yang dipegangnya. Kemudian si Hakim, dia adalah burung kolibri karena badannya paling kecil dan suaranya indah, seperti burung yang dalam bahasa Inggris disebut hummingbird itu. Sementara si Pemberi, kugambarkan sebagai burung gagak, karena penampilannya yang serbahitam dan bulu-bulu yang juga hitam di bukunya, serta suaranya yang parau kalau mengucapkan kutukan (meskipun aku belum pernah mendengarnya memberikan berkat atau kutuk. Aku hanya membayangkannya sendiri dari percakapan singkatku dengannya). Sisanya adalah sentimenku belaka, karena wanita itu adalah yang paling tidak kusukai dari ketiga Fidelia, dan bagiku burung gagak adalah pertanda segala hal yang buruk.
*
Hari Senin setelahnya, jadwal kuliah sudah dimulai kembali. Dian tampak pucat di kelas.
“Hai,” sapaku, mengambil tempat di sampingnya sambil mengeluarkan ponsel. “Aku punya lagu baru. Mau dengar?”
Dian tersenyum lemah. “Boleh.”
Kami tak membicarakan apa pun soal ujian kemarin, soal beasiswanya, soal surat peringatan yang diterimanya, soal apa yang dia lakukan seminggu terakhir setelah kejadian itu. Aku tak mau melukai perasaannya dengan terpaksa bercerita padaku, tapi aku merasa bahwa di dalam hatinya Dian sudah berjanji. Dia tidak akan mengulangi perbuatannya itu.
Aku hanya penasaran; karena Fidelia bilang nama Dian sudah tercatat di buku, apa artinya dia sudah dikutuk dan kutukan itu akan menyertainya seumur hidup? Padahal dia mestinya menyesal sekarang? Bagaimana caranya penyesalan yang terlambat bisa membatalkan pekerjaan Fidelia?
“Eh, Ra, tahu nggak. Teman SMA-ku kemarin kehilangan hape di Gedung Utama, pas lagi jogging.”
Aku mengerutkan dahi, merasa familier dengan kabar itu. “Gitu. Lantas?”
“Katanya, malamnya, hapenya diantar kembali ke rumah, coba.”
Kalimat Dian membuatku terperanjat. “Bentar. Itu kapan kejadiannya?”
“Hilangnya Sabtu pagi. Dia histeris waktu itu, karena hapenya itu satu-satunya dan dia harus nabung berbulan-bulan kalau harus beli lagi. Nah, sorenya, dia coba hubungi hapenya pakai nomor temannya yang lain, dan, ajaib, nyambung!”
“Berarti hapenya memang nyala? Nggak dimatikan sama pencurinya?”
“Iya, dibiarin nyala. Orang yang nemu hape itu angkat teleponnya, dan mau ngantar ke rumahnya.”
“Hapenya ditemu orang? Apa mungkin nggak dicuri, tapi jatuh?”
Dian menggeleng. “Kata temenku itu, dia memang taruh hapenya di bangku pinggir lapangan pas mau ngebenerin tali sepatu. Karena harus jongkok, dia takut hapenya keluar dari kantong celana terus jatuh dan membentur paving. Terus dia jongkok di situ sambil ngawasi anjing, karena takut. Dia nggak lihat ke arah hapenya terus-menerus, dan dalam semenit itu ada yang ngambil.”
“Lha, bukan orang yang ngembaliin itu? Jangan-jangan dia cuma ngaku-ngaku nemu, padahal dia yang mencuri,” tuduhku.
“Orang yang ngembaliin itu bilang, dia nemu ada hape tergeletak di jalan keluar dari parkiran Gedung Utama.”
Aku tertegun. Jadi si pencuri, siapa pun itu, batal mencuri ponsel? Itukah mengapa terompet si Pengingat berhenti berbunyi?
“Masih ada orang baik di dunia ini, ya, Ra,” pungkas Dian.
Aku membenarkan dalam hati dan mengamini, semoga memang demikian adanya.
*
“Kamu gimana, Ra?”
Malam itu, aku kembali bertemu Markus di latihan PSM dan dia bicara padaku sebelum latihan dimulai.
“Memar dikit, nih,” aku menunjuk pelipisku yang sudah tertutup bedak.
Markus mengamat-amati sambil mengernyit. “Mana? Apa persis di balik frame kacamata?”
“Sekitar situ lah. Udah nggak sakit, kok.”
“Bekasnya udah nggak kelihatan. Syukurlah.”
Bibirku melengkung; Markus saja tertipu dengan make-up, padahal nyerinya masih terasa bahkan tanpa disentuh. Sudahlah, yang penting aku tak tampak begitu lemah di matanya.
“Minusmu nggak apa-apa?” Markus masih bertanya.
“Yang ini lensanya cuma selisih minus setengah, masih jelas kok buat ngelihat,” balasku sambil mendorong jembatan kacamata di hidungku. Lama-lama aku agak risih juga karena kasak-kusuk berdua dengan Markus di tempat umum begini—aku memang aneh. Di satu sisi aku bangga bahwa orang-orang tahu aku sudah punya pacar, tapi di sisi lain aku tak terlalu suka kami terlihat begitu dekat.
“Kalau nonton bioskop bisa, ‘kan, ya?”
Aku mendongak. “Kamu mau ajak aku nonton?”
Markus mengangguk, senyumnya melebar. Aduh, tipikal senyum yang membuat hatiku meleleh sejak pertama kali mengenalnya. “Anime movie. Kamu pasti suka.”
Hatiku melonjak kegirangan, tapi aku tetap jaga imej. “Judulnya apa?”
“Black Butler: Book of Atlantic.”
“Oh my God,” aku tak bisa menahan diri menyeringai, mukaku seketika panas karena terlalu gembira. Kombinasi maut yang aku sukai! Aku tahu serial Black Butler; sebuah film animasi Jepang bertema kebarat-baratan, dengan tokoh utama bangsawan Inggris pada zaman Ratu Victoria!
“Bener, ‘kan?” Markus ikut menyeringai, puas melihat reaksiku. Kedua tanganku kutangkupkan di mulut saking bahagianya.
“Kapan nih?” gumamku masih dengan nada parau, kesulitan menutupi kegiranganku.
“Besok tayang perdana. Besok malam gimana? Ada yang jam 18.30.”
“Eh? Besok?” Aku meragu. “Kalau besok ... hmm, gimana, ya.”
“Kamu udah ada agenda?”
Aku menggigit bibir. “Sebetulnya nggak penting, sih. Tapi aku udah janji.”
“Oh. Lha kalau sudah janji, ya, harus ditepati, dong.”
Kuhindari mata Markus yang menyelidik.
“Janji apa, sih?” tanyanya akhirnya. “Kok, kamu bilang nggak penting?”
“Ini, lho. Aku diminta ngelatih paduan suara di asrama. Anak-anak asrama yang nyanyi. Buat tugas misa bulan depan.”
Markus tertawa. “Lho. Penting, itu.”
“Nggak,” bantahku. “Selama ini juga, paduan suara asrama jalan terus aja tanpa ada yang melatih.”
Saat itu, Mas Tunjung, pelatih kami yang rambut panjangnya dikucir ekor kuda, berdiri di podium dan menepukkan tangan, pertanda latihan akan segera dimulai. Orang-orang mulai bergerak ke tengah ruangan, sementara aku dan Markus juga mengikuti lambat-lambat.
“Nah, ‘kan, sekarang beda, karena ada orang PSM kampus di asrama?” goda Markus.
“Aduh, please, deh.” Kuputar bola mataku sambil meraih teks partitur dari kardus. Markus mengikutiku. “Terus, apa bedanya? Ada atau nggak ada aku pun, paduan suaranya tetap baik-baik saja.”
“Lha kamu sudah janji sama siapa?” tanya Markus sambil meneliti teksnya.
“Kak Prita. Dia pengurus asrama bagian liturgi.”
“Nggak enak, ‘kan, kalau udah janji?”
Aku juga melihat-lihat judul lagu yang akan dinyanyikan hari ini dan menghela napas. “Harusnya aku nggak usah cerita ke anak-anak asrama kalau aku ikut PSM. Toh ada Kristin juga sebenernya, tapi dia selalu sibuk banget. Buat konser yang kali ini aja dia nggak bisa ikut tampil. Tapi, aku juga sibuk, kali!”
“Jangan gitu, lah. Bakatmu, ‘kan, anugerah Tuhan. Nggak ada salahnya kamu persembahkan kembali pada Tuhan lewat padus asrama.”
Aku tak butuh khotbah dari Markus, tapi kurasa omongannya ada benarnya. Dia menambahkan selagi aku merenung,
“Lagian, jadi pelatih, ‘kan, artinya kamu bisa nggalakin orang.”
Kemudian suara bariton Mas Tunjung yang menggelegar menyela pembicaraan kami yang memang sedang terjeda,
“Guys, aku nggak melarang kalian pacaran, tapi at least baris dulu sesuai suaranya. Tenor di tenor, sopran di sopran.”
Markus dan aku buru-buru memisahkan diri. Wajahku panas karena malu sementara Markus disoraki oleh barisan tenor dan bas.
“Lha, kalau yang pacaran tenor sama tenor gimana, Mas?” kilah Markus. Dia mengirim kerlingan geli ke arahku sementara aku tersenyum kecil. Barusan saja Markus bilang tentang menjadi pelatih galak, meski galaknya Mas Tunjung dibawakan dengan cara yang jenaka sehingga membuat kami segan tapi bukan takut.
Oke, demi janjiku dan harga diriku: akan kulatih paduan suara asrama.


 roux_marlet
roux_marlet