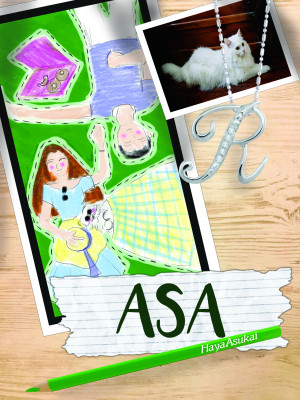Almira
Sepertinya aku butuh lebih banyak olahraga. Badanku yang tidak pernah bergerak lama dua tahun terakhir terasa berat saat mengikuti Ci Ailin berjalan sembari berhenti beberapa kali untuk mengenalkan tiap ruangan di empat lantai kantor.
Tiga puluh menit pertama masih bisa aku hadapi dan dengan semangat aku mencatat fungsi ruangan di lantai 27 yang ditujukan untuk tempat utama bekerja karyawan. Aku bahkan masih ingat penjelasan Ci Ailin di awal.
Mulai dari aula tempat kami berkumpul yang digunakan untuk tempat istirahat dan juga town hall bulanan perusahaan. Kemudian, pantry yang ukurannya lumayan besar dilengkapi dengan kulkas, coffee maker dan rak berisi snack beraneka ragam. Ini baru pantry kantor, aku tidak bisa membayangkan seberapa luas ruang makan perusahaan ini.
Ruang kerja mengambil space paling luas terbagi dua dengan sisi kiri yang diisi bagian promosi mulai dari tim desain grafis, public relation, dan pemasaran. Lalu di sisi kanan untuk tim produksi, sales dan distribusi, serta bagian paling besar milik tim editor. Beberapa karyawan menyapa rombongan kami sebelum kembali berkutat dengan komputer di hadapan mereka. Nice vibe, so far!
Kemudian berjalan sampai ke ujung ruangan, kita akan bertemu dengan deretan pintu dengan papan nama berisi nama pengarang klasik. Mataku berbinar melihat nama Conan Doyle di hadapanku saat Ci Ailin menjelaskan fungsi tiap ruangan sebagai ruang rapat. Kami terus berjalan melewati tiap ruang rapat yang hanya dipisahkan oleh kaca sehingga aku bisa melihat ke dalam ruangan.
Pandanganku terhenti di ruang paling ujung yang memperlihatkan blacklist utamaku sedang duduk bersandar di kursi sambil menyilangkan tangannya di dada. Aku menatapnya sinis. Ia terlihat serius memperhatikan papan tulis di depannya. Telunjuknya beberapa kali bersandar di gagang kacamata hitam sebelum mengangkat tangannya dan menyampaikan sesuatu. Aku menghela napas pelan mengagumi sesaat penampilan pria berkemeja abu lengan panjang itu yang semakin keren dengan kacamata. Andai sifatnya tidak menyebalkan.
Sampai di titik ini, penjelasan Ci Ailin sudah mulai kabur dari ingatanku bahkan tanganku tidak sempat mencatat karena terlalu lama memandang ke dalam ruangan berisi pria menyebalkan itu. Apa karena diskusi mereka tentang promosi buku baru yang terlihat menyenangkan untuk dilihat meski tidak terdengar? Atau karena sosok pria yang tidak mau kusebutkan namanya itu?
Tanpa sadar mataku beradu pandang lagi dengan pria itu. Ia tersenyum sinis kearahku sembari mengangkat cinnamon rolls di hadapannya dan mengigit kue itu perlahan. How dare he? Aku melotot dan langsung mendengus pergi membuat Luna disampingku keheranan melihat tingkahku.
Untungnya Ci Ailin segera menyudahi penjelasannya dan mengarahkan rombongan untuk menaiki tangga menuju lantai 28 yang seingatku adalah ruang percetakan. Kami tidak lama di lantai itu karena tidak banyak yang harus dijelaskan selain waktu operasi mesin di dalamnya. Setelahnya kami berkunjung ke lantai 29 yang berisi ruangan petinggi perusahaan dan kantor Ci Ailin alias ruang HRD. Lalu akhirnya turun ke lantai 26 menuju ruang makan karyawan.
“Oke, guys! Kita istirahat lima belas menit dulu. Kalian bisa menyantap snack yang kita bagikan tadi dan silahkan mengambil minum di ujung kanan ruangan, ya!” Ci Ailin mengeraskan suaranya agar arahan istirahat terdengar sampai ke barisanku di belakang.
Rombongan karyawan baru perlahan mengecil seraya mereka berpisah menuju grup kecil masing-masing dan duduk di kursi ruang makan. Karena belum mengenal karyawan lain, aku mengikuti Luna dan dua teman kuliahnya menuju meja makan paling dekat dengan pintu. Buru-buru aku duduk di sebelah Luna menghadap ke pintu masuk. Sementara dua temannya itu duduk di hadapan kami.
Kembaran Elle Woods tadi duduk di hadapanku. Ia langsung menyodorkan tangannya ke hadapanku dengan senyum cerah. “Hai! Kita belum kenalan, kan? Gue Andin.”
Kukira ia tidak bisa lebih mirip lagi dengan tokoh ikonik dari film Legally Blonde itu. Suaranya lembut tapi penuh keceriaan persis seperti Elle Woods. Ia juga ceriwis dan dengan mudahnya berbicara dengan orang baru. Melihat Luna dan Nisa mengikuti alur yang dibuat Andin dalam obrolan, aku seperti melihat langsung interaksi Elle Woods dengan Margot dan Serena, dua temannya di asrama Delta Nu. Andin tinggal membawa anjing peliharaan seperti Chihuahua ikonik Elle dan… voila! You will get a real life Legally Blonde in a publishing house!
Aku terdiam sejenak membayangkan situasi tadi sebelum tersadar kembali. “Oh… Sorry, aku Almira. Panggil Ami saja.”
“Ha!” cetus Andin tiba-tiba seraya memajukan badannya ke hadapanku membuatku tersentak mundur. Ia tersenyum melanjutkan, “Lo dari Bali, bukan?”
Aku tertegun lalu mengangguk takjub. “Kok tahu?”
“Tuh, kan! Logat bicara lo kental dan Bali banget. Gue dulu pernah punya teman SMA pindahan dari Bali jadi familiar sama penekanan lo di tiap akhir kata.”
Aku mengangguk antusias mendengar penjelasannya. “Wah kamu bisa dengar juga? Hebat, observasimu detail banget, ya!”
Andin membusungkan dadanya bangga mendengar pujianku. Masih dengan ekspresi wajah yang cerah, ia melanjutkan, “Oh iya, kenalin juga yang ini Nisa.”
Andin menunjuk Nisa yang masih asyik bermain ponsel. Tangan kanan Nisa terangkat melambai ke arahku lalu kembali sibuk menekan layar ponsel.
“Itu Luna. Kalian udah kenalan duluan, kan?” Aku mengangguk. “Kita satu jurusan di UI, ambil Sastra Inggris. Terus karena kita ngirim lamaran di tempat yang sama akhirnya jadi dekat selama proses rekrutmen, padahal dulu kita nggak pernah ngobrol di kelas.”
Sepertinya Andin senang membagikan informasi kehidupannya bahkan ke orang yang baru ia kenal. A day with her will never be boring, I think.
“Wow, That sounds like a destiny.”
“Yah, sayang takdir nggak mempertemukan gue dengan pasangan hidup.”
“Lo tuh mikirnya jodoh mulu, Din!” tukas Luna membuat Andin mendengus kesal.
“Gue kan punya target nikah umur dua lima, Lun. Which is dua tahun lagi waktu gue buat cari pasangan sehidup semati.”
Luna hanya bisa menggelengkan kepala pasrah mendengar bantahan temannya itu. Dan aku hanya bisa menelan ludah dan tertawa canggung mendengar rengekan Andin.
“Nah, sekarang giliran lo.” Pandangan Andin beralih menatapku. “Kalau lo dulu kuliah dimana, Mi?”
“Ah… Aku ambil bisnis di Monash. Terus setelah lulus pulang ke Indonesia, lamar-lamar kerja ke beberapa perusahaan sampai akhirnya diterima di Gautama.”
“Wow, jauh-jauh kuliah di luar negeri kenapa balik lagi kesini, Mi? Kalau gue jadi lo, gue bakal stay di Aussie dan cari jodoh di sana. Oh ya, cari kerja juga.”
“Let’s say, takdir juga membawaku kembali ke tanah air,” jawabku canggung namun mengundang gelak tawa dari Andin dan Luna. Sementara Nisa hanya melirik sesaat dari balik ponselnya.
Sesi perkenalan singkat kami harus berakhir ketika Ci Ailin masuk kembali ke ruang makan dan mengarahkan semua karyawan baru untuk kembali ke lantai 27 untuk melanjutkan sesi onboarding.
Kali ini waktunya pengenalan masing-masing tim. Aku duduk di lantai kayu aula di tengah-tengah Luna dan Andin. Nisa duduk santai di atas beanie bags yang menempel ke tembok di belakangku. Rasanya menyenangkan memiliki teman baru di lingkungan yang asing.
“Jadi, pekerjaan kita semua di sini saling terhubung dan tujuan akhir kita adalah untuk menyampaikan suara penulis ke seluruh penjuru Indonesia lewat bukunya,” tutup Ci Ailin setelah menjelaskan tugas masing-masing tim.
“Wah, gue baru tahu ternyata kerja editor ngga cuma baca buku, tapi harus komunikasi intens dengan penulis dan semua tim dan ternyata kerjaan meriksa tanda baca dan teman-temannya itu bukan job kita tapi tim copy editor,” cetus Andin dengan semangat menuliskan semua poin penjelasan Ci Ailin di notebook pink.
Aku mengangguk setuju, “Iya, aku juga baru tahu kalau proses penerbitan buku sepanjang dan serumit ini. Kukira dari penulis ke editor dan langsung dipasarkan. Ternyata harus melalui banyak meeting koordinasi internal, koordinasi dengan penulis, dan juga dengan retailer alias toko-toko buku yang bekerja sama dengan kantor kita, ya. Eh berarti, kita nanti bakal punya tim project untuk tiap buku yang kita handle, kan?”
“Yup, yang gue tangkap juga begitu. Dari naskah yang disortir editor, lalu diskusi dengan tim pemasaran dan sales untuk melihat segmen pasar. Terus nanti tim desain grafis akan buat desain cover dan tim produksi akan coba cetak bukunya untuk dievaluasi lagi dalam rapat. Baru deh setelah oke semua, tim sales mulai distribusi bukunya, tim pemasaran mulai buat iklan, dan tim PR bakal buat kampanye dengan media. Lalu kita, sebagai editor, harus ikut campur di semua tahapnya dan menjaga hubungan dengan penulis.”
Andin terdiam mencoba meresapi kesimpulannya tadi. “Wah, gue jadi grogi sekarang! Kita harus saling bantu buat adaptasi dengan flow kerja ini. Lo semua jangan lupa dan ninggalin gue sendirian!”
Luna langsung mengalihkan pandangan ke arah depan agar tidak dilibatkan dalam drama Andin.
Bisa kurasakan pandangan berbinar Andin beralih ke arahku. Aku hanya bisa terdiam kikuk tidak tahu harus berkata apa selain mengangguk canggung. Namun, ia tetap menunggu jawaban dariku yang bisa memuaskan hatinya.
“Teman-teman, sekarang kalian bisa menuju meja tim kalian masing-masing. Posisinya sesuai arahan saya di tur kantor tadi, ya.” Arahan Ci Ailin menyelamatkanku dari tatapan penuh ekspektasi Andin.
Nisa tiba-tiba menaruh lengannya di pundak Andin dan tersenyum lebar untuk pertama kalinya hari ini. “Let’s go, guys!”
Seakan lupa dengan dramanya tadi, Andin langsung melangkah semangat ke arah barisan meja tim editor denganku dan Luna mengikuti di belakang mereka.
Sampai ke empat baris pertama meja putih panjang dengan empat kursi di dua sisi meja itu. Sosok wanita dengan potongan rambut bob pirang dan setelan blus krem berdiri dari tempat kerjanya meja baris pertama. Penampilannya membuatku teringat Edna Mode tapi yang ini adalah versi terangnya.
“Selamat datang teman-teman.”
Suara wanita itu tegas dan ia kini sudah tersenyum simpul dengan tangan dilipat di dada. “Saya Eri, Chief Editor Gautama Books. Kalian bisa segera duduk di satu baris kosong di depan saya. Setelah ini saya akan minta mentor kalian untuk segera brief pekerjaan dan tugas pertama kalian. Saya harap kalian segera bisa beradaptasi dengan pace kerja kita dan memberikan 100% usaha di tiap pekerjaan kalian.”
What a great way to put an expectation on us. Aku menelan ludah mendengar sambutan dari Bu Eri. Perasaan grogi yang dirasakan Andin tadi seperti menular membuat tanganku berkeringat.
“Oke, off you go, then! Semangat teman-teman!”
Lantas delapan orang yang sedang tertegun di hadapan Bu Eri segera berjalan cepat menuju meja di baris kedua. Aku berani bertaruh sekarang kami memandang ke target tujuan yang sama, tempat duduk yang paling jauh dari pengawasaan ibu ketua tim.
Pada akhirnya, aku tidak tahan dengan pandangan memelas Andin saat tangan kami memegang kursi pojok yang berada di titik buta pengawasan Bu Eri. Sementara Luna dan Nisa sudah duduk bersebelahan di kursi tengah menghadap ke pintu masuk. Dengan langkah gontai aku berjalan memutar ke seberang mereka dan duduk di kursi pertama yang bersebelahan langsung dengan perbatasan tim Editor dengan PR. Tempat duduk yang juga dalam pengawasan langsung mata elang Bu Eri.
Teman tim lain menatapku kasihan. Termasuk Andin yang membisikkan maaf dari kursinya. Aku hanya bisa tersenyum simpul sambil mengacungkan jempol, pertanda bahwa aku tidak apa-apa. Padahal sebenarnya aku bisa saja pingsan merasakan tatapan tajam Bu Eri di belakang punggungku.
¡Por Dios! For God’s sake! What luck I have today…
“Hai! Welcome to the team!” Sambutan hangat dari wanita yang sudah menarik kursinya ke sebelahku mengejutkanku. Bahkan aku belum sempat membalas senyumanya saat ia melanjutkan perkataannya, “Masih ingat gue, kan?”
“Kak Felice, benar?” tanyaku sembari memastikan apakah sosok wanita di sampingku dengan wanita yang tadi pagi membagikan snack adalah orang yang sama.
Kalau dilihat dari baju yang ia kenakan, blus kuning dan rok krem semata kaki, juga senyumannya yang lebar hingga membuat matanya tersenyum di balik kacamata bulatnya itu sih sepertinya benar. Aku sempat ragu ketika melihat penampilannya yang berbeda karena rambutnya yang tadi pagi digerai sekarang sudah tergelung rapi.
“Betul sekali. Namamu… Almira? Kalau tidak salah lihat di form absen.”
Aku mengangguk tersenyum, “Panggil Ami saja, kak. Mohon bimbingannya Kak Felice.”
“Sure! Kita langsung mulai sekarang gimana?”
Aku melirik ke arah teman satu timku yang lain dan terlihat mereka sudah sibuk mendengarkan arahan mentor dengan laptop terbuka. Belum sampai lima menit setelah kami duduk di meja masing-masing dan wajah mereka sudah memancarkan aura gelap.
Aku beralih menatap Kak Felice dengan mata berbinarnya, entah karena semangat menjadi mentorku atau ia tidak sabar melihatku tersiksa. It’s now or nothing. “Oke. I’m ready, kak.”
Okay, maybe not too ready yet. Aku menatap kosong ke arah laptopku yang sudah menampilkan laman admin website Gautama Books. Kak Felice masih bersemangat menjelaskan cara pemakaian website untuk melihat naskah masuk, memasukkan komentar, dan menandai naskah berpotensi.
Untuk aku yang terbiasa menjadi admin di perpustakaan universitasku dulu, mengoperasikan website ini dan menemukan fungsi-fungsi untuk menuju halaman pengajuan reimburse sampai database naskah terkumpul bukan hal baru lagi.
Benar, bukan itu yang membuatku terdiam melongo. Melainkan deretan naskah yang sudah ditandai dengan namaku. Artinya aku harus membaca semua naskah itu dan mencari naskah berpotensi untuk diterbitkan. Tenggat waktunya hari Jumat minggu ini dan rasanya mataku sudah mengeluh sakit sebelum mulai membaca.
“Nah, semua naskah ini dari penulis yang mengirimkan naskahnya ke kita periode tiga bulan terakhir. Lo bisa sortir naskah yang menurut lo menarik. Kita targetkan minggu ini bisa dapat satu naskah per orang. Kedepannya kalian bisa diminta mencari tiga sampai empat naskah dan dari sumber beragam. Bisa dari platform menulis, kompetisi novel, atau nanti kalian akan diajak ke festival literasi gitu. Jadi selagi bisa, take your time to adapt to our work pace.”
Keringat dingin mulai keluar dari pelipisku. Rasanya aku bisa saja pingsan kapan pun. “Satu naskah ini nanti kita kumpulkan dimana, kak?”
“Oh nanti lo bisa masukkan ke folder dengan nama ‘Prio-1’ di drive kita ya. Hari Jumat lo akan presentasikan naskah pilihan lo di editorial meeting. Pastikan lo tahu semua alasan kenapa naskah pilihan lo pantas diterbitkan. Sejauh ini mengerti?”
“I-iya… Mengerti, kak.”
“Duh… Jangan tegang gitu, dong!” Gimana nggak tegang, ini pertama kalinya aku jadi orang kantoran. Kak Felice sepertinya menyadari kegugupanku dan menaruh pelan tangannya di bahuku. “Mi, ingat tujuan kita semua sebagai tim editor Gautama. Membantu suara para penulis di luar terdengar lewat versi terbaik karya mereka.”
Perkataannya tadi membuat saraf-saraf di tubuhku berhenti tegang. Aku tersenyum mengangguk sebelum wanita di sebelahku ini melemparkan bom ke mentalku. “Oh ya, tugas kamu belum selesai. Kita sekarang belajar cara menyusun kontrak penulis dan alur negosiasi dengan penulis.”
Rasanya napasku tercekat. Ada lagi? Aku sudah merasa kewalahan dengan tugas pertama yang berbeda sekali dari saat aku masih bekerja menjadi freelance editor di Bali.
Aku melihat ke sekelilingku lagi dan menemukan wajah terkejut yang sama dari tujuh karyawan baru lainnya. Rambut Andin bahkan sudah acak-acakan dengan tangan yang belum berhenti menulis daftar tugas di notebook pink miliknya.
Well, I guess it’s every newcomer’s problem!


 wrtnbytata
wrtnbytata