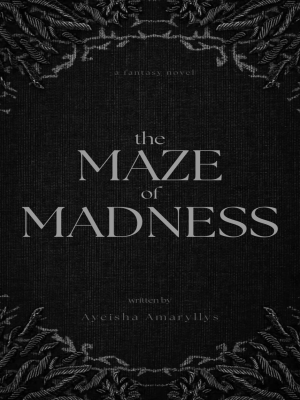Dirga adalah yang pertama kali angkat suara setelah keheningan yang panjang. "Jadi, Asa bereinkarnasi atau tidak?" tanyanya.
Diya menggeleng. "Tidak pernah bertemu dengannya lagi semenjak itu," jawabnya. Dirga mengangguk sekali untuk bersimpati.
Bunyi mengejutkan yang diikuti getaran meja memotong percakapan mereka. Aniara telah meletakkan buku di tangannya ke atas meja dengan keras, hanya berhasil menahan diri untuk tidak benar-benar membantingnya.
Sudut mulut Diya berkedut dan tangannya bergerak untuk mengambil buku itu dari Aniara dengan perlahan seperti menghadapi seekor kucing liar yang mencuri kaos kakinya.
Ada bunyi hantaman keras kedua yang kembali membuat meja kopi itu bergetar lebih kuat dari sebelumnya, seruan 'wow, wow, hei' dari Dirga, dan jari-jarinya mendadak terasa nyeri.
Ketika Diya harus mendongak untuk menatapnya, barulah ia sadar bahwa bunyi keras tadi adalah dirinya yang berdiri dan memukul permukaan meja.
"Karena itu kau meninggalkanku? Karena itu kau membakar lukisan-lukisanku? Karena kau egois? Hanya karena itu?"
Suara yang mengutarakan isi pikirannya itu terdengar asing, retak dan tajam seperti pecahan kaca. Ia hampir tak mengenali suaranya sendiri.
Diya tetap menatapnya lekat, tidak terkejut mendengar ledakan amarahnya dan tidak menjawab sama sekali. Ada emosi yang bergejolak di dalam ekspresi wajahnya, tapi Aniara terlalu marah untuk mencari tahu.
Dirga menepuk bahunya dan ketika Aniara lanjut bicara, suaranya tak sekeras tadi. "Kau– kau menghapusku, Diya. Kau melenyapkan semua hal yang pernah kubuat di masa lalu. Kau menghancurkan karya-karyaku. Kau berniat untuk tidak memberitahuku tentang semua ini agar hanya kau yang tahu." Aniara menggigit bagian dalam pipinya. "Kau membunuhku."
Diya akhirnya bereaksi. Ekspresinya seperti hendak menangis, tapi ia menegakkan punggung. "Aku tidak ingin ada yang menyakitimu termasuk ingatan tentang dirimu sendiri," katanya. "Lebih baik aku menyembunyikan semuanya darimu daripada…."
"Jadi, untuk apa aku lahir, kalau begitu?" potong Aniara.
Itu mengejutkan Diya. "Maaf?"
Aniara menarik napas dalam, merasakan udara dingin karena hujan di luar memenuhi paru-parunya, memerangi kemarahannya. "Di dalam bukumu ini, kau selalu bertanya-tanya kenapa aku selalu dilahirkan hanya untuk mati dan akhirnya kau menyerah mencari tahu, meskipun kau benar. Semua hal pasti punya alasan, termasuk ini. Tidak ada yang tahu kenapa kau tidak bisa mati. Aku juga tidak bisa menebak. Tapi aku tahu kenapa aku terus menerus terlahir kembali."
Ia memotong kalimatnya di sana, menunggu Diya untuk bertanya. Karena jika Diya tidak ingin mendengarkan kata-katanya, maka lebih baik ia pulang dan menghindarkan mereka berdua dari penyesalan yang lebih besar.
"Apa?" tanya Diya.
"Untuk menemanimu," jawab Aniara. "Kau tidak bisa mati karena suatu alasan. Aku tidak bisa jadi abadi karena suatu alasan. Solusi yang paling jelas adalah membuat kematianku tidak permanen."
Ia kembali duduk, kedua lengan memeluk dirinya sendiri dan kepala terbenam di antara dua lutut. "Aku terus terlahir kembali untukmu, Diya. Dunia tidak ingin kau sendirian, jadi kelahiranku selalu ditulis ulang. Tapi jika kau menolaknya, jika kau justru membiarkan kita hidup sendiri-sendiri, keadaanku justru akan jadi sia-sia." Ia mengangkat kepala, menatap Diya. "Jika kau tidak membiarkanku mengingat semuanya, aku tidak punya alasan untuk terus kembali."
Selama bermenit-menit, yang mengisi keheningan mendadak di antara mereka adalah bunyi deru angin dan hujan di luar. Dirga duduk setengah-merosot di sofa dengan kedua lengan menyilang di depan dada. Sejak tadi, ia hanya menonton percakapan Diya dan Aniara tanpa mengatakan apa pun. Sekarang, ia menyenggol kaki Aniara dengan lututnya dan menaikkan sebelah alis.
Kau baik-baik saja?
Aniara menggeleng, berhenti, lalu mengangkat bahu. Di sisi lain meja, Diya sedang memutar cangkirnya dengan ekspresi bercampur aduk.
"Aku tidak pernah memikirkannya seperti itu," akunya, akhirnya berhenti memutar cangkir. "Mungkin aku terlalu tenggelam dalam kesedihanku sendiri. Aku cuma berasumsi jika kau diberi pilihan untuk ingat atau tidak, kau akan memilih tidak karena … karena itulah yang akan kupilih."
"Masalahnya, kau tidak membiarkanku memilih," sahut Aniara.
"Di sini tidak ada pilihan, Aniara. Itu yang aku– kalau kau ingat satu hal, kau akan mengingat semuanya. Jadi pilihannya hanya ingat atau tidak sama sekali," balas Diya, rahangnya mengeras.
"Bukan berarti kau boleh menentukan untukku," tandas Aniara. "Lagipula, Diya, kau bilang kau sudah menerima nasibmu – nasib kita – tapi apa kau tidak kesepian, hidup sendiri dengan semua ingatan tentang masa lalu? Semuanya? Kau tidak jadi gila saja sudah luar biasa."
"Jadi solusimu apa? Apa solusi yang tidak akan menyakiti kita?"
Suaranya terdengar kosong. Aniara melirik buku yang telah kembali ke pangkuan Diya. Mungkin … Diya belum sepenuhnya sembuh. Belum sepenuhnya bebas dari kekangan duka yang seperti tali gantungan di lehernya.
Jadi, ia mencondongkan diri ke depan, meraih ke seberang meja, dan menggenggam tangan Diya.
Ah. Ia ingat ini. Memori tangan mereka yang bertaut semenjak mereka kecil sampai yang terakhir kali, ketika Diya menggenggam tangannya sebelum mati.
"Tidak ada solusi yang tidak menyakitkan di sini," ujarnya. "Ingatkan aku, Diya. Kau harus mengingatkanku. Bagiku akan sakit dan kau juga akan merasa sakit melihatku kesakitan, tapi kalau tidak begitu, tidak ada gunanya kita berdua hidup."
Kedua mata Diya bagai kedalaman sungai yang keruh. Warna mata Aniara persis sama. Maka di sini, tangan mereka bagai jangkar.
"Kau tidak akan membenciku?" tanya Diya, nyaris tak terdengar.
Aniara mendengus. "Aku akan marah padamu. Itu sudah tugasku sebagai saudaramu dan jangan kira aku lupa tentang lukisan-lukisanku yang kau bakar." Ia tersenyum. "Tapi 'benci' itu kata yang kuat. Aku tidak sekuat itu untuk menggunakannya."
Sebuah tangan yang familier mendarat di antara tulang belikatnya dan mendorongnya maju. Aniara tertawa dan menahan tubuhnya dengan satu tangan di atas meja.
"Ayo sana, pelukan," kata Dirga. "Lupakan saja aku ada di sini. Lupakan juga fakta bahwa aku ternyata dilahirkan hanya untuk jadi teman Anya seumur hidup."
Aniara mundur sedikit agar bisa melihat sahabatnya tanpa melepaskan tangan Diya. "Kalau kau keberatan, bilang saja."
"Siapa, aku? Keberatan? Omong kosong. Selama aku masih punya cita-cita dan hobiku sendiri, kenapa keberatan?" Dirga menepuk punggung Aniara sambil tertawa, lalu mendorong Aniara lagi dan meraih bahu Diya untuk menariknya mendekat.
Pelukan itu canggung karena tubuh mereka dipisahkan oleh meja, tapi wajah Diya terletak pas di bahu Aniara dan tak lama, ia merasa bajunya di bagian itu menjadi basah. Setelah tiga menit, bukan hanya Diya seorang yang menangis.
"Hei, Diya, apa kau tahu tentang fakta unik urutan bilangan prima?" tanya Dirga tanpa diminta.
"Aku lulusan Jurusan Perkebunan, Manajemen, dan Sinematografi, mana kutahu," jawab Diya, tertawa di sela isakannya yang sama-sama pelan.
*
Pada deret awal bilangan prima, ada banyak bilangan yang berdekatan, hanya dipisahkan oleh satu angka genap. Tiga dan lima, lima dan tujuh, dan lain-lain. Namun semakin panjang deret bilangan prima, semakin sedikit pasangan bilangan yang berdekatan. Semakin banyak bilangan yang terpisah jauh, sampai lima, enam angka jauhnya.
Namun ketika kau mengira bahwa jarak itu akan menjadi semakin jauh dan kekosongan di antara setiap bilangan prima akan menjadi tak terhingga, kau akan kembali menemui dua bilangan prima yang berdekatan, hanya terpisah satu angka genap.


 aishayara13
aishayara13