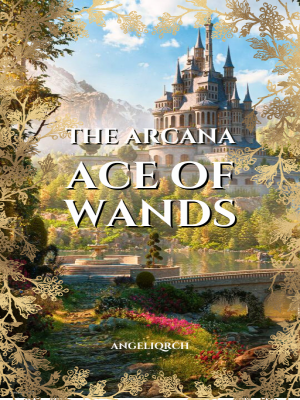Aniara mengelus bulu Buron yang sehat namun kasar sambil mencelupkan ujung kuas ke dalam cat. Ia tidak punya kanvas lain untuk melukis, jadi yang sekarang terbentang di lantainya adalah seragam SMA putih kusam yang dulu ia pakai nyaris setiap hari.
Beberapa kali ia mendapatkan kilas balik mendadak serta melihat bayangan seseorang yang muncul di sekitarnya, tapi pada titik ini ia sudah cukup bisa mengabaikan semua itu.
Ia melukis sebuah lingkaran dengan sempurna dan menghadiahi diri dengan sepotong kue bolu pemberian Dirga dan ibunya. Omong-omong tentang Dirga … apakah pertemuannya dengan Nova sudah selesai? Informasi apa yang ia temukan?
Sebenarnya agak mustahil bagi Aniara untuk menghubungkan identitas sang pencuri lukisan dengan akun buangan yang, meskipun aneh, merupakan salah satu pelanggan setianya. Tapi dia rasa, kalau teorinya tentang dimensi lain benar, semuanya bisa saja terjadi.
Dirga baru menghubunginya menjelang sore, ketika seragam lama Aniara sudah dipenuhi potongan-potongan pemandangan yang dilukis seperti potongan pazel yang tidak cocok.
"Kau tidak akan percaya penjelasanku," adalah kalimat pertama Dirga begitu Aniara mengangkat teleponnya.
"Halo juga buatmu," kata Aniara sinis. "Ada apa? Kau bertemu dengan Nova? Bagaimana?"
"Err, ya, itu dia masalahnya. Kami hanya sempat bertemu sebentar. Dia sepertinya kenal denganku dan langsung kabur," kata Dirga. "Tapi yang paling anehnya bukan itu."
"Lalu?"
"Biar kukirimkan rekamannya padamu. Tolong jangan syok."
"Hah?"
Ping!
Aniara membuka pesan yang baru dikirimkan Dirga dan mengklik video yang ada di sana. Selama beberapa detik, yang bisa dilihatnya adalah interior rumah Dirga dan meja tamu yang dilengkapi bolu dan teh. Kemudian kamera berputar ke pintu depan diiringi bunyi langkah kaki Dirga. Selot pintu dilepas. Pintu dibuka.
Napas Aniara tertahan di paru-parunya.
Ia melihat wajahnya sendiri, dengan matanya dan hidungnya dan mulutnya, berdiri di dalam video, menatap langsung ke arah kamera.
Genggamannya melemas. Ponselnya jatuh ke lantai.
Apa-apaan.
*
Wajah-wajah yang dulunya kabur di semua kilas balik dan mimpinya menjadi jelas. Mata yang mirip dengan matanya menatap balik. Cengiran yang mirip dengan cengirannya.
Apa yang … siapa…?
Aniara mencoba menarik napas, tapi ia justru tersedak udara. Sejak kapan pula ia berlutut di lantai?
"Aniara sudah mati, dia! Kau lihat– lihatlah sendiri!"
"Aniara sudah mati, dia!"
Dia.
Diya.
Dengan liar, Aniara menyambar ponselnya dari lantai dan menghubungi Dirga yang langsung menerima panggilannya. Sebelum sahabatnya sempat mengatakan apa-apa, ia sudah lebih dulu berteriak.
"Dirga, kita harus mencarinya! Aku harus bertemu dengan Diya!"
"Dia? Dia siapa? Nova? Anya, kenapa suaramu begitu? Kau kenapa?"
"Dirga, Dirga, aku harus menemuinya. Aku harus– dia–" Aniara terbatuk. "Aku harus bertemu dengannya."
"Whoa, whoa, oke. Tenangkan dulu dirimu. Kita akan menemukannya lagi, aku janji, aku akan membantumu mencarinya." Sejenak, Dirga terdiam. "Anya, apa yang kau dapatkan?"
"Nama orang itu. Namanya Diya. Pakai huruf Y," kata Aniara dengan napas pendek-pendek. Buron mengeong lembut dan menyundulkan kepala ke lengan Aniara.
"Oh hei, itu kata yang kutemukan di sweater Nova – atau Diya, sekarang."
Aniara secara refleks mengelus kepala Buron dan menggaruk dagunya sampai kucing itu mendengkur. "Sweater? Kau punya sweater-nya?"
"He-eh, berhasil kutarik sewaktu dia kabur."
Aniara memutar otak sambil menahan histeria yang mencoba menelannya hidup-hidup. "Aku tahu. Aku tahu cara untuk menemukannya. Kita harus cepat, dan aku butuh bantuanmu lagi."
"Oke … selama masih dalam batas kemampuanku," sahut Dirga. "Kau mau menjadikan sweater-nya pancingan seperti lukisanmu?"
Aniara menggeleng, meskipun Dirga takkan bisa melihatnya. "Tidak, dia pasti sudah waspada dengan trik seperti itu. Kita pakai cara lain. Apa kau ingat dengan video ibu-ibu yang menampar anak orang di mal? Yang sempat viral?"
"Ingat. Kenapa?"
"Kau ingat tidak, awalnya orang yang anaknya ditampar itu tidak tahu sama sekali siapa yang menampar anaknya? Lalu dia mengunggah video dan foto buktinya ke media sosial dan tidak sampai sehari setelahnya, netizen sudah menemukan akun pelaku dan menerornya habis-habisan," jelas Aniara.
"Huh … ceritanya begitu? Aku tidak tahu," komentar Dirga. "Tapi kenapa kau menceritakannya padaku– oh. Aku paham."
"Jadi, bisa tolong aku?"
"Pada titik ini, Anya, aku melakukan ini bukan hanya untuk menolongmu, tapi juga untuk kedamaian pikiranku sendiri. Kalau aku tidak melihat wajah si edan tadi setidaknya sekali lagi untuk memastikan kalau aku tidak gila, semua ini bakal menghantuiku," celoteh Dirga. Nadanya yang kesal, seperti yang biasa ia gunakan saat seorang pemain catur di TV melakukan kesalahan bodoh, menenangkan saraf Aniara yang terasa diburai.
"Kita harus gerak cepat," kata Aniara, sedikit memotong perkataan Dirga. "Dia mengenalimu, berarti kemungkinan besar dia akan berusaha kabur secepatnya."
"Ya, ya, aku tahu. Ini lagi kuproses." Dirga terdiam sejenak, lalu menyambung, "Orang tua mana yang memberi nama anaknya 'Diya'?"
"Orang tuaku? Maksudku, orang tuanya yang di dunia alternatif," sahut Aniara.
"Astaga, belum cukupkah orang tuamu yang di sini menamaimu 'Aniara'?"
"Apa maksudnya itu?"
"Bukan apa-apa. Daaan … yep, terkirim. Aku sudah mengirim pesan ke teman-temanku di seluruh kota, juga ke grup alumni anak tingkat kita. Cara 'hantu ke hantu' atau lebih tepatnya 'benang merah' … pasti lokasi Nova – sori, maksudku Diya – akan bisa cepat kita dapatkan."
Suatu cengkeraman yang sejak awal menggaruk sisi dalam rusuk Aniara melonggar. Masih ada kemungkinan bahwa Diya telah kabur dan tak bisa ditemukan, tapi….
"Trims, Ga."
Aniara bertanya-tanya apakah Diya, yang seharusnya adalah versi lain dirinya, memiliki Dirga-nya sendiri. Sahabat baik yang, meskipun mengesalkan dan minta disiram air panas, juga memberikan kesejukan air sungai di bawah panas terik dan mengeluarkan uang receh dari dalam saku tanpa diminta ketika uangnya tak cukup.
Mengingat Diya mengenali Dirga – meskipun memanggilnya Rama – mungkin jawabannya adalah iya.
"Omong-omong, kau oke? Perlu aku ke kos-kosan?" tanya Dirga setelah beberapa saat.
"Tidak usah, aku tidak apa-apa. Ada Buron di sini."
"Okelah. Akan kukabari kau kalau ada informasi penting."
Hubungan diputus. Aniara meletakkan ponselnya di lantai dan merebahkan diri dengan lelah di lantai. Rasa penasaran yang sejak awal membakar sebuah lubang di dadanya sekarang masih ada, menjilat sekitaran jantung Aniara dengan lembut, tapi … jujur saja, pada saat ini, dia hanya ingin semua pertanyaannya dijawab.
*
Sebuah pikiran muncul di kepalanya. Aniara mengambil kembali ponsel dan menghubungi nomor ibunya. Panggilannya segera diangkat.
"Halo, Nia?"
"Halo, Bu. Apa kabar di kampung?"
Ibu tertawa halus, seperti helaian kumis kucing ditiup angin. "Harusnya Ibu yang tanya kamu, Nak. Kamu lama sekali tidak menelepon. Ibu kangen."
Aniara meringis, sedikit merasa bersalah. Bagaimana caranya menjelaskan kenapa ia sangat sibuk akhir-akhir ini? "Aniara dapat banyak komisi, Bu. Kemarin sempat sakit juga," jelasnya, sebisa mungkin hanya berbohong sedikit.
"Sakit? Sakit apa, Nak? Sudah baikan?"
"Flu biasa, hari sebelumnya kehujanan. Sekarang sudah sembuh, Bu." Aniara membiarkan Ibu menasihatinya sejenak sebelum mengubah topik. "Bu … boleh Aniara tanya sesuatu? Tapi Ibu jangan kaget."
"Ibu kayaknya sudah kebal kaget semenjak melahirkan kamu, Nia," sahut Ibu. Senyum dan kilat mata iseng di mata ibunya terbayang jelas di benak Aniara. "Ada apa? Ada masalah?"
"Bukan masalah juga sih, Bu. Aniara cuma mau tanya … Aniara anak tunggal, 'kan? Ibu tidak hamil anak kembar?"
Selama beberapa detik yang terasa lama, Ibu tidak menyahut. Lalu, ia berkata, "Nia, kalau Ibu melahirkan anak kembar, jahitan di perut Ibu pasti lebih besar."
"Oh…."
"Kenapa tiba-tiba tanya? Kamu ketemu kembaranmu di jalan atau bagaimana?"
"Dirga yang ketemu, Bu. Ada fotonya juga, memang terlalu mirip denganku cuma berambut pendek. Aniara jadi penasaran."
"Nak, percayalah, kamu yang cuma satu orang tapi tingkahnya kayak anak tikus selusin saja Ibu sayang sampai sekarang, apalagi kalau kamu punya saudara. Mustahil Ibu menelantarkannya atau tidak memberitahu kamu."
Aniara nyengir. "Iya deh, Bu, makasih. Bulan depan Aniara usahakan pulang ke tempat Ibu, ya?"
"Kalau bisa sih, Ibu mau kamu pulang minggu ini."
Cengiran Aniara melebar. "Wah, kalau minggu ini sih, Nia masih sibuk, Bu. Bulan depan deh, janji."
"Bawa Dirga juga, ya. Ibu mau nyoba bikin tar susu kesukaan dia."
"Ini yang anak Ibu yang mana sih, Bu?"
Ibu tertawa. "Dua-duanya!"
Setelahnya, Aniara mengakhiri percakapan dengan hati ringan. Kenapa tidak sejak kemarin dulu ia menelepon ibunya?


 aishayara13
aishayara13