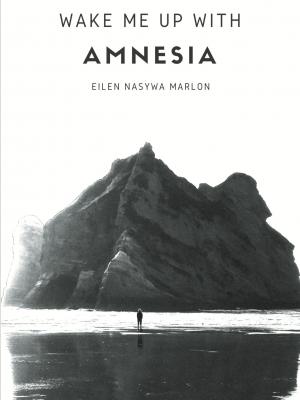<1 Juli 2015, 08:39. Jakarta.>
Gerimis.
Titik-titik air jatuh layaknya jarum yang ditancapkan ke permukaan kain halus baju.
Aku menekan tuas pengait payung, merentangkan plastik yang didesain sedemikian rupa hingga langit berwarna kuning dan merah di bawah naungan logo genset murahan. Seorang gadis kecil masuk berteduh di sampingku.
Suara rintik air perlahan mengabur, dikedapkan lalu lalang kendaraan yang sibuk berpacu mengikuti dan melawan arus lalu lintas. Sirine mobil patroli berhenti setelah lampu berubah merah, trotoar penuh dengan derap-derap sepatu yang mencipratkan lumpur dan tanah. Jaket yang kukenakan bau keringat, angin dingin yang bertiup dari laut tak mampu menusuk melewati kehangatan wol.
“Di tempatku dulu, air biasanya berwarna lebih keruh, tak ada yang setransparan ini. Apa kalian meminumnya?”
“Tidak, tidak. Manusia biasa akan keracunan bakteri jika minum air tanpa memasaknya.” Aku menoleh.
“Hmm, kalian lemah. Kalian harus lebih pandai mengapresiasi apa yang alam berikan, tahu?”
Gadis berambut seputih salju itu tetap melangkah maju, tak menyadari keberadaan saluran bawah tanah yang penutup besinya mencuat, meninggalkan jejak sebuah lubang gelap yang membahayakan tak seorangpun. Kecuali orang yang tak berhati-hati.
Semacam makhluk yang berjalan di sampingku sambil tak mengenakan alas kaki apapun.
Morrigan terjerembab, jidatnya pertama kali menyentuh pegangan kap besi.
“Ugh.”
Ibu-ibu yang membawa kedua anaknya dalam seragam TK menonton, sebuah senyum kecil mengiringi tawanya yang tertahan. Polisi lalu lintas yang sedang berjaga dengan mantel hujan juga mengalihkan pandangannya, bahkan hingga pegawai kantoran yang berlari layaknya ini adalah hari kiamat juga sempat menoleh ke belakang.
Aku menghela nafas.
Nasibku untuk 7 hari ke depan mungkin akan menjadi semakin berbahaya. Namun, tak ada yang memberitahuku bahwa harga diriku sebagai pejalan kaki juga akan diserang.
“Uhm, kau tak apa?” Aku mengulurkan tangan kepadanya.
Morrigan mengelus-ngelus dahinya yang memerah, berubah menjadi benjolan. “Tak kusangka dunia kalian yang damai juga memiliki perangkap yang bertebaran.”
“Mana ada. Kau saja yang lalai dalam berjalan.”
“Tidak, tidak. Ada piranha ganas yang berniat melahap telapak kakiku.”
Gelak tawa dari anak-anak SMA yang baru berjalan pulang semakin menggerus harga diriku. Semoga ponsel mereka tak merekam kejadian ini ke internet.
“Ya, ya. Kita pulang dulu, oke?”
“Jadi, kau mengakui bahwa ada semacam organisasi bawah tanah yang mengincarmu?”
Sial, aku ingin meremas pipinya dan menarik ekornya yang melingkar tersembunyi di punggungnya untuk kembali ke apartemen.
Atau, setelah dipikir-pikir, mungkin paling bagus untuk tak bertindak gegabah.
Aku sedikit menaikkan volume suaraku. “Tak ada organisasi yang mau mengincar orang sepertiku. Dan sekali lagi kau berkata begitu, maka jatah sarapan susumu akan kupotong.”
Sebuah senyum memelas di muka cantiknya yang menyebalkan terpancar terang.
Kemudian keringat dingin.
Lalu, ia dengan cepat mendorongku pergi dari kerumunan.
“Uhm, apapun selain itu, oke?”
Aku kembali menghela nafas, kali ini dalam kelegaan.
Siapa juga yang menyangka bahwa iblis dari dimensi sebelah akan dapat dijinakkan dengan makanan kotak dan susu sapi?
...
...
...
<30 Juni 2015, 22:45. Jakarta.>
Hari itu juga hujan.
Badai besar mengguyur Jakarta. Siaran berita dari televisi membawa berita menyebalkan, banjir. Bencana yang jarang menyebabkan korban jiwa, setidaknya di area sekitar sini, tapi akan menaikkan biaya maintenance apartemen.
Aku menghela nafas, mempercepat gosokan sikat gigiku. Satu detik lupa menghirup udara, insting alami manusia membuatku hampir muntah. Aku dengan cepat berlari ke wastafel terdekat di dapur mini untuk mengeluarkan campuran air dan odol di rahang. Cipratan putih seperti cat yang belum kering di cermin menggagalkan sorak sorai kemenanganku untuk tak membersihkan furnitur klasik ini.
Sekaan kain bekas dari celana sobek-sobekku menghilangkan noda tersebut.
Aku membenamkan diri di sofa.
Tak ada hal yang lebih menyenangkan daripada bersantai di rumah pada hari libur tanpa kuliah, menikmati musik alami yang menggerus jendela-pintu geser yang ditutupi gorden, sambil menonton televisi. Pendingin ruangan tak perlu dibuka, angin dapat masuk melalui sela-sela ventilasi yang memisahkan oksigen dengan nyamuk.
Sebentar lagi perlu kusegel dengan pintu plastik, sih. Badainya sudah mendekati level berbahaya yang dapat membahayakan tingkat kekeringan baju jemuranku.
Kurang popcorn.
Lalu, pacar. Atau teman juga boleh.
“Korban jiwa tidak ditemukan pada kejadian ini, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Pada hari ini, tim sepakbola ...”
Satu ketukan di remote mematikan benda membosankan itu.
Aku mengunyah kacang yang terkandung di dalam coklat batangan merek tertentu. Pecahannya menyangkut di gigi, tak dapat dihilangkan dengan jilatan lidah.
Liburan tanpa siapapun membosankan juga.
Orang tua liburan di luar negeri, saudara yang ikut bersama mereka, tak ada teman.
Kadang cukup menyesal juga tak lebih berusaha dalam memperbanyak relasi. Tapi, mengingat pengorbanan yang perlu dilakukan untuk mentraktir makan dan mentolerir perbuatan buruk mereka, sejujurnya itu membuatku tak ingin mencoba.
Hmm.
Benar juga. Jika saja ada orang yang jatuh dari langit, maka aku akan berteman dengannya.
Hentakan keras menimpa pungggungku.
Beban seberat beton ... mungkin? Tidak, aku akan langsung mati jika tertimpa itu. Tulang punggungku serasa patah, apapun yang singgah di atasku sesekali bergerak pelan, memegang lengan dan pantatku. Cairan mengalir, membasahi sweaterku.
Aku dikutuk?
Hanya dengan sebuah semangat membara yang menggebu-gebu, baru aku bisa menyingkirkan apapun yang mendarat di atasku.
“Huh!” Aku terbaring, menatap langit-langit.
Aneh, tak ada lubang di atap. Lampunya juga masih menyala.
Apa yang terjadi?
“Manusia?”
Pertama kali aku bertemu dengan iblis berwujud manusia satu ini.
Gadis itu terlalu rendah untuk berharap dapat menyaingi tinggi badanku yang dijuluki oleh para tetangga sebagai kandidat pencuri pohon mangga. Rambutnya masih belum berwarna seputih salju, kondisinya lebih seperti abu vulkanik yang baru diletupkan dari sumbernya, setengah menutupi tanduk hitamnya yang mencuat. Pupilnya merah seperti baru mandi darah, tangannya memegang pisau kecil yang tampak dapat menelan cahaya, menampakkan kegelapan tak terhingga. Ia mengenakan pelindung dada dan rok pendek serta jubah bulu binatang, semuanya dalam keadaan robek. Kuku panjang di ujung jarinya bermain-main degan lubang kocekku.
Dia memelototiku, aku pun tertegun tak dapat mengutarakan kalimat.
Kesunyian ini berlangsung hingga petir menyambar, kilatan cahayanya memberiku dorongan untuk menurunkan beban satu ini.
“Hup!” Aku kembali berdiri.
Gadis itu terselip jatuh ke lantai, kakinya menghancurkan meja bundar yang menaruh segelas kopi berasap dalam prosesnya.
Sial, aku sangat yakin ia masih berada di bawah umur. Darimana kekuatan gorilanya?
Dia kembali memelototiku.
Entah kenapa keringat dingin malah mengalir di punggung.
Tidak, tidak. Dia yang entah darimana masuk ke kamarku, menghancurkan furnitur, dan aku malah takut dengannya? “Hei, bocah.”
“Bocah berani memanggilku bocah?” Gadis itu menyipitkan matanya, melototi perutku yang seharusnya tak buncit.
“Kau berbicara seperti orang tua saja, anak kecil?”
“Aku berumur 692 tahun. Berapa umurmu, manusia?”
Pandai sekali melawak. “Jika ada orang yang percaya dengan leluconmu, maka dunia akan kiamat, nak.”
“Dunia ini memang akan kiamat, anak manusia. Dalam 7 hari.”
Sunyi.
Matanya berkedip, alisku naik.
Ia tak menambah penjelasan, aku pun masih memproses perkataannya.
Raut mukanya tak seperti berbohong, tapi mana mungkin kata-katanya adalah kenyataan? “Jadi, dimana orang tuamu, hmm? Kau anak aneh darimana sampai bisa tersesat ...”
Hmm, cairan merah di tubuhnya ...
Cat yang mengering. Pisau di tangannya tak terlihat mainan, ujungnya memantulkan cahaya layaknya peralatan masak tajam. Lagipula, zirah pelindungnya memang berat dan kukunya seperti binatang saja. Apa dia berasal dari dunia lain?
Mana mungkin! Pisau itu adalah hasil dari teknologi dari zaman sekarang, dan zirahnya juga merupakan mainan buatan pendesain handal.
“Hmm? Kenapa kau malah diam?” Gadis itu menggosok-gosok ujung kukunya yang terlihat seperti milik vampire.
“Kurasa aku hanya akan membuang-buang waktu untuk bertanya itu.”
Ia tak memandangku tepat di mata, bukan karena tak berani, tapi lebih karena ia mengacuhkanku. Berjalan ke jendela, ia menyibak tirai bermotif garis-garis untuk melihat ke dunia bawah apartemenku yang lapangan parkirnya berbatasan langsung dengan jalan.
Aku mengambil senjata tajam gadis ini.
“Huh.” Ia menghela nafas besar. “Kau satu dari beberapa orang yang berani mengambil senjataku, dan tidak mengoceh saat berbicara denganku.”
Tapi tak seperti anak-anak normal pada umumnya yang akan merengek dan memberontak saat mainannya diambil, gadis ini hanya melihatku dengan tenang.
“Asal kau tahu saja, tak ada senjata tajam saat berbicara. Disini adalah rumahku, jadi peraturanku yang berlaku, mengerti, bocah?”
“Aku bukan anak-anak! Umurku ...”
“Ya, ya.” Nafas panas kembali keluar dari lubang hidung. “Apa namamu?”
“Morrigan.” Ia duduk di atas meja kaca depan sofa, dimana aku bersumpah dapat mendengar suara sesuatu yang retak.
“Cuma Morrigan?”
“Nama asliku sangat panjang. Kau takkan bisa mengingatnya.”
Hmm, terserah. “Oke, umur?”
“692 tahun.”
Tidak dengan lelucon ini lagi. “Bagaimana jika kau memikirkan angka yang masuk akal bagi seorang manusia untuk hidup?”
“Tapi aku bukan manusia?”
Lehernya serasa ingin kuremas. Tanganku sudah bergerak maju, sebelum kewarasan hati dan pikiran membuatku menariknya balik.
“Oke, 692 tahun. Lalu bagaimana caramu masuk ke sini, jika aku boleh tahu?”
“Portal teleportasi yang menghubungkan dua dunia terbuka saat aku terkena serangan terkuat dari pahlawan. Tapi aku malah terkena efek samping saat sampai ke sini dan ... urrghgh.”
Aku mencubit pipi Morrigan, melebarkan lemak kenyal yang terkandung disana, membuatnya tak dapat mengutarakan sepatah katapun.
Saat selesai, ia mengambil tiga langkah menjauh, mendarat pada vas di samping toilet. “Kau sebenarnya kenapa, manusia? Secepat itukah ingin kubunuh?”
“Kau yang kenapa! Kenapa tak bisa berkata dengan bahasa yang dapat kumengerti, hah?”
Aku menatap pakaian lusuhnya yang terlalu mengundang perhatian, kemudian ke sekelilingku, lalu merasakan ketebalan dompet di pantatku.
Miskin bukanlah deskripsi keadaan ekonomiku. Anggap saja ini sebagai ritual pengumpul karma, pembuang sial, atau hanya sekedar perbuatan mencari pacar yang putus asa. “Lupakan apa yang kukatakan. Bagaimana jika aku membelikanmu baju baru?”
Morrigan melihat ke bawah, ke beberapa bagian pada pakaiannya yang sobek, kemudian kembali padaku.
Kesunyian dalam dialog ini membuatku kesulitan membaca keinginannya.
“Jadi?”
“Pakaianku masih layak pakai.”
“Tidak. Kau tampak seperti pemulung, jadi kau akan ikut denganku. Aku tak ingin kesialan menimpaku, jadi kau harus menerimanya. Titik.”
Matanya terbelalak, memancarkan senyuman kecil yang tak kusangka. “Sekarang?”
“Besok. Sekarang saatnya aku mencerna semua yang terjadi dan tidur.”
Langkahku kuseret dalam ketidakpercayaan, ludah menggumpal di mulut sebelum ditelan balik ke tenggorokan. Masuk ke kamar, aku tak langsung tumbang di tempat tidur, melainkan hanya bersandar di pintu, lampu kamar tak dibuka.
Apakah ini modus penipuan baru yang meninggalkan anak dibawah umur agar nanti aku bisa dilaporkan ke polisi dan hartaku disita?
Mungkin sekalian saja aku pergi ke kantor polisi besok.
Pada saat inilah, makhluk menjijikkan itu muncul.
Berukuran seperti kumbang yang biasa bertengger di pohon negara 4 musim, gerakannya lincah seperti tikus. Bisa terbang, dan membawakan kesan horor yang datang dari reflek otak untuk menjauhkan diri dari kejijikan, meskipun sebenarnya binatang itu juga benci menyentuh kita.
Kecoa.
“Woahh!” Betisku terangkat naik saat makhluk itu merangkak masuk melalui sela-sela pintu.
Seperti mengejarku, aku melompatinya sambil berusaha terjun ke zona aman di kasur, sebelum tersandung kipas angin dan berakhir dengan kepala di karpet, kesakitan.
Kecoa itu merangkak masuk ke sela-sela celanaku, yang otomatis membuatku berdiri, ujung kuku meronta liar berusaha mengeluarkannya dari badan.
Pintu kamar terbuka, cahaya ruang tengah apartemen membuatku perlu menyipitkan mata. Fokusku ada pada gadis yang secara ajaib muncul di tempat tinggalku.
Morrigan melototiku, pupil matanya berubah menjadi sepasang garis merah yang bersinar dalam gelap. Sekotak karton yang bergambarkan susu cair dan sapi perah erat diggenggam, lidahnya menjilati bibirnya.
“Minuman ini mantap, manusia. Apa namanya?”
“Uh, maksudmu susu?”
“Susu, hmm? Akan kuingat.” Ia mendekatiku.
Mau apa dia? Tunggu, itu bukan saatnya. Kebersihan tubuhku adalah prioritas, sekarang.
Dalam langkah yang tak dapat kulihat dengan jelas, Morrigan sudah berada di depanku.
Tangannya terangkat, jempol dan telunjuknya membentuk sebuah capit.
Beberapa detik berlalu hingga akhirnya kecoa itu telah berada di genggamannya.
Wow.
Ia melototiku dalam diam, pupil matanya masih menganggu akal sehat.
Mungkin hanya lensa hasil modifikasi.
“Uhm, terima kasih, Morrigan.” Aku sedikit menundukkan kepala.
Pupil matanya melebar, senyuman semanis malaikat terpampang di antara gigi taringnya ... yang tajam.
“Kalian tak bisa melihat dalam gelap, tak seperti kami iblis. Lain kali kau menemukan barang ini, panggil aku.”
Uhh ... iblis?
“Okee ...?” Aku kehabisan kata-kata, selain mengiyakan perkataannya.
“Terima kasih atas makanannya.” Morrigan memakan kecoa itu.
Kurasa aku perlu membersihkan rumah.
Besok.
...
...
...
<1 Juli 2015, 08:41. Jakarta.>
Dan sampailah pada hari ini.
Melihatnya dari sisi mata masih mengocok-ngocok isi perut. Entah karena perasaan terima kasih karena ia telah membersihkan rumahku dari parasit serangga, atau cinta bersemi dalam pandangan pertama, atau karena tindakan tak berperikemanusiaan yang dilakukannya saat memakan kecoa mentah kemarin.
Jujur, aku tak ingin memikirkannya lagi kalau bukan karena bau busuk dari tutup got ini. Keseluruhan dari narasi yang ia bangun bahwa ia bukan manusia yang lahir dari belahan bumi ini bahkan terdengar lebih waras dibandingkan dengan ... tindakannya kemarin.
“Omong-omong.” Morrigan menoleh ke belakang.
“Hmm?” Dompetku aman berada di saku saat berpapasan dengan seseorang yang mencurigakan.
Aku memelototinya, dia mengalihkan pandangannya.
“Kau belum memberitahuku namamu.” Morrigan memegang tanganku.
Ah, kalau dipikir-pikir memang belum. “Walter Hofman.”
“Oh. Nama yang menyulitkan.”
“Kalau begitu jangan tanya.” Orang tadi telah hilang.
“Jadi, ke mana kita pergi?” Morrigan menyeka air berwarna putih kehitaman di pipinya, baju putih yang biasa kugunakan untuk kuliah menyerap air hujan yang menempel, roknya masih sama seperti yang tadi malam. “Saking besarnya kota ini membuatku seperti akan tersesat saja. Peradaban kalian maju, yah.”
Lagi-lagi dengan cara berbicaranya yang aneh. “Yup, dan seperti yang kukatakan kemarin, aku akan membelikanmu pakaian, bocil.”
“Stop panggil aku bocah! Yang kukenakan sekarang baik-baik saja padahal.” Ia menghela nafas dalam, mengendus-ngendus bajuku. “Hmm, bau keringatmu asam juga ya.”
“Hei, jangan dikatakan begitu!” Aku dengan cepat mendorongnya pergi, seorang bapak-bapak pengemudi ojek online mulai menoleh ke sini dengan tatapan jijik.
Melewati penyebrangan trotoar yang menyisakan waktu lampu hijau semenit, gelombang manusia berlalu-lalang tak berhenti. Gedung kaca ditutupi embun pagi yang menolak bersembunyi, cahaya menyerupai matahari menyeruak diantara jendela yang tak tertutup gorden. Pohon besar yang menghiasi tepian jalan kehilangan daunnya, berdiri dengan sedih sambil melambai-lambai dengan ujung cabangnya. Wiper mobil bergerak dalam porosnya, mendahului burung-burung kecil yang bermain di lapangan basket tanpa pemain.
Hujan telah mereda, menyongsong kehangatan untuk kembali bersinar.
Persimpangan jalan menyilang. Morrigan ikut di sampingku, sesekali memasukkan setetes dua tetes air di kerah leherku.
Ia tertawa terbahak-bahak untuk sesaat, sebelum pipinya kucubit hingga memerah.
Distrik toko muncul saat berbelok ke kanan. Lampu sorot yang didesain untuk memperindah produk tampak remang-remang, cahayanya kadang berwujud sebuah garis blur yang terlintas karena ulah awan, terjatuh ke tanah. Foto artis cantik yang pernah kuimpikan untuk menjadi pacar terseret halus ke samping saat pintu geser membuka. Payung hadiah kulipat di tepian toko dekat tempat sampah multifungsi,
Morrigan sudah mendahuluiku masuk.
Sebelum masuk, aku menoleh ke ruas jalan T sekitar 2 kilometer, di belakang departemen pemadam kebakaran.
Kantor polisi, tujuan akhirku untuk hari ini.
Manekin berwajah datar mengenakan serangkaian pakaian wanita dan unisex berdiri mematung di podium pajangan depan. Rak-rak setinggi rumah dua tingkat memamerkan beragam macam model pakaian yang dikategorikan berdasarkan gender, jenis, dan popularitas. Ada juga yang tergantung strategis di samping cermin, bersamaan dengan karyawan yang siap menunjukkan jalan menuju kamar ganti. Pendingin ruangan berbisik halus sambil meniupkan angin ilahi di sepanjang lorong kayu yang higenis.
“Walter!” Teriakan Morrigan mengejutkan staff toko dan aku yang berada di sampingnya.
“Huh?”
“Apa-apaan dengan baju pengemis yang tipis seperti kertas ini?” Morrigan memegang gantungan sebuah baju tidur wanita berwarna hitam yang memiliki kerah rendah, fitur tembus pandang di bagian sekitar perut dan pinggang. Ia melambai-lambaikannya kepadaku tanpa memedulikan pegawai pria di sampingnya yang mukanya sedikit memerah sambil berusaha tak menatap percakapan kami.
“Uhm ...” Jadi, dia masih belum mengenal tentang baju untuk wanita dewasa. Tapi, kalau dipikir-pikir, tidak salah juga untuk melabeli baju dinas itu sebagai pakaian kurang bahan.
“Itu bukan baju yang akan kubelikan untukmu, nak. Kau masih kecil.”
“Stop menyebutku kecil, dasar manusia!”
Aku mendekatinya, dengan gampang merebut baju yang sekarang dipandang anak nakal ini sebagai harta. Tingginya tak membantu saat ia membuat lompat-lompatan kecil.
Aku mengembalikan baju itu kepada karyawan di sampingku yang tersenyum malu.
“Uh, padahal yang tadi juga bagus.”
“Mungkin beberapa puluh tahun ke depan lagi.” Berjongkok, aku mengambil baju putih-pink berukuran setengah mini dan menempelkannya pada Morrigan.
“Ini pilihanmu?”
Maskot Jepang tentang boneka kucing yang memiliki latar cerita suram, ya? “Kau suka?”
Daripada terlihat cemberut, Morrigan cenderung terkesan. “Owh, kucing. Mereka teman tidur yang imut, namun liar.”
Kukira dia akan merengek dan meminta sesuatu yang lebih keren, atau aneh.
“Kenapa?” Morrigan menatapku dalam diam.
Senyumnya berubah menjadi ledekan yang menjengkelkan. “Tak punya uang, rakyat jelata?”
Lesung pipi keluar saat aku tersenyum sombong. “Mulutmu besar untuk seorang anak kecil.”
Nihilnya bayangan hitam di luar toko membuatku enggan meninggalkan toko bersuhu ruangan ini, meskipun pada akhirnya aku merogoh kocek, mengeluarkan dua lembar uang seratusan ribu kepada kasir. Menerima sebuah bon dan senyum formal dari ucapan terima kasih si kasir, Morrigan keluar dari kamar ganti dengan baju putih yang lucu dan roknya yang masih sama layak pakai.
Bel pintu berbunyi sekali saat langkah kami sinkron menginjak bata di halaman toko.
“Ke mana lagi, manusia?” Morrigan tak melepaskan pandangan dari jalanan yang penuh dengan mobil lalu lalang.
“Kantor polisi.”
“Tempat apa itu?”
Aku melihat ke jam tangan, 13:03, masih siang, tapi tepat waktu untuk memakan sesuatu yang lezat. Tak ada salahnya mengajak bocah ini menikmati nasi omelet atau parfait sebelum meninggalkannya di tangan otoritas resmi, anggap saja sebagai investasi masa depan seandainya kami bertemu lagi di masa depan.
“Lupakan dulu. Cuaca juga sudah cerah, kita makan dulu.”
“Oh ho ho, akhirnya sampai pada saat-saat yang kutunggu.” Morrigan melompat ke atas bahuku. Kakinya lincah melingkar di perutku, tangannya dengan cekatan mengenggam leherku tanpa menimbulkan rasa sakit. “Apa yang akan kau suguhkan, manusia?”
Gedung pencakar langit menutupi lingkaran kuning besar yang sudah berkuasa di langit saat memanjat jembatan penyebrangan yang menghubungkan pintu masuk plaza berbentuk dome, panas menyengat digantikan dengan dinginnya hawa dingin mesin.
Tangga semen yang dipugar dengan cat dan dekorasi lampu voltase rendah menjulang tinggi hinga beberapa puluh meter. Kepala perlu didongakkan hingga membentuk sudut tumpul sebelum menyadari keberadaan satpam dengan pendeteksi besi.
Mereka membuka pintu, menawarkan senyum kaku setelah alatnya tak berbunyi.
Kemegahan mall Heigensfuhr belum terlalu jelas jika dilihat dari pintu masuknya saja.
Berkontras 180 derajat dengan rona gelap pada bagian keamanan, cahaya kuning romantis mengiringi ucapan selamat datang halus yang diutarakan atmosfir pusat perbelanjaan yang langsung mencuat. Troli dorong berkeliaran, para pelanggan memilih produk diskon, anak-anak berkutat menguasai kursi yang berdampingan dengan pohon tiruan. Kios makanan dalam bentuk gerobak mengalahkan mereka yang berbasis toko statis dalam hal harga dan aroma, memperdaya hidung Morrigan yang mulai mengendus-ngendus.
Jika saja ia bukan masih dalam masa pertumbuhan, maka jawaban termudah adalah dengan mengunyah pancake atau hamburger.
Akhirnya, kami berhenti di depan restoran keluarga dengan lambang S besar terpasang di langit-langit toko yang setengah tertutup hiasan lampion. Pelayan toko membimbing kami menuju ke dudukan sofa empuk sambil menyodorkan lembaran menu yang penuh dengan gradasi warna-warni.
“Apa yang kau suka?”
“Orc panggang dengan saus Mercullian, dibalut dengan susu banteng tanduk empat. Untuk makanan penutup, salad dengan Anthellian berry dan roti Panellope setengah terbakar.”
“Huh?”
Mata satu garisnya mengisyaratkan pertanyaan, sedangkan aku bahkan kebingungan apa yang ingin kutanyakan tadi.
... oh, ya, dia masih memiliki mental anak-anak.
“Tak ada makanan fantasi semacam itu, nak. Pesanlah sesuatu yang benaran ada.”
“Oh, maaf. Kukira ini kastilku.”
Kastil??
“Berikan padaku cairan putih seperti yang kemarin. Dan roti. Itu cukup mengisi perutku.”
Seketika, pelayan yang daritadi menatap Morrigan dengan senyum hangat memelototiku seperti aku adalah sampah masyarakat yang baru saja keluar dari penjara.
Aku dengan cepat menggeleng kepala, mengambil satu buku menu yang masih digenggamnya. “Uhm, mohon maklum. Dia masih anak-anak.”
“Aku bukan anak-anak!”
“Oh, ayolah. Jangan terus-terusan menyangkalnya, oke?” Jari tangan dan ujung kukuku seperti mulai berkeringat.
Padahal aku tak berbuat salah ... jangan-jangan dia mengira aku adalah penculik anak-anak?
Lumpia goreng ... eh, anak-anak tak boleh sering makan gorengan. Burger, tak sehat. Paket lengkap nasi ayam dan teh es, tak mungkin akan bisa dihabiskannya.
Pelayan tersebut memberhentikan jariku, membalik halaman dengan professional hingga ke bagian khusus menu anak-anak. Nasi, sayur-sayuran, kuah, ayam goreng, dan french fries. Tak buruk.
“Kupesan ini.”
Pelayan tersebut mengangguk halus. “Dan anda, pak?”
“Burger jumbo.”
Ia mencatat pesanan kami, meninggalkan notanya, kemudian pergi.
Kuharap dia tak melihatku sebagai ayah dari anak ini.
Tunggu. Aku tak mengenalnya, dan dia tak mengenalku. Kenapa aku perlu takut?
“Ada apa, Walter?” Morrigan menggeleng ke sana-sini, jelas terpukau oleh suasana restoran yang hidup, dengan gesekan piring di sudut ruangan, ataupun pemandangan koki bertopi putih tinggi yang langsung memasak dari jendela tembus pandang.
“Aku hampir dicurigai telah menculikmu, nak.”
“Hahah, lelucon yang bagus.”
“Aku tahu, kan? Kau bahkan tak meminta izinku dan tiba-tiba muncul di apartemenku.”
Morrigan mengangguk.
Kami menunggu diam-diam, hingga sosok pelayan tadi kembali muncul.
Menarik nafas dalam-dalam, yang menghampiriku adalah bau fantastis dari daging yang baru dipanggang dengan kematangan sempurna, mendarat di depanku dengan piring dan pelayan sebagai moda transportasi. Pisau dan garpu beralaskan tisu diletakkan tepat didepan tangan kami berdua saat nampan berisikan happy meal Morrigan ditancapkan sebuah bendera dengan emoticon tersenyum.
Tanpa menunggu aba-aba dariku, Morrigan sudah melahap hidangan yang tersedia di depannya dengan kombinasi tangan dan gigi taringnya. Mulutnya berepotan dengan saus saatu aku menyekanya, serpihan tomat dan timunnya hampir jatuh saat kukembalikan ke piringnya, hanya untuk dilahapnya dalam satu kedipan mata.
“Gadis kecil, kau bukan anak lima tahun. Gunakan alat makan, kumohon.”
“Istanaku adalah tempat yang aman untuk melakukannya. Selain tempat itu, kuanggap sebagai medan perang. Tak boleh ada kata bersantai saat hidup di garis depan.” Morrigan menyeka mulutnya, menyeruput botol air mineral hingga plastik pembungkusnya penyok.
Ia tersenyum. “Tapi perlu kuakui, makanan di dunia ini sama enaknya dengan di duniaku.”
“Oh.”
Aku menempelkan tisu di mulutnya, menyekanya dengan lembut.
Morrigan mengangguk. “Terima kasih, manusia.”
“Sama-sama.”
Lalu, dia memelototi burgerku.
Aku dengan cekatan menarik piringku menjauh dari matanya yang mengikuti pergerakan tanganku. “Tidak, tidak. Ini jatahku.”
Morrigan menyipitkan matanya, kemudian bersandar di sofa sambil memegang perutnya, mengeluarkan cegukan ringan. “Apa boleh buat.”
Entah mungkin karena terlalu lapar, atau karena kelelahan yang didapat dari mengasuh anak, tanpa sadar menu fantastis yang biasanya akan mengambil setengah jam waktuku telah habis. Kunyahanku bahkan hampir tak terasa lezatnya, meskipun perutku sekarang memang sudah tak komplain lagi.
Aku meletakkan selembar uang merah yang kutimpa dengan piring burgerku yang masih relatif bersih, jika dibandingkan dengan orang yang duduk di hadapanku.
“Ke mana kita?” Morrigan menggandengku.
Aku juga membiarkannya begitu saja. “Selanjutnya, kurasa kantor polisi.”
“Kantor polisi? Jelaskan padaku fungsi tempat itu.”
“Hmm. Markas dari orang-orang yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban dari wilayah yang menjadi tanggung jawab mereka, kurasa?”
“Oh, seperti ksatria di istanaku.”
Lagi-lagi dengan idiom anehnya. Tapi, sebenarnya sesuai dengan narasi yang daritadi didengungkannya saat mendongeng. Jujur saja, kurasa anak ini juga perlu ke psikolog untuk memeriksa mentalnya, seandainya nanti para petugas akan membawanya dariku.
Ketidaktertarikannya dengan permainan lempar balon atau naik kuda otomatis di area taman bermain anak membuatku sedikit lega karena tak harus menunggu dalam kebosanan. Teleponku berdering sekali saat melangkah keluar dari sudut pos satpam yang kurang pencahayaan, mengindikasikan awan pembawa hujan yang berkumpul untuk mendatangkan hujan nanti malam.
Untuk sekarang, kami berbelok dari distrik perbelanjaan, menuju ke kantor polisi.
Seorang sales bahan bangunan menawariku selembar pamflet. Aku dengan sopan menolaknya. Morrigan memanjat pinggangku, berhenti di bahuku.
“Kenapa kau malah naik ke pundakku lagi, hmm?” Pengalaman menggendong adik terkecilku yang masih balita membuatku kembali reflek memegang punggung tangannya yang kasar, seperti pekerja di lapangan.
“Karena aku sadar diri bahwa aku pendek, duh. Efek samping dari pindah dunia mengurangi tinggi badanku.”
“Aneh. Kau mengakui bahwa kau rendah, tapi bukan anak-anak?”
“Aku memang bukan, manusia. Mau berapa kali kubilang, sih?”
“Oke, oke. Kau menang argumen ini. Aku sudah lelah mengulangi ini.”
Morrigan mengangguk dengan antusias.
Sejujurnya dia tak terlalu berat, kurang lebih massa adikku. Tapi yang membuat lelah menggendongnya adalah cuaca menyengat yang ingin menyerap air di dalam tubuhku, dan tingkahnya yang seperti tak mau diam saja.
“Oi, bocah. Berhenti goyang-goyang. Aku lelah menggendongmu.”
Saat kutoleh ke belakang, putaran pupil matanya abnormal, terlalu cepat. Seperti sedang mencari sesuatu, insting bertahan hidupnya meronta-ronta.
Hanya imajinasiku. “Sebenarnya apa yang kau cari, sih?”
“Musuh. Aku tak tahu sihir atau trik apa yang bisa dilakukan dunia ini.”
“Tak ada hal seperti itu. Ini negara yang aman. Kriminalitas tak terjadi semudah itu.”
Kepalanya didongakkan ke bawah, langsung menatapku. Warna merah pupilnya menyeramkan, tapi cantik. “Benaran?”
Aku tak sengaja menelan ludah. “Untuk apa aku bohong. Jika kita memang disergap perampok, maka nasib kita hanya sial saja.”
Morrigan menepukku dua kali dengan tangan mininya, kukunya yang tajam merobek sebuah jahitan benang di bajuku.
“Oi!”
“Aku percaya denganmu, manusia.” Ia memelototiku.
Huh, rasanya agak ... aneh, dipercayai anak-anak yang tak kelihatan seperti anak-anak.
Aku hanya mengangguk. Di antara salon yang sepi pengunjung dan bank dengan plang nama jumbo yang hampir menyebrangi wilayah perbatasan antar tanah, kantor polisi yang telah lama ditunda pemugarannya berdiri. Dinding-dindingnya memiliki cat yang terkelupas, got pembuangan airnya lancar, namun dengan besi penutup yang berkarat. Lapangan parkirnya sempit, diisi beberapa sepeda motor yang diatur sedemikian rupa sehingga hanya meninggalkan sebuah jalan setapak yang cukup untuk dilewati seorang manusia dewasa.
Petugas yang berjaga di pos depan menatap kami dengan tajam untuk memastikan bahwa kami bukan teroris. Setelah ia yakin, mata malasnya kembali ke televisi jadulnya yang sebagian besar hanya menunjukkan layar semut hitam putih, sebelum menayangkan sebuah pertandingan olahraga. Sepakbola, mungkin.
Memasuki pintu kayu yang memiliki beberapa lubang kecil yang dimakan rayap, aku berjalan lurus terus menyusuri ruang tunggu yang diisi oleh beberapa aqua gelas dan kursi tunggu dari besi yang secara mengejutkan, masih baru. Beberapa pasangan orang tua menunggu dengan sabar, beberapa ada yang terfokus membaca koran harian, yang lainnya merajut pakaian atau bermain game ponsel.
Tujuanku adalah pada resepsionis yang dijaga oleh seorang polwan, lengkap dengan topi dan tampang yang professional, namun dingin.
“Ada yang bisa dibantu, nak?”
Sial, kalau dipikir-pikir, ini baru pertama kali aku masuk ke kantor polisi.
Yah, bukan saatnya gugup. Meskipun terdapat jeda yang signifikan hingga mulutku bisa kembali dibuka. “Uhm ... aku ingin melaporkan anak hilang.”
Polwan itu melototiku dengan ... dingin? Tegas? Tanpa ekspresi? Tahi lalatnya lucu.
Aku balik melototinya, dengan gugup.
“Anu ...?”
Tangannya bergerak ke mejanya, ingin mengambil pistol yang tergeletak di sana!
Bukan, ke dokumen penyelidikan tentang dataku yang nantinya akan dipakai untuk membuktikan keterlibatanku dalam penculikan anak!
Bukan juga, ia hanya ingin mengaitkan kacamata bulat ke hidungnya.
“Maaf, saya agak rabun. Jadi, kuasumsikan dia adalah anak yang anda maksud?” Polwan itu menunjuk Morrigan, sepertinya sedang menganalisis fitur wajah dan keunikan tubuhnya.
“Betul, bu.”
Petugas polisi itu mengeluarkan sebuah buku yang biasa digunakan mahasiswa akuntansi, buku ledger. Bolpoin yang terselip diketuk sekali saat polwan tersebut menatapku dengan sama dinginnya seperti tadi. “Baiklah, saya akan meminta keterangan dari anda untuk mempermudah pencarian orang tua dari anak ini. Saya harap anda bisa membantu.”
“Eh, baik. Tentu saja.”
“Nama anda, nak?”
“Walter Hoffman, bu.”
“Oke. Dimana kau pertama kali menemukan anak ini, dan kapan?”
Kalau tidak salah ... “Pertama kali di rumahku sendiri. Dia tiba-tiba muncul entah dari mana dan menimpaku, padahal apartemen yang kutinggali pintunya terkunci.”
Polwan itu mengangguk, alis matanya naik. “Dan, kapan?”
“Kurasa kemarin malam, sekitar jam 11an, kurasa?”
Lesung pipinya mengkerut. “Anda yakin ini bukan anak anda?”
Morrigan menahan tawanya, sejumlah kecil air liurnya mengenai leherku.
“Sudah pasti bukan, bu. Saya baru berusia 20 tahun.”
Wanita di depanku melepas kacamata, menggeleng-geleng kepala.
“Uhm, ada yang salah, bu?”
Ia menatapku dengan serius, seolah memastikanku untuk tak berbohong. “Anda benar-benar yakin nona manis ini.” Ia berhenti untuk melihat sebentar ke Morrigan, yang diluar dugaan malah memancarkan senyum polos nan manis seperti anak-anak selayaknya. “Bukan kerabat anda, atau sejenisnya?”
“Dapat saya pastikan bahwa tak ada hubungan darah atau keakraban di antara kami.”
“Hmm, oke.” Ia keluar dari ruangan kecilnya yang dibatasi kaca, berdiri tepat di depanku dengan sepatu hak tinggi yang nyentrik. “Kalau begitu, anak ini bisa dititipkan dengan kami untuk sementara waktu.”
“Tentu saja, bu.”
Saat tangannya dipanjangkan hendak menyentuh Morrigan, gadis kecil itu tiba-tiba mendarat di ubin keras yang kupijak. Tangannya lekas menggenggamku, senyum kekanak-kanakannya hilang menjadi seorang gadis remaja yang keras kepala. Tidak, pandangan yang dilepaskannya dingin dan rasional.
“Aku ingin bersama Walter, manusia.”
Dua orang dewasa di tempat ini terdiam sejenak.
“Huh?” Polwan itu menatapku.
“Huh? ... tidak!” Aku mencubit pipi Morrigan. “Kau akan dipersatukan kembali dengan orang tuamu. Jangan bersamaku! Aku saja tak kenal denganmu, bocah.”
Reaksinya selanjutnya pasti adalah menyuruhku untuk jangan memanggilnya anak-anak.
“Masa kau lupa, Walter? Orang tuaku sudah meninggal, dan wasiat terakhirnya adalah menitipkanku padamu, setidaknya hingga aku tumbuh dewasa, bukan?” Mukanya memelas, meskipun aku dapat melihat secercah senyum jahat dibalik gigi taringnya.
Aku menoleh ke polwan itu. Dia malah menoleh balik kepadaku, jelas-jelas telah terpengaruh oleh rayuan anak sialan ini!
“Hah?! Kita bahkan baru bertemu kemarin, anak kecil?”
Morrigan malah berbalik ke polisi itu. “Dia berbohong, bu. Kami sudah kenal lama.”
“Jangan dengar dia, bu. Aku dapat bersumpah aku baru bertemu dengannya kemarin!”
“Oke, oke.” Petugas kepolisian itu mengangkat tangannya yang bersarung tangan putih tanpa noda. Sambil meraih buku dan kacamatanya, ia menarikku beberapa langkah menjauh dari Morrigan yang masih memiliki wajah hampir menangis yang jelas-jelas dipalsukan.
Ia kemudian berbisik. “Saya percaya pada anda, nak. Tapi dari pengalamanku, anak seperti ini akan ngambek dan bertindak ekstrem seperti tak mau makan jika keinginannya tak terpenuhi. Atau mungkin, ia akan tiba-tiba kabur dari kantor ini hanya untuk kembali menemuimu. Bahaya akan muncul jika ia berkeliling tanpa pendampingan.”
“Uh, tapi bukan berarti tanggung jawab ini adalah milikku, dong, Bu. Saya hanyalah mahasiswa biasa yang juga punya kesibukan sehari-hari.”
Polwan itu tersenyum. “Kumohon, nak. Saya juga seorang ibu yang memiliki anak. Saya tahu betul akan sifat anak-anak rewel semacam ini. Anda juga tentu tak ingin dia menderita dengan tak layak, betul?”
“Tapi ...”
“Saya berjanji tak akan lama. Untuk tiga hari saja. Dalam tiga hari, saya akan menghubungi anda dan mengembalikan anak ini kepada orang tuanya, atau jika tak ditemukan, maka akan saya pastikan ia akan bersama dengan saya. Tidak akan merepotkan anda lagi.”
Polwan itu merobek ujung dari selembaran kertas bukunya, menulisnya sejenak, kemudian memberikannya padaku. “Ini nomorku. Hubungi saya jika ada masalah.”
“Urgh, oke. Tapi anda berhutang satu pada saya, bu Carrisa.” Aku akhirnya dapat membaca label nama yang tertempel diatas saku bajunya.
“Tentu.”
Morrigan dengan sigap meloncat kembali ke bahuku, langkahku sedikit sempoyongan saat dibimbing ke pintu keluar. Senyuman ibu itu dan bujukannya mengantarku keluar dari gedung pemerintahan yang sebenarnya benci untuk kukatakan sebagai tak kompeten.
Dan aku telah kembali ke jalanan.
Apakah aku telah melakukan sesuatu yang salah? Harus mengasuh anak ini dalam tiga hari?
“Ini pembodohan.”
“Lebih baik bersamamu dibanding dengan manusia aneh-aneh, duh.”
“Dasar anak jahanam.”
“Terima kasih atas pujiannya, hehe.”
Lagi-lagi senyum sialan itu.
Aku menghela nafas panjang. Huh, lagipula hanya tiga hari. Aku akan lepas dari kejadian aneh ini setelahnya, apapun yang terjadi.
Lagipula, kadang dia juga berperilaku seperti orang dewasa. Seharusnya aku tak akan kelabakan dalam mengurus kebutuhan sehari-harinya.
Mungkin.
Hal itu terjadi dengan cepat sehingga aku tak sempat menyadarinya.
Di samping palang air yang sewaktu-waktu dapat dihubungkan dengan selang pemadam kebakaran, seorang pria yang seharusnya hanya lebih tua beberapa umur dariku merampas dompetku yang tersimpan di kocek. Gerakan tangannya ringan, hampir tak dapat dirasakan jika bukan karena angin kencang yang tiba-tiba menerbangkan daun layu, mata menyipit ke belakang untuk melihat motif gantungan di tepi penyimpan uang bahan kulit itu.
“Pencuri!” Teriakanku nyaring, langkahku dengan cepat dibesarkan saat berputar arah.
Saat mulai berlari, pria pencopet itu juga melakukan hal yang sama denganku. Tapi karena tubuhku yang sama sekali tak pernah dilatih untuk aktivitas keras, aku mulai tertinggal.
Setiap satu meter yang berhasil kutempuh, pria bertopi itu menempuh tiga.
Sama sekali tak ada harapan untuk mengejarnya. Menoleh ke jalan, sama sekali tak ada orang yang sadar akan tindakan pencurian di sore ini. Mobil berlalu lalang, orang berpayung bersiap menyambut hujan, beberapa remaja bermain ponsel, orang di dalam toko berpura-pura tak melihat.
Keringat bercucuran, aku menyeka daguku. Dadaku sakit, wajah tak mampu diangkat untuk melihat ke arah pencuri itu kabur. Aku jatuh terduduk di semen.
Sial, uangku ...
Morrigan memegang bahuku. “Walter, untuk apa kau mengejar manusia itu?”
Aku menoleh kepadanya. “Dia mengambil uangku, sial.”
“Oh.” Lidahnya menjilati bibirnya. Untuk sesaat, aku seperti dapat melihat insting nafsu darah dari gerakan tangan dan tatapannya. “Perbuatan kriminal.”
“M-Morrigan?”
“Poketmu itu, penting?”
Aku menelan ludah. Anak ini tak normal. “Ya. Penting.”
Ia mengangguk.
“Kalau begitu tunggu di sini. Pejamkan mata selama 5 detik.”
Seperti melepaskan iblis dari jelangkung saja. “Hah?”
Kemudian Morrigan melesat.
Kakinya melompat-lompat ringan seperti menginjak busa tempat tidur. Kecepatannya tak masuk akal, telah menyusul visual pria itu yang telah berukuran semut.
Mataku memicing.
Tangan Morrigan pelan, halus meraba celana pencuri itu.
Setelah mendapatkannya, kuku tangannya mencakar topi yang dikenakan pria itu hingga terbelah empat. Tak ada yang menyadari kejadian ini, tak ada yang memperhatikan dengan seksama, semuanya sibuk dengan kegiatan masing-masing.
Bahkan si pencuri itu juga.
Morrigan menghilang.
Mengedipkan mata lagi, ia telah berada di sampingku.
“Woah?!” Aku dapat bersumpah detak jantungku berhenti untuk sesaat.
“Walter?” Morrigan berlagak seperti tak terjadi apa-apa. Siulnya ringan, seperti baru selesai membuang sampah di tempatnya. Ia menyelipkan dompetku kembali kepada sakunya, mencubit kancing yang terjahit di sana.
Oh, wow.
Kupikir aku akan kembali menanyakannya tentang omong kosongnya tentang raja iblis, pahlawan, dan blah blah blah.
Firasatku, dia tak berbohong.
Matahari tenggelam, digantikan rintik-rintik air yang perlahan turun dalam irama konstan dan lembut, seakan memberiku waktu untuk membuka payung. Morrigan langsung menadah masuk, memasukkan tangan mungilnya ke dalam saku yang berisi dompetku. Genggamannya erat, seakan memastikan tak ada lagi yang akan mengambilnya dariku.
“Morrigan?”
“Hmm?”
“Terima kasih.”
“Sama-sama.”
Aku tersenyum kecil, dia menampakkan keseluruhan gigi putihnya.
Kurasa hidup bersama bukanlah masalah.


 zelnexceed
zelnexceed