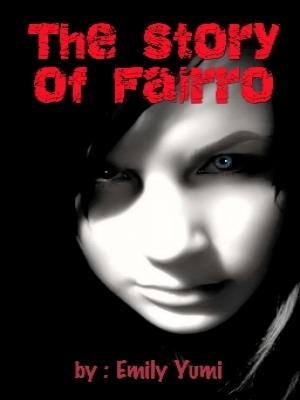Aku dan Dirja dibiarkan menunggu di lobi hotel serba mewah ini. Tidak ada staf, karena mereka semua digiring ke tempat lain oleh Ara. Aku tak tahu mereka akan diapakan oleh gadis itu. Tetapi aku berharap mereka tak akan diancam. Kularikan tatapanku pada lampu gantung kristal tepat di langit-langit bagian tengah lobi ini. Ada beberapa tamu yang keluar masuk. Mereka sama seperti warga-warga Surabaya pada umumnya, bila kulihat dari jenis pakaian yang dikenakan.
“Kamu pilih perempuan gak main-main, Di. Aku jadi khawatir sama nasibmu, cuk.” Di sampingku, Dirja mengedarkan pandangan ke seantero tempat seraya melongo. Aku memilih untuk tidak menjawab ocehannya, karena menurutku ia memang benar.
Mendadak nyaliku menciut karena dengan berani menaruh rasa pada gadis itu. Keluarganya pasti orang ningrat dengan nama yang besar. Dan aku hanyalah kutu kecil di kepala seekor macan.
Ara muncul dari sudut tempat lain diikuti para pegawainya dan dengan segera melanjutkan pekerjaannya yang tertunda. Ia berjalan menghampiri kami masih dengan maskernya seperti biasa.
“Ayo. Aku udah suruh mereka buat nggak membocorkan ini ke Papa. Biaya aku yang nanggung untuk sementara.” Ia memamerkan kunci di tangannya pada kami. “Nih. Kalian bisa istirahat setelah ini. Ayoh!” Ditariknya tanganku agar bersedia mengikutinya. Kutolehkan kepala ke belakang pada Dirja yang menyusul kami. Perlu menaiki lift menuju lantai empat dan berjalan ke kiri untuk sampai di kamar nomor 222. Ara memutar kunci dan membuka pintu. Lampu di dalam menyala dengan otomatis.
“Wih anjir. Mirip kayak hotel-hotel di Bali ya.” Dirja berseru, meletakkan ranselnya secara serampangan dan melemparkan tubuhnya di atas ranjang berukuran king size. Ia menggerak-gerakkan kaki dan tangannya seolah-olah berada di atas tumpukan salju. “Ayang Radi! Nanti malam kita bisa ena-ena nih.”
“Matamu.”
Ara terbahak-bahak di atas kursi santai dekat jendela kaca. “Tadi aku minta antarkan makanan ke sini. Kalian tunggu aja ya.”
“Kamu ngancem mereka ya tadi? Jahat banget.”
“Kalau nggak begitu, nggak ada jaminan biar mereka tutup mulut.”
“Biarin ajalah Papamu tahu. Aku sama Dirja juga gak bakalan lama-lama bersembunyi di balik punggungmu.”
Kudengar desahan napas Ara yang dipanjang-panjangkan. “Yayaya. Untuk sementara ini aja ya.” Aku beranjak berdiri, memilah-milah beberapa baju di dalam ransel. Sebelum aku selesai menarik satu baju, suara Ara terdengar lagi. “Aku tinggal dulu ya. Ke atas sebentar.”
“Mau ke mana?”
“Ketemu Kakak.”
Mencium sebelah pipiku, ia lantas melesat keluar dari kamar. Kudengar decakan lidah Dirja beberapa kali. “Kalian berdua kayak alam. Nggak tahu kapan bakal terjadi bencana, meskipun kelihatannya indah.”
***
Aku duduk di kursi rooftop memandang orang-orang yang juga bersantai dengan segelas limun di atas mejaku. Pesan yang kukirim ke Kenzo dua puluh menit lalu sudah terbaca, namun tidak ia balas.
Zeline: Aku udah pulang. Temui aku di rooftop hotel. Jangan kasih tahu keluarga.
Tak lama, sudut mataku menangkap batang hidung Kenzo yang berjalan cepat celingukan di pintu. Kuangkat sebelah tanganku sebagai kode untuknya. Ia menghampiriku. Duduk di hadapanku, ia mendelikkan mata. “Kamu beneran udah gila, Zel. Kapan pulang? Sama siapa? Ngapain aja kamu di sana?”
Mendengar pertanyaan beruntun yang ia lemparkan, kekehanku keluar. “Chill, bro. Satu-satu nanyanya.” Kusedot minuman di depanku, dan berdeham, “Setelah mendarat, aku langsung ke sini, kok. Aku bawa temanku.”
Ia memajukan wajahnya dan berbisik gaduh, “Yang kamu foto waktu itu?” Melihatku menganggukkan kepala, ia menghempaskan punggung pada sandaran kursi. “You really are a crazy woman.”
Kuraih tangannya di atas meja dan menggenggamnya erat-erat. “Cuma kamu yang bisa aku percaya, Zo. Makanya aku bilang ke kamu aja.” Kusorot matanya dengan tatapan memohon. Ia mendesahkan napas, menyerah terhadapku.
“Kalau ketahuan Papa sama Mama, bukan aku pokoknya. Lagian kenapa sih kudu kamu sembunyiin?”
Kulempar pandangan pada pemandangan gedung-gedung tinggi di seberang sana. “Kalau aku pulang langsung bawa cowok di depan mereka, dikira aku beneran gila.”
“Kamu segini udah gila, Zel!” Kenzo menyambar gelasku dan meminum isinya dengan ledakan emosi. “Pokoknya habis ini kita pulang. Kamu sembunyiin dia di mana? Jangan bilang kalau—”
“Iya. Di sini.”
Matanya semakin melotot horor. Ia lantas mengusap wajahnya gusar. Di tempatku, kukulum senyuman geli berhasil membuat kakakku kelimpungan. “Ah, punya adik gini amat.”
Beranjak berdiri, kucium sebelah pipinya. “Tunggu di lobi ya. Aku mau pamitan dulu.” Lantas, kuangkat kaki dan melimbai pergi setelah mendengar gerutuannya di belakang sana.
Lift bergerak turun ke lantai empat. Beberapa pegawai yang melewatiku melemparkan senyuman dan sapaan. Kuketuk pintu dengan angka 222 di depannya. Tak lama, pintu terbuka, sosok Radi muncul di depanku. Melirik ke atas meja, ada dua piring nasi, dua gelas minuman, dan beberapa makanan camilan. Sudut bibirku terangkat, mereka melaksanakan perintahku dengan baik rupanya. Tak kutemukan keberadaan Dirja di atas ranjang. Namun, suara guyuran air di kamar mandi menjawab pertanyaanku.
“Ketemu Kenzo?”
“Iya.” Menghempaskan tubuh di atas ranjang, aku tertawa mengingat kembali betapa repotnya ekspresi Kakakku itu ketika dihadapkan denganku. “Bahagia banget aku kalau bikin dia kelimpungan. Dosa ya aku jadi adik?”
“Kenapa emangnya?”
Aku beranjak duduk bersila dan mengamatinya yang melanjutkan makan. “Aku bilang ke dia kalau kamu di sini.” Spontan ia tersedak makanannya sendiri, lantas menyambar minuman di depannya.
“Gila.”
“Kamu sama Kenzo kok sama-sama bilang aku gila sih? Aku lebih berani ngomong ke Kenzo karena cuma dia yang biasa aku ajak curhat. Urusan Mama Papa nanti aja deh belakangan.” Aku merangsek mendekatinya dan membuka mulut, memberi kode seperti anak kecil yang menunggu suapan makanan. Dan ia melakukannya. Selesai menelan makanan, kusambar minuman dari gelasnya. “Aku balik ke rumah dulu ya. Kalau butuh sesuatu, kalian bisa panggil room service.”
“Oke. Kabari ya.” Kutolehkan kepala ke arah pintu kamar mandi. Tak kutemukan tanda-tanda Dirja keluar dari sana. Lantas kudaratkan kecupan di sudut bibir dan pipinya. “Ra!” Bisiknya gaduh. Sedangkan aku hanya terbahak-bahak sebelum beranjak keluar dari kamarnya.
*
“Kamu jarang aktif dan sama sekali nggak membalas pesanku, Zeline. Keluargamu bilang kamu liburan. Liburan ke mana?”
Aku turun dari mobil seraya berbicara dengan Anastasia di telepon. Pak Jaka membantu menurunkan koperku, dan kuberi ia kode bahwa aku bisa membawa masuk koperku sendiri. Kenzo di depan setia menantiku. Kuangkat kedua sudut bibirku melihat sikapnya.
“Ada aja pokoknya. Lagipula aku juga butuh liburan.”
“Kalau liburan, kok nggak upload apa pun di medsos?”
Kuputar bola mata meskipun ia tak ada di depanku. “Ya kali tiap keluar rumah harus upload sesuatu, gitu?”
“Ya nggak juga, sih. Tapi jadinya, kan, kukira kamu ada apa-apa.”
Dari arah tangga, kulihat Mama berjalan tergesa-gesa menghampiriku. Kuangkat tangan sebagai kode bahwa aku baik-baik saja tanpa sambutannya. Namun ia keras kepala, ia tetap menghambur memelukku dan menghujaniku dengan ciuman. “I’m okay.”
“Pokoknya kita harus ketemu. Kamu udah dengar berita Nadin Hana sama Ruslan Okta tunangan?”
“Hah? Masa?” Menjauhkan telepon dari jangkauan telingaku, aku berbisik pada Mama, “Aku ke kamar dulu.” Lantas menyeret koperku dan mendekatkan ponsel lagi pada telinga.
“…nggak ikut.”
“Hah? Gimana? Tadi aku nggak dengar.”
Kudengar decakan lidah dari seberang telepon. “Udah hampir seminggu, Zeline. Kamunya aja yang nggak bisa hadir di hari engagement mereka. Dan baru ada kabar sekarang. Kayaknya hari-H nggak lama, deh. Mereka tunangan karena ta’aruf sih. Nggak kaget.”
Benar. Seingatku, Nadin Hana dan Ruslan Okta sama sekali tak pernah diberitakan menjalin hubungan. Oleh karena itu, aku sempat kaget mendengar berita pertunangan mereka setelah sekian lama tidak mengikuti gosip para selebriti ketika aku di Jawa Timur.
“Hm. Jadi gitu.”
“Kita ketemu ya besok.”
“Yaaa. Kalau aku sempat.”
Ia berdecak sekali lagi. “Sok-sokan. Kayak orang yang lagi mau kencan aja.”
“Kalau iya, kenapa?”
“Hah?”
“Eh, eh, aku tutup ya. Mau ngomong sama Mama. Bye, Anastasia!” Lantas, kuputus sambungan secara sepihak. Kupandangi kamarku yang sebenarnya tidak ada siapa pun. Bila dibiarkan, wanita gila itu tidak akan berhenti mengoceh dan mengomel padaku.
Membanting tubuh di atas kasur, muncul sosok Kenzo menghambur masuk ke dalam dan menyusulku berbaring. “Mama panggil Papa, ngabarin kalau kamu udah pulang.”
“Ah, dasar wanita itu.”
“Kamu nggak tahu betapa khawatir dan kangennya mereka berdua sama kamu, Zel.”
Aku merangsek dan merangkul tubuh Kakakku di samping. “Masa sih? Kamu juga, nggak?”
“Ya iyalah, tolol.”
Spontan, kupukul pelan perutnya dan membuatnya mengaduh. “Jahat banget.”
Lengannya beralih merengkuh tubuhku dan mengusap-usapnya. “Jadi, siapa yang kamu bawa?”
Tatapanku berlari menuju langit-langit kamar. Sudut bibirku terangkat naik membentuk senyuman. Pertemuanku dengannya dalam sebuah club malam itu tidak akan pernah aku lupakan selama eksistensiku di dunia. Pelarianku yang awalnya hanya sebagai pelampiasan kekesalanku, bertemu dengan gambaran langsung mengenai eksistensi cinta. “Kamu tahu sendiri jawabanku dia siapa,” jawabku pada akhirnya.
“Kamu ketemu dia waktu di Jawa Timur?” Kuanggukkan kepala tanpa membuka suara. “Pekerjaan dia apa?”
“Melukis dan… menulis?”
“Hah? Seorang seniman? Seriously?”
“Fucking serious.”
Kudengar embusan napasnya. “Kenapa kamu bawa dia ke sini?”
Untuk beberapa detik, aku terdiam. Suasana di kamar hening. Hanya terdengar detak jam dinding yang memenuhi ruangan. Teringat kembali percakapan kami di kaki jembatan Suramadu, tangisannya, dan puisinya. “Aku berusaha mengajak dia berjalan keluar dari kegelapan.”
“Apa?”
Pertanyaan Kenzo gugur begitu saja seperti daun kering yang tertiup angin lantaran kemunculan Papa di ambang pintu. Kami berdua bangkit dari rebahan dan berdiri, kusambut pelukan Papa sebagai perwakilan perasaan rindunya padaku.
“Kamu baik-baik saja, Sayang?”
“Iya, Pa. Maafkan Zeline karena membuat semua orang khawatir.”
“Tidak ada sesuatu yang buruk, kan?”
“No, Papa.”
Papa menepuk-nepuk pipiku dan bahu Kenzo. “Ya sudah. Kamu dan Kenzo sudah makan?”
“Belum, Pa. Kelakuan Zeline udah cukup bikin laperku makin-makin.” Spontan kuinjak kaki Kenzo dan membuatnya mengangkat satu kaki kesakitan.
“Verdammt!” Umpatnya dalam bahasa Jerman.
“Hush!” Tegur Papa di sampingku. Sedangkan aku memilih terbahak-bahak dan mengejek Kenzo dengan juluran lidah. Lantas, kuposisikan tangan melingkari lengan Papa dan beranjak keluar kamar.
Menoleh ke belakang, Kenzo menunjukkan jari tengah padaku.
***
Tatapanku berlari menjamah langit, gedung-gedung tinggi, dan jalanan di bawah sana. Yang dikatakan orang-orang mengenai Jakarta dengan segala kesibukannya tak pernah mati memang benar. Sebenarnya, tidak jauh-jauh dari Surabaya. Kota-kota besar memang seperti itu. Hari sudah menjelang gelap, dan di bawah sana, kendaraan bermotor masih setia memadati jalanan. Kudekatkan cangkir kopi ke bibir dan menyeruput isinya. Tak lama, Dirja merangsek mendekat dan menyodorkan layar ponselnya. Rupanya Pras tengah video call.
“Yayangmu nih.”
“Kalian di mana anjir? Masa aku tinggal kuliah bentar udah ditinggal?”
“Ya sini kalau mau nyusul.”
Layar yang menampakkan wajah Pras bergerak-gerak sebentar, ia mengatur letak benda itu hingga kini tampak jelas ia tengah duduk di sofa kafenya. “Biasanya ada kalian. Jahat banget aku ditinggal. Jakarta gimana?”
Kuangkat bahu dan mencebikkan bibir, “Nothing special.”
“Jadi di sana mau nikah rencananya?”
Apa katanya? “Nikah apaan, cuk?”
“Lah, Dirja yang bilang.”
Spontan kujitak kepala bocah gila di sampingku, sedangkan ia terbahak-bahak. “Pras, iya aku lupa. Dia belum mau nikah. Mau kawin dulu katanya.”
“Heh, njing.”
Kudengar suara tawa mereka berdua. “Makanya, kok aku tadi sempat kaget, Dirja bilang katanya kamu mau nikah. Ngebet banget dirimu.”
“Enggak anjir. Dirja aja yang gendeng.”
Di sampingku, Dirja memutar tubuh dan memperlihatkan gedung-gedung di belakangnya kepada Pras seperti para selebgram. “Tuh, lihat. Tinggi-tinggi, aku ke Surabaya lihat begituan aja melongo. Apalagi di sini. Kapan-kapan dirimu harus nyusul deh.”
“Kalau ada waktu ya. Eh, Zeline mana? Kok gak dengar suaranya?”
Dirja merangsek mendekat padaku. “Zeline ke mana dah?”
“Tadi dia pamit pulang. Ketemu sama keluarganya. Biarin ajalah. Keluarganya juga pasti khawatir banget sama anak itu.”
Pras terkekeh-kekeh di seberang telepon. Ia mengisap vape seperti bagaimana Pras seharusnya. “Tadi Dirja juga sempat bilang, kamu akhirnya jatuh juga ya ke pesona perempuan itu.”
“Wah. Gila. Kalian ghibah tentang aku apa aja ya?” Spontan mereka berdua memecahkan tawa, mirip bapak-bapak di warung-warung kopi.
Tak lama, dari arah pintu, terdengar ketukan berkali-kali. Dirja mencolek pinggangku memberi kode untuk membukanya. Mengembuskan napas, kuletakkan cangkir kopiku di atas meja bundar dan berjalan ke arah pintu. Sosok Ara dengan setelan celana sebatas lutut dan blus merah menghambur melingkarkan lengannya pada leherku setelah meletakkan kameranya di atas meja, lantas menghujaniku dengan kecupan di bibir. “Ra. Ada Dirja,” bisikku gaduh.
“Ya terus?” Apa ia bilang? Gadis ini benar-benar merepotkan.
“Yuhuuu. Ini dia pasangan kasmaran kita.” Kutolehkan kepala dan mendapati Dirja menyorot kami menggunakan ponselnya. Sementara Ara masih bergelayut di depanku. “Heh, heh, ini Indonesia ya. Bukan Amerika. Kalau mau ena-ena sewa kamar lagi sana.”
Gadis itu menolehkan kepala padaku, “Siapa?”
“Pras.”
Memekik, ia menghambur pada Dirja dan menyambar ponselnya. “Haaai, Pras! Astaga lama banget nggak lihat kamu.”
“Bentar doang, belum juga sebulan, dan kalian udah main cium-cium begitu di depan kita?”
Ara terbahak-bahak dan duduk bersila di atas ranjang, memberi kode pada kami untuk mendekat. Ia menarik kerah bajuku dan mengecup pipiku. “Kayak gini?”
“Ara!”
“Kalian berdua memang jancuk.”
Gadis itu semakin terbahak-bahak di tempatnya, bahagia mengusili kami bertiga. Sedangkan aku sendiri, kurasakan pipiku memanas hingga telinga. Di seberang telepon, Pras mendecakkan lidah beberapa kali.
“Asu. Jomlo nyimak.”
“Nyusul ke sini, dong. Kita ngopi bareng lagi.”
“Nanti deh aku kabari ya. Aku lagi ngurusin maba sama urusan lain.” Pras mengangkat muka dan berbicara dengan seseorang. Lantas ia melabuhkan perhatiannya lagi pada layar. “Eh, aku tutup dulu ya.”
“Oke!” Lantas, sambungan ia putus setelah melambaikan tangan. Ara menyodorkan ponsel pada Dirja dan beranjak berdiri. Menghempaskan rambutnya ke belakang. “Nanti malam dinner yuk di restoran hotel. Dekat sama rooftop. Aku biasa nongkrong di sana sama manajerku. Pemandangan dari sana bagus-bagus.” Gadis itu berdiri di ambang pintu kaca, menyugar rambutnya ke belakang. “Tapi nggak sebagus desa kalian berdua sih.”
“Yayaya. Aku udah mulai lapar lagi nih,” Dirja menghempaskan tubuhnya di atas ranjang.
Menghampiri meja dan mengambil kameranya yang hari ini tidak dilindungi tas, aku membuka suara, “Kamu mau ke mana bawa-bawa kamera?” Kuhidupkan kamera di tanganku dan membidik Ara yang masih berdiri menatapku.
“Ya ke sinilah. Aku mau motret sama kalian nanti pas di atas.” Ia berjalan menghampiriku bersamaan dengan beberapa bidikan yang aku tangkap. Tangannya terulur menjauhkan kamera dari depan mukaku. “Aku nggak mau kamu potret. Aku mau kamu lukis.”
Kukedipkan mata dua kali sebelum berkata, “Lukis?”
“Hm. Nanti, kalau semua kanvasmu datang, paint me,” tangannya menunjuk bentang alam di belakangnya, “pakai background itu. Dan juga, kalau kita kembali ke rumah Tante Kinar.”
“Kenapa tiba-tiba?”
“Kamu nggak mau ngelukis aku?”
“Iyain aja deh, Di,” gumam Dirja yang memejamkan mata di atas ranjang. Kulabuhkan perhatianku lagi pada gadis di hadapanku yang mengumbar senyuman. Mengangkat bahu, kulipat bibir menjadi satu garis lurus dan mengangkat alis.
*
Ketika menunggu makanan, ataupun sesudah makan, Ara tak berhenti memotret dan dipotret. Sesekali ia meminta Dirja untuk memotret kami berdua. Aku hanya bisa mendesahkan napas mengikuti semua keinginannya. Ara menyeret tanganku dan berdiri membelakangi gedung-gedung bertingkat, dan berseru pada Dirja. “Ja, fotoin di sini. Yang bagus ya!” Setelah tiga bidikan selesai, ia tak berhenti. Sudah kuduga akan seperti itu. “Eh, coba deh, satu lagi. Tanpa ekspresi deh. Kamu bagus kalau kayak begitu.” Aku perlu mengingatkan diriku sendiri untuk bersabar dan melakukan apa yang ia minta. Usai itu, ia menghampiri Dirja dan mengecek hasilnya.
“Udah, kan?”
Ia mengangkat kepala dari kamera kepadaku, tersenyum lebar. “Udah. Balik, yuk. Kalian habis ini mau ngapain?”
“Mau ngapain, Di? Mau ena-ena sama aku?”
“Najis.” Ara terbahak-bahak mendengar pertengkaran kami berdua, lantas melingkarkan tangannya pada lenganku. “Kayaknya langsung tidur.”
“Kalau di sini ada Pras, pasti diajak dugem. Gak tahu lagi sama itu anak. Polos-polos bahaya.”
“Kalian mau aku pesankan minum dari lounge bar?” Ara melongokkan kepala, membuat rambutnya berjuntai ke depan. “Tapi aku nggak ikut ya, aku harus pulang.” Kulempar pandangan pada Dirja yang meringis di sampingku. Bocah itu mencolek-colek pinggangku berusaha mendapatkan persetujuanku.
“Apa sih. Terserah deh.”
“Bentar ya.” Ara merogoh saku untuk mengambil ponselnya, lantas menghubungi seseorang di seberang telepon. “Dua botol wine ya, antarkan ke kamar 222.” Gadis itu menolehkan kepala menatap kami berdua bergantian, “Merek apa?”
“Terserah, Ra,” desahku. Aku sama sekali tak memahami merek-merek minuman seperti Dirja dan Pras. Sedangkan Dirja di sampingku menyahut dan meminta untuk merek luar saja.
Di sampingku, Ara memberi gestur oke sebelum kembali berkata di seberang telepon, “Jangan yang lokal ya. Oke, makasih.” Lantas, ia memutus panggilan. Sampai di lantai empat, kami perlu berjalan sebentar untuk mencapai kamar 222. Kami bertiga berpisah di depan pintu kamar dengan Ara. Sebelum benar-benar pergi, ia memelukku dan berbisik di dekat telingaku, “Kalau nggak ada Dirja, aku mampusin kamu.” Mendadak, darahku berdesir. Bahaya sekali rupanya nasibku mendapatkan perempuan semacam ia.
“Pulang, Ra.”
Ia berdecak sekali dan memberengutkan muka, lantas mengecup sebelah pipiku sebelum melambaikan tangan dan benar-benar melangkah pergi. Sosoknya hilang ditelan tikungan.
Memasuki kamar, tak kutemukan keberadaan Dirja di atas ranjang. Ternyata ia sedang asyik merokok di balkon. Menyadari keberadaanku, ia menyodorkan satu rokok padaku, “Udud?”
“Nggak.” Lantas, kuposisikan diri di kursi sampingnya. Kularikan tatapanku pada gemerlap cahaya kota.
“Di.”
“Hm.”
“Kayaknya itu cewek nggak main-main sama kamu.” Kutolehkan kepala menatapnya. Ada apa tiba-tiba ia begini? “Aku sempat suudzon sama dia kalau dia cuma mau mainin bocah desa kayak kamu. Tapi, perempuan mana yang rela menghabiskan uang, mengajak ke tempat asalnya, dan membuang-buang waktu bolak-balik dari rumahnya ke sini? Dan itu cuma buat bocah desa kayak kita. Ah, ralat, dirimu lebih tepatnya.”
“Kalau dia ninggal aku, kan masih ada kamu. Katanya kamu yayangku?”
Ia menatapku setengah bergidik. “Kok kalau aku yang dengar jadi merinding ya?”
“Ya makanya, itu yang aku rasain! Tolol.”
“Kita jadi kawan gendeng udah terbilang lama, Di. Makanya aku gak rela kalau nanti ada apa-apa sama dirimu. Apalagi di tengah-tengah perjuanganmu cari nama dan… berusaha bangkit kayak begini.”
Aku terkekeh-kekeh, menekuk lutut dan melempar pandangan ke depan. Kurasakan angin malam mencumbu wajahku. “Makanya jangan ninggalin aku.”
“Kita berjuang bareng,” katanya. Menoleh, ia menatapku dengan senyuman miring. “Inget, bukan lagi dalam ranah sahabat atau bahkan sekadar teman. Kita ini saudara. Susah seneng bareng.” Mengulas senyuman samar, kutepuk-tepuk bahunya bersamaan suara ketukan di pintu. Meletakkan rokoknya di pinggiran asbak, ia beranjak berdiri dan membukakan pintu. Kembali lagi membawa dua botol yang Ara pesan dengan dua gelas berkaki. Ia berseru girang ketika membuka penutup botol dan menuangkan isinya.
Seraya meminumnya, kutatap Dirja dari balik gelas kacaku. Ia benar. Bagiku, tidak ada yang melebihi saudara untukku selain dirinya sendiri.
***
Anastasia menyodorkan dua undangan ke atas meja begitu aku sampai di hadapannya. Hari ini, aku memilih sebuah kafe yang dekat dengan hotel Papa agar aku bisa langsung menghampiri Radi dan Dirja. Kusambar undangan dengan nama Nadin Hana dan Ruslan Okta di bagian depan, dengan nama penerima masing-masing untukku dan Kenzo. Kubaca-baca isinya dengan alis terangkat naik. Tidak, bukan basa-basi dan salamnya, melainkan tanggalnya. Aku tidak akan menghabiskan waktu membaca salam pembukaan dan kalimat-kalimat tai kucing yang selalu sama saja di setiap undangan.
“Hm. Besok banget. Kenapa sih mereka nggak pernah digosipkan pacaran main tunangan aja. Langsung nikah pula. Gak ada spasi banget, nyerepet kayak mulutmu.”
“Heh!” Anastasia melotot padaku. “Ta’aruf katanya.”
“Tai babi.”
“Kamu datang sama siapa? Kenzo? Marcell?”
Kuangkat bahu dan menyedot red velvet di hadapanku. “Marcell mah udah dapat undangan sendiri dia.” Aku tahu bocah itu akan menghujaniku dengan pesan-pesan agar bersedia datang bertiga bersama kakakku. “Tapi… kayaknya aku bakal bawa orang lain selain mereka berdua deh.”
“Hah? Siapa?”
Kugigit bibir bawah dan mengulum senyuman, “Teman.” Sedangkan Anastasia menghempaskan punggung pada sandaran kursi dan mengamatiku dengan tatapan menyelidik. Kumain-mainkan sedotan pura-pura tak tahu.
“Sepulang dari liburan, kamu makin mencurigakan. Jangan-jangan kamu juga diam-diam tunangan,” katanya.
“Ngaco banget. Nggak semua orang diundang ya?”
“Ya iyalah, gila. Aku di sini cuma mau melaksanakan tugasku sebagai manajer yang baik dan budiman. Lagipula aku besok mau quality time sama anak-anak.” Ia memajukan badannya dan menyipitkan mata, “Cerita deh. Kenapa tiba-tiba liburan? Nggak ada kabar lho. Liburan ke mana?”
“Jawa Timur.”
“Sendirian?” Melihatku menganggukkan kepala, ia mendesahkan napas dan menggeleng-gelengkan kepala. “Kurang kerjaanmu ternyata begini ya.”
“Heh, sembarangan. I found something more than special, asal kamu tahu aja.”
Anastasia mengangkat alisnya, “Apaan? Harta karun perang dunia kedua?”
Kulipat bibir membentuk garis lurus dan berpura-pura menampakkan ekspresi berpikir, “Hampir. Pokoknya, berharga melebihi harta karun.”
“Dih, sok-sokan jadi orang misterius.”
Di tempatku, aku terbahak keras-keras melihatnya memberengut kesal. “Ya udah deh ya. Aku tinggal dulu.” Beranjak berdiri, kusampirkan tali tas pada bahu.
“Kamu nggak beneran lagi mau kencan, kan?”
Kukulum senyuman dan memberi ciuman jauh pada Anastasia, mengabaikan teriakannya di belakang yang memanggil namaku.
*
Sebelumnya, aku sudah mengontak Radi agar bersiap-siap sebelum aku sampai di sana. Namun rupanya, aku harus dibuat menunggu lantaran Dirja yang teler berat semalam susah untuk dibangunkan. Kudesahkan napas kesal menunggu anak itu menghabiskan waktu lebih dari lima belas menit di dalam kamar mandi. “Dirja lama!” Mendengar teriakan kekesalanku, Radi terkekeh-kekeh di sampingku. Kutendang kakinya, namun tak lantas membuat ia berhenti tertawa. “Dirja lama banget sih?”
“Maklum, semalam dia teler banget.”
“Tahu begitu nggak aku pesankan minuman.”
Tangan Radi terulur dan membawaku ke dalam rengkuhannya. Mengendus aroma surgawinya, kekesalanku menguap tak tersisa. Aku sendiri heran, apakah kini kehadirannya—dan segala hal tentangnya—sudah menjadi semacam candu untukku? Ia mengecup puncak kepalaku. “Mau ke mana sih?”
“Ada aja pokoknya. Kamu tinggal nurut.” Bersamaan dengan itu, pintu kamar mandi terbuka, diikuti kemunculan Dirja yang telah rapi dengan pakaiannya.
Kulemparkan guling tepat terkena mukanya. “Lama banget, sumpah!”
“Ya maap.”
Usai memastikan mereka berdua siap, kami segera beranjak pergi. Hari ini kukatakan kepada Pak Jaka untuk tidak mengantarkanku karena mobilnya akan kupinjam. Kubawa mereka ke Majnun: Body Addict surganya para borjuis bila sedang mencari tuksedo dan gaun pengantin. Di sana, kita bisa menyewa ataupun membeli langsung. Tempat itu sering aku kunjungi bersama Kenzo bila ia sedang ingin mencari tuksedo baru.
“Lah? Kenapa ke sini? Kalian beneran mau menikah?”
“Dirja bacot.”
Kulangkahkan kaki berjalan mendahului mereka dan menghampiri deretan jas yang dipajang, seraya mengira-ngira ukuran tubuh Radi.
“Halo, Kak Zeline. Mau cari tuksedo untuk Kakaknya lagi?” Pegawai yang sudah cukup hafal denganku berjalan menghampiri dengan senyuman seperti biasa.
“Ah, enggak. Buat mereka berdua.” Kutunjuk Radi dan Dirja dengan dagu. Kulirik Radi dan menyodorkan setelan tuksedo abu-abu padanya. “Coba yang ini, Di. Atau mau pilih-pilih sendiri?” Pemuda itu menyambar tuksedo di tanganku dan segera melesat ke kamar ganti. Kukulum senyuman melihat sikapnya yang ogah-ogahan. Sedangkan Dirja lebih memilih untuk mencari yang cocok dengan seleranya sendiri. Lantas menyusul ke kamar ganti lain.
Tak lama, Radi keluar dari kamar ganti dan berdiri di depan kaca. Untuk beberapa saat aku melongo. Benar kubilang, ia ini memiliki bakat untuk menjadi model!
“Bagus, nggak?”
Pertanyaannya membuatku tersadar dari lamunan. “Bagus. Kita ambil yang itu!” Aku melesat mengambil tuksedo berwarna lain dan menyodorkan padanya yang menampakkan ekspresi kebingungan. Meskipun begitu, ia menurut dan kembali masuk ke kamar ganti. Sementara itu, Dirja keluar dengan setelan jas biru gelap dan memutar tubuhnya di depan kaca. Kutarik bibirku ke bawah, “Nggak tahu, deh. Bagus! Kita ambil yang itu juga ya, Mbak.” Kutolehkan kepala pada pegawai yang masih mengulas senyuman ramah. “Coba deh rekomendasiin buat mereka berdua mana yang bagus ya. Aku mau lihat-lihat dulu.”
“Iya, Kak. Silakan.”
Aku beranjak pergi dan melesat menuju patung dengan gaun-gaun pernikahan dan gaun pesta. Mataku terpaku pada patung yang dilapisi gaun pernikahan dengan lengan yang menjuntai panjang, di bagian dadanya membentuk V panjang hingga di atas pusar.
“Sepertinya ini cocok untuk Kakak.” Seorang pegawai wanita lain yang kehadirannya macam hantu bersuara di belakangku. “Mau mencobanya?”
“Boleh.”
Pegawai itu dengan cekatan melepaskan gaun dari tubuh patung dan menyodorkannya padaku. Memasuki kamar ganti, aku mencoba gaun putih panjang ini untuk selanjutnya dibantu oleh pegawai tadi mengenai penataannya dan penutup kepala.
“Kak Zeline akan menikah ya?” Tanyanya.
“Ah, enggak. Saya hanya iseng.” Dan jaga-jaga bila aku benar-benar akan menikah nantinya. Kutelan jawaban itu ke dalam kerongkongan. Usai menata gaun, kutatap diriku sendiri di depan cermin besar dan memutar tubuh.
“Cocok untuk Kakak.”
Tak lama, dari samping, kudengar suara Radi yang semakin mendekat. “Ra, aku nggak tahu ini cocok apa enggak. Menurutmu—” Kalimatnya terpotong ketika ia sampai di sampingku. Ia berdiri dengan setelan jas hitam resmi dan memakukan pandangan padaku. Kukatakan kepadamu, kepadaku, yang kini tengah dibalut gaun pengantin lengkap dengan penutup kepalanya.
Kini, kami berdiri dengan kebisuan tak wajar di depan kaca super besar yang menampakkan kami. Aku tidak akan munafik untuk mengatakan bahwa kami berdua seperti pasangan pengantin sungguhan saat ini.
Ia, dengan setelan jas hitamnya. Dan aku, dengan gaun pengantinku.


 valentina
valentina