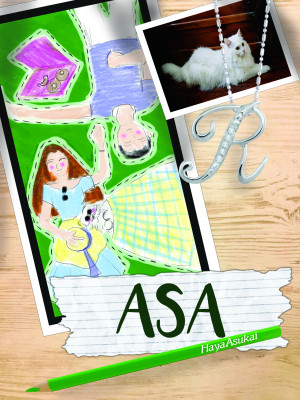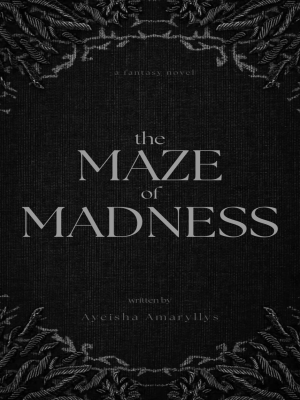Persiapan berkemah di atas bukit.
Acel sangat bersemangat. Dia membawa banyak sekali makanan dari rumah—yang kutahu sedikit, Acel anak yatim piatu. Dia dirawat oleh Hamak—Kepala Suku. Menteng membawa buku astronomi—sumbangan dari luar. Nico dan Itok membawa tenda dari Puskesmas.
Kabar yang kurang menyenangkan sejak saat aku mendengar dia sudah jarang di sini. Itok berkata—rumahnya paling dekat dengan Puskesmas dan dia setiap hari bermain ke sana, dia akan datang, tapi terlambat. Dia menyuruh Nico untuk memimpin perjalanan kami ke sana—badan Nico paling besar dan tingginya sama dengan dia. Membuatku menghela napas sejenak. Baiklah, dia pasti datang.
Persiapan sudah selesai, tinggal berangkat, Inak Bunan menyentuh pundakku. Aku menoleh ke belakang.
“Kau yakin mau berkemah tanpa Hamak Fian?” Inak bertanya.
Aku menghela napas. “Dia akan menyusul, Inak.”
“Kau yakin?”
Aku mengangguk mantap. “Dia bukan pria ingkar janji, Inak. Bukankah begitu?”
Inak Bunan menghela napas. Sorot matanya penuh kekhawatiran. Dia mengangguk pelan, tersenyum lembut. “Baiklah, Inak percaya. Hati-hati, ya, Nak?” Inak mengelus pundakku.
Aku mengangguk, mencium tangan Inak. Anak-anak ikut mencium tangan Inak. Kami mulai melangkah, dipimpin Nico.
“Sebentar,” teriak Inak. Kami berhenti, menoleh ke belakang. Inak berlari ke dalam, lantas keluar lagi. Menyerahkan benda bulat berwarna perak padaku. Aku menatapnya tidak mengerti.
“Bawalah. Inak mendapatkan ini saat Acel ditemukan di tengah hutan. Semoga, ini ada manfaatnya walau Inak tidak tahu kegunaan benda ini.”
Acel langsung berlari mendekat. Melihat lekat benda itu. “Berarti ini milikku, Inak?”
Inak Bunan mengangguk. “Biar Bu Damay yang membawa, takut kau masih kecil.”
Acel menghela napas mengkal, saking penasarannya dengan benda itu.
“Kami berangkat, Inak.” Aku mengangguk pamit. Perasaan yang ganjil sekali.
Inak balas mengangguk, melambaikan tangan.
Petualangan dimulai! Belum dengan dia memang. Aku menatap benda yang diberikan Inak. Menggenggam erat. Pasti, aku percaya dia pasti akan datang. Dia adalah pria yang tidak pernah ingkar janji.
***
Pertama, kami naik longboat selama setengah jam. Anak-anak terlihat antusias sekali. Tertawa terus menerus, ada saja yang mereka obrolkan.
“Ayam, ayam apa yang tidak bisa berkokok?” tanya Acel.
“Ayam betina!” jawab Itok.
“Salah. Menteng jawabannya!” Acel tertawa keras. Menteng melempar kulit kacang rebus ke Acel. Nico tetap diam, hikmat menikmati perjalanan.
“Lagi, buaya, buaya apa yang bisa bicara?”
“Buaya darat!” jawab Itok.
Aku menoleh. “Eh, darimana kau dapat kata-kata itu?”
“Waktu Inak-ku menonton sinetron di TV tetangga,” jawabnya polos.
Aku menepuk dahi. “Memang, buaya darat itu apa, Itok?” tanyaku pura-pura tidak tahu.
Itok mengangkat bahu. “Tak tahu, Bu. Aku hanya mendengar dan menonton saja.”
Aku menghela napas lega.
“Memang artinya apa, Bu?” tanya Acel.
Aku mengerutkan kening. Mereka terlalu kecil untuk tahu apa arti buaya darat. “Em, ya, buaya kan sesekali di darat,”
“Tapi, saat itu tak ada buaya di sinetron, Bu,” seru Itok.
Duh! Bagaimana ini?
“Hei, lihat, ada pelangi!” seru Nico menunjuk ke dekat air terjun kecil.
Anak-anak lalu menoleh, melupakan pertanyaan tadi. Memang, benar-benar menjadi PR untuk pendidik saat ini. Kalau tontonan dan kata-kata yang belum pantas terdengar oleh anak, pasti akan mudah terekam diingatan mereka. Aku bergidik. Berarti, semakin maju teknologi, mental dan kesiapan juga harus lebih maju dahulu. Bayangkan, apabila kemajuan teknologi tidak diimbangi dengan mental dan kesiapan, terutama moral manusia yang baik, bukankah perlahan tapi pasti dunia akan hancur?
Misal, saat sudah ada sistem toko tanpa ada pelayan. Hanya menggunakan sistem robot, mudah saja bukan mengelabui? Pembobolan dengan sistem koding misalnya. Bisa dipelajari dan akhirnya merebak di mana-mana. Anak-anak usia dini sudah dipertontonkan sesuatu yang belum saatnya—dewasa lebih dini istilahnya. Ditambah merebaknya manusia egois dan konsumtif yang tinggi. Benar-benar mengerikan aku membayangkannya.
Apakah, itu yang dimaksud dari Pak Satu?
Beruntung, anak-anak di sini lebih terkendali. Mereka masih memberi dan menerima kasih dari hutan, alam yang mereka jaga. Masih bersahabat baik dengan sungai, tanah, dan memilih memburu hewan—sesuai kebutuhan, daripada seharian penuh menonton TV. Aku memotret mereka diam-diam menggunakan ponsel yang tak ada sinyal. Mereka hikmat sekali melihat pelangi.
“Bu, apakah ada yang indah selain pelangi?” tanya Acel tiba-tiba.
Aku tersenyum. “Menurutmu, apakah ada, Acel?”
“Bu Damay, selalu saja bertanya kembali,” jawabnya.
Aku terkekeh. “Masih ingat materi letak astronomi Indonesia?”
Mereka mengangguk bersamaan.
“Menurutmu, apakah ada negara selain Indonesia?”
“Ada Bu!” jawab Menteng antusias.
“Sebutkan, Menteng!”
“Jepang, Belanda, Kanada, Rusia, Thailand, Singapura, banyak sekali, Bu!”
Nico mengangguk. Sebenarnya dia tahu, hanya dia lebih banyak diam dan mendengarkan.
“Apakah kalian percaya, bahwa ada suatu tempat tersembunyi selain negara-negara yang kalian tahu itu?” tanyaku lagi.
Mereka merapat. Menatapku penasaran.
“Pasti Bu Damay sedang mendongeng,” jawab Acel.
Aku menggeleng pelan. Tersenyum. “Bukankah pulau di Indonesia lebih dari ribuan? Mengapa, yang terkenal hanya tiga puluh empat provinsi saja? Apa kabar pulau-pulau tanpa keterangan lebih detail itu?”
Mereka terdiam dan berpikir.
“Apakah, banyak hantunya?” Mata Acel membulat, takut.
Aku mengangkat bahu. “Ibu tidak pernah tahu.”
“Misterius,” gumam Menteng.
“Menurut Ibu, sesuatu yang belum diketahui itu adalah hal paling indah daripada pelangi,” jawabku sambil tersenyum.
Menteng mengerutkan keningnya. “Maksudnya?”
“Apakah kalian jadi ingin tahu keberadaan pulau tersembunyi?” tanyaku lagi.
Mereka mengangguk bersemangat.
“Itu jawabannya.”
Nico mengangguk, paham.
“Memang kau tahu, Co?” tanya Menteng dengan muka penasaran.
Nico mengangguk. “Proses belajar.”
Aku menjentikkan jari. “Betul, Nico!” Aku tersenyum lebar pada anak-anak.
Anak-anak selain Nico, menatapku tidak mengerti.
“Kemarin kita baru menang lomba LCC bukan? Bagaimana perasaan kalian?”
“Senanglah, Bu!” seru Menteng sambil menepuk dadanya.
“Apa hubungannya proses belajar dengan menang LCC, Bu?” Acel semakin penasaran.
Rasanya, aku ingin tertawa soal muka penasaran dicampur muka tidak tahu mereka. “Ehem, setelah kalian menang apa yang akan kalian lakukan?”
Anak-anak saling menatap. Nico mengangguk takzim.
“Ya, memajang piala, Bu,” jawab Menteng.
Aku mengangguk. “Lalu?”
Menteng menggaruk kepala. Semakin bingunglah dia.
“Sekarang, Bu Damay bertanya mau lagi. Apa yang dilakukan saat tahu nilai Matematika kalian nilainya tiga puluh?”
“Menangis, karena dimarahin Inak,” jawab Itok.
Aku tersenyum. “Lalu, Itok?”
“Inak akan menyuruhkku belajar lagi,”
Aku mengangguk. “Bagaimana perasaanmu? Apakah lebih giat dan tekun belajar agar nilainya baik?”
“Iya, Bu!”
Aku menghela napas. Tersenyum. “Misal, kita mendapat nilai lima puluh, maka kita akan belajar lagi atau bahkan belajar dari kesalahannya. Mencari cara termudah agar bisa mengerjakan lagi. Saat nilai bagus, maka kita akan puas, mengangguk dan semangat lagi dalam belajar. Begitu?”
Mereka mengangguk, tersenyum lebar.
“Sama saat kita belajar berenang. Pertama kali pasti belum bisa, tenggelam, menelan banyak air. Akhirnya, kita penasaran, bagaimana, ya, cara berenang yang lebih mudah? Oh, ada tahapnya. Mulai latihan pemanasan, pernapasan, hingga gerakan dari tangan lalu gerakan kaki, berlatih di sungai yang dangkal, lantas memberanikan diri berenang di sungai besar. Apakah, proses itu menyenangkan?”
“Iya, Bu, menyenangkan! Banyak tantangan dan ingin terus belajar dan belajar!” jawab Acel girang. Yang kutebak, dia sudah paham apa yang aku katakan.
“Proses belajar adalah sesuatu yang lebih indah daripada pelangi.” Aku tersenyum.
“Setelah melihat pelangi, kalian pasti penasaran mengapa bisa terbentuk berwarna-warni bukan?”
Mereka mengangguk bersamaan.
Aku mengangguk. “Begitulah kira-kira. Mengapa manusia dianugerahi Sang Maha Pencipta mempunyai kemampuan berpikir? Tepatnya, agar lebih tahu dan akhirnya kembali ke titik Sang Pembuatnya.”
Mereka terdiam. Melongok ke belakang, melihat pelangi itu sekali lagi. Aku menatap mereka lembut. Ah, jadi seperti ini rasanya bercerita apa yang kita pikirkan. Pantas, dia selalu bercerita kepada anak-anak. Ternyata, memang menyenangkan.
“Hamak Fian memang belum ada di sini. Tapi, kembaran Hamak Fian perempuan sudah ada di sini. Bu Damaylia!” seru Menteng.
Dua kali jitakan dari Acel dan Nico ke Menteng. Itok tertawa. Aku ikut tertawa kecil.
Ayolah, segera menyusul, Bang! Pasti akan lebih menyenangkan saat kamu ada di sini.
Semua anak-anak kembali bercanda sambil sesekali menyipratkan air. Aku memilih membaca buku novel, sambil sesekali menertawakan mereka.
Tanpa tahu, empat mata mengawasi kami.
***
Longboat sudah menjauh.
Kami berlima mulai berjalan kaki, menapaki hutan. Nico memimpin di depan. Menteng di belakang Nico membawa tenda. Itok di belakangnya membawa bahan-bahan masakan. Acel dan aku bersebalahan paling belakang. Aku membawa ransel paling besar untuk membawa baju-baju.
Wangi tanah yang tercium. Enak untuk jadi pijakan. Akar-akar pohon besar yang menembus keluar tanah dengan lumut yang tetap hijau. Terbukti bahwa hutan ini terawat. Menurut Hamak, hutan ini tidak terlalu gelap dan binatang buas masih bisa terkendali. Saat kita berjalan, sesekali suara orang utan terdengar.
Nico menunjuk ke atas. Ada orang utan yang sedang menggendong bayinya. Mereka pergi segerombolan, sambil bersuara dengan ciri khas mereka. Keren sekali melihatnya secara langsung, tidak seperti saat melihat di kebun binatang. Aku justeru merasa kasihan. Orang utan itu terkurung, padahal tempat tinggal mereka harusnya di hutan. Namun, di hutan juga mereka kasihan. Orang-orang tidak waras memburu mereka, dan menghancurkan tempat tinggal mereka. Siapa sebenarnya yang salah dan benar? Abu-abu.
Nico menghentikan langkahnya. Kami mawas diri. Termasuk aku, menggenggam erat alat yang diberikan dari Inak.
“Lihat, jejak itu!” Nico menunjuk jejak kaki.
“Jejak babi,” seru Menteng.
Nico mengangguk. “Bukan jejak babi biasa.”
“Babi rusa?” tanya Menteng menahan gidik.
Nico mengangguk. “Kita harus lebih berhati-hati. Tidak apa. Asal, kita tidak mengganggu, semua baik-baik saja.”
Nico melanjutkan perjalanan. Entahlah, kakiku semakin ragu melangkah. Perasaanku berkata untuk kembali saja, tidak usah lanjut untuk berkemah. Namun, melihat semangat anak-anak dan antusias mereka, tak sampai hati menyampaikan yang kurasakan. Aku menarik napas, menghembuskan perlahan. Semua akan baik-baik saja. Aku menoleh ke belakang. Dia pasti akan segera menyusul.
Jalanan mulai menaik. Bermacam tanaman masih tumbuh alami. Bahkan, tanaman hias yang dijual mahal di Yogyakarta, di sini berserakan. Kalau otak ekonomiku jalan, maka kuambil semua saja, kurawat, lantas kujual dengan harga tinggi. Sayangnya, aku memilih menghormati hutan, mengambil seperlunya, bukan untuk keuntungan semata.
Sesekali, aku mengusap pepohonan yang tingginya sepinggang. Terkadang, Nico memberi peringatan. Ada yang bisa membuat kulit memerah lantas bengkak. Kuusap batang pohon besar dengan akar kokoh yang bisa dijadikan tempat duduk. Pohon yang tidak asing, seperti aku pernah melihatnya. Suara siulan indah burung mulai riuh. Sesekali suara orang utan memanggil teman-temannya terdengar. Baguslah, terpenting bukan suara harimau saja.
Nico memberi kode untuk beristirahat sejenak. Kami mulai membongkar satu tas berisi bekal yang sudah dipersiapkan. Masakan Inak memang juara kedua setelah masakan ibuku. Ah, jadi rindu pada ibu. Bagaimana kabarnya, ya?
“Bu Damay beruntung, bisa setiap hari makan masakan Inak Bunan. Enak sekali!” seru Acel memakan lahap makanan. Nico mengangguk-angguk setuju. Menteng tak peduli. Dia begitu menikmati makanan.
“Apakah Hamak Fian akan menyusul?” tanya Itok.
Aku menatap jalan yang telah kami lewati. Menatap lama. Berharap waktu bisa berputar dengan cepat, agar dia segera di sini. Bersama kami. Aku menghela napas pajang.
“Bukankah, Hamak Fian tak pernah ingkar janji?” Aku menatap mereka satu persatu. Mereka mengangguk pelan.
“Dia pasti akan menyusul,” jawabku sangat yakin.
***
Di lereng bukit.
Kami memutuskan untuk berkemah di bawah puncak bukit. Nico memberi arahan. Kalau di puncak, angin akan kencang tanpa penghalang, berbeda saat mendirikan tenda di bawah puncak dengan ada pohon sebagai penghalang angin. Penjelasan yang menurutku dia cocok menjadi siswa akselerasi.
Bagiku, Nico mirip sekali dengan Eno. Sempurna dalam segala hal, tapi dengan sifatnya yang dingin dan jarang bicara. Eh, kenapa tiba-tiba aku kepikiran Eno?
Kami mulai mendirikan tenda. Cukup dua tenda. Satu tenda untuk laki-laki, satu tenda untukku dan Acel. Dia sudah menyiapkan tenda itu sebelumnya di Puskesmas. Dan Dia juga yang menyiapkan rute perjalanan, berbahayakah ke bukit, beresiko tinggi tidak jalannya. Dia bersama anak-anak sudah mempersiapkan dengan baik.
Tenda digabungkan dengan fly sheet, sehingga terlihat satu rumah dengan dua kamar. Satu sisi terbuka, kami menyalakan kompor kotak kecil dengan gas tabung mungil, lagi-lagi dia yang menyiapkan. Segera, kami menyeduh air untuk masak-masak. Perjalanan yang lumayan membuat kami lapar.
Kami saling berbagi tugas. Ada yang mengiris sayur-sayuran, aku menyiapkan bumbu, dan Nico memastikan tenda sudah berdiri dengan kokoh. Sepuluh menit sibuk memasak, akhirnya kami makan sore juga. Makan malam yang dirangkap siang. Tidak masalah, masih sisa banyak. Bisa dimakan lagi nanti malam.
Matahari mulai merendah, Nico memberi kode untuk segera naik ke puncak. Aku menoleh ke belakang. Dia belum juga terlihat rambut poninya yang menawan. Aku menghela napas. Baiklah, kita tunggu. Semoga segera datang.
Setelah memastikan tenda sudah tertutup rapat dan membawa barang-barang penting, kami mendaki lagi. Tidak lama, paling hanya butuh lima menit saja sampai di puncak bukit. Kini, terlihatlah bukit tanpa pohon terbentang seluas lapangan sepak bola. Bertanah merah dan semak-semak liar. Nico membabat seperlunya dibantu Menteng. Matahari semakin merendah, menandakan senja akan terlihat pemandangannya.
Kami duduk berlima menatap senja. Acel memberi botol minum padaku. Itu bukan air putih, melainkan minuman dari rebusan rempah-rempah. Istilah minuman bagi daerahku adalah wedang uwuh. Aku mengangguk, mengucapkan terima kasih lantas meneguknya perlahan. Acel duduk di sampingku.
“Bu, apakah aku aneh? Saat aku berada di hutan, perasaanku jauh lebih tenang. Seolah hutan adalah rumahku,” ujar Acel sambil menunduk.
Aku menatapnya lamat. Rambut panjang yang indah dengan poni lurus di dahi, gadis yang ceria, tiba-tiba terasa sendu auranya.
“Mungkin, karena kamu sering bermain di hutan. Jadi, kamu nyaman di hutan. Serasa, candu. Bila tidak sehari saja di hutan, maka rasanya kurang. Seperti itukah perasaanmu?”
Acel mengangguk. “Rasanya, aku ingin melindungi hutan ini agar terus ada. Agar aku bisa kembali ke sini.”
Aku mengelus bahunya. “Artinya, kamu sudah jatuh cinta pada hutan, Acel.” Aku tersenyum lebar padanya.
Acel menatap mataku. “Jatuh cinta?”
Aku mengangguk.
Acel tersenyum lebar. Lantas tertawa. “Suatu saat nanti, aku akan menjadi penulis terkenal, menceritakan betapa indahnya hutan ini, lantas mengajak orang-orang untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Sebal saja melihat lubang-lubang tambang itu, Bu. Harusnya diuruk kembali lantas ditanami pohon kembali!” Acel mengepalkan tangan ke atas. Membuat anak lain menoleh.
“Kau berpidato di depan burung-burung dan para orang utan?” Menteng mulai meledek.
Acel melotot pada Menteng. “Kau mendengarnya, berarti kau juga burung, oh, bukan. orang utan maksudku.”
Aku tertawa mendengar jawaban cerdas Acel. Itok tertawa kencang sekali. Nico tertawa sambil menghabiskan bekalnya.
“Tampan dan cerdas sepertiku kau samakan dengan orang utan?” tanya Menteng congak.
“Tampan, kalau di antara bebek berenang.” Nico jahil menjawab.
Kami tertawa keras. Muka Menteng sudah tak terbentuk lagi. Marah iya, sebal apalagi.
Senja yang ditunggu akhirnya datang. Suara jangkrik mulai terdengar. Lengguhan burung-burung yang kembali setelah mendapatkan makanan, dan langit biru keunguan dengan sisa bulan sabit dan dua bintang yang menemani keberadaannya.
Mulutku membisu. Anak-anak tidak bersuara. Bukit, sungai berkelok, dan danau yang dilindungi terlihat jelas dari atas bukit. Memberi pantualan warna senja yang indah. Membuat kami hikmat melihat semua keindahan alam. Awan-awan mulai mengembara dengan slow motion, membuat semakin sempurna apa yang aku lihat.
Aku menghela napas pelan. Aku ingin dia ada di sampingku. Tidak harus berucap dengan obrolan filosofisnya—yang aku yakin pasti dia bicara soal makna senja. Cukup di sampingku, melihat senja yang begitu magis membuat beku seketika. Lantas, dia menoleh, tersenyum lebar, dan berkata “Menurutmu, bagaimana?”
Aku menghela napas sekali lagi. Aku tidak tahu apa urusannya di kota sana. Bahkan, tidak memberi tahu dia mau apa, ada kepentingan apa, atau sekedar memberi tahu dia akan ke mana. Terakhir kulihat wajahnya yang lelah setelah perlombaan, lantas mengangkat piala tinggi-tinggi saat longboat berjalan. Dia begitu bahagia.
Aku tidak tahu tapi ingin tahu. Apakah ada kaitannya dengan telepon itu? Dia bermuka sendu. Atau, keluarganya ada yang sakit? Atau, urusannya di sini sudah selesai? Kalau iya, jahat sekali dia tidak berpamitan denganku. Walau, iya, saat aku datang saja dia tak menyambut. Tak ada kewajibannya untuk berpamitan. Tapi, kalau benar dia sudah selesai mengabdi di sini, aku sungguh terlambat memberi pembatas buku ini, memberi tanda pengenalnya, mengatakan yang ingin disampaikan Ranaya, dan ....
Senja semakin tenggelam, membuat kami terpekur, dan bersiap untuk kembali ke tenda. Menunggu matahari terbit. Aku semakin lelah saja menunggu atas pertanggung jawaban perkataannya. Janji, yang dia katakan sendiri. Padahal, beberapa jam lagi, kami akan menghadapi peristiwa yang tidak akan pernah terlupakan seumur hidupku.
Kejadian, yang membuatku harus bisa berlari secepatnya agar tidak mati.
***
“Bu.” Seseorang menggoyangkan tubuhku.
Aku terbangun,masih setengah nyawa. “Ada apa, Cel?”
Acel meringis. “Aku ingin kencing, Bu, tapi takut. Bu Damay mau temani?”
Aku mengangguk, nyawa masih terkumpul tiga perempat.
Acel membuka resleting tenda, udara dingin menguar. Tanganku bergetar, kedinginan. Acel biasa saja. Kekuatan anak-anak memang luar biasa. Aku menyalakan senter, memberi jalan pada Acel. Kami berjalan berhati-hati.
“Bu, haruskah membangunkan Nico?”
Aku menggeleng. “Kita cari yang dekat tenda saja.”
Kami melangkah perlahan. Gelap dan suara hewan malam mulai terdengar. Dinginnya kali ini lebih dingin dibanding saat membuka tenda pertama kali. Bulu kudukku berdiri. Kalian tahu, bukan? Aku sebenarnya penakut, tapi apalah daya.
Acel semakin merapatkan dirinya ke lenganku.
“Bu, kita panggil Nico dulu bagaimana? Gelap sekali.”
Aku menghela napas, “Acel, ada senter. Tenang saja. Itu, kau kencing di sana. Permisi dulu.”
Acel mengangguk.
KRASAK! Acel yang sudah maju berlari lagi, memeluk lenganku. “Bu, Acel takut!”
Aku menyorot sumber suara. Mengamati dengan cermat. Tidak ada apa-apa.
“Tidak ada apa-apa, sudah kencing sana! Ibu jaga dari sini.”
Acel menggeleng cepat. “Acel tak jadi kencing. Sudah masuk lagi.”
Ingin rasanya tertawa di dalam suasana tegang seperti ini.
“Yakin?” tanyaku.
Acel mengangguk mantap. “Yakin Bu, nanti kalau ingin kencing lagi, kubangunkan Bu Damay lagi.”
Aku mengangkat bahu. Baiklah. Kami berbalik berjalan menuju tenda. Dua langkah lagi masuk tenda, ada suara langkah mendekat dari belakang. Aku mendengarnya semakin jelas, kubalikkan badanku.
Pistol panjang mengacung tepat di depan dahiku. Tangan Acel kupegang erat. Dia memelukku erat di belakangku. Aku tahu, pasti dia sangat ketakutan. Tangannya dingin seperti es. Keringat dinginku mulai mengucur. Siapa dia? Pemburu? Lancang sekali mengadahkan pistol di muka orang lain. Perlahan dalam kegelapan, semakin jelas siapa yang sedang menodongku pistol. Pria berjaket kulit hitam, bertopi hitam, masker hitam, dengan tas ransel di belakang. Menatapku tajam, lantas menatap Acel.
“Good night, daughter,” sapa pria itu.
Seketika, lima pria mendekat ke tenda kami sambil menodongkan pistol panjang. Napasku menderu, tenggorokanku kelu, tidak tahu yang harus kulakukan. Yang jelas, kami sudah terkepung.
***
Nico, Menteng, dan Itok terbangun karena jeritan Acel. Lima pria itu langsung menodongkan pistol ke arah tiga anak yang baru bangun dengan nyawa yang belum terkumpul. Walau Nico belum tahu situasi, dia segera mengangkat tangan. Tahu, bahwa pistol itu bukan main-main. Menteng dan Itok berpelukan di belakang Nico.
“Oh, so, you don’t alone, daughter?” Pria itu bicara lagi.
“Aku bukan anakmu!” jawab Acel lantang—dia bisa bahasa inggris.
“Wah, ternyata kau bisa tahu bahasa asing? Hebat!” Pria itu menjawab lagi. Sudah kuduga, asalnya bukan dari negara ini. Aksen bahasanya masih terlihat bule sekali.
Pria itu mengangkat tangannya. Salah satu lima pria itu mendekat, menggantikan todongan pistolnya ke arahku. Pria itu jongkok, lantas menatap Acel tajam. Dia memegang kepala Acel.
“Apa yang akan kau lakukan?” tanyaku geram.
Pria itu menoleh lagi padaku. “Something.”
“JANGAN BERANI SENTUH ANAK-ANAKKU SEDIKITPUN!” bentakku. Aku benar-benar benci dengan seseorang pengecut, yang hanya mampu mengepung disaat yang pelik seperti ini.
Pria itu berdiri. Tertawa keras. “Anak-anakmu? Jadi, kau yang melahirkan?”
Kujawab dengan dengusan amarahku. Pistol semakin dekat dengan dahiku.
“Oh, wait. Wanita muda nan cantik seperti ini sudah menikah, aku tak yakin. Ah, kau Guru mereka?”
Aku semakin geram menatapnya.
Dia tertawa keras sekali. Memegang daguku. “Tanpa kau beritahu, aku sudah tahu. Kau adalah seorang Guru sementara, berasal dari Yogyakarta, bukankah begitu?”
Aku mengibaskan tangannya. Pistol itu menempel sudah di dahi. Kutatap tajam bola matanya. “Apa urusanmu dengan kami?!”
Pria itu berdecak. “Kalau kau seorang wanita pemarah, mana ada pria yang mendekatimu,” jawabnya dengan tertawa keras. Lima pria lainnya ikut tertawa.
Dia mendekatkan matanya padaku. “Kau ingin tahu?” Dia berjalan mundur ke belakang. Menunjuk Acel.
“Kalau kau menyerahkan dia untukku, selesai. Kalian selamat!”
Aku menatap anak-anak yang lain. Muka mereka pucat pasi. Nico masih berusaha melindungi Menteng dan Itok yang menggigil ketakutan dan kedinginan.
“Apa urusanmu dengan Acel?”
“Kau wanita serba ingin tahu,” jawabnya jengkel, “kalau kuberitahu alasannya, apakah kau mau merelakannya, dan berbohong pada polisi bahwa anak itu hilang di tengah hutan? Aku aman kau aman, bagaimana?”
Aku diam. Mana ada seorang guru yang mau merelakan anaknya dibawa orang gila? Aku berpikir beberapa kemungkinan untuk bisa kabur dari sini membawa keempat anak, termasuk Acel. Aku belum tahu betul, apa urusan Acel dengan pria ini, apakah Acel sindikat? Tidak mungkin. Apakah Acel kabur dari negara lain? Tidak mungkin sekali. Pengasuh Acel bahkan menunjukkan akta kelahiran asli. Lantas, apa urusannya?
Aku mengangguk. Acel menarik lenganku. Aku memegang tangan Acel erat. “Dengan dua syarat. Pertama, kau beritahu alasannya. Kedua, aku harus mengantar Acel sampai di ujung hutan.”
Dia tertawa keras. “Syarat pertama aku setuju, syarat kedua tidak. Aku tidak sebodoh apa yang kau kira. Itulah kesempatan untuk kabur, bukan?”
Aku mendengus.
Dia mengibaskan tangan di antara pendar senter di kepala mereka. “IKAT MEREKA! Kita buang semua tenda, bukti, apapun itu agar polisi dan wanita sialan itu tidak tahu keberadaan kita. SEGERA!”
Mereka menyeret kami. Baiklah, ini kesempatanku, pistol tidak ada di dahi. Segera kutendang alat kelaminnnya, dia mengeluh kesakitan.
“ANAK-ANAK, TENDANG KELAMINNYA!” teriakku.
Nico segera memberi perlawanan. Dia lumayan mahir berkelahi. Menteng menuruti perintahku, Itok juga. Aku segera menggendong Acel. Pria itu menodongkan pistol ke arahku. Tiga pria masih mengeluh kesakitan, satu pria membekukan Itok. Nico dan Menteng berdiri kokoh, saling memunggung.
“Mau lari ke mana kau?” tanyanya.
Segera kukeluarkan alat pemberian Inak Bunan. Pria itu terkejut.
“K-kau?”
Entah, tombol apa di tengah langsung kupencet saja. Tongkat itu memanjang dengan sendirinya. Pria itu segera menghindar dari tongkat itu, tetap menodongkan pistol.
“Kau mau mati sekarang juga? Baiklah!” Dia menggeram.
Dia menekan pelatuk, Nico segera mendorongku. Aku terjatuh bersamaan Nico.
“Aw,” keluhku. Lihatkah! Kulitku melepuh, padahal hanya terkena sedikit saja tongkat itu.
“Tongkat itu bisa mengeluarkan panas, Bu. Sekali hantam bisa membuat lepuh kulit. Terlihat dari asap yang terlihat dari cahaya senter,” jelas Nico.
Aku mengangguk. “Nico, bawa anak-anak lari sejauh mungkin. Kau anak rimba, aku percaya itu.”
“Tapi, Bu.”
DOR!!
Satu tembakan terdengar. Pria itu mendekat sambil mengacungkan pistol ke langit.
“Jangan sampai anak itu lecet sedikitpun!” serunya geram.
Aku mendekatkan tongkat ke arah Acel. Membaca situasi. Acel. Ya, Acel adalah kelemahan mereka. Segera, kutodongkan tongkat panas itu ke lengan Acel. “Akan kulukai anak ini, biarkan kami pergi,” seruku, menatap tajam pria itu.
Pria itu mundur, Menteng yang menendang lagi kelamin pria yang akan terbangun langsung lari ke arahku. Itok masih tertahan dengan satu pria.
“Lepaskan anak itu juga,” Aku menunjuk Itok, “kalau tidak, kulukai anak ini segera,” Aku menempelkan sedikit tongkat ke arah Acel. Sedikit saja demi ancaman. Tentu, dia meringis kesakitan.
Dia semakin mundur, pistol tidak lagi menodong kami. Pria-pria yang sedang kesakitan, bangun dengan tertatih.
“Apa yang kau inginkan?”
“Bebaskan kami!”
Dia membuang pistolnya. Mengulurkan tangan. “Ayolah, aku tidak akan menyakiti anak itu,”
“BOHONG!” jawabku ketus.
“Aku sudah membuang jauh pistolku, apalagi yang kau inginkan?”
“Buang sentermu!”
“Mana mungkin, bagaimana aku bisa ....”
“BUANG SEMUA SENTER!” bentakku galak. Aku semakin mendekatkan tongkat itu ke lengan satunya Acel.
Dia membuang senter. Anak buahnya juga membuang semua senter. Aku tidak paham, mengapa mereka takut sekali Acel terluka.
“Nico, beri petunjuk jalan ini, ayolah cepat!” bisikku. Aku menggendong Acel.
Kami mulai berlari dengan mengendap-ngendap.
“WOI, MEREKA KABUR! SEGERA CARI MEREKA!” teriaknya beringas.
Suara langkah mendekat banyak. Nico langsung lari secepat mungkin diikuti Menteng dan Itok. Aku paling belakang menggendong Acel. Aku takut dia akan ditarik. Sungguh, aku benci berlari. Tapi, ini demi anak-anak selamat. Demi Acel tidak di bawa dan kami tidak mati di sini.
DOR!
Suara pistol terdengar lagi. Mereka menyusul kami di belakang. Aku menoleh ke belakang. Sial, ada salah satu pria yang membawa senter. Itu akan memudahkan mereka menyusul kami.
“NICO, LARI LEBIH CEPAT!” teriakku.
Nico mengangguk. Napasku sudah sesak, tapi harus terus berlari. Entahlah, kami berlari hanya mengikuti insting Nico. Tanpa pencahayaan sedikitpun agar tak terlalu terlihat.
DORR!
Suara pistol menggema kembali. Ranting-ranting tajam sudah melukaiku. Acel menangis di punggungku. Tidak bisa, kali ini tidak bisa menasehati dengan napas terengah-engah. Kami terus berlari sampai di ujung sungai. Aku tahu rencana Nico. Berendam sesaat sampai mereka pergi. Aku menoleh ke belakang. Jarak mereka semakin dekat, mungkin hanya tiga meter. Aku semakin panik. Apa yang harus kulakukan.
Nico menyeburkan diri dengan hati-hati. Diikuti Menteng dan Itok. Tinggal giliranku ....
DORR!
BUG! Aku dan Acel terjatuh. Tembakan tepat mengenai kakiku. Acel terguling. Pria itu semakin dekat, dia mencengkram lengan Acel kuat.
“Biarkan saja mereka! Kita bawa dulu anak ini!”
“LEPASKAN AKU!” Acel memukul-mukul pria itu. Dia menggendong Acel di bahunya.
“LEPASKAN ACEL!” Aku berteriak sekencang mungkin.
Nico segera menarik tanganku.
DOR!
Tepat kami menyelam di sungai dangkal, peluru itu lepas sasaran. Entah, aku benar-benar hanya melihat kegelapan dan menangis sejadi-jadinya di tengah riuh suara sungai.
“ACEL!!” teriakku lagi. Langkah mereka tidak terdengar.
Aku benci keadaan ini. Aku meraung pesakitan. Memukul-mukul air di sungai. Menteng terisak, Itok menangis tersedu, dan Nico terdiam. Kami benar-benar kehilangan berpikir untuk rencana selanjutnya, kakiku sudah telak belum bisa digerakkan. Dan, derap langkah gerombolan itu semakin tak terdengar.
Acel telah pergi, dibawa oleh gerombolan orang yang tak kuketahui siapa dan dari mana asalnya?


 lu_r_an
lu_r_an