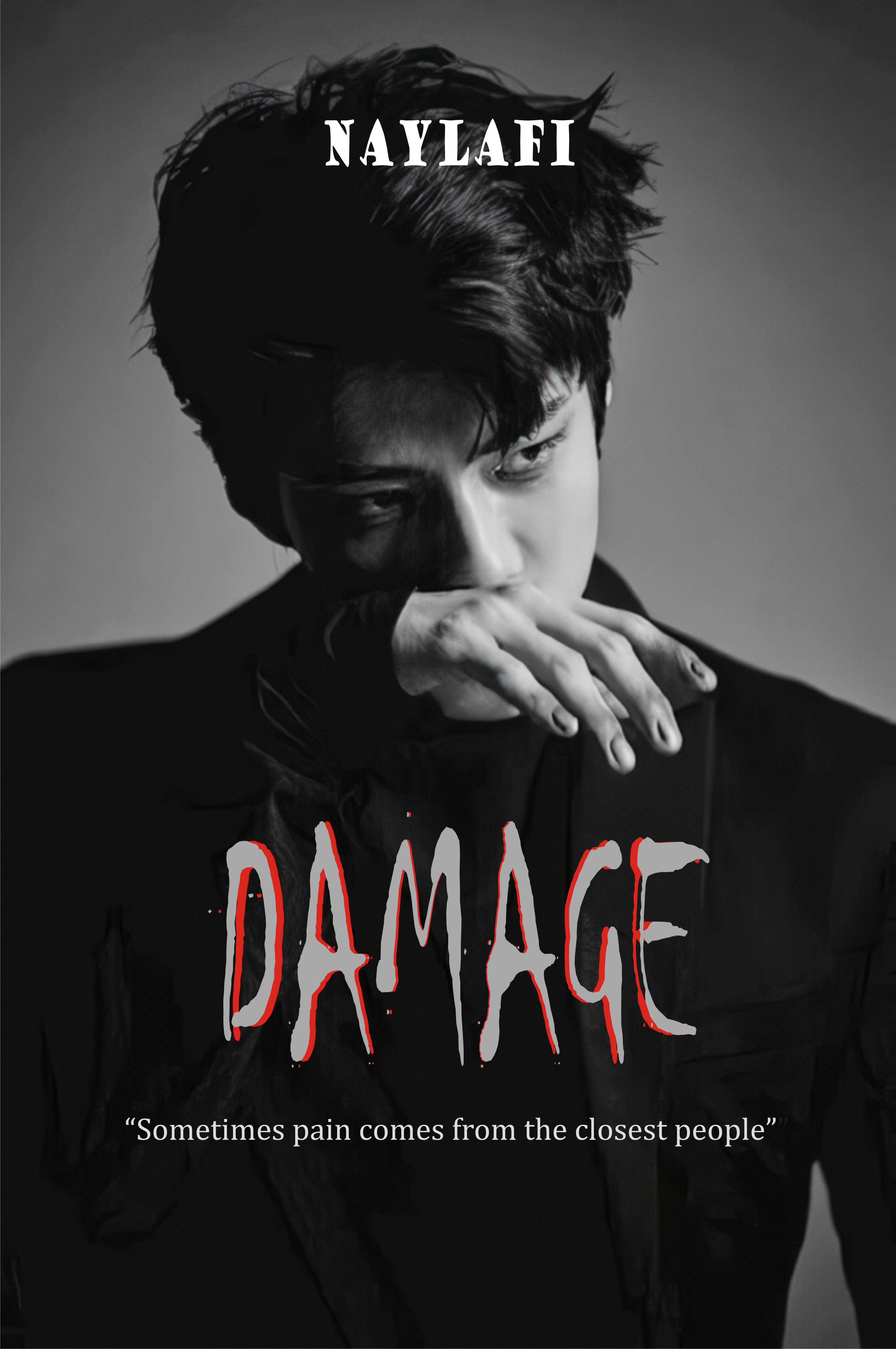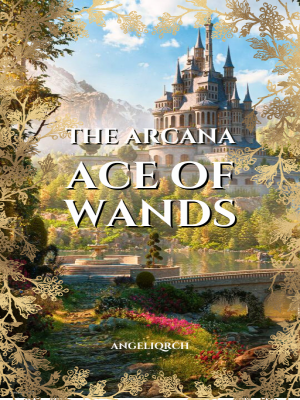Sekolah yang megah
Deretan mobil dan motor tertata rapi di sebelah sekolahan. Anak-anak memakai baju putih-putih bersama gurunya. Bahkan, ada orang tua yang ikut demi melihat anaknya berjuang di perlombaan. Para pedagang kecil seperti cilok—ada juga di Kalimantan, kerupuk basah, es lilin, es serut, terang bulan, dan masih banyak lagi berjajar di dekat parkiran. Beberapa anak sudah membeli es serut, mungkin karena cuaca yang terlampaui panas.
Kami berangkat pagi-pagi sebelum matahari terbit. Hanya ada Kepala Sekolah, beberapa guru, dan beberapa murid yang melepas kami. Termasuk Itok, dia merengek mau ikut, tapi tidak kuizinkan. Nanti, dia akan tertinggal pelajaran. Inak dan Hamak tentu saja memberi semangat, melambaikan tangan di pinggiran dermaga kayu.
Setelah melewati jalanan yang lumayan melelahkan menggunakan truk, Menteng beberapa kali muntah, Nico beberapa kali kentut—masuk angin, dan Acel yang baik-baik saja berseru gembira akhirnya dia bisa melihat pemandangan di luar desanya. Sesampai di depan gedung sekolah mewah, kami berhenti sejenak terpana. Awalnya kukira itu SMP, ternyata SD.
Acel melangkah lebih dulu. Mulutnya tidak menutup, terbuka sambil berkata “Wah”. Kagum melihat gedung yang megah. Nico tak hentinya tersenyum lebar, toleh kanan-kiri demi merekam semua inci gedung. Menteng sama seperti Nico. Dia lebih santai dan cool, sesekali menyisir rambut. Seolah, dia sudah terbiasa sekolah di sini.
“Kau mau menarik perhatian pasti!” ledek Acel.
Menteng tak menjawab. Dia membusungkan dada, seolah dirinya yang paling keren.
“Tak, tak usah berlagak. Tak ada yang mau melihat kau!” ledek Acel sambil nyengir.
Menteng melotot pada Acel, berdeham.
“Lagaknya bak orang dewasa. Mau jadi Hamak kau?” Nico ikut meledek.
“Bisakah kalian diam? Kita akan segera mengikuti lomba. Harus penuh wibawa dan percaya diri,” jelas Menteng.
“Alah!” Acel dan Nico bersamaan.
Aku dan Dia tertawa kecil melihat tingkah anak-anak. Syukurlah, keputusannya membeli baju baru memang tepat. Mereka jadi percaya diri, karena murid dari sekolah lain rata-rata memakai baju bersih. Hanya satu, sepatu mereka butut. Seorang anak perempuan melihat Menteng dari bawah ke atas lama.
Menteng yang sudah ke-pedean, berdeham, berhenti di depan anak itu sambil mengulurkan tangan. Menatap sok serius. “Perkenalkan, namaku Menteng, namamu siapa?”
Anak perempuan itu melihat Menteng dari bawah sampai ke atas sekali lagi. Menatapnya sinis. “Baju bagus, sepatu butut? Lihat! Dari atas sampai bawah aku rapi!” Anak perempuan itu geleng-geleng kepala lantas pergi meninggalkan Menteng yang masih mengulurkan tangan. Membeku.
Acel dan Nico menahan tawa. Aku dan dia saling tatap.
Menteng menunduk. Dia terdiam. Acel dam Nico menghampiri Menteng dengan sisa tawa. Menepuk bahu Menteng keras.
“Lupakan, Menteng. Kau bukan teman yang diinginkan,” Acel menepuk-nepuk bahu Menteng.
“Fokus lomba saja, Menteng!” Nico ikut-ikut menepuk bahu Menteng.
“Oh, tentu!” Menteng menegakkan kepala, “lihat saja nanti, dia akan menyesal mengatakanku pakai sepatu butut.” Menteng berjalan tegak. Semangatnya bertambah.
Aku dan dia saling tersenyum. Menteng memang mental baja. Bukannya minder, tapi semakin semangat untuk mengikuti perlombaan. Acel dan Nico saling tatap. Mengangkat bahu, ikut berjalan di belakang Menteng.
Gedung dua pintu menyambut kami. Rombongan peserta lomba mulai memasuki gedung, duduk di kursi khusus untuk peserta lomba. Setelah mendaftar ulang, anak-anak berhenti sejenak di depan pintu. Mereka menatapku dan dia.
“Kalian siap?” tanyanya sambil mengelus kepala mereka satu persatu.
Acel, Menteng, dan Nico mengangguk mantap. Mengacungkan jempol.
“Tenang, Hamak dan Bu Damay tidak menuntut kalian harus menang. Lakukan yang terbaik seperti latihan. Kalau salah satu ada yang gugup, yang lain menguatkan. Bisa?” ujarnya sambil tersenyum.
Mereka mengangguk lagi. Muka tegang mulai terlihat.
“Kalau tegang, ingat saja saat Acel tercebur ke sungai saat membaca puisi,” tambahnya lagi.
Menteng dan Nico mulai tertawa, Acel merengut ke arahnya.
“Nah, bagus. Sekarang berdoa, lantas masuk. Hamak yakin, kalian pasti bisa!”
Nico memimpin di depan. Menteng ikut di belakang, dan Acel terakhir. Mereka duduk di kursi khusus para peserta lomba. Aku dan dia masuk dan duduk di tempat penonton. Tentu dibatasi.
Kali ini, ada puluhan sekolah yang ikut lomba. Layar besar di depan—menggunakan LCD terlihat sekolah dari desa kami melawan sekolah dari daerah pelosok juga—dia yang memberitahu tahu. Setiap sesi berisi tiga sekolah yang bertanding. Menjadikan, ada sepuluh sesi di dalam perlombaan ini. Waktu bertanding satu sesi adalah dua puluh menit untuk menentukan kelompok yang masuk ke babak selanjutnya. Jantungku mulai berdegup melihat anak-anak dipanggil sesi ketiga.
Ajaib. Apa yang dikatakan dia benar. Lihatlah! Anak-anak begitu percaya diri menjawab pertanyaan dan semuanya hampir benar. Hanya bisa dihitung jari mereka menjawab salah. Aku menoleh padanya, menatap tidak percaya. Dia tersenyum sambil mengangkat bahu.
Jeda waktu istirahat setelah setengah sesi maju. Kurang setengah sesi lagi. Acel keluar ruangan sambil loncat-loncat, tertawa senang. Nico mengusap keringat di dahinya, tersenyum lebar puas. Menteng, membusungkan dada, mencari sesuatu—mungkin mau pamer pada si anak perempuan yang mengejeknya.
Aku langsung mengelus kepala mereka satu persatu. “Wow, kalian hebat sekali!”
Acel memelukku erat. Mungkin, dia baru pertama kali ikut lomba, jadi merasa bahagia sekali saat bisa mengalahkan lawan mereka.
“Jauh sekali skornya, sudah Hamak bilang, kalian pasti bisa!” Dia mengacungkan jempol ke Nico dan Acel.
Nico menunjuk Menteng. “Entahlah, Menteng semangat betul, Hamak. Dia menjawab semua pertanyaan dengan cepat dan benar. Walau, ada salahnya. Aku dan Acel mau memencet tombol, dia sudah duluan,”
Menteng menepukkan dadanya. “Lihat saja, anak itu pasti menyesal telah mengejekku!”
Aku dan dia tertawa bersamaan. Ternyata, dendam Menteng menakutkan juga.
“Baiklah, setelah ini, soal akan semakin panjang. Jawaban juga semakin panjang. Acel, kau paham maksud Hamak?”
Acel mengangguk. “Biarkan Nico memahami soal, Menteng memperkirakan jawaban, Nico memastikan dan Acel menjawab dengan bahasa yang jelas.”
“Bagus. Kerja sama kalian lebih diutamakan, mengerti?”
Mereka mengangguk kompak. “Mengerti!” jawab mereka serempak.
Aku menyerahkan tiga kotak nasi pada mereka. “Makanlah dulu, isinya rica ayam.”
Mata mereka membulat. Langsung saja mereka duduk di atas paving, lantas makan dengan lahap.
“Bang, dulu bukan guru paud, kan?” tanyaku.
Dia tertawa. “Tidaklah. Kenapa kau tanya begitu?”
“Abang seperti bisa memahami anak-anak,” jelasku.
Dia menepuk dahinya. “Aih, begitu, ya? Baiklah, aku juga memahamimu.”
Mukaku mulai merona. “M-maksud Abang?”
Dia menyerahkan topi itu lagi. “Pakailah. Kau pasti kepanasan bukan?”
Aku menghela napas pelan. Kukira paham soal aku siapa, untung saja.
Ponsel Dia berdering. “Sebentar, aku ada telepon penting. Kau jaga anak-anak dulu.” Dia menjauh dan bercakap pelan di sana. Aku menatapnya tanpa berkedip. Telepon dari siapa? Sampai harus menjauh segala.
“Ehem, Bu Damay suka Hamak Fian?” Acel berdeham sambil memegang paha ayam.
“Eh, em, Acel itu nasi di mulutmu!” Aku berusaha mengalihkan pembicaraan.
Acel buru-buru membersihkan mulutnya. Dia menatapku lagi. “Bu Damay belum menjawab pertanyaanku tadi.”
Nico menyikut Acel. “Tidak sopan!” serunya sambil melotot.
Acel menunduk takut-takut sambil memakan paha ayamnya. Menteng tidak menggubris mereka berdua. Sesekali, dia menghapalkan materi yang akan dilombakan. Aku harus berterima kasih pada anak perempuan itu. Membuat Menteng bersungguh-sungguh dan mentalnya lebih mantap.
“Maaf, eh, lima menit lagi. Bergegas habiskan!” Dia kembali. Mukanya sedikit redup.
Anak-anak segera makan secara kilat. Membuang sampah di tempat sampah, mencuci tangan lantas masuk kembali ke ruangan. Aku menahan Dia.
“Abang, baik-baik saja?” tanyaku.
Dia menoleh. Tersenyum tipis. “Aku baik-baik saja, buktinya tidak gila.”
Aku menepuk bahunya pelan. “Mulai lagi.”
Akhirnya dia tertawa kecil. Mengubah sedikit muka redupnya. Kami berjalan beriringan masuk ke gedung. Menyaksikan sesi selanjutnya, menanti lawan siapa yang akan dihadapi oleh anak-anak di babak final
***
Sekolah kami masuk ke grand finale.
Tempat duduk khusus pelatih semakin sedikit, begitu juga dengan tempat duduk peserta lomba. Tertinggal tiga kelompok yang maju ke grand finale. Anak-anak sudah duduk di bangku depan berjejeran dengan para lawan. Mereka menghadap juri. Aku sudah tidak bisa duduk dengan tenang. Berdiri, menyemangati anak-anak. Dia juga berdiri di sampingku. Mukanya tegang.
Aura persaingan semakin sengit. Beberapa pelatih melirik ke arah kami. Mungkin, tidak percaya ada sekolah pelosok bisa sampai sejauh ini. Menteng lebih bersemangat lagi, sesekali dia melirik ke anak perempuan yang mengejeknya itu—dia termasuk kelompok yang masuk grand finale. Menteng tersenyum sinis padanya. Si anak perempuan menatap sinis Menteng, seolah berkata “aku tak takut”.
Juri menganggukkan kepala. Bel berbunyi, tanda pertandingan di mulai. Anak-anak mulai fokus, menatap juri dengan tajam. Menteng menatap rileks, sesekali dia melirik sinis ke anak perempuan itu.
Pertanyaan demi pertanyaan panjang dimulai. Kalian tahu? Semua perkiraannya tentang soal itu hampir benar. Bahasa latin soal bakteri pun keluar. Bahkan, bahasa latin dan bahasa inggris juga keluar. Tentu, di sini keunggulan Acel dalam mengingat bahasa. Nico memahami soal, dibantu Menteng yang hapal teori, lantas dirapikan bahasanya oleh Acel. Nilai pertama diraih oleh sekolah kami.
Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, masih sekolah kami unggul. Beberapa bisa dijawab oleh sekolah lain. Sekolah anak perempuan yang mengejek Menteng dan sekolah kami selisih tipis. Menteng menghembuskan napas panjang, melirik sinis ke perempuan itu. Acel menyikut Menteng agar fokus.
“Pertanyaan terakhir, skor terbesar,” ujar Juri, membuat semua peserta lomba dan penonton tegang.
“Seperti kita tahu, ada cacing hati pada sapi. Menyebabkan, manusia yang mengonsumsi hati sapi, cacing ikut masuk ke dalam tubuh manusia. Setelah diselidiki, ternyata penyebab utamanya adalah karena sapi mengonsumsi rumput dan kangkung yang berada di pinggir sungai. Mengapa demikian?”
Aku menghela napas keras. Gila, pertanyaan yang sulit menurutku bagi anak seusia Acel, Nico, dan Menteng. Lihat, mereka saja mukanya pucat, menatapku perlahan. Muka kekhawatiran. Aku tersenyum, memberi semangat. Dia tetap tenang saja, tidak panik.
“Abang tidak panik?” bisikku.
Dia tersenyum simpul. “Tidak.”
“Baiklah, kami beri waktu satu menit untuk berdiskusi,” ucap Juri.
Waktu berjalan. Ketiga kelompok kasak-kusuk membicarakan pertanyaan. Muka Menteng dan Nico tegang. Mereka saling tatap. Namun, tidak bagi muka Acel. Dia tenang, dan tersenyum lebar. Tanpa berdiskusi dengan Menteng dan Nico, Acel menekan tombol pertama kali. Peserta lomba melihat Acel tidak percaya, termasuk Nico dan Menteng.
“Silakan,” ujar juri.
Acel berdeham pelan.
“Saat kotoran hewan ternak keluar, maka telur juga keluar dan menetas menjadi larva yang disebut dengan Mirasidium. Mirasidum akan masuk ke siput Lymnea dan menjadi Sporokista. Sporokista akan berkembang menjadi Redia dan Redia akan berubah menjadi Serkaria. Serkaria akan meninggalkan tubuh siput dan menempel pada rumput atau kangkung. Eh, bukankah, siput kebanyakan ada di pinggir kali sawah-sawah? Serkaria yang menempel di rumput akan berubah menjadi Metaserkaria. Nah, Metaserkaria inilah yang berbahaya, rumput dimakan hewan ternak dan Metaserkaria ikut sudah ke dalam pencernaan sapi. Jadilah, cacing muda.” papar Acel begitu gamblang. Bahkan, bahasa latin pun dia benar dalam pengucapan.
Ketiga juri menatap Acel heran. Bahkan,menurunkan kacamata, saking tidak percayanya yang menjawab adalah anak kelas lima SD. Dia juga terperangah, lantas tersenyum lebar, reflek bertepuk tangan. Aku ikut bertepuk tangan. Penonton yang tersisa ikut bertepuk tangan. Menteng dan Nico melongo menatap Acel.
Ketiga juri berdiri memberikan standing applause lalu mengangkat papan, memberikan nilai sempurna bagi jawaban Acel. Mereka memberi pengumuman bahwa pemenangnya, tentu Acel, Nico, dan Menteng. Mereka saling berpelukan dan bersorak sembari mengepalkan tangan.
Penyerahan piala kejuaraan diberikan setelah sepuluh menit pertandingan. Acel, Nico, dan Menteng berdiri di podium juara pertama. Nico mengangkat piala tinggi-tinggi. Aku mengelap air mata saat piala itu diserahkan padaku. Dan aku serahkan ke dia. Atas bantuannya, kami bisa maju sejauh ini.
Para peserta lain menyalami Acel, Nico, dan Menteng satu persatu. Tibalah, si anak perempuan yang mengejek bersalaman dengan Menteng.
“Oh, kau mau bersalaman?” Menteng mengulurkan tangan, tersenyum sinis.
“Selamat,” ucapnya pendek.
“Apa? Aku tak dengar?” Menteng menodongkan telinganya.
“SELAMAT!” serunya sambil melotot.
Menteng terkekeh. Puas sekali balas dendamnya berhasil. “Namamu siapa?”
Aku tertawa pelan. Pintar sekali Menteng modus disaat yang tepat.
“Hana, kau?” tanyanya malu-malu.
“Menteng, anak laki-laki yang paling cerdas,” jawabnya sambil membusungkan dada.
“Berlagak sekali kau, Menteng. Acel lah yang menjawab pertanyaan terakhir,membuat kita menang!” Nico ikut menimbrung.
Menteng menatap sebal ke Nico. “Oi, aku juga sudah menjawab banyak!”
Hana tertawa, lantas menyalami Nico dan Acel. Dia berjalan meninggalkan Menteng. Entahlah, Menteng menatap terus pada Hana.
Hana berhenti. Berbalik badan. “Kalau kau bisa masuk SMP di sini, aku mau berteman denganmu.” Dia langsung berlari menyusul teman-temannya.
Acel dan Nico terbatuk-batuk kompak. Muka Menteng mulai merona. Dia juga ikut tertawa, apalagi aku. Ternyata, dunia anak-anak juga membutuhkan suatu perasaan, ya? Eh, apakah iya itu perasaan? Mungkin, Menteng belum tahu namanya—dan aku tak berniat memberitahunya.
Kami pulang dengan ramainya ledekan Acel pada Menteng dan kebanggaan membawa pulang piala. Membawa atas nama desa pelosok yang mempunyai anak-anak hebat meraih prestasi. Anak-anak yang mau berjuang keras demi tahu suatu ilmu dan menikmati perlombaan. Dan, kuharap impiannya bisa terwujud. Entah dari anak-anak ini atau anak-anak generasi berikutnya.
Dia tiba-tiba berhenti di depan kami. Tersenyum lebar. “Baiklah, mari kita bayar kerja keras kita hingga bisa meraih piala ini. Ayo, kita berkemah bulan depan! Kita lihat bintang bertaburan dan malam yang menyenangkan di atas bukit. Setuju?”
“SETUJU!” jawab mereka serempak. Aku mengangguk, tanda setuju, tersenyum lebar padanya. Apakah, sudah saatnya aku beritahu, jawabanku atas pertanyaannya kemarin?
***
Seminggu setelah perlombaan, tentu warga heboh dengan kemenangan itu.
Warga berbondong-bondong ke sekolah, termasuk Hamak dan Hinak. Warga lantas mencari ketiga anak itu, menggendong tinggi-tinggi, padahal pembelajaran sedang berlangsung. Mereka antusias dan bangga sekali, akhirnya desa mereka yang pelosok bisa ada namanya daerah luar sana.
Tidak hanya warga yang bangga, Menteng selalu membusungkan dada, bangga sekali apa yang dia capai. Selalu membual ke sana-ke mari, bercerita perjuangannya meraih kemenangan itu.
“Aku harus memenangkan pertandingan itu, wajib diejek terlebih dahulu memakai sepatu butut!” serunya saat di duduk di longboat. Aku mendengarnya sendiri, menemani mereka memancing ikan—padahal mereka bisa mencari ikan tanpa memancing.
“Sungguh?” Si korban bualan, Itok, mendengarkan sungguh-sungguh.
Menteng mengangguk mantap. “Sungguh, bahkan, aku harus minum kopi banyak!”
“Bualnye! Minum satu gelas kopi saja sudah tidur awal,” seru Acel cekikikan. Membuat Menteng kesal.
“Kau tahu sendiri, kopi tidak semuanya membuat orang susah tidur!”
“Tapi kau bilang banyak minum kopi!” tanya Acel sambil memicingkan mata.
Menteng menggaruk kepala dengan cepat. “Taulah! Malas aku bercerita.”
Itok menatap Acel dan Menteng bergantian. “Jadi, Menteng bohong?”
“Enak saja bohong!” jawab Menteng mengkal.
“Tak bohong, tapi berlebihan!” jawab Nico yang sedari tadi diam, fokus ke pancingan.
“Aku tahu yang tidak bisa membuat Menteng tidak bisa tertidur.” Acel menyipitkan mata, pura-pura bergumam.
“Apa?” tanya Menteng.
“Apalagi kalau bukan Hana yang senyumnya manis bak madu lebah hutan.”
Muka Menteng mulai merona. Nico dan aku tertawa keras, sampai perahu bergoyang sedikit. Itok menatap kami penasaran.
“Hana? Siapa Hana?” tanya Itok.
“Pacar Menteng,” bisik Acel, tapi dengan suara yang keras.
“Heh, sejak kapan Menteng anak paling cerdas di sungai Kapuas pacaran? Tak ada. Adanya bersungguh-sungguh belajar. Kau itu, juga harus rajin belajar Acel. Nilai Matematikamu masih di bawah lima puluh!”
Acel menepuk lengan Menteng sambil melotot. “Bual! Tinggal akui kalau kau menyukai Hana, kan?”
“PANCINGKU BERGERAK!” Menteng berseru. Mengalihkan pembicaraan lebih tepatnya. Kami berfokus ke pancing Menteng—yang sedari tadi belum mendapatkan ikan. Aku sih, tidak ikut memancing. Membaca di atas longboat sambil menemani anak-anak, menyenangkan juga. Aku melihat antusias mereka, menutup buku. Dulu, apakah aku dan Ruki sebesar itu antusias-nya?
“BESAR PASTI, HAHA!” seru Menteng lagi. Nico dan Itok membantu di samping Menteng.
“Kita angkat hitungan ketiga. Satu ... dua ... tiga...!”
Kail terangkat. Putus. Ketiga anak itu terjungkal ke belakang.
BYURR!
Mereka tercebur ke sungai. Aku dan Acel berpegangan pada longboat yang berguncang.
“Kalian baik-baik saja?” tanyaku.
TAK! Nico menjitak kepala Menteng.
“Gara-gara kau, kita semua tercebur!”
Itok menatap jengkel Menteng.
“Dasar, Hana pembawa sial!” teriak Menteng lagi.
TAK! Satu jitakan dari Nico. TAK! Satu jitakan dari Itok.
“ITU KARENA KAU!” teriak mereka bersamaan.
Acel dan aku tertawa kecil. Kami membantu mereka bertiga naik ke longboat.
“Lebih baik, kita kembali saja. Ibu takut kalian masuk angin,” ucapku.
Nico mengangguk. Menghidupkan mesin longboat, kembali dengan beberapa ikan di ember masing-masing anak, kecuali Menteng. Tidak mendapatkan ikan, tercebur ke sungai iya. Aku menatap ke depan, teringat bersama dia ke Putussibau menggunakan longboat. Apa kabarnya? Apakah, dia baik-baik saja yang entah ke mana?
Seminggu ini, dia tidak ada di Puskesmas. Keterangan itu kudapatkan dari Itok. Tiga hari sekali pergi ke kota lantas kembali lagi. Sudah seminggu aku tidak bertemu dengannya. Merasa sebal sendiri, mengapa waktu terasa lambat saat dia tidak ada? Atau, setidaknya berilah waktu yang lebih cepat agar bulan depan segera tiba.
Hari ini, malam bulan purnama. Anak-anak sekitar keluar rumah, bermain di halaman depan rumah. Para ibu dan bapak berkumpul, sekedar mengobrol dan bertanya kabar. Aku di dalam kamar, menatap tumbuhan bunga anggrek hitam yang kubawa. Kotak hitam berukuran sedang kubuka perlahan, puluhan bunga anggrek hitam kering bertumpuk-tumpuk di dalamnya.
Perlahan, kubuka laminating plastik yang kubawa sejak dulu. Plastik laminating ini sudah ada lemnya, tinggal merekatkan saja. Satu persatu bunga kering itu kususun di plastik ini, kususun sebagus mungkin agar hasil memuaskan. Sesekali menyeka keringat di dahi.
Untuk apa? Yes, kubuat pembatas buku. Jelas, untuknya. Sebagai hadiah mau membimbing anak-anak kemarin, bahkan sampai rela lembur mengajari dan mencari materi untuk bahan belajar. Rela tertidur duduk di kursi. Rela membagi jatah makannya untuk kami berempat. Rela mengambil waktu me time-nya untuk mengajari anak-anak.
Aku tersenyum simpul. Menata bunga agar lebih apik. Sejenak, hatiku bertanya sendiri. Apakah, sudah saatnya kujawab pertanyaannya secara jujur? Saat aku berikan hadiah ini, kukatakan yang sesungguhnya. Akulah, gadis PMR yang berjalan di lorong Puskesmas saat tengah malam membawa teman yang hampir sekarat. Akulah, gadis yang selamat dari arus deras sungai yang mematikan itu.
Aku memejamkan sejenak. Menghela napas perlahan. Menatap pembatas buku yang hampir jadi. Kenapa sekarang aku merasa takut? Takut, apa yang selama ini kuharapkan tidak sesuai dengan apa yang akan terjadi setelah aku menjawab pertanyaannya. Aku takut, duniaku berubah berbalik dibanding hari-hari kemarin. Bagaimana bila kujawab pertanyaannya, duniaku akan lebih buruk dari sebelumnya?
Memang benar, ya. Jatuh cinta ibarat seperti makan gulali. Begitu manis saat awal, begitu menyenangkan, memberikan dampak baik bagi perasaan kita. Namun, saat kita makan terus-terusan, di suatu waktu menjadi takut. Takut terkena penyakit. Takut berdampak pada kesehatan. Yang pada akhirnya, memberi batasan untuk makan gulali.
Apakah, harus kulakukan memberi batasan padanya agar perasaan tidak seperti saat makan gulali? Apakah aku berusaha menyukainya dengan cara secukupnya? Terlambat. Sangat terlambat. Harusnya kulakukan saat aku masih menunggu empat tahun lalu. Harusnya, aku tidak bermuram durja, menangis sendiri, mengendalikan perasaan, percaya pada takdir bahwa perasaan pasti akan terbawa sendiri. Akan menemukan jalan pertemuan yang memang ditakdirkan.
Tanganku menggigil. Menghentikan menyusun bunga-bunga kering itu. Menatap bulan purnama. Menghela napas lagi. Pipiku mulai basah. Memikirkan atas kemungkinan-kemungkinan, yang bahkan belum tentu sesuai apa yang aku pikirkan. Ternyata, menyimpan perasaan sendirian memang tidak menyenangkan. Membuat pertanyaan sendiri dan harus menjawab kemungkinan dari diri sendiri.
Sepertinya aku memang belum siap mengatakannya. Hingga, kejadian besar itu, aku tahu jawabannya. Tanpa aku harus menjawab pertanyaannya.


 lu_r_an
lu_r_an