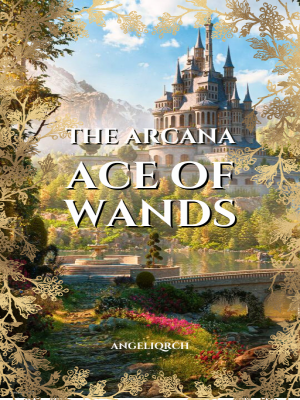Detak jarum jam mengisi keheningan ruangan persegi tersebut. Rena perlahan menyesap teh hangatnya dalam diam, ia kemudian merapatkan selimut tebal yang tadi diambil dari lemari berdebu. Sudah belasan tahun tidak ada yang menempati ruang kesehatan, membuat beberapa barang jadi agak apek.
"Bagaimana badanmu?" tanya Stevan pelan.
"Sudah tidak terasa pusing lagi. Terimakasih atas bantuannya dan maaf karena agak kasar tadi."
"Tidak masalah."
"Kalau begitu kami keluar dulu." Devan menarik tangan Ben yang wajahnya langsung berubah kebingungan.
"Aku akan mengantarmu pulang. Ayahmu pasti khawatir."
"Tidak perlu. Aku-" Rena menatap Stevan dengan dahi berkerut.
Mereka saling tatap selama beberapa detik.
"Ah! Maksudku... orang tuamu pasti khawatir."
Rena tidak bereaksi apapun, ia kemudian menghela nafas pendek.
"Sejak tadi aku tidak mau berpikiran aneh, jadi katakan saja yang sejujurnya. Apa kau salah satu stalker? Tenang saja, aku tidak akan melapor ke polisi asalkan kau diam dan pergi jauh-jauh dari kota ini. Aku pikir itu sudah adil karena asal kau tau, tindakan yang kau lakukan itu salah. Maksudku kenapa harus aku? Apa karena aku cantik? Ha! Yang benar saja, aku tau aku ini punya aura yang sangat besar jadi sulit untuk mengalihkan pandangan dariku. Tapi-" Kalimat itu terputus saat ia melihat Stevan tertawa kecil.
"Kau pikir ini lucu? Ini termasuk tindakan ilegal tahu!" Suara Rena yang meninggi langsung membuat Stevan terdiam. Ia berdehem pendek sambil mencoba menahan tawa.
"Apa kau percaya hantu?" tanya Stevan, ia melirik ke sudut ruangan.
"Ha-hantu? Itu kan hanya mitos. Tapi aku tidak bisa bilang tidak percaya." Wajah gugup Rena tampak gemas, ia ikut menoleh ke belakang dengan tatapan takut.
"Bagaimana dengan vampir? Apa kau percaya?"
"Jangan ajukan pertanyaan aneh dan jawab saja pertanyaanku tadi." Gadis itu mendengus sebal. Ia minum satu tegukan sambil memberikan tatapan mematikan.
"Kalau kau menjawabnya aku akan menjawab pertanyaanmu juga."
"Aku tidak percaya. Itu hanya karangan orang dewasa. Puas? Jadi jawab. Kau stalker?"
"Satu lagi. Apa kau percaya Santa Claus?"
"Ha! Apalagi ini, apa kau anak kecil? Jaman sekarang siapa yang percaya dengan hal semacam itu? Cepat jawab dan hentikan pertanyaan tidak masuk itu."
"Aku tidak bisa mengatakannya kalau kau sejak tadi bilang tidak percaya. Tapi aku bukan stalker."
"Lalu?"
"Sudah kubilang kan?" Satu alis Stevan naik. Rena kembali mendengus sebal, ia akhirnya paham.
"Kau mau mengatakan kalau kau itu makhluk jadi-jadian? Goblin? Malaikat pencabut nyawa? Atau apa? Jangan jadikan hal-hal aneh untuk alasan. Aku mulai kemarin tidak percaya lagi dengan manusia terutama laki-laki yang sejak awal sudah tidak dapat dipercaya."
"Aku sejak awal tidak pernah berbohong. Aku hanya ingin melindungi hal yang harus kulindungi." Suara yang terdengar sandu tersebut sedetik kemudian membuat hati jadi luluh sebentar ditambah tatapan wajah Stevan yang mendadak seperti peran utama pria yang tengah mengatakan cinta pada pasangannya.
"Ada apa dengan wajahmu. Hampir saja aku tertipu," gumam Rena. Saat ia melihatnya, tatapan itu memang tampak meyakinkan. Bukan tatapan buaya darat yang sering lewat.
"Lupakanlah. Jam berapa ini. Aku harus pulang." Selimut tersebut ia singkap, bersiap turun.
"Istirahatlah lebih lama, diluar masih dingin."
"Kau punya mobil?"
Devan ragu-ragu memberikan kunci mobilnya. Ia sejak pagi membiarkan kendaraan roda empat tersebut istirahat dan memilih naik kendaraan umum karena sudah terlalu lama dipakai berkendara dua hari yang lalu. Bolak balik dari kota lain untuk sekedar mengambil beberapa peralatan pamannya yang rusak.
"Setengah jam?" Pertanyaan kesepuluh itu kembali keluar. Stevan mengangguk malas.
"Kenapa tidak pakai taksi saja? Kau kan kaya raya! Benar! Taksi!"
"Apa ada taksi yang lewat depan tokomu ini? Sepertinya aku pernah lihat, beberapa puluh tahun yang lalu. Saat daerah ini masih ramai."
Hening. Devan menatap kunci mobilnya, menggenggam erat. Stevan masih menjulurkan telapak tangannya, siap menerima.
"Ah, baiklah. Jangan lama-lama, aku tidak mau keluar uang lagi kalau harus masuk bengkel."
"Tenang saja, aku akan tanggung jawab. Seperti katamu, aku kaya raya. Duitku banyak, kalau belum digunakan." Stevan menerima kunci bergantung bintang tersebut lalu buru-buru pergi.
***
Jalanan agak lenggang, tidak banyak mobil yang lewat. Mungkin karena ini sudah sore, lampu-lampu jalan juga sudah menyala 15 menit yang lalu. Rena hanya diam sepanjang jalan, ia sebenarnya tidak mau pulang tapi ia masih punya hati. Takut ayahnya khawatir, handphonenya tidak mau menyala sejak tadi, entah mati karena pingsan tadi atau habis baterai ia juga tidak tahu.
Navigasi sudah dipasang alamat menuju komplek tempat Rena tinggal, Stevan hampir saja langsung menancap gas sesaat setelah naik mobil. Ia lupa kalau tindakannya bisa berbahaya.
"Kau mau kubelikan minuman hangat dulu?" tawar Stevan yang sejak tadi menoleh, bisa dihitung ia sudah lebih dari sepuluh kali menoleh ke arah Rena. Menatap raut wajah datar yang sejak tadi tidak berubah.
"Tidak perlu." Kecil sekali suara gadis itu, nyaris tidak terdengar.
Tidak menurut, Stevan berhenti di depan kafe yang agak sepi. Ia segera turun dan masuk ke dalam kafe. Beberapa menit kemudian kembali dengan kopi hangat dan roti.
"Kau harus makan. Jangan sampai pingsan lagi seperti tadi."
Rena mau tidak mau menerimanya. Ia menyesap sedikit kopi lalu makan satu gigitan roti. Stevan sengaja membeli roti yang jarang Rena makan. Stroberi. Supaya gadis itu tidak curiga.
"Makanlah lagi, perutmu pasti kosong. Apa kita makan dulu ke restoran?"
Rena hanya diam. Ia kemudian menatap Stevan sebentar.
"Aku memang agak lapar."
Senyum lebar mengembang, Stevan langsung tancap gas. Menuju restoran terdekat. Mereka makan sup daging dan pangsit rebus. Rena makan beberapa suap saja, walau ia hanya makan sedikit saat sarapan tadi, tapi ia tidak begitu berselera makan makanan berat. Padahal baru beberapa menit yang lalu gadis itu bilang lapar.
"Kau kebetulan memilih tempat ini kan?" tanya Rena curiga.
"Tentu saja. Apa kau pernah kesini? Bukankah ini restoran populer? Itu yang dikatakan internet." Stevan menunjuk handphone, ia berusaha mengatur wajahnya yang sempat tegang tadi.
"Ya, maafkan aku karena sudah curiga."
"Tidak usah dipikirkan." Ia makan lagi. Tapi pandangannya teralihkan dengan mangkuk Rena yang masih penuh.
"Makanlah lagi. Kau sudah kenyang?"
"Aku tidak begitu berselera. Kalau kau sudah selesai lebih baik kita cepat pulang."
Stevan agak kecewa, ia punya jutaan cara untuk membuat gadis itu bahagia. Tapi kebahagiaan seseorang tidak bisa dipaksakan, semua itu berasal dari hati. Kalau hati itu masih belum patah seutuhnya, ia masih bisa merekatkannya dengan lem. Tapi kalau sudah terbelah dua, akan sulit mengembalikannya. Aura hitam yang awalnya berkurang sedikit saat gadis itu pingsan kini semakin lama semakin besar. Kegelapan menyelimuti gadis itu, Stevan bisa melihatnya.
Aura hitam yang mirip asap hitam tebal tersebut tampak menyeramkan, ia tidak pernah melihat yang sebesar ini.


 sitirobiatul
sitirobiatul