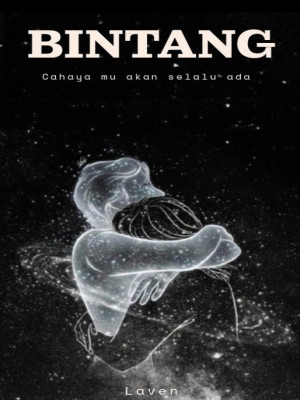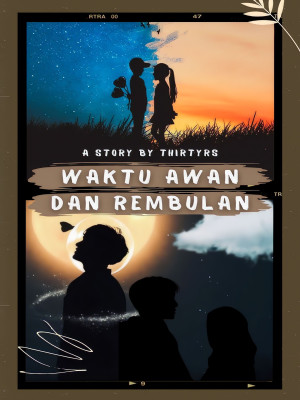Tiga bulan sebelum kematian Marcus.
Hari ini, Ibu mengajari Reza memasak sayur setelah tahu bahwa remaja itu menyukai sayur bayam buatan Ibu. Aura tersenyum kagum menonton Reza yang melakukan segala hal sesuai intruksi Ibu dengan lihai dan sempurna. Persis kuah sayur mendidih, terdengar suara dorongan pintu kasar dari luar.
Ketiga insan di dapur menoleh serempak. Suara itu khas tanda Marcus datang. Aura menghela napas tidak suka. Tidak butuh waktu lama hingga pria itu menampakkan sosoknya yang langsung melangkah ke kamar Ibu. Untuk apa lagi selain dengan tujuan mengambil lembaran uang di dompet Ibu.
Aura hendak mengikuti ayahnya untuk mencegah uang hasil kerja susah payah ibunya hilang sia-sia kesekian kalinya, tetapi ditahan. Ibu tersenyum pelan, beranjak menghampiri suaminya. Akhir-akhir ini, Marcus sudah jarang berteriak-teriak marah atau memukuli Ibu dengan sesuatu. Tetapi masih sering tiba-tiba datang untuk meraup semua uang yang ada.
“Di mana sisa uangmu?” tanya Marcus dengan suara berat yang serak tanpa memandang istrirnya.
Ibu membuka loker lemari, mengambil beberapa lembar uang tersisa di sana. Menurut menyerahkannya. Aura yang menyaksikan dari luar pintu mengepalkan tangannya erat-erat. Ibu memberikan uang terakhir yang ia punya.
“Hanya ini?” tanya Marcus lagi, menghitung jumlah uang.
Ibu mengangguk.
Marcus mengomel pelan sebelum meninggalkan kamar, hendak pergi lagi dari rumah. tetapi lengannya dicegah Ibu. Pria tersebut menoleh dengan wajah acak-acakannya yang seram seperti preman.
“Kamu pasti belum makan. Reza baru saja membuat sayur bayam pertamanya, cobalah terlebih dulu.” Ibu tersenyum menuntun Marcus ke dapur.
“Aku tidak tertarik!” seru Marcus saat Ibu menuangkan sayur panas yang baru saja diangkat dari panci ke dalam mangkuk.
Ibu memberikan sendok ke jemari suaminya, tersenyum lembut. “Setidaknya cobalah sedikit. Sudah lama kamu tidak makan makanan rumah.”
“Kubilang tidak—” tolak Marcus lagi.
“Ayolah—”
“MENYINGKIR!” bentak Marcus mendorong mangkuk sayur di hadapannya hingga menumpahi lengan Ibu yang langsung meringis kepanasan. Kulitnya langsung melepuh merah.
Aura refleks mendekat, berjalan di antara pecahan mangkuk yang berserakan. “Astaga, Ibu nggak apa-apa?” tanyanya cemas.
Reza juga ikut memeriksa lengan Ibu dengan raut wajah khawatir.
“Tidak bisakah Ayah berhenti menyakiti Ibu?!” seru Aura menatap ayahnya marah. “Sekali saja menghormatinya yang sudah mencari uang yang selama ini Ayah ambil sembarangan! Ingat berapa kali pukulan yang sudah dirasakan sosok tanpa dosanya karena dirimu!”
Marcus tidak mendengarkan, bahkan tidak melihat ke arah putrinya.
“Pikirkan lagi apakah kau bisa disebut suami yang baik dengan semua perilakumu. Karena aku bahkan tidak bisa terima menganggapmu sebagai seorang ayah.” Kedua mata Aura mulai memerah dan berkaca-kaca. “Jangan pernah kembali ke rumah ini. Jangan pernah kembali karena kau bukan siapa-siapa lagi di keluarga ini! Aku tidak akan pernah sudi memanggilmu ayahku lagi! Pergi!”
Marcus mengembuskan napas keras, lalu berjalan meninggalkan mereka.
Reza membantu Aura mengantar Ibu ke puskesmas lewat pintu belakang, bahkan sebelum Marcus benar-benar keluar.
♦♦♦
“Aku benar-benar benci! Kenapa Tuhan harus menakdirkanku menjadi anak dari pria itu?” gusar Aura saat menunggu di luar kamar puskesmas. Ibu sedang diobati.
Reza menelan ludah, salah tingkah menghibur Aura.
Dokter puskesmas keluar dari ruangan, menghampiri Aura yang langsung berdiri. “Kulitnya yang melepuh mungkin perlu waktu untuk disembuhkan. Tetapi ibumu baik-baik saja, kamu bisa masuk ke dalam untuk menemuinya.”
Aura mengangguk, cepat-cepat membuka pintu ruangan ibunya berada. Dilihatnya Ibu sedang menutup mata. Aura tidak berani membangunkannya, ia hanya diam menunggu ibunya membuka mata.
“Ibu tahu kamu marah, Aura,” ucap ibunya tanpa membuka mata. “Tetapi kalimatmu keterlaluan. Dia tetap ayahmu, apapun yang terjadi. Tidak ada hal yang bisa memutus hubungan darah antara orang tua dan anaknya. Tidak ada.”
Aura termangu.
Ibu menghela napas sembari menatap putrinya.
“Kita tidak bisa memilih oleh siapa kita dilahirkan, tidak bisa meminta seperti apa orang tua kita. Tetapi kita selalu bisa memilih akan jadi seperti apa anak kita. Jadi Ibu harap, kamu menjadi anak yang baik dan sabar, tak peduli seberapa kejam takdir yang datang mengunjungi. Percayalah, semuanya akan baik-baik saja pada akhirnya.”
“Kenapa … Ibu memberi semua uang yang ada?” tanya Aura pelan.
“Jika ayahmu memintanya, maka berarti dia memang membutuhkannya. Apa salahnya berbakti kepada suami sendiri?” Ibu bertanya balik.
Aura keluar dari ruangan dengan wajah murung. Kenapa pikirannya dengan ibunya tidak pernah sejalur? Tidak dapat dipercaya, Ibu masih membela ayahnya sampai saat ini. Tidak ada tanda-tanda kekecewaan apalagi kemarahan sama sekali. Sungguh aneh.
“Hey, aku membawakanku sayur yang tadi kumasak. Mau coba, nggak?” Reza tiba-tiba menghampiri dengan sekotak tempat makan.
Sebenarnya ingin sekali Aura tolak dengan alasan tidak lapar, tapi melihat wajah antusias Reza memamerkan makanan buatannya, gadis itu mengangguk. Reza tersenyum lebar, membuka kotak bekal sembari duduk di kursi panjang besi.
Pandangan lelaki tersebut lamat-lamat pada Aura yang menyuap sayur bayam dengan senyum menghiasi.
“Bagaimana rasanya?”
Aura balas tersenyum, setengah lebih ceria dari sebelumnya. “Untuk pemula sepertimu, sayur ini sudah lebih dari kata enak. Meskipun garamnya kebanyakan sedikit, tapi bukan masalah bagiku, aku lebih suka asin daripada hambar.”
Reza bersorak pelan, “Nilainya?”
“Delapan per sepuluh? Atau mungkin, sembilan per sepuluh karena kamu yang memasaknya.” Aura menyantap lagi makanan di hadapannya, kali ini dengan nasi putih yang sudah disiapkan Reza di kotak makan sebelumnya.
Reza tertawa pelan, “Penilaian yang bagus.”
“Tapi subjektif,”
“Biarin,” balas Reza. “Nanti mungkin seru kalau aku jadi koki, terus banyak yang suka makanan buatanku. Apa aku buat restoran saja, ya?”
“Kalau kamu jadi koki, aku jadi kepala kokinya.”
“Nggak lah, kan restorannya punyaku, kamu nggak jadi apa-apa. Kalau mau makan, bayar dulu dua kali lipat.”
“Heh!” Aura memukul Reza pelan dengan seringai lucu.
♦♦♦
Sejak awal, Reza tidak pernah merepoti siapapun. Bahkan saat masih di panti asuhan, pengurus panti senang sekali menyekolahkannya dengan beasiswa di sekolah yang cukup bagus dibanding sekolah anak-anak panti lainnya. Ia tidak pindah sekolah meski sudah berada di bawah naungan Marcus ketika usianya hampir 13 tahun.
Sementara Aura yang ketika keluarganya masih baik-baik saja bersekolah di sekolah swasta yang banyak digemari di kotanya, harus pindah ke sekolah yang sama dengan Reza saat menginjak kelas sembilan dikarenakan biaya yang bengkak di sekolah lamanya. Syukurlah, di sekolah yang sama seperti Reza, Aura juga bisa mendapat beasiswa karena kepintarannya.
Sudah hampir setengah tahun keluarga Aura pindah ke kontrakan kecil dekat dengan sekolah. Enam bulan pula lamanya Aura belajar di tempat yang sama dengan Reza. Kelas mereka bersebelahan.
“Seperti yang kamu minta, Aura, besok aku akan pergi meninggalkan kalian.” Reza berbicara ketika mereka sedang mencoba baso aci di kantin sekolah.
“Pergi?” Bibir Aura hampir melepuh karena kuah baso yang panas, ditambah keterkejutannya gara-gara kalimat yang didengar.
Reza mengangguk, memasang wajah serius.
“Ke-kenapa?” Aura menyembunyikan wajah kagetnya, bersikap biasa saja.
Reza menyeringai kecil, “Pertanyaan yang tepat saat seseorang mau pergi harusnya bukan kenapa, tapi ke mana. Hey, kamu sedih ya, aku mau pergi?”
Aura menelan ludah, “Aku baru saja mau bertanya ke mana setelah kamu menjawab kenapa.” Malas melihat wajah puas Reza, gadis itu kembali mencicipi kuah baso seusai meniup beberapa kali.
Reza tertawa, “Kasihan. Bukan kok, aku bukan pergi jauh nggak kembali seperti yang kamu cemaskan. Besok ada lomba iptek tingkat nasional di ibukota, sekolah mengutusku mengikuti lomba tersebut besok.”
Aura menoleh lagi, “Serius? Keren! Berapa hari?”
“Tiga hari. Kalau lama-lama, takut kamu kangen. Nanti galau lagi, bahaya.” Reza santai menggigit basonya. Ber-hah kepedesan.
“Dihh,” cibir Aura. “Lalu bagaimana dengan study tour? Masa kamu nggak ikut?”
Reza menggeleng, “Ikut kok. Nanti kasihan kalau kamu sendirian di sana, jomblo, bakal aku temani kok.”
Aura tidak menggubris kalimat lelucon Reza. “Study tour kan tiga hari lagi. Nanti pas kamu masih di sana, yang lain sudah pada berangkat. Ketinggalan, dong.”
“Jangan khawatir, wali kelas siap mengantarku ke sana sehabis lombanya usai. Priviledge, khusus untukku.” Reza menyatukan ibu jari dan telunjuknya di dagu, bergaya sombong.
Meski sudah ditahan, Aura tetap tersenyum melihatnya. Dia malah sedikit terkekeh akibat tingkah Reza yang konyol.
Reza dan Aura merupakan peraih peringkat pertama dan kedua paralel seangkatan. Bayangkan betapa senang Ibu mendengar kabar tersebut. Apalagi khusus untuk ketiga besar murid peringkat paralel, biaya study tour digratiskan. Mereka hanya perlu membawa uang saku jika ingin membeli sesuatu.
♦♦♦


 grey_nor
grey_nor