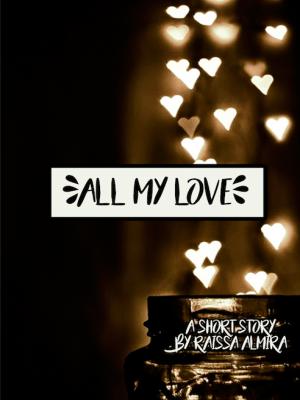“Dasar wanita tidak tahu diri! Hanya ini uang yang didapat setelah bekerja seharian, hah?”
Lelaki itu menghantam sesosok wanita kurus di hadapannya menggunakan kayu rotan. Berkali-kali, hingga tangannya mulai merasa lelah. Berhenti sebentar untuk membentak dengan ucapan yang kejam, lalu mengayunkan kembali kayu rotan. Entah sudah keberapa kalinya, bekas sabetan di tubuh wanita tersebut tidak terhitung lagi. Ia hanya meringis menahan sakit dengan air mata yang mengalir.
“Berhenti!” seru Aura menghalangi sabetan pria itu, yang malah menyakiti pinggangnya. Sedikit mengaduh, Aura tetap berdiri tegak melindungi ibunya.
“Anak zaman sekarang! Beraninya memberontak pada ayahmu!” Marcus melotot marah. Menakutkan melihat matanya yang merah.
Aura balas menatap tidak terima.
Ayahnya baru pulang tadi subuh, dengan pakaian bau alkohol. Tidak ada salam, dia membuka pintu yang tidak dikunci dengan kasar. Terakhir kali Ibu mengunci pintu, Marcus mengamuk menggebrak-gebrak pintu, lalu menghardik Ibu ketika pintu sudah dibuka. Sampai di rumah, Marcus mengacak-acak seisi kamar Ibu—yang sebenarnya juga kamarnya—dan merampas setiap uang yang ada. Tidak puas dengan jumlah nominalnya, pria bengis itu berteriak-teriak membangunkan Ibu.
“Kau mau membela ibumu, begitu? Dasar sok jagoan! Minggir, atau kau rasakan pukulanku!” hardik Marcus, kembali memainkan rotannya.
Aura sigap memeluk ibunya. Tubuhnya terkena rotan yang diayunkan tanpa sedikitpun belas kasihan. Pergelangan tangannya, juga bagian punggungnya terasa nyeri. Namun pastinya tidak lebih sakit dari yang dirasakan Ibu.
Dua kali. Aura memejamkan mata merasakan tubuhnya disakiti.
Tiga kali. Apa yang bisa dia lakukan? Lihat ibunya, lemah tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Mereka tidak bisa menghindar. Biarlah Aura menahannya, dia rela merasakan ini demi ibunya.
Keempat kalinya Marcus hendak merotan Aura, tiba-tiba tangannya dicegah oleh seseorang.
“Kau juga mau melawanku, rupanya! Anak tak tahu untung! Aku sudah merawatmu, tapi apa balasanmu, hah?” seru Marcus.
“Hentikan, tetangga akan ke sini jika suara pukulan tetap terdengar.” Reza mengalihkan, mencari alasan.
Marcus berpikir sekejap, lalu mengibaskan tangan Reza dan melempar rotan sembarang arah. Kalau saja Reza tidak cepat menangkap rotan yang melayang itu, mungkin Aura akan terkena rotan keempat kalinya.
“Kalian baik-baik saja?” tanya Reza cemas.
Pertanyaan bodoh, Aura mendengus. Dia melepaskan pelukan di tubuh ibunya yang langsung lunglai ke belakang. Aura menahan tubuh ibunya, menoleh pada Reza, “Bawa Ibu ke puskesmas segera.”
Reza mengangguk, “Kamu juga.”
Aura menolak, “Aku baik. Pergilah, aku akan mengurus rotan ini. Berusaha mematahkannya, atau membuangnya jauh-jauh. Satu yang pasti, aku nggak akan membiarkan pria itu memukuli Ibu lagi.”
Reza menghela napas, “Baiklah. Aku bakal memanggil Lucy untuk menemanimu, sekaligus mengobati lukamu.”
Aura hanya mengangguk sekilas. Begitu Reza membawa Ibu pergi, tak lama panggilan bernada khawatir disertai hentakan langkah kaki yang terburu-buru terdengar.
“Astaga!” jerit Lucy melihat luka yang ada di pergelangan Aura ketika gadis itu menggulung lengan panjangnya.
Dengan cepat, Aura menyembunyikan luka tersebut dengan lengan baju. Sedikit meringis saat Lucy mencoba memegang punggungnya.
“Aduh, maaf!” refleks Lucy. “Punggung lo juga kena? Ya ampun, Ra, kenapa nggak ikut ke puskesmas?”
Aura tidak menanggappi. Gadis itu tidak ingin Reza dan ibunya tahu tentang bekas lukanya. Hanya akan memperkeruh keadaan. Ibu akan menangis tidak keruan melihatnya, yang akan menambah rasa sakit di hati Ibu.
Lucy membantu mengobati luka di pergelangan tangan Aura setelah berkali-kali dibujuk. Hampir satu jam kemudian, Lucy pamit bersamaan dengan Reza yang datang kembali.
“Bagaimana Ibu?” tanya Aura.
“Sudah siuman, tapi masih lemas. Ibu memanggilmu, juga memintamu diobati.” Reza menyampaikan pesan.
Ibu tahu. Aura menelan ludah. Tentu saja, wanita itu adalah orang yang paling mengenalnya. Diam sejenak, Aura melangkah keluar diikuti Reza yang bersyukur karena kali ini tidak ada penolakan dari Aura.
Tiba di puskesmas yang jaraknya tidak jauh dari rumah, Aura dapat menyaksikan ibunya yang tertidur tenang. Wajah letihnya menunjukkan betapa banyak cobaan yang menghampiri hidupnya. Perempuan berumur hampir 40 tahun itu membuka matanya perlahan. Sosok Aura adalah yang pertama ia tangkap.
Lengang sejenak. Kedua ibu-anak tersebut saling tatap.
“Lukamu sudah diobati?” Kalimat pertama ibunya.
Aura hanya bisa menunduk, enggan menjawab belum. “Aku akan melaporkan Ayah ke polisi,” tegasnya.
Ibu meraih tangan Aura, menggeleng. “Kamu nggak perlu melakukannya. Ibu baik-baik saja, Aura Sayang.”
“Aku yang nggak baik-baik saja melihat Ibu dipukuli!” seru Aura. “Kenapa Ibu nggak pernah mau melawan saat dipukuli?”
Ibu tersenyum, “Karena Ibu mencintai ayahmu.”
Aura memandang tidak percaya. Bagaimana ibunya bisa tetap mencintai sosok pria yang menyakitinya?
“Sejak Ibu memutuskan menikahi ayahmu, Ibu telah berjanji untuk selalu mencintainya apapun yang terjadi. Seburuk apapun takdir berubah, Ibu akan tetap menerima apa adanya sepenuh hati. Tidak berkurang sedikitpun rasa sayang Ibu.” Sembari mengenang masa lalu, Ibu mengusap jemari anaknya lembut.
“Mungkin kamu belum mengerti jalan pikiran Ibu sekarang, berpikir Ibu terlalu naif. Tetapi percayalah, Aura, sekali kamu menemukan lelaki pujaan hatimu, apapun yang dia lakukan—entah itu baik atau buruk—dia akan selalu sempurna di matamu. Maka berhati-hatilah memilih seorang laki-laki,” lanjut Ibu.
“Lalu kenapa Ibu memilih pria seperti Ayah?” tanya Aura tersenyum miris.
“Kamu juga tahu, ayahmu sebenarnya adalah orang yang baik. Sosok ayah yang menyenangkan. Coba kamu hitung, berapa banyak mainan yang ia belikan ketika kamu kecil dulu. Betapa sering ia menggendongmu di punggungnya, betapa dia rela meluangkan waktu dan menghabiskan tenaganya demi putri semata wayangnya. Ingatlah itu selalu saat kamu merasa membencinya, Aura.”
Tidak ada kalimat yang keluar dari bibir Aura. Bukan karena dia mulai setuju dengan perkataan ibunya, hanya saja Aura malas berdebat. Jalan pikiran mereka berlainan. Mau seberapa keraspun Aura meyakinkan ibunya, akan tetap nihil.
Aura bukan tipe orang yang suka mengingat masa lalunya. Apa yang penting dari masa lalu? Hanya orang yang terjebak dalam kenangan yang akan mengingat masa tersebut.
“Kamu bisa meminta bantuan Reza untuk menemukan lelaki terbaik untukmu. Dia dapat dipercaya,” saran Ibu sebelum Aura pamit meninggalkan ruangan.
Ibu baru pulang ke rumah menjelang senja. Itupun perlu dibantu petugas puskesmas yang mengantar Ibu karena tubuhnya yang masih lemah. Aura menyuapi ibunya semangkuk bubur.
“Untuk malam ini, lebih baik Ibu beristirahat saja,” bisiknya.
Syukurlah kali ini Ibu langsung menurut, balas berbisik terima kasih. Aura mematikan lampu kamar. Semoga malam ini Marcus tidak datang. Kondisi Ibu bisa lebih buruk karena pria itu.
Aura pergi keluar rumah untuk menghampiri Reza yang sedari tadi duduk menunggu di teras. Tidak ada percakapan di antara mereka selang beberapa saat, hanya duduk diam di kursi masing-masing. Suara jangkrik malam memecah lengang yang membekukan angin malam.
“Kamu bisa pergi, Reza.” Aura membuka suara. “Kamu selalu bisa meninggalkan rumah ini.”
Reza hanya mendengarkan. Ini sudah kesekian kalinya Aura membahas topik sensitif tersebut. Belasan kali Reza menolak, belasan kali pula Aura kembali membicarakan hal yang sama.
“Kamu nggak harus menghabiskan waktu menonton keluargaku yang acak-acakkan. Ini bukan pemandangan yang indah melihat ayahku memukuli ibuku setiap dia datang. Bukan pula rasa yang menyenangkan merasakan pukulan ayahku. Kamu sungguh lebih baik pergi.” Aura melanjutkan kalimatnya.
Reza masih diam, hanya helaan napasnya yang terdengar.
“Tawaran menjadi anak angkat walikota bukan sesuatu yang buruk. Kenapa kamu nggak menerimanya saja?”
“Sudah kubilang berkali-kali, aku nggak tertarik, Aura.” Reza menjawab sedikit kesal.
“Kamu nggak rasional!” seru Aura menoleh. “Bisa-bisanya kamu lebih memilih di sini, bersama keluarga asing yang hanya menyusahkanmu. Kamu bisa menggunakan kecerdasanamu dalam bidang IT seperti yang walikota bilang.”
“Kalian bukan orang asing untukku, Aura!” Reza menatap tajam. “Kamu dan Ibu sudah seperti keluargaku juga. Pun ayahmu yang meskipun sekarang kejam memukuli Ibu, tapi dia sering memerlakukanku dengan baik dulu. Lalu jika ibumu disakiti seperti ini, apakah aku bisa pergi begitu saja? Aku nggak akan membiarkanmu sendirian mengurus Ibu.”
Aura balas memandang tajam bola mata Reza yang hitam pekat.
“Aku nggak akan pergi. Nggak akan pernah.” Reza mengakhiri kontak mata, berkata tegas. Itu keputusan finalnya.
“Kita bahkan bukan keluarga,” Aura berkata ketus.
“Terserah, yang aku tahu kamu lebih dari sekadar teman. Aku bisa menganggapmu sebagai adik—seperti banyak adikku di panti asuhan dulu. Atau mungkin lebih. Dan Ibu, beliau sudah menjadi orang tuaku. Merawatku, memberiku makan dan tempat tinggal, juga kasih sayang. Kalaupun kalian bukan keluargaku, kalian telah berbuat baik padaku.”
Tidak ada tanggapan dari Aura.
“Berhenti membahas hal ini lagi, Aura. Jawabanku akan tetap sama, aku nggak akan pergi.” Reza menutup pembicaraan.
♦♦♦


 grey_nor
grey_nor