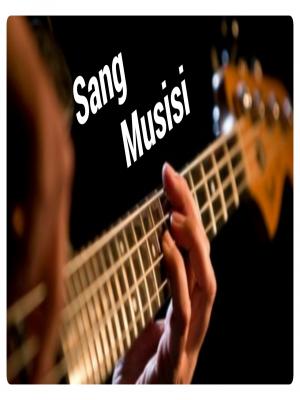Seperti yang dijanjikan Reza dalam email-nya, hari ini ia menelepon Aura tepat di waktu yang disetujui. Aura bukan tipe anak yang suka bolos pelajaran karena malas, tapi khusus sekarang, anak itu sengaja pergi ke gerbang belakang sekolah yang sepi untuk menerima telepon istimewa tersebut.
"Hai Aura," sapa Reza.
Aura menelan ludah sebelum balas menyapa pelan.
"Dua tahun lepas nggak mendengarmu bicara, suaramu masih sama. Bedanya, kali ini terdengar suram." Reza berbicara. "Kamu baik-baik saja?"
Aura mengangguk pelan, walaupun dia tahu Reza tidak dapat melihatnya.
"Entah apakah aku harus marah atau nggak, pada Lucy yang nggak pandai menjaga rahasia. Entah apakah keputusanku menghubungimu benar atau nggak. Dua tahun ini aku selalu berusaha menjauh dari segalanya tentangmu, Ra."
"Untuk melupakanku?" lirih Aura.
Reza tertawa pelan, "Kalaupun iya, aku punya alasannya. Maafkan aku. Aku nggak berniat melupakanmu."
"Bohong."
"Kamu boleh nggak percaya padaku," ucap Reza. "Meskipun kamu menganggap kalimatku dusta, tapi aku nggak pernah melupakanmu. Aku juga kangen."
Aura tidak dapat angkat suara mendengar ungkapan tersebut.
"Kangen Ibu juga. Sebenarnya aku ingin berkunjung, tapi mungkin bukan sekarang. Bukan juga nanti. Sebesar apapun rasa rinduku pada kalian, aku nggak mau kembali, Aura."
Aura menunggu kalimat berikutnya.
"Aku takut ayahmu."
Gadis itu mengernyit, "Pria itu sudah nggak di sini lagi. Apa yang harus ditakutkan?"
"Bagiku dia selalu ada, Aura. Selalu menghantuiku, ke manapun aku pergi, bahkan di sini. Bagaimana aku bisa kembali? Akan banyak sekali kenangan nggak mengenakkan tentangnya yang muncul ketika aku di sana." Reza berhenti sejenak. "Dan kamu tahu? Bertelepon denganmu seperti ini, juga membuatku takut. Ayahmu nggak pernah lepas dari benakku, semenjak aku pergi."
Aura menghela napas panjang.
"Hari terakhir kali aku melihat ayahmu, aku takut mengingatnya. Maafkan aku yang pengecut, Aura. Maafkan aku yang nggak bisa lagi menjadi seseorang yang pemberani untukmu." Reza berdehem pelan, "Sampaikan salamku pada Ibu. Bye, Aura."
Aura hendak meminta waktu lebih lama, tetapi batal.
"Bye, Reza."
Panggilan telepon ditutup. Sesingkat itu.
"Psstt, bukankah itu gadis yang bernama Aura? Yang dipanggil ke ruangan Kepala Sekolah itu." Terdengar bisik-bisik dari kejauhan.
"Benar. Kasus kematian Pak Marcus, dia ada hubungannya."
"Waduhh, jangan-jangan...?"
Aura menoleh ke gerombolan siswa lelaki yang tengah asyik membicarakan dirinya, berpikir gadis itu tuli. Mulut mereka terkunci begitu bersitatap dengan Aura, pura-pura tidak melihat dengan mengalihkan pandangan. Peduli amat, Aura memasukkan ponsel ke sakunya. Kemudian melangkah melewati mereka bertiga yang menahan napas.
"Cantik juga anaknya," komentar salah satu dari mereka.
"Bagaimana kalau dia yang benar-benar membunuhnya? Seram!" timpal yang lain.
Siswa ketiga menyikut temannya, "Jangan asal menuduh. Mana mungkin dia melakukannya?"
"Siapa yang tahu?"
♦♦♦
"Tujuh belas Februari. Hari Bazar dua tahun lalu. Menjelang waktu makan siang, aku menuju aula untuk mengambil barang yang tertinggal saat pelajaran pertama. Sesampainya di sana, aku melihat seorang murid yang tengah terkejut dengan pandangan terpaku ke arah Bapak Marcus. Pria itu sudah tergeletak di lantai aula dengan darah mengalir dari perutnya yang tertusuk pisau. Aku meneriakinya untuk pergi dari aula, lalu menekan tombol darurat. Dia nggak melakukan apapun, tapi siapapun bisa saja menuduhnya melukai Bapak Marcus jika melihatnya berada di tempat itu. Aku cuma nggak mau membuat orang yang nggak bersalah harus menanggung tuduhan atas sesuatu yang nggak ia lakukan."
Aura bercerita.
"Kenapa kamu tidak menceritakan hal penting tersebut pada Ibu, Aura?" tanya wali kelasnya yang juga hadir dalam ruangan tersebut. Wajahnya tampak kecewa.
"Maaf," jawab Aura tanpa ekspresi.
"Apakah ceritamu dapat dipercaya?" tanya Detektif Sam.
"Kalau nggak percaya, kenapa memintaku menjadi saksi?" ketus Aura bersitatap dengan pria tersebut.
Bapak Obay menahan Detektif Sam berbicara lebih. "Bisakah kamu beritahu kami siapa murid yang ada di sana juga?"
"Untuk apa? Kalian akan menyelidikinya juga? Aku percaya seratus persen dia nggak membunuh Bapak Marcus, bahkan lebih dari aku percaya pada diri sendiri bahwa aku nggak melakukannya."
"Bukan begitu, Aura. Kami tidak mencurigai murid itu. Sama seperti dirimu, dia adalah saksi penting dalam kasus ini." Bapak Obay menjelaskan.
"Dia sudah pindah, pergi jauh dari sini. Nggak ada gunanya menyebutkan nama murid itu," tolak Aura. "Kalian nggak perlu repot menambah saksi, aku saja yang menjawab pertanyaan kalian."
"Lalu, jawab pertanyaan tentang murid itu!" Detektif Sam bicara. "Siapa yang tahu dia ternyata membunuh Marcus?"
"Berhenti bertanya tentangnya! Untuk apa lagi membahasnya? Dia nggak punya kaitan apapun dengan kasus ini. Pegang taruhan aku, dia nggak membunuh siapapun. Kalau kalian nggak percaya, maka kesepakatan menjadikan aku saksi usai sampai di sini. Peduli amat dengan buku harian sialan itu, terserah apa yang akan kalian lakukan dengannya. Aku jamin, buku itu nggak akan lebih membantu daripada pernyataan yang bisa aku kasih." Aura berbicara tegas.
Kepala Sekolah sekali lagi menahan Detektif Sam.
"Baiklah, Aura. Bel masuk sudah berbunyi, kamu bisa kembali ke kelas." Bapak Obay mempersilakan.
Aura mengangguk, beranjak dari tempatnya.
Mereka telah bersepakat, proses penyelidikan dengan Aura hanya dilakukan ketika jam istirahat dan berakhir ketika bel masuk berdering, supaya tidak mengganggu belajarnya. Juga tidak setiap hari, hanya di hari-hari tertentu yang memang di saat yang diperlukan pula.
Aura melangkah ke kelasnya.
♦♦♦
Tiga tahun lalu.
"Misi, ada Aura?"
"Astaga, Reza. Ini sudah ketiga kalinya hari ini lo mampir ke kelas hanya untuk mencari Aura dengan senyuman lebar." Teman semeja Aura, Lucy, yang berdiri di depan pintu menepuk dahi. "Masuk saja."
Reza menyeringai, setengah berlari ke tempat Aura. Ia membuka buku paket yang sedari tadi ditenteng, "Aku menemukan jawaban dari soal nomor 13!"
Aura menyambut riang, menunggu penjelasan. Reza semangat menerangkan sambil duduk di sampingnya, sementara Aura menganguk-angguk mendengarkan, sesekali bertanya. Lucy menyimak interaksi mereka, tersenyum manis. Sekejap, ia teringat bahwa ia hendak ke toilet tadi. Sudah diujung.
Sepulang sekolah, hari sudah sore menjelang malam. Bimbingan olimpiade biologi berjalan terlalu larut—tapi menyenangkan. Ketiga sekawan yakni Aura, Reza dan Lucy menyusuri kelas-kelas para senior. Kalau saja bukan sore hari, pasti banyak kakak kelas berkeliaran di koridor ini. Aura pernah sendirian melewati kerumunan kakak kelas tersebut, merasa minor karena dirinya yang masih kelas delapan, ia memilih tidak iseng berkunjung ke koridor ini lagi, setidaknya sampai dialah yang menjadi kakak senior SMA tersebut. Sekolah mereka adalah sekolah menengah tingkat pertama dan tingkat atas. Gedung kelasnya yang panjang dan bertingkat tiga digabung menjadi satu.
"Bye, Lucy." Aura melambaikan tangan, mengikuti Reza ke parkiran sekolah sedangkan Lucy pulang ke rumah dengan angkutan umum.
Baru saja hendak naik ke atas motor, Aura mendapat panggilan dari nomor ibunya. Tetapi ketika menempelkan ponselnya ke telinga, bukan suara ibunya yang terdengar. Orang itu mengabarkan ibunya yang dibawa ke rumah sakit.
"Reza!" panggil Aura. "Kita ke rumah sakit sekarang. Ibu nggak baik-baik saja."
♦♦♦
"Nak Lucy, sudah lama Ibu nggak melihatmu. Ayo masuk, Sayang," ajak Ibu ketika Lucy mampir ke rumah pagi hari ini.
"Aura memintaku untuk datang, katanya dia mau mengobrol," ungkap Lucy sambil tersenyum ramah.
"Baguslah, cukup lama kalian nggak bersama. Ini camilan untuk kalian," Ibu menyuguhkan bolu lapis sembari membuka pintu kamar anaknya.
"Terima kasih."
Pintu ditutup, sementara Lucy duduk di kasur Aura. Teman kecilnya dulu keluar dari kamar mandi. Mengeringkan rambut dengan handuk.
"Baru mandi?" tanya Lucy berbasa-basi.
"Baru bangun, malah. Tadi malam begadang, mengobrol sama Reza." Aura mengempaskan tubuh ke kursi belajar yang terletak tidak jauh dari kasur.
"Teleponan?"
Aura menggeleng, "Hanya lewat pesan. Dia masih membatasi interaksi, juga menyembunyikan apa yang sedang dia lakukan di luar sana."
"Kalian jadi nggak sedekat dulu," komentar Lucy. Tatapannya tertuju pada meja kecil di samping kasur, memerhatikan boneka anjing mungil yang lucu berwarna putih.
"Mungkin," Aura meraih boneka anjing sebelum Lucy menyentuhnya. "Ini boneka dari Reza dulu."
"Lucu," tukas Lucy.
Aura memandang lamat-lamat boneka tersebut. Ingatannya melayang pada kenangan saat ibunya dibawa ke rumah sakit. Tante Lida, tetangga persis sebelah rumah yang menemukan tubuh pingsan ibunya di ruang tamu saat hendak berkunjung. Beliau tahu banyak tentang keluarga Aura.
"Meskipun tubuhnya banyak luka lebam, ibumu baik-baik saja, Ra. Sekarang sedang istirahat. Tante turut prihatin, ya." Tante Lida mengusap bahu Aura lembut.
Aura memandang ibunya yang tertidur.
"Biarkan ibumu di sini sampai besok. Pulanglah lebih dulu, kamu harus sekolah besok. Tante akan menunggu di rumah sakit."
Aura menggeleng tegas, "Aku nggak mau meninggalkan Ibu." Bahkan saat Reza mencoba membujuk, gadis tersebut tetap bersikeras tinggal. Tante Lida akhirnya menyerah, keluar dari ruangan. Reza belum, kini dia mengeluarkan sebuah benda dari kantong jaketnya.
"Lihat ini," boneka kelinci kecil terlihat, "boneka ini bisa bicara, tahu. Dengar, dia bicara sesuatu! Aura, kamu tahu apa yang dia katakan?" Reza pura-pura bertanya.
Aura melirik enggan.
"Dia bilang, biarkan aku yang menjaga ibumu malam ini, Gadis Cantik. Kamu nggak perlu khawatir, ada aku yang menemani. Pulanglah." Reza mengubah bicaranya seperti suara anak kecil. "Dengar, Ra. Kelinci ini berbaik hati membantu kita. Bagaimana kalau kita serahkan pada kelinci ini? Aku sih yakin dia bisa menjaga Ibu dengan baik."
Astaga. Aura mengernyitkan dahi, merasa heran. Cara membujuk yang konyol. Apakah lelaki ini benar-benar berpikir dirinya akan menurut? Sekali lagi Aura memerhatikan wajah Reza yang memasang wajah (sok) imut, sambil menjulurkan boneka kelinci.
"Aku mohon, kamu nggak percaya kelinci pemberianku ini akan bekerja dengan sungguh-sungguh?" Reza bertanya sekali lagi.
Demi melihat wajah Reza yang memelas dengan bibir membentuk pelangi, Aura menerima perlahan boneka kelinci. Masih dengan tatapan heran hendak tertawa, Aura meletakkan boneka itu di meja sebelah kasur. Reza tersenyum melihatnya.
Aura membungkuk, berbisik di telinga ibunya sebentar. Mengucap sampai nanti.
"Ayo," Reza mengajak Aura keluar. Mereka berjalan bersama menuju tempat parkir rumah sakit.
"Jangan sedih karena harus berpisah dengan kelincinya. Nih, gantinya." Reza memberikan boneka lagi, kali ini sebuah boneka anjing mungil dengan kalung di lehernya. "Aku beli dua, tadinya buat kamu satu, buat aku satu. Tapi biar kamu nggak kesepian gara-gara boneka kelincinya lagi menemani Ibu, ini juga buat kamu deh."
Reza tampak senang melihat Aura yang menerimanya sambil tersenyum. Kemudian lelaki itu menyalakan motor.
Di atas motor, Aura memerhatikan lamat-lamat boneka tersebut diam-diam, masih dengan senyuman. Ia teringat apa yang ia bisikkan pada ibunya.
"Ibu, kalau saja bukan Reza yang memintaku dengan wajah memelasnya, aku nggak akan menurut."
♦♦♦


 grey_nor
grey_nor