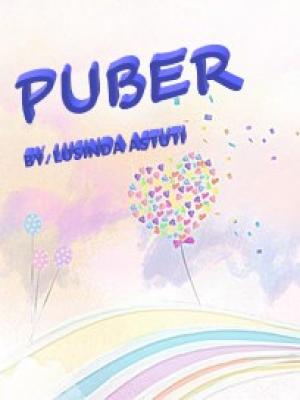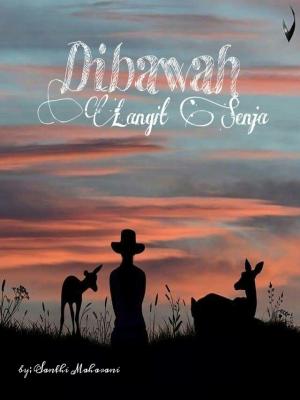"Panggilan kepada Aura dari kelas 11 IPA 2, ditunggu kehadirannya di ruang kepala sekolah sekarang juga. Sekali lagi, panggilan kepada Aura dari kelas 11 IPA 2, ditunggu kehadirannya di ruang kepala sekolah sekarang. Terima kasih."
Pengumuman dari speaker yang disediakan di setiap kelas membuat guru di kelas Aura menghentikan sebentar penjelasan guna menyimak isi pengumuman.
"Aura? Kamu dipanggil, kamu boleh keluar, Nak." Guru berkaca mata itu mengangguk.
Siapa yang mau keluar? Aura mengerutkan dahi tanda menolak.
"Ayolah, kamu ditunggu di ruang kepsek sekarang. Itu pasti sesuatu yang penting. Pergilah," bujuk gurunya.
Aura menggeleng.
"Kamu nggak perlu khawatir ketinggalan pelajaran. Kalau kamu mau, Ibu akan menjelaskan ulang padamu nanti. Sekarang, patuhi perintah tersebut, pergi ke ruang kepala sekolah sekarang." Kali ini guru itu malah memegang tangan Aura. Sialnya, teman di sekitarnya juga membantu mendorong Aura. Membuat gadis itu keki, menggubris tangan temannya dan keluar kelas dengan enggan.
Sesuatu yang penting apanya? Panggilan itu pasti bermaksud untuk menginterogasi dirinya lagi. Mana mau Aura pergi ke sana. Gadis itu hanya berjalan beberapa langkah menjauh dari kelas, kemudian memandang koridor yang kosong. Berdiri menyandar dinding. Apa yang bisa dia lakukan sekarang? Guru di kelasnya tadi resek sekali, memaksa segala.
Tidak punya ide, Aura mengeluarkan ponselnya. Iseng membuka-tutup aplikasi. Baru sekian menit, dirinya merasa bosan. Tepat sebelum Aura benar-benar memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku, ada notifikasi yang masuk. Membuat mata menyipit malas Aura berubah. Dengan cepat, jari telunjuknya menyentuh pelan layar ponsel, membuka email yang datang.
Lama sekali Aura memerhatikan alamat si pengirim. Membaca isi pesan.
"Maafkan aku yang baru membalas pesanmu, Aura. Entah perasaan apa yang membuatku selalu takut mengirimimu pesan. Aku nggak mau kamu mengingatku lagi. Dua tahun aku berusaha menjauh darimu, berhenti mencari tahu apa yang sedang kamu kerjakan, nggak pernah berhasil. Aku selalu ingin tahu apa yang kamu sibukkan, selalu memikirkanmu setiap kali aku mencoba mengosongkan pikiran. Menjauhimu nggak mampu menghapus kenangan bersamamu. Aku kangen dirimu yang kadang melawan, meski nggak jarang kamu jadi penurut."
Pesan yang ditulis Reza membuat seutas senyum terkembang di bibir Aura. Di paragraf terakhir, Reza menjanjikan satu telepon besok hari.
"Aku juga ingin sekali mendengar suaramu lagi." Aura menghela napas senang.
Tidak ada kilat, tidak ada petir, tiba-tiba saja ponselnya diambil. Aura terkejut, mendapati guru yang terkenal suka menyita ponsel murid yang bermain di saat jam pelajaran, berdiri di hadapannya. Menceramahinya, "Kamu ini loh! Ngapain di sini, senyum-senyum ke benda gepeng ini? Bukannya belajar!"
"Kembalikan," Aura berkata pelan dengan tangan menyodor.
"Enak saja. Ponselmu saya sita sampai besok! Ini hukuman karena kamu bermain ponsel saat bukan waktunya. Eh?" Guru itu berhenti sebentar, meneliti wajah Aura. "Kamu kan, yang namanya Aura! Kok masih di sini? Itu Bapak Kepala sudah menunggu. Ayo ikut saya!"
"Nggak. Tolong kembalikan ponselku." Nada Aura sedikit meninggi.
Guru itu menggeleng, "Saya kembalikan setelah kamu ikut saya. Ayo."
Aura tidak beranjak. "Nggak ada alasan untuk pergi ke ruangan itu. Kembalikan ponselku, Anda nggak punya hak menyitanya. Aku nggak memainkannya, hanya melihat sekilas pesan penting."
"Oh ya? Pesan penting apa—"
"Bu Guru!" seru Aura, mencegah guru tersebut melihat isi ponsel.
"Apa yang akan kamu lakukan jika saya melihat isi ponselmu? Melaporkannya pada Kepala Sekolah?" Guru itu menyeringai. "Saya tidak akan melihatnya sepanjang kamu mengikuti saya sekarang."
Aura malah menyilangkan tangan di bawah dada, walaupun gurunya telah melangkah.
"Kalau tidak ikut, saya lihat isi ponselmu sekarang!" Dengan nada mengancam, ia mengangkat ponsel.
Aura buru-buru melangkah mendekat, berusaha meraih ponselnya. Guru itu berjalan cepat menjauh ke arah ruang kepala sekolah. Aura menghentakkan kaki ke lantai koridor, mau tidak mau dia beranjak mengikuti.
♦♦♦
Ruangan dingin dengan ukuran seluas ruangan kelas tersebut sudah dihadiri oleh peserta pertemuan yang telah menunggu Aura sedari tadi. Detektif Sam dan Bapak Obay. Dengan terpaksa Aura duduk di hadapan mereka, di bawah tatapan intimindasi.
Aura menghindari kontak mata.
Detektif Sam berdiri dari tempatnya, "Kami menemukan sebuah buku yang sepertinya bisa membantu penyelidikan ini. Mungkin kau tertarik melihatnya."
Aura melirik tangan Detektif Sam, terkesiap. Buku ukuran A6 dengan ujung berbentuk spiral itu amat ia kenali. Buku hariannya. Aura jarang menulis tentang kesehariannya, tapi dia jelas-jelas menulis sesuatu yang penting dalam buku itu. Terkait kasus kematian Marcus. Sudah lama Aura kehilangan buku tersebut, bagaimana detektif itu bisa memilikinya?
"Milikmu, bukan? Namamu tertulis di halaman depannya." Detektif Sam berjalan mendekat. "Seseorang memberikannya dengan alasan ingin membantu penyelidikan ini. Belum kami baca, karena buat apa membuka buku hak orang lain? Kau pasti berpikir itu tidak sopan. Meski itu mungkin bisa memberitahu satu dua hal."
Aura hanya menutup mulut.
"Jadi," Detektif Sam meletakkan tangan di meja depan Aura, "Bukankah lebih baik jika kami bertanya padamu langsung daripada bertanya pada buku ini?"
Detektif Sam menyodorkan buku tersebut, tapi ketika Aura hendak mengambilnya, pria itu menarik tangannya.
"Kau setuju menjadi saksi?" tanyanya.
"Aku nggak punya keinginan sedikitpun membantu menyelesaikan kasus ini," ketus Aura. "Entah dia mati karena bunuh diri, atau dibunuh, itu sama sekali bukan urusanku. Jujur saja, aku nggak peduli. Dia pantas mendapatkannya."
"Pantas mendapatkannya?" Bapak Obay mengulangi kalimat Aura. "Apa maksudmu, Nak?"
"Takdir yang membuatnya meninggal, apapun alasannya, dia sudah nggak ada. Itulah yang Tuhan putuskan sebagai takdirnya. Kenapa kita harus susah payah mencari alasan mengapa takdir mencabut nyawanya," jelas Aura.
"Bukan kau yang ... membunuhnya?" tanya Detektif Sam.
Aura menoleh, menyeringai kecil, "Aku bisa mendengar keraguan dari nada bicara Anda. Saat hendak menuduh orang, sebaiknya yakinkan diri terlebih dulu. Tuduhan tanpa keyakinan dari si penuduh, bukanlah apa-apa."
"Kau benar membunuhnya?" tanyanya lagi.
Aura mengembuskan napas, "Payah. Detektif sekarang suka menuduh tanpa bukti, ya?"
"Apakah ini bukti?" Detektif Sam mengangkat buku kecil.
Aura menatap sebentar, "Buku kecil itu nggak akan membantu kalian menemukan bukti bahwa aku pembunuhnya."
"Baiklah, mari kita buka—"
"Hentikan." Aura refleks berdiri. "Bukan aku pembunuhnya, sungguh. Jadi kembalikan buku itu."
Dengan pandangan menyelidik, Detektif Sam berjalan mengitari Aura, "Hanya ketika kau siap menjadi saksi kami."
Aura tidak menjawab.
"Tujuh belas Februari. Peduli amat dengan kematian pria itu, aku hanya berharap nggak ada yang tahu dia juga di sana. Semoga dia baik-baik saja." Detektif Sam membacakan sedikit kalimat di halaman pertama buku.
Aura menatap tajam detektif itu.
"Kau tidak pernah memberitahu ada orang lain di sana. Siapa orang itu? Mengapa kau melindunginya? Apakah mungkin dia yang—"
"Bukan dia pembunuhnya!" seru Aura tegas.
"Jadi siapa pembunuhnya?"
"Manaku tahu! Sungguh demi apapun, aku nggak tahu!" bentak Aura.
"Tapi aku yakin kau tahu banyak tentang hari itu. Ceritakan semuanya pada kami, maka kami tidak akan mencurigaimu atau orang yang kausebut dalam buku ini. Aku berjanji tidak akan membuka buku harianmu tanpa izin, asalkan kau bersedia menjadi saksi." Detektif Sam memberi penawaran.
Aura menutup matanya kesal.
"Tidak masalah jika kau menolak. Buku ini bisa dijadikan barang bukti, aku bisa menyelidikinya dengan ini." Detektif Sam mengangkat bahu.
"Aku bersedia," tukas Aura akhirnya. "Mulai besok aku akan mengikuti sesi tanya-jawab kalian."
"Baguslah, kau juga bisa memegang janjiku juga." Detektif Sam tersenyum penuh kemenangan.
♦♦♦


 grey_nor
grey_nor