Apa aku harus mengganti waktu tiga jamku yang hilang dengan berjualan sampai malam? Masalahnya aku pernah mencoba jualan sampai pukul delapan malam di daerah ini dan hasilnya memang tidak optimal. Kantor sebagian besar sudah tutup. Mahasiswa tentu tidak ada yang mau berlama-lama di kampus sampai malam, apalagi karyawannya.
Bagi pelangganku, menu-menu Warung ENTRY pukul sepuluh pagi sudah terlalu telat untuk mereka. Siapa yang mau makan waffle atau french toast savory tinggi kalori yang mengenyangkan ketika dua jam lagi mereka akan berhadapan dengan makan siang? Memangnya brunch?
Sebentar, sebentar. Brunch, ya?
Brunch adalah makanan tinggi kalori yang disajikan di waktu sarapan dan menjelang makan siang. Apa aku coba aja membuat menu brunch? Mungkin ide itu tidak terlalu buruk. Aku akan memikirkan beberapa kemungkinan menu untuk brunch ini dengan Jeff di lain waktu. Jeff itu seperti mesin penghasil ide. Mungkin karena dia sekolah di luar negeri sehingga pikirannya terbuka dengan ide-ide makanan luar biasa untuk diterapkan pada lidah orang Indonesia. Mungkin inikah hikmah dari menjaga Kai? Semoga saja.
Mengenai Kak Mala, aku terus berharap Bapak dan Ibuk enggak pilih kasih untuk anak-anaknya. Aku menyayangi saudaraku, keponakanku. Namun, bukankah orang tuaku sudah keterlaluan telah memutuskan segala sesuatu secara sepihak tanpa merasa perlu mendengar isi kepalaku?
Suara motor mendekat ke warung memutus pikiran negatif tadi. Aku bersyukur untuk siapa pun itu. Maafin aku Pak, Buk.
Itu abangnya Hayu! Sepertinya dia datang sama tukang ojek pengkolan.
"Pak Harsa!" seruku spontan sambil melambai riang. Aku tidak peduli dengan tampangku yang mungkin kelihatan bodoh saat ini.
Aku tahu dia sedikit kaget. Namun, sedetik yang lalu mataku menangkap senyuman yang tipiiiis banget di bibirnya. Eh, beneran yang tadi itu senyum? Aku enggak salah lihat, kan? Aku sendiri meragukan penglihatanku.
Betewe, ini adalah hari pertama kami berjumpa setelah kecelakaan itu. Dua minggu lebih dan Pak Harsa masih memakai arm sling-nya.
"Gimana tangannya, Pak? Masih sakit?" Pak Harsa memindahkan tas ransel di tangan kirinya dengan hati-hati ke lantai.
"Bukan sakit, tapi lebih ke kurang nyaman. Tidak boleh banyak gerak dulu tanganku. Kamu!" Tatapannya tiba-tiba mengunciku, seakan ingin menerkam jiwaku yang lemah.
"Aku kenapa?" Wajahnya kok serius amat?
"Kenapa telat terus bukanya?! Masih niat jualan? Tega kamu bikin aku yang lagi pemulihan kayak gini bolak-balik pakai ojek untuk memastikan Warung ENTRY sudah buka apa belum?!"
Astaga! Padahal dia bisa tanya baik-baik, loh. Pak Harsa yang barusan persis seperti Mara kalau belum makan. Bawel!
Sabar, Cala. Pikirkan ikan paus yang sedang berenang dengan damai di laut dalam.
"Maaf, Pak. Tadi ada urusan keluarga. Mereka yang bikin aku telat dan... ehem, ya gitu deh." Mengingat Ibuk yang tiba-tiba pergi menghadiri pembukaan toko baju temannya membuatku kesal.
"Aku yakin kamu punya segudang urusan dan segunung masalah, tapi kamu harus tetap profesional. Kamu pikir artis broadway kalau manggung tidak punya masalah di belakang mereka? Mereka tetap senyum, berakting, bernyanyi, dan menari dengan penuh totalitas, padahal ada setumpuk urusan di belakang panggung. Seorang penyanyi sekaliber Raisah tetap melaksanakan konser dan memberi kebahagiaan pada penonton yang rela membayar mahal tiket konsernya walaupun dia harus meninggalkan anaknya yang sedang sakit di rumah."
Aku bukan Raisah. Aku nggak sekaliber artis broadway itu. Aku—
"Tapi aku yakin kamu bisa mengatasinya."
"A-apa?" Wajah kebapakannya barusan sempat melenakanku. Cepat-cepat aku menggeleng. "Pak Harsa kan nggak tahu apa masalahku!" Tiba-tiba aku bersikap defensif di depan pria ini. Aku nggak tahu kenapa. Aku beringsut menjadi remaja puber di depan pria ini.
"Karena keluarga, kan?" Dia... tersenyum tipis. Aku yakin sekarang sedang menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Kali ini mataku enggak salah.
"Keluarga itu entitas yang kompleks. Ada si pemarah, si pengkhianat, si manja, si cuek, si otoriter, dan ada yang baiknya kebangetan. Tapi mereka juga yang telah membentuk kamu yang sekarang.Dan mereka adalah tempat di mana kamu akan kembali setelah lelah berjibaku mencari uang." Dia...ada benarnya. "Hanya kamu yang paling tahu karakter keluargamu, Cal. Bicarakan masalahmu dari hati ke hati dengan mereka sesuai karakter mereka masing-masing. Ingat! Bicara dengan baik dan santun. Mereka adalah keluargamu, bukan musuhmu."
Apa aku bisa bicara baik-baik kalau orang yang aku hadapi...Nyonya Bet? Akan tetapi, kenapa kami malah membicarakan keluarga?!
"Pak Harsa ke sini mau belanja atau mau kasih aku nasihat cuma-cuma?"
"Astaga! Gara-gara kamu nih, aku sampai lupa tujuanku ke sini."
"Lho, kok aku?!"
Pak Harsa sepertinya tidak mau repot-repot menggubris protesku sebab dia sibuk membaca jam tangannya.
"Masih ada waktu sekitar 30 menit. Aku mau french toast savory lengkap. Bisa di double rotinya? Aku kelaparan menunggu warungmu buka." Lalu si Bapak yang suka seenaknya melipir ke meja lesehan di belakang meninggalkanku. Aku sampai tak mampu mengatupkan rahang dengan sempurna karena saking anehnya situasi ini.
Antara senang dan dongkol, tak tahu rasa mana yang lebih dominan. Apa aku harus minta maaf, gegara telat buka warung dia jadi enggak makan dari tadi? Padahal banyak kedai sarapan dengan berbagai varian makanan yang buka di sekitaran kampus. Bubur ayam Bandung, kupat tahu, bahkan rumah makan Padang juga ada. Tapi masalahnya, aku nggak bisa marah sama si manja jutek ini.
"Cal."
"Iya, Pak?"
"Tolong potong-potong rotinya." Pak Harsa menunjuk-nunjuk tangan kanannya yang tak berdaya tergantung dalam arm sling.
"Baik, Pak."
Dalam sepuluh menit, pesanan Pak Harsa selesai. Saat menghidangkan piring yang isinya masih mengepul di meja, Pak Harsa sedang tenggelam membaca kertas folio yang penuh dengan tulisan tangan. Kertas yang sama tertumpuk di sebelah kirinya. Seperti...kertas ujian.
"Rotinya, Pak."
"Hm." Matanya masih tertuju pada kertas.
"Kamu mau ke mana?!" cegatnya buru-buru saat aku hendak berdiri.
"Ke sana." Aku menunjuk tempat kerjaku yang menghasilkan uang: kompor, panci, roti dan segala adonannya.
"Di sini saja. Tidak ada pelanggan, juga," ucapnya pada kertas tadi seakan wujudku tidak ada.
Hah! Mulutku sudah berkedut-kedut tak tahan ingin membalas dan mengatakan, Elo siapa, kisanak? Suruh-suruh gue seenaknya! Tapi aku enggak sanggup. Pelanggan adalah raja, dan dia belum bayar roti panggang double savory-ku.
"Baiklah."
"Good." Hah! Aku duduk memberengut di seberang meja.
Aku memerhatikan lekat-lekat dia menyingkirkan kertas-kertas tadi dengan tangan sehatnya lalu memakan pesanannya.
"Bisa makannya, Pak? Mau dibantu?"
Matanya tajam seakan mengulitiku, menusukku lewat bulu matanya yang tebal dan lurus dari balik lensa kaca mata. Detik itu juga ada sebuah dorongan dalam diriku untuk menyuruhku kabur dari muka bumi.
"Kenapa? Mau suapi aku? Kamu tidak tahan betapa leletnya aku menusuk roti ini?!"
"Astaga, cuma tanya, Pak. Baper banget sih jadi orang? Aku tanya karena Bapak kelihatan kepayahan makan pake tangan kiri."
"Kalau tidak mau bantu sejak awal, jangan menawarkan." Ngomel-ngomel, sepotong roti dengan daging asap, keju, tomat, dan telur meleleh lolos juga ke dalam mulutnya. Cih!
Oke, baiklah. Pria ketus ini tidak punya masalah makan dengan tangan kiri.
"Emang Bapak tadinya butuh bantuan, ya?"
Terkutuklah mulut ini yang tidak bisa berhenti bicara! Nyesel banget aku tuh nanya pertanyaan yang enggak bermutu.
Tiba-tiba garpu yang dipegang Pak Harsa melayang-layang di depan batang hidungku.
"Bapak nawarin aku makan?"
"Masih menawarkan bantuan, kan? Nih, tolong suapi."
"Heee? Ogah. Emang Bapak anak kecil pake disuapin?" Kepalaku otomatis menggeleng kencang. "Kan, tadi bisa makannya."
"Ck! Aku beneran kecewa, lho." Eh, air mukanya langsung turun, dong. Ini...seriusan lagi ngambek?
"Pak. Bapak beneran baperan banget, ya?" Ini lakik kok kelakuannya nggak sesuai umur?
"Padahal saya mau," gerutunya lirih dan menusuk-nusuk si french toast dengan malas. Masih kedengeran sama aku, Pak. "Boleh tambah mayo dan saus sambal?" sambungnya. Tubuhku spontan bergerak dan mengambilkan apa yang diminta Pak Harsa.
"Makasih."
"Sama-sama."
"Cal. Tolong ambilkan tisu." Aku pun langsung mengerjakan perintah Pak Harsa.
"Cal, tolong air mineral dingin." Lagi-lagi tubuhku ringan berdiri mengambil air mineral di kulkas showcase.
"Cal."
"Apa lagi yang Bapak butuh?" Tubuhku sudah pasang kuda-kuda untuk permintaan berikutnya. Asalkan tidak menyuapinya, aku akan melakukan apapun untuknya.
"Tidak ada. Terima kasih telah membantuku," katanya lembut dan ada sedikit senyum menghias bibirnya. Kalimat sederhana tadi membuatku tak berkutik. Sungguh.
Ketika dia bicara, matanya yang tajam berubah teduh dan mengunci mataku, membuatku tak dapat bergerak selama beberapa saat.
Tatapannya seperti hipnotis. Aku bisa saja terbuai, hanyut dalam kedalaman irisnya yang gelap, dan... Tidak, tidak! Bahaya kalau lama-lama menatap mata itu. Mata itu terlalu melenakan. Mata itu bisa saja membuatku ingin memandangnya lama-lama dan tenggelam dalam pesona si manja, galak, ketus, dan... Ya Tuhan. Apa yang terjadi padaku? Otakku mulai kacau...
Maka dari itu aku menggelengkan kepala kuat-kuat agar bisa segera lepas dari jerat hipnotisnya.
"Sa-sama-sama, Pak."
"Maksudku ini." Dia menunjuk tangannya yang tergantung dalam penyangga lengan berwarna biru. "Dan ya, tentu saja pertolonganmu tadi." Pak Harsa juga menunjuk botol mayonais, saus sambal, kotak tisu, dan air mineral dingin.
"Aah, aku ikhlas bantu Bapak."
Pak Harsa malah mendengkus kecil. "Kalau aku tidak paksa, kamu bakal meninggalkan aku di pinggir jalan atau di rumah sakit, Cal." Bibirnya mencibir minimalis.
Hey! Dia barusan ngejek aku! Aku cabut pernyataan matanya yang menghipnotis. Sekarang matanya berubah jahil.
"Yaah Bapak. Diingetin lagi." Risi banget aku sumpah. "Maaf, aku ragu-ragu nolong Bapak waktu itu," akuku malu.
"Tapi aku yakin kamu pasti akan menolongku. Kamu bukan manusia tega yang akan meninggalkanku kesakitan, Cal," katanya kalem.
"Hm... entahlah," ucapku tak yakin. Aku mengangkat kedua bahuku bersamaan. "Lagian, dari mana Bapak yakin aku adalah orang yang seperti Bapak pikirkan? Aku bisa aja lariin mobil sama isi dompet Bapak waktu di rumah sakit." Jawaban panjang lebarku dibalas dengan tawa kecilnya.
Hey! Mana muka juteknya yang tadi? Mengapa begitu banyak emosi yang aku lihat di wajahnya pagi ini?
"Tapi tidak ada yang terjadi, kan?" jawabnya dengan senyum kemenangan.
Pak Harsa yang aneh. Ini yang kumaksud dengan banyaknya emosi yang muncul di balik kaca matanya. Tadi marah-marah, terus jutek, sekarang tatapannya begitu meneduhkan.
Matanya bagai irigasi yang mengairi jiwaku yang kering kerontang akan perhatian dan kasih sayang.
Plis deh, kenapa aku berubah jadi Niscala Shakespeare, si penyair kesiangan?
"Ya...kita aja enggak kenal. Bapak kan enggak tahu karakter asliku gimana."
Sebelum menjawab, seulas senyum manis menghias wajah juteknya, lagi. Kenapa Pak Harsa banyak tersenyum hari ini?
"Ya, tahu saja."
***
"Ayolah, Butter. Aku buru-buru nih."
Pagi hari, jantungku harus dibawa berolahraga, berdentam enggak karuan karena si Butter nggak mau hidup. Perkenalkan, nama motorku Butter.
Dipencet berkali-kali tombol starter-nya enggak terjadi apa-apa. Kamu maunya apa, sih? Biasanya enggak pernah mogok. Pliis, jangan bikin aku lebih telat.
Lagi-lagi aku harus ngemong Kai. Ibuk dengan santainya bilang beliau mesti ke pasar karena udah janjian sama tukang daging yang sediain buntut sapi. Alamat diomelin lagi sama Pak Harsa kalau ketahuan telat.
Aaaargh!
"Kenapa si Butter, Kak?"
Suara Mara memberiku angin segar.
"Deeek, tolongin motornya, enggak mau hidup," rengekku, memelas setengah mati.
Wajahnya masih muka bantal—memang ada gurat-gurat bekas bantal di pipi kanannya—dan aku sangat yakin nyawanya belumlah terkumpul seratus persen, tapi Mara tetap berjalan ke arah motorku dengan terseok-seok dan sesekali menguap lebar.
Ini anak kenapa santai banget berkeliaran di rumah hanya dengan singlet dan bokser bercorak Bob si spons?
"Kapan terakhir diservis, Kak?" Mara menegakkan standar motor dan mulai mengengkol.
"Kapan, ya?"
Karena aku mikir kelewat lama, dia bersuara, "Udah lama pasti." Aku menyeringai malu. Tebakan Mara sangat jitu. Dia kembali mengengkol sambil memutar gas.
"Jangan-jangan businya kotor."
"Atau filternya butuh dibersihin."
"Aaaah, olinya mesti diganti ini."
"Jangan-jangan akinya soak."
Mara terus bermonolog. Aku enggak ngerti soal motor tua ini selain memakainya, mengisi bensin, dan sesekali mencucinya di halaman rumah.
"Gue antar ke bengkel kapan bisa," ujarku agar hatinya senang. Itu pun kalau sempat. Pagi udah ke Four Seasons, terus buka warung, sorenya baru pulang.
Baru saja mau buka aplikasi ojek, si Butter hibahan dari Bapak ke Kak Mala terus ke aku meraung-raung semangat karena digas terus sama Mara. Spontan aku melompat riang.
"Alhamdulillah. Tengkyu verimach adikku cayang." Aku hendak mencium pipi ileran Mara, tapi Mara keburu menghindar dengan tampang jijik. Senangnya menjahili si Bungsu.
"Setop Kak! Jangan deketin gue!"
"Datang aja ke warung. Gue traktir. Hehe."
"Iye. Awas kalau enggak. Entar kalau sempat gue bawa ke bengkel terdekat."
Duh, terharu.
***
Di saat aku menyelesaikan adonan panekuk, seseorang dengan wajah datar berjalan mendekati warungku, lengkap dengan arm sling di tangan kanan dan ransel menggantung di pundak kiri. Berarti Dokter Mo belum membolehkan Pak Harsa bergerak bebas. Padahal hampir tiga minggu sejak kecelakaan. Atau... masih sakit? Ya Tuhan, angkat sakit bahunya Pak Harsa.
"Selamat pa—"
"Kalau tidak mau jualan, mending kamu cari usaha lain. Mungkin saja detik ini setengah pelanggan kamu sudah kabur ke tempat lain karena warung ini tidak pernah buka tepat waktu!"
Apa-apaan?!
"Aku—"
"Kalau mau bisnismu lancar, serius menjalankannya. Kamu bisa bikin pelangganmu kecewa kalau begini terus."
Ya Tuhan. Bapak Grumpy! Datang-datang langsung ngomel dan enggak membiarkanku bicara! Dia benar-benar menguji kesabaranku pagi ini setelah Butter.
"Bapak Harsa yang terhormat. Aku maunya bisa datang tepat waktu, tapi keadaan rumahku... Aku harus menjaga keponakan... Ahem." Buat apa aku cerita padanya, sih? "Maksudku selain masalah lain, motorku tiba-tiba mogok. Makanya aku telat, Pak. Maaf," ucapku enggak ikhlas. Jengkel, tapi tetap saja aku merasa harus menjelaskannya.
Ingat Cala, pelanggan adalah maharaja diraja dan sumber pundi-pundi. Eh, maksudku Tuhan yang kasih rezeki lewat mereka. Astaga, aku merasa jadi menuhankan pelangganku. Ampun, Tuhan.
Lagian, mengapa mesti marah-marah enggak jelas, sih? Kan, dia bisa nanya baik-baik. Demi Tuhan!
"Tapi tidak setiap hari, Cal. Mau pesan lewat jasa delivery, warungmu belum buka. Aku samperin langsung, ya sama saja. Rolling door-nya masih tertutup sempurna," sindirnya.
Ujung bibirku sampai berkedut ingin membalas semua kata-kata pedasnya. Tapi, sebentar, deh. Setelah diperhatikan lebih saksama, Pak Harsa bukannya marah, tapi kesal karena... lapar! Ya, persis seperti Mara yang uring-uringan karena darahnya belum dialiri asupan gula.
"Bapak...lapar?"[]


 kepodangkuning
kepodangkuning 









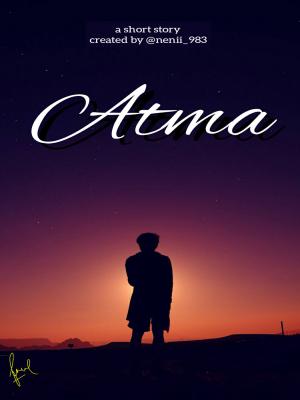
Love it... alur ceritanya enak untuk dibaca, bikin penasaran, jd bacanya harus sampai tuntas gak boleh kejeda2.
Comment on chapter 21. Seperti Namamu