Setelah pria itu memohon setengah memaksa agar aku membantunya berdiri, aku terpaksa... eh, jangan terpaksa deh. Ikhlas ya Allah, ikhlas. Entar nggak dapat pahala. Aku memapah tubuh jangkungnya yang kesakitan agar bisa duduk di salah satu kursi warung kecilku.
Dari luar, Pak Harsa tidak terlihat parah kecuali fakta dia sangat kesakitan di area tangan kanannya. Itu yang membuatku khawatir. Aku penasaran, apa sih yang bikin sakit? Saat akan menyibak lengan pendek batiknya...
"Stop! Aku mohon jangan pegang," katanya mengiba. Kali ini tampangnya membuatku menurungkan niat. Dia terlihat...kesakitan. Sangat.
"Apanya yang sakit, Pak?" Kini aku benar-benar khawatir.
"Kayaknya bahuku dislokasi."
"Dislokasi?!" Aku merinding. Aku nggak tahu dislokasi itu apa, tapi tetap merasa dislokasi adalah istilah yang tidak bagus.
"Iya. Sakit banget."
"Emang dislokasi itu apa?"
Pak Harsa menghela napas berat sebelum menjawab. "Tulang bahuku lepas dari sendinya. Yang di sini," jelasnya merintih. Dia menunjuk-nunjuk lokasi dislokasi di pangkal tangan dekat bahu.
"Heee?!"
Detik itu juga aku nggak berani memegang walau hanya seujung bajunya. Aku ikut-ikutan meringis. Pasti sakit banget.
"Terus gimana? Ke rumah sakit aja ya, Pak, biar dioperasi," celetukku khawatir tanpa pikir panjang. Uugh, rumah sakit pasti identik dengan jarum, kan? Hiiii...
"Lihat apa kata dokter saja. Temani aku ke rumah sakit."
Eh, Gimana?
"Kok aku yang temenin Bapak?"
"Ya siapa lagi kalau bukan kamu? Kamu yang nolong aku, kamu yang bawa aku ke rumah sakit. Ayo jangan mikir terlalu lama. Tanganku makin sakit, nih."
Tunggu, tunggu. Ada yang salah deh. Aku... barusan dipaksa temenin Pak Harsa, nih?
"Namamu...?"
"Cala." Pakai huruf k ya. Jadi dibaca Kala.
"Cala, aku tidak berani sendirian ke rumah sakit dengan kondisi begini. Kalau terjadi apa-apa?" Pak Harsa menunjuk tangan kanannya.
Iya juga, sih.
"Terus tokoku gimana, Pak? Motorku? Aku belum beres-beres."
Kalau mau mengadu nasib, aku jabanin! Tapi, aku mengadu nasib sama orang sakit. Enggak apple to apple deh, Cal. Demikian protes hati kecilku.
"Kamu bisa bawa mobil?" tanyanya menahan sakit. Argumenku nggak direspon! Tapi, duuuh, lihat wajahnya udah semaput. Jiwa kasihan dan nggak tegaanku meronta-ronta. Tolong nggak, nih?
"Bisa."
"Masukkan motormu ke dalam warung, beres-beres sebisanya, pastikan semua kompor dan lampu mati, lalu tutup toko. Antar aku ke rumah sakit. Sekarang."
"Kan Bapak bisa pakai taksi, Pak." Walaupun berkata demikian, hati nuraniku barusan memarahiku.
"Tolong, Cal..."
Aku mana bisa menolak kalau wajahnya udah kayak anak kucing yang butuh pertolongan. Mirip wajah si Oncom, kucing Pak Bas.
"Iya, iya."
"Terima kasih."
Tuh kan, wajahnya berubah jadi lega banget. Bodoh, kamu Cala. Kenapa enggak diiyain dari tadi?
***
Sudah pertengahan jalan, otak kecilku masih belum bisa mencerna apa yang terjadi. Mengapa aku nyupirin si aneh bin jutek Pak Harsa?!
"Cala, jangan melamun. Fokus nyetir," rintihnya.
Sial. Pak Harsa bikin aku kaget. Lirikannya seakan menyindir kebodohanku yang ragu-ragu menolongnya.
"Enggak melamun kok, Pak. Lagi menikmati kemacetan. Jam pulang kantor," ucapku melawan rasa bersalah. "Sabar ya, Pak." Pak Harsa mendengkus kecil gara-gara kata 'menikmati'ku
"Tidak apa-apa. Biar lambat asal selamat," rintihnya. Setelah mengatakan itu, Pak Harsa tak lagi bersuara untuk beberapa menit ke depan.
Aku enggak nyaman dengan kesenyapan yang begitu memekakkan telinga model begini. Aku putuskan untuk mengintip lewat sudut mata. Pak Harsa memejam mata dan keningnya berkerut samar. Anak rambutnya lengket karena basah, bulir keringatnya terus bermunculan di kening. Padahal AC di mobil udah dingin begini. Pasti sedang menahan sakit.
"Pak, aku bawa ngebut enggak apa-apa?" Tentu harus aku tanya. Nanti yang bersangkutan protes, gimana? Dia kan tukang protes.
"Aku tidak mau kecelakaan untuk yang kedua kali," gumamnya. "Safety first, Cala."
Tuh kan?
"Iya, iya."
Setelah dua puluh menit membersamai kemacetan ibu kota yang penduduknya buru-buru mau pulang, akhirnya kami sampai di salah satu rumah sakit di bilangan Jakarta Timur dan disambut kursi roda oleh dokter kenalannya di IGD. Pak Harsa yang menelepon temannya itu.
Dokter Mo mendorong kursi Pak Harsa ke salah satu bilik pemeriksaan, kemudian langsung memeriksa bahunya. Dan apa yang ditemukan? Owmaigad, bahunya terlihat tidak normal. Ada tulang yang menonjol dengan tidak wajar di sana.
Kemudian Pak Harsa disuruh melakukan rontgen. Maka aku yang bertugas menjaga barang-barang Pak Harsa, mulai dari baju, dompet, hingga ponselnya. Apa dia enggak takut aku bisa aja dibikin lupa oleh hasutan setan bahwa ada malaikat pencatat amal di kiri dan kananku, lalu kabur dengan semua barang berharga ini dan membawa lari mobilnya? Edyan memang Pak Harsa.
Ngomong-ngomong, aku mesti lihat ke mana, nih? Ada mahakarya Tuhan yang lagi enggak pake baju. Ehem, telingaku kok panasan gini, ya?
"Berita baiknya enggak perlu dioperasi. Bisa dilakukan reduksi tertutup kayak dulu, Sa."
Syukurlah suara si dr. Mohammad Saleh, SP.OT—begitu yang tercetak di papan nama dada kirinya—mengalihkan mataku dari dada Pak... SETOP CALA.
Pak Harsa langsung menghebuskan napas lelah.
"Reduksi...tertutup?" tanyaku. Aku enggak ngerti apa-apa soal istilah medis tadi.
"Dia ini pernah dislokasi bahu," jelas dokter berkaca mata itu. "Jadi mudah terjadi dislokasi lagi kalau jatuh atau dalam kasus tadi... kecelakaan. Jadi, reduksi tertutup itu kalau bahasa sederhananya memosisikan kembali tulang yang lepas dari sendinya tanpa operasi."
"Aaah, begitu."
"Kita mulai ya, Sa."
"Hm." Pak Harsa mengangguk pasrah.
"Nggak mau ditenangin dulu pacarnya, Mbak?"
"Siapa?" tanyaku.
"Ya dia, lah." Si dokter mengulum senyum dan nunjuk... Pak Harsa?
Aku tertawa sumbang. "Mana ada, Dok. Dia—"
"Bisa cepetan, Mo?"
"Udah tua nggak boleh buru-buru. Entar cepat keriput."
"Ck. Sakit, Mo," rengeknya. Yang benar saja. Dasar Pak Manja!
"Iya, iya. Aku suntik obat penenang dulu."
"SUNTIK?!" Jarum. Aku benci jarum. Benci sangat!
Kedua orang itu menoleh kaget padaku. Biarin. Aku enggak peduli. Aku.Benci.Jarum.Titik!
"Ada masalah, Mbak?"
"Mo!"
"Iya, iya, bawel. Akan menyengat dikit, Sa."
Sebelum dokter Mo mengoles alkohol, aku tidak mau tahu lagi apa yang mereka lakukan. Lebih baik aku berada dalam kegelapan daripada melihat jarum itu ditancapkan ke kulit Pak Harsa.
"Tahan, Sa," kata suara Dokter Mo.
Setelah beberapa menit yang hening, tiba-tiba ada suara teriakan yang membuat bulu kudukku merinding.
"AAAARGH!"
Ketika aku membuka mata, Pak Harsa udah ngos-ngosan aja. Matanya merem seperti kelelahan. Dadanya yang... ehem... bidang, naik turun seakan habis berlari mengelilingi rumah sakit.
"Bapak kenapa? Kenapa suntikannya? Nggak berhasil? Jarumnya patah? Jarumnya ketinggalan di dalam kulit Pak Harsa?"
"Selesai."
"Apanya yang selesai, Dok?" tanyaku enggak mengerti.
"Bahunya sudah kembali seperti semula."
"Owh. Alhamdulillah. Bukan gara-gara jarum suntik teriaknya?" selidikku.
"Ya enggak lah, Cala. Kamu terlalu penakut lihat tulangku di-adjust lagi ke posisi semula, iya, kan?"
"Bukan begitu," rungutku. "Aku..." Ah, untuk apa aku repot-repot menjelaskannya? "Lupakan, Pak."
Aku perhatikan Pak Harsa terus menekuk tangannya dan menekannya ke arah dada.
"Pakai arm sling ya, Sa, selama satu sampai tiga minggu. Nanti kontrol lagi ke aku."
"Oke. Thanks, Mo."
"Kayak kamu orang asing untukku, Sa, Sa."
"Bajunya, Pak?"
"Pegang saja dulu, Cal. Aku masih gamang menggerakkan badan." Oh, Baiklah. Tapi...yakin enggak pakai baju sampai dia pulang?
Dokter Mo sendiri yang memasangkan alat untuk menyangga lengan Pak Harsa agar tetap dalam posisi huruf L.
"Udah beres kan, Pak? Aku udah bisa pergi, kan? Aku ada janji sama temen."
Waktu aku hendak menyerahkan semua barangnya, Pak Harsa berkata, "Kamu mau melarikan diri dengan meninggalkanku di rumah sakit?"
Begimane maksudnye, Bapak? Telingaku mendadak berdenging.
"Dia yang nabrak kamu, Sa?!"
"BUKAN, Dok!" Aku beralih ke Pak Harsa. "Pak, Bapak buat aku terlihat seperti orang jahat di depan Dokter Mo. Klarifikasi. Enggak mau tahu!"
"Bukan, Mo. Dia yang antar aku ke sini."
Nah, kebetulan Jeff nelepon. "Halo Jeff," jawabku segera.
"Jadi kan, makan gultiknya?"
"Jadi dong. Ini mau pergi."
"Oke. Gue berangkat ya."
Udah telat kalau mau pulang, mah. Langsung dari rumah sakit aja.
"Cala. Tolong antar aku sampai ke rumahku. Nanti supir keluargaku akan antar kamu pulang. Ya?" selanya tanpa merasa bersalah.
"Tapi Pak..."
Wajah memelas itu mengunciku. Aku nggak bisa nolak. Bukan, bukan. Aku nggak mampu nolak Pak Harsa kalau begini ceritanya. Pak Harsa curang!
"Cala, gimana?" sahut Jeff di seberang sana.
Haaah. "Maaf, Jeff..."
***
Ada negara Perancis pada nama french toast. Padahal makanan ini aslinya bukan dari Perancis. Digadang-gadang, resep roti yang direndam dengan larutan telur, dan susu ini mirip dengan resep roti yang terdapat dalam kumpulan resep pada zaman kekaisaran Romawi, yaitu apicios.
Lalu, kenapa ada kata french-nya? Nah, katanya lagi nama french toast muncul di buku masak Inggris di abad ke-17. Potongan rotinya mirip dengan potongan kentang goreng, yang dalam bahasa Inggris disebut french fries.
Teori lain mengenai nama french toast, seorang chef bernama Joseph French dari Amerika Serikatlah asal muasal kata french dipakai untuk menunjukkan resep roti tersebut dibuat oleh Chef French, sehingga dinamakan French's toast. Karena dia sendiri kesulitan melafalkan nama resepnya, maka jadilah roti buatannya dinamakan french toast.
Demikianlah sekelumit sejarah penamaan roti panggang itu. Terserah kalian mau condong ke sejarah yang mana. Tapi buatku, aku amat berterima kasih kepada siapapun yang menemukan ide brilian yang lezat itu. Makanan ini yang menjadi pengingat bahwa Ibuk pernah menyayangiku amat tulus, sebab Ibuk sering membuatkan aku roti ini, sebelum Mara menghirup oksigen di bumi, dan sebelum bibir Mara robek dan gigi susunya patah. Aku enggak akan melupakan masa-masa indah itu.
"Mbak! Hangus. Hangus!"
Apa yang hangus?
"Astaga! Rotiku!" Asap putih di permukaan roti membuatku panik. Aku telah membiarkan pesanan pelanggan tak tersentuh perhatian spatula gara-gara lamunan yang enggak berfaedah.
Asap pekat yang menipu. Ternyata setelah dibalik, roti panggangku masih selamat.
"Nggak hangus, Mbak. Hanya warnanya sedikit lebih gelap," ucapku harap-harap cemas. Aku perlihatkan bagian tadi pada perempuan berbusana coklat khas seorang pegawai negeri. "Tapi kalau Mbak mau tukar, aku buatin lagi," tawarku. Pelanggan adalah raja. Itu motoku.
Aku bisa melihat ada pergolakan di matanya ketika dia mengintip jam tangannya.
"Itu aja. Aku mau cepat-cepat balik kantor."
"Baik, Mbak. Ditunggu lima menit."
Jadi pegawai negeri, ya? Apa aku coba saran Nyonya Bet dan ikut tes? Enggak, enggak. Aku masih cinta warung ENTRY.
Kotak kertas yang sudah aku tulis Malika—sesuai dengan nama si pembeli—aku serahkan. Mungkinkah dia dibesarkan bagaikan anak sendiri? Tentu saja dibesarkan oleh orang tuanya sendiri. Memangnya aku, yang dibesarkan bagai anak orang lain di rumah sendiri?
Setooop! Kamu bisa berhenti, Cala. Kamu enggak pantas mendiskreditkan keluargamu sendiri. Tapi Tuhan, aku enggak bisa lepas dari gagasan itu. Gagasan ketika aku mungkin aja anak yang tidak terikat kromosom, gen, apalagi DNA Pak Bas dan Nyonya Bet. Makin lama, aku makin tenggelam dengan argumen sesat itu. Masalahnya, mau menyangkal dengan ekstrim, jelas-jelas keriting paripurna rambutku, alis tebal bak pasukan semut beriring, dan berkarakter sumbernya dari Bapak. Kepintaran memasak dan kecantikan Masyaallah dari Ibuk. Konon kata Bapak, wajahku ngejiplak wajah Ibuk kala remaja. Masih mau menolak takdir Tuhan?
Aku tidak mau berprasangka, tapi Ibuk terlalu sering melupakan eksistensi anak keduanya ini. Masa baru pulang dari mengantar Pak Harsa, aku dapati Ibuk, Bapak, dan Mara baru selesai menyantap pempek. Tinggal kuah cuko doang. Aku enggak disisain, dong! Aku juga mau. Enggak jadi makan gultik sama Jeff pula. Kan lapar maksimal.
Begini nih, nukilan alasan Ibuk malam itu.
"Ibuk kira kamu makan di luar."
"Tapi Ibuk bisa sisain, Buk. Ibuk kan tahu Cala doyan pempek," ucapku sedikit merengek.
Saat itu aku sudah meradang. Mungkin karena perutku sudah terlalu lama tidak diisi makanan membuat emosiku bagai ombak pasang. Padahal aku SELALU menyisihkan makanan untuk anggota keluarga lain yang belum kedapatan makanan yang aku beli atau aku buat.
"Lha, kata Ibuk enggak usah ditinggalin buat Kak Cala. Kak Calanya mau ternyata, Buk," protes adikku." Ah, sudah, lah.
"Cala ngantuk. Mau cepet-cepet tidur. Malam Pak, Buk."
Malam itu tenggorokanku bagai tersumpal roti empuk Jeff. Aku memilih menghilangkan diriku masuk kamar.
Pasti kalian pikir aku makhluk lebay. Hanya karena pempek aku ngambek seperti anak kecil. Ini kan perkara sepele.
Tidak. Tidak sesepele itu bagiku. Kejadian seperti ini terlalu sering terjadi dalam hidup singkatku. Sepanjang belasan tahun hidupku. Mengalah adalah nama tengahku, apalagi bila berkaitan dengan Mara. Mau itu untuk makanan, mainan, buku, baju, ah, terlalu banyak. Demi Tuhan... selama belasan tahun, aku... diperlakukan seperti anak tiri.
Ting!
Ada pesanan masuk. Alhamdulillah. Pesanan adalah angin segar bagi pikiranku yang sumpek gara-gara pempek.
"Atas nama Harsa Hasyim."
Demikian nama pemesan yang masuk ke dalam sistem pemesananku dengan mitra ojek daring perusahaan hijau. Harsa Hasyim sudah beberapa hari ini menjadi pelanggan virtualku. Aku mulai curiga dia adalah orang yang sama dengan orang yang aku tolong tempo hari. Hari ini pesan french toast gurih lengkap. Kemarinnya lagi waffle gurih lengkap. Bukankah ini kebetulan yang lucu?
Dan yang lebih lucu lagi tuh, Pak Harsa! Aku nggak kenal dia, tapi dia enggak segan-segan menunjukkan betapa rewel dan manjanya dia sebagai pria dewasa. Persis seperti Mara yang rewel saat demam. Padahal kami baru bertemu dua kali.
Tanda-tanda kerewelannya dimulai ketika kami hendak pulang dari rumah sakit. Pak Harsa kan udah enggak pakai baju sejak tangannya dipakaikan arm sling. Jadinya, itu baju beralih fungsi menjadi selimut penutup badan.
Dingin, Cala. Matikan AC.
Tidak boleh buka jendela.
Jangan berisik.
Bawa mobilnya pelan-pelan saja. Ngeremnya harus mulus, masih sakit tanganku. Terima kasih, Cala.
Demikian rengekan Pak Harsa yang aku rekam. Benar-benar lucu.
"Kakak ketawa sama teman imajiner, ya?"
Saat aku mendongak mencari sumber suara, seorang gadis manis tersenyum manis padaku. Dan aku balas dengan senyuman pula.
"Aku enggak punya teman imajiner, ya. Aku masih normal!" belaku. Hayu tertawa kecil.
Betewe, dia Hayu, salah seorang mahasiswa di kampus N yang kerap membeli waffle, sandwich buah, dan pancake— tiga menu itu adalah kesukaannya. Dia sering banget nongkrong sendirian di warungku sambil mengerjakan tugas sejak tahun pertamanya.
"Habisnya, ketawa sendiri. Atau pesan dari pacar?" godanya.
"Bukaaan. Aku dapat pesanan, Yu. Seneng lah," kilahku. Gara-gara Pak Harsa manja, nih.
Lagi-lagi Hayu terkekeh.
"Kak, waras selalu ya. Hayu masih pengen jajan di ENTRY."
Aku spontan tertawa lepas. Mungkin aku memang butuh tawa untuk mengendorkan sarafku yang tegang gara-gara putaran arus pikiran yang memutar adegan keluarga harmonisku, Harsa Hasyim, dan Pak Harsa yang manja.
Kami tuh sudah seperti long lost sister yang enggak pernah aku dapatkan dalam keluargaku.
"Iya. Pasti. Mau pesen?"
"Ho'oh. Pancake sirup maple satu makan di sini."
"Oke. Aku kelarin pesanan yang ini dulu ya."
"Tentu." Hayu masih tidak beranjak dari meja kerjaku. "Kak, aku pengen deh mulut abangku disumpal sandwich buah seger buatan Kak Cala, biar enggak cerewet lagi itu mulut." Bibir perempuan cantik ini sampai mengerucut karena cemberut.
"Emang kenapa?"
"Aku baru tahu, kalau habis kecelakaan mulut abangku sumpah baweeel banget. Darahnya kurang gula kali ya!" Wajah manisnya jadi tertekuk lucu.
Kecelakaan? Belakangan kupingku rada sensitif dengan kata kecelakaan.
"Kecelakaan gimana, Yu?"
"Dia mau nyebrang, eeeh ditabrak pemotor ugal-ugalan. Untung cuma dislokasi bahu, bukan dislokasi kepala dari badannya." Hayu sampai geleng-geleng kepala.
Sebentar. Dislokasi? Motor ugal-ugalan? Kok, bisa samaan sama kecelakaan si manja Pak Harsa?[]


 kepodangkuning
kepodangkuning 


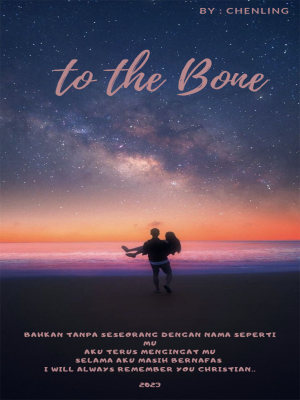







Love it... alur ceritanya enak untuk dibaca, bikin penasaran, jd bacanya harus sampai tuntas gak boleh kejeda2.
Comment on chapter 21. Seperti Namamu