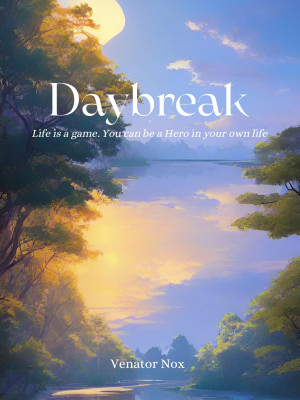Hanya sejumput insan yang mengetahui benang merah. Lihat saja orang yang pacaran bertahun-tahun tapi pada akhirnya duduk di pelaminan bersama orang lain. Jangan pernah berlebihan dalam mengharap jika tak mau nestapa, karena jodoh itu tak hanya satu, aku membuktikannya.
Pengkhianatan Arya sempat membuatku trauma untuk menjalani hubungan lagi. Namun, melihat teman sebaya yang sudah menjalani resepsi pernikahan membuatku dongkol. Aku tak mau diberondong pertanyaan bodoh tentang kapan menikah. Usiaku sebentar lagi dua puluh dua, terhitung tua untuk ukuran perawan desa.
Kedatangan Pranaja bersama orang tuanya dengan maksud melamar membuatku bimbang. Aku malas menjalani suatu hubungan jika lelaki itu ujung-ujungnya berlaku bejat. Aku tak mau peristiwa lama terulang kembali bersama lelaki yang berbeda. Lagi pula, aku tak memiliki rasa pada lelaki bermata sipit itu. Aku tak percaya lagi pada kata “cinta”.
“Aku tahu trauma yang kaumiliki. Maka dari itu, aku tak ingin kau bersama orang yang salah lagi. Aku bisa belajar dari kesalahan Arya dengan tidak mencontohnya.” Pranaja menghampiriku yang tengah memikirkan jawaban ya atau tidak di belakang rumah. “Kalau kau tidak mencintaiku, bukan masalah. Jodoh tidak melulu dilandaskan cinta, tetapi kecocokan.”
Aku menatap matanya, mendapat sorot penuh keseriusan darinya. Aku tak tahu apa kecocokan yang dimaksudnya selain weton. Sifat kami bertolak belakang sehingga aku kerap kesal padanya.
“Aku takkan mengatakan kata “cinta” yang menurutku konyol. Yang pasti, aku merasa cocok dan ingin menjalani hidup denganmu.”
Tak mau menyia-nyiakan kesungguhan itu, aku mengangguk dan berbisik pada Ayah untuk mewakiliku menjawab “iya” pada orang tua Pranaja.
🌼
"Jadi, kalau waktu itu Papa gak meyakinkan Mama, belum tentu Papa sama Mama menikah, ya?" tanya seorang gadis kecil dengan rambut ikal sebahu, tak lain adalah putriku.
"Kamu baca diary Papa ya?" tanya suamiku gelagapan. Sudah bisa ditebak siapa dia, bukan?
"Gemboknya lepas sih," sahut putri kecilku sembari menunjukkan buku berwarna merah muda dengan gembok terbuka. Aku tidak bisa lagi menahan tawa.
Pranaja merenggut buku itu dari tangan putri kami, kemudian menyembunyikannya di belakang tubuh sambil menghindar dari tatapan jenakaku.
Itulah Pranaja dengan tingkah ajaibnya. Kadang aku merenung, kok bisa aku memaklumi keabsurdannya yang kekanakan itu. Padahal ketika melamarku, pengutaraan tentang pikirannya yang begitu dewasa telah membuatku terkesima.
"Papa kenapa sih suka ribut? Lihatlah Mama yang selalu kalem. Sepertinya gender kalian tertukar," ucap putri kecilku yang masih berusia empat tahun.
Citrakara Jasrin Reswara namanya. Putriku yang dewasa pikirannya apalagi ia suka membaca buku harian penuh aib milik ayahnya. Aku tidak terkejut mendengar setiap kalimat yang dilontarkannya. Namun, lain dengan Pranaja Reswara.
"Demi apa kamu bilang seperti itu?! Kamu tahu kata gender dari mana? Na, lihat anak kita sudah setua itu!"
Kini, kami tinggal di Yogyakarta. Pranaja bekerja sebagai petani hutan dan sekarang sedang cuti sementara aku di rumah mengurus Jasrin. Kalau ia sudah sekolah, aku akan kembali bekerja di cabang butik milik budeku.
Rumah yang kami tinggali sederhana, bergaya joglo dengan halaman penuh tanaman hias. Di ruang tamu, terpajang kain batik motif bunga dan sulur-suluran di bagian tepinya khas Majapahit yang disebut wdihan ganjar patra sisi, serta terpampang lukisan Nayaviva yang dilukis oleh Arya Buntara. Lukisan itu dibawa Pranaja sejak kami kembali ke masa depan karena waktu itu aku ketakutan melewati hutan gelap sehingga tak begitu menghiraukan keberadaan lukisan itu. Arsitek yang membangun rumah ini adalah Mas Dika yang sampai sekarang belum beristri padahal usianya sudah kepala tiga.
Setelah menikah lima tahun silam, Pranaja lekas memperkerjakan Mas Dika dan beberapa tukang untuk membuat rumah setelah mendapat lahan. Ia menghendaki punya rumah sendiri untuk kami tinggali supaya lebih leluasa menjalani kehidupan berumah tangga. Ia paham keceriwisan ibunya yang bisa membuatku tak betah. Ia tahu bahwa istrinya lebih bahagia jika tak tinggal serumah dengan mertua. Meski tak percaya lagi dengan cinta, aku menyayangi Pranaja yang begitu memahamiku.
Jasrin terlelap, menyisakanku dengan Pranaja dalam keheningan. Kami duduk di bangku teras sembari mengenang masa-masa di mana kami hidup dalam zaman ratusan tahun silam. Kami mengutarakan ketakjuban terhadap diri kami sendiri yang mampu beradaptasi.
"Kautahu kejadian sebelum kita bertemu? Waktu itu aku ditanyai oleh orang bertombak yang menatap heran pakaianku. Karena aku ketakutan dan tak tahu bahasanya, aku lari tunggang-langgang kemudian menubruk babi hutan yang sedang minum di kali," kata Pranaja.
"Oh jadi itu sebabnya kau dikejar babi hutan lalu bertemu denganku ... "
"Omong-omong gimana kabar si Buntel itu ya?"
"Aku pernah dapat mimpi, dia bertapa di gua. Entah untuk apa, toh bukan urusan kita lagi." Aku mengangkat bahu tak acuh.
"Bagaimana kalau dia berusaha menarikmu ke sana?"
"Tidak mungkin, aku telah mempunyai perisai." Kutunjukkan kalung emas dengan bandul kembang wijayakusuma pemberian Kakung, bentuknya sama persis dengan anting milik Roro Sukmo.


 orenertaja
orenertaja