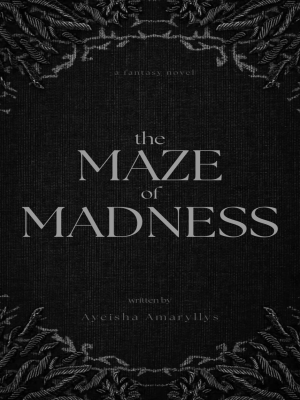Debaran di dalam dadaku tak bisa terkontrol ketika Pranaja mengucapkan nama asliku. Untuk pertama kalinya ada yang menganggapku sebagai Renjana. Aku merasa seolah-olah dianggap keberadaannya, kemudian kunaiki undakan panggung untuk menyapa insan yang mengerti siapa diriku. Selama ini, orang-orang mengenalku sebagai orang lain yang kudiami jasmaninya. Bahkan suamiku sendiri tak pernah memanggilku sebagai Renjana padahal ia sudah mengetahui identitasku. Ia mencintaiku sebagai Nayaviva yang jelita, bukan sebagai Renjana yang pemarah.
Netraku dan Pranaja beradu, kudapati manik gelap nan sipitnya berkaca-kaca entah mengapa. Tahu-tahu lengan kurusnya merengkuhku dan tanpa sadar aku pun membalas.
Bruk! Hantaman pada pintu yang terbuka membuatku terperanjat serta jantungku kian bertalu-talu seperti ingin melepaskan diri. Tanpa memberi kesempatan untuk jantungku lebih tenang, si penghantam bertelanjang dada itu menarik kasar lenganku hingga tulang bahuku berderak dan ngilu.
"Agaknya kau belum kapok, Viva! Masih saja bermain dengan bocah itu!" Arya menekan kalimatnya, membuat rahang yang tegas itu semakin keras.
"Jangan gertak Renjana!" Pranaja mendorong Arya yang bergeming tak mendapat pengaruh dari tubuh kecil lawannya. Aku menggeleng kepada Pranaja, mengingatkan bahwa Arya tak sepadan dengan dirinya.
Pria dengan destar merah serta rambut digelung itu melepas cengkeramannya, kemudian memberi bogeman pada muka Pranaja hingga hidungnya berdarah. Aku melaung seraya mendekap Arya dari belakang sementara Pranaja bangkit hendak membalas pukulan yang menurunkan harga dirinya.
Arya melepas tanganku dari tubuhnya kemudian meladeni Pranaja yang tak sadar dengan kemampuan bela dirinya yang tampak konyol. Aku amat yakin, segala jurus yang Pranaja keluarkan tak cukup menghindarkannya dari babak belur mendapat kepiawaian Arya yang ilmunya tak perlu diragukan sampai memiliki macan putih.
Aku meringkuk, tak sanggup melihat banyaknya darah yang menetes dari Pranaja. Lelaki keras kepala itu terus melawan walau tak membuahkan goresan sekecil pun pada tubuh Arya.
"Pranaja, mengalahlah! Kau bisa terluka parah!" seruku kemudian memekik tatkala Arya memukul tengkuk Pranaja hingga tak sadarkan diri.
"Arya! Dasar biadab. Tak cukupkah kau melukaiku selama ini?!" Aku menyeru sembari melangkah lemas menuju Pranaja yang terkapar.
"Biadab?! Kau yang membuatku seperti ini, Viva!" balas Arya sambil menunjukku dengan hina. Harga diriku tergores. Ke mana Arya yang suka menggodaku?
"Aku bukan Viva. Aku Renjana! Tak ingatkah kau dengan diriku yang sebetulnya?!" ucapku, berdiri dengan dada kembang-kempis.
"Baguslah kalau begitu. Jadi aku tidak mengenalmu dan kau bukan siapa-siapaku. Jangan kembali ke rumahku!" balas Arya penuh penekanan. Ia menyodorkan sebuah lukisan yang membuat hatiku tercebur dalam kepiluan tiada tara. “Itu adalah bukti cintaku padamu, Viva. Namun kau tak menghargainya dengan berlari ke pelukan lelaki asing yang tak jelas asal-usulnya itu.”
"Arya ... Kau berubah," lirihku dengan pandangan mengabur oleh air mata. Lukisan di tanganku yang gemetar tak lagi jelas terlihat. Aku berkedip, menitiklah air bening nan asin di atas lukisan sosok Nayaviva yang tengah memegang sekeranjang kecil buah. Bunga sepatu dan kemboja bertengger di atas gerai rambut. Wajahnya tak tampak karena waktu itu aku melengos malu.
Tanpa banyak cakap lagi, Arya bertolak diri melewati ambang pintu dengan langkah mantap dan bahu tegak. Aku paham, ia sosok lelaki tegar yang takkan sepenuhnya jadi budak cinta. Ia masih punya perempuan di rumahnya yang tak menye-menye macam diriku. Maka, tak mungkin ia sudi berbalik padaku. Tak dapat dipungkiri hatiku ketaton membayangkan hidup tanpa seseorang yang selalu membayangi masa-masa manis di tengah sawah.
Kami sudah berakhir.
Aku memandang sendu Pranaja yang terkapar dengan banyak darah di wajahnya. Kuletakkan lukisan di amben, kemudian mengecup pipi Pranaja sebelum berlalu ke hutan mencari herbal untuk membuat ramuan. Aku tak tahu alasan melakukan itu, padahal aku baru saja dicampakkan lelaki yang kucintai.
Tak mau memikirkannya terlalu dalam, aku terbengong mendapati diriku tak mahir membuat ramuan. Namun aku harus membuat Pranaja cepat pulih. Bagaimanapun ia telah berpihak padaku sampai babak belur begini.
Aku memetik beberapa jenis daun yang bisa menjadi obat; daun jintan, daun kemangi, dan daun binahong sembari memutar otak bagaimana meracik tanaman itu hingga menjadi obat manjur.
"Permisi, Nyisanak. Sedang mencari apa?" Suara pria tua membuatku terperanjat.
"Ini, Kisanak. Saya mencari bahan untuk membuat ramuan," sahutku. Timbul perasaan bersalah setelah sadar kemungkinan pria itu pemilik tumbuhan yang tengah kujumput.
"Maaf bila tumbuhan yang saya petik ini milik Kisanak. Saya akan membayarnya," kataku seolah-olah aku punya banyak keping gobong.
"Ah tidak perlu, dan panggil saya Ki Suro. Omong-omong, untuk siapakah ramuannya?"
"Teman saya, Ki. Sejujurnya saya tidak pandai membuat ramuan," kataku lalu ki Suro menawarkan untuk membantu.
Aku pun lega mendapati seseorang yang dengan senang hati mengulurkan tangan di saat-saat seperti ini. Ki Suro membantuku mengangkat Pranaja ke amben, kemudian membuatkan ramuan untuknya yang kesadarannya mulai pulih.
"Terima kasih banyak, Ki. Saya tidak tahu apa yang terjadi bila tidak ada Ki Suro." Pria tua dengan pakaian serba hitam dan rambut putih uban itu mengangguk sambil tersenyum memperlihatkan giginya yang tinggal beberapa.
Ki Suro mengucapkan sesuatu, seperti mantra ke air putih yang kemudian dicipratkan ke wajah Pranaja. Ia juga memberi mantra pada ramuan hijau pekat sebelum diminum oleh empu keras kepala yang sok menandingi pawang harimau.
Setelah menelan habis ramuan, Pranaja mengeluarkan isi perutnya dengan bonus gumpalan darah.
"Tenang, itu pertanda baik. Tak lama lagi dia pasti sembuh," ucap ki Suro menenangkanku yang resah dan mulai menangis. Rupanya dicampakkan amat berpengaruh terhadap psikisku hingga cengeng seperti ini.
Ki Suro menyuruh Pranaja istirahat. Ia berkata, "Aku tabib di desa ini. Kalau kau butuh bantuan, bisa bertandang ke rumahku di dekat persimpangan Alas Ringin."
Aku mengiakan dengan senang hati. Kami duduk di dekat kaki Pranaja sementara Ki Suro menanyakan sebab pemuda ini terluka.
"Aku dan suamiku terlibat pertengkaran dan Pranaja membelaku. Mereka beradu, tentu saja Pranaja kalah dari suamiku yang punya ilmu kanuragan sekaligus aji-ajian tinggi."
"Mungkin suamimu tidak menyukai kedekatanmu dengan pemuda itu."
"Memang. Dan bukan hanya itu, ia mulai membenciku karena aku tak kunjung memberikan keturunan. Sedangkan istri barunya sudah mau mitoni*," jelasku.
"Sabar. Pasrahkan semua pada Sang Hyang Taya."
Aku mengangguk sadrah. Memangnya apa lagi yang bisa kuperbuat selain sabar?
Aku bertolak menuju dapur untuk mengambil minuman buat Ki Suro. Pranaja sepertinya tidak pernah membubuk teh atau kopi karena di dapur hanya ada kendi berisi air putih rebusan. Setelah keluar dari dapur, Ki Suro sudah menghilang dari pandangan. Aku mencari di setiap sudut ruangan, tetap juga tak menemukannya.
Mungkin di pelataran.
"Eh?!" seruku makin tercengang. Di pelataran yang memaparkan langsung aliran sungai, tak kutemukan kehadiran tabib sepuh yang membuatku amat terbantu. Lalu ke mana perginya Ki Suro? Secepat itukah ia pulang?
_______
*Mitoni atau Tingkeban adalah salah satu tradisi selamatan kehamilan anak pertama yang menginjak usia kandungan tujuh bulan. Tradisi ini dilakukan dengan tujuan mendoakan bayi yang dikandung agar terlahir dengan normal, lancar, dan dijauhkan dari berbagai kekurangan dan berbagai bahaya. (Wikipedia)


 orenertaja
orenertaja