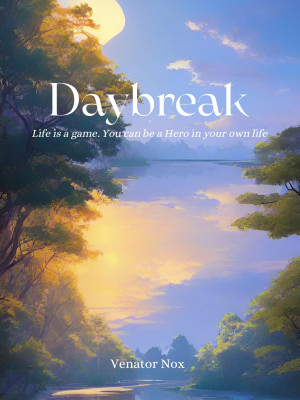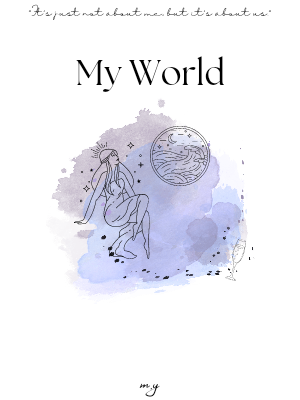Siang bolong, rumah kami kedatangan tiga orang bercelana sedengkul yang memamerkan otot dada dan perutnya. Rambut digelung, salah satunya punya kumis yang lebat menutupi bibir. Di belakang mereka, teronggok gerobak besar yang menampakkan isinya berupa bungkusan-bungkusan beras dan berikat-ikat padi. Mereka adalah rāma, pejabat desa yang tengah menarik pajak secara keliling dari rumah ke rumah penduduk. Pajak yang berupa beras maupun padi itu kemudian akan diserahkan oleh para rāma kepada mangilāla drawya haji, petugas pemungut pajak yang kemudian akan sampai pada rakai yang akan meneruskannya pada raja melalui pranata pasowanan agung.
Musim panen sudah berlalu, pajak pun ditarik pada bulan-bulan Phālguna (Februari hingga Maret) dan Caitra (Maret hingga April) dalam setiap tahunnya. Kuamati dari balik pintu sekat ruang tamu dan dapur saat Emak dan para rāma tengah sibuk bercengkerama sebelum mengangkut padi yang disetorkan Emak. Aku kembali ke kamar, tercenung mendapati pengetahuan yang terlintas begitu saja di pikiran. Aku tak pernah mempelajari sejarah, bagaimana bisa aku mengetahui orang yang datang itu adalah rāma serta memahami sistem pajak yang bahkan sama sekali tidak membuatku tertarik untuk mempelajarinya lebih dalam. Kurasa, tubuh Viva mulai menyatu dengan jiwaku sehingga apa yang diketahuinya bakal menjadi pengetahuanku juga.
Tak ayal aku terperangah, sampai-sampai dadaku bergemuruh mendebarkan pengetahuan yang merasuk. Mulutku terkunci nan kering hingga rasanya ludahku habis terkuras.
Tubuhku letoi, ambruk dan meringkuk di atas peraduan. Mataku kuyu memandang terik yang menyinari kebun dari jendela yang terbuka.
Aku tidak berniat berbicara maupun bertemu dengan siapa pun. Aku tak enak badan. Jika perkara menyatunya diriku dan Nayaviva tak dapat sepenuhnya jadi alasan, maka masuk anginlah penyebab diriku kuyu. Memang sedari kecil aku selalu masuk angin bila berhadapan langsung dengan udara dingin. Apalagi setiap hari yang kukenakan hanyalah kemban yang membuat bahuku telanjang sepanjang hari dan malam.
Untunglah Emak cepat tanggap dengan membuat ramuan alami untukku. Sebenarnya bisa saja mengundang tabib. Walaupun bapaku yang merupakan prajurit pangkat tinggi sudah mangkat, keluargaku masih mendapat bantuan uang maupun bahan pangan dari pemerintah. Berhubung dulu Bapa adalah ksatria yang cukup berpengaruh bagi kemajuan Majapahit. Emak tidak bela pati karena beliau masih memikirkan nasibku kala itu.
Aku tertidur hingga matahari mencapai ufuk barat. Suara Emak yang cempreng memenuhi ruang tamu yang kemudian merambat ke kamarku, sedang berbicara dengan seseorang yang familier. Tentu saja Arya, pria yang akhir-akhir ini mengalirkan gelenyar aneh di sekujur tubuhku.
"Viva, bagaimana keadaanmu?" tanyanya setelah duduk di sebelah ranjang yang kutiduri.
"Sudah lebih baik," jawabku sembari tersenyum walau bibirku rasanya perih, efek pecah-pecah dan kering.
"Maaf mengganggu waktu istirahatmu. Semoga cepat sembuh dan aku akan menemanimu," ucapnya.
"Tidak apa, kau pasti ada kegiatan lain yang lebih berguna. Lagi pula, ada emakku di sini yang menjagaku," sahutku. Tentu saja aku menolak. Bukannya bisa istirahat, yang ada jantungku kepayahan maraton kalau Arya di dekatku.
"Aku hanya di sini sampai emakmu kembali dari pasar." Oh, jadi Emak pergi ke pasar tanpa memberitahuku?
Kupandangi kumis tipisnya, membayangkan hal yang bisa saja terjadi selama hanya ada kami berdua di rumah.
"Buang pikiran kotormu jauh-jauh! Aku hanya tidak ingin kau di rumah sendiri dengan keadaan tidak baik. Siapa tahu ada penculik yang membawamu lalu dijadikan budak?" celotehnya, membuatku memalingkan wajah.
"Kau bisa membaca pikiran orang lain."
"Tidak."
Namun aku tidak percaya dan tidak peduli.
Hidungku mengeluarkan ingus ketika bersin, menciprat sampai ke lengan pemuda yang duduk di depanku, membuatku malu setengah mati.
Kami sama-sama membatu untuk beberapa saat, sampai aku mengusap perlahan ingus di lengannya dengan kikuk.
"Maaf," cicitku yang tidak tahu harus mengatakan apa selain itu. Melihat mukanya yang datar, nyaliku semakin menciut.
"Arya ..." rengekku karena ia masih memasang muka datar dan menatapku lurus. "Aku tidak sengaja!"
Aku menunduk menahan malu yang sudah mencapai ubun-ubun. Arya memiringkan kepala melihatku yang sudah berkaca-kaca, kemudian ia terbahak.
"Sudahlah, tidak apa-apa. Jangan menangis! Nanti Mak Lastri memarahiku," tuturnya.
Aku memukul sekuat tenaga lengannya yang tadi terciprat ingus.
"Ini buatmu," ucapnya lalu mengambil bunga yang telah dironce.
"Terima kasih banyak sudah repot-repot membuatkannya untukku," kataku. "Apa nama bunga ini?"
Arya menjawab dengan malu-malu, "Entut-entutan dan suring."
Jawabannya membuatku tergelak hingga kepalaku berdenyut. Masa namanya mirip dengan kentut? Kalau diingat-ingat, bunga itu mirip dengan bunga ubi di desaku di masa depan.
"Jangan hiraukan soal nama, yang terpenting kan bunganya bagus. Dironce oleh orang bagus pula," ucapnya narsis.
Aku memutar bola mata dan menahan tawa dengan kelakuannya yang terlampau percaya diri itu. "Terima kasih." setidaknya ia telah menghiburku.


 orenertaja
orenertaja