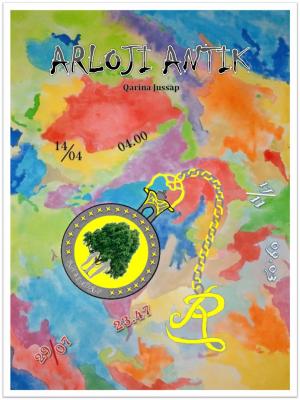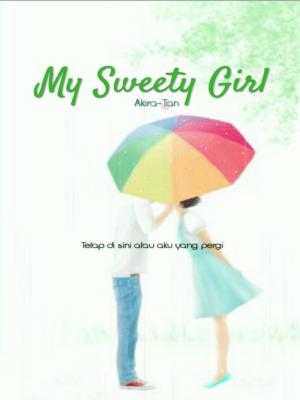Kantin agaknya bisa menjadi tempat untuk melepas lelah setelah seharian bergulat dengan pekerjaan yang tiada habisnya. Maka, tak heran saat Ara sudah menapakkan dua tungkai jenjangnya memasuki wilayah segala umat tersebut, ia sudah dihadapkan dengan ramainya pengunjung yang memenuhi tempat duduk terutama jika mengingat ini adalah jam makan siang.
“Ara!”
Namun, sesaat manakala rungunya itu mendengar panggilan dari suara yang tak lagi asing. Lengkap saat kepalanya menoleh, ia disuguhkan dengan seorang lelaki yang menampilkan senyum lebar sampai membentuk dua garis melengkung dari netra cokelatnya, Ara membalas tak kalah hangat. Melangkah pasti dan menghampiri sahabatnya tersebut sekaligus bersyukur karena ia tak perlu lagi mencari tempat duduk dengan susah payah.
“Sudah nunggu lama?” tanyanya basa-basi.
Lelaki bersurai hitam tersebut menggeleng pelan, “Nggak begitu lama. Kamu mau pesan makan siang? Biar sekalian sama aku saja.”
Ara berpikir sejenak untuk beberapa saat. Jemarinya menggaruk pelipis sebelum mengungkap ringan, “Boleh, deh. Aku hari ini mau makan soto saja.”
Pemuda di hadapan Ara masih menunggu tanpa sekalipun melepas pandang. Sedang Ara setia melihat daftar makanan dari buku menu di hadapannya, “Minumannya es jeruk saja, deh,” putus Ara.
Pemuda tersebut mengangguk patuh, “Satu soto sama satu es jeruk, ya?” tanyanya memastikan.
Ara mengangguk membenarkan. Namun, tatkala sahabatnya tersebut sudah beranjak dan baru berjalan dua langkah. Seruan Ara kembali menghentikannya.
“Juniar!”
“Apa?”
“Es jeruknya diganti saja, deh. Pakai jeruk hangat.”
Mata Juniar memincing, “Kenapa? Tumben.”
“Tenggorokanku agak serak.”
“Habis minum es pasti semalam.”
Ara tersenyum tanpa dosa. Sedang Juniar justru merotasikan matanya jengah, “Kebiasaan. Ya sudah, aku ganti.”
Menunggu Juniar memesankan makanan sampai ia benar-benar kembali. Ara memilih untuk menatap sekitar dibanding harus memainkan ponsel seperti kebanyakan orang. Tidak. Ara bukanlah orang yang tak suka bermain dengan benda pipih kotak tersebut. Hanya saja, menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar laptop dan ponselnya untuk menuntaskan tugas agar dia bisa cepat-cepat lulus, tentunya perempuan tersebut butuh hiburan segar untuk menenangkan mata.
“Jun,” Ara memanggil saat sejak tadi bosan karena Juniar yang masih asyik berkutat dengan ponselnya.
“Hm.”
“Tau, nggak? Semalam aku ketemu sama om-om ganteng.”
Perhatian Juniar pada gawainya teralihkan. Satu alisnya merangkak naik dengan senyum ledek khas di wajahnya, “Jadi seleramu sekarang sudah ganti? Biar pas lulus nggak perlu capek-capek kerja. Sudah ada sugar daddy.”
Ara menatap datar sahabatnya itu, “Bukan. Cuma, semalam aku mampir buat beli toast. Gara-gara kamu ninggalin aku kelamaan buat nge-bucin. Jadinya, aku ke sana. Plang kafenya masih buka, tapi ternyata sudah tutup. Untungnya om-om itu baik.”
Juniar meringis seraya menggaruk tengkuknya yang tak gatal, “Ya, maaf. Habisnya kan semalam itu mendadak,” namun mendadak ingatan pemuda tersebut tertuju pada seorang pria yang mengantar Ara sampai pintu depan, “maksudmu mas-mas yang di depan pintu itu?”
Ara mengangguk semangat. Ia menampilkan satu senyum lebarnya, “Berita bagusnya, aku sekarang kerja di dia. Well, nggak kerja juga, sih. Magang dulu.”
“Magang?” Juniar mengernyit bingung, “Kenapa nggak diterima sekalian saja? Lagian cuma kerja ngurus kafe.”
“Ih, bukan kafe, Jun!” Ara mendelik kesal. Bibirnya mengerucut manakala Juniar menyimpulkan itu. Kendati saat hendak melayangkan protes, makanan pesanan mereka sudah datang dan tersaji nyata di hadapan masing-masing.
Setelah mengucapkan terimakasih pada pelayan, sembari meminum es teh miliknya, Juniar lantas berkata, “Terus? Kalau bukan di kafe, dimana?”
“Jadi pengasuh anaknya.”
“Uhuk! Uhuk! Uhuk!”
“Jun!” pekik Ara, matanya menatap nyalang Juniar dengan alis menukik sempurna. Perempuan itu bahkan melayangkan beberapa pukulan di lengan Juniar yang belum sempat mendapat penolakan lantaran si pemuda tersebut masih harus menetralkan batuknya. “Jijik!” Ara lekas menarik beberapa lembar tisu serampangan guna membersihkan sisa-sisa air yang bercampur dengan liur Juniar di wajahnya.
“Gendheng kamu, Ara!” Juniar memekik tak mau kalah. Ara bahkan sampai mendelik sekali lagi hanya agar memastikan mereka tidak lagi menjadi bahan tontonan sekitar.
“Apanya yang gendheng?” Ara menaikkan bahu acuh, “Yang penting aku dapat kerja, Jun. Biar dapat uang buat beli novel. Skin care-ku juga sudah mau habis. Kamu nggak mau kasih subsidi lagi, sih. Halal juga, lagian.”
Juniar menatap tak habis pikir. Dua tangannya spontan meremas rambut tak peduli lagi itu akan berantakan. Ia memajukan kursi dengan suara yang memelan kendati penuh penekanan, “Ara! Dia itu sudah punya anak! Kamu masih muda! Gila saja. Memangnya dia nggak punya istri? Nanti kalau ada apa-apa gimana?”
Ara memandang polos, “Ada apa-apa gimana?”
Juniar mengeram gemas, “Ara, kamu perempuan, oke? Sedang dalam usia matang-matangnya. Daun muda. Pria mana pun, selagi mereka normal dan punya istri. Kalau lihat yang masih segar-segar sepertimu, bisa saja sesekali dia tergoda. Kamu mau jadi sebab pernikahan orang lain rusak? Jangan mentang-mentang drama korea tontonanmu lagi tenar-tenarnya pelakor, kamu malah mau ikut-ikutan.”
“Sudah?”
“Apanya?”
“Ngomelnya,” sahut Ara datar.
“Mau aku tambahin lagi?”
Cepat-cepat Ara menggeleng, ia memandang Juniar lekat dengan dua tangan yang terlipat di pinggir meja. Sepenuhnya mengerti apa yang diucapkan sahabatnya barusan, “Justru ini, Jun. Kayaknya dia jadi single daddy, deh.”
“Duda maksudmu?”
Ara mengangguk, “Soalnya dia minta aku ngasuh anaknya sejak siang sampai malam. Katanya kalau pagi, dia yang ngurus semuanya. Logikanya, kalau dia punya istri, nggak mungkin dia sampai minta diurusin anaknya selama itu. Sekalipun istrinya wanita karir, nggak mungkin kan sampai full time begitu?”
Juniar mengangguk mangut-manut. Amarahnya perlahan mereda, “Well, kalau dia duda sih nggak masalah. Asalkan dia nggak punya istri saja. Kamu harusnya peka, kenapa sebabnya banyak pasutri yang nyewa pembantu atau baby sitter ibu-ibu yang sudah berumur ataupun wanita yang sudah bersuami. Selain karena lebih pengalaman―ya, kamu ngerti sendiri kan alasannya kenapa.”
“Iya, iya, Jun. Aku ngerti. Duh, kamu ngomelnya kalah-kalah Mama.”
“Terus?” Juniar lantas kembali bertanya, ia sudah bisa memulai sesi makannya setelah tadi mendadak terserang serangan jantung akibat ucapan Ara.
“Apanya?” tanya Ara galak, dengan tangan yang mengaduk soto di hadapannya.
“Ya, kerjaanmu, lah. Kenapa pakai acara magang segala? Cuma ngurusin bocah doang. Lagian kamu kenapa capek-capek kerja, sih? Fokus skripsian saja, kenapa? Bentar lagi lulus juga, masa depanmu sudah diatur sempurna. Kamu tinggal jalanin saja.”
Ara memutar bola matanya. Lagi-lagi Juniar mengeluarkan rentetan kalimat yang panjangnya kurang lebih sama dengan rel kereta api dan pasokan kata yang seolah tidak ada habisnya di kepala pemuda tersebut.
“Jun, keluargaku nggak se-sultan keluargamu. Kamu dikasih uang bulanan, masih bisa beli apapun yang kamu mau. Lha, aku? Cuma buat ongkos hidup sama kebutuhan. Apa yang ku mau belum bisa ku beli. Aku juga mau lagi beli barang-barang yang aku suka.”
“Terus dulu kenapa nggak lanjutin kontrak?”
Ara mengedikkan bahu, “Satu tahun, Jun. Sedangkan aku nggak tahu lagi, selepas lulus, mau tetap di Jogja atau ke luar kota. Kamu tau sendiri, Mama penginnya aku lanjut S2.”
Juniar akhirnya mengangguk paham.
“Ah, iya. Kenapa aku magang? Karena dia nggak percaya sama aku. Soalnya tampangku kan tidak meyakinkan, ditambah aku nggak kelihatan punya pengalaman yang mumpuni. Makanya aku nawarin magang dulu. Kalau cocok, lanjut.”
“Asalkan kamu hati-hati saja, Ra.”
Ara mengernyit, “Hati-hati kenapa lagi? Pikiranmu jelek banget sama aku dari tadi, heran.”
“Bukan begitu,” Juniar berucap sabar. Tampak serius dengan aura-aura pria dewasa dan Ara tebak pasti ucapannya setelah ini tak jauh dari petuah-petuah yang acapkali diberikan Juniar padanya. Mendadak Ara takut, kendati ia memasang atensi dan mendengarkan baik-baik.
“Aku percaya kamu bisa jaga diri dengan baik, Ra,” ucap Juniar lembut, “aku selalu percaya dan selalu dukung kamu. Kamu tau sendiri kita kenal nggak cuma satu-dua tahun. Tapi, aku hanya bisa nasihati, kamu hati-hati untuk jaga hati.”
“Hah? Memangnya aku ngelamar kerja buat cari jodoh? Ngaco kamu, Jun.”
Juniar masih tampak sabar. Ia menyesap sesaat es teh guna melanjutkan ucapannya, “Ya hati-hati saja. Nggak menutup kemungkinan kalau kamu atau pun dia yang bisa saja jatuh hati duluan.”
Ara justru menatap jenaka. Ia tiba-tiba saja bergidik ngeri, “Jun, tau nggak? Mendadak aku jadi ngerasa kayak tokoh-tokoh cewek di novel-novel yang ku baca.”
Pletak!
Ara mengaduh saat Juniar tanpa belas kasihan menjitak kepalanya, “Aku lagi serius, Ara. Malahan bercanda.”
Ara cengengesan, “Habisnya, dibandingin serius, kamu justru kelihatan kayak cowok yang cemburu dan minta aku nggak jelalatan.”
Sesaat di sana, Ara mendadak merutuki ucapannya. Manakala senyum yang menampilkan lesung pipit kecil di sudut bibir Juniar perlahan lenyap, dan ekspresinya yang berubah secara drastis. Bahkan senyum dan tatapannya yang berubah sendu, Ara menggigit bibir bawah canggung.
“Jun, aku nggak bermaksud―”
“Mana aku berani, Ra,” sahut Juniar, tak memberikan Ara kesempatan berbicara. Pemuda itu menunduk sejenak untuk mengaduk asal bakso yang tadi dipesannya.
Pun di sekon setelahnya, Juniar mengangkat kepalanya. Menatap Ara dengan senyum yang terlihat dipaksakan di sana, “Mana berani aku cemburu sama kamu. Sekalipun aku ingin sekali dari dulu―bahkan sampai sekarang,” ucapnya lirih yang masih bisa tertangkap jelas di telinga Ara.
“Tapi sayangnya aku nggak bisa,” Juniar masih mempertahankan senyumannya. Memandang Ara semakin sendu, “Karena kamu tau sendiri, Ara. Aku ... nggak akan pernah bisa untuk khianatin Nava.”


 bintangsarla
bintangsarla