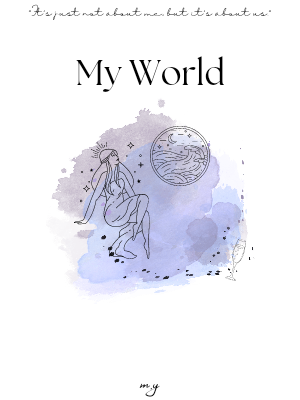“Kinna mana, Kal? Tumben nggak sama Kinna. Mama kangen, deh.”
Hanya itulah yang didengar Kalla saat kaki jenjangnya melangkah memasuki pintu utama. Masih rapi dengan tas selempang besar dan topi golf terbalik. Bekas main bersama Arniko— sahabatnya— tadi sore. Dan melihat Donna berdiri di sana, tentu senyumnya melebar. Kalla rindu setengah mati. Mamanya baru saja pulang dari Sidney berminggu-minggu. Mana tidak memberi kabar lagi. Tahu-tahu sudah berada di sini. Tentu saja Kalla kaget sekaligus senang bukan main saat tadi siang mendapat chat dari Donna kalau sudah mendarat di Jakarta.
Tapi, ternyata bukan dirinya yang pertama dicari. Malah si Kinna. Sebenarnya yang anaknya itu siapa, sih? Dirinya atau Kinna?
“Kal, Mama itu tanya, loh. Kamu ngajakin Kinna, nggak?”
Kalla merengek, memberikan kecupan kecil di pipi Donna. “Mama gimana, sih? Kok yang dicari malah Cendol! Anaknya Mama tuh aku atau dia!” dengusnya kesal, “Im really miss you, Ma! Please, don’t ask other!”
Donna hanya tertawa ringan. Balas mengecupi anak sulungnya itu. “Ya, kan, biasanya Kinna main ke sini. Suruh ke sini, Kal. Bilangin, Mama bawa oleh-oleh banyak. Ada baju, parfum, coklat, snack, camilan kesukaan dia. Semua ada.”
Kalla menghembuskan napas malas. Saking cintanya Donna pada Kinna, ya begini jadinya. Kadang anak sendiri dilupakan. Malah si Kinna yang lebih disayang. Apa saja Donna belikan untuk Kinna. Coba untuknya dan Reval. Donna mana peduli. Katanya, dia dan Reval sudah besar, bisa menghasilkan uang sendiri.
Sedangkan Kinna? Sahabat perempuannya dari jaman bahulak itu sudah dianggap sebagai anak sendiri. Donna sangat mengidamkan anak perempuan. Tapi semua anaknya laki-laki. Alhasil, sejak kehadiran Kinna di hidup Kalla, secara tidak tertulis Donna sudah mengganggapnya sebagai anak perempuan. Begitulah besarnya rasa cinta Donna pada si Cendol.
“Mama kan pas mau pergi dulu janji mau beliin Kinna coklat Aussie, Kal.”
Kalla mendumel. Mana dirinya dan Kinna di kantor tadi sedang marahan pula. Gara-gara Jordan yang mengganggu. Dan Kalla gengsi minta maaf dulu. Harus Kinna yang mengemis maaf padanya. Enak saja dia minta maaf pada si Cendol. Mana sudi harga dirinya yang tinggi.
“Kal!” Donna menghardik.
“Ck, iya, deh. Nanti aku anter ke kosnya Cendol, Ma!”
Donna tersenyum. “Terus Reval mana? Mama cari di kamar kok nggak ad—” dan yang dimaksud ternyata sejak tadi berdiri di ujung pintu. Baru pulang dari praktek rumah sakit. Dengan tangan melipat di dada. Tersenyum dari jauh menatap sang mama. “Ah, my little son. Come here, Val. Mama really... really... Miss you!”
Tapi Reval malah menyindir Kalla. “Mama nyari si Kinna terus, artinya emang pengen anak perempuan. Kenapa lo nggak segera nikah aja? Kasih Mama anak perempuan?”
Kalla benci pada Reval dan kata-katanya yang selalu menusuk. “Jadi, lo nyuruh gue nikah, Val?”
“Jangan bertanya sesuatu yang udah jelas jawabannya, Mas Kal!” suara Reval makin menjatuhkan, “putusin anak kuliahan bau kencur itu!”
Kalla bersiul-siul santai. Beberapa hari lalu, dia memang iseng memacari anak kuliahan yang ingin mendaftar magang. Sudah putus kemarin. Meski sayang, kepergok Reval duluan sewaktu ciuman di sofa. Reval yang melihatnya dendam setengah mati. Merasa jijik dan paling suci. Lalu mengusir mahasiswi itu dari rumah mereka.
Donna mengatupkan mulut kaget. “Ap—apa?! Ka—kamu pacarin bocah kuliahan, Kal? Sadar umur, dong!”
Kalla berdecak. “Anak kuliahan bukan bocah, Ma! Lagian aku udah putus sama bocah itu, Ma! Bocah itu mau porotin aku aja! Udahlah, forget it!”
Reval mendecih, mengabaikan Kalla, memilih memeluk Donna. Berusaha mendapat perhatian sang mama. “I miss you, Ma! Mama kesepian di sana?”
Donna membalas pelukan Reval. Sedikit lebih tenang. “Nggak, kok. Mama, kan, ada Thalia di sana. Jadi, Mama nggak kebosanan. Thalia itu gadis yang sangat baik. Kebetulan baru selesai S2 di Canberra. Flat-nya sebelahan sama milik Auntie Giselle.”
Kalla mengernyit. “Thalia? It seems for the first time I hear that name. Who is her?”
“Tuh, kan, kamu pasti tertarik!” Donna malah menggoda. “Thalia anak kerabatnya Auntie Giselle. Minggu depan pulang ke Jakarta. Mau temui dia? Mama udah janji ke Thalia, mau kenalkan kamu.”
“What? Kok Mama jadi bikin janji-janji seenaknya gitu, sih?” tentu saja Kalla jadi malas. Kepo bukan berarti tertarik. Kenapa Donna selalu salah mengartikan. “I don’t know who is Thalia. And I don’t interested!”
Tapi Donna tidak peduli. Tidak ada bantahan. “Mama mau kamu jemput Thalia minggu depan.”
***
“Ki, gue duluan, yak!”
“Yuhuuu! Hati-hati di jalan, ya, Beib!”
Kinna hanya geleng-geleng kepala melihat kepergian Riris. Aroma parfum mahal semerbak menguar dari tubuh temannya itu. Ditambah dandanan super berani yang mencolok dari jauh. Rok jeans separuh lutut dan tanktop seksi berwarna hitam. Belum lagi rambutnya yang di-blow. Lalu bibir berlipstik merah menyala. Hasil curian dari sisa produk yang mereka tawarkan.
Riris itu temannya sesama SPG di mall. Lebih tepatnya SPG salah satu brand make up yang sedang berjuang merangkak ke pasaran. Berani memberikan gaji yang lumayan jika produk yang dipromosikan laku keras. Bagaimana Kinna tidak tergiur? Hidupnya yang pas-pasan dan selalu diperas Sukma, juga harus menghidupi adiknya, Tarumi. Tahun depan adiknya itu mau kuliah. Sudah pasti Kinna membutuhkannya.
Bohong jika Kinna sudah keluar dari pekerjaannya sebagai SPG. Faktanya dia masih terjebak di sini. Dalam balutan seragam pink-pink ini setiap malam. Harus rela didandani super menor demi mempromosikan make up. Diam-diam membohongi Kalla. Berkata bahwa dia sudah berhenti dari pekerjaannya sebagai SPG. Padahal Kinna tidak berhenti. Hanya meminta pindah lokasi mall saja. Sialannya, malah bertemu Riris— perempuan gila setengah dajjal.
Jika Kinna adalah karyawan swasta merangkap SPG di mall. Maka, Riris berbeda. Kastanya berbanding terbalik. Riris adalah SPG merangkap simpanan Om-Om. Alias sugar baby. Tapi Kinna tidak menampik, bahwa sebenarnya nasib mereka sama saja. Adalah segelintir manusia yang diuji oleh tekanan hidup, mental dan terutama ekonomi. Hanya saja, nasib Kinna sedikit lebih beruntung. Pernah merasakan jadi sarjana dan memiliki Kalla. Sebagai malaikatnya. Sementara Riris perempuan lulusan SMK Kecantikan yang memasrahkan hidup pada jalinan keberuntungan menggaet om-om.
Kinna masih ingat perkataan Riris beberapa hari lalu.
“Ki, lo kalau didandanin cakep juga!”
“Masak, sih? Ah, nggak! Gue, kan, kayak cowok!”
“Kata siapa? Cantik gini, kok! Cuma lo belum bisa dandan bener aja! Bentar lagi juga bisa! Eh, gue tanya, deh! Lo masih butuh duit buat kuliah adek lo tahun depan, nggak?”
“Ya, iyalah, Ris! Banyak! Gue butuh banyak duitlah! Tante gue tuh sialan! Duit gue buat Rumi malah dibayarin ke rentenir! Brengsek banget, kan!”
“Capek, deh! Mending lo gabung gue aja! Banyak pelanggan Madam belum dapet partner! Santai, nggak semua buaya, kok! Mereka cuma kesepian dan butuh temen curhat aja! Bayarannya tetep gede! Dapetlah lima juta sekali jalan! Gimana?”
“Sorry, Ris! Gue masih inget Allah.”
Kinna hanya menghela napas panjang. Sebanyak apapun uang yang akan dia dapat nanti, dia masih ingat pada Sang Maha Kuasa. Dan masih mencintai dirinya sendiri. Sampai kakinya patah sekalipun, dirinya tetap tidak sudi bergabung dengan Riris.
Bola mata Kinna berputar malas. Meraih kapas di dalam pouch. Berusaha membersihkan sisa make up di mukanya dengan micelar water. Sesekali ditatapnya riasan warna-warni yang nyaris terhapus di sana. Eyeshadow yang berwarna purple, lipstik orange yang menghias bibirnya, juga blush on yang membuat pipinya semakin imut dan chubby. Diam-diam sedikit memuji. Riris benar, mungkin dia sedikit cantik. Andai saja dia pantas menjadi cantik. Tapi, siapa dirinya? Sampai pantas mendapat label begitu?
Menghela napas, Kinna cepat-cepat menghapusnya. Lalu mengganti seragamnya dengan jaket jeansnya yang kedodoran. Mulai melaju membelah padatnya malam di Jakarta. Sampai nyaris pukul setengah dua belas malam, dirinya baru memasuki gerbang kos. Menemukan mobil kebanggaan Kalla terparkir rapi di sana. Hatinya berdebar ketakutan tiba-tiba. Laki-laki itu di sini tengah malam. Sedang apa lagi?
Kinna memasuki beranda kos sambil menahan napas. Nyaris menjepit hidung. Sebisa mungkin tidak menimbulkan suara apapun dari langkahnya. Tapi terlambat, sosok jangkung itu bangkit juga dari tidurannya di bangku bambu. Kinna melangkah mundur. Panik saat Kalla melemparkan asbak dari sana.
“Apaan, sih, lo, Kal?! Lo mau bangunin temen-temen kos gue, iya? Mau cari gara-gara sama Ibu Kos? Sana pergi!”
Tapi Kalla malah tersenyum sinis. “Dari mana lo tengah malem gini?”
Kinna membeku.
“Gue tanya! Dari mana, lo, Kinnanthi!”
“Gue... gue dari...” Kinna meringis menatap sekeliling. Sangat menakutkan jika Kalla sudah memanggil dengan nama aslinya— dan bukan Cendol seperti biasa. Tamat sudah riwayatnya kalau sampai Kalla tahu dia masih bekerja sebagai SPG. Laki-laki itu akan marah besar dan akan menghancurkan semuanya. “Dari—”
Kalla menarik lengannya, mengamati bibir Kinna yang tersisa bekas lipstik di sana. Jemarinya menghapus kasar. “Apaan, sih?! Nggak pantes lo tuh pake lisptik menor segala! Nggak cocok! Sok kecakepan banget jadi cewek! Genit banget ke Jordan! Bilang, lo pasti jalan sama Jordan, kan?! Lo pikir gue nggak tahu?”
Kinna membeku kesal. Tidak tahan lagi. “Iya, gue jalan sama Jordan. Terus masalah lo apa? Udah sana pergi, jangan ganggu gue! Capek mau tidur!” dan dibukanya pintu kos, lalu melangkah masuk, nyaris membantingnya kalau Kalla tidak menahan. “Apaan, sih?! Udah, urusin sendiri idup lo! Nggak usah recokin idup gue!”
Kalla menyusulnya memasuki pintu kos. Mengikuti Kinna yang tengah mengobrak-abrik almari baju. Mencari sepasang piyama. Napasnya meninggi saat Kalla sudah berada di belakangnya. “Gue udah bilang, pergi! Mau gue jalan sama siapa aja itu bukan urusan lo! Gue juga nggak peduli lo mau lakuin apa aja!”
“Kok lo gitu, sih, Ki? Gue bilang gini, karena gue peduli!” Kalla menghela napas melihat setitik air menggenang di sudut mata Kinna. “What are you doin out there in the middle night?”
“I can do what everything I want! So, please!”
“Oke, sorry,” Kalla meringis. Mungkin dia memang keterlaluan. Berbalik sebentar ke dalam mobilnya, diambilnya beberapa paperbag titipan dari Donna. “Mom told me to bring you this— Gue cuma mau nganter oleh-oleh dari Mama. Mama pulang dari Aussie tadi siang. Dan dia langsung nyari lo. Bawain banyak coklat kesukaan lo. Gue udah di sini dari maghrib. Hampir ketiduran. Tapi, lo nggak pulang-pulang. Gue khawatir, Ki.”
Kinna hanya menunduk. Menatap tidak enak pada empat buah paperbag di hadapannya. Dari kilau kertasnya pasti sangat mahal. Donna memang sangat menyayanginya seperti anak sendiri. Itu yang membuatnya benar-benar merasa berhutang budi. Donna yang sering membelikannya banyak barang, yang bahkan memberinya pekerjaan di perusahaan. Semua paksaan Donna. Dan Kinna tidak tahu bagaimana cara membalas ini semua. Perlahan dipeluknya paperbag itu penuh sesal. “Gu... Gue nggak tahu... Sorry... and thanks! Besok gue ke rumah temuin Tante Donna.”
“Oke. Let’s forget about it,” dengusan panjang Kalla mengakhiri perdebatan mereka malam itu, segera melangkah mundur menuju pintu kos.
Tapi, diam-diam Kalla masih di sana. Berdiri kosong di sudut pintu kos Kinna. Menatap pada sebuah pigura di atas meja. Tempat foto mereka yang sudah usang dulu. Berbalutkan seragam basket jaman SMA. Saling merangkul dengan cengiran bodoh. Di sampingnya terdapat pigura foto Kinna dan keluarganya. Papa Kinna dan tantenya mungkin. Kalla hanya ingat sebatas itu. Karena Kinna sangat tertutup tentang keluarganya.
“Gue yakin, kalau keluarga lo tahu, lo pulang malem gini, mereka juga pasti khawatir. Jadi, please.”
Kinna berani bersumpah jika saat ini dia ingin tertawa dalam hatinya. Keluarganya peduli? Sukma dan Dimas— papanya yang suka berhutang. Justru mereka malah akan senang melihatnya bekerja banting tulang begini dan menghasilkan banyak uang.
Sebelum benar-benar pergi, diliriknya Kinna sekali lagi. “Gue kayak gini karena peduli sama lo. Saat keluarga lo nggak ada di sini, biarin gue yang ngambil alih tugas mereka buat jagain lo. Gue sayang sama lo, Ki. Lo itu sahabat gue.”
Nyaris saja Kinna menitikkan air matanya lagi. Kalla tidak pernah serius. Sebagian besar hidupnya hanya digunakan untuk menabur omong kosong. Tapi, mendengarnya berbicara seserius itu, selembut itu, membuat hatinya menjadi lemah. Apa tadi? Kalla menyayanginya, karena dia sahabatnya?
Tapi, gue sayang sama lo lebih dari sahabat. Gimana, Kal? Kinna menghapus embun di matanya. Dan gue nggak bisa selamanya bergantung sama lo.
***
Suara ketukan papan billiard beradu kencang di dalam ruangan itu. Melihat bola sasarannya meleset, Kalla meletakkan kembali cue yang masih berada di tangannya. Kalla menghela napas panjang. Malas mengingat pertengkarannya dengan Kinna kemarin. Ditambah pagi ini dirinya mendapati Kinna jalan berdua dengan Jordan di sekitaran lobby kantor.
“You look so pitty, dude.”
Sambil tertawa, Niko— sahabatnya— melangkah masuk. Diiringi Dipta dan Leon. Menerobos ruang kerja milik Kalla, mengambil alih tongkat cue yang menganggur di ujung papan. Lalu melancarkan aksi menerjang beberapa bola yang bertebaran di sana. Lalu shoot, masuk dengan mudah.
Tawa Niko puas sekali. Mengirim high five pada Leon Ketiganya senang main ke sini saat jam istirahat. Karena ruang kerja milik Kalla paling luas. Ditambah ada papan billiar rahasia yang diletakkan di sana. Wih, Niko suka sekali harta karun semacam itu.
“Asisten lo ke mana?” tanya Dipta, berputar menatap divisi yang sepi di depannya.
Kalla mengernyit, meraih beberapa kaleng soda dari pantry. Lalu melemparnya secara bergantian pada mereka bertiga. “Asisten siapa, sih?”
“Heru, bambang! Heru!” ralat Niko cepat.
Kalla nyengir menatap Dipta dan Niko yang memberi julukan seenaknya pada Heru. Meski memang benar, sih. Heru itu lebih mirip asistennya ketimbang bawahannya. Karena kemana-mana dirinya pasti dikawal Heru. “Tahu, deh, tuh anak lagi menebar gosip di mana.”
Leon menambahi, “Tadi, sih, gue sama Dipta mergokin dia makan di kantin bawah.”
Dipta mengangguk serius. “Iya, tapi tumben—” Kalla dan Niko langsung melirik waspada, “tumben hari ini Heru nggak pesen lotek. Biasanya dia pesen lotek.”
Dan emosi Kalla beserta Niko langsung naik beberapa oktaf.
Niko melotot pada Dipta. Kalau mode lola Dipta sudah kumat. Beginilah jadinya, semua ikut pusing. “Anjir, terus penting bagi gue si Heru makan apa?”
Dipta masih menampilkan muka seriusnya. Tidak terima penghinaan Niko. “Tapi sejauh pengamatan gue, ya, Nik. Tiap hari dia mesen lotek. Baru hari ini gue liat dia mesen gado-gado.”
Kalla merangkul bahu Dipta. Nyaris mencekik menggunakan otot-ototnya yang bermunculan. “Dip, lo udah pernah diceburin ke rawa-rawa belum? Kalau belum, gih.”
Dipta nyengir polos. “Belum. Lo bertiga kan pernahnya nyeburin gue ke kolam.”
“Ye, malah dijaweb lagi! Bener-bener, ya, lo, Dip!” Niko gemas, ingin meremasnya. “Dah, lo berdua sama Eyon nyebur bareng sana.”
Leon mencibir tidak suka. “Apaan gue segala! By the way, tadi gue lihat Cendol makan bareng Jordan!”
Niko merangkul bahu Kalla, tertawa mengejek. “Ternyata bener gosip dari Heru, Jordan lagi pdkt-in Cendol. Ck, ada juga yang mau sama Cendol, Kal. Gue kira tuh anak bakal jadi perawan tua. Ya, siapa, sih, yang mau ama cewek jadi-jadian macem Cendol?” dan tawanya mengencang. “Paling lo doang, Kal, yang betah sahabatan ama Cendol bertahun-tahun. Selain lo, siapa cowok yang mau deketin Cendol?”
“Gengs,” usul Leon, “kalau sampe Cendol laku, ayo kita rayain!”
“Rayain atau ngeledek nih ceritanya! Buahaha!” tawa Niko paling kencang dari yang lain.
Kalla hanya menghela napas panjang. Kadang sahabat-sahabatnya sangat over jika sudah meledek Kinna. Maksud hati bercanda, tapi kadang Kalla kasihan juga.
***
Hari yang diajukan Donna datang juga. Sabtu ini weekend, alias hari libur. Kalla ingin bersantai. Tidak ingin terlibat apapun dengan ide gila mamanya. Tapi, Donna tetaplah mama pemaksa pada umumnya. Dirinya tidak dibiarkan tenang hari ini. Pagi-pagi sudah diseret untuk ke bandara menjemput si Thalia-Thalia itu.
“Ma, please, I don’t want to get involved in anything with this girl. Thalia or whatever her name! I don’t care!”
“Ya, tapi kamu coba dulu! Mama nggak enak udah janji, Kal! Minimal kamu kenalan dulu sama Thalia! Siapa tahu bisa jadi temen?”
Reval menyusul dari ruang tamu. Sudah rapi dengan tas jinjingnya dan jas laboratorium tersampir di pundak. Seperti biasa, bersiap ke rumah sakit. Hanya bisa tersenyum tipis. “Mam, Mas Kal, I have to go. Sorry, I can’t join you all this morning. But,” dialihkan matanya pada Kalla. “Have a good day.”
Donna mengecup kening Reval. “Sure, baby. You too. Be careful on the way.”
Selepas kepergian Reval, keadaan rumah jadi sepi. Hanya beberapa ART yang hilir mudik melintasi ruangan. Tomi— papanya— juga pergi menghadiri agenda main golf bersama klien dari Thailand. Mau tak mau Kalla bersiap juga. Malas berdebat lama-lama dengan Donna.
Satu jam kemudian di sinilah Kalla berada. Terjebak dalam mobil bersama Donna. Melintasi hiruk pikuk kemacetan Jakarta menuju Bandara Soekarno Hatta. Sesekali alunan musik punk beradu dari radio. Musik kesukaan Kinna dan dirinya tentu saja.
“Bisa nggak kamu jangan puter musik rock kayak gini. Mama itu nggak suka loh, Kal.”
“Iya, Ma. Sorry, aku ganti,” jemari Kalla terhenti saat suara Donna kembali memelas. “Ini musik kesukaannya Kinna padahal.”
“Mama tahu. Tapi, please, aduh, telinga Mama jadi sakit ini,” dan lagu pun berhenti, Donna masih mengoceh, “Thalia nggak bakal suka lagu-lagu rock kayak gini. Dia perempuan anggun, Kal. Tuturnya lemah lembut. Kamu jaga sikap, ya, depan Thalia nanti. Kalau sama Kinna mah terserah kamu. Mau salto atau jumpalitan,” kekehnya geli.
Kalla memilih bungkam. Sampai mobil berhasil masuk ke area bandara. Kalla menunggu Donna di dalam mobil. Tidak mau terjebak permainan mamanya. Sambil menunggu dinyalakannya kembali musik punk keras-keras dalam mobil. Sesekali bernyanyi sepuasnya. Kadang dirinya dan Kinna akan melakukan travelling menaiki gunung. Sesekali di jalan, mobil akan menepi sebentar. Lalu mereka stop dan bernyanyi sepuasnya. Tapi itu sudah lama. Kalla bahkan lupa kapan terakhir kali travelling dengan Kinna. Mungkin terakhir main ke Ciwidey tahun lalu. Karena belakangan ini mereka sibuk bekerja di kantor. Jadi, jarang travelling.
Saking asyiknya Kalla bernyanyi hingga tak sadar ketukan di jendela mobil. Matanya nyaris terkantuk-kantuk kalau saja Donna tidak menelpon ponselnya. Dan dia tersentak kaget, buru-buru membuka pintu mobil. Baru akan mengambil alih koper besar di tangan seorang perempuan— pasti ini Thalia— sampai Kalla sadar, dirinya telah terkesima. Pada pandangan pertama kepada perempuan itu.
“Thalia, he is Kalla. My son.”
Thalia hanya tersenyum anggun. Tipis sekali. Tapi membuatnya terlihat semakin cantik. Kalla bahkan bisa menghitung berapa jengkal senyuman yang terpatri mahal di wajah Thalia. Wangi parfum rose bercampur cendana menguar kuat dari tubuhnya. Dengan balutan long dress dan blazer hitam kasual yang membuat Thalia tampak semakin catchy. Gaya yang classy dan berkelas. Kalla hanya perlu menilai sekali, untuk langsung tahu berada di kelas mana Thalia berpijak. Thalia pasti memiliki segalanya. Tipe-tipe perempuan sempurna yang diidamkan banyak laki-laki untuk dijadikan istri. Termasuk dirinya.
Thalia kembali tersenyum sambil membenarkan clutch hitamnya. Suaranya lembut tapi tegas. “Aku Thalia.”
“Oh... Thalia, ya?” dan Kalla menertawai diri sendiri yang tampak bodoh. Jarang sekali dirinya bersikap bodoh di hadapan perempuan. Karena biasanya, merekalah yang akan tampak bodoh di hadapannya. Tapi, bertemu Thalia, semua jadi berbeda. Segera diusapkan tangannya ke jeans. Membersihkan dari kuman bekas ngupil tadi. Lalu menjabat tangan Thalia. “Gue Kalla. Sakalla Hanggra Tanubradja.”
***
Hanya butuh satu jam bagi Kalla untuk mengenal Thalia Adiswara Soeharisman. Perempuan yang berhasil menyandang gelar master itu berasal dari bidang psikologi. Lahir dan menghabiskan masa kecil di Australia. Lalu pulang ke tanah air saat SD hingga SMA, dan kembali lagi untuk berkuliah di tanah kelahirannya.
Thalia sangat menyukai dunia politik meski tidak berminat terjun di sana. Sempat bercita-cita menjadi dokter juga karena rasa tertariknya pada dunia medis. Dan obrolan mereka jadi makin nyambung berkat Reval. Karena Reval terjun di bidang medis. Jadi, Kalla punya bahan obrolan yang bisa disangkut-sangkutan. Thalia juga kelihatan tertarik mendengar kisahnya dengan Reval.
“Reval itu dari kecil pinter. Cita-citanya emang jadi dokter. Beda banget sama gue yang nggak punya cita-cita. Abangnya ini kebanyakan main dulu. Benci banget sama belajar,” kekehnya, sesekali melirik Thalia dari kegiatannya menyetir. Menemukan Thalia yang hanya tersenyum tipis. “Of course if you are doctor, you’ll be more better than my brother, right? But, don’t worry, Thal. You’re success whatever you’re now.”
Binar mata Thalia mulai tampak. “Sure. I like what I’am doing now, where I’am, and I don’t regret it.”
Awalnya dia pikir, Donna hanya akan mengenalkannya dengan perempuan-perempuan membosankan seperti yang sering dipacarinya. Kalla tahu dia salah besar sekarang. Thalia terlalu mahal hanya untuk disandingkan dengan hal semurah itu. Thalia terlalu sempurna, terlalu cerdas, berwawasan, dan berwibawa. Bahkan jago memasak.
Kalla seperti menemukan semua yang dicarinya ada pada diri Thalia. She’s the one. She is. Bisikan dalam suara hatinya terus bergejolak. Bahkan rasanya Kalla tidak perlu berpikir seribu kali untuk menjadikan Thalia sebagai pendamping hidupnya.
Dan semesta mendapati diri mereka saling jatuh cinta. Semudah itu. Hanya lewat percakapan-percakapan kecil di pagi hari. Juga tatapan redup dan menghangatkan Thalia yang membalasnya. Bersama semilir angin yang bersambut sepanjang jalan. Kalla menemukan dirinya sangat mengagumi Thalia.
Donna hanya berdeham-deham di kursi belakang. “Ehem, Mama kok jadi dikacangin gini, sih?” tatapannya bergantian menatap dua insan di hadapannya. “Kalian cepet banget akrabnya. Padahal tadi Kalla ogah-ogahan ketemu kamu, loh, Thal.”
Tentu saja Kalla melotot menahan malu. Nyaris mengumpat dari kursi setirnya. “Mama apaan, sih? Ember banget!” dengusnya, mengalihkan pada Thalia. “Nggak, Thal. Nggak usah dengerin.”
Thalia hanya tersenyum menunduk. “Nggak apa-apa, Kalla. Aku juga...” bahunya mengedik, “Sebenarnya nggak begitu nyaman dengan orang asing. Tapi, aku senang berkenalan dengan kamu.”
“Gue juga...” senyuman Kalla manis, “Seneng banget kenalan sama lo, Thal. You’re such a great person. Im lucky to meet you, Thal.”
Donna mencibir. Paham sisi buaya anaknya. Halah. Tapi ikut tersenyum juga. Jika ada seleksi pemilihan menantu-menantu idaman. Maka Thalia akan lulus tanpa tes. Karena Donna tahu betul bibit-bebet-bobotnya. Bukankah dalam menentukan menantu, yang paling penting adalah tiga poin itu? Dan Thalia memenangkan semuanya.
***
“Ki, kok tumben belakangan ini gue lihat Pak Kaleng senyum-senyum sendiri terus?”
Kinna melirik Jelita dari layar komputernya. Sesekali masih terus mengetik keyboard, tengah mengakumulasi laporan keuangan milik divisi mereka. Isinya angka-angka semua dalam worksheet excel itu. Membuat Kinna mau gila rasanya. Tidak ingin terusik sama sekali. Tapi, karena ini menyangkut Sakalla Tanubradja, tentu dia langsung menghentikan pekerjaannya.
“Si Kaleng kenapa, Je?”
Royhan dari ujung meja Jelita menambahkan. “Sebenernya hubungan lo sama Pak Kalla itu gimana?”
“Hubungan gue sama Kaleng? Gue udah bilang ribuan kali,” Kinna memutar kursinya ke arah Royhan dan Jelita. “We are best friends. From es-em-peh,” ejanya kesal. Malas mengingat kalau mereka memang saling kenal dari seragam biru putih. Itu konyol dan memalukan.
Royhan membulatkan bibir. “Tapi mata lo bicara lain, Kunthi. Do you ever love him? Alias sahabatan sama cowok sempurna macem Pak Kaleng gitu. Apa nggak pernah lo ngerasa baper, Kun?”
Kinna langsung mengalihkan muka melasnya pada Jelita yang sibuk berdeham-deham. Jelita tentu tahu semuanya. Kisah cinta one sided love-nya pada Kalla bertahun-tahun lamanya. Kinna sudah menyembunyikannya serapat mungkin. Dan berakhir ketahuan Jelita, akhirnya Kinna terpaksa membongkarnya. Bahwa benar yang dikatakan orang, persahabatan antara perempuan dan laki-laki tidak ada yang murni. Pasti salah satunya menyimpan rasa atau minimal baper. Tapi cukup Jelita saja yang tahu. Roy dan Jordan sudah cukup membuatnya sebal karena terus menerka-nerka.
“Ehem... gue anter ini dulu ke bagian anggaran, ya? Butuh persetujuan buru-buru. Kalau ada yang nyari, bilang gue ke sebelah,” memilih bangkit dari kursinya, Kinna merampas map berisi setumpuk kertas laporan hasil print out, lalu berlalu meninggalkan ruang divisi.
Tapi langkahnya terhenti saat sumber gosip itu muncul. Tengah berjalan sambil bersiul-siul riang melewatinya. Nyaris menubruk tubuh mungilnya dengan badan jangkung itu.
“Sakalla Tanubradja,” Kinna mendesis emosi. “Jalan pake mata, bisa? Badan lo itu kayak genter, ngerti?!”
Kalla malah berakting pura-pura tidak melihatnya. Mentang-mentang dirinya pendek, mungil, dan kecil. Sekarang laki-laki itu sok mengernyit. “Kayak ada yang ngomong? Siapa, ya?”
“Ish, budek ya lo?!”
Akhirnya Kalla menunduk. Tertawa puas setengah mengejek menemukan tubuh pendek Kinna di sana. “Eh, si Cendol! Ternyata ada Cendol di sini! Kok gue nggak lihat lo, sih, Ndol?!”
“Gue dari tadi di sini, sialan!”
Kalla terkekeh, menoyor gemas kepala Kinna, “Ck, Cendol... Cendol... Makanya jadi cewek yang tinggian, dong! Cebol gini, mana kelihatan coba! Nggak ada ideal-idealnya sama sekali lo, mah! Kapan lo laku, sih?”
Sontak Kinna menyipitkan mata curiga. Kalla dalam mode memanggilnya ‘Cendol’ dan menistakannya, berarti laki-laki itu telah kembali seperti semula. Padahal Kinna masih ingat jelas, beberapa hari lalu Kalla marah padanya karena dia pulang larut malam. Setelah itu mereka puasa bicara. Saling mengabaikan satu sama lain. Biasanya Kinna minta maaf lebih dulu. Tapi belakangan ini, Kinna terlalu sibuk dengan segudang deadline. Bahkan belum sempat menemui Donna. Sekarang melihat laki-laki itu tertawa puas mengejeknya, sedikit membuat Kinna lega bahwa mungkin Kalla telah memaafkannya.
“Gue kira... lo masih ngambek?”
“Hah? Masak iya gue ngambek?” Kalla terkekeh geli. “Kapan, sih, Ndol? Ah, lo mah, ngaco banget jadi orang! Gemesin, deh! By the way, pipi lo makin chubby aja, sih, kok gue baru sadar?” dan dicubitinya pipi Kinna tanpa ampun.
Kinna tentu kesal menjadi sasaran. “Jangan pegang-pegang pipi gue! Lo kira bakpau?!” Segera menjauhkan tangan Kalla dari pipinya. “Mmm, Kal, gue belum jadi ke rumah. Besok, ya, gue ketemu Tante Donna-nya? Nggak apa-apa, kan?”
Kinna semakin mengernyit karena Kalla malah kembali tersenyum-senyum, “Lagian ada apa, sih? Tumben ceria banget lo.”
“Ada, deh.”
“Idih, pasti gara-gara bocah kuliahan yang lo pacarin itu, ya?” Kinna semakin memancing. “Udah lo mainin apa aja dia? Gue kasih tahu, ya, dia itu masih kecil. Kasihan orang tuanya. Please, Kal, ngotak dikit, dong.”
“Cendol! Cendol! Kata siapa gue masih pacaran sama bocah itu? Orang gue sama bocah itu udah putus dari kapan hari! Hah, lo itu ada-ada, aja!”
“Terus sekarang siapa lagi?” Mau tak mau Kalla menarik lengan Kinna menuju salah satu bangku kosong di lorong. Rupanya semakin ceria. Penuh senyuman bahagia. Membuat Kinna semakin curiga. “Sakalla Tanubradja, gila, ya, lo? Udah mulai nggak waras?!”
Tapi suara Kalla mulai berubah serius. “Pernah nggak, sih, setelah ketemu seseorang, lo tiba-tiba ngerasa he is the one gitu, Ki?”
“Maksud lo gimana, sih, Kal? Gue nggak paham, deh.”
“Ya, kayak lo ke Jordan. First sight lo ke Jordan itu gimana, sih?” Kinna hanya menggeleng tidak paham. Kalla memeluknya gemas, “Ndol, sekarang gue setuju kalau lo sama Jordan! Setelah gue pikir-pikir, kalian berdua cocok juga! Sama-sama cupu!”
“Enak aja, Jordan nggak cupu, ya! Lagian kenapa jadi lo yang mutusin? Emang lo siapa?! Nyokap gue?”
“Ya, gue sahabat lo, lah! Gimana, sih?!” tawa Kalla mengencang mengacak rambut Kinna. “Lo butuh restu dari gue!”
Kinna semakin mengernyit. Apaan, sih? Tumben sekali Kalla membahas hal seperti ini dengannya. Beberapa tahun lalu, Kalla pernah mengatakannya. Tapi itu hanya lelucon belaka disela mereka main monopoli di beranda kos.
“Eh, Ndol, menurut lo, besok di antara kita, siapa yang bakal married duluan?”
Kinna ingat saat itu hatinya nyeri. Tapi buru-buru dijawabnya. “Ya, itu pasti gue, lah! Lagian lo nggak pernah serius sama cewek! Paling lo jadi perjaka tua! Kalau gue, sih, gue bakal nemuin Pangeran idaman gue!”
Dan Kalla tertawa puas mengejek. “Hah? Apa? Nggak salah?! Emangnya lo bakal laku? Cendol, Cendol, yakin banget, lo! Cowok aja nggak punya! Jomblo sepanjang abad! Sok-sokan mau nikah sama Pangeran! Cih, bangun, Ndol, ini udah siang!”
“Ih, ya suka-suka gue, dong! Lihat aja, gue buktiin kalau gue bakal nikah dulu!”
“Gih, buktiin!” Kalla semakin tertawa mengejek.
Suara dering ponsel yang tiba-tiba mengacaukan lamunan Kinna. Perlahan dicarinya sumber suara. Ternyata di dalam saku Kalla. Bersamaan dengan itu senyuman Kalla mengembang. Buru-buru bangkit mengangkatnya. “Halo, iya, Thal. Aku ke depan sekarang, ya. Ini aku udah selesai, kok. Wait. Ini lagi jalan.”
“Siapa, tuh?” Kinna mengernyit. Pasti mainan baru, batinnya mencelos.
“Ndol, gue pergi dulu, ya!” dikirimkan satu cubitan pada Kinna, “Dah, Ndol! Muah!”
“Hm.”
Kinna menghela napas menatap punggung Kalla yang menjauh tak sabaran menuju lift. Masih sambil tersenyum-senyum menjawab panggilan dari telpon. Diam-diam Kinna mengikutinya lewat lift belakang. Di lobby menemukan laki-laki itu masuk ke dalam sebuah jazz merah yang menghadang di depan.
Kinna hanya diam mematung saat jazz itu melaju. Mainan baru lagi. Kapan laki-laki itu sadar bahwa dirinya ada di sini? Kapan Kalla melihatnya? Sepertinya itu hanya mimpi saja. Dan diremasnya jemari perlahan. Sampai Kinna sadar ada kehangatan lain di sana. Tengah menggenggam tangannya. Sontak Kinna tersentak kaget, menemukan tubuh menjulang Jordan di sampingnya.
“Astaga, Jor, lo kayak cenayang aja! Bikin gue jantungan!”
Tapi Jordan malah tersenyum manis. Merebut map di tangan Kinna dan tertawa membaca judulnya. “Mau ke bagian anggaran, tapi jalannya sampe lobby bawah. Jauh banget, Ki.”
Kinna meringis malu, bersiap merebut map itu kembali. Jordan menahannya.
“Gue bantu. Sekalian gue mau ke anggaran. Ketemu Pak Angga.”
Akhirnya Kinna menghela napas panjang. Menyusul Jordan naik kembali ke dalam lift. Hanya hening sampai Jordan mencetus tiba-tiba.
“Ki?”
“Hmm?”
“Do you love him, right?”
Dan ditodong pertanyaan itu tentu Kinna jadi kelabakan. “Maksud lo apaan, sih, Jor? Kok ngaco!” tawanya.
“Sakalla Tanubradja. You love him... but, he don’t.” Jordan menatap Kinna yang semakin mematung, “Everybody know that’s fact. Your eyes, your behavior, and your expression can’t lie anymore. I can see it, Ki. You love him so much.”
“Ke... Kenapa lo jadi kayak Roy, yang sok tahu, sih, Jor?” melihat tatapan Jordan yang makin menajam, membuat Kinna menghela napas. “Okay, you got it.”
Jordan tersenyum puas mendengar pengakuan Kinna.
“Kalla is... someone that I can’t life without. He gave me everything, Jor. When I had nothing, he is there. Giving me friendship, family, and... of course love. Cause I love him so much, no matter what. The reason why I can still survive in this saddest world.”
“You have me, too.” Jordan bersuara lirih. “Can you replaced him with me?”
Kinna hanya tersenyum geli. Setengah bercanda. “You’re too kind.”
“But this is serious.”
“Ah, lo mah, bikin geer mulu. Mana ada cowok kayak lo tertarik ama cewek macem gue, Jor! Gue, kan, nggak menarik! Kalla juga selalu bilang gitu!” Kinna tertawa mengejek bayangannya sendiri yang terpantul dari kaca lift. Tubuhnya yang pendek dan mungil. Juga rambut bob-nya yang sedikit mengembang. “Gue nggak akan masuk tipenya. Bahkan tipe semua cowok di dunia.”
Dan Jordan menarik bahunya, lirih. “Hey, tell me. Who say that? You’re my tipe.” Kinna malah tertawa lagi. “Cause you’re pretty, what you are, Ki.”
***


 ReynBee
ReynBee