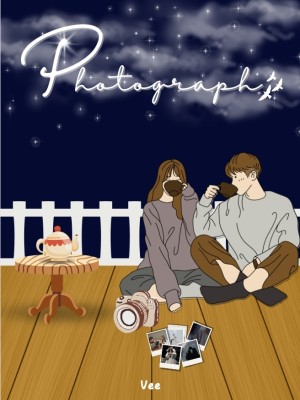T H E Y O U T H C R I M E
03
"DAUN BERGUGURAN bukan berarti tak berguna setelahnya. Begitupun anak-anak, kita harus memandang mereka dengan dua sisi."
Mahendra tengah sibuk menulis jurnal harian yang biasa dilakukannya untuk menghabiskan sisa malam. jurnal itu bukan sembarang jurnal, alih-alih catatan atau riwayat hidup, Mahendra fokus untuk menuangkan ide dan pemikirannya terkait kenakalan remaja yang acap kali disepelekan sebab orang-orang menganggap mereka itu tak bisa dimengerti dan belum paham bagaimana dunia berjalan. Kenakalan itupun tak pernah berkurang jumlahnya dikarenakan mereka berlindung di balik sebutan 'anak-anak'. Selain itu, dia juga menyelipkan beberapa kisah yang ditemukannya selama mengajar di SMANJA.
Bullying, kekerasan, pemerkosaan, pelecehan seksual, popularitas dan tindak kriminal lain. Semua itu mengancam garis kehidupan anak-anak yang menginjak remaja, di mana kurangnya pengawasan dari orang tua akan memudahkan mereka untuk terjerumus dalam jurang tak berujung. Jika tak disikapi secara cepat dan tanggap, remaja bisa menggeser kedudukan kasus orang dewasa di era modern ini dan menimbulkan korban jiwa.
"Hukuman perlu diubah dengan bimbingan karakter … karakter …." gumam Mahendra menggerakkan pena hitamnya hingga tetes tinta terakhir. Habis. Meski dia sudah sering menulis jurnal, jari-jarinya tetap terasa kaku dan berat. Mengalihkan diri dari kebosanan, Mahendra membuka laptop dan mencari berita-berita menarik.
Mahendra terkejut ketika mendapati ada panggilan masuk.
"MAHENDRA!"
"Ya! Halo?"
"INI IBU! KAMU MASIH INGAT UNTUK KIRIM UANG TRANSFERANNYA KAN?!"
"Ibu! Kalau bicara jangan keras-keras begitu! Siap, nanti Mahendra kirim!"
Ponsel kembali bergetar. Mahendra kembali bangkit dari tidurnya dan mengangkat panggilan.
"PAK MAHENDRA!"
"Halo! Dengan siapa dan di mana?" Karena disapa secara cepat dan tiba-tiba tanpa salam pembuka, Mahendra sedikit keceplosan.
Panggilan telepon bersuara wanita itu lantas menjawab. "Dengan Lucy dari Lebak Bulus!"
"Ada apa Bu–"
"Saya protes terkait nilai bahasa Indonesia! Anak saya di kelas 11-A!"
Mahendra terperangah sejenak dan menatap berkas rekapan nilai Bahasa Indonesia kelas 11-A. Dia ingat bahwa diantara tiga puluh siswa itu, satu diantaranya mendapat nilai rendah. Tentu saja bukan tanpa alasan, Mahendra pun telah menggandeng jawabannya.
"Perkenalkan saya Mahendra, wali kelas 11-A. Sepertinya Anda orang tua siswa? Mari bicara baik-baik."
"Saya Lucy, orang tua dari Gio. Setahu saya, Anak saya sudah berusaha membuat tugas dengan baik tetapi malah mendapat nilai dibawah seratus! Kenapa Anda tega sekali memberikan nilai sekecil itu?!"
"Saya tega? Mohon Anda tenang dulu. Penilaian saya bukan semata palsu tetapi sesuai dengan fakta di lapangan. Anak Anda, Gio memang mengerjakan tugas dengan baik tetapi caranya bersikap di kelas sangat kurang."
"Bukankah nilai itu hanya mencakup kelengkapan tugas-tugas sekolah? Mengapa karakter dan sikap juga termasuk?"
"Setiap guru memiliki penilaian yang berbeda, begitupun saya. Saya selalu memprioritaskan karakter siswa-siswi dibandingkan nilai tinggi atau rendah yang mereka dapat. Apalagi nilai itu hanya sebagai acuan sementara agar anak Anda dan Anda sebagai orang tua juga turut berbenah."
"Saya paham maksud Bapak tetapi saya kurang mengerti. Mari saya buktikan bahwa anak saya itu pintar dan rajin. Silakan catat alamat rumah ini …."
Zaman berubah, pola pikir manusia juga ikut berubah. Dahulu, orang tua memberikan pengawasan penuh terhadap anak-anaknya dan sekolah diutamakan menjadi tempat membina moral dan perilaku. Jika anak-anak di sekolah berperilaku buruk dengan nilai akademik yang kecil, orang tua tidak akan langsung menyalahkan pihak sekolah. Tentu saja mereka akan menginterogasi anak terlebih dahulu untuk mencari tahu sebab akibat mengapa nilai yang didapat begitu kecil? Orang tua akan menggunakan kekerasan agar si anak tidak bisa berbohong. Karenanya anak akan merasa bersalah lantas mencoba berubah menjadi lebih baik.
Sekarang, kalau melirik satu tugas si anak dengan perolehan nilai kecil langsung menyulut emosi orang tua. Mereka buru-buru menghubungi pihak sekolah dan berkeluh kesah dengan nilai tersebut, mencari-cari alasan agar si anak mendapat nilai tinggi. Pernyataan fakta dari sekolah seolah tak berguna lagi sebab para orang tua pun memiliki seribu alasan lain. Perolehan nilai kecil atau besar itu disesuaikan oleh seberapa baik si anak dalam membuat dan mengumpulkan tugas tepat waktu, di sini sekolah telah berkontribusi penuh dengan memberi hukuman serta pembinaan. Tetap saja, anak-anak tidak mau berubah. Dan orang tua yang biasanya mendukung pihak sekolah kini seolah membela si anak.
Rumah dengan pintu gerbang raksasa menjadi pemandangan pertama yang dilihat Mahendra. Warnanya hitam legam dan memantulkan cahaya di bawah sinar matahari, meninggalkan kesan elegan. Tanaman hias dan pepohonan besar tumbuh di area kebun. Beberapa pembantu tampak menyirami bunga mawar dan anggrek cattleya, kebetulan cuaca sedang bagus-bagusnya maka kebun itu terlihat cantik. Namun, Mahendra tidak ada waktu untuk melihat-lihat.
"Halo, saya ingin bertemu dengan Ibu Lucy."
Seorang wanita berambut gimbal buru-buru meletakkan sapu. "Silakan masuk, Pak. Mari saya antar."
Bukan orang kaya namanya kalau rumah tidak layak huni, setidaknya harus berupa istana. Mahendra menyusuri lorong panjang yang menghubungkan antara kamar-kamar. Seorang wanita berambut hitam setengah ubanan duduk tegap di sofa. Ia tampak menunggu kedatangan seseorang yang kini akan segera datang.
"Halo, Pak Mahendra. Apa Anda ingin kopi atau teh?" Ibu Lucy meletakkan secangkir teh miliknya yang tersisa setengah seraya tersenyum.
"Terima kasih, Bu. Tidak perlu repot-repot," ucap Mahendra sambil mencari posisi duduk ternyaman. Ruang tamu itu disesaki dengan beberapa piala dan pigura foto yang berisi potret seorang laki-laki diapit bersama orang tua dengan menggenggam medali perunggu. Ada juga koleksi buku-buku kimia dan fisika yang terpajang di rak buku kecil, menandakan bahwa keluarga itu memiliki kegemaran terhadap ilmu alam dan sains.
"Anak Anda meraih banyak penghargaan, aktif di bidang sains. Bahkan sempat mewakili OSN ketika SMP ya?"
Ibu Lucy melengkungkan bibir. "Ah, benar. Anak saya memang suka menggali potensi dirinya, tidak selalu berkutat dengan pelajaran di sekolah. Terus belajar meski di rumah. Nah dengan semua ini, apa Bapak puas? Anak saya pintar dan rajin 'kan?"
Mahendra merapatkan bibirnya seraya menekan pulpen, menulis sesuatu di jurnal rekapan nilai kelas 11-A. Dia menyodorkan jurnal itu dan menunjukkan nilai dari tiga puluh siswa.
"Besar atau kecil nilainya, saya tidak mempermasalahkan itu. Tetapi saya fokus untuk menekankan karakter pada tiap siswa. Gio, meski pintar dan rajin seperti yang Anda katakan tadi tidak bisa mengubah nilai yang sudah tertulis di sini."
Mendadak raut wajah Ibu Lucy murung, tatapannya dingin. Jelas sekali dia kecewa.
"Omong-omong apa Ibu bisa menjelaskan secara rinci aktivitas Gio dari pagi hingga menjelang malam?"
Ibu Lucy kembali sumringah dan menarik napasnya sesekali. "Hari Senin sampai Sabtu, sebelum matahari terbit, Gio berganti pakaian dan pergi ke sekolah. Dia tidak sarapan, lebih suka makan di kantin. Sepulang dari sana, istirahat sebentar diselingi dengan makan siang. Gio kembali mengganti pakaian dan menyiapkan alat tulis. Pukul tiga, saya mengantarnya pergi ke tempat bimbel. Dua jam setelahnya, saya mengantar Gio ke lapangan kota untuk latihan futsal. Usai mandi dan makan malam, Gio belajar mandiri dan menggunakan sisa malam untuk bermain ponsel. Begitu,"
"Sangat padat … bagaimana dengan hari Minggu?"
"Di hari itu porsi istirahat Gio lebih banyak di rumah jadi bisa lebih leluasa. Namun, tetap saja dia menunaikan kewajibannya untuk belajar dengan mendatangkan guru privat."
Mahendra menopang dagu. "Apa anak Anda tidak merasa stres?"
"Tidak, justru dia senang. Saya tidak memaksa Gio untuk mengikuti semua kegiatan itu, murni dari keinginannya sendiri. Perlu diketahui, sekarang anak-anak SMA jadi lebih sibuk untuk meraih nilai tinggi demi melanjutkan kuliah di universitas ternama. Tentu saja saya pun tak ingin menyia-nyiakan waktu untuk Gio," jelas Ibu Lucy dengan mata berkaca-kaca dan memandang jam dinding.
"Nilai memang adalah prioritas utama bagi seluruh orang tua tetapi bagaimana dengan sikap anak Anda?" Mahendra melontarkan pertanyaan sengit.
"Jujur, meski Gio pintar di akademik dan beberapa kali menjuarai kompetisi di bidang non-akademik, sikap dia memang banyak berubah. Lebih berani dan mengendepankan ego untuk meraih sesuatu. Tetap saja, dia itu pintar dan saya hanya menginginkan nilai tertinggi di raportnya nanti. Itu saja." Ibu Lucy menekan perkataan terakhirnya, tanda bahwa ia tak ingin disesaki pertanyaan lagi.
"Jadi Anda tidak mempermasalahkan itu?"
"Tidak. Namanya juga anak-anak, itu hal biasa bukan?"
Matahari telah menyentuh area kepala, pukul dua belas siang. Mahendra mencatat poin-poin penting yang telah didapatkannya hari ini sebagai referensi. Sebelum melangkah keluar, Mahendra mengingatkan pada Ibu Lucy agar selalu menjalin komunikasi bersama si anak dan jangan cepat menyalahkan pihak sekolah apabila merasa nilai tugas ataupun raport rendah.


 shadowalker15
shadowalker15