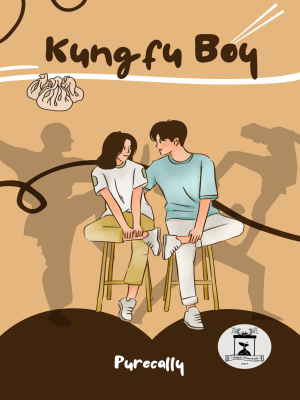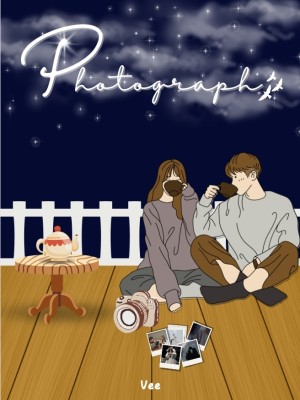T H E Y O U T H C R I M E
02
Juli 2018, Jakarta Selatan.
"SEKARANG SARAPANKU nasi kuning saja, persediaan mie instan juga sudah habis." Mahendra mengambil dompet yang terselip dalam tas hitam dan tidak lupa memesan ojek online.
Selama terduduk di belakang mas-mas berkumis yang mengendarai motor dengan kecepatan sedang, Mahendra mengetatkan jaketnya, menahan rasa kantuk yang menyerang tiap kali angin malam menampar pipi dan rambutnya. Lalu memandangi kelap-kelip lampu jalanan beraneka warna yang menyilaukan mata. Mahendra membuka bungkusan permen kecokelatan yang selalu dibawanya dalam saku baju. Sayang sekali, permen itu ialah satu-satunya persediaan anti kantuknya saat ini. Kau pasti sudah tahu lebih dulu tentang bungkusan permen bergambar biji kopi. Namanya apa? Tulis di kolom komentar.
"Nasi kuning satu, jangan lupa sambal yang banyak!" celetuk Mahendra saat sepasang kakinya menapaki trotoar dengan lubang menganga, di situlah penjual nasi favoritnya berjualan setiap pagi.
Sang penjual nasi kuning, Nenek Mei, ialah legenda kuliner yang menjadikan jalan perempatan di dekat area SMANJA sebagai markas jualannya, tepat sebelum jalan-jalan umum diaspal hitam dan sekolah megah nan terfavorit itu selesai dibangun. Nenek Mei selalu menjadi lokasi persinggahan bagi para mahkluk pagi untuk sekadar membeli sebungkus nasi kuning atau makan langsung di tempat dengan ditemani para kucing-kucing oranye yang menunggu sesuap nasi. Pekerja kantor dan pegawai negeri rata-rata mendominasi pembeli Nenek Mei yang sudah berkelana ke tengah jalan untuk menunaikan tugas tepat sebelum matahari menampakkan diri.
Makanan yang disajikan pun tidak terlalu berbeda dengan penjual lain, tetapi sambal matah buatannya telah menjadi ikon tersendiri. Sambal yang dibuat dari campuran bawang merah, cabai, garam, terasi dan sedikit minyak goreng. Meski bawang merah kerap disangka-sangka sebagai tokoh jahat penuh emosi pada dongeng umum anak-anak di era modern ini tetapi emosi itulah yang menguatkan rasa dan aroma dari bawang merah, tidak sekadar berarti buruk tetapi ada nilai tersembunyi.
Meskipun sang legenda nasi kuning itu sudah menua, pipi berkerut seperti kayu jati dan tidak mampu berdiri lama-lama, tetapi selama dia semangat bangun pagi dengan tangan yang bergerak dinamis mengaduk-aduk sambal dan nasi--terkadang emosi juga dapat diaduk bersamanya--usahanya tetap akan dikenang sampai ke generasi selanjutnya.
"Pak Martinus tumben sudah ke sekolah pagi-pagi buta begini." Mahendra mengunyah bulir nasi seraya memandang seberang gerbang sekolah.
"Ah, kau tidak tahu ya? Beliau dan anak tunggalnya terkenal rajin datang ke sekolah sebelum mentari menyapa."
"Saya baru-baru ini mendaftar sebagai guru honorer di SMANJA. Wajar tidak tahu."
"Oh? Apa kau sudah dengar tentang gosip yang beredar di sekitaran sekolah?"
Nenek Mei melontarkan pertanyaan yang dibalas gelengan kepala Mahendra.
"Saya tidak suka bergosip."
"Ah, setidaknya kau selalu mendengar gosip anak-anak meski kau laki-laki. Kau tahu Aksan? Dengar-dengar dia sudah punya banyak pacar. Pagi mengantar wanita berambut pirang, siang mengantar wanita berkacamata dan malam membawa wanita berbadan gemuk. Bayangkan, tiga wanita!"
"Ya, Nenek tidak perlu terkejut seperti itu. Masa SMA penuh dengan kisah cinta 'kan? Maklum."
"Tapi bagi nenek itu bukan kisah cinta biasa. Sepertinya … mereka bercinta sambil menjalankan bisnis."
"Maksud–" Mahendra menyudahi pembicaraannya ketika Nenek Mei tengah sibuk membungkus pesanan dan langit sudah mulai menampakkan garis-garis kemerahan. Pagi telah tiba.
"Anda wali kelas 11-A? Mari ikut saya," seorang perempuan dengan name--tag bertuliskan 'Fransisca', wakil kepala sekolah membawa beberapa berkas dan bertugas memberi pengarahan.
Mahendra mengenakan name--tag yang sudah disediakan untuknya seraya melepas jaketnya. Di luar, anak-anak tengah sibuk berbaris menunggu arahan dari pengeras suara untuk melaksanakan upacara bendera di lapangan basket. Mereka segera mengambil posisi masing-masing, tampak tertib dan rapi tanpa perlu disuruh. Namun, para guru hanya sedikit kelihatan batang hidungnya. Maka anak-anak harus menunggu sepuluh menit. Ada sedikit rasa iba ketika Mahendra memandangi barisan tertib itu.
"Sebaiknya para guru juga dibuatkan aturan untuk hadir lebih cepat di hari Senin, tidak hanya para siswa. Bukankah guru harus memberi contoh yang baik?"
Fransisca mengatur posisi kacamata. "Ya, itu benar. Sayangnya tidak ada aturan seperti itu di sekolah ini. Mohon dimaklumi."
Upacara bendera berlangsung lancar dan khidmat. Ini adalah hari pertama di bulan Juli, bulan penuh dengan persiapan menghadapi semester ganjil. Anak-anak tentu akan meningkatkan nilainya selama 6 bulan ini sebelum mendekati detik-detik ujian nasional. Kedengarannya mengerikan tetapi mereka tidak perlu risau. Setelah bendera berkibar di langit membiru, seperti biasa kepala sekolah memberikan sambutannya. Di lanjutkan dengan penyerahan hadiah kepada siswa-siswi berprestasi yang sempat mengikuti lomba.
Anak-anak kembali memasuki ruang kelas dan bersiap mengikuti pelajaran. Sebelum Mahendra menginjakkan kaki di kelas 11-A, terlebih dahulu dia mendengar gosip dan rumor yang beredar tentang kelas itu. Anak-anak yang energik sekaligus aktif ketika jam kosong tiba. Namun, ketika guru tiba mereka akan terlihat pasif. Gosip tetaplah gosip. Bisa benar, bisa saja salah.
"Berdiri!"
Anak-anak memberikan hormat dan salam kemudian kembali duduk. Mahendra meletakkan jurnal kehadiran di meja dan mulai mengecek nama-nama yang ada di kelas 11-A. Total siswa berjumlah 30, lebih sedikit dibanding kelas lain. Di sini mayoritas dihuni oleh anak guru dan anak-anak dengan nilai tinggi. Sebagai guru baru, tentu Mahendra melakukan pengenalan diri.
"Anak-anak, perkenalkan nama Bapak Mahendra Wicaksana. Kalian bisa panggil Bapak Hendra atau Bapak saja. Senyaman kalian."
Mahendra berdiri, mengambil sebuah spidol hitam dan mulai menulis judul materi Bahasa Indonesia. "Hari ini sebagai pertemuan awal, kita akan mempelajari teks cerpen."
Di bangku depan dan tengah, anak-anak tampak fokus memerhatikan penjelasan dan mencatat jika ada hal penting. Sementara di bangku belakang, terlihat beberapa siswa lelaki duduk seenaknya sambil mengobrol santai. Ribut. Obrolan mereka yang lucu akhirnya mengundang siswa lain ikut tertawa terbahak-bahak. Entah apa yang dibahas tetapi itu sangat mengganggu ketenangan kelas.
Daripada memarahi atau menegur, Mahendra lebih senang memberikan kesempatan bertanya pada anak-anak. "Apa ada pertanyaan terkait materi cerpen?"
"Tidak–"
"Tidak ada!" celetuk lelaki berambut cepak yang duduk di bangku paling belakang. Dia duduk sendiri. Tetapi para gadis terus menatap mata hitam lelaki setinggi 172 senti itu. Bukan karena dia pintar tetapi pesona ketampanannya yang dingin, kelam, dan tajam dibanding laki-laki lain membuatnya berbeda.
Aksan, ketahuilah bahwa dia anak dari kepala sekolah, Martinus. Sebagai penyandang Ten Angels posisi pertama, dia jadi pusat perhatian tiap hari. Sudah banyak gadis yang menawarkan hati tulus untuknya tetapi Aksan sudah memiliki hati sendiri. Tidak sedikit pula yang membenci dirinya tetapi itu tidak masalah.
"Kalau tidak ada, maka Bapak yang akan bertanya. Mengapa cerpen itu harus ada?"
Hening. Tiada yang mengangkat tangan. Beberapa ada yang ingin mencoba tapi ditahan. Mahendra mengelus dada. Beginikah potensi siswa SMA sekarang? Mental mereka masih labil dan tidak menunjukkan sifat dewasa?
"Aksan silakan maju." Mahendra melirik ke arah lelaki yang masih berkutat dengan obrolan.
Aksan berjalan tanpa malu-malu sambil tersenyum tipis. Mahendra menggenggam pundak anak itu seraya menunggu jawaban.
"Karena … cerpen itu sebagai komunikasi untuk dia yang terkasih … tanpa perlu biacara langsung dia pun tetap mengerti bagaimana imajinasiku saat ini …. " Aksan memutar-mutar kepalanya untuk menghasilkan kata-kata mutiara nan bijak bernada romansa.
"Jawabanmu ngawur. Tapi intinya sudah benar. Tepuk tangan!"
Mahendra meninggalkan kelas 11-A setelah jam istirahat tiba. Energinya sedikit terkuras mengatur keributan di kelas. Dia berjalan menuju ruang guru dan membuka bekal makan siang. Alasan dia tak ingin membeli makanan di kantin sebab tergolong mahal apalagi guru honorer tak mendapat jatah makan gratis seperti guru tetap. Perbedaan kasta yang amat terlihat. Sebentar lagi dia akan mengajar di kelas lain.
Penomoran kelas di tiap sekolah diikuti dengan angka ataupun huruf. Biasanya ini dilakukan untuk memberikan tingkat pada kelas yang sama. Di SMANJA sendiri, kelas dengan pemberian A adalah kelas yang paling disorot oleh para guru. 10-A, 11-A, dan 12-A. Pokoknya citra sebagai kelas tertinggi itu dituntut untuk menjadi yang paling terbaik dari kelas lain. Maka jangan heran di kelas ini anak-anak guru biasa ditempatkan agar terlihat menonjol. Apalagi rata-rata siswa yang berada di kelas ini memiliki nilai raport tertinggi semasa SMP.
Kadang nilai tinggi tidak sebanding dengan moral dan perilaku siswa. Sekalipun pihak sekolah menggalakkan pendidikan karakter, tetap saja nilai masih yang paling diutamakan. Begitulah sedikit kenyataan yang dilihat Mahendra.
Beberapa guru berdatangan masuk ke ruang guru. Mereka sibuk meletakkan buku tugas siswa, absensi kehadiran dan buku pelajaran di atas meja masing-masing sembari mengecek notifikasi di ponsel, siapa tahu ada pesan penting.
Beberapa siswa laki-laki tampak berjemutmr dibawah terik matahari. Mereka pasrah menerima hukuman dari para guru setelah diketahui bahwa mereka ketahuan bolos sekolah. Alasannya? Mereka berpacaran dan merasa sekolah bukan lagi sebuah kewajiban.
Seluruh warga sekolah tampak melempar tatapan sinis ke arah anak-anak itu di jam istirahat. Memang hukuman bertujuan agar mereka sadar dan segera menjadi pribadi yang lebih baik tetapi apa benar ini caranya?
Seorang guru wanita bertampang judes bernama Deysi yang tertulis di name--tag tampak berdiri memantau siswa sembari sibuk berfoto. Album fotonya dipenuhi oleh foto selfie yang bila dihitung mencapai seribuan. Mungkin bisa dikatakan hobi. Mahendra menghampiri Deysi seraya merapikan rambutnya.
"Ibu Deysi, hukuman itu tidak akan membuat mereka sadar. Mereka hanya merasa takut lalu akan mengulangi yang sama lagi. Karena mereka berlindung pada sebutan 'anak-anak'."
Wanita itu melempar sorot mata tajam. "Kau membela mereka? Kau pikir dengan cara yang halus mereka bisa berubah?"
Mahendra berhenti seraya berucap dengan suara dalam. "Supaya mereka mau berubah, hukuman harus musnah."


 shadowalker15
shadowalker15