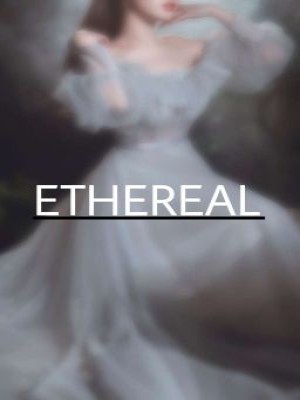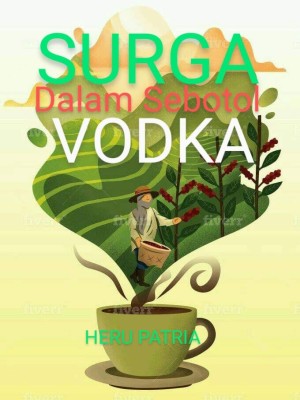Sudah satu jam aku berada di masjid bandara untuk beristirahat sebentar sambil menunaikan salat zuhur berjamaah. Aku sudah mengirimkan pesan pada Enre untuk menjemputku di bandara saat aku mendarat di Singapura. Aku mengabarkan pada Enre bahwa hari ini aku pulang ke Makassar.
Katanya dia siap menjemputku kapan saja seperti komentarnya di salah satu foto di Instagram yang kuunggah saat aku transit di Singapura. Katanya dia juga siap mentraktirku apang paragi, kue bakar tradisional khas Sengkang kesukaan kami. Dulu kami sering makan kue yang terbuat dari adonan yang dicampur dengan bumbu spekuk[1] itu tiap akhir pekan. Biasanya kami makan di warung langganan kami di Warkop Temangnge, warung legendaris yang sudah berdiri sejak tahun 1950-an di Sengkang.
Kulihat kembali pesan yang kukirim kepada Enre melalui WhatsApp sejak tadi aku turun pesawat. Namun, masih saja belum ada balasan darinya. Kulihat masih ceklis satu tanda pesan belum diterima. Mungkin jaringan sedang tidak bersahabat atau Enre sedang menonaktifkan ponselnya. Kulihat juga pesan yang kukirim melalui Facebook dan Instagram-nya tapi belum juga ada tanda-tanda pesanku dibaca.
Kuperhatikan sekelilingku, kuarahkan pandangan ke kanan dan kiri, satu persatu orang-orang mulai beranjak dari tempatnya. Masjid mulai sepi. Aku berdiri dengan sigap menuju pintu keluar. Sambil berjalan aku memikirkan dengan apa aku pulang menuju Sengkang. Perjalanan pulang kampung yang begitu berat. Bukan lantaran jauhnya jarak dan lamanya perjalanan yang memakan waktu panjang sekitar empat sampai lima jam. Namun, ternyata kisah-kisah kelam masa lalu masih terus terbayang meski telah sekian lama meninggalkan Sengkang.
Bekas tamparan bapak memang sudah tidak terasa lagi tapi lukanya masih membekas di hati hingga kini. Bahkan sering kali trauma-trauma itu hadir tanpa pernah kuminta. Ibarat sebuah bangunan, pondasiku masih kokoh tertanam, tapi tiang-tiangnya telah roboh berjatuhan perlahan satu demi satu. Entah apakah aku bisa mendirikannya dengan kekuatan yang kupunya. Banyak hal yang telah membuatnya berjatuhan, tapi hal paling besar adalah karena sikap bapak.
Dulu aku sering menangis karena pedihnya hidup yang kujalani. Namun, lama-kelamaan akhirnya aku mulai terbiasa. Bahkan kini aku sudah lupa bagaimana caranya mengeluarkan air mata. Mungkin karena terlalu pedih hingga air mataku menguap entah ke mana. Aku menyembunyikan luka dengan menghibur diri dan menghibur teman-teman agar mereka gembira. Aku tertawa, tapi itu hanya untuk menutupi segala perih hati yang selama ini kurasa.
“Pabbura iyya manenna malasae iyana itu ati senang'e.”[2]
Ya aku percaya dengan kata-kata itu. Sebab itu lah, aku selalu berusaha agar aku selalu bahagia dengan berbagai cara. Tentu dengan cara yang lebih dan bertanggung jawab. Pun tetap sesuai dengan norma dan aturan agama. Meski pada kenyataannya setelah itu, kadang aku masih larut dalam hati yang patah.
Entah siapa yang harus dipersalahkan atas semua yang telah terjadi dalam hidupku. Entah siapakah orang yang seharusnya paling bertanggung jawab dengan ini semua.
Ya Rabb
Kuatkan hati yang rapuh agar tidak terjatuh
Hiburlah hati hamba
Dengan janji-Mu yang baka
Kuatkan langkah
Agar tetap istiqomah
***
“Tiiinnn….”
Suara klakson panjang dari arah depan mengagetkanku yang sedang berjalan pelan menuju arah parkiran. Aku tak mempedulikannya. Aku terus berjalan tanpa menghiraukan suara klakson yang berbunyi beberapa kali entah memberikan kode kepada siapa. Mataku fokus pada aspal jalanan yang mulai panas terbakar matahari.
Aku terus berjalan dengan langkahku yang terasa begitu berat. Di kepalaku berkecamuk berbagai macam pikiran tentang bagaimana reaksi keluarga saat melihatku pulang ke rumah. Entah akankah kedatanganku nanti di rumah menjadi kejutan yang menyenangkan atau malah sebaliknya.
Aku melangkah pelan. Lalu, terdengar suara orang meringis kesakitan dari arah belakang. Lagi-lagi aku tak menghiraukan. Aku terus melangkah ke depan. Namun, mendadak timbul rasa penasaran hingga akhirnya aku menolehkan pandanganku ke arah belakang. Sekilas, aku melihat ada seorang bapak tua memakai songko bone[3] terjatuh di aspal. Di sebelahnya kulihat ada seorang lelaki bertopi merah marun yang kuperkirakan seusia denganku sedang menolongnya berdiri.
Aku hanya melihatnya dari jauh tanpa terdetik pun rasa iba untuk membantunya. Kulihat lelaki tua itu berusaha bangkit dengan dipapah anak muda di sebelahnya. Sekilas dapat kulihat raut wajah tua yang tampak kesakitan. Aku terus melangkah lalu memalingkan wajahku ke depan.
Entah mengapa, wajah kesakitan lelaki tua itu terus membayang. Entah mengapa, wajah itu mengingatkanku pada seseorang. Aku merasa tak asing dengan wajahnya. Lalu, aku memperlambat Langkah. Berhenti sejenak. Jika tadi hanya sekadar menolah saja, kini aku membalikkan badanku ke arah bapak tua.
Aku memutar badanku seratus delapan puluh derajat menghadapnya. Aku memperhatiakan lagi wajahnya. Rasanya wajah tua itu sangat khas dan sangat membekas di ingatan. Aku masih berdiri beberapa saat, memandangi dua sosok lelaki yang berjarak sekitar seratus meter di hadapanku.
“Puang Bahar?” ucapku ragu.
Aku masih belum yakin dengan apa yang kulihat. Mungkinkah duganku benar? Ataukah hanya orang yang mirip saja dengannya? Maklum, sejak tadi memang aku sedang memikirkan sosok-sosok yang pernah berjasa padaku di masa lalu. Salah satunya adalah Puang Bahar.
Tak berapa lama lelaki bertopi merah marun itu mengangkat kepalanya. Tiba-tiba mataku berkaca-kaca. Benar, setelah perhatikan ternyata kedua orang itu adalah Puang Bahar dan lelaki bertopi merah marun itu Enre, anaknya. Maklum sudah tujuh tahun berpisah, tentunya penampilan mereka sudah banyak yang berubah sejak terakhir aku melihatnya.
Tanpa pikir panjang lagi, aku segera melangkah mendekat ke arah mereka. Tak sabar ingin bertemu, aku pun mempercepat langkah hingga akhirnya berlari kecil sambil memanggil nama mereka.
“Puang … Enre ….”
Puang Bahar dan Enre melihat ke arahku. Aku tersenyum lebar dengan air mata yang tiba-tiba mengalir deras di pipiku. Betapa bahagianya hatiku melihat mereka. Begitu pun mereka. Aku dapat melihat raut wajah mereka yang semringah. Kulihat mata keduanya pun berkaca-kaca sambil memberikan senyuman yang terindah.
***
Puang Bahar dan Enre adalah sosok yang begitu berharga dalam hidupku. Bertahun-tahun tak berjumpa akhirnya kini bertemu juga. Aku masih bisa merasakan Puang Bahar dan Enre sebagai sosok yang sama. Sosok yang hangat dan bersahabat. Tak ada yang berubah dari mereka, kecuali rambut Puang Bahar yang mulai ditumbuhi uban. Sementara, Enre kini makin terlihat lebih gempal dan makin banyak menyimpan lemak di perutnya.
Aku makin mendekat dan kini berada tepat di depan mereka.
“Wellang.” Kudengar lirih Puang Bahar memanggil namaku.
Enre masih berusaha membantu ayahnya untuk berdiri. Ingin rasanya segera melerai rindu dengan pertemuan yang sudah di depan mata. Tanpa basa-basi lagi aku mencium tangan Puang Bahar penuh takzim. Lalu, dengan segala rindu aku memeluknya erat.
“Puang ….”
“Aga kareba, Nak?[4]” sapa Puang Bahar lembut di telinga kananku.
Hatiku meleleh bisa mendengar lagi suara itu dan membuatku makin erat memeluknya. Air mataku berjatuhan. Aku merasakan Puang Bahar menepuk-nepuk pelan punggungku. Rindu sekali dengan dekapan ini. Dekapan hangat dari orang tua yang sudah menganggapku seperti anaknya. Dekapan yang begitu nyaman dan masih sama rasanya seperti dulu saat aku menangis di pelukannya.
***
[1] Campuran 4 rempah yaitu: kayu manis bubuk, cengkih bubuk, bunga pala bubuk, kapulaga bubuk
[2] Obat segala penyakit adalah hati yang gembira
[3] Topi khas Makassar.
[4] Bagaimana kabarmu, Nak?


 hadismevlana
hadismevlana