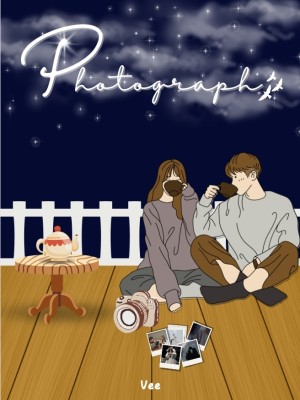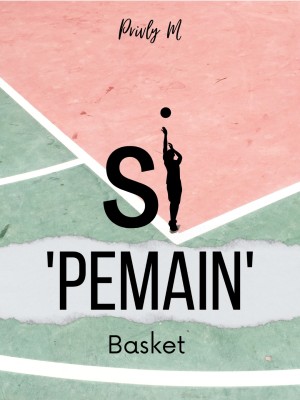Ponselku bergetar. Ada chat masuk. Aku segera membukanya. Ternyata dari Berlian Marauleng, adik semata wayang yang kutinggalkan jauh di Sengkang. Seperti biasa, aku sudah bisa menebak apa isi pesannya. Karena sejak kami berpisah tujuh tahun lalu hanya satu permintaannya yang sampai saat ini belum juga bisa kupenuhi : “Lesuni, Daeng, moddanika sibawa indo.”[1]
Aku menarik napas dalam. Tidak ada maksud sedikit pun dalam hatiku untuk tidak ingin bertemu adik dan ibu. Jangan ditanya apakah aku tidak rindu? Namun ah, wajah bapak selalu terbayang. Bentakannya, pukulannya selalu menghalangi keinginan untuk pulang.
“Lesuni Daeng, meloka idi dampingika ri esso abottingekku. Mellau tulungka kesi daeng.”[2]
chat berikutnya masuk. Aku kembali menarik napas dalam.
Rasanya baru kemarin kami bercanda tawa dan bulan depan Uleng akan menikah. Adik kecilku yang dulu manja, kini sudah menjadi seorang gadis jelita. Sebentar lagi, dia akan menempuh kehidupan baru dalam rumah tangga. Aku bangga memiliki adik sepertinya. Dia sosok perempuan gigih dan memiliki komitmen yang kuat. Salah satu yang membuatku bangga karena dia masih mempertahankan hijab yang sudah dikenakannya sejak masih duduk di bangku sekolah. Meski banyak teman sebayanya yang memilih melepas hijab mereka.
Uleng cerita, mereka melepas hijabnya karena pergaulan yang melawati batas sewajarnya. Penampilan yang sudah baik menjadi erotik, sebab berteman dengan lingkungan toxic hanya demi terlihat asik. Namun, ada juga aturan berseragam di tempat bekerja. Uleng pun sempat tergoda untuk menanggalkan pakaian muslimahnya demi mengejar dunia. Alhamdulillah, Allah masih sayang dan menjaganya.
Aku pun bangga saat tahu kalau sekarang dia sudah bekerja. Dia sekarang sudah menjadi seorang perawat di sebuah Rumah Sakit Umum Daerah Lamadukelleng yang jaraknya sekitar 15-20 menit berkendara dari rumah. Sebuah profesi yang memang sudah menjadi cita-citanya sejak lama.
***
Sebetulnya sudah sejak beberapa bulan lalu Uleng memintaku pulang. Dia ingin mendiskusikan tradisi dan adat yang berlaku sebelum hari lamaran tiba. Tentang uang panai yang seolah menjadi momok menakutkan para calon pengantin pria ketika hendak melamar gadis pujaannya. Panai seolah menyulitkan dan menjadi kendala bagi proses pernikahan dua insan sebab nominalnya kadang begitu luar biasa.
Kejadian ini sempat terjadi pada salah satu keluargaku. Pamanku dari pihak ibu sempat stress lantaran dia gagal meminang gadis pujaan. Panai yang diminta dari pihak keluarga perempuan begitu memberatkan. Maklum, gadis pujaaan pamanku itu anak seorang yang terpandang di masyarakat. Berasal dari keluarga berdarah ningrat.
Secara tersirat, tradisi panai ini ingin memberikan gambaran tentang arti sebuah kualitas. Pamanku jatuh hati dengan seorang dokter cantik lulusan salah satu universitas negeri di Jakarta. Gadis itu tidak lain adalah temannya sejak mereka duduk di bangku SMA. Pamanku tak menyanggupi permintaan panai yang jumlahnya sungguh luar biasa.
Pamanku tak mampu memenuhi permintaan panai dari pihak keluarga perempuan yang nilainya sangat fantastis. Akhirnya keluarga sang perempuan menolak pinangannya. Selang beberapa bulan, terdengar kabar bahwa gadis pujaan pamanku itu menikah dengan lelaki lain pilihan orang tuanya. Pamanku begitu patah hati. Dia mengurung diri di kamar selama beberapa hari.
***
Melihat pengalaman dari pamanku itu tampaknya Uleng bingung terkait penentuan berapa kelayakan uang panai untuk dirinya. Namun, sayangnya saat itu aku tak bisa memenuhi keinginan Uleng untuk pulang. Uleng sempat marah tak mau menerima telepon atau membalas WhatsApp-ku. Aku sudah berusaha mengontak melalui Facebook dan Instagram, tapi dia tak menggubrisnya. Berhari-hari aku berusaha terus menghubunginya. Aku hampir kehabisan akal membujuknya agar dia mau berkomunikasi lagi denganku.
Berhari-hari kesedihan menguasai hatiku. Tak pernah rasanya aku merasakan hati sesedih ini. Uleng, adik kesayanganku satu-satunya begitu kecewa karena keegoisanku. Selama beberapa hari itu pun aku menghibur diri dengan melihat-lihat kembali foto kami berdua beberapa tahun lalu. Namun, sedihku tak kunjung reda. Sebaliknya, rindu yang makin memuncak membuat hatiku makin lara.
Penyesalanku makin menjadi karena telah membuat Uleng kecewa. Dalam kegelisahan dan penyesalanku itu aku terus berusaha berpikir bagaimana caranya merebut kembali hati Uleng. Aku hanya bisa berdoa agar Allah membukakan kembali sedikit celah agar aku bisa kembali bersemayam di hatinya.
Akhirnya terlintas dipikiranku untuk mengirimkan sebuah foto kepada Uleng melalui WhatsApp. Aku berharap hatinya akan luluh setelah melihat sebuah foto keakraban terakhir kami sebelum akhirnya aku meninggalkan Uleng bertahun-tahun lamanya. Foto uleng bergelayut manja di lenganku saat mengantarku ke Bandara International Sultan Hasanuddin. Foto bersejarah bagiku sebab itu adalah foto pertemuan terakhir kami dan belum sekali pun kami bertemu sampai saat ini.
Uleng meneleponku beberapa saat setelah kukirimkan foto itu. Sambil sesegukan dia mengungkapkan betapa rindunya dia padaku. Lagi-lagi aku hanya bisa meminta maaf padanya sambil menjelaskan sedikit alasan tentang betapa sakitnya hatiku mengingat tentang kenangan yang bertabur luka di rumah. Betapa traumaku masih belum sembuh. Betapa aku butuh waktu mengiklaskan semua itu.
“Assalamualaikum, Kak ….”
“Waalaikumsalam.”
Sejenak kami hening setelah aku menjawab salamnya. Kudengar samar ada sesegukan dari seberang sana. Uleng menangis. Terdengar begitu pilu.
***
[1] “Pulang, Kak, Aku dan Ibu kangen.”
[2] “Pulang, Kak. Aku ingin Kakak mendampingiku di hari pernikahan. Tolonglah, Kak.”


 hadismevlana
hadismevlana