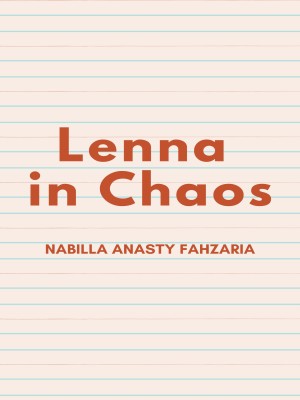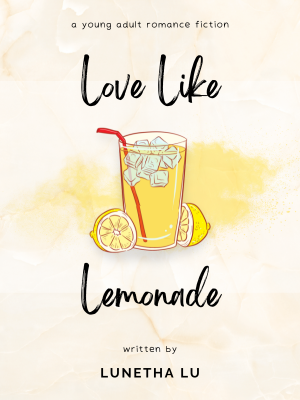Aku sudah membaca pesan WhatsApp dari Enre, tapi belum sempat membalasnya. Raya sudah memanggilku untuk segera kembali ke campervan karena akan melanjutkan perjalanan berikutnya. Kumasukkan kembali ponselku ke dalam saku celana. Sebelum beranjak, kurentangkan kedua tangan sambil menghirup segarnya udara.
Sejenak kunikmati pagelaran alam yang begitu indah sambil menghayati senja yang turun perlahan di tepi langit yang terlihat semakin cantik. Angin bertiup lembut membuat riak-riak gelombang berlarian di permukaan danau. Bunga-bunga Russell Lupines pun menggoyang-goyangkan tubuhnya pelan seolah menghantarkan mentari yang sebentar lagi menutup matanya.
Kupejamkan mata. Kutarik napas panjang perlahan lalu kuembuskan. Kubayangkan segala permasalahan dan beban-beban batin ikut melayang terbang bersama angin yang berhembus jauh dan tak ingin lagi kuhirup deritanya. Lalu, kunikmati kembali wajah New Zealand, berharap wajah duka terhapus oleh keindahannya.
Tak jauh dari tempatku duduk, ada sebuah keluarga kecil yang baru saja turun dari kendaraannya. Mobil sedannya terparkir tak jauh dari campervan kami. Wajah mereka sepertinya tak asing lagi bagiku. Aku mencoba mengingatnya sambil terus memperhatikan dua gadis kecil itu.
Dua wajah kembar berwajah manis itu memakai baju yang sama. Rambut mereka pun sama-sama dikepang dua. Mereka berlari-lari dengan lincah bermain piring terbang di padang bunga Lupin yang tumbuh liar di tepi danau bersama sang ayah.
Sesekali ayah mereka berkelakar membuat kedua gadis kecil itu tertawa kegirangan. Sementara, sang ibu sedang asyik memotret pemandangan di sekitarnya. Tak lama kudengar salah seorang dari gadis kembar itu memanggil ibunya. Sang ibu yang tengah mengarahkan kameranya ke The Church of the Good Shepherd segera menoleh dan menghentikan buruan gambarnya.
Sang ibu segera menghampiri mereka yang sedang asyik bermain bersama sang ayah. Tak berapa lama sang ayah memasang sebuah tripod. Lalu, sang ibu menyetel kamera. Kedua gadis kecil itu langsung memamerkan senyumnya. Mereka sedang berfoto keluarga. Aku sangat iri melihat kehangatan mereka. Keceriaan mereka tak kalah indah dari bunga-bunga yang sedang mekar.
Aku tersenyum, tapi sebenarnya batinku menangis. Tersenyum ikut bahagia melihat kebahagiaan mereka, menangis karena aku tak pernah mengalami kebahagiaan seperti mereka.
Aahh … betapa sempurnanya hidup kalian adik kecil. Alangkah gembiranya kalian memiliki orang tua seperti mereka. Betapa bahagianya memiliki ayah yang bisa berbagi kebahagiaan.
“Uncle Prince …,” tiba-tiba dua gadis kembar itu sambil melambaikan tangannya ke arahku.
Aku mengerutkan kening. Seketika aku kembali teringat sesuatu begitu mendengar sebutan “Uncle Prince”. Sebutan yang baru kali itu disematkan untukku. Tak ada yang menyebut dengan nama itu selain mereka. Namun, aku mencoba memastikan. Khawatir julukan “Uncle Prince” itu tak hanya special untukku.
Aku melihat sekitar, memastikan hanya ada aku dan lambaian tangan dua gadis kembar itu memang tertuju untuku. Ternyata hanya ada aku yang sedang duduk sendirian. Lalu, Kutatap dua gadis kembar itu dalam-dalam.
Ah iya. Aku ingat. Segera aku melambaikan tangan kepada mereka. Ternyata mereka adalah dua gadis kecil asal Singapura. Kami bertemu saat mendarat di Bandara Queenstown kali pertama. Baju dan rambut mereka yang ditata sama membuatku hampir tak bisa membedakan mana Alma dan mana Alya.
Kuhapus air mataku. Lalu, tersenyum kepada keduanya sambil melambaikan tangan. Aku melihat senyum mereka pun makin lebar. Senyum tulus dan bahagia mereka terasa hingga ke hati. Ingin rasanya menghampiri dan berbincang sejenak dengan mereka. Namun, Raya memanggilku lagi untuk segera kembali ke campervan.
“Wellang ... ayo balik ...,” teriak Raya.
“Sebentar ...,” jawabku sambil terus mengamati pemandangan sebuah keluarga yang menurutku sempurna.
Ingin rasanya berandai-andai ingin begini begitu. Seandainya saja aku lahir dari keluarga yang bahagia dan seterusnya. Namun, segera aku halau pikiran-pikiran itu. Aku ingat, Raya pernah mengatakan bahwa sebagai seorang muslim kita dilarang untuk berandai-andai. Dosa katanya. Aku pernah ditegur Raya gara-gara hal itu.
“Andai saja dia bukan bapakku?” celetukku tempo hari kepada Raya.
“Hush, sembarangan saja kalau bicara,” tegur Raya, “nggak bagus berandai-andai.”
“Yaah kan cuma pura-pura,” jawabku enteng.
“Tapi berandai-andainya kamu itu seperti mengeluh dengan takdir-Nya, Wellang. Nah itu yang dilarang dalam agama.”
Lalu, Raya memberitahuku sebuah potongan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang larangan berandai-andai itu.
… Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan: ‘Seandainya aku lakukan demikian dan demikian.’ Akan tetapi hendaklah kau katakan: ‘Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi.’ Karena perkataan law (seandainya) dapat membuka pintu setan.”
“O … aku baru tahu,” ucapku sambil mengangguk usai Raya membacakan kutipan hadits itu.
“Tapi bukan berarti semua penggunaan ungkapan ‘seandainya’ itu terlarang. Kembali lagi, semua tergantung dari motif yang mendasari penggunaan kata ‘seandainya’ itu. Misalnya, seperti yang tadi kau katakana. Kau berandai-andai kalau dia bukan bapakmu.”
Aku mengangguk pelan mendengar penjelasan Raya.
“Jika motif pengucapan seandainya itu karena kita mengeluh, mengungkapkan kesedihan, mempermasalahkan takdir, memprotes syariat yang ditetapkan Allah atau berangan-angan untuk melakukan keburukan, maka hal ini tercela dan terlarang.”
Kupalingkan wajahku ke arah Raya. Dia sudah beranjak meninggalkanku. Aku bergegas berlari mengejar Raya yang sedang berjalan menyusuri tepi danau bersama pasangan jiwanya, Rona. Perempuan cantik berkacamata dengan tinggi semampai sepadan dengan Raya itu telah menjadi bagian hidupnya sejak beberapa bulan lalu.
***


 hadismevlana
hadismevlana