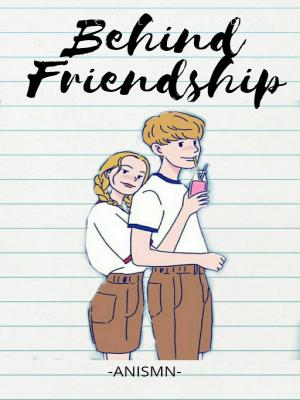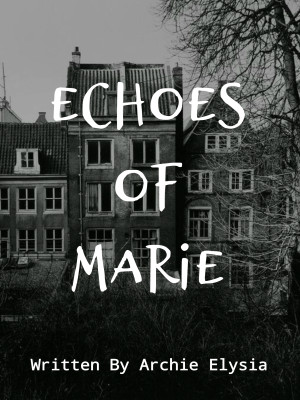Kamis, 18 April 2013.
.
“To err is human.”
Sambil mengepalkan tangan, Pandu Raharjo ingat potongan petuah seorang filsuf Romawi yang pernah dibacanya di buku ayahnya itu. Selama tujuh belas tahun hidupnya, barangkali ini satu-satunya momen ketika petuah purba itu harus Pandu bangkitkan dari kubur. Bukan dari kuburnya Seneca, sang filsuf, tentunya. Kubur memori Pandu sendiri, maksudnya.
Manusia berbuat kesalahan, sesekali, dan berbuat kesalahan itu manusiawi. Namun, bagi Pandu, seorang perfeksionis kronis yang kini sedang terjebak dalam situasi di mana kesalahan itu bisa berakibat fatal bagi masa depannya, kutipan Seneca bagai duri dalam daging ikan bandeng menu sarapannya tadi pagi. Kecil dan mengganggu, tapi tak ada pilihan lain.
Penanda waktu di dinding menunjukkan pukul sebelas kurang satu menit.
Pandu menelan ludah dan menunduk, pikirannya terbagi dua tiap melihat jarum jam: “Segeralah saat ini berlalu biar aku nggak menyesal,” dan, “Bekulah dulu, hai, Waktu. Beri aku kesempatan untuk mencegah kesalahan”. Masih ada rasa amis bandeng di kerongkongan Pandu dan itu sama mengganggunya dengan kalimat Seneca. Dia sudah melakukan segalanya demi hari ini dan dia tak bakalan memaafkan dirinya jika sampai ada kesalahan.
Saat itu, sebuah suara berdering nyaring dan Pandu ingin berteriak sekeras-kerasnya sekaligus berlari sekencang-kencangnya, namun ia tak dapat. Ada otoritas yang menahannya bergerak dan bersuara, dan urgensi yang ditahan-tahan dari kedua hal itu membuat Pandu melupakan Seneca. Dua pria dewasa berseragam melangkah mendekatinya, seorang di tiap sisi. Jantung Pandu berdegup kencang.
Salah satu pria itu, yang berpostur pendek dan berkulit sawo matang, mengambil sesuatu dari tangan Pandu yang terjulur.
Dan akhirnya ... inilah dia. Begitu plester itu sudah menempel dengan rapi pada tepi lipatan amplop cokelat ukuran folio, seluruh manusia dalam ruangan itu berdiri. Sebagian bertepuk tangan dan bersorak, yang lain terutama perempuan saling berpelukan, dan sisanya membereskan benda-benda yang terserak di meja masing-masing dengan terburu-buru.
“Akhirnya!” Pandu menjerit, nyaris terbahak, mengangkat tinjunya ke udara.
“Semoga lulus seratus persen ya,” ujar pria yang satunya, berbadan tinggi dan berkulit terang, sembari membetulkan letak kacamata yang bertengger di hidungnya.
“Aaaammmmiiiinnnn,” seru para siswa bak paduan suara.
*
Hari itu, seluruh prajurit kelas tiga batalion es-em-a telah selesai menempuh Ujian Nasional; klimaks studi di bangku Wajib Belajar, Perang Terakhir bersenjatakan buku dan seragam, serta Perburuan-Tanpa-Kenal-Lelah demi mendapatkan selembar kertas bertitel IJAZAH.
Di pojokan food court, Pandu sedang menyeruput es teh krampulnya dengan wajah kelewat puas dan lega, sepuas dan selega dirinya selepas buka puasa.
“Finally …,” desahnya setelah tegukan terakhir meluncur masuk di kerongkongannya.
“Haaah! Cukup, Ndu! Cukup! Jangan ingetin neraka mapel Bahasa Inggris!” seru si Gempal Angga, sok dramatis. Bahasa asing memang selalu asing buat dia, tak peduli pelajaran itu sudah diberikan sejak TK.
“Nggak usah sok Inggris, deh,” komentar Reni, singkat tapi tajam. Gadis berambut ikal dan berwajah oval itu memasukkan suapan terakhir chicken katsu-nya sambil melirik dengan pandang mencela ke arah Pandu dari balik bulu matanya yang lentik. Bukannya dia sama dengan Angga yang antibahasa Inggris, malahan nilai Bahasa Inggris Reni bisa dibilang nomor dua paling sempurna di kelas XII-A3. Lalu, siapa nomor satunya? Tak lain dari Pandu Raharjo. Nama keduanya paling sering muncul di daftar nilai tertinggi milik para guru dan mereka berdua selalu ada dalam kelas yang sama. Pendek kata, pemilik nama lengkap Reni Kejora Rahmawati itu selalu menganggap Pandu adalah saingannya.
“Ya, sori aja, bahasa Inggris hamba pun nggak sebagus itu,” cecar Reni lebih lanjut dengan nada datar, sedatar piring-piring ceper tempat makanan mereka disajikan.
“Hei, kalian. Jangan ngerusak suasana, ah,” sergah Gita tanpa mengangkat wajah dari ipad yang dipegangnya. Seperti biasa, di piringnya masih tersisa cuilan sayur dari burger yang telah berpindah ke perutnya. Gita memang paling ogah makan sayur, tapi doyan banget junk food hingga tak menyadari badannya mekar subur.
“Aku enggak. Lha, wong barusan aku cuma ngomong satu kata, kok,” lontar Pandu membela diri. Dilihatnya Reni sudah akan mendebatnya, jadi dia menambahkan, “Pada udah selesai, ‘kan, makannya? Yuk, ke Various Vizta, ntar keburu penuh.”
Dan, dengan Reni yang terpaksa menelan argumennya, Angga yang masih meratapi ujian Bahasa Inggrisnya, serta Gita yang asyik dengan piranti gawainya, Pandu berhasil mendapat antrean di rumah karaoke itu.
“Tapi, tetep aja … bahagia banget rasanya, udah selesai ujian,” ujar Angga sambil mengempaskan pantat di salah satu kursi tunggu di balik pintu kaca.
“Jadi, jangan nangisin masa lalu, dong!” serang Reni, menyoroti ujian bahasa Inggris Angga.
“Wah, ambigu,” komentar Pandu cengengesan. “Emang, ada apa di masa lalu, Ren?”
Alis yang ditanya menukik tajam, matanya menyipit. “Apaan coba.”
Angga menengahi, “Sudah, sudah, jangan berteman—eh, jangan bertengkar.”
Reni melengos sementara Pandu cengar-cengir sambil bertukar pandang penuh makna dengan Angga.
Mereka ada di Solo Square, salah satu mall di Kota Surakarta—atau lebih bekennya, Solo. Kebetulan mall ini letaknya cukup dekat dari sekolah mereka. Lantai empat tempat keempat sohib itu akan karaokean juga merupakan arena bioskop serta food court. Tak heran ramainya minta ampun.
Eh, tunggu dulu—ini, ‘kan, hari Kamis? Mengapa mall penuh pada hari non-akhir-pekan?
Angga tahu-tahu ikut nyengir. “Eh, ada yang tahu, nggak? Udah berapa siswa SMA bersliweran di depan sini sejak kita duduk?”
“Emangnya penting, ya, Ngga?” Gita menyahut, seraya mengibaskan poni panjangnya ke samping, mata masih terpaku di tablet-nya. Layar benda itu menampilkan gambar-gambar hitam-putih dengan beberapa balon kata. Biasa, baca manga online.
“Ngga? Kok, malah diem. Emangnya penting?” desak Gita karena tak mendapat respons, meski agaknya tak benar-benar bermaksud sinis lantaran fokusnya masih pada gawai.
“Dari tadi, banyak banget anak SMA yang masih pake seragam, berkeliaran di Solo Square,” Angga mengulang retorikanya dalam kalimat berita, sedikit bete karena yang mengajak bicara malah mantengin gawai.
“Mereka makhluk-makhluk bahagia …,” seloroh Pandu menanggapi kalimat Angga. Kedua cowok itu kemudian terbahak keras.
“Hah? Apa? Bisa diulangi?” Gita akhirnya mendongak, wajahnya terlihat bingung.
“Mall penuh. Jelas, lah. Ini, ‘kan, hari terakhir ujian,” balas Reni, menjelaskan maksud Pandu tanpa diminta.
“Merdeka!” seru Angga sambil meninju udara.
“Yeah, merdeka!” sahut Pandu.
“Oi, masih lama, kali! Ini masih empat bulan menuju Agustus,” sambung Gita nggak nyambung, matanya kembali terpancang pada layar gadget.
“Oi, ngomong-ngomong soal merdeka, aku punya teka-teki, nih,” seloroh Pandu. Tanpa menunggu yang lain menyahut, dia melanjutkan, “Kemarin siang, aku pulang dari sekolah jam setengah dua belas dan baru nyampe rumah jam satu. Padahal kalian tahu, waktu tempuh dari sekolah ke rumahku cuma sekitar lima belas menit. Kira-kira, kenapa aku pulang telat? Eits, tunggu, jangan dijawab dulu, Ren. Aku langsung pulang dari sekolah ke rumah dan nggak mampir-mampir. Petunjuk pertama ada di mall ini. Di dalam ruangan ini, malah.”
Angga mengerang pelan dan Gita masih menikmati manga-nya, tapi Reni diam sebentar sambil berpikir.
“Kamu kebanan?” tebak Reni. “Ban motor pecah?”
“Salah,” jawab Pandu sambil nyengir.
“Aku tadi sempet mikir ada mokmen. Atau kamu mampir ke Warung Soto Pak Makmur dulu baru pulang,” sahut Angga ogah-ogahan. “Ternyata enggak. Aku nyerah, Ndu.”
“Kok, mokmen, sih. Ini, ‘kan, belum libur Lebaran atau Natal,” Pandu terkekeh. “Jawabannya ada di deket warung Pak Makmur, lho, sebenernya. Itu petunjuk kedua. Ups. Nanti Reni jadi bisa nebak, nih.”
“Mokmen apaan?” seloroh Gita sambil lalu, merasa asing dengan istilah baru.
“Git. Kamu, tuh, Bapak-Ibumu asli Solo dan kamu nggak ngerti mokmen itu apa?” cela Angga.
“Diem, ah! Lagi seru ini, lho!” Mata Gita masih terpancang pada layar.
“Mokmen tuh razia kendaraan itu, lho! Biasanya emang motor yang kena! Yah, Gita anak mami, sih, jadinya mana tahu. Tiap hari, ‘kan, kamu diantar supir naik mobil!” balas Angga selagi ada kesempatan. Biasanya, sih, selalu dirinya yang di-bully oleh Gita. Sekarang dia yang ganti nge-bully cewek itu, hehehe.
Gita sendiri santai saja, tak merasa sedang di-bully lebih karena memang lagi fokus pada bacaannya. “So what? Lagian, dari mana istilahnya ‘razia’ bisa jadi ‘mokmen’? Nggak umum banget!”
“Mokmen tuh asalnya dari ... ‘A moment, please. Minta waktu sebentar, bawa SIM dan STNK nggak?’ Gitu kira-kira, Git,” Pandu menjelaskan tanpa diminta.
“Oh, gitu,” sahut Gita dengan nada mengambang.
“Makanya belajar bahasa daerah yang bener!” sahut Angga lagi.
“Eh? Mana ada itu di pelajaran sekolah? Itu, ‘kan, kearifan lokal?” balas Gita, memutar posisi duduknya tanpa melepas pandangan dari gawai. “Udah, deh, berisik aja kalian ini.”
Reni menyambar, “Oi, kembali ke topik, Ndu. Kalau aku berhasil nebak teka-tekimu, kamu mau kasih aku apa?”
Tadinya Pandu pengin merespons jahil dengan balik bertanya, “Lha, Mbakyu Reni minta dikasih apa, hayo?” tapi itu bakalan kedengaran tengil banget dan Pandu ogah digampar di tempat umum begini, jadi dia menjawab, “Jatah patungan bagianmu buat karaokean hari ini, aku yang bayar.”
“Oke, deal,” sahut Reni sambil mengedarkan pandangan mencari petunjuk yang dimaksud Pandu. “Dari sekolah ke rumahmu, ya ....” Reni bergumam-gumam. Dia membayangkan jalan mana saja di kota yang tak seberapa luas itu yang mungkin dilewati Pandu dengan sepeda motor dan sudah mendapatkan peta imajiner dalam benaknya. Ada warung Pak Makmur sebagai petunjuk, dan letaknya di tengah kota, dekat Monumen Pers Nasional ....
Reni mengernyit dan melihat sesuatu. Itu dia! Poster di seberang tempat duduk mereka mengumumkan adanya sebuah ...
“... kompetisi fotografi tanggal 15-17 April 2013 di Monumen Pers Nasional. Pengumuman pemenangnya tanggal 17 siang dengan arak-arakan Piala Walikota dari Balaikota ke monumen ... astaga.” Mata Reni terbelalak. “Pasti macet banget di sekitar situ. Itu yang bikin jalan pulangmu terhambat, ‘kan, Ndu?” Reni mengutarakan jawabannya dengan yakin.
“Ting tong, Reni betul!” Pandu pura-pura tepuk tangan. “Parah banget, sih, macetnya. Satu ruas jalan raya yang panjang itu diblokir semua, mau muter arah malah kejebak.”
“Terus, apa hubungannya sama merdeka tadi?” tanya Angga yang sebal karena Gita mengabaikannya dan yang sudah nggak heran lagi dengan tingkah kedua temannya itu: yang satu kasih teka-teki dan yang satunya menjawab.
Pandu menanggapi, “Monumen Pers Nasional itu, ‘kan, wajah kebebasan pers, kemerdekaan di—”
“Atas nama Pandu,” panggil Mbak-mbak Resepsionis tiba-tiba.
“Eh, iya, Mbak,” sahut Pandu sambil berdiri. “Come on, guys!”
“Bisa nggak, pake bahasa Indonesia aja?” keluh Angga, kembali lesu.
“Oops, I’m so sorry!” goda Pandu.
“Pandu ...!” erang Angga.
“Let’s go!” Pandu melanjutkan sembari nyengir.
“Git!” Reni menggamit lengan Gita yang bangkit berdiri sambil tetap tunduk membaca. “Ayo, komiknya nggak akan hilang meski belum selesai kamu baca, kok!”


 roux_marlet
roux_marlet