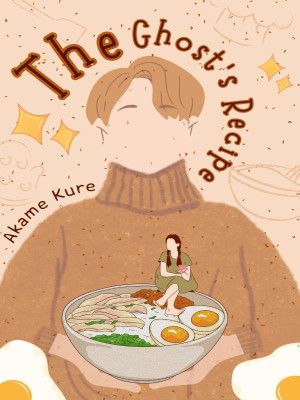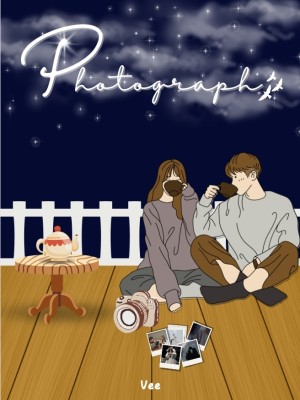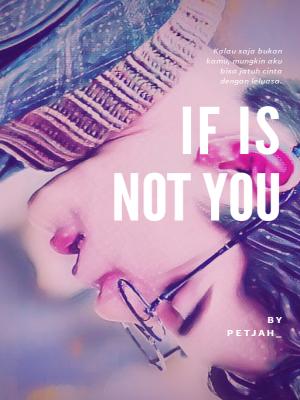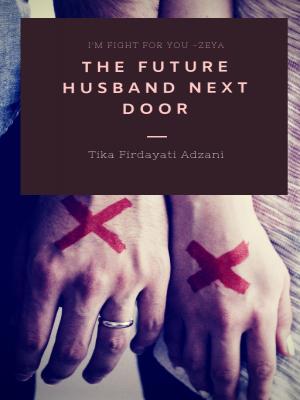Sebuah Ayla putih memasuki pintu gerbang perumahan elit, Royal Mansion kawasan Surabaya Barat. Setelah melaju lurus dan belok kanan dua kali, mobil itu berhenti tepat di sebuah rumah besar ber-cat coklat nuansa vintage. Pagar rumah itu masih tertutup. Pak Mulya, selaku satpam rumah, sedikit mendongakkan kepala keluar jendela pos. Mengamati mobil siapa yang berhenti.
“Hm... Jadi ini rumah pak guru?” Azkadina bergumam.
“Bukan. Ini rumah orang tuaku.” Shafwan menunduk lalu memandang sekilas gadis di sampingnya.
“Jadi, pak guru anak sultan nih ceritanya…” Senyum tengil Azkadina mulai menyeruak.
Shafwan tersenyum lalu berkata,”whatever.”
“Tidak ada yang tahu rumah pak guru di sini?” Alis mata Azkadina mulai bertautan.
Shafwan mengangguk.
“Boleh tahu kenapa?”
“Ya gak ada apa-apa. Mengalir saja.” Jawab Shafwan ringan.
“Jadi, aku saja yang tahu? Ustazah Humaira juga tidak tahu?” Mata Azkadina mulai membulat melirik Shafwan. Dalam hati, ia berharap jawaban Shafwan tak membuatnya patah hati.
Shafwan terkekeh. “Kenapa harus Ustazah Humaira?”
“Ya kan dia cantik, saliha, pintar. Perfecto deh!”
“Oh berarti, yang di sebelahku ini gak cantik, gak pintar, gak saliha?”
Azkadina cemberut. Ia mengambil botol air minum dan menenggaknya sampai habis.
“Aku boleh masuk?”
“Janjinya kan mengantar sampai depan saja ya..”
“Jahat banget!” Azkadina nyengir. Hidung mancungnya tampak lebih membulat.
Shafwan lagi-lagi terkekeh melihat ekspresi Azkadina.
“Kenapa gak boleh?”
“Belum saatnya.”
“Belum saatnya atau belum siap?”
Shafwan terdiam. Pertanyaan Azkadina membuat hatinya bimbang. Benarkah ia belum siap mengenalkan Azkadina? Atau belum bisa melupakan Aida? Ia menunduk. Suasana menjadi hening.
“Hello Mister Pak Guru sultan… jadi ngelamun. Iya gak pa-pa kalau gak boleh masuk. Next time aja.” Azkadina memecah kebekuan.
Shafwan tersenyum seraya berkata, “Maaf.”
“Ndang masuk sana, atau kubawa lagi ke rumah belajar ceria lho!”
“Terima kasih kausnya. Ini kaus kedua yang Azkadina berikan.”
Azkadina tertawa, menertawakan kecerobohannya yang kesekian kali. Lagi-lagi Shafwan memakai kaus distro bertema sarangheyo itu.
“Biar kucuci baju pak guru. Letakkan saja di sini.”
“Tidak perlu.”
“Sudahlah. Aku mau bertanggung jawab, gak boleh?”
“Aku bisa mencuci sendiri.”
“Jangan membuatku manja. Biar aku saja yang mencuci. Fix. Gak boleh menolak!” pungkas Azkadina.
“Gadis aneh. Terserah deh,”timpal Shafwan,“Aku masuk ke dalam ya.”
“Iya pak guru sultan…”
“Sekarang?” goda Shafwan melirik Azkadina.
“Tahun depan!” Suara Azkadina naik setengah oktaf. Matanya melotot ke arah Shafwan.
Shafwan tertawa dan membuka pintu. Ia meninggalkan baju batik seragam yang terkena susu soda itu di kursi mobil.
“See you tomorrow, Azkadina Jasmine Irawan,” ucap Shafwan sambil membalikkan badan dan berlalu dari mobil Azkadina.
Belum sempat menyampaikan balasannya, Azkadina sudah terdiam. Speechless.
Baru kali ini pak guru memanggil nama lengkapku.
Azkadina mematung. Memandang Shafwan dari kejauhan masuk ke dalam rumahnya. Senyumnya tak henti mengembang.
***
“Kamu benar-benar yakin mau berhijab?” Sonya menata beberapa piring dan sendok di atas meja makan. Azkadina yang sedang tertunduk mendongakkan kepalanya yang tertunduk.
“Yakin dong. Kan sudah sukses sehari kemarin pakai hijab.”
“Hari ini juga mau pakai?” Sonya melirik saudara kandungnya. Tangannya masih sibuk menata nasi goreng dan lauk telur dadar.
“Iya dong, Mbak. Masa’ mau dilepas?”
“Apa motifmu pakai hijab? Biasanya lho kamu kegerahan kalau pakai hijab beberapa jam.”
“Ya pengen aja jadi baik kayak Mbak Sonya.”
“Gombal! Paling juga karena Ustaz Shafwan.”
Azkadina tersenyum mendengar nama Shafwan disebut. Pipinya bersemu merah.
“Tuh kan merah pipinya, Ma.” Timbrung Zakaria.
“Apaan sih, Mbak dan Mas ini,” protes Azkadina.
“Sudah sejauh apa hubunganmu dengan Ustaz Shafwan?” selidik Sonya.
“Hubungan apa? Kami lho cuma berteman baik.”
“Halah! Gak mungkin. Udah ngaku aja. Kamu suka Ustaz Shafwan kan?” cecar Sonya lagi.
“Kalau iya kenapa?”
“Ough! Syukur deh. Akhirnya adikku normal juga.”
“Apaan sih!?”
“Ya kan kamu dulu sempat anti cowok. Bener kan Mas Zaka? Masih ingat gak, dua tahun dulu ada yang pernah bilang, semua cowok itu sama brengseknya.”
Zaka tertawa. Azkadina cemberut.
“Ya sudahlah. Memang jatuh cinta itu fitrah manusia. Pertanyaan berikutnya, mau dibawa kemana hubungan kalian? Mau pacaran berapa tahun?” Kali ini Zaka ikut bertanya.
Azkadina menggeleng.
“Siap menikah?” tanya Sonya.
Azkadina terdiam.
“Ustaz Shafwan apa juga punya perasaan yang sama denganmu?” tanya Zaka.
“Ih, kalian itu kompak banget interogasi aku,” sewot Azkadina. Matanya menyipit tanpa senyum.
“Entahlah, Mbak. Sejauh ini, aku nyaman aja saat sama Ustaz Shafwan. Ya walaupun secara pemikiran kami agak berbeda. Dia yang islamis, aku yang agak-agak liberal. Hahaha…”
“Dasar!” tukas Sonya.
“Terus?” Zaka menghentikan makannya. Kali ini dia serius menyimak cerita adik iparnya itu.
“Ada seseorang di hati Ustaz Shafwan. Kupikir dia adalah Ustazah Humaira. Aku pikir dugaanku salah. Tapi aku juga tidak tahu siapa. Bahkan aku baru saja mengetahui di mana rumahnya. Dia masih penuh misteri.” Gerutu Azkadina. Tatapan matanya memandang ke luar jendela.
Sonya duduk kembali dan memperhatikan perubahan raut wajah adiknya.
“Ya sudah, Pertegas hubungan kalian. Jangan menggantung. Islam tidak mengenal pacaran. Kalau memang siap menikah, kakak bantu komunikasi ke Ayah.”
“Ayah?”
“Tentu saja. Kalau kamu menikah, yang jadi walinya ya Ayah.”
“Duh! Gak bisa apa, kalau pakai wali hakim saja?”
“Enak aja! Kalau ayah sudah meninggal, baru pakai wali hakim. Itu pun jika Pakde Yoyok meninggal juga.”
“Aku malas ketemu Ayah.”
“Iya Mbak tahu, kamu gak suka dengan perilaku Ayah. Tapi gimana-gimana, dia ayahmu. Dia yang akan menikahkanmu,” tukas Sonya, meluruskan perilaku adiknya yang salah.
“Walah! Sudah-sudah! Siapa juga yang mau menikah? Aku juga belum lulus kuliah.” Azkadina menyudahi makan malamnya lalu ngeloyor pergi. Seperti biasa tanpa pamit.
Sonya menggelengkan kepala melihat sikap keras adiknya.
***
Humaira menutup lembaran Al Quran yang dibacanya. Sudah tiga hari sejak pertemuan perdana taarufnya. Sudah tiga hari pula, Humaira istikharah. Meminta petunjuk atas sebuah keputusan besar yang akan diambilnya. Melanjutkan proses taaruf atau tidak.
Tidak ada mimpi yang Humaira alami, seperti yang di-klaim teman-temannya ketika istikharah. Namun batin Humaira seakan diberi keyakinan dan ketenangan untuk melanjutkan proses. Perasaannya kepada Shafwan juga lambat laun sirna. Tak ada lagi harap-harap cemas apalagi jantung berdegup kencang saat bertemu Shafwan. Selain itu, juga tidak ada rasa cemburu saat melihat Azkadina menjemput Farel di sekolah. Humaira semakin yakin, pilihannya benar.
Ia mengambil ponsel dan menekan nomor ponsel Hilwa, guru mengajinya.
“Mbak, aku insyaAllah melanjutkan proses ini.”
“Alhamdulillah. Barokallah. Hanif juga memutuskan melanjutkan proses.” Suara Hilwa dari kejauhan membuat hati Humaira gerimis.
“Baik dek. Kita bersiap untuk khitbah ya.”
“Bismillahirrohmanirrohim.” Lirih Humaira berucap.


 neea_sweet
neea_sweet