Hari ini sama seperti beberapa hari yang sudah berlalu. Tidak ada obrolan atau sapaan. Alen berangkat sebelum semua orang bangun. Naik bus paling pagi, menembus udara dingin yang juga pernah ia tembus dengan teman khayalannya dulu.
Galen memang masih sering menyelinap ke dalam prefontal Alen, tapi tidak lagi membuat gadis itu berdebar-debar. Lucu rasanya kalau mengingat dulu Alen pernah merasa sangat nyaman dan bersemangat karena seseorang yang sebenarnya tak pernah ada.
Alen memasang headset-nya selagi ia berjalan melintasi koridor sekolah yang sepi. Gadis itu segera duduk di bangku paling belakang begitu sampai di kelas. Ia memutuskan untuk menyelesaikan sisa siaran podcast yang tidak sempat ia dengar sampai habis semalam.
Jangan terlalu sering memikirkan hal-hal negatif. Lagi pula, di dunia ini ada banyak hal yang lebih baik yang bisa kamu pikirkan. Coba berhenti sejenak dari aktivitas yang sedang kamu lakukan. Tarik nafas dalam-dalam, pejamkan mata, dan renungkan hal baik apa yang sudah terjadi kemarin?
Alen menyeringai menanggapi ocehan podacster yang meluap-luap di telinganya. Meski dalam hatinya ia mencibir, tapi diam-diam Alen tetap menarik nafas, memejamkan mata, dan mulai mengingat-ingat hal baik yang terjadi padanya.
Tidak ada.
Sekoyong-koyong prefontal Alen memutar pertengkaran hebat dengan Alice kapan hari. Alen cepat-cepat membuka mata saat suara-suara fiktif, tuduhan, dan teriakan dari otaknya terdengar begitu nyata. Gadis itu terhenyak, lalu melepas headset, membanting benda berkabel itu ke meja dengan mata kosong. Sampai kapan suara-suara itu akan menganggu Alen? Apa tak cukup membuat Alen terjaga, gelisah sepanjang malam.
Detik berikutnya Alen melirik jam di pergelangan tangannya, mendapati jarum masih mengarah pada angka 6 kurang lima belas menit.
Baiklah.
Sebelum orang-orang datang, Alen harus pergi.
Dengan kaki yang tiba-tiba bergetar hebat, Alen terseok-seok meninggalkan kelas. Headset dan ponselnya dibiarkan tergeletak di meja sementara ia menyusuri selasar sekolah yang masih lengang. Seperti terhipnotis secara gaib, langkah Alen pasti meski jantungnya mengentak-entak ketakutan.
Akhirnya Alen sampai.
Gadis itu berhenti di kamar mandi sekolah dengan napas terengah-engah. Hal pertama yang Alen pikirkan setelah sampai di sekolah adalah menahan keinginannya yang menggebu-gebu sejak bertengkar dengan Alice. Alen tidak ingin menyerah, apalagi mati. Tapi suara-suara tadi terasa begitu nyata.
Sudah lama Alen ingin mengakhiri ini. Sejak dulu, Alen muak dengan hidupnya, tapi tak pernah punya keberanian untuk mengambil tindakan. Untunglah hari ini datang. Hari yang mengilhami Alen. Yang akan menyelamatkan Alen dan mengakhiri dunianya.
Katanya, sakit hati itu seperti penyakit HIV yang hanya mati jika inangnya mati. Jadi jika Alen mati, maka suara-suara yang menjadi akar kesakitannya itu juga akan ikut mati.
Alen maju selangkah, menatap mirat yang memantulkan bayangan wajahnya. Gadis itu menghela napas sebelum kemudian meninju mirat sekuat tenaga. Saat mirat di hadapannya retak, Alen menggila, lalu kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Gadis itu meninju mirat berkali-kali sampai seluruh permukaan benda itu berubah merah karena darah.
Tetesan darah meluncur dari tangan Alen. Beberapa buku jarinya sobek berbenturan dengan retakan kaca. Tapi perih di buku jarinya tak menyadarkan gadis itu. Alen meraih potongan kaca yang bertebaran di lantai, kemudian berjongkok.
Ditempatkannya pecahan kaca itu di pergelangan tangannya, tepat di garis biru kehijauan yang timbul pada permukaan kulitnya. Potongan kaca itu menekan nadi Alen, membuat Alen memejamkan mata merasakan getaran darahnya yang siap bercucuran.
Kalau saya jadi kamu, kemudian saya mati dan masuk surga, saya akan minta pada Tuhan supaya saya diberikan keluarga yang sama dan kehidupan yang sama seperti di bumi meskipun saya tahu saya bisa meminta lebih dari pada itu.
Alen terhenyak.
Ia menolehkan kepalanya ke seluruh penjuru kamar mandi. Gadis itu lebih terhenyak lagi saat mendapati bayangan hitam mendekat padanya dari arah luar.
Alen melempar potongan kaca dalam genggamannya. Gadis itu berniat meninggalkan kamar mandi, tapi rasa takut yang menyelimutinya mengambil seluruh sisa kesadarannya.
Semuanya gelap
#
Embusan hangat memenuhi seluruh hampa di ruangan itu. Seperti ditaburi pasir, sulit rasanya bagi Alen untuk membuka mata. Terasa perih.
Awalnya Alen berpikir inilah saatnya ia akan bernegosiasi dengan Tuhan soal apa yang bisa ia dapatkan dan apa yang bisa Tuhan beri. Tapi Alen tidak menemukan malaikat atau lapangan besar bercahaya dipenuhi jiwa-jiwa yang melayang seperti yang sering diceritakan Renata tentang dunia orang mati. Yang Alen temukan malah langit-langit putih polos serta udara lembab yang membelai kulitnya.
Samar-samar suara yang tak asing masuk, memenuhi telinga Alen.
“Nah. Akhirnya bangun juga.”
“Kamu membuat semua orang khawatir. Untung saya menemukan kamu, kalau tidak, mungkin saya tidak akan melihat kamu lagi.”
Alen tak bisa begerak, apalagi mengatupkan mulutnya yang menganga lebar.
Di depannya, tepat di matanya, bola mata coklat bening bertabrakan dengan manik-manik miliknya. Wajah putih pucat yang Alen rindukan, serta suara lembut yang menenangkan.
Alen melihatnya. Alen membayangkannya. Galen.
“Saya benar-benar sudah gila.” Tanpa sadar Alen berkata. Di sudut matanya, hangat melintas, terjun melalui ujung luar matanya yang penuh oleh sosok Galen.
“Kamu tidak gila. Harus berapa kali saya bilang?”
“Kamu tidak nyata, Galen. Setiap kali saya membayangkan kamu adalah setiap kali saya menjadi gadis gila yang sesungguhnya.” Alen terisak kecil. Harusnya ia mati saja di kamar mandi sekolah. Kenapa ia harus terbangun dan bertemu Galen lagi?
Galen tidak nyata, hanya bayangan. Hanya imajinasi Alen. Hanya sosok yang menjadi penanda bahwa gejala Skizofrenia Alen sudah semakin parah.
“Saya nyata. Kamu melihat saya, kan?”
Alen menggeleng kuat-kuat. Ia menutup matanya dengan sebelah tangan, sementara tangannya yang lain terasa kebas dan kaku oleh selang infus.
“Kamu bisa merasakan saya.”
Alen merasakan sentuhan hangat menghilangkan kebas di tangannya yang tergeletak kaku di ranjang.
“Kamu merasakan saya.”
Perasaan hangat ini. Sebuah sentuhan yang mampu mengalirkan kenyamanan secara ajaib. Sentuhan Galen yang mestinya tak bisa Alen resapi senyata ini.
“Terserah kamu percaya pada siapa. Kamu boleh percaya pada orang-orang yang bilang saya tidak pernah ada, atau kamu percaya pada saya bahwa saya selalu ada bersama kamu.”
“Tapi lebih penting dari itu, kamu harus lebih dulu percaya pada dirimu sendiri, Alen. Tidak akan ada yang percaya padamu kalau kamu meragukan dirimu sendiri.” Suara Galen memantul-mantul di telinga Alen.
“Dan satu lagi, kalau kamu berpikir kematian adalah awal dari segalanya, kamu salah. Kamu tidak akan mendapatkan hidup baru hanya dengan mati. Kamu tetap akan melanjutkan hidup yang saat ini kamu jalani, mempertanggung jawabkan semuanya. Kamu hanya meninggalkan duniamu dan datang ke dunia baru yang mungkin saja lebih kejam. Jangan pernah berpikir mati itu menyelesaikan segalanya.”
Lalu Galen melepaskan genggaman tangannya pada tangan Alen. “Kalau kamu memang ingin dunia yang baru, maka bangunlah Alen. Bangun. Lihat sekelilingmu. Lihat orang-orang yang menyayangi kamu. Tanyakan pada mereka apa mereka senang seandainya kamu mati? Saya yakin, ketika kamu mendengar jawaban tidak dari mereka, kamu akan merasa duniamu berharga.”
“Bangun, Alen.”
Alen menelan ludah. Ia menyingkirkan tangan yang menutupi wajahnya.
Bukan Galen lagi yang Alen lihat. Ia menemukan Renata dan Alice sama-sama memandangnya, lalu saling melemparkan senyum dengan kucuran air mata sesaat setelah Alen berkedip tak percaya.
#
“Kamu ingin Mama mati? Atau kamu ingin Mama selamanya disiksa rasa bersalah?” Renata menyusut wajahnya. Ini sudah melebihi batas ketegaran yang ia miliki. Renata sengaja mendiamkan Alen setelah pertengkaran gadis itu dengan kakaknya, tapi sungguh, bukan dengan tujuan untuk membuat Alen merasa tersisih dan mendorong gadis itu mengakhiri hidupnya. Renata hanya berpikir, seperti dirinya, Alen juga mungkin butuh waktu untuk menenangkan diri. Tapi kenyataannya, tidak seperti yang Renata pikir.
“Kalau penjaga sekolah tidak menemukan kamu, apa…” Renata tak sanggup meneruskan kata-katanya.
Pagi tadi, pihak sekolah menelpon. Penjaga sekolah mendengar suara kaca pecah di kamar mandi sekolah, ketika ia memeriksa kamar mandi, ia menemukan Alen sedang berjongkok lemas. Tangan gadis itu berdarah-darah dan tak hanya itu, Alen juga menempatkan pecahan kaca ke pergelangan tangannya membuat penjaga sekolah ketakutan dan hanya berdiri di ambang pintu kamar mandi tanpa mengatakan apa-apa. Ketika penjaga sekolah berniat menenangkan Alen dan menghampirinya, Alen sudah lebih dulu pingsan.
“Jadi bayangan di sekolah? Bayangan hitam itu penjaga sekolah?” Alen bergumam. Kepalanya berdenyut-denyut.
“Jangan sekali-kali lagi kamu berbuat gegabah seperti ini, Alen.” Renata menyeka wajah dengan punggung tangan. Tak apa ia terlihat cengeng sekarang. Toh, Renata sudah tidak tahan lagi berpura-pura tegar. Dengan menangis, setidaknya Renata bisa menunjukkan bahwa ia menyayangi Alen seperti halnya ia menyayangi Alice.
“Kenapa, Ma?”
Renata berang mendengar pertanyaan lirih Alen. Emosinya memuncak. Ubun-ubunnya seolah akan meledak dalam hitungan mundur.
“Kenapa kamu bilang?”
“Alen, Mama gak mau kehilangan kamu!”
Alen tampak tersentak, tapi tak lama. Pandangan gadis itu meredup, lalu matanya yang selalu kosong berubah terisi. Seolah sekelompok ingatan dan potongan memori baru saja selesai dijejalpaksakan ke dalam otak gadis itu.
“Kalau begitu, apa Mama senang kalau aku mati?”
“Tidak, Alen. Mama tidak akan pernah senang.”


 Uswatunn
Uswatunn


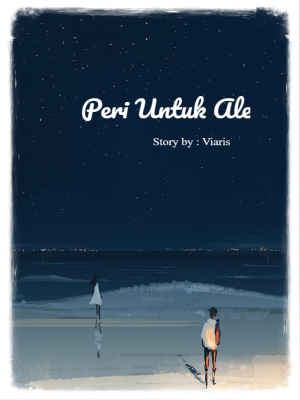
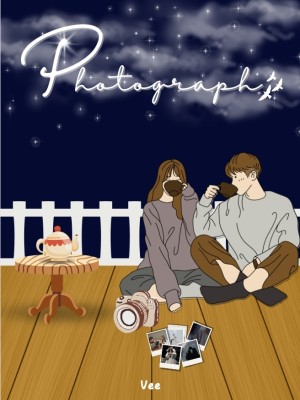

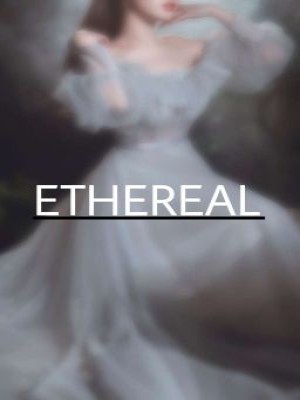




bagus
Comment on chapter Yang tidak diketahui